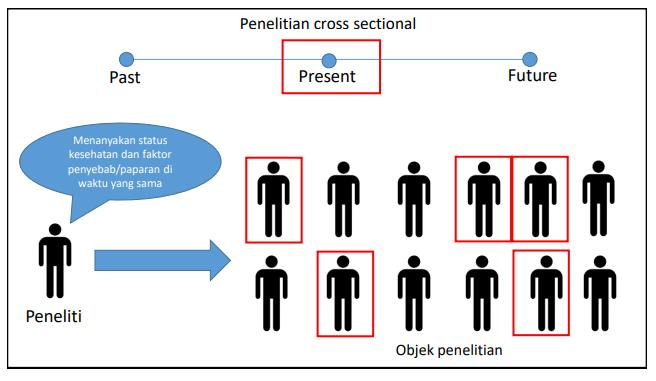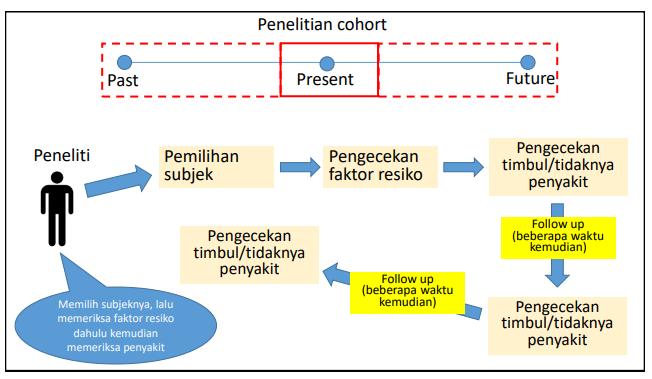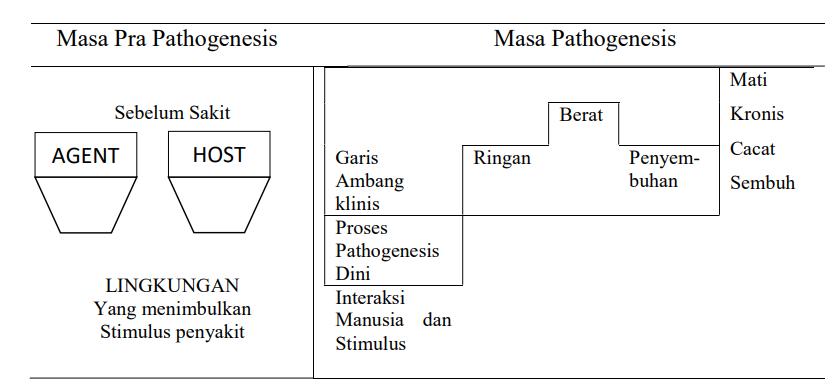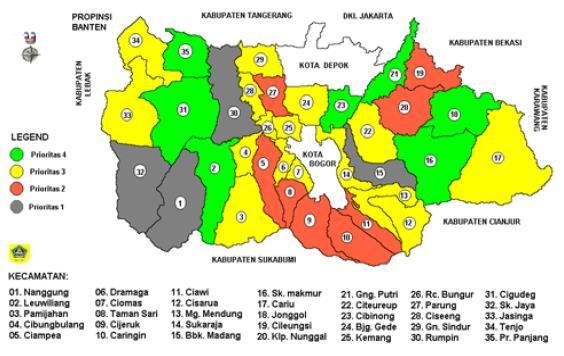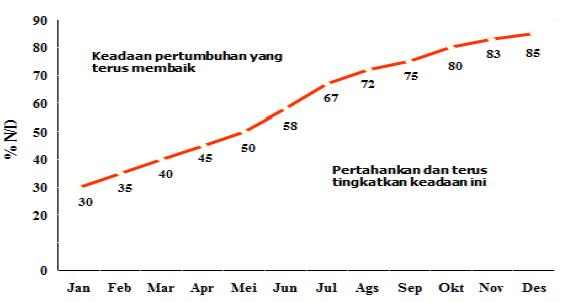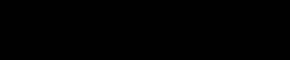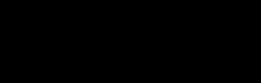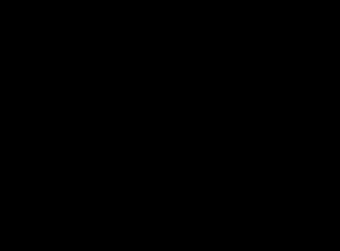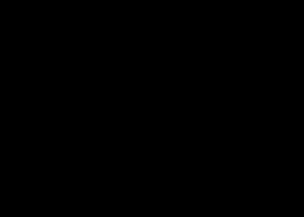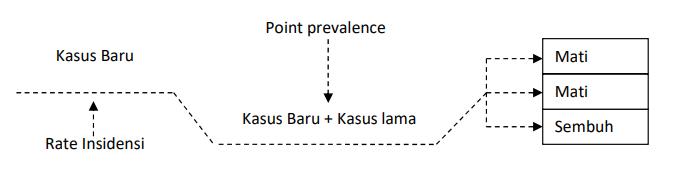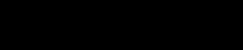KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulis selesai menyusun E modul Epidemiologi Gizi ini. Buku ini disusun untuk memperkaya bahan bacaan ilmiah bagi praktisi, mahasiswa serta teman sejawat, ahli gizi dan profesi lain yang terkait dengan penerapan Epidemiologi Gizi.
Saat ini perkembangan ilmu gizi demikian pesat seiring dengan meningkatnya masalah kesehatan terkait gizi. Menyikapi hal tersebut pembaharuan sumber belajar merupakan hal yang mutlak dilakukan sehingga kompetensi lulusan gizi sesuai dengan kemajuan pembelajaran bidang gizi. Menyadari hal tersebut, E modul Epidemiologi Gizi ini mampu menjadi langkah strategis untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan bidang gizi di seluruh Indonesia sehingga lebih terstandarisasi.
E-modul Epidemiologi Gizi ini mengacu pada berbagai referensi standar epidemiologi baik dari hand book epidemiologi maupun berbagai bahan yang dapat diakses dari berbagai sumber. E modul ini memuat pengertian dan perkembangan epidemiologi gizi, host, agent dan environment tentang masalah gizi di Indonesia, faktor determinan, distribusi dan variabel tentang masalah gizi di Indonesia, riwayat alamiah terjadinya masalah gizi di Indonesia . Selain itu juga dibahas tentang desain penelitian epidemiologi gizi, penelitian kasus kontrol, penelitian kohort, penelitian eksperimental serta hubungan asosiasi dan kausalitas dalam epidemiologi gizi yang terkait dengan masalah gizi di Indonesia.
Penulis menyadari E modul Epidemiologi Gizi ini jauh dari sempurna, baik dari segi substansi maupun bahasanya, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat. Untuk itu guna penyempurnaan E modul ini kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan dan penyelesaian E modul ini.
Medan, September 2022 Penulis
E modul Epidemiologi Gizi ii
BAB
SEJARAH DAN

Manusia
Epidemiologi
BAB 2 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN EPIDEMIOLOGI
Penting Dalam
Desain Cross Sectional
Desain Kasus Kontrol
BAB 3 KAJIAN EKOLOGIS DALAM EPIDEMIOLOGI
Biologis
E modul Epidemiologi Gizi iii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................................i KATA PENGANTAR ............................................................................................ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR............................................................................................vii
1
KONSEP EPIDEMIOLOGI GIZI................................. 1 1.1. Sejarah...................................................................................................... 1 1.2. Pengertian Epidemiologi Gizi 3 1.3. Tujuan Epidemiologi Gizi 4 1.4. Perkembangan Epidemiologi Gizi............................................................ 5 1.5. Pendekatan Epidemiologi Terhadap Diet dan Penyakit........................... 6 1.6. Gizi
dan Epidemiologi Gizi 7 1.7. Peran
Gizi Dalam Penyusunan Rekomendasi Gizi 9
GIZI 11 2.1. Pengertian dan Jenis Penelitian.............................................................. 11 2.2. Beberapa Isu
Penelitian Epidemiologi Gizi .................. 15 2.3.
16 2.4.
(Case Control) 18 2.5. Desain Cohort 21 2.6. Riset Eksperimental................................................................................ 23 2.7. Quasi Eksperimental............................................................................... 24
GIZI 25 3.1. Pengertian 25 3.2. Indeks Asupan Makanan........................................................................ 27 3.3. Generalisasi Makroskopik...................................................................... 31 3.4. Konsentrasi Rata Rata Zat Gizi Mikro Pangan Atau Tanah................ 31 3.5. Konsentrasi Rata-rata Racun Pada Pangan dan Air 32 3.6. Indeks
Asupan Pangan dan Status Gizi 33 3.7. Populasi atau Kelompok Yang Diteliti................................................... 34
BAB
KONSEP
BAB 5 RIWAYAT
BAB 6 SURVEILANS
Konsep

BAB 7 UKURAN FREKUENSI
ASOSIASI
PAPARAN
E modul Epidemiologi Gizi iv
4
DASAR TIMBULNYA PENYAKIT 35 4.1. Perkembangan Teori Terjadinya Penyakit 35 4.2. Konsep Dasar Timbulnya Penyakit 36 4.3. Rantai Penyebab Timbulnya Penyakit.................................................... 37 4.4. Model Timbulnya Penyakit.................................................................... 40
ALAMIAH PENYAKIT GIZI 44 5.1. Riwayat Alamiah Penyakit Gizi 45 5.2. Pemasalahan Gizi Ditinjau Dari Segi Epidemiologi.............................. 47 5.3. Pencegahan............................................................................................. 49 5.4. Penelitian Epidemiologi Gizi ................................................................. 51 5.5. Determinan yang Berpengaruh terhadap Status Gizi 52 5.6. Cara Penentuan Status Gizi 54
GIZI................................................................................ 55 6.1. Pengertian Surveilans Gizi..................................................................... 55 6.2. Tujuan Surveilans 55 6.3. Indikator Surveilans Gizi 55 6.4.
Surveilans Gizi 57 6.5. Penerapan Surveilans Gizi...................................................................... 58 6.6. Tahap Pelaksanaan Teknis ..................................................................... 65 6.7. Evaluasi Sistem Surveilans 67
DAN
EPIDEMIOLOGI GIZI 71 7.1. Pentingnya Ukuran Epidemiologi 71 7.2. Ukuran Frekuensi Penyakit.................................................................... 72 7.3. Ukuran Kematian ................................................................................... 79 7.4. Ukuran Ukuran Risiko 84 BAB 8
OUTCOME DAN CONFOUNDER MASALAH GIZI 86 8.1. Variabel Penelitian................................................................................. 86 8.2. Jenis variabel.......................................................................................... 86 8.3. Mengontrol Variabel Confounding........................................................ 89 BAB 9 SKRINING MASALAH GIZI 94 9.1. Pengertian Skrining 94 9.2. Tujuan Skrining...................................................................................... 96

E modul Epidemiologi Gizi v 9.3. Sasaran Skrining 96 9.4. Pelaksanaan Skrining 97 9.5. Kriteria evaluasi 97 BAB 10 SURVEI CEPAT GANGGUAN GIZI................................................ 101 10.1. Pengertian............................................................................................... 101 10.2. Tujuan Survei Cepat 101 10.3. Metode 102 10.4. Pelaksana................................................................................................ 106 10.5.Teknik Pelaksanaan................................................................................ 107 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 110
Tabel
Tabel 4.1. Beberapa
DAFTAR TABEL

Tabel 8.1.
Tabel 10.1. Dasar
Analisis
Mantel
Kekurangan
Luar
10.2 Informasi
Jumlah
Survei
Survei
E modul Epidemiologi Gizi vi
Halaman
3.1. Perkiraan Konsumsi Aktual.................................................................28
Penyakit Yang Diakibatkan Oleh
Kelebihan Zat Gizi Tertentu 39 Tabel 7.1. Perbedaan Prevalensi dan Insidensi.....................................................80
Hasil
Uji
Haenszel Variabel
Terhadap Hubungan Kehamilan Usia Remaja dengan Kejadian BBLR..............92
Pemilihan Cluster Dan
Responden Pada
Cepat Gangguan Gizi..........................................................................103 Tabel
yang Dihasilkan pada
Anemia Ibu Hamil...............109
Gambar
DAFTAR GAMBAR
Klasifikasi Desain Penelitian
Gambar 2.2. Rangkuman
Gambar 2.3. Desain Penelitian
Desain Penelitian
Desain
Sectional
Gizi
dan Urutan Waktu...................16
Gambar
Segi Tiga

Gambar 4.2. Konsep Jaring Jaring Sebab
Gambar 4.3. Faktor Faktor yang Dapat Menyebabkan Masalah Gizi
4.4. Model
Gambar 5.1. Konsep Riwayat Alamiah Terjadinya
Gambar 5.2. Pathogenesis dari Penyakit Kurang Gizi
Gambar 5.3. Konsep Alamiah terjadinya Penyakit Diterapkan Pada Masalah Gizi
Gambar 5.4. Beberapa Penyebab Dari Masalah Gizi..........................................48
Gambar 5.5. Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Status Gizi
Gambar 6.1. Lingkaran 3A Penanggulangan Masalah Gizi
Gambar 6.2. Diagram Pelaksanaan Sistem Informasi Dini dalam Surveilans Gizi
Gambar 6.3. Diagram Sistem Informasi Dini dalam Implementasi Surveilans Gizi
Gambar 6.4. Diagram Analisis Situasi Pangan dan Gizi
Gambar 6.5. Peta Keadaan Gizi Balita di Kabupaten Bogor Tahun 2018..........63
Gambar 6.6. Grafik Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek pada Balita di Kabupaten Bandung Barat.............................................................64
Gambar 6.7. Grafik Persentase Balita yang Naik Berat Badan hasil Pemantauan
Balita di Posyandu...................................................65
Gambar 6.8. Grafik Partisipasi pada Kegiatan Penimbangan Bulanan di Posyandu
Gambar 6.9. Tahapan Surveilans Gizi................................................................67
6.10. Kerangka Konseptual Evaluasi Sistem Surveilans
E modul Epidemiologi Gizi vii
2.1.
Epidemiologi
12
Pengambilan Sampel
Cross
17 Gambar 2.4.
Case Control......................................................19 Gambar 2.5.
Penelitian Cohort................................................................21
4.1. Model
Epidemiologi 41
Akibat...............................................42
42 Gambar
Roda...................................................................................43
Penyakit.............................44
45
Penduduk 46
................53
58
60
60
62
Pertumbuhan
66
Gambar
Menurut WHO............................................................................68
Gambar

E modul Epidemiologi Gizi viii
7.1. Hubungan Antara Poin Prevalen dengan Insidensi......................77 Gambar 9.1. Konsep Skrining Test 95 Gambar 10.1. Pencarian rumah tangga sampel dan kluster terpilih....................105
BAB 1
SEJARAH DAN KONSEP EPIDEMIOLOGI GIZI
1.1. Sejarah

Epidemiologi merupakan ilmu yang telah dikenal sejak zaman dahulu bahkan berkembang bersamaan dengan ilmu kedokteran karena kedua disiplin ilmu ini berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya, studi epidemiologi bertujuan mengungkapkan penyebab suatu penyakit atau program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang membutuhkan pengetahuan ilmu kedokteran seperti: ilmu faal, biokimia, patologi, mikrobiologi, dan genetika. Walaupun epidemiologi telah dikenal dan dilaksanakan sejak zaman dahulu, tetapi dalam perkembangannya mengalami banyak hambatan hingga baru pada beberapa dasawarsa terakhir ini epidemiologi diakui sebagai suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, epidemiologi seolah olah merupakan ilmu yang baru.
Pengamatan hubungan antara makanan dengan penyakit juga telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Hipocrates, seorang filsuf Yunani, dianggap sebagai tokoh gizi linis karena ia menyatakan bahwa kesehatan dapat dijamin oleh diet yang baik dan higienis. Atas dasar itulah maka diet (daita; Bahasa Yunani) diartikan sebagai hidup yang sehat menurut pemilihan pangan yang baik dan sesuai.
Pengamatan Hippocrates tentang kaitan antara kesehatan dengan pilihan makanan membawa ia pada suatu kesimpulan bahwa “...to the human body it makes a great difference whether the bread be fine of coarse; with or without the hull, whether mixed with much or little water, strongly wrought or scarcely at all,bake or raw... Whoever pays attention to these things, or, paying attention, does not comprehend them, how can he understand the diseases which befall men” (Adam, 1939 dalam Byers, 1999).
Hipocrates juga mengatakan bahwa karena semua manusia adalah sama, tidak peduli apa yang mereka makan, mesti ada diciptakan suatu zat gizi yang diperuntukkan untuk segala sesuatu. Seori suatu zat gizi ini bertahan lama hingga mendekati era modern.
Hingga pertengahan abad ke 18, belum ada pengamatan sistematis yang dapat dianggap sebagai percobaan ilmiah. Pada tahun 1946 barulah James Lind,
E modul Epidemiologi Gizi 1
seorang ahli bedah pada angkatan laut nggris, melakukan percobaan. Pada saat itu usis Lind masih 30 tahun.
Lind meneliti 12 pelaut Inggris yang mengalami penyakit Scurvy dengan tingkat keparahan yang sama. Ia membagi 12 pelaut itu menjadi dua kelompok yang samam untuk dua minggu perlakuan. Kepada kelompok yang satu, Lind memberikan jus lemon dan jeruk, sedangkan kepada kelompok yang lain ia memberikan larutan asam belerang atau vinegar. Kelompok yang diberi jus lemon dan jeruk, pulih dalam enam hari; sedangkan kelompok yang diberi asam belerang tidak mengalami perbaikan (Carpenter, 2003). Atas karya ini, Lind dijuluki sebagai pemuka bagi uji klinis terkendali. Hal penting yang terungkap dari percobaan Lind adalah bahwa buah jeruk atau lemon adalah penyembuh atau pencegah scurvy.
Selanjutnya, peristiwa lain yang melatar belakangi perkembangan epidemiologi gizi adalah temuan Christian Eijkman berkaitan dengan penyakit beri beri. Pada tahun 1883, Eijkman melakukan percobaan pada subjek militer penderita eri beri yang tinggal di asrama. Eijkman memberikan nasi dari beras yang tidak ditumbuk halus (kulit arinya tidak hilang) kepada penderita. Beberapa waktu kemudian, penyakitnya hilang.
Pada saat itu, Eijkman belum mengetahui mengapa hal ini terjadi. Setelah itu, Eijkman masih berpikir bahwa ada sesuatu di dalam beras yang tertumbuk halus yang menjadi penyebab beri beri, bukan karena kekurangan sesuatu. Beberapa tahun kemudian, diketahui bahwa justru sesuatu di dalam beras yang tidak tertumbuk halus itulah yang menyembuhkan beri beri. Sesuatu itu kemudian dikenal sebagai vitamin B1 (tiamin). Enam puluh enam tahun setelah percobaannya itu, yaitu pada tahun 1929, Eijkman dianugrahi Hadian Nobel atas prestasinya itu. Inilah hadiah Nobel pertama atas karya ilmiah yang dilakukan di bumi Indonesia. Atas jasanya itu pula, namanya diabadikan pada Lembaga Biologi Molekular Eijkman.
Peristiwa penting lain pada perkemabnagan epidemiologi gizi berkenaan dengan pellagra. Dr.Joseph Goldberger mengatakan bahwa pellagra tidak menghinggapi orang yang mengkonsumsi diet campuran, atau lebih tepatnya diet seimbang. Penyakit ini tidak mungkin menular dari orang yang satu ke orang yang

E modul Epidemiologi Gizi 2
lain. (pada saat itu, pellagra masih dianggap sebagai penyakit infeksi). Kemudian, Goldbeger melakukan eksperimen pada anjing. Pada tahun 1926, faktor pencegah pellagra ditemukan. Faktor ini adalah termasuk keluarga vitamin B. Sebelas tahun kemudian, peneliti pada Universitas Wisconsin menemukan bahwa vitamin itu adalah asam nikotinat (niasin).
Pada tahun 1980 an, peneliti Cina melalui pendekatan epidemiologi dan menunjukkan bahwa kekurangan selenium bertanggung jawab bagi tingginya insidensi penyakit Keshan di wilayah tengah Cina. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa gizi juga dapat mempengaruhi agen penyebab penyakit. Pada orang yang tidak mengalami defisiensi selenium, penyakit ini tidak muncul walaupun sudah terinfeksi virus penyebab penyakit Keshan. Virusnya menjadi lebih ganas ketika seorang pengidap virus tersebut mengalami defisiensi selenium.
1.2. Pengertian Epidemiologi Gizi

Epidemiologi gizi adalaha ilmu yang mempelajari sebaran, besar, dan determinan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi, serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik.
Definisi lain menyebutkan bahwa epidemiologi gizi adalah ilmu terkait kesehatan yang membicarakan distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit dalam populasi. Epidemiologi gizi memadukan pengetahuan yang diturunkan dari penelitian gizi, untuk menguji hubungan diet penyakit pada masyarakat atau individu yang hidup bebas (masyarakat atau individu yang tidak diatur dietnya) (Gibney dkk, 2002). Menurut Byers (1999), epidemiologi gizi adalah semua penelitian mengenai hubungan antara diet dengan kesehatan (penyakit) pda populasi manusia. Sementara itu, Byers dkk (1999) mengatakan bahwa epidemiologi gizi merupakan landasan bagi pemahaman kita mengenai kaitan antara gizi dengan kesehatan. Epidemiologi gizi adalah satu satunya metode ilmiah yang menghasilkan informasi langsung tentang kaitan antara gizi dengan kesehatan dalam populasi manusia yang mengonsumsi zat gizi dan pangan dalam jumlah yang lazim.
Mempelajari kaitan anatar gizi dengan kesehatan atau antara gizi dengan timbulnya penyakit tidaklah mudah dan memunculkan tantangan metodologi. Hal
E modul Epidemiologi Gizi 3
ini disebabkan oleh faktor bahwa diet bukanlah paparan tunggal dalam timbulnya penyakit, akan tetapi merupakan sekumpulan variabel yang saling berinterkorelasi. Selanjutnya, variabel variabel tersebut kemungkinan memiliki hubungan non linear dengan penyakit dan berinteraksi satu sama lain (Willert, 1987).
Selain itu, dalam menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara diet dengan penyakit, epidemiologi harus memperhitungkan kerumitan dari kebiasaan makan, interkorelasi anatar kebiasaan makan, dan korelasi antara kebiasaan tersebut dengan perilaku lain (Freudenheim, 1999).
Hal ini yang menyebabkan sulitnya menghubungkan antara diet dengan timbulnya penyakit adalah sulitnya mengukur asupan pangan yang sebenarnya (true intake). Hal ini akan semakin terasa pada penyakit kronis yang membutuhkan paparan diet yang lama untuk menimbulkan penyakit tersebut. Sebagai contoh, kaitan antara konsumsi pangan dengan timbulnya penyakit jantung koroner dijelaskan sebagai berikut.
Penyakit jantung koroner memerlukan paparan diet, terutama diet yang mengandung kadar lemak yang tinggi, dan dikonsumsi dalam jangka panjang. Hal ini membutuhkan data asupan pangan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penilaian konsumsi pangan yang tepat untuk dapat menggambarkan rata rata atau kebiasaan konsumsi pangan. Metode riwayat makanan mungkin salah satu metode yang tepat, akan tetapi daya ingat subjek akan makanan yang dikonsumsi setahun atau puluhan tahun yang lalu menjadi kendala. Oleh karena itu, salah satu isu yang penting diperhatikan dalam mempelajari kaitan antara diet dengan penyakit adalah pemilihan metode penilaian konsumsi pangan dan desai penelitian yang cocok.
1.3. Tujuan Epidemiologi Gizi
Tujuan utama dari penelitian epidemiologi gizi adalah untuk menyediakan fakta ilmiah yang lebih baik untuk mendukung pemahaman peran gizi dalam timbulnya penyakit atau mencegah terjadinya penyakit.
Epidemiologi gii didasarkan pada pemahaman prinsip ilmiah dari gizi manusia (Human nutrition) dan epidemiologi. Secara klasik epidemiologi gizi memiliki tiga tujuan:

E modul Epidemiologi Gizi 4
Untuk menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia,
Untuk menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi, dan
Untuk menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit terkait
1.4. Perkembangan Epidemiologi Gizi

Pada awalnya, epidemiologi gizi lebih memfokuskan diri pada kaitan antara kekurangan zat gizi dengan timbulnya penyakit. Misalnya, anemia zat besi adalah penyakit yang timbul akibat kekurangan zat gizi besi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kesejahteraan manusia yang pada akhirnya mengubah gaya hidup, fokus epidemiologi gizi pun bergeser dari penyakit akibat defisiensi gizi ke penyakit akibat kelebihan gizi yang umumnya muncul secara kronis (penyakit kronis). Contoh contoh penyakit kronis terkait gizi adalah penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi, dan hiperkolesterolemia.
Walaupun penyakit jantung koroner masih sangat jarang terjadi pada awal ke 20, namun pada pertengahan abad ini penyakit jantung koroner menjadi penyebab utama kematian di negara negara barat. Tidaklah mengherankan jika pada tahun 60 an hingga 70 an, fokus epidemiologi gizi adalah pada penyakit ini. Memang pada masa itu, Dr.Denis Burkit juga melakukan penelitian berkaitan dengan konsumsi serat dengan kejadian kanker kolon di Afrika. Akan tetapi, sebagian besar kajian epidemiologi gizi pada masa itu hanya mengkaji kaitan antara diet dengan penyakit kardiovaskular
Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit kronis pertama yang diketahui memiliki etiologi diet. Penemuan inilah kemungkinan merupakan contoh paling baik dari penggabungan epidemiologi dengan ilmu gizi eksperimental (Byers, 1999). Perbedaan antara pendekatan epidemiologi gizi pada penyakit jantung dengan pada kanker sangatlah menarik.
Untuk penyakit jantung, penelitian kasus kontrol sulit diterapkan, baik karena kematian yang terjadi mendadak maupun karena insidensi penyakit yang menyebabkan perubahan pada faktor risiko fisiologis. Itu sebabnya, kajian
E modul Epidemiologi Gizi 5
gizi.
prospektif lebih tepat untuk dipilih. Awalnya, hubungan sebab akibat antara gizi dengan penyakit jantung diduga diperantai hanya oleh konsentrasi kolesterol serum. Akibatnya penyelidikan menyeluruh dan sistematis tentang kaitan antara diet dengan penyakit jantung belum dilakukan hingga tahun tahun belakangan ini, keika peran yang dimainkan oleh aspek lain dari diet seperti serat, antioksidan, dan folat, pada risiko penyakit jantung telah diungkapkan. Lain halnya dengan kajian longitudinal yang memiliki faktor antara yang kuat (strong intermediate factor) ini, untuk mempelajari kaitan antara diet dan kanker, pendekatan awal yang digunakan adalah desain kasus kontrol. Pendekatan ini digunakan hingga pertengahan tahun 1980 an, sejak saat itu kohort sudah mulai dirancang.
1.5. Pendekatan Epidemiologi Terhadap Diet dan Penyakit
Konsep, hipotesis, dan teknik epidemiologi gizi diturunkan dari berbagai sumber. Sebagai contoh adalah biokimia. Melalui biokimia ini diberikan bukti bahwa zat gizi tertentu berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi komponen sel kritis dari kerusakan. Bukti ini banyak ditemukan pada efek perlindungan sel atau jaringan terhadap kanker. Selanjutnya, metode kultur sel (jaringan) digunakan untuk mengidenifikasi senyawa, misalnya Vitamin A bentuk jadi (preformed vit. A) yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, yang dapat mempengaruhi risiko kanker pada manusia. Berikutnya, percobaan hewan dilaboratorium memberikan informasi mengenai efek diet pada munculnya penyaki dan mekanisme aksinya. Akhriyna kajian metabolik dan biokimia pada sunyek manusia menghasilkan informasi penting pada efek fisiologis dan faktor diet.
Akan tetapi, temuan dari penelitian in fitro dan percobaan hewan tidak dapat di ekstravolasikan secara langsung kepada manusia, dan perubahan fiioslogis dan metabolik adalah beberapa tahpan yang dipenggal penggal dari munculnya penyakit secara aktual pada manusia. Oleh karena itu, pendekatan epidemiologis dibutuhkan untk megetahui hubungfn diet dengan penyakit secara langsung pada manusia.

E modul Epidemiologi Gizi 6
1.6. Gizi Manusia dan Epidemiologi Gizi
Gizi manusia menggambarkan proses proses pada sel, jaringan, organ, dan tubuh secara keseluruhan dalam mendapatka dan menggunakan substansi esensial untuk mempertahankan struktural dan integritas fungsionalnya. Gizi manusia didasarkan pada suatu pemahaman dari efek keseimbangan antar suplai dan kebutuhan dari substrat dan kofaktor (contohnya zat gizi) yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi optimal (termasuk pertumbuhan, kehamilan, laktasi, pencegahan, dan lain lain).
Gizi manusia berupaya untuk memaham kerumitan dari efek faktor sosial dan biologis pada bagaimana individu dan populasi mencoba mempertahankan fungsi normal. Dalam penelitian epidemiologi gizi, penting untuk mempertimbangkan faktor faktor yang mempengaruhi apa yang terjadi terhadap makanan ketika makanan tersebut telah dimakan. Penelitian epidemiologi mecoba untuk mengambil sudut pandang yang lebih luas mengenai diet mempengaruhi atau memelihara kesehatan pada tingkat individu dan populasi.
Penelitian epidemiologi juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang mendasari penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat sangat berkualitas. Epidemiologi gizi adalah landasan ilmiah untuk penyusunan kebijakan gizi kesehatan masyarakat (public health nutrition) gizi kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan kesehatan melalui gizi serta pencegahan primer atas diet yang berkaitan dengan penyakit pada populasi.

Fakta ilmiah yang mendasari peningkatan kesehatan, termasuk penghindari dari penyakit terkait gizi, memerlukan penelitian yang dirancang dengan baik. Singkatnya, epidemiologi gizi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk meneruskan pesan dan upaya promosi kesehatan terkait gizi kepada individu dan populasi secara lebih baik.
Untuk mencapai tujuan ini, apa yang hendak dijawab melalui penelitian (pertanyaan penelitian) yang jelas perlu dijawab oleh penelitian yang dirancang dengan baik. Penelitian yang dirancang dengan buruk hanya membuang waktu dan uang dan juga tidak etis.
E modul Epidemiologi Gizi 7
Dari perspektif metodologis, Riboli, dkk (1996) telah mencatat empat keterbatasan utama dari epidemiologi gizi, terutama untuk kanker, dan juga untuk penyakit lain.

1. Pengukuran diet kurang akurat dan kurang spesifik, terutama untuk memperkiran konsumsi pangan.
2. Asupan gizi berkorelasi kuat, dan pengatributan penyebab terhadap satu zat gizi dapat menimbulkan salah kaprah.
3. Efek biologis zat gizi dalam jaringan dapat tidak akurat dan tidak meyakinkan. Hal ini merefleksikan asupan makanan karena pengaturan biologis dari efek tersebut bersifat rumit dan dapat dipengaruhi oleh kadar zat gizi lain.
4. Sebagian besar penelitian tidak memperhitungkan atatu mempertimbangkan efek karakteristik pangan (misalnya jeruk sebagai suatu kesatuan buah atau sebagai jus, bagaimana pangan diolah atau disiapkan) pada aktivitas metabolik dari komponen penyusun pangan. Untuk menilai efek paparan makanan diperlukan pengukuran asupan makanan. Pengukuran asupan makanan merupakan hal yang rumit. Suatu hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa ukuran yang diperoleh bukan gambaran dari asupan yang sebenarnya. Tingkat kesalahan pengukuran, konsistensi dari subjek yang satu terhadap subjek yang lain dalam penelitian, dan efeknya pada kekuatan statistik (Stastistical power), serta menginterpretasi hasil meruapakan perhatian utama epidemiologi gizi. Norell (1995) menganjurkan tiga tahap dalam mengatasi kesalahan dalam epidemiologi, yaitu:
1. Mengidentifikasi sumber pokok kesalahan
2. Mengeksplorasi dampak kesalahan ini pada hasil]
3. Merancang penelitian yang akan menghindari dan mengendalikan kesalahan tersebut.
E modul Epidemiologi Gizi 8
Meskipun jika memungkinkan mengukur asupan makanan dengan keakuratan absolut, namun mengaitkan asupan dengan penyebab timbulnya suatu penyakit membutuhkan pemahaman tahapan yang melaluinya, yaitu apakah makanan yang dimakan dapat menyebabkan atau menghaindari timbulnya penyakit.
Pendekatan epidemiologi tidak mungkin untuk menguji setiap tahap dalam lintas sebab akibat (causal pathway), dan karenanya perlu diketahui kaitan erat antara faktor faktor yang terlibat dalam eksperimen yang mengeksplorasi proses metabolik.

1.7. Peran Epidemiologi Gizi Dalam Penyusunan Rekomendasi Gizi
Landasan paling baik tentang rekomendasi bagaimana orang harus makan untuk tetap sehat adalah pemahaman seberapa sehat orang tersebut makan. Untuk inilah epidemiologi memainkan perannya.
Era modern pedoman gizi dimulai pada awal abad ke 20 melalui kampanye penghapusan penyakit akibat kekurangan vitamin A. Kampanye ini mencakup sayur sayuran. Kampanye ini didasarkan pada pengamatan ahli epidemiologi gizi yang mengikuti serangkaian pengamatn ekologis ke penelitian kasus kontrol, kemudian melakukan penelitian intervensi untuk mengkonfirmasi kaitan antara pilihan pangan dengan gangguan akibat kekurangan vitamin A ( Byers, 1999).
Rekomendasi umum untuk asupan zat gizi diformalkan pada tahun 1943 dengan angka kecukupan zat gizi (recommended dietary alloawnce) yang pertama rekomedasi ii juga menjadi acuan bagi penyusunan angka kecukupan gizi di Indonesia. Hal ini didasarkan terutama pada kajian klinis dan eksperimental dari keadaan kurang gizi.
Saat ini, kajian ilmiah yang digunakan dalam melahirkan angka kecukupan gizi dikelompokkan oleh food and nutrition board dari National Research Council atau ( NRC, 1989) menjadi 6 jenis, yaitu:
1. Penelitian pada subjek yang dipertahankan pada diet rendah zat gizi.
2. Penelitian keseimbangan yang mengukur status zat gizi dalam kaitannya dengan asupan.
3. Pengukuran biokimia terhadap kejenuhan jaringan atau kecukupan fungsi molekular dalam kaitannya dengan asupan zat gizi.
E modul Epidemiologi Gizi 9
4. Asupan zat gizi pada bayi yang disusui penuh dan pada orang yang tampak sehat sehubungan dengan asupan pangannya.
5. Pengamatan epidemiologis status zat gizi pada populasi dalam kaitannya dengan asupan.
6. Ekstrapolasi data dari eksperimen pada hewan (dalam beberapa kasus).

E modul Epidemiologi Gizi 10
JENIS DAN DESAIN PENELITIAN EPIDEMIOLOGI GIZI
2.1. Pengertian dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkatan pengamatan kaitan antara gizi dan penyakit atau kesehatan terkait gizi, penelitian epidemiologi gizi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penelitian epidemiologi gizi pada tingkat individu dan pada tingkat populasi. Penelitian epidemiologi gizi pada tingkat individu menjawab pertanyaan bagaimana kaitan antara gizi dan timbulnya penyakit pada tingkat individual. Desain penelitian epidemiologi untuk ini adalah penelitian potong lintang, penelitian kasus-kontrol, penelitian kohort dan uji klinis. Jika unit pengamatannya adalah populasi biasanya berdasarkan geografi, penelitiannya disebut epidemiologi gizi pada tingkat populasi. Penelitian ini dikenal sebagai kajian ekologis dan disebut juga sebagai kajian korelasi
Sementara itu, berdasarkan ada tidaknya kendali terhadap subjek yang dilakukan oleh peneliti, penelitian epidemiologi dapat dibagi menjadi penelitian eksperimental dan observasional (non eksperimental) (Gambar 2.1). Pada penelitian eksperimental, paparan diberikan ke subjek oleh peneliti; sedangkan pada penelitian observasional, peneliti tidak memiliki kendali atas bagaimana subjek terpapar. Eksperimen adalah sekumpulan pengamatan, yang dilakukan dibawah kondisi yang terkendali yang pada pengamatan ini peneliti memanipulasi kondisi untuk memastikan bahwa efek yang diamati adalah akibat dari manipulasi yang dibuat. Manipulasi yang dilakukan, atau disebut juga sebagai perlakuan, dapat bermacam macam seperti diet rendah kalori, pemberian suplemen vitamin, dan pemberian diet dengan takaran yang berbeda.
E modul Epidemiologi Gizi 11 BAB 2
Gambar 2.1. Klasifikasi Desain Penelitian Epidemiologi Gizi

Pada penelitian observasional, peneliti hanya mengamati fenomena atau keadaan yang terjadi. Keadaan ini bukan merupakan hasil dari campur tangan peneliti. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti pola makan penderita diabetes tipe 2 pada orang lanjut usia Pada penelitian ini, peneliti tidak turut campur atas pola makan dan keadaan penyakit subjek. Peneliti hanya mengobservasi bagaimana pola makannya dan bagaimana keadaan penyakitnya. Bandingkan seandainya peneliti memodifikasi diet penderita diabetes tipe 2 kemudian melihat efeknya pada kadar gula darah postprandial.
Kadangkala kajian non experimental dapat berasal dari eksperimen alami ketika paparan, secara alamiah, hanya terjadi pada kelompok tertentu. Contohnya adalah kasus beri beri di Indonesia. Secara kultural, dahulu masyarakat Indonesia pada umumnya mengonsumsi beras putih daripada beras cokelat. Akibatnya penyakit beri beri banyak ditemukan di Indonesia.
Isu praktis dan etis mungkin diperlukan dalam menetapkan pendekatan apa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tertentu. Secara umum, penelitian eksperimental menghasilkan fakta yang paling kuat untuk efek paparan terhadap outcome. Namun tidaklah etis (tidak diperbolehkan) untuk menjalankan penelitian eksperimental jika paparan yang akan diberikan diketahui berbahaya. Dalam keadaan ini, penelitian non eksperimental adalah pilihan yang tepat

E modul Epidemiologi Gizi 12
Dalam penelitian observasional, peneliti dapat mengeksploitasi eksperimen alami yang dalam eksperimen ini paparan dibatasi pada satu kelompok dalam masyarakat yang dibandingkan dengan kelompok lain. Sebagai contoh, membandingkan antara kelompok vegetarian yang mematangkan daging dan kelompok yang memiliki pola diet yang berbeda dibandingkan dengan omnivora.
Antar penelitian observasional, perbedaan pokok desain penelitian berkaitan dengan waktu kapan paparan dan hasilnya diukur atau dinilai. Penelitian potong lintang mengukur baik paparan maupun outcomenya, pada saat sekarang dan pada titik waktu yang sama Pada penelitian kasus kontrol, paparan diukur pada saat sekarang dan paparan saat yang lalu dinilai. Dalam kajian kohort, paparan diukur saat sekarang dan hasilnya diukur di kemudian hari.
Penelitian eksperimental mengukur paparan pada saat sekarang, memodifikasi paparan, dan kemudian menilai efek dari modifikasi paparan ini pada outcome di kemudian hari. Ada dua desain yang mendominasi desain eksperimen yaitu uji acak terkendali (randomized control trial) dan desain saling silang (cross over design). Pada desain acak terkendali, subjek ditempatkan secara acak, baik ke kelompok terpapar maupun ke kelompok non perlakuan, atau lazim disebut sebagai kelompok perlakuan dan kelompok plasebo. Plasebo adalah substansi yang tidak dapat dibedakan dari bahan yang diberikan (perlakuan, sehingga subjek merasa diperlakukan sama. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi bias Contohnya adalah pada penelitian untuk mengetahui efek pemberian vitamin antioksidan (vitamin A dan E) pada pencegahan kanker paru. Pada kelompok A menerima vitamin A pada dosis tertentu; kelompok B menerima vitamin E; kelompok C menerima vitamin A dan E dalam bentuk kapsul vitamin, akan tetapi tidak mengandung vitamin A maupun vitamin E.
Desain saling silang pada dasarnya adalah pengulangan perlakuan. Semua subjek menerima paparan, baik kelompok perlakuan maupun kelompok plasebo, pada periode waktu yang setara. Sebagai contoh kelompok A menerima kapsul vitamin A dan kelompok B menerima placebo, masing masing selama 1 bulan. Kemudian setelah kurun waktu tertentu misalnya 1 minggu yang disebut periode pembersihan (washout period) penerima perlakuan dipertukarkan. Kelompok

E modul Epidemiologi Gizi 13
yang tadinya menerima vitamin A menjadi menerima placebo dan sebaliknya. Selanjutnya pemberian dilakukan selama 1 bulan
Adakalanya peneliti atau subjek tidak mengetahui perlakuan apa yang diberikan dan kepada siapa diberikan. Kalau hanya peneliti yang mengetahui perlakuan apa yang diberikan (subjek tidak mengetahui perlakuan apa yang diterima), desain yang seperti ini disebut sebagai uji acak terkendali buta tunggal (single blind randomized control trial Sementara itu apabila peneliti maupun subjek tidak mengetahui perlakuan itu diberikan kepada siapa, maka desain nya disebut uji acak terkendali buta ganda (double blind randomized control trial).
Pada desain quasi eksperimental, pemberian paparan dikendalikan oleh peneliti, tetapi subjek tidak dialokasikan secara acak terhadap kelompok perlakuannya. Desain quasi eksperimental ini kadang kadang disebut sebagai uji intervensi.
Ketika efek dari hanya satu perlakuan (misalnya pemberian zat gizi mikro) dibandingkan dengan efek plasebo, maka eksperimen ini disebut uji tunggal (single trial). Sementara itu apabila efek dari beberapa perlakuan (misalnya pemberian beberapa zat gizi mikro) dibandingkan dengan efek plasebo, maka eksperimennya disebut uji ganda atau uji faktorial (multiple trial) sebagai contoh dalam desain faktorial 2 x 2, dua perlakuan dievaluasi secara simultan dengan membentuk 4 kelompok perlakuan (perlakuan a, b, a dan b, dan plasebo).
Beberapa uji teracak (randomized trial) dikenal sebagai uji pencegahan primer (primary prevention trial) dan yang lainnya disebut sebagai uji pencegahan sekunder (secondary prevention trial). Uji pencegahan primer adalah eksperimen yang dilakukan kepada subjek yang sehat dengan tujuan untuk pencegahan penyakit. Uji pencegahan primer ini disebut juga uji lapangan (field trial) (Margetts and Nelson, 1997 Uji pencegahan sekunder dilakukan pada subjek yang telah menderita penyakit tertentu. Mereka ditempatkan secara acak kepada kelompok perlakuan tertentu atau plasebo. Tujuannya adalah untuk mencegah efek lebih lanjut atau lebih berat dari penyakit yang dialaminya tersebut.
Pilihan desain penelitian sering dipengaruhi oleh alasan pragmatis seperti biaya dan kelayakan (Tabel 2.1). Alasan pragmatis Ini seharusnya tidak menjadi penentu pemilihan desain penelitian. Secara optimal, peneliti harus

E modul Epidemiologi Gizi 14
mengklarifikasi tujuan penelitian, kemudian memutuskan cara yang paling baik untuk melakukan penelitian. Pada tingkat ini, peneliti biasanya harus membuat keputusan tentang sejauh mana ia bersiap untuk penyimpangan dari keadaan ideal. Jika penelitian tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian secara memadai, maka lebih baik untuk tidak melaksanakan penelitian. Faktor utama dalam memilih antara desain kasus kontrol dan kohort adalah apakah paparan atau outcome nya jarang terjadi. Jika paparan nya jarang terjadi, maka desain kohort cocok untuk dipilih; Sedangkan jika outcomenya jarang, maka desain kasus kontrol cocok dengan jumlah sampel yang besar untuk mendapatkan subjek yang cukup dengan berbagai tingkat paparan. Penelitian potong lintang adalah optimal untuk paparan dan hasil yang lazim. Karena kajian ekologis didasarkan pada data teragregat yang biasanya dikumpulkan dari kelompok masyarakat yang besar (keseluruhan negara), maka desain ini baik untuk mengeksplorasi paparan dan outcome yang jarang maupun yang lazim
Desain kohort dapat menilai outcome ganda (jika sampel cukup besar), tetapi terbatas dalam jumlah ukuran paparan yang dapat dinilai (bergantung pada metode penilaian diet); sementara itu, desain kasus kontrol dibatasi untuk menilai satu outcome, akan tetapi dapat menilai beberapa paparan yang berbeda (tetapi juga tergantung pada ukuran diet yang digunakan).
Kajian kohort cenderung mahal dan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya, walaupun tidak selalu (sebagai contoh, penelitian diet maternal dan hasil kelahiran dapat diselesaikan dalam 9 bulan). Desain kasus kontrol umumnya lebih murah dan diselesaikan lebih cepat,
2.2. Beberapa Isu Penting Dalam Penelitian Epidemiologi Gizi
Apapun desain penelitian yang dipilih, ada beberapa isu penting yang berkaitan dengan keakuratan pengukuran paparan diet. Kecuali pada uji klinis, isu yang penting untuk diperhatikan ialah sejauh mana suatu penelitian dapat memperhitungkan faktor perancu (confounding factor) Faktor perancu adalah faktor yang berkorelasi dengan paparan yang menjadi perhatian maupun dengan hasilnya. Perancu menarik perhatian ketika faktor perancu tidak diukur, diukur dengan bias, atau begitu erat berkorelasi dengan paparan diet yang menjadi

E modul Epidemiologi Gizi 15
perhatian, sehingga antara faktor diet dan faktor yang berkorelasi tidak bisa dibedakan
Isu penting kedua adalah efek modifikasi, faktor ketiga yang mengubah asosiasi antara paparan dan penyakit. Berkaitan dengan hal ini, isu yang menjadi sorotan dewasa ini adalah faktor genetik. Faktor genetik dapat menyebabkan perbedaan interindividual dalam hal efek paparan pada risiko penyakit. Terbatasnya pengetahuan akan faktor ini dapat menghasilkan efek pentingnya suatu subkelompok yang dikendalikan di dalam kelompoknya atau, alternatifnya, diasumsikan bahwa paparan berkaitan dengan risiko pada keseluruhan populasi ketika efek benar benar terbatas terhadap suatu subkelompok.
Pemahaman akan keberagaman yang seperti ini di dalam respon terhadap paparan, dapat membantu menjelaskan ketidakkonsistenan antara temuan temuan pada berbagai penelitian yang dikaitkan dengan perbedaan dalam distribusi faktor genetik dalam sampel penelitian (Freudenheim, 1999).
Gambar 2.2. Rangkuman Pengambilan Sampel dan Urutan Waktu
2.3. Desain Cross Sectional

Desain cross sectional dalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach).

E modul Epidemiologi Gizi 16
Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasisekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atauvariabel subjek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti semua subjek penelitian diamati pada waktu yang sama. Tujuan penelitianini untuk mengamati hubungan antara faktor resiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan, ditanya masalahnya (akibat) sekaligus penyebabnya (faktor resikonya).
Gambar 2.3. Desain Penelitian Cross Sectional
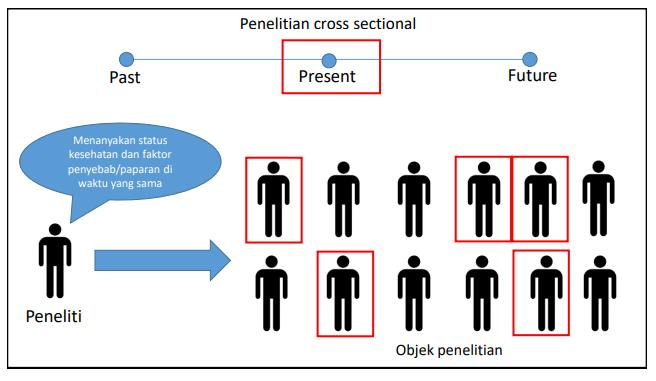

a. Kelebihan penelitian Cross Sectional :
Mudah dilaksanakan, sederhana, ekonomis dalam hal waktu, dan hasil dapat diperoleh dengan cepat dan dalam waktu bersamaan dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel resiko maupun variabel efek.
b. Kekurangan penelitian Cross Sectional :
✓ Diperlukan subjek penelitian yang besar
✓ Tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat
✓ Tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan
✓ Kesimpulan korelasi faktor resiko dengan faktor efek paling lemah bila dibandingkan dengan dua rancangan epidemiologi yang lain.
Epidemiologi
E modul
Gizi 17
Contoh sederhana : Ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan Berat Badan Bayi Lahir (BBL), dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross sectional.
Tahap pertama : Mengidentifikasi variabel variabel yang akan diteliti dan kedudukanya masing masing.
➢ Variabel dependen (efek) : BBL
➢ Variebel independen (risiko): anemia besi.

➢ Variabel independent (risiko) yang dikendalikan: paritas, umur ibu, perawatan kehamilan, dan sebagainya.
Tahap kedua : menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampelnya.
Subjek penelitian: ibu ibu yang baru melahirkan, namun perludibatasi daerah mana mereka akan diambil contohnya lingkup rumah sakit atau rumah bersalin.
Demikian pula batas waktu dan cara pengambilan sampel, apakah berdasarkan tekhnik random atau non random.
Tahap ketiga : Melakukan pengumpulan data, observasi atau pengukuran terhadap variabel dependen independen dan variabel variabel yang dikendalikan secara bersamaan (dalam waktu yang sama) Caranya mengukur berat badan bayi yang sedang lahir, memeriksa Hb ibu, menanyakan umur, paritas dan variabel variabel kendali yang lain.
Tahap keempat : Mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan. Bandingkan BBL dengan Hb darah ibu. Dari analisis ini akan diperoleh bukti adanya atau tidak adanya hubungan antara anemia dengan BBL.
2.4. Desain Kasus Kontrol (Case Control)
Desain case control adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pandekatan retrospective. Dengan kata lain, efek (penyakit atau status kesehatan) diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor resiko diidentifikasi adanya atau terjadinya pada waktu yang lalu.
modul Epidemiologi Gizi
E
18
Study Case Control ini didasarkan pada kejadian penyakit yang sudah ada sehingga memungkinkan untuk menganalisa dua kelompok tertentu yakni kelompok kasus yangg menderita penyakit atau terkena akibat yang diteliti, dibandingkan dengan kelompok yang tidak menderita atau tidak terkena akibat. Intinya penelitian case control ini adalah diketahui penyakitnya kemudian ditelusuri penyebabnya.
Gambar 2.4. Desain Penelitian Case Control
a. Kelebihan penelitian Case Control


✓ Adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol
✓ Adanya pembatasan atau pengendalian faktor resiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibanding hasil rancangan cross sectional
✓ Tidak menghadapi kendala etik seperti pada penelitian eksperimen (kohort)
✓ Tidak memerlukan waktu lama (lebih ekonomis)
b. Kekurangan Rancangan Penelitian Case Control
✓ Pengukuran variabel yang retrospective, objektivitas, dan reabilitasnya kurang karena subjek penelitian harus mengingatkan kembali faktor faktor resikonya.
E modul Epidemiologi Gizi 19
✓
Tidak dapat diketahui efek variabel luar karena secara teknis tidakdapat dikendalikan.
✓ Kadang kadang sulit memilih kontrol yang benar benar sesuai dengan kelompok kasus karena banyaknya faktor resiko yang harus dikendalikan.
Contoh Sederhana: Penelitian ingin membuktikan hubungan antara malnutrisi/ kekurangan gizi pada anak balita dengan perilaku pemberian makanan oleh ibu.
Tahap pertama: Mengidentifikasi variabel dependen (efek) dan variabel variabel independen (faktor resiko).

➢ Variabel dependen : malnutrisi
➢ Variabel independen : perilaku ibu dalam memberikan makanan.
➢ Variabel independen yang lain : pendidikan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak, dan sebagainya.
Tahap kedua: Menetapkan objek penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian. Objek penelitian disini adalah pasangan ibu dan anak balitanya. Namun demikian perlu dibatasi pasangan ibu dan balita daerah mana yang dianggap menjadi populasi dan sampel penelitian ini.
Tahap ketiga: Mengidentifikasi kasus, yaitu anak balita yang menderita malnutrisi (anak balita yang memenuhi kebutuhan malnitrisi yang telah ditetapkan, misalnya berat per umur dari 75 % standar Harvard. Kasus diambil dari populasi yang telah ditetapkan.
Tahap keempat: Pemilihan subjek sebagai kontrol, yaitu pasangan ibu ibu dengan anak balita mereka. Pemilihan kontrol hendaknya didasarkan kepada kesamaan karakteristik subjek pada kasus. Misalnya ciri ciri masyarakatnya, sosial ekonominya dan sebagainya.
Tahap kelima: Melakukan pengukuran secara retrospektif, yaitu dari kasusu (anak balita malnutrisiI itu diukur atau ditanyakan kepada ibu dengan menggunakan metose recall mengenai perilaku memberikan jenis makanan , jumlah yang diberikan kepada anak balita selama 24 jam.
E modul Epidemiologi Gizi 20
Tahap keenam: Melakukan pengolahan dan analisis data. Dengan membandingkan proporsi perilaku ibu yang baik dan yang kurang baik dalam hal memberikan makanan kepada anaknya pada kelompok kasus, dengan proporsi perilaku ibu yang sama pada kelompok kontrol. Dari sini akan diperoleh bukti ada tidaknya hubungan perilaku pemberian makanan dengan malnutrisi pada anak balita.
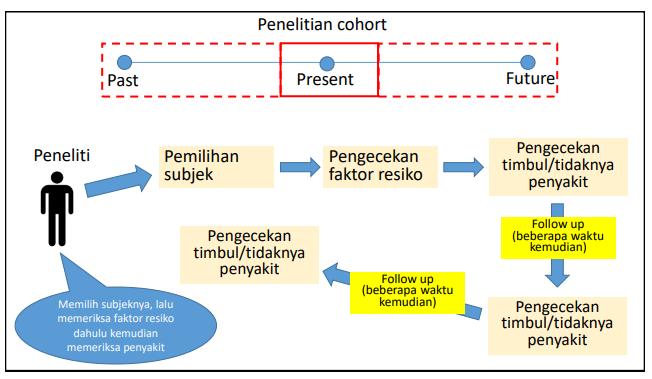
2.5. Desain Cohort
Desain cohort adalah penelitian observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini kelompok penduduk yang diamati merupakan kelompok penduduk dengan 2 kategori tertentu yakni yang terpapar dan atau yang tidak terpaparterhadap faktor yang dicurigai sebagai faktor penyebab. Penelitian cohort adalah kebalikan dari case control. Faktor resiko (penyebab) telah diketahui terus diamati secara terus menerus akibat yang akan ditimbulkannya.
Gambar 2.5. Desain Penelitian Cohort

a. Kelebihan Penelitian Cohort :
✓ Dapat mengatur komparabilitas antara dua kelompok (kelompok subjek dan kelompok kontrol) sejak awal penelitian.
✓ Dapat secara langsung menetapkan besarnya angka resiko dari suatu waktu ke waktu yang lain.
E modul Epidemiologi Gizi 21
✓ Ada keseragaman observasi, baik terhadap faktor resiko maupun efek dari waktu ke waktu.
b. Kekurangan Penelitian Cohort
✓ Memerlukan waktu yang cukup lama
✓ Memerlukan sarana dan pengelolaan yang rumit
✓Kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out dan akan mengganggu analisis hasil
✓ Ada faktor resiko yang ada pada subjek akan diamati sampai terjadinya efek (mungkin penyakit) maka hal ini berarti kurang atau tidak etis.
Contoh Sederhana: Penelitian yang ingin membuktikan adanya hubungan antara
Ca paru (efek) dengan merokok (resiko) dengan menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif.
Tahap pertama: Mengidentifikasi faktor efek (variabel dependen) dan resiko (variabel independen) serta variabel variabel pengendali (variabel kontrol).
➢ Variabel dependen : Ca. Paru
➢ Variabel independen : merokok
➢ Variabel pengendali : umur, pekerjaan dan sebagainya.

Tahap kedua : Menetapkan subjek penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian. Misalnya yang menjadi populasi adalah semua pria di suatu wilayah atau tempat tertentu, dengnan umur antara 40 sampai dengan 50 tahun, baik yang merokok maupun yang tidak merokok.
Tahap ketiga : Mengidentifikasi subjek yang merokok (resiko positif) dari populasi tersebut, dan juga mengidentifikasi subjek yang tidak merokok (resiko negatif) sejumlah yang kurang lebih sama dengan kelompok merokok.
Tahap keempat : Mengobservasi perkembangan efek pada kelompok orang orang yang merokok (resiko positif) dan kelompok orang yang tidak merokok (kontrol) sampai pada waktu tertentu, misal selama 10 tahun ke depan, untuk mengetahui adanya perkembangan atau kejadian Ca paru.
Tahap kelima : Mengolah dan menganalisis data. Analisis dilakukan dengan membandingkan proporsi orang orang yang menderita Ca paru dengan proporsi
E modul Epidemiologi Gizi 22
orang orang yang tidak menderita Ca paru, diantaranya kelompok perokok dan kelompok tidak merokok.
2.6. Riset Eksperimental

Riset eksperimental merupakan Research that allows for the causes of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok dimana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakukan apapun sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan (treatment). Diasumsikan kedua kelompok ini sama.
Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain:
✓ Independent Variable (IV) merupakan faktor yang bisa dimanipulasi.
✓ Dependent Variable (DV) adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap.
✓ Experimental Condition (group) adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen.
✓ Control condition (group) yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi
✓ Confounding variable misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebutkan inilah yang disebut dengan batasan penelitian
✓ An uncontrolled variable yang merupakan variable yang diikuti dengan indipendent variable.
Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada lansia. Pada sekelompok lansia pertama diberikan obat A dan pada Pada sekelompok lansia kedua tidak diberikan obat A. Contoh lainnya misalnya apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e learning dengan yang tidak menggunakan e learning. Bila dengan adanya e learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur dimana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tesebut konstan. Pembanding atau kontrol diantara kedua contoh diatas disebut dengan experimental design. Dimana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul
E modul Epidemiologi Gizi 23
sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkin faktor faktor lain yang berpengaruh. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi, dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e learning dengan yang tidak menggunakan e learning.
2.7. Quasi Eksperimental
Pada penelitian eksperimen murni kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Namun, dalam dunia pendidikan khususnya dalam pebelajaran, pelaksanaan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, karena subjek secara alami telah terbentuk dalam satu kelompok utuh (naturally formed intact group), seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Kelompok kelompok ini juga sering kali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini kaidah kaidah dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh, karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga penelitian harus dilakukan dengan menggunakan intact group. Penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian kuasi eksperimen (eksperimen semu). Jadi penelitian kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact group) untuk diberi perlakuan (treatment), bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Tidak adanya pengacakan dalam menentukan subjek penelitian memungkinkan untuk munculnya masalah masalah yang terkait dengan validitas eksperimen, baik validitas internal maupun eksternal. Akibatnya, interpreting and generalizing hasil penelitian menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, limitasi hasil penelitian harus diidentifikasi secara jelas dan subjek penelitian perlu dideskripsikan. Agar Generalizability dari hasil penelitian dapat ditingkatkan, maka representativeness dari subjek harus diargumentasikan secara logis.

E modul Epidemiologi Gizi 24
KAJIAN EKOLOGIS DALAM EPIDEMIOLOGI GIZI
3.1. Pengertian

Istilah “ekologis” dalam epidemiologi gizi tidak mengacu pada konteks lingkungan yang didalamnya organisme hidup berada, tetapi pada suatu desain penelitian yang berfokus pada karakteristik kelompok populasi dari anggota individunya. Dalam kajian ekologis untuk asosiasi antara gizi dengan penyakit, indeks populasi atau kelompok dari asupan makanan atau status gizi dikaitkan dengan indeks status kesehatan dari populasi atau kelompok. Unit analisis bukan individu, melainkan suatu kelompok yang ditentukan oleh waktu (periode kalender, kohort kelahiran), geografi (negara, provinsi, atau kota), atau oleh karakteristik sosio demografi (misalnya, etnik, agama, atau status sosio ekonomi).
Dalam epidemiologi gizi, kajian ekologis telah menguji hubungan geografis dariindeks asupan makanan atau status gizi dan kesehatan. Suatu contoh penting adalah rangkaian dini dari pengamatan ekologis yang menunjukkan pentingnya peran kolesterol darah dan asupan lemak dalam etiologi penyakit jantung dan menunjukkan aosiasi antara kolesterol plasma, asupan lemak jenuh dari makanan, dan laju penyakit jantung koroner.
Kajian ekologis sering menjadi tahap pertama dalam membangun gambaran epidemiologis dari diferensial distribusi penyakit antar penduduk dengan profil risiko yang berbeda. Variasi pada risiko penyakit antar kategori yang berbeda dari perorangan dapat mengindikasikan perbedaan pada komposisi genetik, perbedaan pada paparan lingkungan, perbedaan pada genetik dan paparan lingkungan, atau interaksi antara keduanya. Kajian ekologis dari populasi migran telah secara luas digunakan untuk memisahkan hubungan sebab akibat antara faktor genetik dengan lingkungan. Perbandingan ini biasanya mengambil keuntungan dari data yang dikumpulkan secara rutin dan karenanya dianggap relatif tidak mahal.
Teknik yang sama dapat digunakan untuk menyelidiki korelasi sepanjang waktu. Sebagai contoh, tingkat mortalitas yang distandarkan menurut usia dari penyakit jantung koroner, yang telah menurun di Amerika Serikat sejak
E modul Epidemiologi Gizi 25 BAB 3
pertengahan tahun 1960 an, telah dikaitkan dengan meningkatnya komsumsi alkohol per kapita pada periode waktu yang sama.

Analisis ekologis hanya berharga ketika kelompok atau komunitas yang dibandingkan memiliki taraf paparan rata rata oleh faktor makanan/gizi yang relatif homogen. Untuk alasan ini, analisis ekologis telah digunakan paling ekstensif untuk perbandingan antar negara daripada untuk perbandingan dalam negara. Pendekatan ekologis terbatas untuk inferensi kausal karena ketidakmampuan untuk menentukan apakah indeks asupan pangan yang menjadi perhatian benar benar berkaitan dengan status kesehatan pada tingkat individual. „Kesalahan Ekologis‟ adalah istilah yang digunakan terhadap bias yang dapat berasal dari pembuatan inferensi mengenai hubungan paparan efek pada tingkat individu berdasarkan hubungan yang diamati pada tingkat kelompok.
Kajian ekologis seringkali menyediakan suatu pandangan pertama yang berharga pada keterkaitan. Ketika digunakan dalam konteks eksploratoris, kajian ekologis ini dapat menghasilkan hipotesis baru yang berharga untuk kajian lebih lanjut. Kajian ekologis juga berguna untuk penilaian awal untuk hipotesis baru yang diajukan.
Selanjutnya, kajian ekologis sering menjadi satu satunya metode penelitian pada asosiasi antara berbagai aspek diet dan risiko penyakit, baik karena data paparan tidak tersedia pada tingkat individu (misalnya, fluorida pada air minum), maupun karena variasi paparan dalam populasi tidak mencukupi untuk menyebabkan variasi risiko penyakit dalam populasi yang terdeteksi. Kajian pada level populasi telah menggais bawahi jurang dalam dalam pemahaman kita mengenai penyebab penyakit jantung koroner. French Paradox, dimana kematian akibat penyakit jantung koroner dalam komunitas ini lebih rendah daripada yang diprediksikan dari faktor risiko yang telah dipahami secara baik, mengisyaratkan bahwa faktor makanan yang belum terduga sampai sekarang ini adalah penting. Sebaliknya, kajian ekologis dapat digunakan untuk memperluas dan mendukung kesimpulan yang ditarik dari penyelidikan pada tingkat individu.
Kajian ekologis yang dirancang dengan baik seringkali mengumpulkan data pada perancu non makanan informasi yang khas tidak tersedia pada kajian
E modul Epidemiologi Gizi 26
ekologis opportunistik. Suatu contoh penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data tingkat kelompok adalah serangkaian kajian yang disponsori oleh International Agency for Research on Cancer (WHO) yang membandingkan konsumsi serat pada populasi yang memiliki insidensi kanker kolorektal yang berbeda. Pada kajian yang berbasis di Skandinavia ini, kimia, bakteri, dan ukuran (bulk) feses diperiksa, demikian juga perkiraan rata rata asupan serat makanan populasi.
Ukuran ekologis telah digunakan utnuk melengkapi data pada tingkat individu dalam pengembangan model multingkat untuk menggambarkan efek kombinasi dari faktor sosial dan perilaku individu pada kesehatan dan penyakit. Pengembangan metodologis ini menciptkan peluang bagi ahli epidemiologi gizi untuk mengembangkan model yangrsifat menjelaskan untuk tingkat individu yang memanfaatkan data pada tingkat komunitas. Karena gizi dipengaruhi sangat kuat oleh faktor budaya demikian juga peluang dan pilihan individu, maka analisis multi tingkat akan mendorong integrasi yang lebih kuat dari teknik ekologis pada desain penelitian tingkat individu.
3.2. Indeks Asupan Makanan
Berbagai indeks asupan makanan baik itu yang bersifat nasional maupun yang internasional akan diuraikan berikut ini. Indeks ini dapat berupa konsumsi rata rata, konsumsi nasioal tidak langsung, serta paparan tidak langsung pada tingkat komunitas. Datanya dapat berupa data langsung maupun data tidak langsung, dan dapat diambil dari data yang telah ada, data stastistik, survei populasi dan rumah tangga, survei mendalam terhadap subkelompok populasi, serta dari catatan penjualan dan pajak yang dibayar atas bahan bahan makanan oleh toko bahan makanan. Data metah ini kemudian dapat diektrapolasi misalnya untuk menentukan skala nasional.
Konsumsi Rata Rata
Perkiraan asupan rata rata individu dapat dibuat dari data yang telah ada sebelumnya (biasanya berorientasi komersial) atau dari data survei populasi yang dikumpulkan dari awal lagi dengan cara yang berbeda sama sekali dari dari cara yang sebelumnya dilakukan (de nevo).

E modul Epidemiologi Gizi 27
Suplai Pangan Nasional Atau Neraca Bahan Makanan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agricultural Organizaition) menerbitkan neraca pangan untuk 146 negara yang memperkirakan jumlah rata rata pangan yang tersedia per orang pada basis harian.

Tabel 3.1. Perkiraan Konsumsi Aktual
Bagian Dari Rantai Pangan Yang Disurvei
Tipe Data Yang Dipublikasikan
Memperhitungkan produksi rumah tangga, impor dan ekspor, perubahan stok pangan.
Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Data Survei Suplai pangan nasional Data neraca pangan yang dikumpulkan oleh Departemen Pertanian dan lembaga terkait seperti Departemen Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perikanan dan Kelautan
Distribusi pasar Data industri
Terbatas untuk sektor spesifik Anggaran rumah tangga Statistik ekonomi Terbtas untuk pengeluaran finansial untuk pangan seluruh rumah tangga; biaya tidak berkaitan dengan nilai gizi yang dibeli. Konsumsi rumah tangga Survei pangan rumah tangga Sering gagal untuk memperhitungkan pangan yang dimakan diluar rumah (dimana saja) Gizi Individu Asupan gizi dan pangan individu Berbagai metode tersedia untuk variabilitas yang beragam
Untuk Indonesia, data statistisk ketersediaaan pangan ini dikenal sebagai Neraca Bahan Makanan (NBM). Data statistik pangan ini dihitung dengan memperkirakan kuantitas pangan yang dihasilkan oleh negara yang bersangkutan, ditambah dengan pangan yang diimpor dan dikurangi dengan pangan yang diekspor, pangan yang hialng selama penyimpanan, pangan yang diberikan kepada ternak, atau pangan yang digunakan untuk tujuan bukan makanan. Angka yang diperoleh dikonversikan menjadi konsumsi per kapita dengan membaginya dengan populasi total. Data ini cenderung merefleksikan pola ketersediaan makanan daripada konsumsi aktual.
Epidemiologi Gizi 28
E modul
Data Survei Populasi dan Rumah Tangga. Survei populasi nasional telah digunakan untuk mengumpulkan informasi makanan secara lebih lengkap pada subkelompok dari populasi. Dengan mengganggap teknik pengambilan sampel telah digunakan, data ini kemudian diekstrapolasikan dengan populasi umum. Di Australia, data ingatan 24 jam konsumsi pangan telah dikumpulkan dengan sampel populasi, sebagai bagian dari penelitian potong lintang dari perubahan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner ang dilaksanakan oleh National Heart Foudation.

Telah diajukan bahwa metode ingatan 24 jam ini adalah satu satunya yang cocok untuk kajian ekologis, dan bukan untuk penyelidikan berbasis individu untuk asosiasi penyakit dan diet individual (terutama untuk zat gizi mikro) menjadikan metode ingatan 24 jam ini lebih rentan mengalami bias dalam memperkirakan asupan individu daripada instrumen yang didasarkan pada konsumsi pangan yang biasa. Disisi lain, data ingatan 24 jam ini dapat menyediakan perkiraan yang masuk akal untuk diet populasi yang ada, yang memperbolehkan perbandingan dibuat dengan populasi lain. Data asupan makanan dari negara yang berbeda dapat dikumpulkan dengan kuesioner frekuensi pangan (food frequency questionnaire, FFQ), pencatatan, penimbangan, riwayat makanan, ingatan 24 jam, ingatan 2 hari, survei pangan rumah tangga, dan metode lain. Mengombinasikan atau membandingkan data yang sangat berbeda menambahkan sumber bias.
Survei Mendalam untuk Sekelompok Populasi. Analisis ekologi terhadap variasi lintas budaya dalam motalitas telah menggunakan analsis gizi yang lengkap dari diet pada sampel kecil individu dari berbagai negara. Sebagai contoh, dalam suatu analisis ekologis dari Seven Countries Studies yang awalnya dirancang untuk menyelidiki asosiasi antara diet dengan penyakit kardiovaskular, ingatn data makanan dan analsis laboratorium dari asupan rata rata pangan digunakan untuk memperkirakan asupan rata rata vitamin antioksidan pada setiap komunits yang diteliti. Ukuran asupan rata rata ini dikorelasikan dengan angka kematian akibat kanker paru, lambung, dan kolorektal antara 16 kohort dari penelitian. Kemudian, data asupan makanan yang lebih lengkap diperoleh dari subkelompok kecil populasi yang dimasukkan dalam analisis mortalitas.
E modul Epidemiologi Gizi 29
Indikator Konsumsi Nasional Tidak Langsung
Didalam ketiadaan pengukuran langsung konsumsi makanan, berbagai penanda tidak langsung telah digunakan. Sebagai contoh catatan penjualan atau pajak digunakan untuk memperkirakan konsumsi alkohol perkapita. Indikator yang demikian digunakan untuk menguji hubungan kecenderungan (waktu) mortalitas akibat kanker laring dengan konsumsi alkohol di Inggris dan Australia. Metode ini dapat itu baik memperkirakan secara salah (underestimate) asupan sebenarnya, karena perkiraan konsumsi ini tidak mengikutkan pembelian alkohol secara ilegal. Minuman yang dibebaskan dari pajak, dan minuman yang dibuat dirumah, maupun itu dapat memperkirakan asupan secara berlebihan dengan tidak memperhitungkan yang terbuang. Namun demikian, jika jenis asupan alkohol yang tidak diukur ini adalah suatu proporsi yang relatif konstan bagi semua asupan alkohol antara populasi yang dibandingkan atau perioda waktu, maka variasi dalam penanda populasi dari konsumsi dapat menjadi individu. Variasi dalam konsumsi yang ektrem tidak diperhitungkan yang dapat berkaitan dengan penyakit tertentu (misalnya, sirosis hati).
Contoh lain dari indikator konsumsi tidak langsung adalah perkiraan dari suatu populasisumber terhadap beberapa derivatif subpopulasi. Secara khusus, metode ini digunakan pada kajian migran dimana diet di negara kelahiran digunakan sebagai indikator bagi diet dinegara tempat tinggal saat ini. Perhatian dibutuhkan didalam analisis yang seperti ini karena ketiadaan informasi mengenai kecenderungan sekuler pascamigrasi dalam pola perilaku makan.

Indikator Paparan Tidak Langsung Pada Tingkat Komunitas
Indikator asupan gizi pada tingkat komunitas telah dikembangkan sebagai bagian dari uji komunitas. Sebagai contoh, ruang rak pada toko grosir digunakan untuk memperkirakan perubahan diet individu menyusul diperkenalkannya program gizi komunitas. Ukuran ini digunakan untuk menarik inferensi mengenai asupan diet dari semua individu yang menggunakan grosir tersebut. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengindikasikan diet kebiasaan masyarakat Aborigin di Australia dimana toko pangan lokal menyediakan pangan yang mayoritasnya dikonsumsi oleh masyarakat Aborigin tersebut.
E modul Epidemiologi Gizi 30
Analisis teoritis saat ini atas kajian ekologis menggarisbawahi bahwa ukuran lingkungan sosial pada tingkat komunitas tempat individu berdiam dspst merefleksikan kombinasi dari efek yang tidak nyata ketika individu diukur secara terpisah. Contohnya diluar epidemiologi gizi adalah hasil kajian Humpherys & Carr Hill (1991) yang mendemonstrasikan bahwa tingkat kemiskinan dari suatu komunitas ditempat individu berdiam memiliki efek pada morbiditas terpisah dari tingkat kemiskinan aktual dari individu yang bersangkutan . Koopman dkk (1994) juga menunjukkan bahwa risiko penyakit pada individu bergantung pada risiko penyakit tersebut pda individulain pada komunitas mereka.
3.3. Generalisasi Makroskopik
Kadang-kadang, pernyataan yang dibuat mengenai pola diet pada populasi didasrkan pada pengamatan pada sekelompok yang tidak dipilih dengan cara pengambilan sampel sacra khusus untuk tujuan ini. Oleh karena itu, generalisasi mengenai asupan makanan pada populasi adalah pernyataan global yang tidak didasarkan pada prosedur pengambilan sampel. Contohnya adalah hasil kajian Burkitt & Trowell (1975). Dipicu oleh perbedaan yang besar pada profil penyakit antara populasi Afrika bagian timur dengan Afrika bagian barat, mereka mambuat pengamatan sebab akibat mengenai diet tradisional masyarakat Afrika yang penuh dengan serat, pangan yang tidak diolah; mereka menduga kalau diet ini melambangkan bahwa semua adalah masyarakat Afrika yang masih tinggal dipedesaan. Mereka kemudian meyimpulkan bahwa serat makanan merupakan faktor krusial yang melindungi masyarakat Afrika dari penyakit kronik yang lazim terjadi di negara negara Barat, dimana serat merupakan komponen yang tidak signifikan pada dietnya.
3.4. Konsentrasi Rata-Rata Zat Gizi Mikro Pangan Atau Tanah
Asupan berbagai zat gizi mikro dapat disimpulkan dari defisiensi atau kelebihan dalam pangan atau tanah pada daerah tertentu. Perkiraan asupan ini sesuai ketika sebagian besar sumber pangan pada daerah tersebut adalah lokal. Sebagai contoh, analisis ekologis di Cina telah menunjukkan bahwa daerah yang tanahnya mengandung molibdenum pada kadar yang rendah (dan juga

E modul Epidemiologi Gizi 31
asupan nitrat rendah) memiliki prevalensi kanker esofagus yang lebih tingggi. Kadar molibdenum yang dianalisis pada rambut sampel nilainya rendah pada daerah berisiko tinggi di Cina telah meningkatkan kadar molibdenum pada sayuran dan menurukan taraf nitratnya. Analisis ini mengkorelasikan laju penyakit dengan defisiensi pangan dan tanah dan juga mendemonstrasikan bahwa perubahan pada kandungan molibdenum pada tanaman pangan lokal terjadi dengan program siplementasi.
Konsentrasi zat gizi mikro dapat dipengaruhi oleh perubahan pada proses produksi. Perubahan proses penggilingan tepung selama Perang Dunia II meningkatkan jumlah serat pada tepung. Perubahan ini berkorelasi dengan penurunan mortalitas akibat kanker kolon 15 tahun sete;ah perubahan ini terkjadi (walapun efek perancu perubahan diet masa perang tidak dikeluarkan pada analisis).
Konsentrasi beberapa jenis mineral pada air minum telah dikaitkan dengan laju penyakit kardiovaskuler pada kajian ekologis antarnegara dan di dalam negara. Pada sebagian besar masyarakat, hal yang tidak mungkin kalau air minum individu dalam rumah tangga diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu, efek potensial perlu diperkirakan dengan perbandingan antar masyarakat dengan sumber air minum yang berbeda. Pada suatu penelitian di Inggris, baik kandungan air dan laju penyakit diperkirakan pada tingkat kota. Beberpa ukuran sosio demografi dan lingkungan juga tersedia untuk unit analisis yang sama, sehingga dapat digunakan pada analisis multivarian untuk memperhitungkan faktor perancu.

3.5. Konsentrasi Rata-rata Racun Pada Pangan dan Air
Variasi jumlah racun pada diet lokal dapat dikorelasikan dengan variasi timbulnya penyakit pada suatu kelompok komunitas. Analisis yang seperti ini hanya berguna pada komunitas yang tidak mengonsumsi pangan dari tanaman pangan yang di tanam di daerah lain dalam jumlah yang signifikan. Penyakit motor neuron, lytico, yang terjadi umumnya di Guam, telah dikaitkan dengan konsumsi Cycad, tanaman yang menyerupai sawit yang merupakan sumber tepung. Tanaman ini mengandung asam amino non protein yang telah diketahui
E modul Epidemiologi Gizi 32
menyebabkan penyakit motor neuron, pada monyet yang menyerupai penyakit penderita di Guam.
Penyelidikan penyebab kanker hati mengkorelasikan kontaminasi aflotoksin dari kacang tanah dengan lanjut kanker hati di Afrika bagian timur. Penelitian yang lebih luas tentang peran aflotoksin pada kanker hati yang dilakukan pada kajian ekologisskala besar di Cina, mampu menguji prevalensi infeksi hepatitis B pada komunitas yang sama dimana laju kanker hati dan paparan aflotoksin ditentukan. Faktanya HBV (Hepatitis B virus) diketahui jauh lebih penting daripada aflotoksin menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan efek potensial variabel perancu ketika menginterpretasikan temuan pada kajian ekologis.
3.6. Indeks Biologis Asupan Pangan dan Status Gizi

Perkembangan dalam epidemiologi molekular menawarkan peluang untuk menggunakan penanda biologis paparan yang merefleksikan baik asupan maupun metabolisme. Karena laju penyakit diduga merefleksikan paparan lingkungan terdahulu, maka spesimen biologis akan memiliki validitas maksimum jika itu adalah indikator konsumsi masa lalu. Sayangnya, hanya sedikit penanda biologis yang baik mampu bertahan dan merefleksikan asupan zat gizi total selain yang larut di dalam lemak atau yang didimpan pada rambut atau kuku.
Meskipun memiliki keterbatasan, analisisi darah, urin, feses, air liur, dan SI, telah menghasilkan informasi yang berharga mengenai dugaan asupan makanan pada suatu rentang pangan dan racun. Spesimen biologis ini memberikan ukuran yang bergunan untuk asupan zat gizi mikro.
Beberapa indeks biologis secara khusus cocok dengan kajian ekologis daripada dengan kajian pada tingkat individu. Sebagai contoh, konsentrasi vitamin
A serum bukan ukuran yang akurat bagi status gizi vitamin A individu. Akan tetapi, pada populasi, frekuensi konsentrasi vitamin A serum yang sangat rendah atau sangat tinggi merupakan suatu ukuran yang berguna bagi status gizi (vitamin
A) rata rata pada komunitas.
E modul Epidemiologi Gizi 33
3.7. Populasi atau Kelompok Yang Diteliti
Perubahan pola penyakit antar populasi migran yang jauh dari negara asalnya dan di negara tujuan migrasi telah menyediakan peluang untuk eksplorasi efek relatif dari predisposisi genetik dan paparan lingkungan terhadap penyakitdT konsumsi makanan per kapita nasional dapat digunakan sebagai diet kebiasaan di negara perantauan atau negara asal. Data ini dapat dibandingkan dengan laju penyakit yang dialami oleh berbagai kelompok migran di negara perantauan.
Dalam analisis mortalitas akibat kanker saluran pencernaan masyarakat Eropa yang migrasi ke Australia, migran dari negara yang memiliki tingkat kanker lambung yang berbeda dengan tingkat kanker lambung di Australia, awalnya memiliki laju yang berbeda dari populasi yang lahir di Australia. Namun demikian, dengan bertambah lamanya mereka tinggal di Australia, dan bersamaan dengan terjadinya akulturasi dalam pola makanan, pola penyakit ini secara meningkat merefleksikan apa yang dialami oleh populasi asli orang Australia.
Kelompok masyarakat yan lain yang dapat diamati pada kajian ekologis adalah:
Kelompok masyarakat agama tertentu

Kelompok masyarakat dengan perilaku yang berbeda
Kelompok dalam transisi budaya
Kelompok masyarakat dalam pergolakan sosial
Subpopulasi yang menunjukkan perbedaan budaya atau perilaku yang tajam
E modul Epidemiologi Gizi 34
KONSEP DASAR TIMBULNYA PENYAKIT

4.1. Perkembangan Teori Terjadinya Penyakit
Menurut Van Dale‟s Groot Woordenboek der Nederlance Tall penyakit adalah suatu keadaan dimana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Pengertian penyakit juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Selain itu perkembangan terjadinya penyakit juga senantiasa merupakan bahan kajian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bab berikut akan membahas tentang timbulnya masalah gizi dari kajian model segitiga, model jaring sebab akibat, model roda, dan model multiple regresi.
Pengertian tentang penyakit banyak macamnya. Beberapa diantaranya adalah: penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian, organ atau sistem tubuh (Gold Medical Dictionary). Definisi lain juga mengemukakan bahwa penyakit adalah bukan hanya kelainan yang dapat dilihat dari luar saja akan tetapi juga keadaan yang terganggu dari keteraturan fungsi fungsi dalam tubuh. Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa penyakit tidak lain adalah suatu keadaan dimana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Dengan pengertian seperti tersebut mudahlah dipahami bahwa pengertian penyakit tidak sama dengan rasa sakit. Penyakit adalah keadaan yang bersifat obyektif, sedangkan rasa sakit adalah keadaan yang bersifat subyektif. Seseorang yang menderita sakit belum tentu merasa sakit, sebaliknya tidak jarang ditemukan seseorang yang selalu mengeluh sakit tetapi tidak ditemukan penyakit.
Apabila ditinjau dari segi perkembangan teori terjadinya penyakit, ternyata banyak teori yang mempunyai pandangan berbeda sesuai dengan lingkup pengetahuan saat itu. Secara ringkas diungkapkan berikut ini :
1. Penyakit dapat timbul karena adanya gangguan makhluk halus.
E modul Epidemiologi Gizi 35 BAB 4
2. Teori Hipocrates menyatakan bahwa penyakit dapat timbul karena adanya pengaruh lingkungan terutama air, udara, tanah, cuaca dan lain lain. Dalam hal ini tidak dijelaskan kedudukan manusia dengan lingkungan.
3. Teori Humoral: dikatakan bahwa penyakit dapat timbul karena adanya gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh (putih, kuning, hitam dan merah).
4. Teori Miasma: penyakit timbul karena adanya sisa sisa dari makhluk hidup yang mati membusuk, meninggalkan pengotoran udara dan lingkungan.
5. Teori Jasad Renik (Teori Germ) terutama didapatkan microskop dan dilengkapi dengan teori immunitas.
6. Teori Nutrisi dan Resistensi sebagai hasil dari berbagai pengamatan epidemiologis.
7. Teori Ekologi Lingkungan: bahwa manusia berinteraksi dengan penyebab dalam lingkungan tertentu yang dapat menimbulkan penyakit.
4.2. Konsep Dasar Timbulnya Penyakit
Konsep terjadinya penyakit sering pula disebut dengan istilah teori atau model terjadinya penyakit. Karena ilmu yang kita pelajari adalah ilmu kedokteran manusia, maka pembahasan selanjutnya dibatasi hanya pada teori atau konsep terjadinya penyakit pada manusia saja. Dalam pembahasan tentang teori terjadinya penyakit, istilah host, tuan rumah, hospes dan pejamu adalah memiliki makna yang sama akan dipakai secara bergantian. Suatu penyakit dapat timbul oleh karena adanya faktor penyebab.
Pengertian penyebab dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat ke suatu proses kejadian penyakit, yakni interaksi antara manusia/induk semang (Host), penyebab (Agent), dan lingkungan (Environment). Menentukan penyebab penyakit tidaklah mudah namun demikian ada beberapa cara dalam menentukan penyebab penyakit antara lain :
1. Secara hubungan statistik

E modul Epidemiologi Gizi 36
Dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi simpulan dalam menentukan penyebab, maka variabel utama (penyebab) dan akibat dapat ditentukan.
2. Kuat tidaknya hubungan asosiasi terutama pada dose response relationship
3. Berdasarkan pengamatan pada waktu tertentu yang berhubungan dengan kasus
4. Adanya hubungan asosiasi yang khas antara penyakit yang dicurigai
5. Hasil experimental dengan memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh.
Dari beberapa cara tersebut diatas dalam menentukan penyebab penyakit, masih perlu diperhatikan adanya beberapa faktor yang sangat berpengaruh diantaranya :
1. Adanya konsistensi pengamatan
2. Adanya hubungan antara pengetahuan yang sudah ada dan diakui serta ketentuan ilmu yang berlaku
3. Adanya pengalaman peneliti sendiri dan pengalaman orang lain.
4.3. Rantai Penyebab Timbulnya Penyakit
Pada umumnya rantai penyebab dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga dalam proses terjadinya penyakit dapat dikatakan berbagai faktor ikut mengambil bagian (multiple causations). Oleh karena itu pada setiap program pencegahan maupun penanggulangan penyakit, harus memperhatikan faktor pengaruh penyebab jamak tersebut.
1. Penyebab/Sumber Penyakit (Agent)
Penyebab penyakit dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder.
a. Penyebab Primer
Yang termasuk kedalam unsur penyebab primer adalah :
1) Unsur biologis (mikroorganisme penyebab)

2) Unsur gizi (bahan makanan/zat gizi)
3) Unsur kimiawi (bahan dari luar maupun dalam tubuh)
4) Unsur psikis
E modul Epidemiologi Gizi 37
5) Unsur genetik

b. Penyebab Sekunder
Merupakan unsur yang membantu atau menambah dalam proses sebab akibat terjadinya penyakit. Dalam analisa penyebab penyakit tidak hanya terpusat pada penyebab primer/kausal saja tetapi harus memperhatikan pengaruh primer/kausal saja tetapi faktor lainnya diluar penyebab kausal. Contoh : Penyakit kardiovaskuler, tuberkulosa, kecelakaan lalu lintas, tidak terbatas pada penyebab primer saja tetapi harus dianalisa dalam bentuk rantai penyebab (pengaruh penyebab sekunder sehingga penyebab primer dapat menimbulkan penyakit).

Unsur biologis adalah merupakan salah satu penyebab penyakit yang telah lama dikenal orang sejalan dengan ditemukannya teori jasad renik/teori germ. Sebagai contoh yang nyata dalam hal ini adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh virus TB. Unsur gizi dapat menjadi penyebab sekunder terjadinya penyakit TBC. Karena defisiensi zat gizi kurang akan membuat daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap masuknya mycobacterium tuberculosis sebagai kuman penyebab TBC. Dibawah ini beberapa contoh akibat kekurangan dan kelebihan zat gizi yang dapat menimbulkan penyakit tertentu.
Tabel 4.1. Beberapa Penyakit Yang Diakibatkan Oleh Kekurangan Kelebihan Zat Gizi Tertentu
E modul Epidemiologi Gizi 38
Munculnya penyakit akibat zat kimia dari luar seperti obat obatan, bahan kimia yang terdapat dalam makanan, penambahan zat additive dalam makanan yang berlebihan, dan sebagainya. Sedangkan dalam tubuh seperti dari dalam yang dihubungkan dengan metabolisme dalam tubuh seperti sistem hormonal (Hormone Tiroksin), kelebihan lemak, dan sebagainya.
Faktor faal dalam kondisi tertentu seperti pada saat kehamilan, ekslamsia pada waktu melahirkan dengan tanda tanda bengkak atau kejang. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik seperti kencing manis/Diabetes Mellitus (DM) dan kepala besar yang terdapat pada orang Mongoloid.
Faktor psikis juga sering dapat menimbulkan penyakit seperti tekanan darah tinggi dan penyakit maag yang disebabkan oleh perasaan tegang (stress).
Sinar matahari, radio aktif, dan sebagainya adalah faktor tenaga dan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan penyakit. Sedangkan faktor biologis disamping sebagai mana telah dijelaskan diatas, juga dapat menyebabkan penyakit defisiensi gizi (metazoa, bakteri dan jamur).
2. Manusia (Host)
Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi manusia sehingga terjadinya penyakit adalah genetik, jenis kelamin, etnik group, keadaan fisiologis, keadaan immunologis (hypercensitive, maternal antibody), kebiasaan seseorang (kebersihan, makanan, kontak perorangan, pekerjaan, rekreasi, pemanfaatan pelayanan kesehatan). Faktor manusia yang cukup berpengaruh terhadap timbulnya penyakit khususnya yang sedang berkembang adalah kebiasaan yang buruk, seperti membuang sampah/kotoran yang tidak pada tempatnya, taboo, cara penyimpanan makanan yang kurang baik, hygiene rumah tangga yang kurang mendapatkan perhatian.
3. Lingkungan (Environment)

Faktor lingkungan sangat menentukan dalam hubungan interaksi antara manusia dengan faktor penyebab. Lingkungan dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu :
1. Lingkungan Fisik : Meliputi : iklim/cuaca, tanah dan air.
2. Lingkungan Biologi :
E modul Epidemiologi Gizi 39
a. Kependudukan : kepadatan penduduk
b. Tumbuh tumbuhan : sumber makanan yang dapat memengaruhi sumber penyakit.
c. Hewan : sumber makanan, juga dapat sebagai tempat munculnya sumber penyakit
3. Lingkungan Sosial Ekonomi :
a. Pekerjaan: yang berhubungan dengan bahan bahan kimia, atau pola aktivitas.
b. Urbanisasi: Kepadatan penduduk, adanya ketegangan dan tekanan sosial.
c. Perkembangan Ekonomi: pendapatan, status social ekonomi, daya beli pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan.
d. Bencana alam seperti : banjir, gunung meletus, gempa bumi, peperangan dan lain lain.
4.4. Model Timbulnya Penyakit
Dalam konsep dasar timbulnya penyakit kaitan antara faktor host, agent dan environment, para ahli menggambarkannya dengan berbagai model. Dewasa ini dikenal 3 model yaitu : 1) Segi Tiga Epidemiologi (the epidemiologi triangle),
2) Jaring jaring sebab akibat (the web of causation) dan 3) Model roda (the wheel).
1. Segi Tiga Epidemiologi

Dalam uraian konsep terjadinya penyakit menurut segi tiga epidemiologi adalah kaitan antara host, agent dan environment, seperti terlihat pada bagan 3.1. Menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan merubah keseimbangan antara mereka, bertambah atau berkurangnya suatu penyakit yang bersangkutan. Konsep yang disederhanakan tentang tiga faktor utama yang memengaruhi tingkat keseimbangan kesehatan:
E modul Epidemiologi Gizi 40
Gambar 4.1. Model Segi Tiga Epidemiologi

2. Jaring jaring Sebab Akibat
Menurut model ini, penyakit tidak tergantung pada satu sebab saja yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses “sebab dan akibat”. Dengan demikian maka timbunya penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan cara memotong rantai pada berbagai titik. Berdasarkan metode ini, dalam usaha menanggulangi masalah gizi, kita harus melakukan intervensi berdasarkan penyebab utama (root causes of malnutrition) dari masalah gizi. Sebagai contoh di negara berkembang umumnya masalah gizi disebabkan oleh sosial ekonomi yang rendah disamping faktor faktor lainnya. Konsep jaring jaring sebab akibat dapat dilihat pada gambar 4.2. berikut ini:

E modul Epidemiologi Gizi 41
Gambar 4.2. Konsep Jaring-Jaring Sebab Akibat
Model seperti ini, banyak pula dikembangkan oleh ahli gizi. Dalam Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1979 digambarkan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah gizi serta kaitan satu faktor dengan faktor yang. Hal ini dilukiskan sebagaimana terlihat pada bagan 3.3 berikut di bawah ini.
Gambar 4.3. Faktor Faktor yang Dapat Menyebabkan Masalah Gizi (Call and Levinson, 1973).


3. Model Roda
Seperti halnya model jaring jaring sebab akibat, model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agent. Dalam model ini yang duipentingkan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan masing masing lingkungan bergantung pada penyakit yang diderita. Sebagai

E modul Epidemiologi Gizi 42
contoh: Peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya dari pada “Sorbun”. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan seperti pada penyakit Diabetes Mellitus/Kencing Manis. Konsep timbulnya penyakit menurut model Roda, seperti yang digambarkan dalam gambar 4.4.

Gambar 4.4. Model Roda

E modul Epidemiologi Gizi 43
RIWAYAT ALAMIAH PENYAKIT GIZI
Proses alamiah penyakit dimulai dari masa pra pathogenesis (sebelum sakit), yaitu jika terjadi ketidakseimbangan kondisi antara host, agent dan environment, sehingga menimbulkan stimulus (rangsangan sakit). Dengan adanya interaksi antara manusia dengan stimulus, maka mulai terjadi proses pathogenesis dini yang dilanjutkan dengan kondisi yang berada pada garis ambang batas klinis. Keadaan penyakit yang terjadi bisa bersifat ringan atau berat, yang berakhir dengan keadaan sembuh atau cacat, atau bahkan mungkin timbulnya penyakit kronis atau dapat pula berakibat dengan kematian. Untuk dapat memahami pengertian tersebut diatas, dapat dilihat pada Gambar 5.1
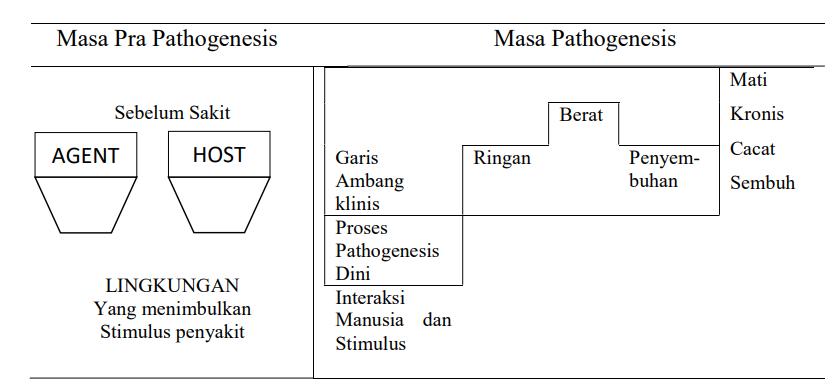
Gambar 5.1. Konsep Riwayat Alamiah Terjadinya Penyakit

E modul Epidemiologi Gizi 44 BAB 5
5.1. Riwayat Alamiah Penyakit Gizi

Dalam proses pathogenesis seperti pada bagan diatas, Jelliffe dan Florentino Salon (1977) telah membuat bagan mengenai pathogenesis dari penyakit kurang gizi, yang berdasarkan penelitian dan pengalaman di negara sedang berkembang, seperti terlihat pada gambar 5.2.
Gambar 5.2 Pathogenesis dari Penyakit Kurang Gizi

Proses diatas terjadi akibat faktor lingkungan dan faktor manusia (Host) yang didukung oleh kekurangan zat zat gizi. Akibat kekurangan zat gizi, maka simpanan zat gizi didalam tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama dan terus maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. Pada saat ini orang sudah dapat dikatakan malnutrisi, walaupun baru hanya ditandai dengan penurunan berat badan dan pertumbuhan yang terhambat (stunting). Hal ini diketahui dengan pemeriksaan anthropometri.
Dengan meningkatnya defisiensi zat gizi, selanjutnya akan muncul perubahan perubahan biokimia, seperti rendahnya zat zat gizi dalam darah yaitu:
E modul Epidemiologi Gizi 45
rendahnya kadar Haemoglobin (Hb), serum, rendahnya serum Vitamin A. Dapat pula terjadi peningkatan beberapa hasil metabolisme seperti meningkatnya asam laktat dan piruvat pada kekurangan thiamine. Apabila keadaan ini berlangsung lama, maka akan terjadi perubahan fungsi tubuh seperti ditandai dengan menurunnya fungsi fungsi syaraf yaitu lemah, pusing, kelelahan, nafas pendek dan lain lainnya.Keadaan ini akan berlanjut terus yang diikuti dengan tanda tanda klasik dari kekurangan gizi, seperti kebutaan dan photopobia, nyeri lidah pada penderita kekurangan riboflavin, kaki kaku pada defisiensi thiamine dan lain lain. Selanjutnya keadaan ini akan diikuti dengan luka pada anatomi seperti xeropthalmia dan keratomalasia pada kekurangan Vitamin A Angular Stomatitis pada kekurangan riboflavin, oedema dan kulit luka pada penderita kwashiorkor. Banyak lagi jenis penyakit kekurangan gizi yang dapat dijelaskan dengan bagan diatas, sebagaimana telah disebutkan jenisnya pada bab bab terdahulu.

Konsep alamiah terjadinya penyakit sering diterapkan dalam mempelajari terjadinya penyakit kekurangan gizi dapat dilihat pada gambar 4.3.
Gambar 5.3 Konsep Alamiah terjadinya Penyakit Diterapkan Pada Masalah Gizi Penduduk (Sumber Leavell & Clark, “Prevention Medicine for the Doctor in his Community “ 3rd. New York, 1965.
Terjemahkan oleh : Dr. Soekirman)

E modul Epidemiologi Gizi 46
5.2. Pemasalahan Gizi Ditinjau Dari Segi Epidemiologi
1. Masalah Gizi

Menurut pandangan epidemiologi masalah gizi terjadi akibat interaksi antara orang/anak (sebagai host), makanan yang dimakan (sebagai agent), dan lingkungan disekitar tempat tinggal (sebagai environment).
Penelitian epidemiologi melibatkan beberapa pertanyaan tentang faktor faktor apa yang terlibat dari ketiga komponen tersebut, dan bagaimana variable variabel tersebut berinteraksi hingga terjadinya masalah gizi. Masalah kurang gizi mempunyai riwayat alamiah, yaitu melalui proses berkesinambungan yang dimulai dari keadaan sehat, terjadi perubahan klinis dan akibat klinis dapat berakibat terjadinya kematian. Proses tersebut dapat diputus dengan adanya intervensi faktor penyebab pada setiap tingkat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan di India dan Philipines, yang berusaha mencari jawaban pertanyaan tersebut dengan menggunakan analisa multiple regresi, diperoleh gambaran tentang interaksi kompleks yang dapat memengaruhi kerangka faktor faktor biologis, sosial budaya, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi terjadinya masalah gizi (KEP). Untuk lebih jelasnya kerangka tersebut dapat dilhat pada bagan: 10.
Dari sudut pandang perencanaan, gambaran yang sederhana dan sering digunakan adalah menurut Call & Levinson, 1973 seperti yang terlihat pada gambar 4.4 tentang faktor faktor yang menyebabkan timbulnya masalah gizi.
E modul Epidemiologi Gizi 47


E modul Epidemiologi Gizi 48
Gambar 5.4 Beberapa Penyebab Dari Masalah Gizi
5.3. Pencegahan
Epidemiologi adalah merupakan ilmu dasar pencegahan dengan sasaran utama mencegah dan menanggulangi penyakit dalam masyarakat. Pencegahan mempunyai suatu pengertian, mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah langkah untuk pencegahan, haruslah didasarkan pada keterangan yang ada dan bersumber dari hasil analisa penelitian epidemiologis.
Dalam kaitannya dengan epidemiologi pencegahan masalah gizi, dapat dilihat dan diberikan intervensi pada beberapa tingkat yaitu :
Pencegahan I : Peningkatan keadaan kesehatan Pencegahan khusus untuk penyakit tertentu.
Pencegahan II: Diagnose tahap awal/dini dan perkiraan treatment untuk penyembuhan dan mengurangi kecacatan.
Pencegahan III : Rehabilitasi untuk pemulihan kondisi seperti normal Kembali dan mencegah terulangnya kejadian penyakit.
Sebagaimana yang ditulis oleh Leavell & Clark terdapat 5 tingkatan pencegahan (dalam 3 tahapan) untuk diterapkan dan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi. Konsep ini sangat relevan, karena disetiap tingkatan digambarkan pula dengan contoh contoh kegiatan sebagaimana penjelasan berikut ini.
a) Masa Pra Pathogenesis :
1. Peningkatan Pengetahuan

a. Penyuluhan gizi yang intensif
b. Penggalakan ASI dan makanan tambahan untuk bayi/balita
c. Pemenuhan kebutuhan gizi sehari hari
d. Standard mutu gizi yang terjamin
e. Perlindungan keselamatan makanan.
f. Pemberian makanan di sekolah sekolah
g. Pemberian makanan pada buruh dipabrik/perusahaan
h. Pemenuhan kebutuhan pokok : makanan, air bersih, jamban, pakaian, perumahan dan lain lain.
2. Perlindungan Khusus (Specific Protection)
E modul Epidemiologi Gizi 49
a. Perlindungan khusus terhadap : bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui
b. Fortifikasi bahan makanan (misalnya iodisasi garam)
c. Suplementasi zat gizi tertentu (misalnya pemberian kapsul vitamin A)
d. Immunisasi
e. Penggalakkan penggunaan ASI dan makanan tambahan untuk bayi dan balita.
b) Diagnose dini, pengobatan cepat dan tepat (Early Diagnosis and Prompt Treatment)
1) Penimbangan balita setiap bulan sekali
2) Survei gizi secara periodic
3) Pemeriksaan anthropometri, klinik, biokimia yang teratur
4) Pemberian Kapsul Vitamin A dosis tinggi pada anak dengan gejala xeropthalamia
5) Pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil dan ibu menyusui yang anemia
6) Larutan gula garam (oralit) pada anak yang diare
c) Masa Pathogenesis :
1. Membatasi Cacat (Disability Limitation)
a. Perawatan khusus KEP berat (Kwarsiorkor/Marasmus)
b. Tempat tempat penampungan penderita kelaparan dan HO
2. Pemulihan Kesehatan (Rehabilitation)

a. Penyuluhan Gizi
b. Mental feeding (Usaha memperbaiki perkembangan mental anak)
c. Memperbaiki lingkungan hidup (biologis, fisik, dan sosial) dan cara hidup
d. Persediaan pangan bergizi yang cukup
e. Melembagakan kebiasaan pemberian makanan dan kesehatan yang baik.
modul Epidemiologi Gizi 50
E
5.4. Penelitian Epidemiologi Gizi
Kegiatan penelitian epidemiologi gizi yang khusus, berupa penelitian deskriptif/ analitik, umumnya berupa penelaahan masalah gizi di masyarakat untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :
a. Apakah faktor makanan atau gizi menyebabkan terjadinya penyakit, atau mengurangi / menurunkan kondisi kesehatan
b. Seberapa jauh pengaruh yang tidak diharapkan dari faktor tersebut, terhadap keadaan kesehatan. Bagaimana hubungan timbal balik yang terjadi ?
c. Apakah faktor tersebut dapat dicegah, atau apakah akibatnya dapat dikurangi untuk setiap individu.
d. Seberapa besar angka kejadian faktor tersebut dan akibatnya terhadap total populasi. Apakah prevelensinya bertambah atau berkurang ?
e. Apakah faktor tersebut dapat dicegah, atau akibatnya dapat dikurangi dalam populasi.
f. Bagaimana proporsi dari kesakitan, pengurangan performance kejadian kematian sebelumnya didalam populasi, dapat menggambarkan faktor ini untuk sekarang dan yang akan datang.
g. Bagaimana kira kira dengan pembiayaan dan keuntungan dari pencegahan dari faktor faktor tersebut, atau pengurangan efek kasus tersebut dalam populasi yang besar berdasarkan hasil intervensi pada kelompok masyarakat yang lebih kecil.
h. Bagaimana dengan keuntungan sesungguhnya dan biaya intervensi dalam populasi yang lebih besar.
Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut diatas dilakukan penelitian
gizi dengan bentuk bentuk sebagai berikut :
a. Nutritional Assement :
Pengukuran dan deskripsi status gizi masyarakat dan hubungannya dengan sosial ekonomi, demografi, fisiologi yang memengaruhi keadaan gizi.
b. Monitoring :
Pengukuran perubahan status gizi dalam waktu tertentu
c. Sistem Isyarat Dini dan Intervensi ( SIDI ) :

E modul Epidemiologi Gizi 51
Pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan sehari hari dalam program kesehatan dan gizi.
5.5. Determinan yang Berpengaruh terhadap Status Gizi
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa masalah kurang gizi yang terjadi merupakan interaksi antara anak/orang (sebagai host), zat zat gizi (sebagai agent), dan lingkungan dimana mereka berada (sebagai environment). Oleh sebab itu, berbagai faktor baik faktor yang langsung maupun faktor yang tidak langsung berpengaruh terhadap status gizi, disatu pihat ditentukan oleh utilisasi zat gizi dan dilain pihak asupan zat gizi. Kedua faktor tersebut diatas sendiri sendiri atau bersama sama, dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti : lamanya sakit, seringnya sakit, kesehatan lingkungan, tersedianya sarana kesehatan, kuantitas dan kualitas makanan, pola pembagian makanan dalam keluarga, cara memilih bahan makanan, daya beli, tingkat pendidikan dan lain sebagaianya, sebagaimana terlihat dalam bagan 4.5.

Menurut Lechtig, dkk (Sanjur, 1982) status gizi seseorang adalah merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk kedalam tubuh (nutrient input) dengan kebutuhan tubuh (nutrient output) akan zat gizi dimaksud. Kebutuhan tubuh akan zat gizi ditentukan oleh banyak hal antara lain, tingkat dari metabolisme basal, tingkat pertumbuhan dan aktivitas fisik. Disamping itu beberapa faktor lain secara relatif dapat memengaruhi kebutuhan ini seperti adanya gangguan pencernaan (ingestions), perbedaan daya serap (absorption) dan tingkat penggunaan (ultization) yang tidak sama, atau perbedaan pengeluaran dan penghancuran (excretion and destruction) dari zat gizi tersebut.
Scrimshaw dan Taylor (1959) juga telah mengupas masalah hubungan timbal balik kurang gizi dan infeksi lebih dari tiga dekade yang lalu. Hubungan timbal balik antara kedua faktor tersebut menurutnya jarang dapat ditentukan yang mana dapat menyebabkan yang lain. Beberapa mekanisme saling pengaruh ini antara lain adalah : tidak adekuatnya intake makanan seseorang akan menyebabkan turunnya berat badan, terhambatnya pertumbuhan, turunnya imunitas dan kerusakan mukosa. Selanjutnya, keempat keadaan terakhir ini akan memengaruhi terjadinya penyakit infeksi, maupun lama dan keparahan keadaan infeksi tersebut.
E modul Epidemiologi Gizi 52
Gambar 5.5 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Status Gizi

Melihat beberapa determinan tersebut diatas maka status gizi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat komplek dan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya saling berkaitan. Dalam menilai keadaan gizi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu populasi maka faktor faktor tersebut diatas berguna untuk menganalisa sebab sebab serta proses proses gizi yang berujung pada status gizi. Sinclair melukiskan hubungan antara gizi sebagai proses dan status gizi (nutriture) sebagai akibat, bagaikan air sungai yang mengalir kedalam danau. Tingginya permukaan air danau tergantung kepada bagaimana aliran sungai yang memberi air. Aliran sungai tersebut langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.
Dengan demikian dalam menilai status gizi secara lengkap maka perlu diperhatikan 3 komponen yakni 1) Penentuan status gizi, 2) Penentuan proses gizi, 3) Penentuan lingkungan non gizi. Dalam pembicaraan selanjutnya akan dibatasi

E modul Epidemiologi Gizi 53
pada komponen 1 yaitu penentuan status gizi, baik perorangan/individu maupun kelompok.
5.6. Cara Penentuan Status Gizi
Tujuan dari pada penilaian status gizi adalah untuk memperoleh gambaran umum, wujud luas, masalah, siapa, dimana masalah faktor ekologi yang langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dilakukannya upaya upaya perbaikan.
Metode penentuan status gizi dapat digolongkan menjadi dua bagian besar yaitu : Penentuan Status Gizi secara langsung dan penentuan status gizi secara tidak langsung. Yang termasuk metode secara langsung meliputi :
1. Penilaian status gizi secara anthropometri

2. Penilaian status gizi secara biokimia
3. Penentuan status gizi secara klinis
4. Penentuan status gizi secara biofisik
Sedangkan penilaian status gizi secara tidak langsung meliputi :
1. Statistik vital
2. Konsumsi makanan
3. Faktor faktor ekologi
E modul Epidemiologi Gizi 54
BAB
SURVEILANS GIZI
6.1. Pengertian Surveilans Gizi
Menurut World Health Organizaton (WHO) Surveilans gizi adalah suatu sistem pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berhubungan dengan masalah dan program gizi yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan dan program gizi dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk keadaan darurat kondisi kesehatan masyarakat, mendokumentasikan dampak dari intervensi yang telah dilakukan dan memantau masalah gizi yang terjadi di masyarakat.

Pengertian ini juga sejalan dengan keputusan menteri kesehatan RI (2014) yang mendefenisikan surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah masalah kesehatan termasuk masalh gizi dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan, penularan penyakit masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
6.2. Tujuan Surveilans
Beberapa tujuan surveilans yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem surveilans :
a. Deteksi dan prediksi masalah terkait gizi
b. Monitoring kecenderungan untuk memperhatikan perubahan dalam melakukan intervensi
c. Melakukan evaluasi terhadap program gizi
d. Memproyeksikan perencanaan pelayanan kesehatan
e. Eliminasi eradikasi penyakit.
6.3. Indikator Surveilans Gizi
Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola
E modul Epidemiologi Gizi 55
6
konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015, 2016, dan 2017 menunjukkan tidak terjadi banyak perubahan prevalensi balita gizi kurang maupun balita pendek (stunting). Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 prevalensi balita gizi kurang (underweight) secara berturut turut adalah 18,8%, 17,8% dan 17,8%. Sedangkan prevalensi balita pendek berturut turut sebesar 29,0%, 27,5% dan 29,6%. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018, terjadi penurunan prevalensi balita gizi kurang dari 19,6% menjadi 17,7%, penurunan prevalensi balita pendek dari 37,2% menjadi 30,8% dan penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 12,1% menjadi 10,2%. Riskesdas juga menunjukkan capaian kinerja gizi yang masih kurang optimal seperti persentase ibu hamil yang mendapat TTD sebesar 73,2%, persentase bayi 0 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 37,3% dan persentase balita mendapat vitamin A mencapai 82,4%.
Dengan mengacu pada data tersebut diatas diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi melalui kegiatan surveilans gizi, antara lain sebagai berikut:
1. Indikator Masalah Gizi
a. Persentase balita berat badan kurang (underweight);
b. Persentase balita pendek (stunting);
c. Persentase balita gizi kurang (wasting);
d. Persentase remaja putri anemia;

e. Persentase ibu hamil anemia;
f. Persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik (KEK); dan
g. Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (berat badan kurang dari 2500 gram).
2. Indikator Kinerja Program Gizi
a. Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif;
b. Cakupan bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif;
c. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
E modul Epidemiologi Gizi 56
d. Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan;
e. Cakupan balita kurus yang mendapat makanan tambahan;
f. Cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) ;
g. Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
h. Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S);
i. Cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS);
j. Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D);
k. Cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut turut (2T/D);
l. Cakupan balita 6 59 bulan mendapat kapsul vitamin A;
m. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A;
n. Cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; dan

o. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan kegiatan Surveilans Gizi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. Untuk itu diperlukan pedoman pelaksanaan teknis Surveilans Gizi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan masalah gizi masyarakat.
6.4. Konsep Surveilans Gizi
Kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan teknis Surveilans Gizi yaitu pengkajian (assessment), analisis (analysis) dan respon (action) yang merupakan suatu siklus Sistem Surveilans Gizi adalah alat untuk menghasilkan informasi yang sangat membantu dalam formulasi, modifikasi dan aplikasi kebijakan gizi disuatu wilayah. Surveilans mencakup informasi tentang pengaruh pola konsumsi gizi dan status gizi, oleh karena itu didalam analisis Surveilans Gizi juga membutuhkan informasi terkait faktor ekonomi, sosial budaya dan biologis.
E modul Epidemiologi Gizi 57
Gambar 6.1. Lingkaran 3A Penanggulangan Masalah Gizi (World Health Organization (WHO)), 2013

Berdasarkan gambar 5.1. dijelaskan fungsi Surveilans Gizi dalam menanggulangi masalah gizi ada 3 langkah yaitu pengkajian (assessment), analisis (analysis) dan respon (action).

1. Assessment atau pengkajian adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data mengenai situasi gizi populasi di suatu wilayah.
2. Analysis atau analisis adalah kegiatan menganalisis determinan masalah gizi termasuk penyebab langsung, tidak langsung dan mendasar. Analisis ini disajikan dalam bentuk informasi yang digunakan untuk diseminasi dan advokasi.
3. Action atau respon adalah tindakan yang didasari oleh hasil analisis dan sumber daya yang tersedia. Hasil analisis menjadi dasar perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan perencanaan program.
6.5. Penerapan Surveilans Gizi
1. Peramalan
Implementasi dari hasil Surveilans Gizi diawali dengan sebuah proses yang dinamakan peramalan. Selanjutnya dilakukan pemantuan, dan analisis situasi. Peramalan dan pemantauan situasi ini disebut sebagai Sistem Informasi Dini (SID). Program pangan dan gizi yang ditetapkan kemudian dilaksanakan sekaligus kewaspadaan (pemantauan) untuk tindakan segera dan pencegahan memburuknya situasi. Contoh dari Sistem Informasi Dini (SID):
E modul Epidemiologi Gizi 58
a. Kegiatan SID berupa pemantauan atas situasi di suatu wilayah atau kelompok masyarakat dengan menggunakan indikator pertanian. Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan luas tanam, luas panen, luas kerusakan lahan pertanian, atau perubahan jumlah produksi pangan, apakah terjadi adanya eskalasi perubahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan atau tidak. Rekomendasi dari kegiatan pemantauan indikator pertanian ini adalah untuk melakukan pencegahan apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah.
b. Kegiatan pemantauan pertumbuhan anak balita yang berbasis data hasil penimbangan bulanan (data SKDN: S = seluruh balita yang terdaftar, K = balita yang memiliki Buku KIA/Kartu Menuju Sehat, D = balita yang ditimbang, N = balita yang naik berat badannya), dengan melakukan konfirmasi. Idealnya, seluruh balita yang terdaftar memilik KMS, setiap bulan seluruhnya ditimbang, dan berat badannya naik. Rekomendasinya adalah informasi untuk pencegahan dan penanggulangan, jika kondisi ideal tidak tercapai, atau ambang batas yang disepakati tidak tercapai. Jika didapatkan balita dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS (BGM), perlu dilakukan konfirmasi oleh petugas puskesmas, dengan menggunakan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Hal ini untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk kategori gizi buruk yang perlu dirawat atau tidak.
c. Pemantauan indikator sosial ekonomi didasarkan kepada laporan regular instansi terkait, dengan melakukan konfirmasi. Indikator yang dapat dikumpulkan antara lain adalah perubahan tingkat daya beli masyarakat, khususnya untuk bahan pangan. Rekomendasinya adalah informasi dan langkah langkah alternatif untuk penanggulangan.
d. Pemantauan indikator lokal seperti kasus gizi buruk pada balita dan kelaparan dengan melakukan konfirmasi. Untuk indikator kemiskinan, kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan konsumsi

E modul Epidemiologi Gizi 59
makanan rumah tangga, apakah terjadi penurunan tingkat asupan gizi atau perubahan pola makan masyarakat setempat. Rekomendasinya adalah informasi untuk penanggulangan.
Secara diagramatik kegiatan peramalan serta penerapan sistem informasi dini, dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.
Gambar 6.2. Diagram Pelaksanaan Sistem Informasi Dini dalam Surveilans


Gizi (Abas Basuni Jahari)
Gambar 6.3. Diagram Sistem Informasi Dini dalam Implementasi Surveilans
Gizi (Abas Basuni Jahari)
Dalam gambar 6.3. di atas ditunjukan keterkaitan antara kegiatan analisis situasi pangan dan gizi dan kegiatan pemantauan/peramalan status gizi dan pemanfaatan informasinya untuk perumusan kebijakan,
Epidemiologi Gizi

E modul
60
perencanaan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Hasil analisis situasi pangan dan gizi dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi. Selanjutnya dalam penerapan kebijakan dan upaya perbaikan gizi dilakukan pengawalan oleh kegiatan pemantauan status gizi agar indikasi akan terjadinya masalah gizi dapat segera dideteksi dan ditanggulangi. Dengan demikian upaya perbaikan gizi masyarakat dapat dikelola lebih baik sehingga keadaan gizi masyarakat pada waktu waktu berikutnya akan menjadi lebih baik.
2. Analisis Situasi

a. Diagram Analisis
Analisis situasi pangan dan gizi serta faktor faktor penyebabnya, merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi hasil Surveilans Gizi di suatu wilayah. Hasil analisis digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk kebijakan dan perencanaan serta evaluasi program pangan dan gizi. Hasil analisis situasi bisa berupa Peta Masalah, Grafik, atau Tabel Angka. Pada akhir tahun berjalan, dilakukan kembali analisis situasi pangan dan gizi serta faktor faktor penyebabnya dengan menggunakan data yang tersedia selama kurun waktu tahun berjalan tersebut. Hasil analisis dijadikan bahan rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan dan perencanaan ulang program pangan dan gizi periode selanjutnya. Demikian seterusnya, proses ini berulang ulang merupakan siklus yang berkesinambungan dan seakan tanpa batas.
E modul Epidemiologi Gizi 61
Gambar 6.4. Diagram Analisis Situasi Pangan dan Gizi

1) Penyajian Hasil Analisis
Sesuai dengan tujuan Surveilans Gizi, maka analisis data harus dapat menyediakan informasi tentang:
a) Besaran masalah saat ini, baik yang terkait dengan pengelolaan program gizi (indikator input dan proses)
b) Besaran masalah yang terkait dengan indikator output dari pengelolaan program gizi
c) Besaran masalah yang terkait dengan outcome (indikator status gizi)

d) Kecenderungan (trend) dari indikator indikator tersebut pada poin a, b, dan c
e) Analisis hubungan berbagai situasi
f) Analisis situasi masalah gizi untuk memahami karakteristik permasalahannya dan faktor faktor atau penyebab yang terkait
Hasil hasil dari analisis tersebut di atas harus disajikan dalam bentuk: (1) Laporan atau publikasi rutin
E modul Epidemiologi Gizi 62
(2) Peta besaran masalah

(3) Grafik yang menggambarkan kecenderungan dari indikator indikator yang dipantau secara rutin dan teratur Penyajian informasi Surveilans Gizi dapat dilakukan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Berikut ini adalah contoh penyajian informasi Surveilans Gizi terkait dengan besaran masalah.
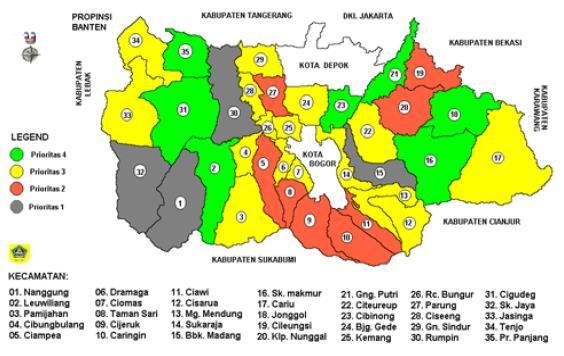
2) Peta prevalensi masalah gizi balita Contoh penyajian hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 8, yang menyajikan situasi keadaan gizi balita di Kabupaten Bogor. Pada peta tersebut tampak gradasi warna sebagai tanda besaran masalah dan tingkat prioritas upaya penanggulangannya. Terdapat empat tingkat prioritas masalah dengan pembedaan warna, yaitu: warna abu abu sebagai tingkat prioritas tertinggi, yang pada kasus ini meliputi empat kecamatan. Sedangkan prioritas tingkat kedua meliputi delapan kecamatan di wilayah selatan yang ditandai oleh warna merah. Penggunaan gradasi warna bisa menggunakan piranti lunak khusus atau manual. Dengan memanfaatkan gradasi warna sebagai gambaran tingkat prioritas, maka pemerintah maupun lembaga terkait, dapat segera mengambil langkah langkah alternatif penanganan masalah.
Gambar 6.5. Peta Keadaan Gizi Balita di Kabupaten Bogor Tahun 2018
E modul Epidemiologi Gizi 63
3) Grafik kecenderungan masalah gizi balita Gambaran masalah gizi juga dapat ditampilkan berupa grafik berdasarkan periode waktu, baik periode bulanan, tahunan, maupun periode tertentu sesuai dengan kebutuhan program. Gambar 9 dibawah ini menunjukkan kecenderungan angka prevalensi masalah gizi balita.
Gambar 6.6. Grafik Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek pada Balita di Kabupaten Bandung Barat

Situasi kecenderungan masalah gizi dapat dibuat berdasarkan kategori status gizi, yaitu balita gizi kurang, balita pendek, dan balita kurus. Contoh kecenderungan seperti itu dapat dilihat pada Gambar 5.6, yang menampilkan data hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2014 2017.
Pada gambar 5.7 disajikan contoh grafik perkembangan persentase balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) di Posyandu.

E modul Epidemiologi Gizi 64
Gambar 6.7. Grafik Persentase Balita yang Naik Berat Badan hasil Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu
Pada gambar 11 disajikan contoh grafik kecenderungan persentase partisipasi balita datang ke Posyandu (D/S).

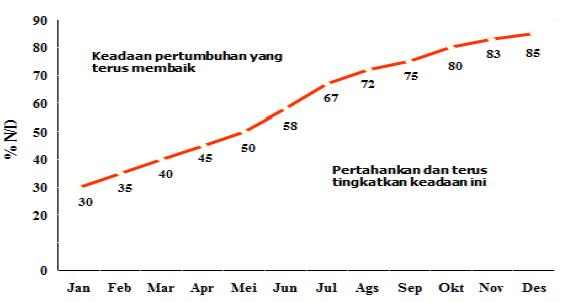
Gambar 6.8. Grafik Partisipasi pada Kegiatan Penimbangan Bulanan di Posyandu
6.6. Tahap Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi ditujukan kepada seluruh kelompok umur dalam siklus kehidupan, yaitu Anak Sekolah dan Remaja, WUS (Wanita Usia Subur), Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Dewasa, dan Lanjut Usia.
Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan mulai dari Posyandu, Puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Tahapan Surveilans Gizi meliputi
E modul Epidemiologi Gizi 65
pengumpulan, pengolahan, analisis data dan diseminasi informasi serta pemanfaatan data dengan alur seperti terlihat pada gambar 12.

Gambar 6.9. Tahapan Surveilans Gizi
modul Epidemiologi Gizi

E
66
6.7. Evaluasi Sistem Surveilans
WHO (2014) merumuskan kerangka konsepsional evaluasi sistem surveilans
sebagai berikut:
Struktur Sistem Surveilans
Legal aspek termasuk
IHR ‟05

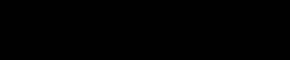
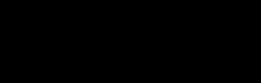

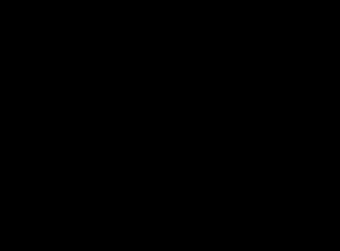
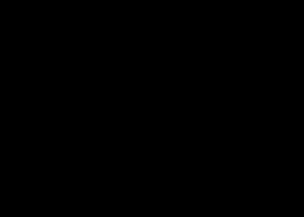


Strategi & Kebijakan Nasional Stake holder
Jejaring SE (Lab, UPT/D, LS, Reg, Global)

Fungsi Pokok Sistem Surveilans
Definisi kasus/masalah Registrasi Konfirmasi Pelaporan Analisis & Interpretasi Kesiapsiagaan Respon Umpan balik
Kualitas Sistem Surveilans
Kesederhanaan fleksibilitas Akseptibilitas Sensitifitas Spesifisitas Kerepresentatifan
Fungsi Pendukung Kegiatan
Standart & Guideline Training Supervisi Dukungan sarana, tenaga Monitoring & Evaluasi Koordinasi
Gambar 6.10. Kerangka Konseptual Evaluasi Sistem Surveilans Menurut WHO
Quadrant kanan atas berisi delapan Fungsi Pokok Surveilans (Core Function), berikut keterangan masing masing fungsi :
1. Deteksi kasus : proses mendeteksi peristiswa atau kejadian kesehatan. Unit sumber data menyediakan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan surveilans epidemiologi termasuk rumah sakit, puskesmas, laboratorium, unit penelitian, unit program sektor dan unit statistik lainnya.
2. Registrasi: proses pencatatan harus hasil identifikasi peristiwa atau keadaan kesehatan.
3. Konfirmasi : evaluasi dari ukuran ukuran epidemiologi sampai pada hasil penacatatan laboratorium.
modul Epidemiologi Gizi
E
67
4. Pelaporan: data, informasi, rekomendasi sebagai hasil kegiatan surveilans epidemiologi disampaikan kepada pihak pihak yang dapat melakukan tindakan penanggulangan penyakit atau upaya peningkatan program kesehatan, pusat pusat penelitian dan riset riset lainnya serta pertukaran data dan jejaring surveilans epidemiologi lainnya. Pengumpulan data harus pasien dari tingkat yang lebih rendah dilaporkan kepada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti lingkup daerah atau nasional.
5. Analisa data: analisis terhadap data data dan angka angka dan menentukan indikator terhadap tindakan
6. Respon sasaran/kesiapsiagaan wabah: kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah/kegiatan luar biasa.
7. Respon terencana: sistem pengawasan kesehatan masyarakat hanya dapat digunakan jika data yang ada bisa digunakan dalam peringatan dini dan munculnya masalah dalam masyarakat.
8. Umpan balik : berfungsi penting dari semua sistem pengawasan, alur pesan dan informasi kembali ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat yang lebih tinggi.

Quadrant kanan bawah berisi fungsi fungsi pendukung sistem Surveilans yaitu : perumusan protap dan petunjuk surveilans, pelatihan, supervisi, komunikasi, logistik, dan koordinasi. Fungsi fungsi ini diharapkan dilaksanakan oleh staff Unit Pendukung Surveilans (UPS) di Dinas Kesehatan
Quadrant kiri bawah memperlihatkan kriteria mutu surveilans yaitu kecepatan, kelengkapan, kegunaan, sensitivitas, spesifisitas, fleksibilitas, kesederhanaan, akseptabilitas, reliabilitas, nilai prediksi positif, dan keterwakilan. Beberapa kriteria inilah yang menjadi atribut sistem surveilans yang akan dinilai. Berikut adalah keterangan dari masing masing kriteria atribut Surveilans :
a. Kesederhanaan
Kesederhanaan sistem surveilans menyangkut struktur dan pengorganisasian sistem. Besar dan jenis informasi yang diperlukan untuk menunjang diagnosis, sumber pelapor, cara pengiriman data, organisasi yang menerima laparan, kebutuhan pelatihan staf, pengolahan dan analisa data perlu
E modul Epidemiologi Gizi 68
dirancang agar tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar dan prosedur yang terlalu rumit.
b. Fleksibilitas
Sistem surveilans yang fleksibel dapat mengatasi perubahan perubahan dalam kebutuhan informasi atau kondisi operasional tanpa memerlukan banyak biaya, waktu dan tenaga.
c. Akseptabilitas
Akseptabilitas terhadap sistem surveilans tercermin dari tingkat partisipasi individu, organisasi dan lembaga kesehatan. Interaksi sistem dengan mereka yang terlibat, temasuk pasien atau kasus yang terdeteksi dan petugas yang melakukan diagnosis dan pelaporan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tesebut. Beberapa indikator akseptabilitas terhadap sistem surveilans adalah jumlah proporsi para pelapor, kelengkapan pengisian formulir pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan. Tingkat partisipasi dalam sistem surveilans dipengaruhi oleh pentingnya kejadian kesehatan yang dipantau, pengakuan atas kontribusi mereka yang terlibat dalam sistem, tanggapan sistem terhadap saran atau komentar, beban sumber daya yang tersedia, adanya peraturan dan perundangan yang dijalankan dengan tepat.
d. Sensitivitas.
Sensitivitas suatu surveilans dapat dinilai dari kemampuan mendeteksi kejadian kasus kasus penyakit atau kondisi kesehatan yang dipantau dan kemampuan mengidentifikasi adanya KLB atau wabah. Faktor faktor yang berpengaruh adalah :
1) Proporsi penderita yang berobat ke pelayanan kesehatan
2) Kemampuan mendiagnosa secara benar dan kemungkinan kasus yang terdiagnosa akan dilaporkan
Suatu sistem surveilans yang kurang sensitif masih bemanfaat untuk memantau adanya trend kejadian penyakit asalkan sensitivitas sistem tersebut tidak berubah.
e. Nilai Prediktif positif
Daya prediksi suatu sistem surveilans diukur sebagai proporsi mereka yang diidentifikasi sebagai kasus, yang memang menderita penyakit atau kondisi

E modul Epidemiologi Gizi 69
sasaran surveilans (positive predictive value). Surveilans dengan nilai prediksi rendah akan banyak menimbulkan kasus yang sebenarnya merupakan penyakit lain dan bukan penyakit sasaran surveilans. Akibatnya terjadi pemborosan khususnya bila kasus kasus palsu tersebut diselidiki sebagai wabah. Daya prediksi dipengaruhi oleh prevalensi atau insidensi penyakit dan sensitivitas alat .
f. Kerepresentatifan

Sistem surveilans yang representatif mampu mendeskripsikan secara akurat distribusi kejadian penyakit menurut karakteristik orang, waktu dan tempat. Kualitas data merupakan karakteristik sistem surveilans yang representatif. Data surveilans tidak sekedar pemecahan kasus kasus tetapi juga diskripsi atau ciri ciri demografik dan infomasi mengenai faktor resiko yang penting.
g. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu suatu sistem surveilans dipengaruhi oleh ketepatan dalam memproses data mulai dari deteksi, pengisian form, pelaporan dan pengolahan data serta pendistribusian informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan. Pelaporan penyakit penyakit tertentu perlu dilakukan dengan cepat agar dapat dikendalikan secara efektif atau agar tidak meluas sehingga membahayakan masyarakat. Ketepatan waktu dalam sistem surveilans dapat dinilai berdasarkan ketersediaan infomasi untuk pengendalian penyakit yang mendesak atau untuk perencanaan program program dalam jangka panjang. Teknologi komputer semakin mampu mendukung ketepatan waktu penyediaan informasi dalam sistem surveilans.
Quadrant kiri atas menunjukkan struktur yang mengatur surveilans, yaitu perundang undangan, legislasi dan peraturan peraturan international health regulation (IHR), strategi surveilans, aliran data antar tingkat administratif, dan jejaring/kemitraan.
E modul Epidemiologi Gizi 70
UKURAN FREKUENSI DAN ASOSIASI EPIDEMIOLOGI GIZI
7.1. Pentingnya Ukuran Epidemiologi
Salah satu unsur pokok yang terdapat pada epidemiologi adalah mempelajari tentang ukuran ukuran masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok masyarakat. Dengan demikian untuk dapat memahami epidemiologi dengan baik, haruslah dipahami pula tentang ukuran ukuran tersebut. Dengan diketahuinya ukuran ukuran dimaksud, akan dapat diketahui keadaan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk kemudian dengan pengetahuan tersebut akan dapat disusun berbagai jalan keluar guna mengatasinya. Ukuran-ukuran epidemiologi yang dimaksudkan adalah keterangan tentang banyaknya suatu masalah kesehatan yang ditemukan dalam sekelompok manusia yang dinyatakan dengan angka mutlak, rate maupun ratio
Dalam pokok bahasan ini, akan diuraikan beberapa ukuran epidemiologi yang meliputi: 1) Angka insidensi, 2) Angka serangan, 3) Distribusi proporsi, 4) Angka kematian, 5) Ratio. Dipilihnya kelima ukuran tersebut adalah karena paling seringnya dipakai untuk mengukur dan menjelaskan peristiwa kesakitan dan kematian. Dengan mempelajari ke 5 ukuran diatas diharapkan para pengguna lainnya dapat :
a. Mendefinisikan angka insidensi, angka serangan, distribusi proporsi, angka kematian dan ratio

b. Menggunakan kelima cara perhitungan untuk menganalisa soal yang diberikan
c. Menentukan dengan tepat pembilang dan penyebut dari perhitungan suatu data tertentu yang diberikan
d. Melakukan perhitungan dengan tepat dan menafsirkan hasil maupun gambaran yang diperoleh.
E modul Epidemiologi Gizi 71 BAB 7
7.2. Ukuran Frekuensi Penyakit
Data epidemiologi dapat dikatagorikan kedalam 3 jenis data yaitu : data kelahiran (fertility), datra kematian (mortality) dan data kesakitan (morbidity).
Data kesakitan lebih sulit didapatkan bila dibandingkan dengan kedua data yang lain karena gejala penyakit sangat bermacam macam dan sukar ditentukan kapan mulai terjadinya.
Agar hasil pengukuran dapat dipakai orang lain dan dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang lain maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pengukuran tersebut.
a. Definisi dari penyakit atau ciri ciri yang akan diukur serta cara pengukurannya. Misalnya penyakit gizi (KEP) dapat diukur dengan klinis, biokimia, maupun dengan antropometri. Ketiga macam ukuran akan menghasilkan jumlah yang berbeda.
b. Apakah yang dihitung jumlah penyakit atau penderita itu sendiri. Hal ini penting karena ada penyakit yang menyerang seseorang berkali kali seperti diare, influenza dan lain lainnya.
c. Apakah yang dihitung adalah penderita baru saja atau penderita lama dan baru.
Pernyataan frekuensi penyakit dalam epidemiologi biasanya daklam arti perbandingan diantara populasi atau di antar sub kelompok di dalam populasi itu. Perbandingan tersebut harus memenuhi unsur pembilang (numerator), penyakit (denominarator) dan waktu atau jarak waktu (periode).
Angka kesakitan adalah jumlah frekwensi kejadian penyakit pada suatu populasi/penduduk tertentu. Untuk penilaian besarnya angka tersebut harus dilengkapi dengan tempat atau waktu kejadian. Pada dasarnya ada tiga angka kesakitan yang sering digunakan yakni insidensi, angka serangan (attack rate) dan prevalensi.
a. Rate : Rate suatu penyakit adalah nilai relative kejadian penyakit tertentu dalam suatu populasi tertentu pula. Dalam mencari rate harus memenuhi unsur unsur tertentu yaitu :

E modul Epidemiologi Gizi 72
1) Pembilang adalah jumlah kasus penyakit yang terdapat didalam suatu populasi atau sub kelompok dalam populasi.
2) Penyebut adalah populasi atau sub kelompok didalam populasi yang mempunyai resiko untuk mendapatkan penyakit yang bersangkutan (susceptible).
3) Waktu, misalnya pukul 12.00, tgl 1 januari 1992, 1 hari, 1 bulan.
Dengan demikian rumus umum rate adalah sbb :

a = jumlah kejadian penyakit pada waktu tertentu
b = jumlah populasi dimana kejadian tersebut berlangsung dalam waktu tertentu
k = nilai perkalian tertentu (100, 1000, 10.000, dst ).

Nilai rate biasanya dihitung dalam bentuk rate umur (crude rates), ataupun dalam bentuk rate khusus (specific rate). Rate adalah untuk menggambarkan kejadian secara umum dalam suatu populasi tertentu sedangkan rate khusus lebih menekankan pada kejadian yang sifatnya khusus yang ada pada populasi tersebut seperti misalnya : umur, jenis kelamin, ras dan lain sebagainya. Populasi dalam rate tidak selalu populasi dalam arti demografi akan tetapi dapat dalam bentuk lain. Misalnya maternal Mortality Rate. Adalah jumlah kematian ibu diantara ibu yang melahirkaan dirumah sakit.
Contoh : Pada tahun 1992 disuatu rumah sakit terdapat 305 orang ibu melahirkan meninggal akibat suatu kelainan tertentu diantara 1.100 orang ibu yang melahirkan dirumah sakit tersebut. Maka angka kematian dari kasus tersebut akan menjadi : 305/1.100 x 100 = 27.7 %.
Dengan nilai rate seperti diatas kita dapat membandingkan berbagai kejadian antar kelompok kelompok penduduk tertentu ataupun antar waktu tertentu. Sedangkan membandingkan keadaan/kejadian berdasarkan nilai absolute akan memberikan gambaran yang kurang tepat.
E modul Epidemiologi Gizi 73
1. Rate Insidensi
Insidensi adalah jumlah penderita baru suatu penyakit tertentu pada suatu kelompok penduduk tertentu (populasi) selama jangka waktu tertentu. Rate insidensi biasanya digunakan pada studi prospektif. Nilai insidensi secara mutlak hanya digunkan untuk pelaporan penyakit secara rutin, umpanya untuk pelaporan penyakit tertentu baik mingguan maupun bulanan. Dalam prakteknya rate insidensi sering digunakan untuk menyatakan rate suatu penyakit dalam suatu daerah.
Catatan : pembilang hanya meliputi penderita baru penyakit tersebut dalam waktu tertentu, sedangkan penyebut adalah mereka yang mempunyai risk pada waktu itu dengan ketentuan bahwa penyebut penderita dan mereka dengan risk tetapi tidak menderita.
Rate insidensi dapat digunakan untuk :
1. Membandingkan peristiwa penyakit antar kelompok penduduk tertentu, maupun antara waktu yang berbeda
2. Menilai besarnya hubungan sebab akibat (assosiasi) serta besarnya pengaruh faktor penyebab/faktor keterpaparan
3. Menilai hasil usaha dibidang kesehatan terutama pencegahan
4. Menilai keadaan penyakit dari waktu ke waktu (trend secular)
Walaupun terdapat beberapa kegunaan, namun rate insidensi mempunyai beberapa kelemahan pemakaiannya yaitu :
a. Pembilangnya adalah kasus baru. Kasus baru ini sudah ditentukan oleh karena waktu serangan sesuatu penyakit tidak jelas. Beberapa kejadian dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah
Kapan mulainya gejala pertama
Waktu diagnose Tanggal notifikasi
Masuk rumah sakit
b. Sulit menentukan yang susceptible dengan yang bukan

E modul Epidemiologi Gizi 74
2. Angka Serangan (Attack Rate)
Adalah rate insidensi yang biasanya dihitung dalam nilai persen dan secara umum digunakan untuk menilai letusan/wabah penyakit menular ataupun pada peristiwa keracunan (misalnya pada common source epidemics).
Dalam perhitungan angka serangan secara umum, maka jumlah penderita (jumlah mereka yang terserang) pada suatu waktu tertentu didasarkan pada pelaporan penyakit tersebut atau dilakukan pencarian dan pelaporan penderita secara rutin.
Dengan demikian, maka derajat kebenaran nilai ini (tingkat reabilitasnya) sangat dipengaruhi oleh :
1. Kemantapan sistem yang digunakan dalam mencatat dan pelaporan penderita
2. Sifat alamiah penyakit itu sendiri.

Pada penyakit dengan gejala yang tidak jelas, atau sulit dilakukan diagnose, maka nilai angka serangan ini akan lebih rendah mutunya (kurang reliable). Penyebut dapat merupakan seluruh penduduk yang bersifat khusus (umur, jenis kelamin, ras dan lain sebagainya) atau penduduk dengan kategori lainnya (anak sekolah, tukang dokar dll). Dengan sendirinya data penyebut sangat dipengaruhi kebenaran catatan yang dimiliki. Sedangkan besarnya populasi juga dipengaruhi oleh periode waktu terjadinya serangan.
Oleh karena itu angka serangan ini merupakan nilai khusus/sifat khusus dari situasi penyakit pada sekelompok penduduk, amak sangat tepat digunakan untuk membandingkan keadaan penyakit tertentu pada sekelompok penduduk yang berbeda.
Perbedaan rate pada perbandingan tersebut merupakan perbedaan serajat keterpaparan serta derajat keterancaman (risk dan suceptable) yang ada pada masing masing populasi tersebut.
Angka serangan sekunder (secondary attack rate) merupakan suatu penilaian khusus pada penyakit infeksi/menular yang didasarkan pada jumlah penderita baru dijumpai pada suatu unit populasi tertentu, yang berasal dari kontak/penularan oleh kasus primer dalam suatu tertentu yang sesuai dengan masa
E modul Epidemiologi Gizi 75
tunas penyakit tersebut. Rumus untuk angka serangan sekunder ( ASS) adalah sbb:
Sedangkan rumus untuk angka serangan umum, sama dengan rumus insidensi rate hanya saja konstanta ( k ) hampir selalu 100.


Contoh :

Dalam suatu letusan (our break yang melibatkan 26 kasus penyakit “X”, 7 kasus wanita dan 19 laki laki dalam kelompok dimana terjadi letusan ada sejumlah 9 wanita dan 87 laki laki. Berapakah angka serangan menurut jenis kelamin dan seluruh anggota kelompok ?
Perhitungan :

Perhatian :
Untuk menghitung angka serangan seluruhnya diperoleh dengan cara membagi jumlah kasus seluruhnya dengan jumlahn seluruh orang, tidak dengan menjumlahkan angka serangan dari masing masing jenis kelamin.
3. Rate Pravalensi
Pravalensi adalah jumlah penderita penyakit tertentu dalam suatiu kelompok penduduk tertentu pada suatu jangka waktu tertentu, atau pada suatu titik waktu tertentu. Dalam perhitungan prevalensi, maka yang sering digunakan adalah prevalensi poada titik waktu tertentu (Point Prevalence) sedangkan prevalensi pada periode waktu tertentu (Period Prevalence) biasanya digunakan dalam laporan rutin atau data referensi.
modul Epidemiologi Gizi 76
E
Rate prevalensi merupakan jumlah penderita (seluruhnya) dalam suatu populasi tertentu terhadap jumlah total penduduk tersebut, tanpa melihat factor risk.
Dengan melihat angka prevalensi dan angka insidensi, tampak bahwa angka prevalensi mengarah kepada keadaan penyakit dalam masyarakat pada saat tertentu, sedangkan insidensi lebih menunjukkan ke kejadian penyakit pada waktu tertentu. Rate prevalensi dapat kita lihat umpamanya pada jumlah penderita penyakit hasil survai tertentu dalam masyarakat.
4. Hubungan dan Kegunaan dari prevalen rate dan Insidensi Rate
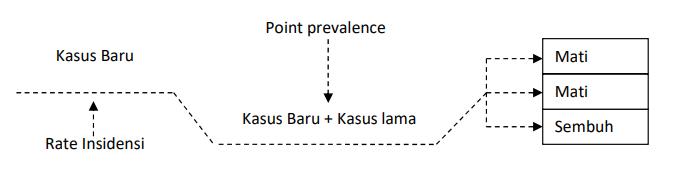


Point prevalen didapatlkan bila dilakukan sensus terhadap penduduk atau dengan melakukan survai. Jadi point prevalen adalah suatu ukuran frekwensi dari penyakit pada saat tertentu dan menyatakan proporsi dari penduduk yang sakit pada saat tertentu.
Insidensi rate biasanya didapat dari suatu penelitian dalam mana kita dapat menghitung frekwensi dari kasus baru. Bila insidensi rate hendak dihitung pada suatu daerah, maka sebagai penyebutnya adalah jumlah penduduk pada pertengahan periode yang bersangkutan. Hubungan antara poin prevalen dengan insidensi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
Gambar 7.1. Hubungan Antara Poin Prevalen dengan Insidensi
Hubungan antara rate insidensi dengan rate prevalensi serta lamanya masa sakit juga ditentukan oleh penyakit itu sendiri. Artinya pada penyakit yang waktu penyembuhannya lebih lama (penyakit menahun) akan memberikan angka
E modul Epidemiologi Gizi 77
prevalensi yang lebih besar walaupun insidensinya lebih rendah atau sama dengan penyakit lainnya dengan masa sakit yang lebih pendek. Sedangkan masa sakit sangat erat hubungannya dengan pengobatan, perawatan, tingkat fasilitas penyakit dan lain sebagainya. Dengan demikian, prevalensi dapat berubah dengan adanya proses penyembuhan yang lebih cepat (umpamanya pengobatan baru) atau karena fasilitas penyakit lebih cepat prosesnya (umpamanya tetanus neonatorum, rabies dan lainnya). Insidensi dan Prevalensi dapat meningkat walaupun insidensi tetap/menurun umpamanya bila masa sakit bertambah panjang.
Nilai prevalensi merupakan niai yang menyatakan keadaan penyakit dalam masyarakat pada waktu itu, dan sangat berguna untuk :
1. Menilai keadaan penyakit pada masyarakat tertentu bila dibandingkan dengan populasi lain atau pada waktu yang berbeda
2. Menjadi dasar dalam perencanaan kesehatan
3. Membantu menyusun fasilitas dana, material maupun tenaga
4. Untuk menilai hasil kegiatan terutama bidang kesehatan
5. Hubungan Prevalensi, Insidensi dan Periode Waktu

Makin lama periode waktu suatu penyakit seperti apa yang disebut dengan penyakit kronis akan makin tinggi prevalen penyakit tersebut. Bila periode waktu dinyatakan dengan D dan prevalen dinyatakan dengan P, makan pada penyakit kronis, bila D tinggi maka P akan tinggi.
Tetapi pada penyakit akut dimana periode waktu sangat pendek maka insidens akan semakin tinggi. Secara perhitungan sederhana dapat dilukiskan sebagai berikut:
Penyakit kronis D → P D = f (P)
Penyakit Akut D → P D = f ( 1/I)
E modul Epidemiologi Gizi 78
6. Perbedaan antara Prevalensi dan Insidensi


Perbedaan antara prevalensi dan Insidensi dapat dilihat pada Tabel 7.1.
Tabel 7.1.
Perbedaan Prevalensi dan Insidensi
7.3. Ukuran Kematian

Ukuran kematian merupakan frekuensi kejadian kematian pada kelompok penduduk tertentu, dalam waktu dan pada tempat tertentu pula. Angka kematian merupakan salah satu nilai yang dapat digunkaan untuk mengukur tingkat kesehatan kelompok penduduk tertentu.Dalam perhitungan ada berapa jenis angka kematian sesuai dengan kebutuhan / kegunaannya.
1. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate)
Angka kematian ini menggambarkan angka kematian sebenarnya yang diobservasi dalam suatu populasi, tanpa melihat sifat sifat khusus dari pada kelompok tersebut.
Angka kematian kasar (AKK) merupakan efek dari faktor :
1) Probabilitas untuk mati (faktor ini secara tepat untuk diukur dengan angka kematian menurut umur)
2) Karakteristik/distribusi umur dari populasi
Pada umumnya nilai ini dihitung dalam perseribuan, namun nilai ini kadang kadang memberikan gambaran yang kurang tepat bila digunakan untuk
E modul Epidemiologi Gizi 79
membandingkan dua atau lebih kelompok penduduk dengan sifat karakteristik yang berbeda.Terutama karena perbedaan penyebaran umur, jenis kelamin, ras serta sifat karakteristik person lainnya. Untuk menghindari hal tersebut dapat dilakukan standarisasi atau penyesuaian (adjustment).
2. Angka kematian Sebab Khusus (Cause Specific Death Rate)
Angka ini didasarkan pada jumlah kematian karena sebab/penyakit tertentu (penyebab kematian berdasarkan laporan/daftar kematian) terhadap jumlah seluruh seluruh penduduk yang risk (jangan keliru dengan proporsi) pada waktu dan tempat tertentu. Angka ini biasanya digunakan untuk membandingkan pengaruh sebab kematian khusus antar populasi tertentu dengan sifat yang berbeda.
3. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate)
Bayi merupakan kelompok umur khusus yang mempunyai risk tersendiri terhadap peristiwa kejadian penyakit dan peristiwa kematian. Berbagai aspek pelayanan kesehatan sangat erat hubungannya dengan angka kesakitan dan kematian bayi antar lain : sistem pelayanan kesehatan melalui KIA, Program Imunisasi, program perbaikan gizi, keadaan sanitasi lingkungan setempat serta berbagai hal lainnya yang erat hubungannya dengan kesehatan. Dengan demikian, maka angka kematian bayi sanhgat erat hubungannya dengan status kesehatan serta tingkat kemajuan kesehatan kelompok penduduk tertentu, baahkan merupakan salah satu indikator/tolak ukur derajat kesehatan.
Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa hanya mereka yang lahir hidup diperhitungkan dalam penyebut, yakni mereka yang mempunyai risk untuk mati. Selain angka kematian bayi dikenal Angka kematian perinatal (antara kehamilan 28 minggu s/d umur satu minggu kelahiran).
Angka kematian Neonatal (Kematian bayti sampai umur 28 hari)
modul Epidemiologi Gizi

E
80
4. Angka Kematian Balita (Bawah Lima Tahun)

Nilai ini hampir sama pentingnya dengan kematian bayi, dengan mengutamakan kematian anak bawah lima tahun (tanpa atau dengan bayi). Bila populasi anak balita (tanpa bayi) diketahui maka angka tersebut lebih memberikan arti yang cukup penting.
5. Angka Kematian Kelompok Khusus Lainnya :
Angka kematian ibu yang didasarkan atas jumlah kematian ibu karena proses reproduksi dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran tahun tersebut. Dalam hal ini seharusnya yang dipakai adalah jumlah kelahiran dalam tahun itu, tetapi disepakati mengambil jumlah kelahiran karena alasan pencatatan dan pelaporan.
Angka kematian lainnya seperti umur khusus, jenis kelamin tertentu, rasa tertentu dsbnya. Dihitung berdasarkan kebutuhan analisa. Angka ini dapat digunakan untuk melihat beratnya/pengaruh penyakit dalamn masyarakat sebagai kematian.
Dalam hal ini, penyebut merupakan orang yang menderita penyakit A yang mendapat risiko akan mati. Sedangkan pembilang adalah jumlah orang yang mati karena penyakit A. Bila CFR dihitung dalam periode tertentu maka CFR merupakan suatu insiden rate. Oleh karena setiap kematian merupakan insiden yang baru. CFR menggambarkan keganasan (fatality) suatu penyakit sehingga menyebabkan kematian. Bila CFR penyakit A lebih tinggi dari CFR penyakit B, maka penyakit A lebih fatal dari penyakit B.
Dalam menilai CFR maka kita harus benar benar menilai kematian oleh penyakit tertentu secara pasti serta jumlah penderita dalam waktu yang sama. Biasanya nilai CFR dirumah sakit akan lebih tinggi dari pada nilai yang sebenarnya untuk berbagai penyakit tertentu, karena hanya penderita yang berat yang berobat kerumah sakit sehingga tidak semua penyakit tersebut dicatat. Sedangkan perhitungan CFR untuk penyakit menahun, nilainya akan berbeda
E modul Epidemiologi Gizi 81
sangat tergantung cara perhitungan, apakah berdasarkan cross sectional dimana penderita dan yang meninggal diambil pada waktu yang sama, ataukah berdasarkan kohort dimana penderita yang diamati dan kematian yang dicatat pada waktu dan orang yang sama.

Proporsi
Adalah suatu persen (yakni proporsi dari jumlah peristiwa peristiwa dalam sekelompok data yang mengenai masing masing kategori/sub kelompok dari kelompok itu). Dapat pula dikatakan bahwa proporsi adalah jumlah perbandingan (ratio) dimana pembilangnya merupakan sebagian dari penyebutnya. Hasilnya merupakan bilangan pecahan dan nilai terbesar adalah satu. Persen adalah proporsi yang dikalikan dengan 100, sedangkan rate merupakan bentuk proporsi yang paling sering dipakai dalam epidemiologi.
Rumus : Dimana :
x = banyaknya peristiwa atau orang, dll yang terjadi dalam kategori tertentu atau sub kelompok dari kelompok yang lebih besar.

y = jumlah peristiwa satu orang, dll yang terjadi dalam semua kategori dari kelompok data tersebut.
k = selalu sama dengan 100 Proporsi umumnya dipakai dalam keadaan dimana tidak mungkin menghitung angka insidensi; karena itu ia tidak dapat menunjukkan peluang keterpaparan atau infeksi, kecuali jika banyaknya peristiwa, orang, dll, terhadap mana peristiwa dapat terjadi adalah sama pada setiap sub kelompok. Akan tetapi hal ini biasanya sangat jarang terjadi.
Karena x dan y berada pada tempat yang sama, berbagai persen dalam kelompok data yang asda dan seharusnya dapat saling ditambahkan dari semua kategori data, dan jumlahnya harus menjadi 100 %. Sedangkan angka rate tidaklah demikian
E modul Epidemiologi Gizi 82
Interpretasi proporsi adalah dari jumlah frekwensi dimana suatu jenis peristiwa tertentu terjadi, kejadiannya dinyatakan dalam persen dari berbagai sub kelompok utama.

Contoh : Suatu letusan mengenai 26 kasus penyakit x, 7 wanita dan 19 laki laki. Jumlah orang dari masing masing jenis kelamin yang berada dalam kelompok tidak diketahui. Berapa proporsi kasus menurut jenis kelamin?

Persen Lelaki = 19/26 x 100 = 73,1 %
Persen Wanita = 7/26 x 100 = 26, 9 %
Ratio
Adalah suatu perbandingan, dimana ciri ciri yang dibandingkan tidak diharuskan sama, misalnya sex ratio dari penyakit radang hati adalah lelaki : wanita = 3 : 1. Ini menunjukkan sifat dari penderita penyakit tersebut
Dapat pula dikatakan bahwa ratio adalah suatu pernyataan frekwensi nisbi kejadian suatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya.
Misal: jumlah anak sekolah kelas VI yang sudah diimmunisasi dibandingkan dengan jumlah anak sekolah kelas VI yang tidak diimmunisasi pada suatu sekolah tertentu.
Catatan
Populasi dan masa jedah/titik waktu dari data yang dipakai haruslah tertentu/khusus, sama seperti unuk angka/rate. Ratio dapat dihitung untuk angka hanya sebagai banyaknya oeristiwa. Umunya, kedua pembilang nilai (x) maupun penyebut ( y ) dibagi oleh, baik nilai x maupun nilai y sehingga salah satu nomor dalam nilai ratio menjadi sama dengan 1,0.
Misal : jika suatu kelompok 20 orang menderita suatu penyakit tertentu dan 2 mati karenanya, maka ratio kasus terhadap kematian lebih tepat dinyatakan 10 : 1 (10 kasus : 1 mati), bukan 20 : 2, tetapi kedua angka itu dibagi menjadi 2, sehingga hasilnyya sebagaimana ttersebut diatas. Interpretasinya adalah : bahwa pada
E modul Epidemiologi Gizi 83
episode ini dalam 10 kasus ada 1 yang mati. Atau, 10 kali banyaknya kasus dari kematian.
7.4. Ukuran Ukuran Risiko

1. Relative Risk
Merupakan ratio (bukan rate) insiden penyakit dari sekelompok yang terpapar dengan inseiden penyakit dari kelompok yang tidak terpapar oleh semua faktor. Relative risk bukan menunjukkan insiden suatu penyakit, tetapi menyatakan beberapa banyak resiko seseorang yang terpapar suatu factor akan meningkat diabndingkan dengan yang tidak terpapar oleh suatu faktor.

Relative risk juga menunjukkan manfaat tentang kemungkinan berkurangnya penderita jika faktor resiko tersebut dapat dihindarkan. Sebagai contoh: ukuran penurunan resiko penderita paru paru yang telah berkorban untuk merubah sikap dengan berhenti merokok. Namun demikian, relative risk tidak mengukur probabilitas bahwa dengan faktor tersebut akan menderita suatu penyakit.
Relative risk juga mengukur kuatnya hubungan antara faktor dan kejadian tertentu, jadi angka relative risk menunjukkan penyebab dan berguna dalam penelitian etiologi suatu penyakit.
Melihat hasil (RR) tersebut diatas maka keluarga yang miskin, 9 kali kemungkinan anak balitanya akan meninggal karena menderita gizi buruk dibandingkan dengan balita dari keluarga yang mampu.
E modul Epidemiologi Gizi 84
2. Atributable Risk
Attributable risk (AR) merupakan ukuran insiden dari kelompok yang dinyatakan terpapar terhadap salah satu factor (kemiskinan). AR dapat dihitung dengan cara insiden rate dari kelompok yang terpapar dikurangi insiden dari kelompok yang tidak terpapar. Dengan demikian maka :

AR dapat mengukur pengaruh apabila faktor tertentu yang menimbulkan penyakit dihilangkan. Karena itu program intervensi dapat didasarkan atas nilai AR. Identifikasi AR dari berbagai pemaparan pada penyakit tertentu merupakan alat bantu yang rasional dalam perencanaan pelayanan kesehatan.

E modul Epidemiologi Gizi 85
BAB
PAPARAN OUTCOME DAN CONFOUNDER MASALAH GIZI
8.1. Variabel Penelitian
Konsep adalah suatu abstraksi dari suatu realita atau fenomena yang kepadanya diberikan nama atau istilah untuk dapat mengkomunikasikan tentang realitas atau fenomena. Sedang variabel adalah operasionalisasi dari suatu konsep atau konsep yg mempunyai bermacam macam nilai atau segala sesuatu yang bervariasi. Variasi nilai adalah ciri objektif variabel berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari hasil menghitung atau mengukur. Misalnya status gizi merupakan variabel penelitian karena mempunyai variasi nilai yaitu status gizi kurang, gizi normal dan gizi lebih atau contoh yang lain yaitu kecemasan karena mempunyai variasi nilai yaitu cemas ringan, cemas sedang, dan cemas berat. Selanjutnya, luas ventilasi merupakan variabel penelitian karena mempunyai variasi yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Secara sederhana pengertian variabel penelitian adalah Suatu objek yang akan diteliti dan mempunyai variasi nilai. Objek itu bisa makhluk hidup, ataupun benda mati.

Ciri ciri dari variabel adalah :
1. Dapat didefinisikan dengan jelas
2. Dapat diukur atau diobservasi
3. Hasil ukur akan bervariasi antara satu objek dengan objek lain.
8.2. Jenis variabel
1. Variabel Independen/Paparan
Variabel independen/paparan sering disebut juga sebagai variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dengan demikian variabel independen mempunyai ciri ciri :
Variabel yang menentukan variabel
Kegiatan stimulus yang dilakukan peneliti menciptakan suatu dampak pada
Variabel dependen
Biasanya dimanipulasi, diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya
E modul Epidemiologi Gizi 86
8
2. Variabel Dependen/Outcome
Variabel dependen disebut juga variabel terikat, variabel akibat, variabel respon, output, konsekuen,. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel terikat yang besarannya tergantung dari besaran variabel indpenden ini, akan memberi peluang terhadap perubahan variabel dependen (terikat) sebesar koefisien (besaran) perubahan dalam variabel indepen. Artinya, setiap terjadi perubahan sekian kali satuan varibel dependen, diharap akan menyebabkan variabel depnden berubah sekian satuan juga. sebalikanya jika terjadi diharapkan akan menyebabkan perubahan (penurunan) variabel dependen sekian satuan juga. Dengan demikian variabel dependen mempunya ciri:

Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain
Asepek tingkah laku yang diamati dari suatu organiseme yang dikenai stimulus
Faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Sebagai contoh: Hubungan umur balita dengan status gizi.
3. Variabel Confounding/Perancu
Variabel perancu merupakan jenis variabel yang berhubungan dengan variabel bebas danvariabel tergantung, tetapi bukan merupakan variabel antara. Keberadaan variabel perancu dapat memengaruhi validitas penelitian. Contoh variabel perancu yaitu jika suatu penelitian inginmencari hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian penyakit jantung korener (PJK) pada lelaki dewasa. Jika diantara lelaki tersebut ada yang merokok maka merokok dapatmemengaruhi hasil penelitian. !al ini dikarenakan biasanya terdapat hubungan antara kebiasaanminum kopi dengan merokok, selain itu merokok juga diketahui berhubungan dengan PJK, oleh karena itu merokok dalam hal ini disebut variabel perancu.
Variabel perancu dapat menimbulkan bias yang serius, maka seorang penel iti harus berupaya untuk mengidenti&ikasi setiap variabel perancu dan menyingkirkan variabel perancu. Cara mengidenti&ikasi variabel perancu yaitu
E modul Epidemiologi Gizi 87
dengan studi literature komprehensi& selain&aktor pengalaman dan logika. Identifikasi semua variabel baik yang diteliti maupun yang tidak, menggolongkannya, kemudian membuat diagram hubungan antar variabel dalam diagram yang jelas.
4. Variabel Moderator
Variabel Moderator Variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Analisis hubungan yang menggunakan minimal dua variabel, yakni satu variabel dependen dan satu atau beberapa variabel independen, ada kalanya dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model statistik yang kita gunakan. Dalam analisis statistik ada yang dikenal dengan variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang selain bisa memperkuat hubungan antara satu atau beberapa variabel yang selain bisa memperlemah hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dan variabel dependen.

Misalnya pembelajaran laboratorium yang diikuti oleh mahasiswa gizi keperawatan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan individu. Seluruh mahasiswa yang mengikuti pembelajaran laboratorium tersebut memiliki jenjang pendidikan yang sama. Tetapi setelah selesai mengikuti pembelajaran laboratorium dan dilakukan uji keterampilan, ternyata kemampuan mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA, memiliki keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari jurusan IPS. Perbedaan keterampilan (skill) individu yang berasal dari jurusan IPA dan jurusan IPS pada keterampilan skil individu disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan menyerap materi yang disampaikan ketika melaksanakan pembelajaran laboratorium.
Kondisi ini bisa saja terjadi karena ada variabel moderator yang bisa menyebabkan mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengikuti pembelajaran laboratorium jika dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari IPS. Dalam contoh di atas pembelajaran laboratorium adalah variabel independen dan keterampilan individu adalah
E modul Epidemiologi Gizi 88
variabel dependen, dan motivasi untuk mengikuti pembelajaran laboratorium adalah variabel moderator. Atau dengan kata lain, variabel moderator memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.
5. Variabel Intervening atau variabel antara.
Dalam hal ini Tuckman (1988) menyatakan “an intervening variabel as that factor that theoretically offect the observed phenomenon but can not be seen, measured, or manipulated”. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi (memperlemah dan memperkuat) hubungan antara variabel independent dengan dependent, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel ini berperan menambah atau mengurangi efek variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, biasanya menemukan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel (variabel moderator)yang sedang diukur. Secara teori setiap variabel ada sebagian variabel yang nilainya secara satuan relatif tidak dapat diukur secara pasti. Misalnya nafsu makan, stress, frustasi dsb. Variabel seperti itu dinamakan variabel intervening. Contoh : anak yang pandai nilainya akan tinggi, tetapi dalam kasus tertentu ada anak yang pandai nilainnya rendah, ternyata ia sedang sakit hati sewaktu mengerjakan soal. Sakit hati, dalam hal ini, merupakan Variabel Intervening.
8.3. Mengontrol Variabel Confounding
1. Tahap Desain Penelitian

a. Restriksi
Metode restriksi dilakukan dalam penelitian pada tahap desain penelitian dengan cara membuat kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. Keuntungan dari metode ini dapat mengontrol variabel perancu sebelum dilakukan analisis. Namun kelemahan pada metode ini terdapat dalam generalisasi penelitian. Pada umumnya, variabel yang dikontrol dengan cara restriksi adalah variabel dengan prevalensi kecil sehingga tidak mempengaruhi generalisasi penelitian. Sebagai
E modul Epidemiologi Gizi 89
contoh, pada suatu penelitian observasional tentang hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian penyakit jantung koroner. Kebiasaan merokok dapat dikatakan sebagai perancu, maka peneliti dapat menentukan dalam desain penelitian adalah perokok dijadikan sebagai kriteria ekslusi dalam penelitian tersebut (baik pada kelompok peminum kopi maupun kelompok kontrol).
Minum kopi
Merokok
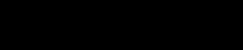


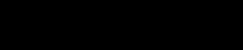


Penyakit jantung koroner
b. Matching
Matching adalah proses untuk menyamakan variabel perancu pada kedua kelompok. Kondisi tertentu apabila tidak memungkinkan untuk melakukan ekslusi pada variabel perancu, maka proses matching dapat dilakukan dengan menyeragamkan variabel perancu pada kelompok kasus maupun kontrol. Contoh pada penelitian kasus kontrol, Penelitian pasien Age related Macular Degeneration (AMD) yang memiliki kebiasaan merokok dan tidak merokok. Telah diketahui bahwa usia sangat berpengaruh terhadap kejadian AMD. Usia berpotensi menjadi variabel perancu karena dapat mempengaruhi fokus utama penelitian mengenai paparan rokok terhadap AMD. Sedangkan terdapat asumsi lain bahwa semakin tua usia pasien maka semakin sedikit intensitas merokok pada pasien, sehingga dilakukan proses matching pada usia pasien dengan rentang yang tidak terlalu besar.
Riwayat merokok AMD Merokok
E modul Epidemiologi Gizi 90
c. Randomisasi

Metode randomisasi lebih sering digunakan pada uji klinis. Dengan randomisasi, faktor yang mempengaruhi prognosis pengobatan diharapkan terdistribusi secara seimbang antar kelompoknya. Syarat randomisasi harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan dengan total subyek cukup besar. Variabel perancu yang terbagi rata tersebut meliputi variabel yang saat penelitian sudah diketahui maupun belum diketahui memiliki hubungan sebagai perancu. Contoh pada suatu uji klinis untuk menilai manfaat obat tradisional tertentu untuk menurunkan tekanan darah, dilakukan randomisasi, sebagian subyek diberikan obat tradisional, sebagian lain diberikan plasebo. Bila kebiasaan memakan mentimun di kemudian hari ternyata memiliki hubungan dengan penurunan tekanan darah, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian dikarenakan telah terbagi secara seimbang dengan randomisasi pada kedua kelompok.
Kelompok Perlakuan
Minum kopi Merokok
Kelompok Kontrol
2. Tahap Analisis
a. Analisis stratifikasi



Analisis stratifikasi dilakukan untuk mengontrol suatu kerancuan dengan cara evaluasi terhadap paparan penyebab penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan secara terpisah pada masing masing faktor perancu. Adapun tujuan dari analisis stratifikasi adalah untuk mengetahui adanya efek modifikasi dan untuk mengetahui apakah variabel luar termasuk variabel confounder. Jenis uji yang digunakan pada tahap ini adalah Mantel Haenszel. Syarat dari analisis stratifikasi adalah variabel perancunya berjumlah satudan suatu variabel kategorik. Teknik yang lazim dilakukan adalah Mantel Haenszel, baik untuk studi potong lintang, kasus kontrol, kohort maupunuji klinis.
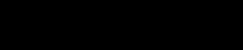
E modul Epidemiologi Gizi 91
Contoh: berikut pada penelitian hubungan kehamilan usia remaja dengan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Tabel 8.1. Hasil Analisis Uji Mantel Haenszel Variabel Luar Terhadap Hubungan Kehamilan Usia Remaja dengan Kejadian BBLR
Analisis stratifikasi juga digunakan untuk menentukan apakah variabel luar sebagai confounder atau tidak dalam hubungan kehamilan usia remaja dengan kejadian BBLR dengan melihat perubahan nilai RR sebelum dan sesudah dilakukan stratifikasi. Jika perubahan nilai RR≥10% maka variabel luar dianggap sebagai confounder namun jika perubahannya <10% maka tidak dianggap sebagai confounder

b. Analisis Multivariat
Analisis multivariat merupakan pengolahan data statistika dengan variabel bebas lebih dari satu. Terdapat dua jenis pengolahan data multivariat yaitu regresi logistik bila skala variabel berupa data kategorik, sedangkan untuk data numerik lebih umum digunakan regresi linear. Dengan kedua teknik tersebut dapatd iketahui asosiasi antar variabel dengan menyingkirkan variabel lain, termasuk

E modul Epidemiologi Gizi 92
variabel perancu. Kelebihan analisis multivariat ini dapat melihat peran masing masing variabel bebas, termasuk variabel perancu, terhadap kejadian efek. Analisis multivariat merupakan teknik yang kuat untuk menyingkirkan berbagai variabel perancu sekaligus.
Tahapan analisis multivariat:
1. Melakukan analisis bivariat.

2. Menyeleksi variabel yang akan masuk ke dalam regresi logistik
3. Melakukan analisis terhadap variabel interaksi secara hierarchial backward elimination procedurs sampai didapatkan model baku emas
4. Melakukan analisis terhadap variabel confounding dengan prinsip valid dan presisi.
5. Mendapatkan model akhir dan estimasi hubungan variabel utama dengan variabel tergantung.
Contoh: studi dalam penelitian faktor risiko diabetik retinopati pada pasien dengan diabetes mellitus. Variabel kejadian diabetik retinopati sebagai variabel tergantung.Variabel kadar HbA1c, Tekanan darah, hiperlipidemia dan indeks massa tubuh sebagai variabel bebas, beberapa variabel bebas tersebut dilakukan analisis sekaligus dengan metode analisis multivariat, sehingga didapatkan hasil berupa pengaruh dari masing masing variabel bebas terhadap variabel tergantung.
Epidemiologi Gizi
E modul
93
BAB
SKRINING MASALAH GIZI
9.1. Pengertian Skrining
Skrining adalah suatu upaya dalam penemuan penyakit secara aktif pada individu individu yang tanpa gejala dan nampak sehat dengan cara menguji, memeriksa atau prosedur lain yang dapat dilakukan dengan cepat. Skrining bukan suatu penetapan diagnosis, subyek subyek yang ditemukan positif atau kemungkinan mengidap suatu penyakit tertentu, perlu dirujuk kembali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Bustan (2006) skrining adalah upaya terorganisasi pada masyarakat yang tampaknya sehat untuk mendeteksi kelainan ataupun faktor resiko yang tidak disadari keberadaannya.
Untuk mendeteksi tanda dan gejala penyakit secara dini dan menemukan penyakit sebelum menimbulkan gejala dapat dilakukan dengan cara berikut :
1. Deteksi tanda dan gejala dini
Untuk dapat mendeteksi tanda dan gejala penyakit secara dini dibutuhkan pengetahuan tentang tanda dan gejala tersebut yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Dengan cara demikian, timbulnya kasus baru dapat segera diketahui dan diberikan pengobatan. Biasanya penderita datang untuk mencari pengobatan setelah penyakit menimbulkan gejala dan mengganggu kegiatan sehari hari yang berarti penyakit telah berada dalam stadium lanjut. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan ketidakmampuan penderita.

2. Penemuan kasus sebelum menimbulkan gejala
Penemuan kasus ini dapat dilakukan dengan mengadakan Skrining terhadap orang orang yang tampak sehat, tetapi mungkin menderita penyakit.
Diagnosis dan pengobatan penyakit yang diperoleh dari penderita yang datang untuk mencari pengobatan setelah timbul gejala relatif sedikit sekali dibandingkan dengan penderita tanpa gejala.
Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit yang tanpa gejala, atau faktor risiko untuk penyakit, dengan melakukan suatu uji pada suatu kelompok populasi yang belum berkembang menjadi gejala gejala klinis.
E modul Epidemiologi Gizi 94
9
Sreening test biasanya dan biasanya berusaha untuk mengidentifikasi sebagian kecil individu yang berisiko tinggi untuk kondisi tertentu.
Secara garis besar, Skrining adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita.
Proses Skrining terdiri atas 2 tahap, tahap pertama yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap memiliki risiko tinggi menderita penyakit. Bila hasil tes negatif maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Bila hasil tes positif maka dilakukan pemeriksaan tahap kedua yaitu pemeriksaan diagnostik yang bila hasilnya positif maka dianggap sakit dan mendapatkan pengobatan, tapi bila hasilnya negatif maka dianggap tidak sakit. Bagi hasil pemeriksaan yang negative dilakukan pemeriksaan ulang secara periodik.
Gambar 9.1. Konsep Skrining Test
Pemeriksaan yang biasa digunakan pada Skrining test dapat berupa pemeriksaan laboratorium atau radiologis, misalnya :

Pemeriksaan gula darah
Pemeriksaan radiologis untuk Skrining penyakit TBC Pemeriksaan tersebut harus dapat dilakukan

E modul Epidemiologi Gizi 95
:
Dengan cepat dapat memilah sasaran untuk pemeriksaan lebih lanjut (pemeriksaan
Tidak mahal
Mudah dilakukan oleh petugas kesehatan
Tidak membahayakan yang diperiksa maupun yang memeriksa
Dasar pemikiran dilaksanakannya Skrining adalah
1. Yang diketahui dari gambaran spektrum penyakit hanya merupakan sebagian kecil saja sehingga dapat diumpamakan sebagai puncak gunung es, sedangkan sebagian besar masih tersamar.
2. Diagnosis dini dan pengobatan secara tuntas memudahkan kesembuhan.
3. Biasanya penderita mencari pengobatan setelah timbul gejala atau penyakit telah berada dalam stadium lanjut hingga pengobatan menjadi sulit atau penyakit menjadi kronis atau bahkan tidak dapat disembuhkan lagi. Penderita tanpa gejala mempunyai potensi untuk menularkan penyakit
9.2. Tujuan Skrining
1. Deteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan gejala tidak khas terhadap orang orang yang tampak sehat tetapi mungkin menderita penyakit, yaitu orang mempunyai risiko tinggi untuk terkena penyakit (population at risk).
2. Dengan ditemukannya penderita tanpa gejala dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya dan tidak menjadi sumber penularan hingga epidemi dapat dihindari.
3. Mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin.
9.3. Sasaran Skrining
Sasaran utama Skrining adalah penyakit kronis seperti : Infeksi bakteri (lepra, TBC, dll)
Infeksi virus (hepatitis) Penyakit non infeksi; hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, karsinoma serviks, prostat, glaucoma

E modul Epidemiologi Gizi 96
diagnostik)
:
AIDS
9.4. Pelaksanaan Skrining
3. Massal
Skrining ini dilakukan tanpa mempertimbangkan population at risk Cara ini dimaksudkan menjaring sebanyak mungkin kasus tanpa gejala. Untuk melaksanakan Skrining secara massal, besarnya biaya dan banyaknya tenaga yang dibutuhkan hendaknya menjadi pertimbangan yang masak sebelum dilaksanakan.
4. Spesifik

Skrining secara spesifik dilakukan terhadap orang orang yang mempunyai risiko atau di kemudian hari dapat meningkatkan risiko terkena penyakit seperti hipertensi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Uji tapis secara spesifik dilakukan dengan mempertimbangkan faktor umur, jenis kelamin atau pekerjaan, dll. Lokasi Skrining
a. lapangan (Skrining TBC dengan rontgen foto “mobil”)
b. rumah sakit umum (Skrining ca.serviks dengan papsmear pada wanita yang datang ke RSU) rumah sakit khusus (Skrining glaukoma di RS mata
c. pusat pelayanan khusus (pusat pelayanan kanker dan penyakit jantung)
9.5. Kriteria evaluasi
Untuk menilai hasil uji skrining dibutuhkan kriteria tertentu yaitu:
a. Validitas
Validitas suatu alat uji didefinisikan sebagai kemampuan alat uji itu untuk membedakan siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit atau secara benar mengkategorikan orang ke dalam kelompok dengan dan tanpa penyakit atau mengindikasikan individu mana yang benar benar sakit dan mana yang tidak sakit.
Penilaian validitas pengukuran dalam tes penyaringan dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran tes penyaringan dengan diagnosa standar
E modul Epidemiologi Gizi 97
Tes Penyaringan
1) Sensitivitas yaitu kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu dengan tepat, dengan hasil tes positif dan benar benar sakit, atau proporsi orang dengan penyakit dalam populasi yang diskrining dan teridentifikasi sebagai sakit oleh alat uji skrining = a / (a + c) x 100%.
2) Spesifisitas yaitu kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu dengan tepat, dengan hasil tes negatif dan benar benar tidak sakit, atau proporsi orang yang bebas penyakit dan juga terindentifikasi tidak sakit (negatif) oleh alat uji skrining = d / (b + d) x 100%.
3) Nilai Prediksi Positif (positive predictive value) yaitu kemampuan mendeteksi yang benar benar menderita suatu penyakit dari semua hasil uji skrining positif = a / (a + b) x 100%.
4) Nilai Prediksi Negatif (negative predictive value) yaitu kemampuan untuk mendeteksi yang benar benar tidak sakit dari semua hasil skrining yang negatif = d / (c+d) x 100%.
Idealnya, hasil tes Skrining harus 100% sensitif dan 100% spesifik, tapi dalam praktik hal ini ada dan biasanya sensitivitas berbanding terbalik dengan spesifisitas. Misalnya, bila hasil tes mempunyai sensitivitas yang tinggi, akan diikuti oleh spesivisitas yang rendah, dan sebaliknya. Hal ini tampak jelas pada tes yang menghasilkan data kontinu seperti :

E modul Epidemiologi Gizi 98 (gold standard). Dengan asumsi bahwa diagnosis yang tepat disusun pada tabel 2 x 2 dengan katagori variabel dikotomi, sebagai berikut : Tabel 2x2 uji validitas
Gold Standar Total Positif Negatif Positif a b a+b Negatif c d c+d Total a+c b+d a+b+c+d Keterangan : a = True positive c = False negative b = False positive d = True negative Uji validitas yang akan dilakukan adalah :
Hb
Tekanan darah
Serum kolesterol
Tekanan intraokuler
b. Reliabilitas
Suatu alat uji dikatakan reliabel jika tes yang dilakukan berulang ulang menunjukkan hasil yang konsisten. Reliabelitas ini dipengaruhi oleh berberapa faktor yaitu:
1) Variabilitas alat, misalnya stabilitas reagen dan stabilitas alat ukur yang digunakan.

2) Variabilitas orang yang diperiksa, misalnya, lelah, kurang tidur, marah, sedih, penyakit berat dan lain lain.
3) Variabilitas pemeriksa
a) Variasi interna, merupakan variasi yang terjadi pada hasil pemeriksaan yang dilakukan berulang ulang oleh orang yang sama.
b) Variasi eksterna, variasi yang terjadi bila suatu sediaan dilakukan pemeriksaan oleh berberapa orang (Budiarto & Anggraini, 2002).
Upaya untuk mengurangi berbagai variasi :
Standarisasi reagen dan alat ukur Latihan intensif pemeriksa Penentuan kriteria yang jelas Penerangan kepada orang yang diperiksa Pemeriksaan dilakukan dengan cepat
c. Yield
Yield merupakan jumlah penyakit yang terdiagnosis dan diobati sebagai hasil dari uji skrining. Hasil ini dipengaruhi oleh berberapa faktor yaitu:
1) Sensitivitas alat uji, bila alat uji skrining memiliki sensitivitas rendah, akan dihasilkan banyak negatif semu yang berarti banyak penderita yang tidak terdiagnosis. Hal ini dikatakan bahwa uji skrining dengan yield yang rendah,
E modul Epidemiologi Gizi 99
demikian sebaliknya. Jadi sensitivitas alat dan yield mempunyai korelasi yang positif.

2) Prevalensi penyakit yang tidak tampak, makin tinggi prevalensi penyakit tanpa gejala yang terdapat di masyarakat akan meningkatkan yield
3) Uji skrining yang dilakukan sebelumnya, bagi penyakit yang jarang dilakukan uji skrining akan mendapatkan yield yang tinggi karena banyaknya penyakit tanpa gejala yang terdapat di masyarakat. Kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap masalah kesehatan akan meningkatkan partisipasi dalam uji skrining sehingga kemungkinan banyak penyakit tanpa gejala yang dapat terdeteksi dan dengan demikian yield akan meningkat (Budiarto & Anggraini, 2002).
Gizi 100
E modul Epidemiologi
BAB 10
SURVEI CEPAT GANGGUAN GIZI
10.1. Pengertian
Survei cepat adalah salah satu alternatif terhadap survei tradisional yang mencakup skala besar. Pertama tama dikembangkan oleh WHO untuk mendapatkan cakupan imunisasi dan diadaptasi dalam bidang epidemiologi lainnya oleh Frerichs. Akhir akhir ini survei cepat telah digunakan oleh pelayanan kesehatan masyarakat dengan penekanan khusus pada pemakaian survei cepat bagi para pimpinan untuk mendapatkan status kesehatan, kebiasaan, dan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan. 5 Hal penting metode survei cepat yaitu:
a. Jumlah pertanyaan sedikit dan jelas.
b. Penggunaan teori sampel yang sahih.
c. Penggunaan komputer/laptop dan printer bertenaga baterai; atau dapat menggunakan kalkulator biasa.
d. Perangkat lunak yang memadai
e. Adanya pemindahan data yang lebih banyak ke komputer. Survei cepat dapat dilaksanakan dalam waktu 8 Minggu sejak dari perancangan sampai pelaporan akhir. Wawancara mencakup 200 300 rumah tangga yang diambil dari 30 kluster di mana masing masing terdapat 10 responden mencakup 20 30 variabel berupa pertanyaan ya atau tidak, sehingga analisis yang dilakukan cukup sederhana. Survei ini seringkali disiapkan dalam kode sehingga dapat diolah dan dianalisis dengan segera
10.2. Tujuan Survei Cepat
Survei cepat gangguan gizi dilaksanakan untuk berbagai tujuan seperti diuraikan berikut ini:
1. Survei cepat anemia (ibu hamil, balita, wanita usia subur (WUS) bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang:

a. Prevalensi anemia (ibu hamil balita WUS).
b. Frekuensi pelayanan antenatal pada ibu hamil dan pemeriksaan pada balita
E modul Epidemiologi Gizi 101
c. Cakupan program penanggulangan anemia ibu hamil.

d. Kualitas program penanggulangan anemia ibu hamil
e. Masalah yang melatarbelakangi tingginya prevalensi anemia.
f. Informasi lainnya tentang ibu hamil balita yang tidak dapat diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP).
g. Data penunjang untuk perencanaan program penanggulangan anemia (ibu hamil, balita, WUS) pada wilayah tertentu
2. Survei cepat kurang energi kronis (KEK) bertujuan untuk menghasilkan
informasi tentang:
a. Prevalensi risiko KEK.
b. Masalah yang melatarbelakangi tingginya prevalensi WUS risiko KEK.
c. Data penunjang untuk perencanaan program penanggulangan kek pada ibu hamil dan WUS.
3. Survei cepat GAKI bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang:
a. Prevalensi gondok nyata dan prevalensi gondok total.
b. Mengetahui tingkat endemisitas
c. Data penunjang untuk perencanaan program penanggulangan GAKI.
10.3. Metode
Survei cepat ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengambilan sampel yang disusun dengan pemilihan responden. Responden pada survei cepat ini berbeda beda yang membuat pilihan responden ini berbeda pula. Misalnya responden anemia ibu hamil berbeda dengan responden anemia balita dan jenis anemia lainnya. Dari responden ini kemudian didapatkan data yang diperoleh dari wawancara dan pengukuran.
a. Pengambilan sampel
Pada dasarnya untuk survei cepat gangguan gizi, digunakan cara pengambilan sampel 2 tingkat. Unit sampel terkecil adalah individu yang sesuai dengan tiap tiap masalah Adapun 2 tahapan pengambilan sampel tersebut ialah pemilihan 30 cluster dan pemilihan responden. Rincian dasar pemilihan Cluster untuk tiap tiap survei cepat gangguan gizi tercantum pada Tabel 10.1.
modul Epidemiologi Gizi 102
E
b. Pemilihan Sampel
Setelah nama desa diketahui langkah berikutnya adalah memilih responden dalam desa tersebut. Untuk survei anemia ibu hamil, sebagai responden untuk setiap kluster akan dipilih 10 ibu hamil. Jika pada sebuah desa terpilih 2 kelompok, maka pada Desa itu dapat diperoleh 20 responden. Jika pada sebuah desa terpilih 3 kelompok, maka pada Desa itu dapat diperoleh 30 responden, dst. Tabel 10.1. Dasar Pemilihan Cluster Dan Jumlah Responden Pada Survei Cepat Gangguan Gizi
Jenis Survei Cepat Dasar Pemilihan Cluster Responden
Anemia ibu hamil Daftar seluruh desa di kabupaten 300 ibu hamil
Anemia balita Daftar seluruh desa di kecamatan 300 balita
Anemia WUS Daftar seluruh desa di kecamatan 300 WUS

KEK WUS Daftar seluruh desa di kecamatan 300 WUS
GAKI Daftar seluruh desa di kecamatan 300 anak usia 6-10 tahun
Karena setiap survei cepat kelainan gizi ini mempunyai responden yang berbeda beda, maka cara pemilihan responden tidak sama. Khusus untuk survei anemia ibu hamil, di Desa terpilih ini seluruh ibu hamil harus didaftar, sedangkan survei lainnya akan dipilih rumah tangga dengan karakteristik responden untuk tiap tiap survei. Cara pemilihan responden dijelaskan berikut ini.
Anemia ibu hamil. Dengan dasar pemilihan kluster adalah Kabupaten, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Pergilah ke desa Yang Terpilih
Buatlah daftar responden ibu hamil di desa itu.Penting seluruh ibu hamil harus didaftar agar setiap ibu hamil mempunyai kemungkinan untuk dipilih. Gunakan catatan yang ada di Posyandu dan catatan pada parat desa dan kohort ibu hamil yang ada di Puskesmas agar diperoleh daftar seluruh ibu hamil. Jika catatan ini tidak tersedia perlu dilakukan pendataan ibu hamil di desa terpilih tersebut
Dari seluruh ibu hamil yang ada di Desa terpilih, lakukan pemilihan ibu hamil dengan cara acak. Cara pemilihan responden dapat dengan tabel bilangan acak, namun yang termudah adalah cara yang biasa dilakukan
E modul Epidemiologi Gizi 103
pada arisan. Setiap nama ibu hamil ditulis pada secarik kertas. Seluruh kertas kecil yang berisi nama itu dimasukkan ke dalam gelas Lalu kocok dan keluarkan satu persatu sampai diperoleh jumlah yang diperlukan.
Jika jumlah ibu hamil sama atau kurang dari jumlah responden yang diperlukan (misalnya terdapat 6 ibu hamil dari 10 yang diminta, atau 15 ibu hamil dari 20 yang diperlukan untuk desa yang mendapat dua kelompok) maka seluruh ibu hamil terpilih harus dijadikan sebagai responden.
Nama ibu hamil yang terpilih dicatat. Ibu hamil inilah nantinya yang akan diwawancarai dan diambil darahnya.
Anemia- balita, anemia WUS, dan KEK-WUS serta GAKI. dengan dasar pemilihan Cluster adalah Kecamatan, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pergilah ke desa yang terpilih
Pelajari peta desa terpilih. Pada desa dengan jumlah 1 kluster, Tentukan pusat desa sebagai titik gerak untuk penentuan responden yang selanjutnya disebut sebagai titik Cluster. Pada desa dengan jumlah 2 Cluster bagilah desa tersebut menjadi 2 bagian dan tentukan titik Cluster untuk tiap tiap bagian sebagai titik gerak penentuan responden. Demikian seterusnya untuk 3 atau 4 kluster titik klaster bisa berupa rumah tangga, kantor desa, mesjid, dll.
Pada masing masing titik kluster, Pilihlah rumah tangga yang mewakili anak balita dan anak usia 6 sampai 10 tahun. Selanjutnya Carilah rumah tangga lain sampai ditemukan 10 responden untuk tiap tiap kelompok
Jumlah rumah tangga bisa lebih atau kurang dari 10 rumah tangga; pada prinsipnya dapat diperlukan 10 responden balita 10 responden WUS, dan 10 responden anak berusia 6 sampai 10 tahun.
Nama responden yang terpilih kemudian dicatat responden diwawancarai dan perlakuan lainnya (diambil darah untuk anemia diukur LILA untuk KEK dan di palpasi kelenjar gondok serta diambil urinnya untuk GAKI). Untuk jelasnya Perhatikan gambar Desa berikut: (Gambar 10.1).
modul Epidemiologi Gizi 104
E
Desa A dengan 1 titik

B dengan 2 titik kluster
Keterangan: Pusat desa (titik kluster)
Rumah tangga yang menjadi responden
Gambar 10.1. Pencarian rumah tangga sampel dan kluster terpilih
Pada desa ini pencarian rumah tangga sampel dan titik kluster dapat bergerak searah jarum jam dan berputar membentuk spiral (seperti spiral obat nyamuk) sampai ditemukan seluruh responden yang telah ditetapkan. Pada daerah yang melaksanakan survei cepat lebih dari satu masalah dan bila respondennya sama, maka pada responden yang sama dapat dilakukan wawancara sekaligus untuk kedua masalah bersangkutan (misalnya, anemia dan KEK WUS)
c. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan setelah informasi responden yang akan menjadi sampel untuk tiap tiap masalah telah ditetapkan (terpilih). Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengukuran antropometri, pengukuran kelenjar gondok, dan pengambilan sampel darah dan urin.
1. Wawancara. wawancara dilakukan pada semua rumah tangga yang terpilih sebagai sampel untuk wawancara menggunakan kuesioner sesuai dengan masalah yang akan dicari wawancara dilakukan oleh petugas yang telah dilatih untuk melaksanakan survei cepat kelainan gizi
2. Pengukuran antropometri . Pengukuran antropometri dilakukan dengan melakukan pengukuran LILA dan pada WUS dan ibu hamil. Pada balita dilakukan pengukuran berat badan (BB).
3. Pengukuran kelenjar gondok. Untuk pengukuran kelenjar gondok dilakukan dengan palpasi kelenjar gondok pada anak berusia 6 sampai 10 tahun.
E modul Epidemiologi Gizi 105
kluster Desa
4. Pengambilan sampel darah dan urin. Pada anemia ibu hamil, anemia
balita, dan anemia WUS harus dilakukan pengambilan darah untuk diperiksa kadar hemoglobin (HB) dengan metode cyanment HB. Untuk
GAKI,pada anak berusia 6 sampai 10 tahun dilakukan pengambilan urin untuk diperiksa (UIE) di laboratorium.
10.4. Pelaksana
Pelaksanaan survei cepat ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat Puskesmas. Pelaksana untuk tiap tiap tingkat dan tugas tugasnya berbeda untuk setiap tingkat.
a. Tingkat Kabupaten/Kota
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Pelaksana : Kepala Seksi
Tugas tugasnya meliputi:
a. Menyiapkan dan mendistribusikan alat dan bahan
b. Memilih 30 Cluster sebagai sampel
c. Memilih responden berdasarkan pendataan sasaran/keluarga dan Puskesmas
d. Melaksanakan pertemuan di tingkat kabupaten kota
e. Melaksanakan pertemuan orientasi/latihan petugas pelaksana (Puskesmas)
f. Melaksanakan pengolahan dan analisis data
g. Melakukan pemeriksaan HB di laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota, laboratorium kesehatan daerah provinsi atau di rumah sakit
h. Mengirimkan sediaan urine untuk pemeriksaan UIE ke lab
i. Melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data untuk perencanaan
b. Tingkat Puskesmas
Koordinator : Kepala Puskesmas

Pelaksana : Staf Puskesmas dan Lintas Sektor
Tugas tugasnya meliputi:
a. Melakukan pendataan desa dan sasaran/keluarga di wilayah kerja
b. Mengikuti orientasi/latihan di tingkat kabupaten/kota
E modul Epidemiologi Gizi 106
c. Menyiapkan alat/bahan untuk pelaksanaan pengumpulan data
d. Menyiapkan lapangan antara lain pemberitahuan jadwal survei
e. Melaksanakan pengumpulan data:
Hasil wawancara
Hasil pengukuran LILA
Hasil penimbangan
Hasil palpasi kelenjar gondok
Sampel darah
Sampel urine
f. Mengirimkan hasil pengukuran data kabupaten/kota
10.5.Teknik Pelaksanaan
Perbedaan tujuan dilakukannya survei cepat mengakibatkan perbedaan pelaksanaanya. Data yang dikumpulkan untuk setiap tujuan surveicepat dijelaskan berikut ini. Survei cepat Anemia
1. Responden
Responden dipilih berdasarkan kebutuhan dan masalah yang akan diidentifikasi. Tidak tertutup kemungkinan dalam satu kabupaten dipilih satu atau lebih kelompok responden sebagai berikut:
a. Ibu hamil
b. Balita usia 12 sampai 59 bulan
c. WUS (usia 1 sampai 45 tahun), termasuk remaja putri, tenaga kerja wanita sektor formal dan nonformal
2. Data yang dikumpulkan
a. Ibu hamil
Identitas

Aktivitas fisik
Riwayat kehamilan
Informasi tentang tablet tambah darah TTD
Perilaku makan
Sampel darah untuk pengukuran HB
Epidemiologi Gizi
E modul
107
Pengukuran Lila untuk risiko KEK
b. Balita
Identitas
Status gizi BB/U
Riwayat penyakit (malaria, cacingan, ISPA, diare, dan campak)
Perilaku makan
Sampel darah untuk pengukuran HB
c. WUS
Identitas
Aktivitas fisik
Pola haid
Riwayat penyakit (malaria, cacingan, dan TB)
Sampel darah untuk pengukuran HB
Pengukuran Lila (untuk risiko kek)
Survei cepat GAKI
1) Responden
Anak berusia 6 sampai 10 tahun
2) Data yang dikumpulkan
Identitas

Pengetahuan dan penggunaan garam beryodium
Informasi tentang kapsul iodium
Tingkat pembesaran kelenjar gondok
Pemeriksaan sampel urin
Gizi
E modul Epidemiologi
108
Tabel 10.2. Informasi yang Dihasilkan pada Survei Anemia Ibu Hamil INFORMASI YANG DIHASILKAN
Usia ibu hamil

BENTUK PENYAJIAN
Dalam bentuk rat rata atau dalam bentuk kategori usia berisiko <20 tahun dan 30 tahun, serta usia tidak berisiko 20-35 tahun
Dalam bentuk distribusi frekuensi Pekerjaan dan kegiatan sehari-hari ibu hamil
Pendidikan ibu hamil
Dikategorikan dalam bentuk aktivitas ringan, sedang, berat
Disajikan dalam trimester 1, 2, dan 3 Frekuensi pelayanan antenatal
Lama kehamilan
Dalam bentuk rata rata menurut trimester kehamilan Kehamilan, persalinan, keguguran, Kategori menurut usia berisiko/tidak berisiko
Banyaknya ibu hamil yang mengetahui tentang Tablet Tambah Darah (TTD)
Distribusi frekuensi Cakupan program penanggulangan anemia ibu hamil
Distribusi frekuensi Waktu pertama kali mendapat TTD Rata rata Cakupan dan kualitas program penanggulangan anemia ibu hamil
Distribusi frekuensi
Distribusi frekuensi, yang mendapat 1x, 2x, 3x Pemanfaatan tempat pelayanan untuk mendapatkan TTD oleh ibu hamil
Pengetahuan ibu tentang dosis TTD Distribusi frekuensi Pengetahuan ibu tentang lamanya pemberian TTD
Distribusi frekuensi, dan median Untuk menghitung jumlah tablet yang seharusnya diminum
Rata rata Kepatuhan ibu hamil meminum TTD Rata rata
Penyebab tidak diminumnya TTD
Distribusi frekuensi Pantangan dan anjuran makan yang berakibat buruk/baik untuk ibu hamil
Berakibat baik kalau mengandung atau membantu penyerapan besi; dan berakibat buruk kalau mengganggu penyerapan besi
Baik atau buruk Hasil pengukuran LILA
Kebiasaan yang baik/buruk pada saat hami
Rata rata, bandingkat dengan mean (standar deviasi)
E modul Epidemiologi Gizi 109
DAFTAR PUSTAKA

Boeing, H. (2013). Nutritional epidemiology: New perspectives for understanding the diet disease relationship?. European Journal of Clinical Nutrition (2013) 67, 424 429. www.nature.com/ejcn
Bustan, M.N. (2019). Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Gibson S.R., (1990). Principles of Nutritional Assessment. New York: Oxford University Press
Christakis, G. (1973). Nutritional Assessment in Health Programs.Washington DC: American Public Health Association.
Grimes, D.A., Schulzz, K.F. (2002) Epidemiologi series : An Overview of Clinical Research: The lay of the land, London, The Lancet
Gurinovic, Mirjana. (2016). Nutrition Epidemiology and Public Health Nutrition Belgrade, Serbia:Elsevier.
Martono, N. (2011). Metode penelifian Kuanfitafif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Noor, N.N. (2008). Epidemiologi. Rineka Cipta: Jakarta
Nugrahaeni, D.K. (2011). Konsep Dasar Epidemiologi. Buku Kedokteran EGC: Jakarta
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi. Kementerian Kesehatan RI.
Popay, J. (ed.) (2006) Moving beyond Effecfiveness in Evidence Synthesis: Methodological Issues in the Synthesis of Diverse Sources of Evidence. London: National Institute of Health and Clinical Excellence.
Ryadi, S., Wijayanti, (2011). Dasar dasar Epidemiologi. Jakarta: Salemba Medika
Siagian, Albiner. (2010). Epidemiologi Gizi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Suaranta, I.M.R., Suiraoka.I.P. (2018). Epidemiologi Gizi. Denpasar: Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES).
Sugiyono (2012). Metode Penelifian Kuanfitafif Kualitafif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Timmreck, T.C. (2005). Epidemiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
modul Epidemiologi Gizi 110
E
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Jakarta. Kementerian Kesehatan RI.

E modul Epidemiologi Gizi 111