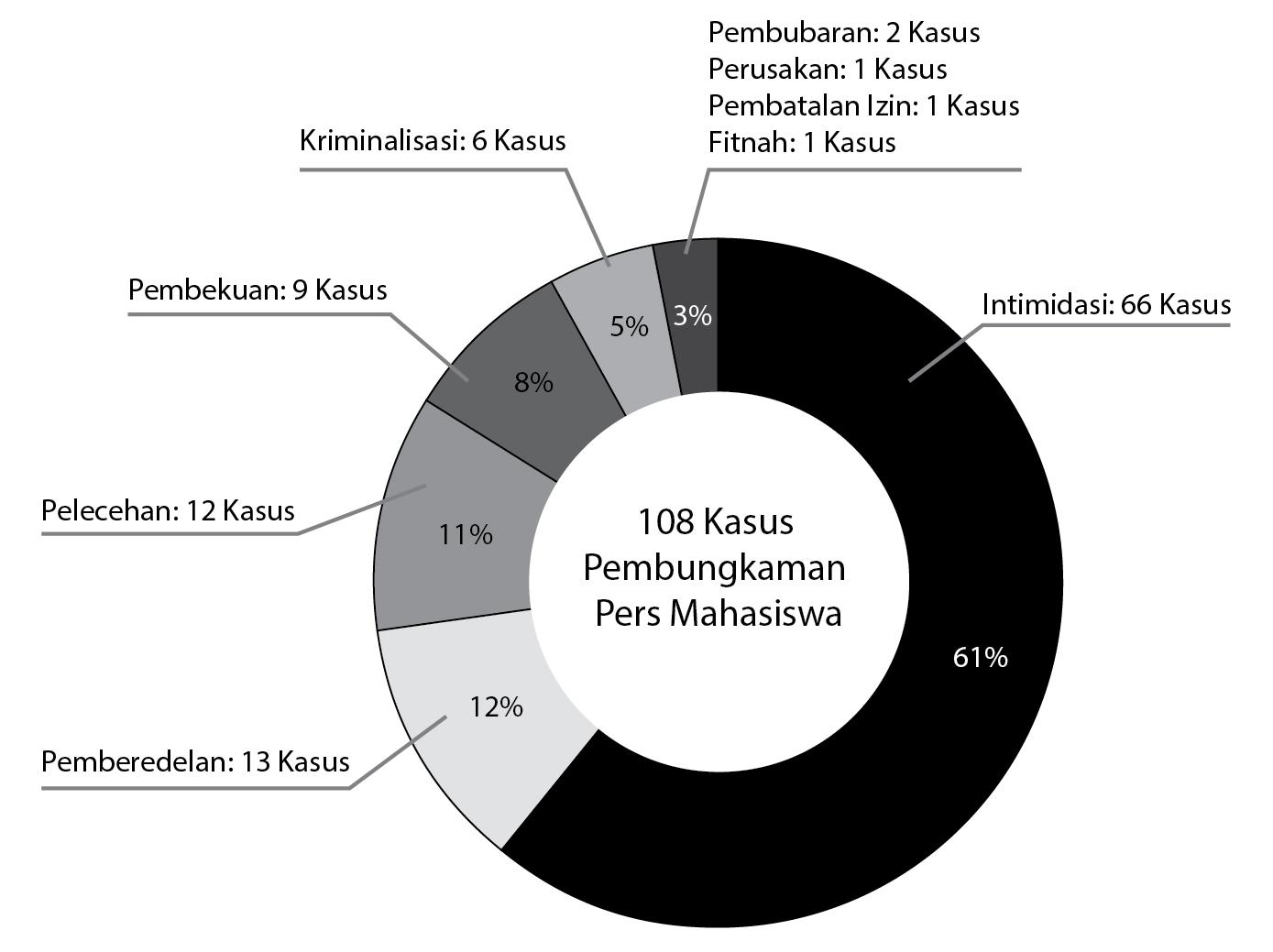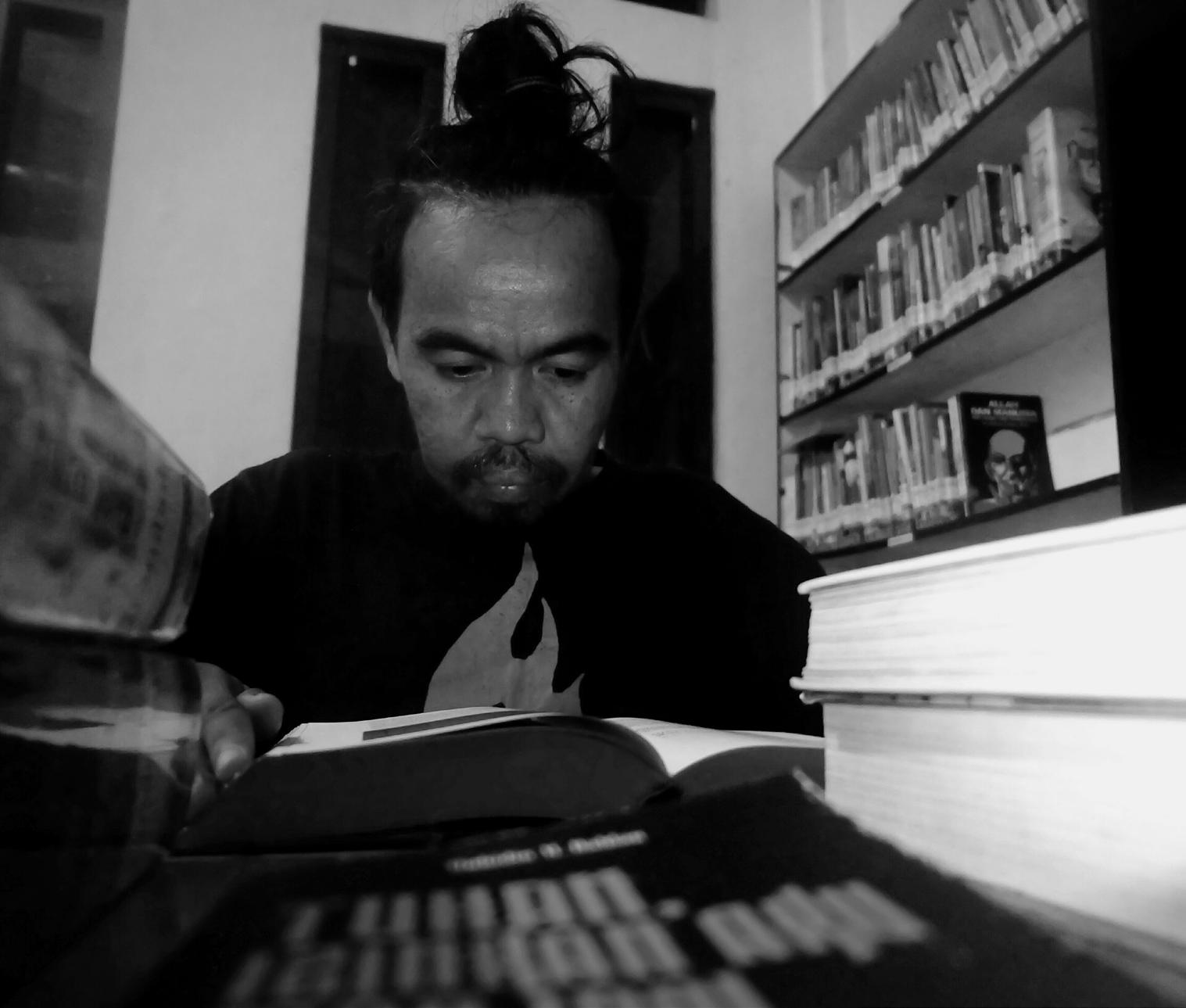9 minute read
mentor
Memburu Hasan Tiro
Kegagalan seorang jurnalis bukan karena tidak berhasil melakukan wawancara. Tapi saat tidak bisa bertemu dengan narasumber.
Advertisement
Oleh: Sirojul Khafid
Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo menceritakan pengalaman reportase bersama Hasan Tiro di Swedia pada tahun 2000 lalu (8/10/2015). Di restoran Hotel Neo Plus Awana Yogyakarta, ia bercerita perjuangan mencari keberadaan Pemimpin Gerakan Acheh Merdeka tersebut yang menjadi buruan nomor satu pihak keamanan Indonesia.
Suatu waktu saya membaca tulisan Arif Zulkifli yang berjudul Dua Jam Bersama Hasan Tiro. Tulisan itu menceritakan hasil reportasenya pada pertengahan Mei 2000, di Stockholm, Swedia. Azul—begitu ia biasa dipanggil teman-temannya— berhasil bertemu dengan Hasan Muhammad Di Tiro, buronan nomor satu Pemerintah Republik Indonesia saat itu. Jakarta murka karena pemberontakan yang telah ia lakukan. Hasan Tiro ingin Aceh merdeka.
“Ia (Hasan Tiro –red) jarang muncul ke depan publik,” tulis Azul.
Wawancara pun hanya dilakukan dengan media asing. Media Indonesia sebenarnya pernah berkesempatan mewawancarai Hasan Tiro, namun hanya melalui sambungan telepon internasional. Dalam bukunya, Demokrasi untuk Indonesia yang ditulis di Amerika pada 1958, Hasan Tiro menyatakan penentangan terhadap konsep negara kesatuan yang digagas oleh Soekarno.
Akumulasi nasib buruk yang diterima Aceh membuat Hasan Tiro tak memiliki alasan lain kecuali memerdekakannya. Itu merupakan asal muasal berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menariknya saat membaca tulisan Azul, ia mengaku bahwa Hasan Tiro selalu menolak perbincangan mereka direkam dan dijadikan bahan wawancara. Namun, tulisan tersebut terbantu oleh studi pustaka yang Azul lakukan.
Seperti artikel yang ditulis Hasan Tiro pada November 1980, The Legal Status of Acheh Sumatra under International Law, misal. Hasan Tiro menyebutkan penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada Indonesia pada 1949 sebagai sesuatu yang ilegal.
Basis hukum yang dipakainya adalah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan negara kolonial menyerahkan daerah jajahannya kepada penduduk asli. Indonesia, menurut Hasan Tiro, bukanlah penduduk asli Aceh.

Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo menceritakan pengalaman reportase bersama Hasan Tiro di Swedia pada tahun 2000 lalu (8/10/2015). Di restoran Hotel Neo Plus Awana Yogyakarta, ia bercerita perjuangan mencari keberadaan Pemimpin Gerakan Acheh Merdeka tersebut yang menjadi buruan nomor satu pihak keamanan Indonesia.
“Penyerahan kedaulatan itu dilakukan tanpa pemilihan umum yang menyertakan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Aceh,” tulis Azul mengutip wawancara Hasan Tiro dengan televisi Hilversum Belanda pada 1996.
Kepada saya, Azul juga menjelaskan buku The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro. Buku setebal 226 halaman itu merupakan catatan harian Hasan Tiro saat ia berperang di Hutan Aceh pada 1976-1979.
Di buku itu, Hasan Tiro menggambarkan kepulangannya kembali ke Aceh pada 1976 setelah 25 tahun tinggal di Amerika. Meskipun Azul tidak mendapatkan informasi dari proses wawancara, buku tersebut menjadi studi pustaka yang memperkuat penjelasan terkait Hasan Tiro dan GAM.
Di samping studi pustaka yang melimpah, Azul juga dapat menangkap detail pertemuannya dengan Hasan Tiro di apartemen pinggiran kota Stockholm. Itu membantu pembaca membayangkan suasana pertemuannya dengan Hasan Tiro. Seperti mantel biru yang dikenakannya, deskripsi perawakan, dan kondisi apartemen seperti letak sofa kuning di ruang tengah yang berhadapan dengan meja kerjanya.
Di meja itu terdapat tumpukan map, kertas, dan sebuah vandel GAM serta miniatur bola dunia. Di sampingnya, ada meja kecil tempat koleksi foto Hasan Tiro bersama pasukan GAM. Ada pula foto bersama istri, anak serta cucunya saat ia di Amerika. Agak ke samping lagi ada meja kerja yang di atasnya terdapat kliping pemberitaan tentang GAM dan foto Hasan Tiro pada kesempatan pertemuan internasional.
Selain deskripsi tempat dan tubuh, Azul juga bisa menangkap detail suasana yang menambah tulisan tersebut menjadi lebih menarik. Detail suasana tersebut seperti katakata Hasan Tiro “That’s Stupid” dan “Sumatra!” yang menambah suasana emosional dalam tulisan.
Detail lain seperti lagu Johann Sebastian Bach berjudul Toccata & Fugue dan Air in G. String yang Hasan Tiro putar saat Azul di apartemennya. Serta buku The Drama of Achehnese History 1873-1978 yang dibaca Azul atas permintaan Hasan Tiro juga tidak kalah penting. ***
Pada Oktober 2015, saya dan beberapa rekan berkesempatan bertemu Azul di Hotel Neo Plus Awana Yogyakarta. Saat kami temui, ia sedang duduk di salah satu meja restoran hotel. Dekat kaca, sekitar deret nomer dua dari depan. Belum ada orang lain di sana kecuali Azul, pramusaji, dan koki.
Azul duduk sambil menyantap sup. Sesekali, santapan supnya terhenti karena harus membalas pesan yang entah dari siapa. Dan sekali lagi, santapan supnya harus terhenti saat kami menyapanya. Kami memang sudah berencana berbincang sebelum ia mengisi acara di hotel yang sama satu jam kemudian. “Tak ada wawancara waktu itu, Hasan Tiro tidak mau,” kata Azul saat kami tanya pengalamannya bertemu Hasan Tiro di Swedia.
Azul berperawakan sedang, tingginya sekitar 165 sentimeter. Rambutnya hitam pendek dengan belah tengah yang mulai memutih di sela-selanya. Raut mukanya santai dan matanya fokus pada obrolan. Muka bulatnya dihiasi kacamata yang lebih bulat lagi. Beberapa kali ia tertawa yang membuat gigi putihnya terlihat.
Sambil sesekali menyantap supnya, Azul melanjutkan cerita “perburuan” Hasan Tiro di Swedia. Azul yang telah menjadi jurnalis sejak 1995 ini merasa “panas” saat majalah Forum berhasil melakukan wawancara dengan Hasan Tiro. Forum mengklaim telah mewawancarai Hasan Tiro via sam-
bungan telepon internasional.
Memang, saat itu—sekitar 2000-an—menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk bisa berkomunikasi dengan Hasan Tiro. Selain dijaga oleh anggota GAM, Hasan Tiro juga sering menolak berhubungan dengan media Indonesia, apalagi Jawa.
Hasan Tiro menganggap Jawa sebagai penjajah. Azul ingin mendapatkan wawancara setelah sekitar dua tahun mempelajari Hasan Tiro dan GAM. “Saya harus wawancara, tapi bertemu langsung. Karena prinsip jurnalisme adalah verifikasi.”
Azul kemudian membuat rencana untuk menemui Hasan Tiro. Melalui kenalannya di New York yang merupakan anggota GAM—anggota GAM tersebar di beberapa negara—ia mendapatkan informasi bahwa akan ada pertemuan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Jenewa. Pertemuan yang sudah terlaksana lebih dari sekali itu sangat dirahasiakan. Dan Hasan Tiro terlibat dalam pertemuan itu.
Sampai di Jenewa, Azul menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Ia menanyakan di mana pertemuan tersebut dilaksanakan. Namun pihak kedutaan tidak ingin memberi tahu. Buntu akan informasi tempat pertemuan, ia ingat bahwa pertemuan tersebut disponsori oleh Henry Dunant Center (HD Centre), sebuah organisasi swasta yang berperan memediasi dua pihak yang terlibat konflik. Maka Azul menuju kantor HD Centre. Namun ia tak mendapati pertemuan apapun di sana. Hanya ada bangunan tua dan sepi. Tidak ada orang sama sekali.
Tidak mendapat apa-apa, Azul lalu kembali ke KBRI. Di sana ia bertemu temannya, warga negara Prancis yang ia kenal saat bertugas di Timor Timur. Melalui temannya itu, Azul mendapat informasi tempat pertemuan itu diadakan.
Namun informasi itu tidak membuatnya beranjak dari KBRI. Selain jarak tempuh yang jauh—sekitar lima jam, tenggat waktu tulisan, serta kemungkinan besar Hasan Tiro yang telah meninggalkan Jenewa selepas acara menuju ke Zurich. Terbukti, semua Pers yang mengejarnya tidak mendapatkan apa-apa.
Tidak lama berselang, datang Hassan Wirajuda—wakil Indonesia dalam pertemuan tersebut—dan bertemu dengan Azul. Karena merasa tidak enak dengan Azul yang telah datang dari Jakarta, Wirajuda memberitahu isi pertemuan perdamaian itu. “Ya saya tulis seadanya di majalah,” ujarnya sambil menyandarkan badannya ke kursi.
“Walaupun saya sudah mendapatkan informasi penting terkait pertemuan, tapi bukan itu yang saya cari,” lanjutnya.
Obrolan terhenti sejenak saat Azul kembali memakan sup yang ada di depannya. Baru satu suapan, ia beralih ke ponselnya untuk membalas pesan elektronik yang masuk. “Maaf tadi habis mengirim berkas. Sampai mana tadi, oh iya, pertemuan di Jenewa,” kata Azul.
Langkah selanjutnya, ia menghubungi lagi beberapa anggota GAM. Di antaranya Malik Mahmud dan Hussaini yang belakangan menjadi Gubernur Aceh. Keduanya merupakan orang dekat Hasan Tiro. Mereka menyuruh Azul untuk datang ke suatu hotel. Di sana Azul berbicara dengan anggota GAM yang ternyata telah pecah kongsi. Orang-orang yang pecah dari GAM pimpinan Hasan Tiro membentuk Majelis Pemerintah (MP) GAM dengan pimpinan Hussaini.
Kubu MP GAM lebih terbuka daripada GAM. Hal itu karena MP GAM adalah minoritas. Selain itu, di MP GAM sistem demokrasi juga sudah dijalankan, contohnya dalam pemilihan pimpinan. Tidak seperti GAM pimpinan Hasan Tiro yang menganut sistem kerajaan. Di GAM Hasan Tiro dianggap raja. Posisinya pun tidak jauh dari keturunan ayahnya yang juga bangsawan.
Anggota MP GAM adalah mantan orang-orang inti di GAM. Selain Malik Mahmud dan Hussaini, ada pula Tengku Daud Paneuk (Panglima GAM pertama). Orangnya kecil, kurus, dan pincang. Konon, kakinya pincang karena tertembak. Adapula Yusuf Daud, anak dari Daud Paneuk dan beberapa orang lainnya. “Ini menjadi menarik saat bisa menuliskan cerita mantan anggota GAM,” kata Azul.
“Tapi sekali lagi, bukan ini yang saya cari. Saya harus bertemu Hasan Tiro.”
Dari obrolan dengan anggota MP GAM, tetap saja informasi terkait tempat tinggal Hasan Tiro belum ia dapatkan. Sementara biaya meliput semakin banyak ia keluarkan. Azul
kembali meminta kepada anggota MP GAM. Kalau tidak bisa mendapatkan alamatnya, paling tidak nama daerahnya saja.
“Nama daerah tempat tinggalnya Albi,” kata salah satu anggota MP GAM.
Albi merupakan daerah pinggiran kota. Azul mengibaratkan, jika Stockholm itu Jakarta, maka Albi mungkin seperti Depok. Walaupun tidak mendapatkan alamat detail, Azul tetap menuju ke Albi. “Di Swedia itu pola kotanya teratur. Pertama stasiun, pasar, tanah lapang baru pemukiman (apartemen). Beda dengan di kita (Indonesia) yang awut-awutan.”
“Di Indonesia yang awut-awutan saja saya bisa cari orang kok, apalagi di Swedia,” kata Azul.
Berbekal informasi daerah tempat tinggal Hasan Tiro, Azul menyusuri apartemen satu persatu. Dari siang sampai hampir petang mencari, Azul belum juga menemukan apartemen milik Hasan Tiro. Sampai pada suatu apartemen yang memperlihatkan nama “HT”—di setiap apartemen ada daftar nama penghuninya. Merasa penasaran bahwa itu singkatan dari nama Hasan Tiro, ia mencoba untuk masuk. Namun terhalang saat pintu apartemen terkunci dan hanya bisa dibuka dengan kartu yang dipegang para penghuni.
Setelah menunggu, datang seorang ibu yang sepertinya baru pulang belanja dari pasar.
“Permisi, saya mau menemui saudara saya. Dia tinggal di sini. Namanya Hasan Tiro,” kata Azul.
“Saya tidak mengenal semua penghuni apartemen ini. Mereka sangat banyak.”
“Boleh saya ikut masuk dengan ibu untuk mencari saudara saya? Saya tidak punya kartu untuk masuk.”
“Bisa, silahkan.”
Sampai di lift apartemen, nama penghuni jadi lebih detail. Di lantai lima, ada nama Hasan Tiro, tidak lagi disingkat “HT”. Azul pun menuju lantai lima dan menuju nomor apartemen yang ditempati Hasan Tiro.
Azul mengetuk pintu dan keluarlah Hasan Tiro dengan mantel birunya.
“Kamu siapa?” Kata Hasan Tiro.
“Wali, saya wartawan dari Jakarta. Mungkin wali sudah dengar nama saya. Saya ikuti wali dari Jenewa,” kata Azul sambil memegang dan mencium tangan Hasan Tiro. Dia tahu kalau Hasan Tiro suka dihormati.
“Oh ya, saya dengar ada wartawan yang mencari saya,” balas Hasan Tiro dengan mata yang waspada.
“Bagaimana kamu tahu saya di sini? Siapa yang kasih tahu kamu? Kamu bertemu siapa saja?” Lanjutnya.
“Saya bertemu semuanya. Saya bertemu Dr. Hussaini tapi dia tidak memberi tahu wali tinggal di mana. Akhirnya saya mencari sendiri,” kata Azul.
“Maaf kalau ini kurang ajar, tapi tolong hargai ini sebagai sesama warga Sumatra.”
Azul lahir di Lampung. Ibu dari Palembang dan Ayah Madiun. Azul tidak memberi tahu ayahnya dari Madiun karena tahu Hasan Tiro akan marah mendengar apapun yang berkaitan dengan Jawa.
“Oh, kamu orang Sumatra?” Kata Hasan Tiro.
“Iya wali. Nama saya Arif Zulkifli. Boleh saya masuk?”
Azul berhenti bercerita sejenak. Menghela napas.
“Di dalam tidak ada wawancara sama sekali. Ada dua hal dalam jurnalisme. wawancara dan reportase,” kata Azul. “Oke lah, dia (Hasan Tiro –red) bisa menghalangi saya untuk wawancara. Tapi dia tidak bisa menghalangi saya untuk reportase. Dia tidak bisa menghalangi saya untuk menulis apa yang saya alami dengannya,” lanjtunya. Menurut Azul, kegagalan seorang jurnalis bukan karena dia gagal melakukan wawancara. Tapi ketika dia tidak bisa bertemu dengan narasumber.
Kata-kata itu muncul dengan santai tapi cukup membuat kami tertegun. Ceritanya kembali terhenti. Waktu telah menunjukan pukul satu siang. Azul kembali memakan sup yang sepertinya sudah dingin karena terlalu lama didiamkan. Dia baru tersadar kalau sudah saatnya untuk mengisi materi di acara lain saat ada panitia yang menegur. Suapan sup nya pun terhenti, sekali lagi.q