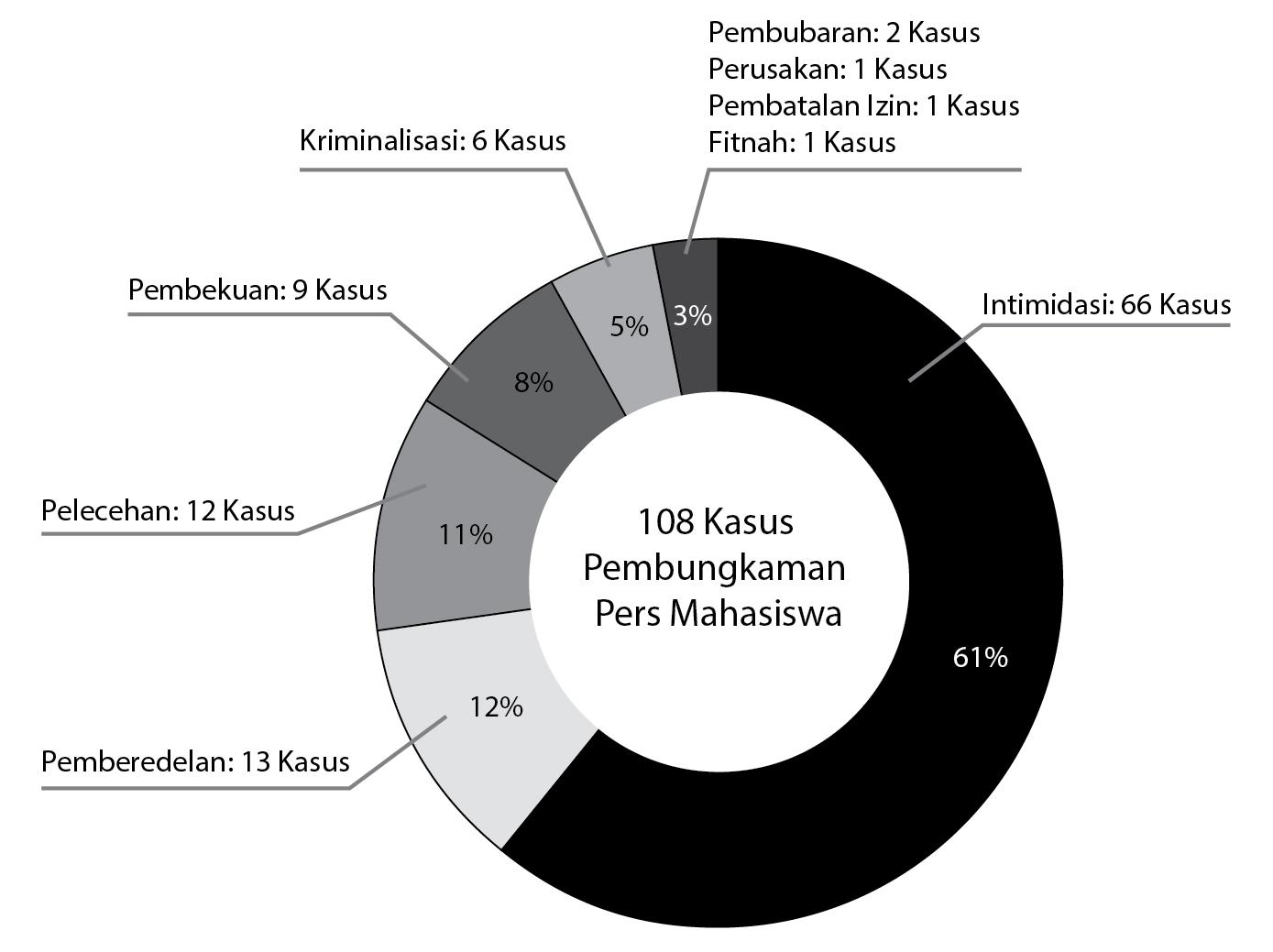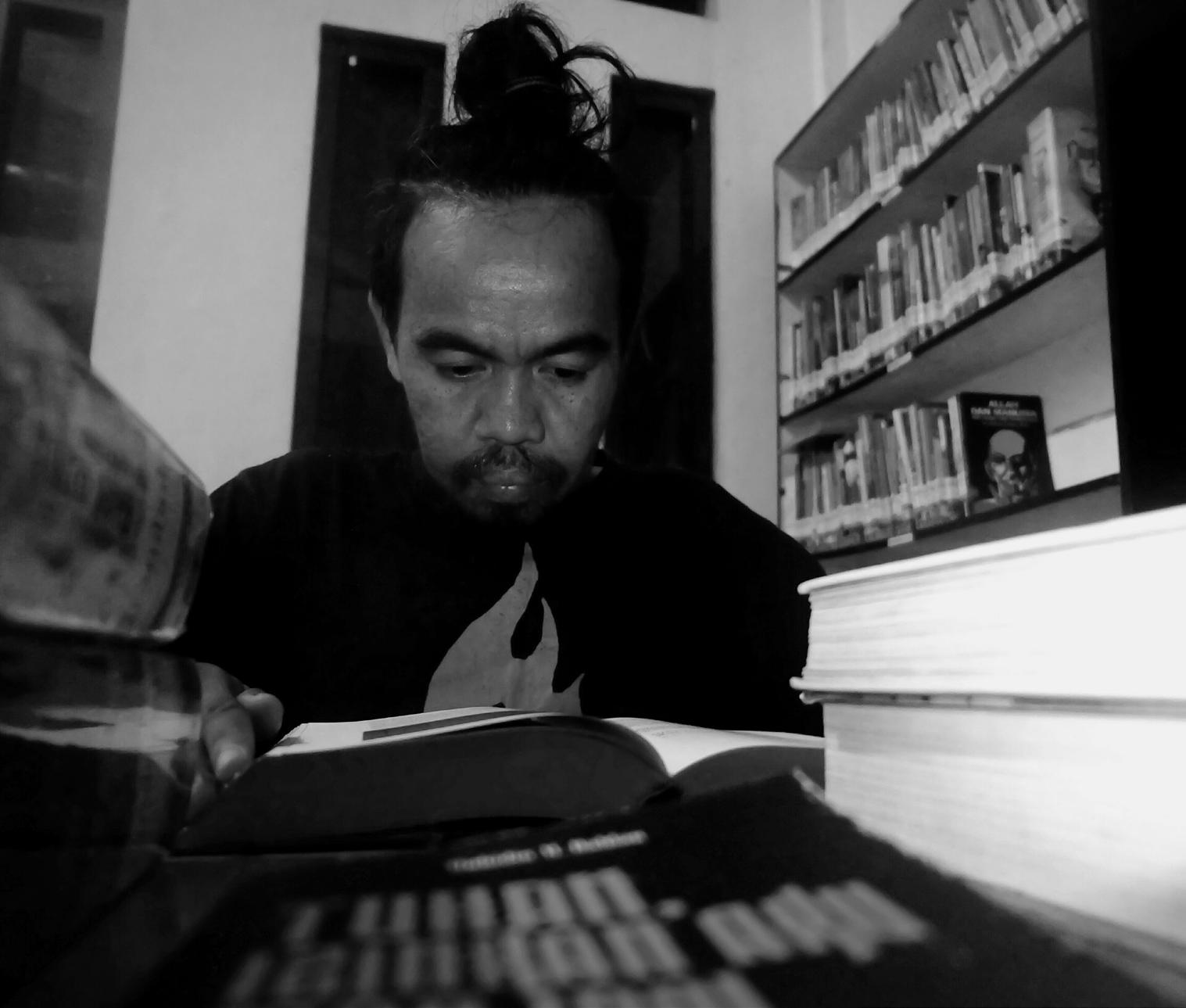3 minute read
bismillah
Proletar
Oleh: Fahmi Ahmad B.
Advertisement
Thomas Malthus, seorang ekonom pada abad ke 18 pernah mencetuskan hukum populasi. Terlepas dari kontroversinya teori Malthus yang menganggap bahwa kaum miskin hanya sebagai beban, perlu dicatat juga bahwa omongan Malthus adalah sebuah fakta. Takdir umat manusia dengan kondisi populasi yang berlebihan kini, akan berkembang pesat melebihi pangannya sendiri, begitu kata Malthus.
Kondisi timpang ini membuat manusia saling berebut kuasa. Di balik gedung megah yang ditempati konglomerat, disitu pula ada nestapa pekerja bangunan dengan cucuran keringatnya. Kemewahan beriringan dengan kesengsaraan. Dari sini terlihat, bahwa umat manusia tak bisa lepas dari adanya kelas. Semuanya ditentukan oleh kelas. Kaya, miskin, terdidik, bodoh.
Masih di abad yang sama, filusuf sekaliber Karl Marx pun menggambarkan relasi kelas melalui analisis materialisme dialektika historisnya. Bahwa masyarakat yang ada sekarang adalah bentukan sejarah perjuangan kelas. Di benua Eropa, Marx mencoba melukiskan kisah pertentangan antara kaum borjuis, feodal, dan proletar. Coba melirik pula ke India. Kastakasta macam brahma, ksatria, waisya, dan sudra, menjadi cerita tersendiri dalam bab-bab sejarahnya. Drama itu dielaborasi menjadi sebuah percikan-percikan pertentangan.
Tak pelak, itu pula yang terjadi di Indonesia. Di negeri gemah ripah loh jinawi yang Pram sebut sebagai Bumi Manusia ini, relasi produksi antara kaum penjajah dan yang terjajah, antara kolonial dan pribumi menjadi tonggak baku sejarahnya juga. Atau lihat saja tatkala Tan Malaka menggambarkan sejarah penjajahan Indonesia, “Hongi-hongi cultuur stelsel, monopoli stelsel dan gencatan pajak yang takkan ada ampunnya,” kata Tan. Begitu pula yang terjadi di berbagai bangsa dan negara lainnya.
Nampaknya kelas juga yang melandasi saling hajar sana hajar sini, perang, rampok, jajah, musnahkan, singkirkan, juga lenyapkan. Karena seiring bertambah tuanya usia bumi kita, bertambah rusak juga seisinya. Diperparah pula dengan kondisi yang tidak berimbang antara pertumbuhan jumlah populasi manusia dan sumber daya yang tersedia. Saling rebut sumber daya, kuasa, menjadi cerita yang tak ada habisnya.
Adalah proletar yang menjadi kaum terasing di pinggir jalan, korban kelas atas. Pemain peran yang digambarkan sebagai sosok tanpa alat produksi, tak punya apa-apa selain tenaga. Sialnya lagi, sumber tenaganya pun dijadikan komoditas, lewat tarik ulur si tangan tak hampa, begitu ekonom menyebutnya. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh akademisi dari Inggris, John Molyneux, sebagai ciri khusus kapitalisme. Bahwa dalam kapitalisme, tenaga kerja menjadi barang dagangan.
RB. Radix Sabili D. P. | HIMMAH
Di Indonesia, Bung Karno memberi istilah sendiri bagi kaum proletar ini, yaitu marhaen. Dalam tulisannya di Fikiran Ra’jat, 1933, Bung Karno menyebut marhaen sebagai petani kecil tak berlahan atau petani gurem, buruh pabrik, dan siapa pun yang tidak memiliki sarana produksi.
Kaum yang terhempas oleh perebutan kuasa ini terombang-ambing dalam pertentangan kelas. Sedangkan sang imperialis berusaha untuk mencari kemenangan, terus mencari kemenangan. Entah bangsa apapun menjajah bangsa manapun, dengan menggunakan segala cara, bahkan legitimasi undang-undung yang busuk sekalipun.
Perlu sepertinya mencermati apa yang digambarkan Marx dalam teori akumulasi primitif. Bagaimana perampasan tanah oleh pemodal yang membuat petani tradisional atau produsen independen menjadi kehilangan lahan garapannya. Ini pula yang menjadikan adanya proletarisasi, yaitu proses yang mengubah produsen independen terpaksa menjual tenaganya. Ia terpaksa memilih jalan itu karena tidak lagi mempunyai apaapa. Pilihan tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Henry Bernstein seorang sosiolog, sebagai pilihan semu atau paksaan samar. “Jual tenagamu atau kamu akan kelaparan, anda punya pilihan,” kata Bernstein.
Tanahnya dirampas untuk kuasa pemodal. Mau tidak mau, suka tidak suka, ia terikat oleh relasi industri yang pelik. Semakin meluas, proletar tak punya lagi kuasa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia terkungkung, tak bisa lepas dari cengkraman. Terpaku oleh upah, dan menjadi ketergantungan. Kini, konflik agraria di mana-mana, pabrik-pabrik rakus akan tanah. Sang proletar yang terjerat itu pun ditimpa pula oleh nestapa politik upah murah. Mau melawan, apa daya, sang majikan punya sejuta siasat pemberangusan.
Memang, selepas revolusi Industri di Inggris, industrialisasi meluas ke semua tatanan bumi manapun. Sistem pembangunan dihegemoni semua oleh kuasa industrialisasi. Tanah dirampas untuk dalih kemajuan zaman. Tak ayal, setelah itu satu negara tak bisa lepas dari cengkraman target-target mencekik manusia. Hanya untuk memuaskan birahi kaum pemodal, sang proletar menguras habis tenaga, tercucur keringat, disedot sampai pucat. Ia tak punya waktu untuk bersanda gurau, ia teralienasi dari sistem sosial dan terbelenggu dengan asap pabrik yang mengepul.
Kini, sadar tidak sadar, posisi proletar ada di bawah. Walau bagaimanapun juga, politik persekongkolan untuk melemahkan dan semakin melemahkan kaum proletar tetap kentara. Negara yang katanya jadi wasit, malah jadi wasit yang berat sebelah, demi target-targetnya, efisiensi, kemudahan investasi dan pertimbangan lainnya.
Terkadang si wasit ini pun bermuka dua. Bahkan untuk politik praktis macam pemilu, ia berhasil berperan bak malaikat penolong. Janjinya akan memperjuangkan nasib kaum proletar yang terpinggirkan. Tapi apa mau dikata, itu hanya sandiwara. Maka dari itu, perjuangan kelas demi merebut kesejahteraan kaum proletar harus berdasar pada kesadaran. Kesadaran akan kelas, kesadaran akan persatuan, dan kesadaran, bahwa saat ini kondisi negaranya sedang tidak baik-baik saja.q