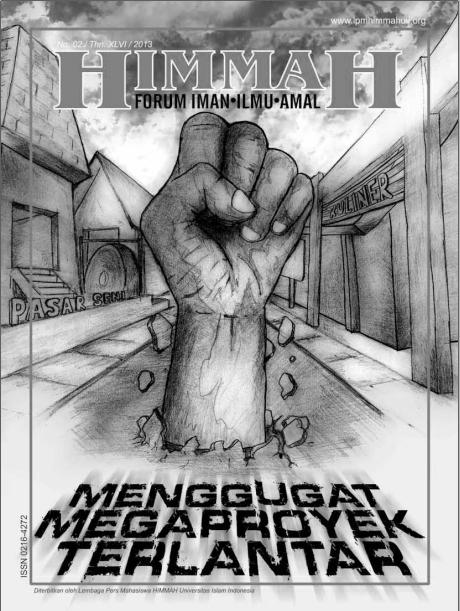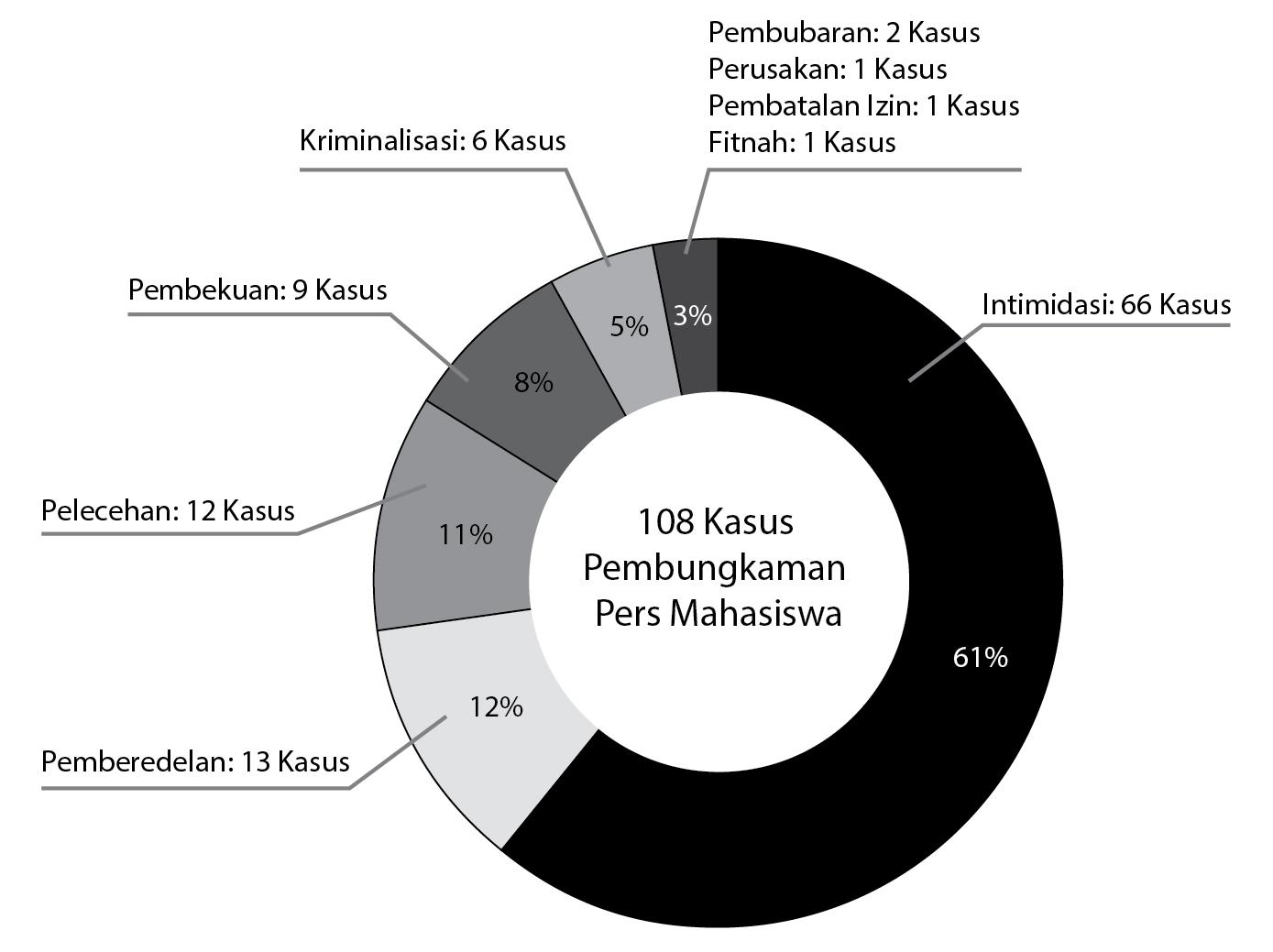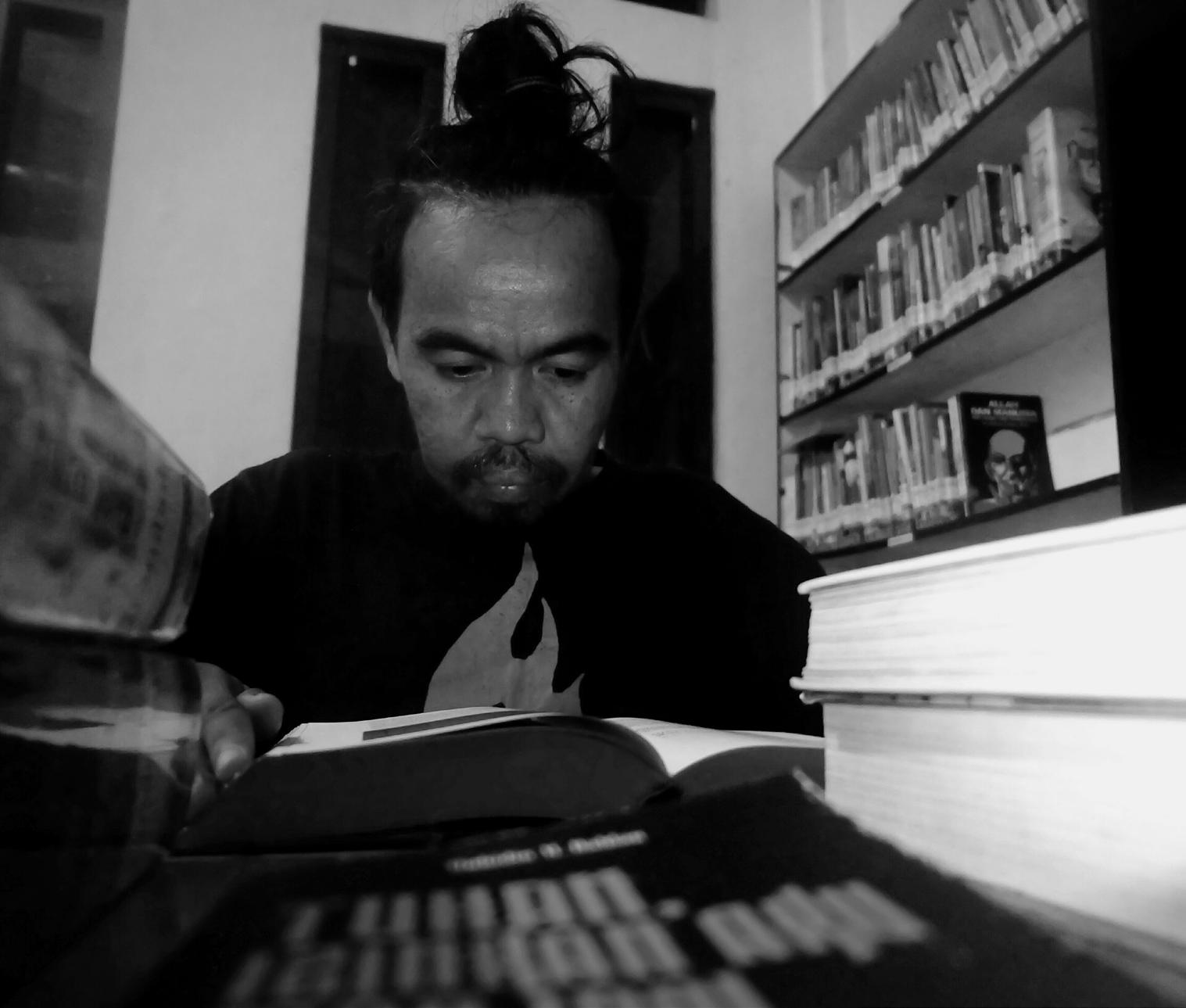3 minute read
assalamu’alaikum
Salim Kancil dibunuh ketika melawan tambang pasir ilegal yang berpotensi merusak kelestarian ekosistem di Desa Selok Awar-awar, Kabupaten Lumajang. Kasus pembunuhan Salim Kancil itu menjadi salah satu bukti bahwa persoalan lingkungan hidup di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan rumit. Sebab tak hanya berkutat pada kelestarian alam tetapi juga menyoal interaksi antar individu dalam memenuhi kepentingannya.
Advertisement
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) pada 1987 membuat suatu laporan. Berdasarkan laporan itu, ada tiga aspek problema lingkungan hidup, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
Pertama problema lingkungan hidup alam. Hal ini berkaitan dengan gangguan manusia terhadap keseimbangan sumber daya di suatu lingkungan. Misalnya penggunaan bom untuk menangkap ikan yang berdampak pada kerusakan terumbu karang. Implikasinya, jika banyak terumbu karang rusak, biota laut akan susah menemukan tempat tinggal untuk berkembang biak. Jumlah ikan di laut pun akan menurun. Kedua adalah problema lingkungan hidup buatan. Biasanya menyangkut bagaimana manusia mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada. Sementara yang ketiga problema lingkungan hidup sosial. Terjadi manakala timbul benturan kepentingan antar individu atau kelompok yang mengakibatkan ketidakserasian hidup.
Pada kasus tambang ilegal di Lumajang, sebelum terbunuhnya Salim Kancil, warga di sana diketahui memang sudah berkonflik lebih dulu. Antara yang pro pertambangan dan yang kontra pertambangan.
Di tempat lain, seperti Rembang. Kita bisa menyaksikan benturan kepentingan serupa. Antara mereka yang menentang pendirian pabrik semen dan yang mendukung pendirian pabrik semen. Mereka yang menentang menilai pendirian pabrik semen akan merugikan kelestarian ekosistem. Sementara yang mendukung berdalih akan adanya penguatan sektor ekonomi domestik.
Ana Nadya Abrar dalam buku Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup mengatakan bahwa respon manusia terhadap lingkungan hidup bergantung pada sejauh mana pengetahuan dan pengalaman mereka tentang lingkungan hidup itu sendiri. Artinya, semakin masyarakat paham tentang persoalan lingkungan hidup maka seharusnya mereka semakin sadar betapa pentingnya melestarikan alam. Bukan malah mendukung korporasi-korporasi yang jelas punya agenda mengeksploitasi lingkungan besar-besaran. Dalam keadaan demikian, Ana mengatakan bahwa medialah yang memiliki peran besar untuk menyokong informasi-informasi mengenai lingkungan ke masyarakat.
Di samping itu, para pekerja media di Indonesia secara fundamental juga mengimani 9 elemen jurnalisme yang dirumuskan oleh Bil Kovach dan Rossenstiel. Salah satu poin utama dari 9 elemen itu adalah memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Kenyataan tersebut memunculkan suatu tuntutan dan harapan akan kemampuan pers dalam memotret kompleksitas persoalan lingkungan, sekaligus berkontribusi atas pemecahan masalahnya. Pada gilirannya tuntutan dan harapan ini pun melahirkan suatu disiplin tersendiri dalam kajian media, yaitu jurnalisme lingkungan hidup.
Kendati menjadi salah satu solusi literatif masyarakat akan pentingnya penyebaran informasi terkait persoalan lingkungan. Penerapan jurnalisme lingkungan nyatanya menuai beberapa kritik. I Gede Gusti Maha Adi, Direktur Eksekutif Society Of Indonesian Environmental, menyebut jurnalisme lingkungan sebagai jurnalisme yang rentan terjebak dalam jurnalisme keaktivis-aktivisan atau jurnalisme advokasi. Dampak negatifnya ialah kecenderungan penulisan yang tidak lengkap dan kurang cover both side. Dampak negatif lainnya yaitu seringkali jump to conclusion (langsung menarik kesimpulan).
Adi mencontohkan pemberitaan pencemaran lingkungan oleh PT Newmont Minahasa Raya yang ramai beberapa
tahun silam. Pers cenderung langsung menyimpulkan apa yang terjadi tanpa verifikasi dan kehati-hatian. Opini tentang kepastian terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan Newmont telah berkembang. Panjang lebar berita itu ditulis. Ada korban, dokter, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi narasumber. Pokoknya Newmont bersalah dan mesti diadili. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada cukup bukti kuat mengenai pencemaran yang dilakukan Newmont. Di persidangan, masyarakat dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun kalah.
Memang, ada kecenderungan para jurnalis untuk menerapkan etika utilitarianisme yang menyandarkan nilai-nilai moral pada keuntungan mayoritas. Jika misalnya ada pemberitaan yang merugikan suatu industri tetapi dianggap menguntungkan masyarakat kebanyakan, maka hal itu dinilai sah secara moral. Namun jika menilik kenyataan bahwa media kita di monopoli oleh segelintir orang saja, tentu muncul pertanyaan. Apakah pemberitaan media tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat? Ataukah hanya menjadi alat kuasa untuk menjatuhkan pihak tertentu?
Untuk menghindari dugaan semacam itu, jurnalisme lingkungan yang berpihak pada keberlangsungan ekosistem harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Keberimbangan, imparsialitas, kehati-hatian, dan akurasi, jangan sampai dilupakan. Hal yang tak kalah penting, wartawan lingkungan hidup juga mesti menguasai ilmu ekologi. Tujuannya agar dapat melihat serta memahami konteks alam secara keseluruhan. Sebab, masyarakat berhak mendapat informasi yang utuh dan terpercaya mengenai persoalan lingkungan. Yang terpenting, wartawan lingkungan hidup harus berani membela yang benar dan melawan yang salah sekalipun itu pemilik instansinya sendiri.q
K.A. Sulkhan, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII angkatan 2014