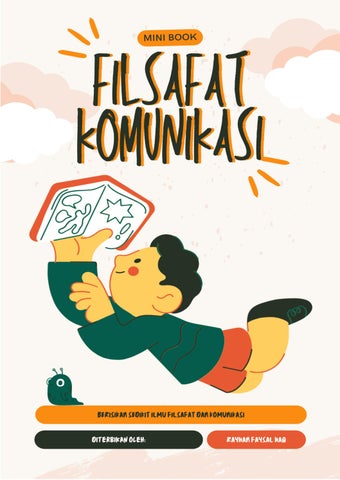FILSAFAT KOMUNIKASI
Penulis:
Rayhan Faysal Haq
Editor:
Rayhan Faysal Haq
Cover:
Rayhan Faysal Haq
Dosen Pengampu:
Abu Amar Bustomi, M.Si.
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023
KATA PENGANTAR
Puji syuur ehadirat Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah saya mampu mengerjakan Mini Book ini dengan judul “Filsafat Komunikasi” sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Mini Book ini saya susun untuk menyelesaikan tugas Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Fisafat Komunikasi yang diajar oleh Bapak Abu Amar Bustomi, M.Si. pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Selain itu, saya juga sangat berharap agar Mini Book ini dapat menambah sedikit ilmu kepada pembaca.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abu Amar Bustomi, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Tugas yang telah kami terima ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang kami tekuni. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Mini Book ini. Saya menyadari bahwa tulisan Mini Book ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan adanya penyempurnaan. Saya terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan tulisan ini. Apabila terdapat banyak kecacatan dalam tulisan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama.
Sidoarjo, 22 Juni 2023.
A. LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN
Komunikasi merupakan sebuah ativitas antar individu untuk bertukar pesan dan setiap individu tersebut memahami isi pesan yang disampaikan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kwgiatan berkomunikasi. Sesungguhnya manusia yang menjauhi individu lain dan tidak ingin berkomunikasi merupakan manusia yang menyalahi hukum alam, karena manusia seharusnya saling berinteraksi guna membangun konsep diri, membangun komunitas sekitar, dan lain sebagainya.
Dengan komunikasi, kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Kita bisa memberikan efek psikologis positif atau pun negatif kepada lawan bicara. Oleh karena itu, tujuan utama komunikasi adalah untuk menciptakan suasana yang positif untuk setiap individu dan janganlah sekali-kali menciptakan efek psikologis yang negatif kepada orang lain atau masyarakat. Dengan begitu, kita akan menciptakan masyarakat yang positif bagi lingkungan di kehidupan sekitar kita.
Filsafat bisa diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Filasat berasal dari kata Yunani. Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu di dunia. Di dalam filsafat, kita dituntut berfikir untuk mencari tahu nilai dari suatu hal. Ilmu filsafat selalu berkembang mengikuti zaman sehingga ilmu filsafat harus terus diperbaharui untuk bisa mengejar zaman yang semakin modern ini.
Hubungan filsafat dengan komunikasi yaitu kebenaran dalam berbicara di depan khalayak umum, dengan siapapun, dimanapun, dan dimana saja kita berada. Kajian filsafat tentang komunikasi menjadi sebuah petunjuk bagi disiplin ilmu lain yang subjeknya menelaah perilaku manusia.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa definisi dari filsafat?
2. Apa macam-macam filsafat?
3. Apa hubungan antara filsafat dengan komunikasi?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui apa itu filsafat.
2. Untuk mengetahui hubungan filsafat dengan komunikasi.
3. Untuk mengetahui macam-macam filsafat.
A. FILSAFAT
BAB II
PEMBAHASAN
Terdapat banyak pengertian dari para ahli filsafat, hal ini karena setiap filsuf mempunyai pendapat masing-masing dan memiliki dasar pemikiran serta pandangan yang berbeda pula. Filsafat berasal dari Bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata tersebut dari dari 2 kata, yaitu philos dan sophia. Masing-masing kata tersebut memiliki definisinya. Philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia memiliki arti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Dari 2 kata yunani tersebut menjadi kata philosophia yang berarti bahwa cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran, dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan.
Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terkenal dalam ilmu filsafat:
1. Socrates.
Beliau adalah seorang filsuf yang hidup di Yunani pada tahun antara 469-399 SM. Menurut Socrates, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa manusia merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan tersebut, Socrates tidak ingin memaksa orang lain untuk menerima ajarannya. Socrates menginginkan untuk setiap manusia dapat menyampaikan opini mereka sendiri. Socrates mempelajari ilmu dialektika untuk bisa berdialog dengan baik dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengemukakan opininya, sehingga Socrates mendapat pandangan-pandangan baru
2. Plato.
Plato adalah salah satu murid dari Socrates yang hidup pada tahun 427-347 SM. Plato merupakan seorang murid dari Socrates. Plato mengemukakan pendapatnya bahwa realitas yang mendasar adalah ide atau idea. Menurut Plato, dunia yang konkrit itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi. Plato juga menyatakan bahwa ada 2 realitas, yaitu dunia nyata dan dunia ide. Menurutnya, untuk bisa masuk ke dalam dunia ide, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk dan memperbanyak kegiatan yang bermanfaat. Plato juga mengatakan bahwa terdapat 3 tingkatan, yaitu bagian tertinggi adalah akal budi, bagian tengah adalah rasa atau keinginan, dan bagian paling bawah adalah nafsu. Akal budilah yang digunakan untuk mendapatkan ide-ide dan bisa memperbaiki sifat-sifat tercela manusia.
3. Aristoteles.
Aristoteles hidup pada 384-322 SM. Aristoteles merupakan seorang murid dari Plato. Beliau pernah menjadi guru dari seorang Pangeran Alexander yang kemudian menjadi Raja Alexander Yang Agung. Aristoteles adalah seorang cendikiawan yang sering melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang Ia miliki. Aristoteles juga seorang penulis yang menuliskan ilmunya. Tulisan Aristoteles yang termasyhur hingga saat ini adalah tentang logika yang disebut analitika.1
Ilmu filsafat merupakan suatu ilmu yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi pemikiran manusia-manusianya juga berubah, hal tersebut membuat filsafat mejadi ilmu yang dinamis. Berikut ini adalah beberapa pandangan yang ada dalam ilmu filsafat:
Idealism merupakan salah satu pandangan dalam filsafat. Idealisme adalah cara pandang filosofis yang membuat ide atau gagasan sebagai faktor konstitutif dalam keseluruhan realitas.
Idealisme memiliki pandangan bahwa semua isi dunia ini berasal dari sebuah gagasan atau ide. Secara harfiah, idealisme dalam Bahasa Yunani memiliki arti yakni, penglihatan atau pandangan terhadap sesuatu. Pandangan yang dimaksud adalah pandangan bersifat intelektual.2
2. Rasionalsime.
Semakin berkembangnya zaman, manusia menaruh keyakinan yang besar terhadap kemampuan akal. Dengan akal, semua masalah bisa diselesaikan. Pemikiran rasional mengedepankan akal pikiran yang sehat, bukan mengedepankan perasaan.
3. Kritisisme.
Filsafat ini memfokuskan kepada pikiran kita untuk memahami objek yang bersifat apriori. Pandangan ini menuntut untuk menganalisis objek terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dari objek yang dianalasis.
4. Konstruktivisme.
Pandangan ini bernaggapan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses konstruksi pemikiran manusia menggunakan objek untuk menunjang hasilnya. Sebuah pengetahuan dibangun untuk menjadi pengetahuan yang lebih baik lagi dan pengetahuan tersebut dibangun lagi dan lagi oleh diri sendiri ataupun orang lain.
5. Empirisme.
Empirisme merupakan suatu doktrin yang mengedepankan suatu pengalaman dalam memperoleh suatu pengetahuan. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme.
6. Humanism.
Filsafat humanisme memandang esensi manusia terletak pada potensi rasionalitas.
Pengaplikasian teori humanisme lebih fokus pada sisi perkembangan kepribadian manusia.3
Dalam ilmu filsafat, terdapat juga mcama-macam filsafat yakni:
1. Ontology.
Ontologi dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada di kehidupan nyata dan tidak mengada-ada. Ontologi membahas tentang cara pandang akan sesuatu itu, apakah dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau sesuatu yang bernuansa jamak, terikat dengan sesuatu sehingga harus dipahami sebagai sesuatu yang fakta (holistik).4
2. Epistemologi.
Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Cabang ilmu filsafat ini adalah bagian filsafat yang mencari tahu penyebab, asumsi dasar, sifat-sifat, dan cara memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan model filsafat.
3. Aksiologi.
2 Fitzgerald K. Sitorus, “Dualitas Idealisme Dan Materialisme,” Extension Course Filsafat (ECF), 2017.
3 Novia Nuraini, “ALIRAN FILSAFAT BEHAVIORISME, KOGNITIVISME, HUMANISME, DAN KONSTRUKSTIVISME,” n.d.
4 Erwin Ridha Ardhi, “ONTOLOGI LOGIKA DALAM FILSAFAT,” n.d.
Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai. Pengetahuan dan moral merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aksiologi tidak terlepas dari nilai, setiap ilmu pasti ada nilai di dalamnya.5
B. KOMUNIKASI
Komunikasi berasal dari kata communicare yang memiliki arti menyampaikan. Terdapat juga kata common yang memiliki arti kesamaan. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu dalam maksud mendapaatkan keserasian makna.
Komunikasi merupakan sebagai suatu proses mestimulasi dari seorang individu terhadap individu lain dengan mengguakan lambing-lambang yang memiliki arti, berupa lambang kata untuk mengubah tingkah laku. Secara sederhana, komunikasi merupakan sebuah cara untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, dan sebagainya melalui symbol-simbol yang bisa dimengerti oleh individu lain. Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.6
Menurut Prof. Onong Ucahana Efendy, filsafat komunikasi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analisis, kritis, dan holistis tentang teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, teknik dan perannya.
Hubungan filsafat dengan komunikasi yaitu kebenaran dalam berbicara di depan khalayak umum, dengan siapapun, dimanapun, dan dimana saja kita berada. Kajian filsafat tentang komunikasi menjadi sebuah petunjuk bagi disiplin ilmu lain yang subjeknya menelaah perilaku manusia.
Berkomunikasi merupakan sesuatu yang wajib dilakukan manusia untuk bersosialisasi. Tanpa adanya komunikasi, manusia akan kesulitan untuk bertahan hidup. Sejak lahir, manusia diajari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi adalah sebuah keharusan bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial.
Terdapat etika dalam berkomunikasi, hal tersebut dapat mengelaborasi standar etnis yang digunakan oleh komunikator dan komunikan. Etika komunikasi juga berhubungan dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagaimya. Dengan berkomunikasi, manusia bisa menyelesaikan sebuah konflik atau bisa mencapai sebuah tujuan, atau bahkan bisa memulai sebuah konflik.
Hakikat komunikasi merupakan sebuah proses pernyataan antarmanusia. Isi dari pernyataan tersebut ialah pikiran atau perasaan seseorang kepada komunikan dengan menggunakan lambanglambang yang bisa dimengerti oleh komunikan.
5 S. Pd Herdayati and S. Th I. Syahrial, “Sekilas Informasi Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu: Objek (Identifikasi) Aksiologi,” n.d.
6 Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis (IRCISOD, 2009).
Dalam ilmu filsafat, terdapat 3 aspek yang menajadi penyangga filsafat, yani logika, ontology, epistemologi. Keempat aspek tersebut dikenal sebagai 4 pilar filsafat. Komunikasi termasuk suatu disiplin ilmu, maka komunikasi termasuk dalam keluarga filsafat.7
Secara Bahasa, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philos dan sophia. Terdapat banyak tokoh-tokoh dalam filsafat, diantaranya adalah Socrates (469-399 SM), Plato (427-347SM), Aristoteles (384-322 SM), dan banyak lainnya.
Dalam filsafat terdapat beberapa pandangan, yaitu idealisme, humanisme, rasionalisme, empirisisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Teredapat juga beberapa cabang dalam ilmu filsafat, antara lain yakni ontology, epistemologi, aksiologi.
Komunikasi adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan dengan berupa lambing-lambang yang dimengerti oleh masing-masing individu sehingga individu yang lain dapat memahami pesan yang disampaikan. Kajian filsafat dalam komunikasi menjadi sebuah petunjuk bagi disiplin ilmu lain yang subjeknya tentang perilaku manusia.
C. HAKEKAT KOMUNIKASI MANUSIA
Istilah komunikasi saat ini telah digunakan dalam arti yang sangat luas, artinya mengalami perluasan makna. Kalau dulu komunikasi diartikan percakapan atau interaksi antar individu. Namun saat ini komunikasi sudah dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menyampaikan pemikiran dari sebuah pemikiran ke pemikiran yang lainnya. Karena semua proses komunikasi adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain. Secara tekstual-normatif, ilmu komunikasi sudah ada dan berkembang dalam tradisi Islam, hanya saja karena pengkajian, penelitian dan perkembangannya secara ilmiah dimulai dari Barat (Eropa AS) maka secara historis-kontekstual, ilmu komunikasi sebagai ilmu muncul dan berkembang dari barat.
Komunikasi mulai dari komunikator yang ingin mengatakan sesuatu. Kemudian memutuskan bagaimana cara mengatakan dan mentransmisikannya. Komunikasi sampai ke penerima, membentuk kesan apa yang telah didengarnya dan menterjemahkannya menurut sikap dan pengalamannya.
Masalah utama dalam komunikasi adalah bahwa arti yang diterima oleh seseorang mungkin bukanlah apa yang dimaksudkan oleh pengirimnya. Pengirim dan penerima adalah dua orang yang hidup dalam dunia yang berbeda. Beberapa hal dapat terjadi dan mengganggu pesan yang lewat diantara mereka. Kebutuhan dan pengalaman orang cenderung untuk mewarnai apa yang mereka lihat dan dengar. Pesan-pesan yang tidak ingin mereka dengar ditekan, sementara yang lainnya diperbesar, yang tercipta dalam lingkungan yang sempit atau terganggu dari kenyataan yang sebenarnya.
Ada sebuah pertanyaan mendasar “Mengapa kita berkomunikasi” hal tersebut bisa dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:
1. Apa yang mendorong kita berkomunikasi ?
2. Manfaat apa yang kita dapat dari komunikasi ?
3. Sejauhmana komunikasi memberi andil kepada kita ?
7 Irvilani Sari, “Filsafat Komunikasi,” accessed March 23, 2023, https://www.academia.edu/30042259/Filsafat_Komunikasi.
4. Bagaimana faktor citra diri, pengalaman, situasi dan mitra komunikasi mempengaruhi kita ?.
5. Kendala apa saja yang menghambat kita untuk berkomunikasi?.
Kita berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang yang berada disekitar kita, mempengaruhi orang, namun tujuan utama dalam berkomunikasi adalah mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Fungsi komunikasi ada 4 macam, berikut penjelasannya:
a. Komunikasi Sosial. Komunikasi sosial amat penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat. Komunikasi digunakan untuk menata diri dalam lingkungan sosial, juga digunakan agar bisa menyatu dengan masyarakat sekitar kita, bagaimana kita bersikap dan berperilaku, memperlakukan orang lain, itu semua bisa dipelajari lewat komunikasi yang terus menerus dengan masyarakat.
b. Komunikasi Ekspresif. komunikasi untuk menyampaikan perasaanperasaan (emosi) kita. Hal ini dikomunikasikan melalui pesan nonverbal, perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, sedih, takut, prihatin, marah dan benci, disampaikan lewat kata-kata, terutama lewat perilaku nonverbal.
c. Komunikasi Ritual. Biasanya komunikasi ini dilakukan secara kelompok, wujudnya seperti pelaksanaan upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, hingga upacara kematian. Dalam kegiatan diatas orang mengucapkan kata-kata dan menunjukkan perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Melaksanakan ibadah sholat, naik haji, membaca kitab suci, upacara wisuda, perayaan lebaran termasuk juga dalam bentuk komunikasi ritual. Mereka yang bersama dalam kegiatan tersebut saling menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, agama, ideologi, suku, bangsa dan negara mereka. d. Komunikasi Instrumental. Komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan, untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan bisa juga untuk menghibur.8
Pertanyaan dasarnya adalah mengapa kita berkomunikasi? dan bukan bagaimana kita berkomunikasi,sebagaimana banyak dibahas oleh para pakar selama ini. Dari perspektif agama, secara mudah kita bisa menjawabnya bahwa Tuhan-lah yang mengajari kita berkomunikasi, dengan akal dan kemampuan berbahasa yang dianugerahkan-Nya kepada kita. Firman Allah; “Tuhan yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarinya pandai berbicara”. Barangkali perlu dirumuskan beberapa pertanyaan yang spesifik, sehingga lebih mudah untuk menjawabnya, seperti; Apa yang mendorong kita berkomunikasi? Manfaat apa yang diperoleh dari komunikasi? Sejauh mana komunikasi memberi andil kepada kepuasan kita?
Berkomunikasi penting untuk membentuk konsep diri, aktualisasi diri, untuk kepentingan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga, RT,RW, desa, kota) untuk mencapai tujuan bersama.
Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, bisa dipastikan akan tersesat, karena ia tidak berkesempatan menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai
8 Adhis Ubaidillah, “Konsep Dasar Komunikasi Untuk Kehidupan,” AL IBTIDA’: Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4, no. 2 (2016): 30–54.
panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Komunikasi pula yang memungkinkannya mengajari dan menerapkan strategistrategi adaptif untuk mengatasi situasi problematiknya. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara, karena cara berprilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dengan orang lain.9
D. ASUMSI ONTOLOGIS KOMUNIKASI
1. Komunikasi interpersonal
Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti dua sejawat atau dua rekan kerja, dua sahabat, atasan –bawahan, dan lain sebagainya. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang dalam situasi tatap muka. Pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan secara verbal ataupun nonverbal. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif dan lain sebagainya.
Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi anatar komunikator dengan komunikan, dianggap sebagai jenis komunikasi yang paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal meliputi perilaku verbal dan nonverbal.
Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dan diungkapkan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Hal ini mencakupi isi pesan dan bagaimana isi pesan dikatakan atau diungkapkan. Komunikasi interpersonal meliputi komunikasi berdasarkan perilaku spontan, perilaku menurut kebiasaan, perilaku menurut kesadaran atau kombinasi ketiganya.
Komunikasi interpersonal tidaklah statis tetapi berkembang. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berkembang, yang berbeda-beda tergantung dari tingkat hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, pesan yang dikomunikasikan dan cara pesan itu dikomunikasikan.
Komunikasi interpersonal mencakup umpan balik pribadi, interaksi, dan kohesi. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang memungkinkan terjadinya timbal balik. Dalam komunikasi ini terjadi interaksi diantara pengirim dan penerima pesan, yang satu mempengaruhi yang lain. Pengaruh itu terjadi pada tataran kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan behavior (perilaku).
Komunikasi interpersonal berpedoman pada aturan intrinsik. Peraturan intrinsik adalah peraturan yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengatur cara orang harus berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan peraturan ekstrinsik adalah peraturan yang ditetapkan oleh situasi.
Komunikasi interpersonal merupakan suatu aktivitas. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal mencakup persuasi. Komunikasi interpersonal berperan untuk saling mengubah dan mengembangkan.
Melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memberi inspirasi, semangat, dan dorongan untuk mengubah pemikiran, perasaan, dan sikap yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas bersama.10
2. Komunikasi kelompok
Ada dua istilah yang perlu di tekankan ketika berbicara tentang komunikasi kelompok, yaitu komunikasi dan kelompok. Istilah komunikasi dalam Bahasa Inggris “communication” berasal dari bahasa Latin “communicates” atau “communication” atau “cummunicare” yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”, memiliki makna bersama di antara yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya terkait dengan istilah komunikasi akan banyak dibahas pada pembahasan tentang komunikasi organisasi.
Kelompok adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena melalui kelompok manusia dapat berbagi dan bertukar informasi , pengalaman dan pengetahuan antara anggota kelompok yang satu dengan lainnya. Kelompok merupakan suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.
Komunikasi kelompok adalah suatu bidang studi, penelitian dan terapan yang tidak menitikberatkan perhatiannya pada proses kelompok secara umum, tetapi pada tingkah laku individu dalam diskusi kelompok tatap muka kecil.
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya.
Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari tiga individu atau lebih individu guna mmemperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat.
Komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan ke dalam 2 macam yaitu:
a. Kelompok kecil (microgroup) adalah kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal atau dalam komunikasi kelompok komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok, seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar dan lain-lain. Umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil ini biasanya bersifat rasional, serta diantara anggota yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan normanorma yang ada. Dengan perkataan lain, antara komunikator dengan setiap komunikan dapat terjadi dialog atau tanya jawab. Komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti dan dapat menyangkal jika tidak setuju dan lain sebagainya.
b. Komunikasi kelompok besar (macrogroup) yaitu yang terjadi dengan sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi (kontak pribadi) jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan, karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul seperti halnya yang terjadi pada acara tabligh akbar, kampanye dan lain-lain. Angggota kelompok besar apabila memberitakan tanggapan kepada komunikator, biasanya bersifat emosional, yang tidak dapat mengontrol emosinya. Lebih-lebih jika komunikan heterogen, beragam dalam
usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, pengalaman, dan sebagainya. Seperti halnya jika diantara kerumunan itu seorang yang tidak suka pada komunikator, maka dia berusaha mencari kesempatan untuk melempar dengan sandal dan yang lainnya tanpa tahu permasalahan akan mengikuti tindakan tersebut.
Suatu kelompok yang sedang melakukan diskusi atau komunikasi antara satu dengan yang lain selalu memiliki tema-tema yang berbeda antara kelompok satu dengan yang lainnya. Tematema ini dapat diteliti dan menghasilkan kecenderungan kelompok yang sedang berkomunikasi tersebut dengan tema-tema yang dibicarakannya.11
3. Komunikasi massa
Komunikasi massa adalah proses pengiriman pesan yang ditujukan kepada massa atau khalayak yang jumlahnya banyak. Proses komunikasi berbeda dengan dengan komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk:
a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi kemasyarakatan dalam jumlah yang besar. Contohnya, pada saat siaran Seputar Indonesia di RCTI, secara serentak dapat diterima oleh khalayak (pemirsa) dalam jumlah yang besar pula.
b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Sangat terbatas adanya peluang untuk terjadi dialog dua arah di antara pemberi pesan dan penerima pesan.
c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi di antara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara.
d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal (non personal) dan tanpa nama. Contohnya, tidak mudah mengetahui dengan cepat siapa dalang dari demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa tertentu.
e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan (market) di masyarakat. Karena tuntutan pasar, pemberitaan-pemberitaan massa lebih cenderung disesuaikan dengan permintaan pasar (khalayak). Misalnya, kalau tayangan Bukan Empat Mata tidak lagi disukai pemirsa, maka dengan segera pemilik siaran akan menghentikan acara tersebut karena tentu berpengaruh pada permintaan iklan/sponsor.
Ada banyak pandangan yang berbeda tentang fungsi dari komunikasi massa. Namun secara umum, fungsi komunikasi massa antara lain:
a. Fungsi informasi.
b. Fungsi hiburan.
c. Fungsi persuasi.
d. Fungsi transmisi budaya.
e. Fungsi untuk mendorong kohesi sosial.
f. Fungsi pengawasan.
g. Fungsi korelasi.
h. Fungsi pewarisan sosial.
i. Fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif.
Persuasi merupakan suatu teknik yang terdapat dalam kegiatan komunikasi dimana didalamnya terdapat upaya bagi komunikator untuk membujuk, mempengaruhi, merubah sikap, pola pikir dan perilaku komunikan sehingga tujuan dari komunikasi tercapai. Dalam media massa, keberadaan unsure persuasi sangat kental, dimana hampir semua kegiatan komunikasi massa dalam media massa menjadikan persuasi sebagai senjata utama dalam mempengaruhi masyarakat.
Besarnya pengaruh persuasi dapat dilihat dalam setiap pesan yang terdapat dalam media massa, yang semuanya terbungkus dalam desain acara yang berupa sinetron, iklan, music, film, humor maupun fashion.
Efektiitas dari teknik persuasi untuk mempengaruhi khalayak melalui media massa tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut menjadikan media massa sebagai salah satu kiblat bagi masyarakat dalam membentuk sikap dan perilaku mereka tanpa mereka sadari, dengan munculnya efek ketergantungan yang tinggi masyarakat terhadap segala bentuk media komunikasi massa.
Efek tersebut yang menjadi peluang sekaligus ancaman yang muncul dari media komunikasi massa dengan memfokuskan pada pesan persuasi yang sangat masif dimiliki oleh setiap kegiatan komunikasi massa.
Maka diperlukan filter yang kuat bagi komunikan dalam menerima pesan dari komunikator massa agar dalam kegiatan komunikasi melalui media massa tetap memiliki konsistensi moral baik yang dikontrol oleh komunikan sendiri maupunkomunikator dalam mendesain pesan mereka sehingga produk dari persuasi sarat dengan moral dan etika yang bertanggung jawab. Keberhasilan membangun persuasi yang efektif namun bermoral dan bertanggung jawab, serta menciptakan kontrol yang tinggi oleh masyarakat terhadap esensi persuasi dalam kegiatan komunikasi massa menjadi indikator keberhasilan masyarakat dalam mengendalikan media, sehingga masyarakat sebagai komunikan tidak lagi dikendalikan oleh media tetapi sebaliknya masyarakatlah yang mengendalikan dan menguasai media.12
4. Komunikasi organisasi
Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi.
Komunikasi organisasi dengan berbagai dimensinya dapat dipandang sebagai suatu cara untuk memetakan fenomena. Ketika kita menyadari bahwa pandangan terhadap fenomena/realitas pun tidak selalu ajeg, bergantung pada titik berdirinya, maka seyogianya kita menyikapinya bahwa hal itu mencerminkan suatu relativisme ilmu yang mengarah kepada sesuatu yang “baik”.
Demikian pula dengan komunikasi organisasi, adanya perbedaan-perbedaan pendekatan (objektif-subjektif) dalam pengkajiannya, di satu sisi dapat menjadi alternatif dalam menentukan pilihan, dan di sisi lainnya hal tersebut juga mencerminkan bahwa komunikasi organisasi juga bersifat kontekstual, bergantung kepada faktor manusianya, bentuk organisasi, bidang organisasi, dan lain sebagainya.
Komunikasi organisasi sebagai salah satu aspek dari perilaku organisasi, idealnya dengan didukung oleh strategi komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis baik dalam internal organisasi maupun dalam hubungan organisasi dengan stake holder-nya. Persoalannya, antara das solen dengan das sein tidaklah selalu sejalan.
Perilaku organisasi dengan berbagai aspeknya - salah satunya komunikasi organisasimemiliki bidang kajian yang luas, pengkajian yang lebih berfokus pada masalah komunikasi organisasi ini, antara lain dapat memberikan gambaran selintas mengenai keterkaitan antara disiplin ilmu, khususnya ilmu administrasi/manajemen dengan ilmu komunikasi. Untuk tujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai organisasi, tentunya perlu dikaji berbagai aspek perilaku organisasi lainnya.13
5. Komunikasi intrapersonal
Komunikasi Intrapersonal berasal dari 3 kata yaitu Komunikasi, Intra dan Personal atau pribadi. Komunikasi adalah “suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku”. Bagaimana setiap orang mengkomunikasikan dirinya atau berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan setiap orang dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri melalui penggunaan simbol-simbol yang digunakan dalam proses komunikasi. Melalui simbol-simbol ini apa yang dikatakan seseorang kepada orang lain dapat memiliki arti yang sama bagi dirinya sendiri sebagaimana berarti bagi orang lain.
Dalam proses pengambilan keputusan, sering kali seseorang dihadapkan pada pilihan Ya atau Tidak. Keadaan seperti ini membawa seseorang pada situasi berkomunikasi dengan diri sendiri, terutama dalam mempertimbangkan untung ruginya suatu keputusan yang akan diambil. Cara ini hanya bisa dilakukan dengan metode komunikasi Intrapersonal (Intrapersonal Communication/ komunikasi dengan diri sendiri).
Komunikasi intrapersonal juga memiliki elemen-elemen komunikasi atau komponenkomponen komunikasi atau unsur komunikasi yang mendukung proses komunikasi intrapersonal. Adapun elemenelemen komunikasi intrapersonal adalah sebagai berikut:
a. Decoding-bagian dari proses komunikasi intrapersonal yang harus dilalui dimana pesanpesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal.
b. Intergrasi (Integration)-bagian dari proses komunikasi intrapersonal dimana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama. Kita menghubungkan satu bagian informasi kepada orang lain, membuat perbandingan dan analogi, menggambarkan perbedaan, dan kemudian mengelompokkannya atau membuat sebuah keputusan tentang bagian informasi dimana ia berada.
c. Memori (memory)-ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya dan kepercayaan disimpan. Memori melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali.
d. Serangkaian persepsi atau schemata-menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasi informasi.
e. Encoding-bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal dimana pemaknaan diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna.
f. Umpan balik (feedback)-Komunikasi intrapersonal juga memiliki umpan balik yang dinamakan umpan balik diri. Terdapat dua jenis umpan balik diri yaitu umpan balik diri
eksternal dan umpan balik diri internal. Yang dimaksud dengan umpan balik diri eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar. Sementara itu, yang dimaksud dengan umpan balik diri internal adalah bagian yang kita terima dalam diri kita sendiri.
g. Gangguan-Elemen lain dalam komunikasi intrapersonal adalah interferensi atau gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memproses beberapa informasi pada tingkatan yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi.
Proses komunikasi intrapersonal melibatkan beberapa tahapan, yaitu:
a. Sensasi. Proses komunikasi intrapersonal dimulai dengan adanya sebuah stimulus. Komunikasi intrapersonal adalah reaksi terhadap stimuli yang dapat berupa stimuli internal atau stimuli eksternal.
b. Persepsi. Organ-organ kemudian menangkap sebuah stimulis dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf peripheral. Ketika kita menerima seluruh stimuli yang diarahkan kepada kita, kita memberi perhatian hanya kepada beberapa stimuli saja. Hal ini disebabkan karena kita menerapkan persepsi selektif. Hanya stimuli yang tinggi saja yang diterima sedangkan stimuli yang rendah akan dikesampingkan.
c. Memori. Tahap selanjutnya adalah memproses stimuli yang terjadi dalam tiga tingkatan yaitu kognitif, emosional, dan fisiologis. Proses kognitif berhubungan dengan intelektual diri termasuk penyimpanan, retrieval, pemilahan, dan asimilasi informasi. Proses emosional berkaitan dengan emosi diri. Semua emosi dan sikap, kepercayaan, dan pendapat berinteraksi untuk menentukan respon emosi terhadap berbagai stimulus. Proses fisiologis terjadi pada tingkatan fisiologis dan hal ini berkaitan dengan psikologis diri. Respon semacam ini direfleksikan melalui perilaku fisik seperti aktivitas otak, tekanan darah, dan lain-lain.
d. Transmisi. Pada tahap ini, pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Transmisi terjadi melalui berbagai impuls saraf.
Komunikasi intrapersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu:
a. Kesadaran diri.
b. Rasa kepercayaan diri.
c. Manajemen diri.
d. Motivasi diri.
e. Terfokus.
f. Kemandirian.
g. Kemampuan beradaptasi.
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori-teori komunikasi intrapersonal terkait erat dengan teori-teori komunikasi anatar pribadi atau teori komunikasi interpersonal. Hal ini disebabkan karena menurut beberapa ahli komunikasi intrapersonal merupakan bentuk khusus dari komunikasi interpersonal. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa komunikasi interpersonal yang efektif dapat terjadi manakala komunikasi intrapersonal berjalan dengan sukses.
Adapun manfaat berkomunikasi di dalam diri sendiri, jika seseorang ingin marah, tawuran, diajak pergi, sebelum ia akan marah atau tidak, menerima atau menolak tawuran, pergi atau tidak,
dia akan mempertimbangkan beberapa alternatif didalam pemikirannya serta mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Dengan kata lain, seseorang tidak langsung melakukan tindakan.14
Berikut adalah paradigma-paradigma yang ada dalam ilmu komunikasi:
1. Paradigma 1
Komunikasi harus terbatas pada pesan yang disengaja (purpose) dan diterima/sampai (received). Artinya, untuk terjadi komunikasi harus terdapat:
a. Komunikator pengirim pesan,
b. Pesan itu sendiri,
c. Komunikan penerima pesan.
Implikasinya, jika pesan tidak sampai ke penerima, maka tidak ada komunikan; karena tidak ada manusia yang menerima pesan. Karena tidak ada komunikan penerima pesan, maka tidak ada komunikasi yang menjadi objek kajian ilmu komunikasi.
Misalnya, ketika terdampar di pulau, anda menemukan sebuah botol plastik beserta secarik kertas beserta alat tulis. Anda menulis pesan dengan tujuan untuk meminta tolong. Kertas berisi pesan anda masukkan ke botol dan anda larung ke laut. Komunikasikah ini? Objek kajian ilmu komunikasikah ini?
Penganut Paradigma-1 menganalisis: pesan sudah disampaikandengan bertujuan (minta tolong), namun belum ada manusia yang menerima pesan. Artinya, sudah ada komunikator, sudah ada pesan, namun belum ada komunikan yang menerima dan memaknai pesan. Artinya, belum ada komunikasi antara anda yang berada di pulau dan orang lain yang menerima pesan anda, dan karenanya di luar objek kajiannya.Atau, dalam bahasa filsafat ilmu, peristiwa ini di luar ontologi Paradigma-1.
2. Paradigma 2
Komunikasi harus mencakup semua perilaku yang bermakna bagi penerima, apakah disengaja (purposive) ataupun tidak. Paradigma ini menyatakan bahwa pesan tidak harus bertujuan, tetapi harus sampai (received). Artinya, sudah harus ada pihak yang memaknai pesan. Sehingga, syarat objek kajian ilmu komunikasi bagi paradigma ini adalah harus ada:
a. Pesan yang sudah dikirim,
b. Komunikan.
Namun, perlu dicatat, Paradigma-2 memiliki definisi komunikan versinya sendiri.
Bagi paradigma ini, semua manusia yang berkomunikasi disebut komunikan; sama seperti semua orang Indonesia adalah Indonesian atau semua orang Amerika adalah American. Sehingga, pengirim maupun penerima pesan adalah manusia yang berkomunikasi: komunikan.
Dengan kata lain, karena tidak mensyaratkan purpose, paradigma ini tidak mempersoalkan pengirim dan penerima pesan, yang penting sudah sudah ada pihak yang memaknai pesan, berarti pesan itu sudah sampai (received).
3. Paradigma 3
14 Rahmiana Rahmiana, “Komunikasi Intrapersonal Dalam Komunikasi Islam,” Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam 2, no. 1 (2019): 77–90.
Komunikasi harus mencakup pesan-pesan yang disampaikan dengan sengaja, namun derajat kesengajaan sulit ditentukan. Artinya, pesan harus disampaikan dengan sengaja, memiliki tujuan (purpose), tapi tidak mempersoalkan apakah pesan itu sampai di sisi penerima.
Maka, syarat komunikasi bagi Paradigma-3, harus ada:
a. Komunikator pengirim pesan,
b. Pesan yang disampaikan,
c. Target komunikan keada siapa pesan itu ditujukan.
Ketika anda melambaikan tangan tapi teman tidak melihat, ini sudah merupakan komunikasi yang menjadi objek kajiannya. Bagi Paradigma-3, pertanyaannya adalah: mengapa pesan tidak sampai? Gangguan apa yang sedang terjadi: apakah pada saluran, atau pada alat penerima (receiver, mata teman anda), atau ada hal lainnya?
Kembali pada contoh di atas, yaitu ketika anda terdampar di pulau, menemukan sebuah botol plastikbeserta secarik kertas berikut alat tulis, kemudian anda menulis pesan dengan tujuan untuk meminta tolong, lantas botol berisi pesan anda larung ke laut. Pertanyaannya, komunikasikah ini? Objek kajian ilmu komunikasikah ini?
Jawaban penganut Paradigma-3, ini adalah objek kajiannya, karena pesan memiliki tujuan (purpose: minta tolong) walau belum ada yang menerima pesan (not received yet), di mana pesan itu jelas ditujukan kepada manusia di seberang sana, dan tidak ditujukan kepada ubur-ubur umpamanya. Artinya, sudah ada komuniator, sudah ada pesan, dan sudah ada target komunikannya.15
Kita berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang yang berada disekitar kita, mempengaruhi orang, namun tujuan utama dalam berkomunikasi adalah mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Fungki komunikasi ada 4 macam, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ritual, komunikasi ekspresif, dan komunikasi instrumental.
Terdapat 5 macam jenis komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan komunikasi intrapersonal. Ada juga bermacammacam paradigma dalam ilmu komunikasi.
E. ONTOLOGI.
Ontologi dapat diartikan sebagai studi yang membahas sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Secara terminologis ontologi juga diartikan sebagai metafisika umum yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan yang terdalam, ontologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan
Ontologi merupakan pembahasan tentang bagaimana cara memandang hakekat sesuatu itu, apakah dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan bisa dipisah dari sesuatu yang lain atau bernuansa jamak, terikat dengan sesuatu yang lain, sehingga harus dipahami sebagai suatu kebulatan (holistik). Pengertian paling umum pada ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu.
Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge base. Sebuah ontologi juga dapat
15 Dani Vardiansyah, “Ontologi Ilmu Komunikasi: Usaha Penyampaian Pesan Antarmanusia,” KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 14, no. 2 (2017).
diartikan sebuah struktur hirarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah knowledge base Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada.16
Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada diluar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris, sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri yakni berorientasi pada dunia empiris.
Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan dua macam:
1. Obyek material (obiectum materiale, material object) ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu.
2. Obyek Formal (obiectum formale, formal object) ialah penentuan titik pandang terhadap obyek material.
Hakekat obyek ilmu (ontologi) terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan dan objek format yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu.17
Landasan dasar eksistensi sebuah ilmu adalah adanya paradigma. Semua disiplin ilmu memiliki paradigma yang melandasi pemikiran keilmuannya. Paradigma adalah pendekatan umum, ssebuah pandangan tentang dunia, dengan berpijak pada teori yang lebih spesifik, dan menjelaskan sebuah fenomena atau fakta-fakta.
Pemahaman terhadap paradigma yang kini menjadi acuan dalam teori komunikasi modern diilhami oleh tradisi proses informasi dan sibernatika, dimana teori komunikasi itu berawal dari sudut pandang pemrosesan informasi sehingga menjadi paradigma.
Banyaknya ragam dan perpektif tentang paradigma, baik perspektif penelitian maupun keilmuan, maka pembahasan tentang paradigma komunikasi ini dibatasi pada dua pendekatan paradigma yaitu pertama, paradigma pendekatan proses komunikasi dan kedua, paradigma pendekatan penelitian komunikasi.
Paradigma dengan pendekatan proses komunikasi meliputi paradigma mekanistis, psikologis, interaksi simbolik, dan paradigmatic. Sedangkan paradigma pendekatan penelitian komunikasi ada tiga yaitu, classical paradigm, critical paradigm, dan constructivism paradigm. 18
F. KONSTRUKSI.
Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun, membangun dari segi kemampuan, pemahaman, Kosntruksivisme menyoroti interaksi orang-orang dan situasi-situasi dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilanketerampilan dan pengetahuan.19
16 Erwin Ridha Ardhi, “ONTOLOGI LOGIKA DALAM FILSAFAT,” n.d.
17 Bahrum Bahrum, “Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi,” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 8, no. 2 (2013): 35–45.
18 Ali Nurdin, Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis (Prenada Media, 2020).
19 Suparlan Suparlan, “Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran,” Islamika 1, no. 2 (2019): 79–88.
Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan itu merupakan bentukan dari orang yang sedang belajar. Pengetahuan bukan kumpulan fakta-fakta tetapi merupakan konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungan. Pengetahuan bukanlah “sesuatu yang sudah ada di sana” dan tinggal mengambilnya, tetapi merupakan suatu bentukan terus menerus dari orang yang belajar dengan setiap mengadakan reorganisasi karena adanya pemahaman yang baru.20
Belajar adalah merupakan proses perubahan konseptual di mana terjadi pengkonstruksian dan penerimaan gagasan-gagasan yang ada. Pemahaman dapat dibangun oleh siswa sendiri secara aktif dan kreaktif, hal ini sesuai dengan pendapat para ahli konstruktivisme yang mengatakan pengetahuan tidak diterima siswa secara pasif, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh siswa.21
Ketika berkomunikasi, orang akan mendapat pandangan-pandangan maupun gagasangagasan baru. Sama seperti teori konstruktivisme. Di saat terjadinya komunikasi, komunikator dan komunikan akan saling menukar pikiran, disitulah seseorang akan mendapat pemahaman yang baru baginya.
Contohnya seperti guru dengan muridnya, ketika guru menerangkan sesuatu, muridnya akan mendapatkan pemahaman baru mengenai apa yang disampaikan oleh gurunya. Komunikasi secara aktif akan lebih efektif saat bertukar pikiran. Ketika murid dengan pasif berkomunikasi dengan gurunya saat pembelajaran berlangsung, maka guru tidak bisa menyampaikan gagasan kepada muridnya secara efektif.
Untuk memperoleh pengetahuan, seorang manusia harus mengambilnya, bukan pengetahuan yang datang kepada orang tersebut. Ketika seseorang berdiam diri saja dan tidak mencoba meraih pengetahuan, maka orang itu tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan diambil dengan cara membaca buku, peristiwa yang telah lampau, bahkan dengan berkomunikasi bisa mendapatkan pengetahuan.
G. DIMENSI PESAN.
Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Pesan tersebut membawa muatan makna dari pengirim kepada penerima melalui suatu medium tertentu. Makna tersebut ‘dibaca’ oleh penerima kemudian diresponi dalam bentuk tindakan komunikasi berikutnya. Jadi komunikasi adalah proses berbagi dan menciptakan makna secara simultan melalui interaksi simbolik manusia. Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.
Sebagai sebuah proses, komunikasi bersifat berkesinambungan, dinamis dan kompleks. Proses penciptaan dan penginterpretasian makna berlangsung terus-menerus. Dalam proses tersebut, makna pun dimanfaatkan sesuai kebutuhan para pelaku komunikasi.
20 Novia Nuraini, “ALIRAN FILSAFAT BEHAVIORISME, KOGNITIVISME, HUMANISME, DAN KONSTRUKSTIVISME,” n.d.
21 Roni Rodiyana and Wina Dwi Puspitasari, “Model Pembelajaran Konstruktivisme Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Dasar,” Proceedings of the ICECRS 2, no. 1 (2019): 147–57.
Kebutuhan akan komunikasi dapat berupa physical needs yang berkaitan dengan kesehatan baik badan maupun jiwa, identity needs yang berkaitan dengan pendefinisian dan pengungkapan diri untuk membentuk suatu identitas atau bayangan tertentu di benak orang lain mengenai siapa diri kita, social needs yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain seperti kesenangan, kasih sayang, persahabatan, pengakuan, pelarian dari tekanan, relaksasi dan kontrol. Di samping itu, kebutuhan akan komunikasi juga dapat didorong oleh practical goals atau instrumental goals, yakni berkomunikasi untuk tujuan praktis tertentu, misalnya membuat orang lain bersikap dan berperilaku seperti yang kita inginkan.
Pesan merupakan sentral dalam proses komunikasi. Tanpa adanya unsur pesan, maka sebuah aktivitas tidak dapat disebut komunikasi. Pesan di sini dapat berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Pesan merupakan perahu makna. Melalui tumpangan pesanlah suatu makna yang diencode oleh komunikator atau pengirim (source) berlayar melewati saluran (channel) untuk kemudian tiba di pelabuhan komunikan atau penerima (receiver) untuk di-decode. Tentu saja, pesan bukan satu-satunya tumpangan makna, karena makna juga dapat menumpang pada saluran atau medium yang dilewati pesan,
Dalam proses encoding, demi mencapai tujuan dan terpenuhinya kebutuhan spesifik komunikasi, komunikator dapat menggunakan wewenang dan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan-tindakan kurang patut atau tidak etis seperti memanipulasi data, informasi, fakta yang dikonversi ke dalam makna sebuah pesan. Tindakan lain dapat berupa konversi makna dari bahan yang tidak benar atau tidak nyata (fiktif) sehingga pesan yang disampaikan merupakan pesan bohong.
Dalam hal ini termasuk disinformasi, yakni informasi palsu yang sengaja (intentionally) disebarkan secara diam-diam (kadang dibungkus dalam bentuk rumor) untuk membentuk opini publik atau mengaburkan suatu kebenaran atau semacam propaganda yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi pemerintah untuk menghadapi kekuatan saingan atau media. Disinformasi berbeda dengan misinformasi, yakni informasi salah yang tidak disengaja.
Begitu pula dengan pemalsuan maupun pengurangan elemen-elemen pesan, misalnya dalam pembajakan teks, penyamaran makna simbol atau ikon untuk mengelabui khalayak, dan penggiringan makna secara sengaja ke arah yang keliru untuk menciptakan kesan tertentu pada suatu obyek. Dalam hal ini, maka bahasa teks dan simbol yang di-encode menjadi makna pesan merupakan kendaraan utama tindakan koruptif yang sekaligus memengaruhi tingkat koruptivitas suatu komunikasi. Semakin jauh bahasa dan simbol yang digunakan dari nilai-nilai kebenaran dan kepatutan nuranif, maka semakin koruptif proses dan hasil komunikasi tersebut.
Kerangka etis komunikasi terletak pada tuntutan yang terkait bahasa. Prinsip-prinsipnya adalah, pertama, pernyataan yang dibuat adalah benar bila isinya benar-benar ada dalam proposisi, kedua, tindak bahasa dianggap tepat bila sesuai dengan konteks normatif yang berlaku, ketiga, maksud yang diungkapkan pembicara benar-benar merupakan isi dari apa yang dipikirkannya. Dengan demikian, tipe komunikasi yang dibangun menjadi medium saling pemahaman tanpa manipulasi, tanpa pengondisian, dan tanpa tipuan.
Konteks dalam komunikasi dapat dimaknai sebagai keadaan atau situasi luas di mana komunikasi terjadi. Komunikasi tak dapat terjadi dalam ruang hampa. Selalu ada kondisi yang dapat diatur, baik yang bersifat formal maupun informal (formal and informal setting). Konteks inilah yang memengaruhi apa yang akan kita katakan (what-to-say) dan bagaimana mengatakannya (howto-say). Konteks juga menentukan tipe komunikasi apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, maka
konteks memegang peranan penting dalam manajemen makna karena setting yang digunakan dapat memengaruhi persepsi khalayak dalam proses decoding terhadap makna pesan yang disampaikan.
Dalam komunikasi pemerintahan, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap acara yang dihadiri pejabat-pejabat pemerintahan, selalu ada pengaturan-pengaturan tertentu di lokasi acara untuk menimbulkan kesan keteraturan. Pada zaman orde baru, seringkali dialog atau interaksi langsung antara pejabat dan rakyat adalah sandiwara belaka, karena baik “sang rakyat” maupun jawaban-jawaban atau pertanyaan yang keluar dari mulutnya telah diskenariokan sebelumnya, dengan kata lain semua palsu, hanya untuk menciptakan kesan positif di mata publik yang lebih luas, terutama jika diliput oleh media.
Komunikasi pencitraan semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif karena fakta dimanipulasi sedemikian rupa sehingga hak publik untuk mendapatkan kebenaran pesan jadi terabaikan.22
Ontologi membahas tentang asas-assas rasional dalam sebuah pengetahuan. Paradigma menjadi sebuah landasan perpektif dalam melihat sebuah pengetahuan. Sebuah makna pesan dapat dikonstruk atau dibangun sehingga orang yang menerima pesan menjadi lebih mengerti dengan makna pesan yang disampaikan.
Berkomunikasi dengan orang lain sifatnya itu dinamis dan terus mengalami perubahan makna isi pesan. Hal tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pelaku komunikasi. Makna pesan bisa saja di manipulasi oleh pembuat pesan, maka harus berhati-hati ketika menerima informasi dari individu maupun dari sebuah lembaga organisasi.
22 Bambang Sukma Wijaya, “Korupsi Komunikasi Dalam Dimensi Pesan, Media, Konteks, Dan Perilaku: Sebuah Proposisi Teoretis Untuk Riset,” Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication 3, no. 1 (2014): 1–13.
BAB III PENUTUP
Dalam filsafat terdapat beberapa pandangan, yaitu idealisme, humanisme, rasionalisme, empirisisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Teredapat juga beberapa cabang dalam ilmu filsafat, antara lain yakni ontology, epistemologi, aksiologi.
Komunikasi adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan dengan berupa lambing-lambang yang dimengerti oleh masing-masing individu sehingga individu yang lain dapat memahami pesan yang disampaikan. Kajian filsafat dalam komunikasi menjadi sebuah petunjuk bagi disiplin ilmu lain yang subjeknya tentang perilaku manusia.
Kita berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang yang berada disekitar kita, mempengaruhi orang, namun tujuan utama dalam berkomunikasi adalah mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Fungki komunikasi ada 4 macam, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ritual, komunikasi ekspresif, dan komunikasi instrumental.
Terdapat 5 macam jenis komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan komunikasi intrapersonal. Ada juga bermacammacam paradigma dalam ilmu komunikasi.
Ontologi membahas tentang asas-assas rasional dalam sebuah pengetahuan. Paradigma menjadi sebuah landasan perpektif dalam melihat sebuah pengetahuan. Sebuah makna pesan dapat dikonstruk atau dibangun sehingga orang yang menerima pesan menjadi lebih mengerti dengan makna pesan yang disampaikan.
Berkomunikasi dengan orang lain sifatnya itu dinamis dan terus mengalami perubahan makna isi pesan. Hal tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pelaku komunikasi. Makna pesan bisa saja di manipulasi oleh pembuat pesan, maka harus berhati-hati ketika menerima informasi dari individu maupun dari sebuah lembaga organisasi.
BIOGRAFI PENULIS
Rayhan Faysal Haq lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juli 2003. Pendidikan dasar diselesaikan di SDI Sabilillah Sidoarjo pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan selesai pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan lulus pada tahun 2022.
Perguruan tinngi sedang dijalani di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Menekuni program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya seorang mahasiswa semester 2 yang baru masuk UINSA pada tahun 2022.
Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Memiliki tempat tinggal yang berada di Sidoarjo.
DAFTAR PUSTAKA
Anna Poedjiadi and S. H. Suwarma Al Muchtar, “Pengertian Filsafat,” Idik4006/Modul 1 (2014): 1–29.
Ardhi, Erwin Ridha. “ONTOLOGI LOGIKA DALAM FILSAFAT,” n.d.
Bahrum, Bahrum. “Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 8, no. 2 (2013): 35–45.
Erwin Ridha Ardhi, “ONTOLOGI LOGIKA DALAM FILSAFAT,” n.d.
Fitzgerald K. Sitorus, “Dualitas Idealisme Dan Materialisme,” Extension Course Filsafat (ECF), 2017.
Furqon, Chairul. “Hakikat Komunikasi Organisasi.” Hakikat Komunikasi Organisasi 2, no. 15 (2003): 1–9.
Irvilani Sari, “Filsafat Komunikasi,” accessed March 23, 2023, https://www.academia.edu/30042259/Filsafat_Komunikasi
Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis (IRCISOD, 2009).
Mudjiono, Yoyon. “Komunikasi Sosial.” Jurnal Ilmu Komunikasi 2, no. 1 (2012): 99–112.
Nida, Fatma Laili Khoirun. “Persuasi Dalam Media Komunikasi Massa.” Jurnal Komunikasi
Penyiaran Islam 2, no. 2 (2014): 77–95.
Novia Nuraini, “ALIRAN FILSAFAT BEHAVIORISME, KOGNITIVISME, HUMANISME, DAN KONSTRUKSTIVISME,” n.d.
Nuraini, Novia. “ALIRAN FILSAFAT BEHAVIORISME, KOGNITIVISME, HUMANISME, DAN KONSTRUKSTIVISME,” n.d.
Nurdin, Ali. “Komunikasi Kelompok Dan Organisasi.” UIN Sunan Ampel Press, 2014.
Nurdin, Ali. Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis. Prenada Media, 2020.
Rahmiana, Rahmiana. “Komunikasi Intrapersonal Dalam Komunikasi Islam.” Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam 2, no. 1 (2019): 77–90.
Rodiyana, Roni, and Wina Dwi Puspitasari. “Model Pembelajaran Konstruktivisme Untuk
Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Dasar.” Proceedings of the ICECRS 2, no. 1 (2019): 147–57.
S. Pd Herdayati and S. Th I. Syahrial, “Sekilas Informasi Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu: Objek (Identifikasi) Aksiologi,” n.d.
Suparlan, Suparlan. “Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran.” Islamika 1, no. 2 (2019): 79–88.
Ubaidillah, Adhis. “Konsep Dasar Komunikasi Untuk Kehidupan.” AL IBTIDA’: Jurnal Program
Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4, no. 2 (2016): 30–54.
Vardiansyah, Dani. “Ontologi Ilmu Komunikasi: Usaha Penyampaian Pesan Antarmanusia.”
KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 14, no. 2 (2017).
Wijaya, Bambang Sukma. “Korupsi Komunikasi Dalam Dimensi Pesan, Media, Konteks, Dan
Perilaku: Sebuah Proposisi Teoretis Untuk Riset.” Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication 3, no. 1 (2014): 1–13.
Wijaya, Ida Suryani. “Komunikasi Interpersonal Dan Iklim Komunikasi Dalam Organisasi.” Jurnal Dakwah Tabligh 14, no. 1 (2013): 115–26.