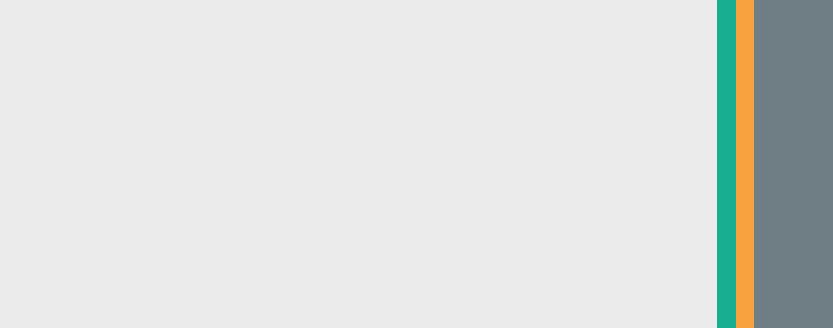
19 minute read
Mengenal Rainwater Harvesting
Arief Dhany Sutadian, ST, M.Eng, Ph.D* Eka Jatnika Sundana, ST, M.Sc** Diana Pramanik, ST, MT***
Pendahuluan
Advertisement
Di banyak negara, keberlanjutan pemenuhan dan penggunaan sumber air untuk kebutuhan perkotaan telah menjadi isu penting para pengambil kebijakan. Utamanya, kapasitas sumber-sumber air permukaan dan air tanah untuk memenuhi kebutuhan masa depan kotakota di dunia patut dipertanyakan. Beberapa kali episode kekeringan berkepanjangan dalam beberapa dekade terakhir menjadi cerita berulang dan sulit dicarikan solusinya. Terlebih di masa depan, kelangkaan air (water scarcity) dan ketidakpastian kehandalan sumber penyediaan air disebabkan bukan hanya oleh keberagaman iklim, tetapi juga oleh arus urbanisasi yang memicu pertumbuhan permintaan kebutuhan air, dan dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air (Sharma et al., 2012). Situasi di atas telah mendorong para pengambil kebijakan dan perencana untuk mencari sumber-sumber air alternatif dan mengkaji ulang paradigma apakah perlu kebutuhan air perkotaan mensyaratkan kualitas air yang sangat baik? Kadang-kadang penyediaan air perkotaan dengan kualitas air yang sangat baik cenderung berlebihan. Sebagai contoh, penyediaan air minum untuk flushing toilet, hal ini terkait persyaratan kualitas air yang ada lebih tinggi daripada yang diperlukan. Oleh karenanya, mempertimbangkan kuantitas yang melimpah sepanjang tahun dan memiliki kualitas yang relatif baik (dalam kondisi alami dan tanpa pengolahan lengkap), memanen air hujan (rainwater harvesting) dapat secara luas dipergunakan untuk penggunaan non potable use (bukan untuk air minum atau memasak).
Sebagai sumber air alternatif, memanen air hujan untuk penyediaan air perkotaan pada skala lokal telah dipraktekan sejak permulaan masyarakat perkotaan ada. Memanen air hujan telah dilakukan di banyak tempat, bahkan di beberapa negara maju telah menjadi kewajiban untuk diimplementasikan (mandatory to implement). Sebagai contoh, sistem memanen air hujan wajib dipasang pada bangunan-bangunan baru di Catolonia, Spanyol dan bangunan yang memiliki atap lebih dari 100 m2 di Belgia. Tidak ada informasi yang dapat memastikan sejak kapan praktek memanen air hujan dilakukan. Namun demikian, bukti menunjukan bahwa sistem pengumpulan air hujan telah digunakan di India, Mesopotamia, China, dan Israel sekitar 2000 tahun sebelum masehi. Memanen air hujan menawarkan benefits kepada siklus air, yakni menurunkan puncak air limpasan (stormwater runoff); mengurangi pencemar nutrients yang diterima badan air; dan memperbaiki ecological health sungai-sungai kecil (Kim and Furumai, 2012).
Terminologi ‘rainwater harvesting’ secara luas diterima sebagai upaya-upaya untuk menghasilkan (to crop) atau memanen (to yield) air hujan dari alam. Secara umum, terminologi memanen air hujan digunakan sebagai suatu konsep untuk serangkaian metode dalam mengumpulkan dan menyimpan air hujan, meliputi air hujan yang jatuh dari atap (rooftop harvesting), air hujan yang menjadi limpasan (stromwater atau runoff harvesting) dan dari saluran drainase (flood water harvesting), dari berbagai sumber (hujan atau embun) dan untuk berbagai tujuan (pertanian, peternakan, air minum dan pengelolaan lingkungan).
Di antara beberapa alternatif sumber daya air yang tersedia, stormwater atau rainwater lebih disenangi oleh masyarakat kebanyakan, terutama dibandingkan dengan air buangan yang didaur ulang (Mitchell et al., 2002). Memanen dan mendaur air hujan merupakan praktek yang secara luas digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penghantaran air
hujan (Hatt et al., 2006). Secara internasional, terminologi ‘stormwater harvesting’, ‘rainwater harvesting’ dan ‘water harvesting’ seringkali dipertukarkan penggunaannya karena memiliki pengertian yang relatif sama. Namun demikian, di Australia dan hampir di sebagian besar tempat, rainwater harvesting secara khusus mengacu hanya untuk air hujan yang berasal dari atap rumah sebelum air hujan tersebut menyentuh tanah. Jika tidak dipanen secara langsung dari atap rumah, air hujan tersebut menjadi bagian stormwater (air hujan yang menjadi limpasan atau run off).
Sistem Rainwater Harvesting
Secara tipikal, sistem memanen air hujan terdiri atas tiga element dasar: sistem pengumpulan, sistem penghantaran, dan sistem penyimpanan. Sistem memanen air hujan dapat berbeda beda dari sistem yang sangat sederhana yang terdiri atas satu rumah tangga sampai kepada sistem yang lebih besar dimana daerah tangkapannya berkontribusi kepada sebuah reservoir yang dibangun di daerah hilir atau lembah dimana airnya dialirkan secara gravitasi atau dipompa menuju bangunan pengolahan air. Kategorisasi sistem memanen air hujan tergantung kepada banyak faktor seperti ukuran dan nature dari daerah tangkapannya dan apakah sistem tersebut berada di lingkungan perkotaan atau pedesaan.
Sistem memanen melalui atap sederhana
Meskipun pengumpulan air hujan oleh sebuah atau beberapa rumah mungkin tidak terlihat signifikan, tetapi bayangkan dampaknya apabila ribuan atau bahkan jutaan rumah menerapkan hal yang sama dalam menyimpan air hujan. Komponen utama dalam pengumpulan air hujan yang diambil dari atap sebuah rumah adalah tangki penyimpanan (secara sederhana masyarakat Indonesia kadang menyebutnya sebagai toren), dan perpipaan yang membawa air dari atap rumah ke tangka penyimpanan. Material dan tingkat teknologinya tergantung kepada investasi awal. Beberapa tangki penyimpanan terbuat dari ferro-cement, plastik, dan lainnya. Di beberapa kasus, air hujan yang dikumpulkan sebelum digunakan boleh jadi diberikan disenfektan untuk membunuh kuman atau mikrobiologi berbahaya bagi kesehatan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Sistem pengumpula atap sederhana (sumber: UN Habitat 2018)
Sistem memanen dari fasilitas besar di perkotaan
Sistem memanen air hujan jenis ini digunakan untuk area yang lebih luas seperti fasilitas pendidikan, bandara, stadion dan fasilitas besar lainnya. Ketika sistem pengumpulan jauh lebih besar, keseluruhan sistem mungkin menjadi lebih sedikit kompleks, sebagai contoh, pengumpulan air hujan bukan hanya berasal dari atap bangunan tetapi juga dari limpasan area tersebut, kemudian disimpan dalam ground reservoir, diolah dan kemudian dipergunakan untuk non potable use.
Sistem memanen di gedung tinggi
Bangunan-bangunan tingi di area perkotaan berpotensi untuk menerapkan rainwater harvesting. Atapnya dapat dirancang untuk tujuan menangkap air hujan dan dikumpulkan pada beberapa tangki penyimpanan terpisah. Contoh fasilitas memanen air hujan diterapkan dan dibangun dengan baik di Sumo Wrestling Arena, Tokyo Jepang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Fasilitas memanen air hujan di Sumo Wrestling Arena, Tokyo, Jepang (sumber: https://thetokyofiles.com/2014/02/08/clearwater-nippon-tokyos-water-infrastructure/japan-stadium-water-storage-1/)

Sistem tangkapan permukaan tanah (land surface catchments)
Memanen air hujan menggunakan tangkapan permukaan tanah dapat menjadi cara sederhana untuk mengumpulkan air hujan, dibandingkan dengan sistem memanen dengan bantuan atap rumah. Sistem tangkapan permukaan tanah menyediakan lebih banyak peluang untuk mengumpulkan air dengan tangkapan area yang lebih luas. Dengan menahan aliran sungai kecil melalui bangunan reservoir atau waduk kecil, sistem ini dapat memenuhi kebutuhan air untuk musim kemarau. Terdapat kemungkinan kehilangan air yang tinggi akibat inflitasi air ke dalam tanah ataupun penguapan sepanjang penghantaran. Karena kualitas air melalui sistem ini seringkali buruk, air hujan yang dikumpulkan biasanya diguakan untuk kebutuhan pertanian atau peternakan.
Potensi Rainwater Harvesting
Jumlah air yang dipanen disebut potensi rainwater harvesting. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi potensi rainwater harvesting, kondisi iklim khususnya curah hujan dan karaketeristik tangkapan dipertimbangkan sebagai dua faktor paling penting. Kuantitas air hujan merupakan variabel yang paling tidak dapat diprediksi dalam perhitungan potensi rainwater harvesting, oleh karenanya, untuk menentukan pasokan air hujan untuk daerah tangkapan tertentu, data curah hujan yang handal diperlukan, lebih diutamakan menggunakan data historis curah hujan sepuluh tahun terakhir. Juga,
akan jauh lebih baik apabila menggunakan data dari stasiun pencacat curah hujan terdekat. Pola hujan juga merupakan variabel penting yang menentukan perhitungan potensi rainwater harvesting. Jumlah hari hujan juga menentukan kebutuhan dan rancangan untuk sistem memanen air hujan. Semakin sedikit jumlah hari hujan atau semakin panjang periode musim kemarau, semakin banyak kebutuhan pengumpulan air hujan untuk suatu wilayah. Dengan demikian, jika musim kemarau terlalu panjang, tangki penyimpanan yang lebih besar akan diperlukan untuk menyimpan air hujan. Oleh karenanya, di wilayah tersebut, akan lebih layak air hujan dipergunakan untuk mengisi akifer air tanah dibandingkan untuk disimpan.
Menyimpan air hujan atau mengisi akifer air tanah?
Air hujan dapat disimpan untuk digunakan secara langsung atau dapat digunakan untuk pengisian akifer air tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan struktur yang sesuai seperti sumur pantek (dug wells), sumur bor (bore wells), parit resapan (recharge trenches), bidang resapan (recharge pits), dan sumur resapan (rescharge wells). Keputusan untuk menyimpan atau mengisi akifer air tanah bergantung kepada pola curah hujan. Sebagai contoh, di wilayah yang memiliki curah hujan sepanjang tahun dan sedikit mengalami musim kemarau dapat memanen air hujan untuk digunakan untuk sehari-hari dengan menyimpan air hujan pada ruang penyimpanan yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan wilayah yang memiliki curah hujan 3-4 bulan dalam setahun. Air hujan yang dikumpulkan sepanjang musim penghujan harus disimpan sepanjang tahun, yang berarti sejumlah besar air hujan harus disimpan pada tempat penyimpanan yang lebih besar. Pada kasus ini, adalah lebih handal apabila air hujan yang ada digunakan untuk pnegisian akifer air tanah sehingga pada musim kemarau air tanah tersebut memiliki muka air tanah yang dapat diandalakan untuk digunakan.
Pemilihan lokasi pengisian akifer air tanah harus dilakukan secara cermat sehingga dapat menjamin secara maksimal pengumpulan air limpasan dari daerah tangkapan air, juga untuk memfasilitasi pengisian akifer air tanah secara maksimal. Secara ilmiah, terdapat beberapa teknik atau metode yang dapat digunakan untuk menentukan (secara geologi) sebuah lokasi ideal untuk pengisian akifer air tanah yang biasanya terletak pada titik terendah suatu daerah tangkapan air, sehingga tujuan pengumpulan dan pengsian maksimum dari suatu akifer air tanah dapat tercapai. Namun demikian, disarankan untuk menjaga jarak aman minimum dari dua sumur resapan harus dipertimbangkan. Secara garis besar, hanya air limpasan yang berasal dari permukaan kedap air (paved surfaces) digunakan untuk pengisian akifer air tanah karena relatif bebas kontaminasi bakteri. Ini dapat dilakukan dengan mengarahkan pipa pembuangan yang mengumpulkan air dari daerah tangkapan atau atap rumah ke tempat penyimpanan.
Box 1 menjelaskan perhitungan potensi rainwater harvesting. Karakteristik area tangkapan menentukan kondisi penyimpanan. Semua perhitungan yang terkait dengan kinerja sistem memanen air hujan melibatkan penggunaan koefesien air larian (runoff coefficient) untuk menghitung kehilangan sejumlah air hujan akibat kebocoran, infiltrasi, area penampang, dan penguapan, dimana hal-hal tersebut, berkontribusi kepada pengurangan jumlah air hujan yang dapat dipanen. Potensi rainwater harvesting dapat didekati melalui formula berikut: Potensi rainwater harvesting = Tingi hujan (m) x area tangkapan (m2) x runoff coefficient Formula di atas dapat digunakan untuk menghitung potensi rainwater harvesting dari area tangkapan yang berasal dari rooftop atau lainnya. Misalkan sebuah Gedung memiliki atap seluas 100 m2. Tinggi hujan rata-rata per tahun di area tersebut 600 mm atau 0.6 m. SEcara sederhana, atap rumah hamper seluruhnya melimpaskan air hujan dan diasumsikan tidak ada proses penguapan (runoff coefficient = 1), maka dalam satu tahun terdapat air hujan yang dapat dipanen sebesar: Potensi rainwater harvesting = 100 m2 x 0.6 m x 1= 60 m3 = 60.000 liter Asumsikan bahwa hanya 80% dari total air hujan di atas dapat dipanen Volume air hujan yang dipanen = 60.000 liter x 0.8 = 48.000 liter. Apabila satu keluarga terdiri dari 4 orang, maka volume air hujan yang dipanen dapat memberikan pasokan sekitar 32 liter/orang/hari.
Box 1 Perhitungan potensi rainwater harvesting
Pengelolaan Air Berkelanjutan
Kebanyakan kota-kota di dunia mendapatkan air baku mereka dari tempat yang sangat jauh (water transfer). Sebagai contoh, air Kota Jakarta dipasok dari Sungai Citarum di Jawa Barat atau air Kota Bandung didapatkan dari Sungai Cikapundung dan Sungai Cisokan, Kabupaten Bandung.
Praktek ini meningkatkan ketergantungan penuh kepada sungai-sungai yang mengalir di daerah hulu yang pada titik tertentu seringkali menimbulkan konflik antar wilayah dan seringkali tidak berkelanjutan. Membangun waduk di area hulu untuk mengamankan pasokan air seringkali harus menenggelamkan rumah penduduk, lahan, dan area kehutanan. Ini juga memberikan dampak sosial-ekonomi dan budaya kepada masyarakat terdampak. Lebih jauh, beberapa wadukyang telah terbangunpun secara perlahan-lahan mengalami pendangkalan karena terisi oleh erosi lahan dan erosi tanah. Apabila waduk-waduk tersebut tidak dikelola dengan baik dengan menjaga tingkat sedimentasi yang masuk, kuantitas air yang dikumpulkan mungkin akan berkurang signifikan.
Pada saat sebuah kota sangat bergantung kepada sumber daya air dari tempat yang jauh, dan terdapat episode dimana curah hujan di daerah hulu waduk yang dibangun mengalami kekeringan berkepanjangan, kemampuan kota tersebut untuk berfungsi dengan baik secara serius dipertaruhkan. Kota tersebut sangat bergantung kepada jaringan perpipaan air terpusat dan sangat rentan menghadapi bencana alam. Perubahan dari sistem terpusat (centralised) ke sistem lokal dan menyebar (decentralised) melaui penerapan praktek-praktek rainwater harvesting seharusnya didorong oleh otorias terkait untuk menyiapkan kota yang lebih tanggap dan tangguh terhadap bencana, sekaligus memberikan tingkat fleksibilitas sebuah kota dalam menghadapi kekeringan atau bencana lainnya.
Siklus Hidrologi, Water Demand Management dan Kualitas Air Hujan
Karena tingkat urbanisasi yang sangat pesat, banyak kota-kota besar di dunia menghadapi masalah banjir perkotaan. Banjir tersebut merupakan manifestasi siklus hidrologi alami pada skala yang berbeda-beda, bergantung kepada faktor iklim, geografi, dan biologi. Setelah hujan jatuh pada waktu tertentu dan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, air hujan tersebut juga mengisi mata air dan sungai. Permukaan yang kedap air seperti lapisan asphalt dan beton cenderung mengganggu siklus hidrologi alami, dan mengurangi jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Penurunan area resapan dimana air limpasan melimpas dengan cepat, menyebabkan air hujan berakumulasi di saluran drainase dan sungai dengan cepat. Setiap kali terdapat hujan deras, terdapat air limpasan dari drainase atau sungai dan berulang kali menjadikannya banjir perkotaan. Memanen air hujan memberikan manfaat besar kepada pengendalian banjir perkotaan dimana sebagian besar air hujan yang ada dikumpulkan dan ditampung pada tingkat rumah tangga dan pada akhirnya dapat menurunkan puncak air limpasan perkotaan.
Memanen air hujan juga merupakan upaya bijak dalam mengelola kebutuhan air (water demand management). Secara tipikal, otoritas penyedia air di banyak kota telah membuat estimasi kebutuhan air dan membangun infrastruktur jaringan perpipaan berdasarkan asumsi pengembangan sumber daya air dan strategi untuk memperluas area pelayanannya. Biaya pengembangan tersebut biasanya direcovery melalui tarif air yang dibayarkan konsumen, dan pada saat terdapat sumber daya air yang melimpah, konservasi sumber daya air cenderung tidak dianjurkan. Hal ini cenderung menciptakan konflik ketika kekeringan terjadi,
akibat kurangnya kebijakan dan program terkait konservasi air. Banyak contoh menunjukan bahwa kurangnya promosi upaya-upaya konservasi air dan memanen air hujan adalah karena kebutuhan untuk membiayai pembangunan infrastuktur perpipaan melalui penjualan air. Proyeksi kebutuhan air yang berlebihan membawa kepada pembangunan sumber daya air yang berlebihan pula, dimana pada akhirnya mendorong masyarakat untuk boros air. Keberlanjutan pasokan air perkotaan mensyaratkan suatu perubahan dengan cara memasok air perkotaan dengan mengontrol dan menekan kebutuhan (water demand management). Memperkenalkan sisi water demand management mendorong masyarakat perkotaan untuk mengadopsi pendekatan konservasi air, termasuk penggunaan sumber daya air yang ada dengan bebas melalui penerapan rainwater harvesting pada tingkat lokal.
Kualitas air merupakan aspek pentimg yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah air hujan yang dipanen akan dikonsumsi sebagai air minum. Secara umum dipercaya bahwa air hujan merupakan sumber air yang aman dan handal yang dapat digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Ini mungkin dapat diterapkan pada area-area yang tidak terpolusi. Sebagai contoh, area pedesaan yang tidak terdampak aktifitas-aktifitas yang memiliki potensi mengeluarkan polusi. Silva et al. (2015) menyarankan bahwa diperlukan evaluasi yang baik termasuk memastikan kualitas air hujan sebelum dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karenanya, untuk menjamin kualitas air, sistem pengumpulan harus dibangun dan dikelola dengan benar dan air hujan tersebut harus diolah dengan baik sesuai kualitas yang dipersyaratkan. Walaupun secara alami air hujan terbebas dari materi-materi yang berbahaya, namun demikian, pada saat air hujan jatuh dan mendapatkan kontak dengan atap rumah, air hujan tersebut mungkin membawa banyak jenis bakteri, jamur, alga, protozoa dan kontaminan lainnya ke tangki penyimpanan. Oleh karenanya banyak studi merekomendasikan untuk mengolah air hujan dengan benar sebelum digunakan untuk keperluan rumah tangga (misal untuk meminum, memasak, dan flushing toilet). Pengolahan yang disarankan dapat berupa pengolahan dengan filtrasi dan disenfektan untuk membunuh mikrobiologi dan bakteri pathogen yang membahayakan kesehatan.
Kesimpulan
Memanen dan mendaur air hujan merupakan praktek yang secara luas digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penghantaran air hujan. Di sebagian besar tempat, memanen air hujan secara khusus mengacu hanya untuk air hujan yang berasal dari atap rumah sebelum air hujan tersebut menyentuh tanah. Jika tidak dipanen secara langsung dari atap rumah, air hujan tersebut menjadi bagian stormwater. Jika hanya satu dua rumah tangga menerapkannya mungkin terlihat tidak signifikan. Tapi bayangkan, apabila jutaan rumah tangga di tempat kita memanen air hujan secara bersamaan, tentunya akan memberikan dampak positif sangat luas secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Memanen air hujan memberikan banyak manfaat kepada pemenuhan kebutuhan air, menurunkan beban banjir perkotaan, dan membantu konservasi air sehingga suatu kota akan lebih memiliki daya ‘resilience’ terhadap bencana kekeringan. Memanen air hujan juga merupakan satu upaya nyata pemanfaatan sumber air alternatif dalam meningkatkan pasokan air yang lebih baik melalui prinsip prinsip desentralisasi pelayanan.
* Arief Dhany Sutadian, ST, M.Eng, Ph.D: Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.
**Eka Jatnika Sundana, ST, M.Sc Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.
***Diana Pramanik, ST, MT
LANGKAH BERLIKU PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU WASTE TO ENERGY DI PROVINSI JAWA BARAT Nurashila Dhiyani, ST* Dr. Helmi Gunawan, ST, MT, Ph.D**
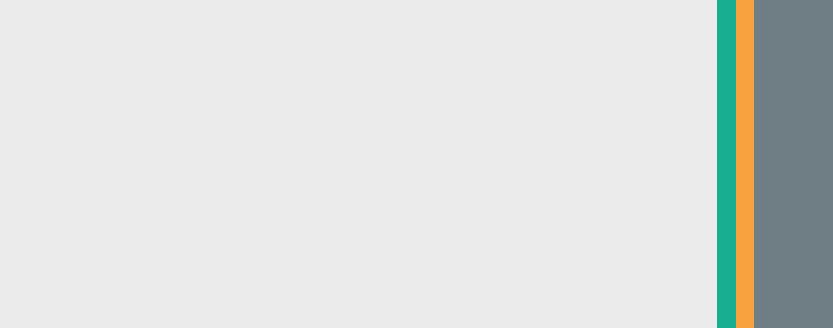
Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki lebih dari 49,5 juta penduduk. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah ini hampir sama dengan penduduk di Korea Selatan. Sebagian besar penduduk yang berada di Jawa Barat menempati wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Sama halnya dengan provinsi lain, Jawa Barat harus menghadapi urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penduduk yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Pengelolaan persampahan menjadi salah satu permasalahan yang kerap muncul di Jawa Barat. Kondisi serupa dialami pula oleh provinsi lain. Masalah sampah akan tetap menjadi persoalan yang harus diselesaikan di kemudian hari. Paradigma pengelolaan sampah “kumpulangkut-buang” harus diubah untuk mengurangi beban pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat menyelesaikan masalah sampah adalah Waste to Energy (WTE), di mana potensi sumber energi yang masih dimiliki

sampah dimaksimalkan dengan teknologi yang tersedia, sehingga sampah yang harus ditimbun di TPA dapat direduksi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut pengelolaan sampah regional. Pengelolaan sampah regional setidaknya harus dikembangkan di tiga regional. Dalam hal WTE, Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan dan mengembangkan dua wilayah di Metropolitan Bandung yang mencakup enam kabupaten/kota (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut) dan Metropolitan Bogor yang mencakup tiga kabupaten/kota (Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok).
Metropolitan Bandung direncanakan akan dilayani oleh TPPAS Legok Nangka dan akan
dibangun sebagai WTE untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan Metropolitan Bogor direncanakan akan dilayani oleh TPPAS Lulut Nambo dan akan dikembangkan sebagai Refusedderived fuel (RDF). Kapasitas operasional TPPAS Legok Nangka yang direncanakan sekitar 1.8502.000 ton/hari dan kapasitas dalam TPPAS Lulut Nambo sekitar 1.500 ton/hari. Proyek-proyek ini direncanakan akan mengurangi 18,8% total sampah yang dihasilkan di Provinsi Jawa Barat.
Strategi pengelolaan persampahan di Jawa Barat merujuk kepada kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) untuk mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani sampah sebesar 70% pada tahun 2025 yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali, sedangkan Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. WTE termasuk ke dalam bagian dari penanganan sampah pada tahap pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pendekatan end-of-pipe, tetapi juga strategi penanganan sampah di sumbernya dalam skala rumah tangga.
Hingga saat ini, pengelolaan persampahan di sumber sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar sampah dari sumber masih dalam kondisi tercampur. Kondisi ini akan mengganggu proses WTE karena material yang tidak diinginkan dapat menimbulkan masalah teknis operasional WTE. Selanjutnya, sampah dari sumber akan dikumpulkan menuju TPS. Pengumpulan sampah dari sumber umumnya dikelola oleh pihak Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat. Sistem keuangan berupa pembayaran retribusi melalui RW hanya akan mampu membiayai penanganan sampah dari sumber (rumah tangga) hingga TPS. Kondisi ini akan membebani pembiayaan oleh pemerintah jika sampah akan diolah pada WTE.
Sebagai ilustrasi, pada proyek TPPAS Legok Nangka direncanakan akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menangani keterbatasan anggaran pemerintah yang tersedia dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. KPBU melibatkan peran pihak swasta untuk mengadakan sarana layanan publik. Pada penerapannya, skema KPBU seringkali menemui hambatan seperti risiko yang tinggi dan ketidaklayakan proyek secara finansial. Berbagai alternatif telah disuarakan oleh pemerintah pusat sebagai langkah pencegahan untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi. Pemerintah dapat memberikan dukungan dana berupa Viability Gap Fund (VGF) guna memenuhi kelayakan finansial. Namun, langkah ini masih berada jauh di depan dalam menyelesaikan proyek ini.
Di samping persoalan anggaran, seringkali upaya pengurangan dan penanganan sampah hanya terpusat di wilayah perkotaan. Mayoritas masalah persampahan di wilayah pedesaan belum ditangani dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. Padahal, saat ini sampah menjadi masalah bagi segala lapisan masyarakat di desa maupun kota walaupun dengan skala dan jenis permasalahan yang berbeda. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan sampah, tata kelola sampah yang kurang baik, serta rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan terjadinya permasalahan persampahan di wilayah pedesaan menjadi lebih rumit.
Mengkaji kondisi ini, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus menilai kembali strategi dalam menangani sampah dari sumbernya. Penerapan strategi pengurangan dan pengelolaan sampah disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tentunya terdapat sisi terang dalam pengembangan pengelolaan sampah pada tahap pengurangan di Jawa Barat. Setelah peraturan presiden tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diberlakukan, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi berusaha membuat skenario dalam mengurangi sampah di sumber dan TPS.
Beberapa upaya pengurangan sampah di sumber telah dilakukan pada skala kabupaten/kota. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengembangkan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan menerbitkan Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengelolaan Sampah melalui Pembuatan Gebyar Lubang Cerdas Organik (LCO)/Lubang Resapan Biopori (LRB), di mana satu rumah diwajibkan membuat minimal dua LCO. Sebesar 45% sampai 60% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat berupa sampah organik, sehingga langkah ini menjadi salah satu opsi dalam pengurangan sampah di sumber.
Upaya pengurangan sampah pada proses antara pun sedang dioptimalkan. Proses antara yang di masa lalu berfungsi sebagai pengumpulan sampah dari rumah tangga, saat ini coba dikembangkan untuk menangani dan mengurangi sampah melalui teknologi yang tepat. Terdapat tiga fasilitas yang berperan dalam pengurangan sampah di proses antara, yaitu Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Bank Sampah. Ketiga fasilitas ini memiliki fungsi untuk mengurangi sampah melalui pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Dari 27 kabupaten/kota, terdapat 139 TPS 3R dan 62 bank

sampah yang tersedia di Jawa Barat. Jumlah fasilitas yang cukup banyak dapat meningkatkan peluang pengurangan sampah. Namun, hal tersebut harus diikuti dengan penguatan kelembagaan agar fasilitas dapat berjalan secara terus-menerus.
Singkatnya, pengelolaan sampah di Jawa Barat harus mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam menangani dan mengurangi sampah. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan menunjang Indonesia untuk mencapai pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
* Nurashila Dhiyani, ST: Tenaga Teknis di Seksi Pengendalian Sampah, B3 dan Limbah B3 DLH Provinsi Jawa Barat
** Dr. Helmi Gunawan, ST, MT, Ph.D: Kepala Seksi Pengendalian Sampah, B3 dan Limbah B3 DLH Provinsi Jawa Barat
Sampurasun #WargiJabar Tahukah kamu Bank sampah itu apa? Bank sampah adalah suatu system pengelolaan sampah kering secara kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul/lapak) sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
Selain memberikan keuntungan ekonomi kepada nasabahnya, Bank Sampah juga dapat membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan memilah sampah.
Secara nasional jumlah bank sampah seperti terdata oleh Kementerian LHK mencapai 7.700 unit. Dari jumlah itu sekitar 1.700 unit berada di Jawa Barat. Bank sampah ini adalah salah satu alternatif untuk memecahkan masalah sampah dan ikut berpartisipasi melestarikan lingkungan. Pada akhirnya bank ini akan berdampak baik untuk bumi ini. Kira-kira wargi sudah pernah belum nih menabung sampah di bank sampah??




