
















Kerabat Mahasiswa Antropologi ( KRAMA )
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
Penanggung Jawab
Aliffiati, S. S., M. Si ( Koordinator Mahasiswa Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana )
Gede Budarsa, S.Sos., M.Si
(Dosen Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya)
Penasehat / Pendamping
Dr. Nanang Sutrisno, S.Ag, M.Si. ( Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya)
Gede Budarsa, S.Sos., M.Si (Dosen Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya)
Pemimpin Redaksi
Ni Putu Nadia Amelia Sari (2201571025)
Moralize Tandri Wulan (2201571003)
Editor
Imam Zamahsari Abbas (2101571027)
I Gede Angga Sastra Pratama (2101571035)
Aina Kamalati (2201571001)
I Nyoman Gde Oka Divira (2201571008)
Maria Paskalia Apriani Tunti (2201571017)
Ridwan Dwi Santoso (2201571036)
A.A. Gede Putra Wibawanta Dharma (2201571046)
Jessicha Nathasya Briliant Br Ginting (2201571029)
Putu Nita Kharisma Yanti (2101571022)
Ida Ayu Gede Martha Parlika (2201571018)
Ni Komang Gita Putri Miartini (2201571011)
I Gede Putu Satya Iswara (Submission)
I Putu Sawitra Danda Prasetia (Submission)
Putu Eka Cempaka Putri (Submission)
Cetakan dan Tahun
Cetakan ketiga-2023


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya majalah The People’s yang ketiga kalinya dengan tema “Lensa Dewata: Menelisik Jejak
Peradaban Bali Aga” Tema yang terkesan klasik sangat lokalitas mencirikan tradisi kajian etnografi yang merupakan “jantung dari ilmu Antropologi”. Tulisan tentang
Bali Aga bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat pemerhati budaya Bali namun
karena penulisnya adalah para “generasi milenial” maka tentunya cara pemaparannya “lebih bergaya kekinian” dan dalam “perspektif anak muda” yang sedang berproses mencari jawaban atas rasa ingin tahu Sebuah keberanian dari

Tim Redaksi Majalah The People’s dan para penulis artikel untuk memilih tema tersebut
Artikel dalam majalah ini hampir sebagian besar merupakan hasil penelitian
mahasiswa Prodi Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana melalui kegiatan penelitian yang bertajuk PENSIK akronim dari Penelitian Asik
Terbitnya majalah ini membuktikan bahwa semangat menulis di kalangan generasi muda khususnya para mahasiswa Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Udayana “masih ada” dan tentunya harus terus diasah dan dikembangkan sehingga menepis anggapan bahwa “mahasiswa antropologi senengnya penelitian tetapi malas mempublikasi hasil penelitian lewat tulisan”. Melalui kesempatan ini, selaku pribadi dan sebagai Koordinator Program Studi
Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengucapkan
selamat atas terbitnya majalah ini. Penerbitan majalah “The People” ini semoga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia keilmuan, khususnya memotivasi “semangat menulis” di kalangan para mahasiswa.
Terimakasih tak terhingga untuk Tim Redaksi, para penulis, para informan dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya majalah ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas terbitan selanjutnya Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberikan kebijaksanaan serta kekuatan kepada kita dalam berkarya mengembangkan ilmu pengetahuan
Denpasar, 25 Agustus 2023
Koordinator Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
(Aliffiati, S.S., M.Si) NIP. 19691022 1999802 1 011
Salam Hangat untuk Para Pembaca Setia Majalah The People’s,
Selamat datang di edisi istimewa majalah kami yang pada tahun ini mengangkat tema “Lensa Dewata: Menelisik Jejak Peradaban Bali Aga”. Kami dari tim redaksi dengan senang hati mengajak anda untuk menjelajahi warisan turuntemurun yang begitu unik dan memesona dari Pulau Dewata. Dari tradisi adat yang mendalam hingga tradisi kesenian khas yang membawa kita pada sebuah perjalanan waktu yang mengagumkan mengenai akar-akar asli pulau ini yang tertanam kuat dalam keberagaman budaya.
Bali Aga dalam hal ini merujuk pada masyarakat asli Bali yang ada sebelum adanya gelombang migrasi dari luar pulau terutama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Masyarakat Bali Aga umumnya mendiami wilayah pegunungan dan menjalani kehidupan agraris yang erat kaitannya dengan alam sekitar. Keunikan utama Bali Aga terletak pada tekad mereka untuk mempertahankan tradisi leluhur dan memegang teguh norma budaya mereka.

Keunikan Bali Aga tidak hanya menjadi penyumbang warna dalam mozaik budaya Bali, tetapi juga menjadi pengingat penting akan sejarah dan nilai-nilai asli pulau ini. Dalam dunia yang terus berubah, mereka adalah pilar yang kokoh dalam memelihara identitas budaya yang autentik. Dengan adanya upaya pelestarian dan apresiasi, kita bisa lebih memahami dan menghargai kekayaan budaya Bali yang luar biasa. Melalui edisi kali ini kami berharap sekiranya mampu membawa pembaca pada suatu perjalanan waktu mengenai kisah-kisah, tradisi, dan nilai-nilai yang membentuk Bali Aga itu sendiri. Besar harapan kami semoga dengan majalah ini kita bisa menghidupkan kembali sejarah dan makna budaya dalam konteks yang lebih luas.

Tidak lupa apresiasi besar kami tujukan kepada tim redaksi dan penulis atas usaha terbaik yang diberikan dalam menyajikan konten-konten berkualitas pada tiap halaman majalah ini. Setiap artikel adalah hasil dari dedikasi dan upaya untuk menghadirkan informasi yang menarik dan edukatif.
Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan turut menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami berharap pembaca menikmati edisi istimewa ini sebanyak kami menikmati tiap proses penyusunannya.
Oleh: Oleh: Oleh:



Kelabu yang hampir-hampir menutup jarak pandang, udara lembut bergerak menepis wajah merona mereka yang lalu-lalang berkendara menuju ladang, serta anjing-anjing seputih salju dengan ekor melengkung bak bulan sabit menghampiri menatap kita dengan senang. Desa Bayung Gede terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Ia merupakan salah satu desa tua di Bali yang secara sederhana masih menjalankan segala warisan budaya leluhur hinggasaatini.
Desa Bayung Gede sulit untuk tidak dideskripsikan dengan mengedepankan aspek estetisnya. Tata letak wilayah utama desa menggunakan konsep Tri Mandala. Utama Mandala dimulai ketika mulai memasuki jalan kecil menuju desa, kita akan disambut oleh pura di kanan dan kiri jalan. Pura Bale Agung, Pura Puseh, Bale Kulkul, Wantilan Desa, dan beberapa Pura Dadia terletak berdekatan di hulu desa. Madya Mandala dapat dilihat melalui jalan setapakyangmembentangditengahdesa,rumahrumahpendudukmenghiasidikeduasisinya. Beberapa kesan tradisional terlihat dari beberapa atap bale yang terbuat dari potongan-potongan bambu dan dinding berlapis terbuat dari anyaman bambu. Jalan setapak membentang lurus itu akan membawa kita sampai di hulu desa hingga sampai di bagian Nista Mandala, terdapat sebuah area yang dibatasi tembok bata menyambut di sebelah kanan, sebuah papan putih berdiri bertuliskan ‘Setra Ari-Ari’. Pohon besar berkumpul di area itu, membuat udara di sana menjadi lebih dingin. Beberapa tempurung kelapa yang menggantung mengelompok di pohon-pohon akan memunculkan tanda tanya bagisiapasajayangmelihatnya.
Pemberian nama Setra Ari-Ari digunakan ketika tradisi ini menjadi salah satu daya tarik wisata Desa Bayung Gede. Masyarakat beranggapan
bahwa penggunaan nama Setra Ari-Ari kurang tepat karena wilayah itu bukanlah setra, kalau kata Jero Bendesa sebut saja dengan pengutangan kau. Pengutangan kau merupakan salah satu warisan budaya leluhur Desa Bayung
Gede. Biasanya masyarakat Hindu di Bali memperlakukan ari-ari dengan cara dikubur di pekarangan rumah mereka. Agaknya berlainan dengan budaya masyarakat Desa Bayung Gede yang menggantungkan ari-ari anak mereka di ranting-ranting pohon bukak yang menyelubungiareaseluas60are.
Rumah para Jero Kubayan–saking banyaknya larangan–terkadangterlihatsepertilebihsuci daripada kehadiran pura di Desa Bayung
Gede Seorang ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui dilarang masuk ke
pekarangan rumah Jero Kubayan, tapi mereka bisa masuk ke pura. Jika ada orang menyusui, kotor kain, dan hamil yang memasuki
pekarangan rumah Jero Kubayan, maka dia

akan dikenakan hukum adat berupa melaksanakan upacara pembersihan dengan memberikansayut.


Berbagaiaturandanlaranganadattersebut memiliki landasan yang kuat, juga termasuk mengapa tidak mengubur ari-ari di pekarangan rumah sehingga para leluhur membuatkan area
khusus untuk menggantung ari-ari yang secara turuntemurundisebutdenganpengutangan kau
Selainitu,aturandanlaranganadattersebutjuga berkaitan dengan rumah adat masyarakat Desa BayungGedeyangsaratakanmakna.
Masyarakat Desa Bayung Gede memiliki sebuah siklus upacara yang dilaksanakan berdasarkan perhitungan sasih dalam kalender
Bali.Diantaraupacaratersebut,terdapatupacara yang bernama Upacara Ulu Apad. Pada saat
pelaksanaan Upacara Ulu Apad, sasih kaenem dari 163 orang yang terdaftar di jero kraman, setiap tahunnya ada 3 orang yang melaksanakan
rangkaian Upacara Ulu Apad dengan memotong


sapi atau banteng. Upacara Ulu Apad terbagi
menjadi 6 rangkaian yakni nilem, mesayut, mapas, mubung, ngantah, nuada. Dari prosesi inilah maka Jero Kubayan bisa nyungsung Ratu Pingit dan Ratu Bungsil yang dilaksanakan di umah paon karena pekarangan mereka itu sudah disucikan. Rumah Jero Kubayan sangat pingit, tidakdiperbolehkanorangmenyusui,orangkotor kain, dan orang hamil masuk ke pekarangan. Maka jika seseorang di Bayung Gede sudah menjadi paduluan, maka di dalam rumahnya tidakdiperkenankantinggallebihdarisatuKK.
Ketika Jero Kubayan meninggal dunia atau anaknya sudah menikah, maka nama anak lakilaki tersebut akan masuk ke daftar jero kraman di bagian akhir. Sedangkan yang menggantikan Jero Kubayan adalah dia yang namanya berada di bawah Jero Kubayan sebelumnya. Demikian perputaran bagaimana orang-orang bisa menjadipaduluandiDesaBayungGede.
Salah satu larangan yang diterapkan oleh seluruh masyarakat Desa Bayung Gede adalah larangan mengubur ari-ari dipekarangan rumah mereka karena dianggap akan mengotori pekarangan rumah selamanya sebagai akibatnya segala bentuk upacara yang melibatkan paduluan tidak bisa dilaksanakan di dalam rumah tersebut. Maka dari itu masyarakat menggantungari-aridiareapengutangankau
Lalu barangkali kita bertanya mengapa masyarakat menggantung ari-ari daripada mengubur–walau sudah di luar pekarangan rumah?
Perlu diketahui bahwa hutan-hutan yang ada di sekitar wilayah Desa Bayung Gede merupakan pura. Pura tanpa pelinggih itu disebutdenganpurayangmertiwi Sebagaimana masyarakat bersikap sakral terhadap pura, demikian masyarakat bersikap sakral juga kepada pura mertiwi yang dalam hitungan kalender Bali setiap sasih ketiga memberikan persembahan melalui pelaksanaan upacara mosa. Demikian terdapat juga hukuman adat bagi mereka yang melakukan pelanggaran seperti merusak lingkungan hutan dan menebang pohon sembarangan. Sama halnya dengan area pengutangan kau yang diperlakukan khusus oleh masyarakat desa. Tidak boleh sembarang orang bahkan memotong ranting kecil pun secara sembarangan tanpa izin Jero Kubayan. Jika pelanggaran-pelanggaran terjadi, maka orang yang melanggar akan dikenakan hukuman berupa menyerahkan 200 kepeng bolong kuna–yang jika dirupiahkan mencapai sekian juta rupiah–kepadadesa.
Ketika bayi lahir berbarengan denganplasenta,plasentaitudibersihkan terlebih dahulu. Pada umumnya yang melakukan pembersihan adalah ayah dari si bayi atau mertuanya, kalau tidak memungkinkan, ayah dari si bayi sendiri pun dapat melakukannya. Sebelumnya sudah disiapkan tempurung kepala yang agak besar atau menyesuaikan dengan ukuran plasenta lalu dimasukkan ke dalamtempurungkelapa.
Diatasplasentaditaburiabusisa-sisaarang masak di umah paon, lalu ditaburi anget-anget seperti merica, ketumbar, dan lainnya Setelah itu ditirisi dengan tengeh, lalu diletakkan pisau dari bambu, sepit dari bambu. Pisau merupakan alat pemotong tali pusar atau plasenta sedangkan sepit adalah alat untuk menjepit plasenta itu sendiri. Setelah semua itu ada di dalam, maka akan ditutup dengan pengikat yang dinamakan talisalang tabuyangberbahan dasar bambu yang masih muda. Setiap belahan diolesi denganpamorkemudiandibentuktapakdara.

Pada umumnya proses penggantungan ari-ari dilakukan di siang hari, atau di kala terang. Jika bayi itu lahir di malam hari, maka prosesinya akan dilakukan besok paginya. Ayah dari si bayi akan memakai pakaian adat, berjalan ke pengutangan kau dan ketika sampai melihat di mana tempat yang bagus dan terdapat banyak ari-ari di pohon itu, karena kepercayaan jika menggantung ari-ari sendiri maka si anak tidak akan bisa bergaul dengan orang lain. Setelah mendapatkan tempat yang tepat, si ayah meletakkan ari-ari dengan tangan kanan, semua kegiatannya dilakukan dengan tangan kanan karena kepercayaan apabila menggunakan tangankirimakaanaknyaakanjadikidal.
Masyarakat Desa Bayung Gede bersikap sangat hati-hati saat berhadapan dengan suatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan adat tertinggi ada pada Jero Kubayan. Sehingga hal-hal yang dilakukan tanpa izin Jero Kubayan–utamanya yang berkaitan dengan keberadaan lingkungan dan alam sekitar–akan dikenakan hukuman adat. Demikian masyarakat Desa Bayung Gede membangun kepercayaan mereka sehingga mampu mempertahankan berbagai warisan dari leluhurmereka.




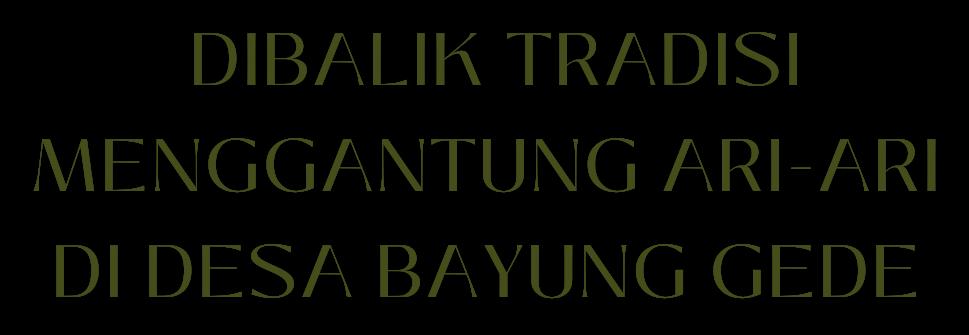
Desa Bayung Gede merupakan salah satu desa kuno yang masih memegang erat kebudayaan Bali

Aga atau Bali Mula yang terletak di Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa ini memiliki berbagai tradisi unik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi menggantung ari-ari bayi yang baru lahir pada pohon kayu bukak
(Cerbera manghas) atau dikenal juga dengan nama pohon bintaro Hal tersebut terbilang sangat menarik karena pada umumnya orang Bali akan menanam ari-ari bayi yang baru lahir di pekarangan rumah.
Menurut I Wayan Tabeng selaku selaku Jero
Kubayan Mucuk pada periode sebelumnya, jika ariari bayi yang baru lahir ditanam di pekarangan rumah bisa menimbulkan leteh (kotor) karena dianggap “masih berdarah” dan akan berdampak pada pekarangan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat desa Bayung Gede diharuskan untuk menggantungkan ari-ari bayi yang baru lahir pada pohon kayu Bukak.
Tidak ada yang tahu persiskapan pastinya
tradisi menggantung ari-ari ini dimulai Namun
konon katanya, tradisi ini telah ada sejak ribuan
tahun yang lalu Masyarakat Bali Mula Bayung
Gede memiliki kepercayaan atau mitos asal usul

masyarakat yang menyebutkan bahwa leluhur
mereka berasal dari tued kayu (pangkal kayu) yang dihidupkan dengan tirta kamandalu oleh bojog putih (kera putih) putra Betara Bayu (de-
-wa angin) Oleh karena asal mereka dari kayu, maka ketika bayi baru lahir dari rahim ibunya harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu kepada kayu sang sumber kehidupan (Putri, D.A.E. 2015). Kepercayaan ini kemudian diwujudkan dalam tradisi penggantungan ari-ari atau saudara si bayi yang disebut dengan Catur Sanak (Empat saudara) di Setra ari-ari (kuburan ari-ari) dengan menggantungkannya di pohon Bukak (Cerbera manghas). Begitulah kisah yang kian santer dari mulut ke mulut secara turun temurun yang beredar di masyarakat Bayung Gede. Meski tidak ada sumber tertulis yang menjelaskan secara rinci mengenai sejarah tersebut, akan tetapi masyarakat tetap taat menjalani tradisi menggantung ari-ari secara turun temurun hingga kini. Tradisi menggantung ari-ari bayi ini dilakukan di sebuah kuburan ari-ari atau yang lebih dikenal dengan Setra Ari-Ari Tempat ini berada di sebelah selatan desa, berupa hutan kecil dengan luas 60 are yang ditumbuhi berbagai jenis pohon dan didominasi oleh pohon bukak (Cerbera manghas). Sejatinya tempat ini merupakan area khusus untuk menguburkan ari-ari bayi Namun warga setempat memilih untuk menggantung ari-ari pada ranting pohon Bukak yang sudah diwadahi kau (batok kelapa) di tempat tersebut. Kebiasaan ini berangkat dari kepercayaan masyarakat terkait mitos asal-usul mereka yakni dari kayu. Semua yang terlahir dari kayu, akan kembali kepada kayu.
Tempat penggantungan ari-ari pun tidak bisa dilakukan pada sembarang pohon, melainkan harus di pohon kayu bukak Masyarakat setempat percaya bahwa getah yang terdapat pada pohon kayu Bukak akan menyerap darah dari ari-ari dan membantunya cepat mengering, bahkan tidak akan menimbulkan bau apapun pada saat tempurung jatuh ke tanah dalam kurun
waktu 6 sampai 12 bulan Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya sebuah cerita bahwa
dahulu ada seseorang yang karena ketidaktahuannya malah menggantungkan ariari pada pohon kayu lain, alhasil ari-ari yang gantungkan tidak kunjung mengering dan menimbulkan bau menyengat
Proses pelaksanaan tradisi menggantung ari-ari juga terbilang cukup kompleks. Pertama, ari-ari harus dicuci sebersih mungkin menggunakan air
tawar bersih. Lalu, disiapkan tempurung kelapa

yang sudah dipangkas menjadi dua bagian dalam kondisi bersih dari air dan serabut kelapa sebagai wadah ari-ari Pada bagian atas tempurung, ditulisi Ongkara (aksara suci Hindu). Belum cukup, masyarakat juga sering memasukkan benda-benda yang bervariasi ke dalam tempurung ari-ari. Ada yang memasukkan robekan tikar, pensil, robekan kertas, mawar, merica/ketumbar, kapur sirih, kunyit, jeruk nipis, hingga duri terung/terong.

Fungsinya agar si bayi tetap harum, hangat, terjaga, dengan harapan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas kelak. Terakhir, tempurung kelapa akan ditutup menggunakan sisa pangkasan tadi yang selanjutnya diikat menggunakan tali bambu dengan simpul salang tabu (Tali Bambu). Kemudian dioleskan kapur sirih pada ruas-ruas batok kelapanya agar dua belah tempurung tetap melekat dan rapat satu sama lain
Peran dari ayah si bayi sangat diperlukan pada saat penggantungan ari-ari bayi pada pohon Kayu Bukak Namun apabila sang ayah berhalangan, maka boleh digantikan oleh anggota keluarga yang lain dan harus seorang pria Hal tersebut dikarenakan konon pada zaman dulu kuburan tersebut adalah hutan yang luas dan bisa jadi ada binatang buas yang muncul. Selain itu, mereka pun harus menggunakan pakaian adat dan membekali diri dengan sabit Saat berangkat dari rumah tangan kanan memegang sabit yang akan dipergunakan untuk menebas ranting Pohon Bukak dan tangan yang kiri harus memegang tempurung. Kemudian ketika sudah siap digantung maka berganti tangan kanan yang dipergunakan untuk menggantungkannya dengan harapan lahir hal-hal positif. Peran laki-laki dalam hal ini bapak si bayi cukup sentral mengingat dalam prosesinya menggunakan pekerjaan fisik sehingga kelompok laki-lakilah yang dianggap bisa melakukannya. Sementara sang ibu masih dalam kondisi lemah paska melahirkan sehingga tidak mengabil peran yang begitu penting.
Bagi keluarga yang baru saja menggantung ariari maka wajib untuk menandai rumahnya dengan daun pakis agar warga tahu bahwa rumah di tersebut ada bayi yang baru lahir dan pantang didatangi oleh orang suci maupun tokoh desa karena terbilang masih leteh (kotor ) Pemasangan daun ini sebagai tanda kepada semua warga terutama kelompok orang suci dan tokoh desa ka-
-rena adanya pantangan tersebut Setelah 42 hari (abulan pitung dina) pasca melahirkan, barulah
dilaksanakan upacara penyucian sederhana di pekarangan rumah bagi ibu yang pertama kali melahirkan. Sementara untuk ibu yang sudah
melahirkan lebih dari dua kali bisa melakukan
upacara tersebut setelah 12 hari pasca melahirkan
Setelah prosesi ini terlewati aktivitas pun kembali
berjalan dengan normal
Dalam pelaksanaan tradisi ini, terdapat beberapa larangan yang berlaku. Pertama, larangan
memakamkan ari-ari saat malam hari, sehingga
dianjurkan untuk melakukan pemakaman sebelum
matahari terbit saat ari-ari masih dalam kondisi
segar Pantangan ini berlaku mengingat lokasi
kuburan ari-ari cukup jauh dari pemukiman serta
kondisinya berupa semak belukar sehingga cukup
membahayakan jika dilakukan pada malam hari.
minimnya enerangan juga menjadi alasan kenapa
penggantungan ari-ari dilakukan menjelang

matahari terbit. Kedua, pantang untuk melakukan
interaksi dengan siapa pun ketika hendak
membawa ari-ari ke kuburan baik itu mengobrol,
menoleh, maupun tertawa Hal ini diyakini oleh
masyarakat setempat dapat membuat pertumbuhan
bayi menjadi tidak baik dan kelak tumbuh menjadi
pribadi yang tidak fokus pada tujuan serta
menimbulkan hal buruk lainnya. Ketiga, pantang untuk menebang pohon di lingkungan kuburan untuk kepentingan pribadi Sebagai ganjaran, siapa
saja yang menebang harus menerima sanksi adat dan harus menanam pohon berjenis sama di areal pekuburan. Hal tersebut dilakukan karena pohonpohon yang ada di area tersebut diyakini cukup
keramat dan harus dijaga. Inilah bentuk
pengejawantahan keyakinan masyarakat Bayung
Leluhur mereka terlahir dari sebuah kayu, maka pohon adalah sumber kehidupan mereka yang harus dijaga dan dirawat. Sebuah kearifan lokal yang penuh dengan nilai ekologis untuk masa depan anak cucu mereka.
Terdapat beberapa makna yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi ini. Makna simbolik yang terkandung di dalam setra ari-ari berkaitan dengan konsep Bhuana Agung- Bhuana Alit dan Panca Maha Bhuta Makna penggantungan ari-ari di setra ari-ari juga berkaitan dengan konsep Catur Sanak atau empat saudara yang terdiri dari yeh nyom (air ketuban), lamad (tali pusar), getih (darah) dan ari-ari (plasenta). Tradisi ini bertujuan agar si bayi yang baru lahir senantiasa dilindungi oleh keempat saudaranya dari dunia niskala. Setra ariari secara denotatif merupakan tempat peleburan unsur Bhuana Alit dan Bhuana Agung Secara konotatif dianggap sebagai rumah niskala dari Catur Sanak. Buah bukak dianalogikan sebagai alat kelamin perempuan dan merupakan simbol ibu dari Catur Sanak. Batok kelapa dianalogikan sebagai rahim ibu yang senantiasa melindungi keempat saudara di bayi di alam niskala Ketika si bayi lahir dari rahim pohon bukak, hendaklah saudarasaudaranya dikembalikan kepada rahim niskala mereka.
DaftarPustaka
Putri, DAE (2015) "Kearifan Ekologi Masyarakat Bayung Gede dalam Pelestarian Hutan Setra Ariari di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli" Skripsi Program Studi (S1) AntropologiFakultasIlmuBudayaUniversitasUdayana
Rohmat, I (2018, 28 September) "Tradisi Unik Menggantung Ari-ari Bayi" BaleBengong https://balebengongid/tradisimenggantung-ari-ari-bayi/
Eka A (2022 11 Mei) "Menilik Uniknya 'Pohon Kuburan' Ari-Ari di Bayung Gede Kintamani" detikbali https://wwwdetikcom/bali/budaya/d-6071791/menilik-uniknya pohon-kuburan- ari-ari-dibayung-gede-kintamani
Utik (2018, 20 Juli) "Mengintip Kesakralan Kuburan Ari-Ari di Desa Bayunggede Kintamani" NusaBali https://wwwnusabalicom/berita/34306/mengintip-kesakralan kuburan-ari-ari-di- desabayunggede-kintamani
Gede dalam menyikapi alam



Sukawana merupakan Desa yang terletak di Kintamani Mmal (Perbukitan Kintamani). Secara Administrasi Negara berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Desa Sukawana memiliki kebudayaan yang unik. Kebudayaan unik ini sejak dahulu dilaksanakan turun temurun dari leluhur masyarakat Desa Sukawana, dan hingga kini masih bertahan. Berbagai desakan para elite politik dan penseragaman dari berbagai lembaga yang ingin menyamaratakan sistem pemerintahan yang ada di Desa Sukawana dengan Bali Majapahit Tetapi Masyarakat Desa Sukawana masih bertahan dan memegang teguh sistem yang telah dijalankan dari leluhurnya
Ulu Apad merupakan sistem pemerintahan adat di Desa Sukawana. Ulu berarti kepala, dan Apad berarti Tangga, jadi Ulu Apad secara harfiah berarti menuju ke puncak dalam posisi pengurus pemerintahan. Sistem pemerintahan ini terdiri dari 23 pengurus, yaitu : Kubayan Tuaan (Tengen), Kubayan Nyomanan (Kiwa), Bau Tengen (2), Bau Kiwa (2), Singgukan Tengen, Singgukan Kiwa, Penakehan Tengen (2), Penakehan Kiwa (2), Kasetdon, Pengelanan Tengen (3), Pengelanan Kiwa (3), Jejeneng tengen (2), Jejeng Kiwa (2). Pengurus dengan berjumlah 23 mengatur dan membuat keputusan yang berada di Desa Sukawana, sepertimempersiapkan Upacara yang akan datang, peraturan bagi Masyarakat, mewadahi peturunan atau uang dari Masyarakat Sukawana guna kebutuhan bersama, memberikan Denda karena telah melanggar, dan keputusan masalah yang terjadi di Desa meski demikian keputusan kembali lagi semua aspirasi dari pengurus atau musyawarah mufakat ini diputuskan oleh Jero Kubayan, antara “Iya” atau “Tidak”.

Hal yang menarik dalam sistem pemerintahan ulu apad ini adalah cara mengorganisir semua anggota terutama saat pengambilan keputusan penting Setiap pengurus memiliki argumen melalui berbagai pertimbangan. Setiap argumen yang di sampaikan memiliki hal yang terselubung bagi setiap individu. Ketika suatu argumen itu di kemukakan penyampaian secara emosial akan terlontar. Dalam penyampaian pendapat atau aspirasi Masyarakat diperbolehkan menitipkan kepada pengurus Ulu Apad.


ketika pengurus tidak dapat menghadiri rapat, diperkenankan menitipkan keris yang dimilikinya sebagai simbol kehadiran pengurus Berbagai aspek yang menyebabkan tidak kehadiran pengurus, seperti keluarga sakit Namun jarang sekali para pengurus tidak hadir pada rapat tersebut. Hal ini didasari rasa kepemilikan bersama demi profesionalitas dan rasa percaya masyarakat terhadap pengurus

Sistem pemerintahan Ulu Apad di Desa Sukawana ini memiliki ciri khas terkait waktu pelaksanaan sangkep atau rapat pada bulan Tilem, dan bulan Purnama. Rapat atau sangkepan, biasa disebut sangkepan Tilem, dan sangkepan purnama. Setiap sangkepan memiliki rentan waktu yang berbeda Kadangkala memakan waktu yang cukup lama, bisa juga memakan waktu yang relatif singkat.

Sumber Foto : Baliexpress jawapos com
Setiap sangkepan akan ada keputusan yang di sepakati bisa juga sangkepan yang dilaksanakan belum menghasilkan keputusan. Ketika hal itu terjadi pembahasan akan di jeda hingga waktu yang akan datang baik pada sangkepan purnama ataupun sangkepan tilem berikutnya. Keputusan ini biasanya tidak dapat hanya di selesaikan satu kali namun berkali kali hingga menukam titik terang.
Ketika sangkepan tilem atau sangkepan Purnama telah usai setiap pengurus memperoleh malang atau kawes yakni berupa nasi dan lauk yang diwadahi daun Daun berbentuk jantung, yang kemudian dibawa pulang dan disantap keluarga setiap pengurus.
Lensa Kearifan

Dalam siklus hidup manusia, kematian merupakan tahap paling akhir dari sebuah perjalanan panjang kehidupan Saat dimana jiwa meninggalkan raganya yang kemudian hanya meninggalkan wadah kosong tanpa adanya “atma”. Ibarat gawai tanpa jaringan, bisu, kaku, dan tak berperilaku. Selalu dan akan terus berulang, begitulah bagaimana makhluk hidup berjalan seiring dengan hukum alam Jasad tersebut kemudian akan diperlakukan sebagaimana adat maupun tradisi yang berlaku di tempat orang tersebut meninggal Entah dikubur, dibakar, ataupun diletakkan begitu saja di atas tanah seperti proses pemakaman di beberapa daerah khususnya di Pulau Bali Membahas mengenai bagaimana suatu proses pemakaman berlangsung mengikuti adat dan tradisi setempat, maka salah satu desa Bali Aga di Bali pun memiliki tradisi pemakaman yang tergolong unik. Desa Bayung Gede, begitulah nama desa yang terletak di dataran utara Pulau Bali ini Terletak pada ketinggian sekitar 800-900 mdpl membuat desa ini memiliki hawa sejuk yang mendukung berkembangnya sektor pertanian lahan kering dengan komoditi berupa jeruk, kopi, dan aneka jenis sayuran. Dalam hal tradisi, Desa Bayung Gede masih tetap menjaga warisan leluhur mereka dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pemakaman di Desa Bayung Gede yang memiliki perbedaan antara posisi pemakaman laki-laki dengan perempuan.
Adanya perbedaan posisi pemakaman tersebut menurut Bapak I Wayan Tabeng selaku Jero

Kubayan Mucuk pada periode sebelumnya memang sudah ada sejak dahulu dan masih bertahan hingga saat ini. Jenazah laki-laki akan diposisikan telungkup pada saat penguburan, sementara bagi perempuan akan diposisikan telentang Posisi tersebut disesuaikan dengan kehidupan jenazah semasih hidup. Posisi saat berhubungan seksual dijadikan pedoman dan tidak boleh diubah maupun ditukar posisinya Adapun perbedaan pemakaman ini diberlakukan kepada seluruh warga di Desa Bayung Gede termasuk pada orang yang berkasta.
Pada umumnya jenazah akan dibungkus dengan kain kafan sebelum dikebumikan, berbeda dengan di Desa Bayung Gede Jenazah akan dikuburkan (dikebumikan) tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh. Masyarakat Bayung Gede hanya menggunakan tiga lembar daun kayu bukak (Cerbera manghas) utuh dan tidak boleh ada robek sedikit pun untuk menutupi kemaluan jenazah. Hal ini berlaku bagi semua jenazah baik laki-laki maupun perempuan Jenazah dimakamkan dengan telanjang dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan bahwa pada saat dilahirkan manusia tidak mengenakan apapun untuk menutupi tubuhnya alias telanjang. Hal tersebut berlaku juga saat manusia meninggal maka harus dikuburkan layaknya sewaktu baru dilahirkan. Digunakannya daun bukak untuk menutup kemaluan jenazah dipercaya mampu menetralisir bau tidak sedap akibat cairan yang berasal dari tubuh jenazah dan mempercepat proses penguraian jasad dibandingkan penggunaan kain kafan. Dengan tidak menggunakan bahan-bahan buatan seperti kain kafan dan benda hasil karya lainnya, maka setra (kuburan) akan tetap bersih dan tidak kumuh akibat benda-benda tersebut
Meskipun terdapat perbedaan posisi tersebut, namun pada saat dimakamkan baik jenazah lakilaki maupun perempuan diperlakukan sama. Sebelum dibawa ke setra (kuburan) jenazah terlebih dahulu akan dimandikan di rumah duka dengan banten yang di dalamnya terdapat lis gede, pesucian dan banten ngiu Setelah proses pemandian selesai, jenazah kemudian dibawa ke setra oleh pihak keluarga maupun penduduk desa lainnya. Dalam prosesi pemakaman ini orang yang dianggap ‘suci’ oleh masyarakat setempat seperti perangkat desa, jero kubayan, dan orang dengan jabatan di desa tidak boleh ikut dikarenakan upacara kematian dianggap leteh (kotor). Oleh karena itu pihak yang terlibat selama upacara kematian hanyalah keluarga dan penduduk desa. Saat jenazah sudah sampai di setra, jenazah akan dimandikan kembali dengan menggunakan tirta (air suci) yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun banten yang diperlukan pada saat proses di setra berlangsung yaitu banten sagi. Banten sagi biasanya berisi olahan siap biing (ayam jantan berwarna merah), nasi, dan kue basah seperti bantal maupun klepon dan dipersembahkan atau ditujukan kepada arwah orang yang meninggal melalui prosesi yang disebut nanjen Dalam banten sagi, ayam yang digunakan memang harus ayam jantan berwarna merah karena berkaitan dengan kepercayaan setempat kepada Betara Dalem sehingga kebanyakan upacara kematian seperti Ngaben diharuskan menggunakan siap biing.
Dalam menentukan hari untuk menguburkan jenazah pun tidak boleh sembarangan dilakukan Terdapat beberapa hari-hari tertentu yang bagi penduduk Desa Bayung Gede pantang untuk melakukan prosesi pemakaman. Adapun hari yang dimaksud yaitu soma pasah (hari senin dengan tri wara pasah) dan dina sukra (hari jumat) Pantangan hari ini ditentukan sesuai dresta (baik buruknya hari) yang berlaku di masyarakat. Dalam kondisi tertentu, aturan ini bisa tidak berlaku terutama dalam kondisi mendesak sehingga prosesi pemakaman tetap dilaksanakan di hari yang dipantangkan tersebut. Jika misalkan terdapat warga yang meninggal, sementara di desa terdapat upacara adat, maka penguburan pada hari tersebut boleh dilakukan Selain itu bagi orang yang meninggal karena salah pati dan ulah pati (secara tidak wajar maupun bunuh diri) maka akan dikuburkan hari itu juga (hari dimana orang tersebut meninggal) tanpa menunggu hari lain. Prosesi dan banten yang digunakan pun sama seperti orang yang meninggal secara wajar
Upacara kematian di Desa Bayung
Gede tidak berhenti setelah jenazah
dikuburkan saja. Selama dua belas hari
setelah penguburan pihak keluarga secara
rutin akan memberikan sesajen berupa nasi
putih di tempat tidur mendiang. Setelah
dua belas hari barulah sesajen berhenti
dipersembahkan dan berakhir pula upacara
kematian untuk selanjutnya menunggu
upacara Ngaben yang biasanya
dilaksanakan setahun sekali pada sasih
desta (bulan kesebelas dalam kalender Bali)
maupun sada (bulan kedua belas dalam kalender Bali)

Selain posisi pemakaman, Desa Bayung Gede juga memiliki satu lagi keunikan mengenai tradisi kematian. Di desa ini setra dibedakan menurut bagaimana orang tersebut meninggal. Jika ada yang meninggal ulah pati atau salah pati, maka jenazah akan dimakamkan di setra tukad.
Orang yang meninggal secara wajar dan tidak berbenturan dengan adanya upacara adat maupun dewa yadnya akan dimakamkan di setra gede Selanjutnya, jika ada orang meninggal dan di desa sedang dilangsungkan upacara adat maka pemakaman akan dilakukan di setra Pludu (nama salah satu banjar di desa Bayung Gede) Bagi orang-orang yang terlibat dalam prosesi pemakaman tidak diperbolehkan untuk memasuki areal pura dalam rentang waktu sehari terhitung saat orang tersebut pulang dari pemakaman karena dianggap sebel (kotor). Setelah sehari orang tersebut akan melakukan pembersihan diri dari sebel (kotor) dengan cara mandi, keramas, dan mengganti pakaian yang digunakan selama mengikuti upacara kematian. Sementara itu, di sebelah setra gede terdapat dua setra yang dikhususkan untuk anak-anak Satu setra untuk bayi dan satunya lagi untuk anak-anak yang sudah berusia satu oton (enam bulan Bali) dan sudah mempunyai nama namun belum ketus gigi (tanggal gigi susu). Jika terdapat seorang anak meninggal dan sudah ketus gigi, maka anak tersebut dapat dimakamkan di setra gede Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis setra di Desa Bayung Gede yaitu setra Pludu, serta tukad, dan setra gede


Punden Berundak berasal dari masa pra sejarah yang mulai berkembang pada masa bercocok tanam dan mencapai puncaknya pada masa megalitikum. Punden Berundak dianggap sebagai simbol sebuah gunung suci tempat bersemayam roh leluhur yang diyakini akan memberikan berkah berupa kesuburan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat penganutnya. Salah satu struktur punden berundak yang masih terawat terdapat di Pura Mehu Desa Selulung, Bangli Punden Berundak yang terdapat di tengah Pura Mehu dengan no.inventaris 4/14-06/STR/5 ini telah dilakukan inventarisasi dan pendokumentasian oleh tim Badan
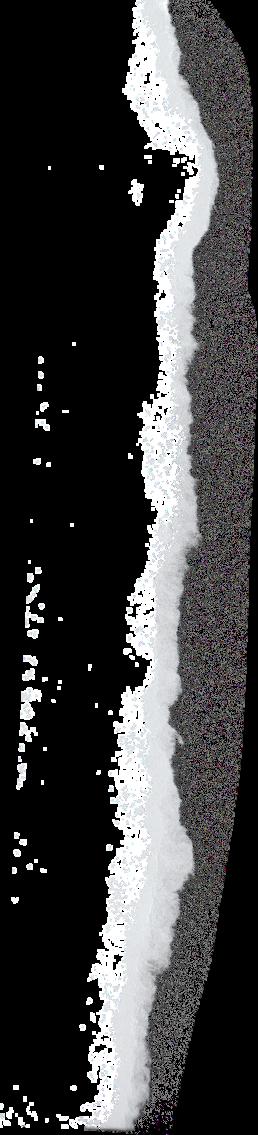
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Bali yang dilaksanakan oleh ketua tim Dra Ni Komang Aniek Purniti, M.Si.

“Dahulunya terdapat beberapa desa di Kintamani yang memiliki situs peninggalan punden berundak serupa, yakni Desa Tanjungan, Desa Petambahan, Desa Bunut, Desa Sukapura, Desa Tangguan, Desa Tohmega, dan Desa Titi Oot. Ketujuh desa tersebut mendapat serangan dari luar yang menyebabkan ketujuh desa tersebut terpecah belah. Raja Tabanan yang mengetahui keadaan tersebut mengutus dalem yang bernama Pasek Nyoman Sadri untuk menyusun dan mempersatukan ketujuh desa tersebut. Berkat kegigihan Pasek Nyoman Sadri, melalui musyawarah dengan para pemimpin tujuh desa yang terpecah belah tersebut, akhirnya disepakatilah untuk membentuk satu desa yang diberi nama Desa Selulung yang berarti ‘Baik Buruk Sepenanggungan’”, ucap Jero Mekel Lingsir

Punden Berundak yang ada di Desa Selulung ini terbuat dari bahan batu padas dengan panjang 5.70 cm, lebar 5.50 cm, dan tinggi 3.11 cm. Dasar pondasinya berbentuk segi empat agak memanjang dengan susunan undak berjumlah
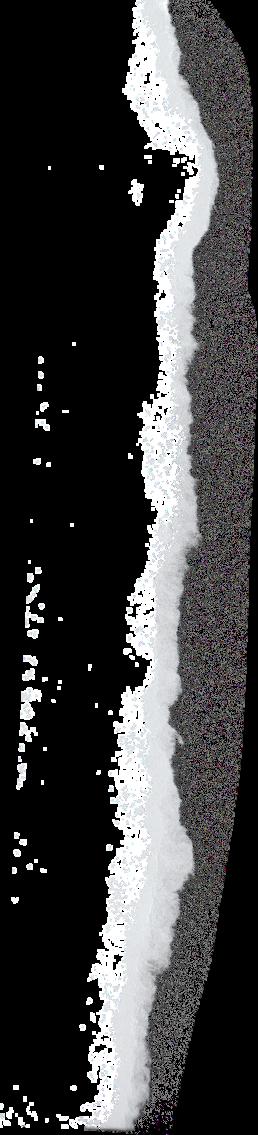
5 tingkat yang semakin ke atas semakin mengecil. Pada masing-masing sudut undakan berhiaskan corak tanaman simbar (sejenis paku-pakuan) kecil serta pola hias ceplok bunga. Pada sisi simetris bidang selasar ; bagian datar alas punden, masing-masing undakan berhiaskan tonjolan persegi empat dengan pola hias ceplok bunga delapan buah. Bagian puncak memakai padma kurung dengan tiga sisi dinding, yakni samping kanan-kiri dan belakang.
Hingga kini masyarakat Desa Selulung masih terus menjaga dan merawat situs peninggalan Punden Berundak tersebut. Hal ini dikarenakan punden berundak tersebut masih menjadi salah satu sarana upacara yang turut serta dalam tiap-tiap pelaksanaan upacara di Pura Mehu Desa Selulung. Punden berundak di Pura Mehu Desa Selulung menjadi simbol peribadatan masyarakat Desa Selulung dan sekitarnya.

Sumber: Dokumentasi Pensik, 2023
Memahami Collaborative Governance dalam
Penyelenggaraan Sistem Kepemimpinan Bali Aga Desa Adat
Kintamani

 I Putu Sawitra Danda Prasetia
I Putu Sawitra Danda Prasetia
Desa Adat Kintamani merupakan salah satu desa tua yang masih mempertahankan
“keasliannya” sebagai salah satu desa Bali Aga hingga saat ini. Kebudayaan yang dimiliki Desa
Bali Aga dicirikan dari sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan istilah ulu apad.

Secara harfiah, kata ulu apad memiliki arti “menarik dari bawah, mendorong ke atas”.
Dikutip dari buku karya seorang antropolog Australia Thomas A. Reuter (2018), mendefinisikan ulu apad sebagai seperangkat majelis tetua desa yang beranggotakan warga yang sudah menikah dan memiliki hak tanah.
Reuter juga menyebutkan rotasi kepemimpinan dalam sistem kepemimpinan ulu apad dijalankan dengan sistem rangking berdasarkan “kelebihdahuluan” perkawinan. Artinya anggota ulu apad yang lebih dahulu menikah akan menduduki posisi yang lebih tinggi, sedangkan posisi dibawahnya akan diduduki oleh anggota yang menikah setelahnya Pola ini akan terus mengulang hingga posisi yang terakhir. Anggota ulu apad dinyatakan pensiun apabila semua anaknya telah menikah atau ia meninggal dunia. Secara otomatis posisinya akan digantikan oleh salah satu anak atau keluarganya
Ulu apad merupakan sistem politik lokal yang bersifat komunal dan berprinsip kolektif kolegial (Nugrahaningari, 2017) Ulu apad berlaku secara umum di desa – desa Bali Aga lainnya namun terdapat perbedaan pada struktur, fungsi, dan mekanismenya. Berdasarkan studi dokumentasi pada awig – awig Desa Adat Kintamani, ulu apad
Desa Adat Kintamani menggunakan istilah saing kutus karena terdapat 8 orang yang menjabat sebagai inti dalam pemerintahan
Awalnya hanya sistem pemerintahan ulu apad

yang memegang peranan dalam menentukan
kebijakan dan peraturan di Desa Adat

Kintamani Namun dalam beberapa dekade
terakhir berdasarkan studi observasi terjadi
pergeseran fungsi dalam dualitas
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Adat Kintamani.
Sumber: Dokumentasi Pensik, 2023
Hal tersebut disebabkan berlakunya peraturan daerah no 4 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini Desa Adat
Kintamani juga menggunakan sistem prajuru yang dipimpin oleh Bendesa yang dibantu Juru Surat, Juru Raksa, Kelian Banjar dan Kasinoman. Sistem prajuru yang diimplementasikan di Desa Adat Kintamani sedikit berbeda dengan desa –desa lainnya, dimana untuk menjadi Bendesa haruslah berasal dari kraman yang menjadi anggota ulu apad.
Saing kutus tersebut terbagi ke dalam dua sibak yaitu sibak kiwa (sisi kiri) dan sibak tengen (sisi kanan) Posisi tertinggi dijabat oleh sepasang Jero Kubayan yaitu Jero Kubayan Mucuk dan Jero



Kubayan Kiwa Posisi kedua terdapat Jero Bahu Tengen dan Jero Bahu Kiwa, sedangkan posisi ketiga dan kempat dijabat oleh Jero Singgukan dan Jero Penakehan, masing – masing berjumlah dua orang. Dibawah jabatan Saing kutus terdapat 8 orang Jero Penembelasan dan dua orang Plekutusan. Posisi selanjutnya terdapat anggota ulu apad yang disebut Kraman dengan posisi paling terakhir disebut Pideran

Awalnya hanya sistem pemerintahan ulu apad
yang memegang peranan dalam menentukan
kebijakan dan peraturan di Desa Adat Kintamani.
Namun dalam beberapa dekade terakhir
berdasarkan studi observasi terjadi pergeseran
fungsi dalam dualitas penyelenggaraan
pemerintahan di Desa Adat Kintamani Hal
tersebut disebabkan berlakunya peraturan daerah
no 4 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi Bali. Saat ini Desa Adat Kintamani juga
menggunakan sistem prajuru yang dipimpin oleh
Bendesa yang dibantu Juru Surat, Juru Raksa, Kelian Banjar dan Kasinoman. Sistem prajuru yang
diimplementasikan di Desa Adat Kintamani sedikit
berbeda dengan desa – desa lainnya, dimana untuk
menjadi Bendesa haruslah berasal dari kraman yang
menjadi anggota ulu apad.
Terjadi pembagian fungsi antara sistem ulu apad dan sistem prajuru, sistem ulu apad lebih banyak mengurusi persoalan niskala yaitu persoalan yang
bersifat religius seperti pelaksanaan pujawali pura.
Sedangkan sistem prajuru mengakomodir
permasalahan sekala yaitu birokrasi pemerintahan
desa adat yang lebih formal
Meskipun terdapat dualitas, pada pelaksanaannya
kedua sistem kepemimpinan baik ulu apad maupun
prajuru di Desa Adat Kintamani saling
berkolaborasi dalam menjalankan roda
pemerintahan guna menentukan dan mengontrol kebijakan yang diputuskan untuk mengatur
masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan adat di lingkup Desa Bali Aga pada era globalisasi
seperti saat ini harus diakui tidak bisa lagi bertumpu pada satu sistem ulu apad saja.
Diperlukan sebuah kerjasama dengan sistem
prajuru tetapi dengan catatan sistem ulu apad wajib dipertahankan. Hal tersebut seirama dengan
pandangan governance dalam ilmu administrasi
publik yaitu membagi peran pemerintah kepada
kelompok lainnya sehingga membangun sinergitas
dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Perkembangannya terjadi
penyempurnaan dalam konsep governance, yaitu collaborative governance atau tata kelola pemerintahan yang kolaboratif Collaborative governance tidak tercipta secara tiba – tiba, akan tetapi penyebabnya berasal dari inisiatif berbagai pihak yang termotivasi untuk berkolakorasi dalam menyelesaikan permasalahan publik (Junaidi, 2015)
Proses c
dalam peny
Desa Ada
pengambila
keputusan
ditentukan
sangkepan


melibatkan
dan masyar
Namun


ambil kepu sebagai ja memberi na dianggap mutlak karena dipandang memiliki kekuatan niskala Proses lainnya juga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dan aset desa. Juru Raksa dalam sistem prajuru merupakan bendahara desa adat dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan memerlukan pengawasan serta konsultasi dari sistem ulu apad. Selain itu proses collaborative governance juga dapat terlihat dari pelaksanaan upacara yadnya. Siklus upacara yadnya di Desa Adat Kintamani sangat padat selama dua belas sasih (dua belas bulan), oleh sebab itu sistem ulu apad bekerja sama dengan sistem prajuru Mengingat upacara yadnya di Desa Adat Kintamani memerlukan biaya yang tak sedikit, sistem prajuru bertugas menjembatani dengan pemerintah daerah untuk memperoleh bantuan keuangan
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Kintamani merupakan salah satu desa Bali Aga yang masih mempertahankan sistem pemerintahan ulu apad yang disebut sebagai saing kutus Meskipun terdapat dualitas antara sistem ulu apad dan prajuru, kedua sistem tersebut dapat bersinergi yang seiras dengan konsep collaborative governance dalam kajian ilmu administrasi publik jika dilihat pada beberapa aspek Diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga untuk melestarikan kebudayaan Bali Aga dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman.
Daftar Pustaka; Desa Adat Kintamani, 2017 Awig – Awig Desa Adat Kintamani
Nugrahaningari, N K (2017) Ulu Apad : Sistem Politik Lokal Masyarakat Bali Mula di Desa Bayung Gede pada Era Modern (Sebuah Kajian Antropologi Politik)
Jurnal Humanis 18(1), 195 - 204 doi:https://doi org/10 24843/JH 2017 v18 i01
Reuter, T (2018) Rumah Leluhur Kami : Kelebihdahuluan dan Dualisme dalam
Masyarakat Bali Dataran Tinggi (Cetakan Pertama Juli 2018 ed ) Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia doi:1514 36 68 2018
Junaidi, 2015 Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang




Pada umumnya, masyarakat yang mendiami Pulau Bali
dikelompokkan menjadi dua, yaitu masyarakat Bali Aga dan masyarakat Bali Majapahit. Adanya pengelompokkan tersebut
digunakan untuk membedakan waktu datangnya kedua kelompok
tersebut Bali Aga adalah kelompok yang lebih dahulu datang ke
Bali Umumnya mereka mendiami wilayah pedalaman sekitar
pegunungan di Bali dan lebih sedikit terkena pengaruh Majapahit.
Sedangkan kelompok Bali Majapahit, datang belakangan
bersamaan dengan datangnya pasukan Kerajaan Majapahit ke
Bali Umumnya mendiami wilayah dataran dan banyak terkena
bahkan membawa pengaruh Majapahit
Masyarakat Bali Aga memiliki kebudayaan yang berbeda dari
masyarakat Bali pada biasanya. Kebudayaan Bali Aga merupakan
hasil sinkretisme antara kebudayaan prasejarah dengan
kebudayaan Hindu sehingga menghasilkan suatu bentuk
kebudayaan yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan
kebudayaan prasejarah, kebudayaan Hindu ataupun kebudayaan
Bali Majapahit. Salah satu contoh kebudayaan Bali Aga adalah

adanya gamelan Salunding atau disebut juga Selonding
Salunding Wesi atau Selonding Besi atau disebut juga Selonding adalah instrumen sejenis gender (bilah) yang berbahan dari besi dan terdapat di desa-desa Bali Aga, seperti Tenganan Pegringsingan dan Bungaya Gamelan ini disakralkan oleh masyarakat pemiliknya dan juga digunakan sebagai pengiring upacara keagamaan (Bandem, 2013:58) Gamelan ini dimainkan dengan teknik dua tangan seperti gender dengan cara dipukul menggunakan panggul sebagai pemukulnya.
Hingga saat ini belum ada sumber sejarah yang menyebutkan secara pasti kapan gamelan Selonding dibuat dan ada dalam kehidupan masyarakat Bali Akan tetapi, gamelan Selonding diperkirakan muncul pada abad ke-9 saat masa pemerintahan Sri Kesari Warmadewa, dibuktikannya dengan muncul kata yang mirip “Selonding” pada beberapa prasasti kerajaan Bali Kuna (Ganeshwari, 2017)
Terdapat sebuah mitos di kalangan masyarakat Tenganan Pegringsingan dimana gamelan Selonding disebut dengan nama Bhatara Bagus Selonding. Munculnya Selonding dikaitkan dengan sebuah mitologi yang menyebutkan bahwa pada zaman dulu orang-orang
Tenganan mendengar suara gemuruh dari angkasa yang datang secara bergelombang Pada gelombang pertama suara itu turun di Bungaya dan pada gelombang kedua suara itu turun di daerah Tenganan Pegringsingan. Setelah hilangnya suara itu ditemukan gamelan Selonding yang berjumlah tiga bilah. Bilah-bilah itu kemudian dikembangkan sehingga menjadi gamelan Selonding seperti sekarang. Bilah-bilah itu diturunkan lagi dan kini gamelan Selonding Tenganan terdiri dari 8 tungguh yang berisi 40 bilah, 6 tungguh masing–masing berisikan 4 bilah, dan yang 2 tungguh berisikan 8 bilah
Gamelan ini berbentuk bilah-bilah lebar yang diletakkan di atas pelawah/wadah yang terbuat dari kayu sebagai wadah sumber suara. Masing-masing pelawah memiliki bentuk yang berbeda-beda (Sukerta, 2010). Bilah selonding berbentuk matun poh (kedua volume sisi atas dan bawah sama) yang memiliki empat lubang di setiap bilahnya Bentuk dari bilah tersebut sangat khas yang hanya ada pada gamelan Selonding, bentuk tersebut memiliki fungsi jika di pasang terbalik tidak masalah karena karena proporsi bentuk sisinya sama Adanya empat lubang pada bilah Selonding memiliki sistem tersendiri pada pemasangan bilah dalam tungguhan-nya.
Gamelan Bali pada umumnya memiliki dua lubang di setiap bilah dan cara sistem menyusun bilah tersebut dengan cara digantung menggunakan tali dan lait (penyangga bilah yang berbentuk bulat berukuran kecil dan terletak di bawah lubang bilah) Lait memiliki fungsi pengait tali yang menyusun bilah pada tungguhan Berbeda halnya dengan tungguhan di gamelan Selonding yang mengunakan sistem dua lubang di setiap pinggir bilah berfungsi untuk menggantung bilah tanpa harus menggunakan lait. Adanya dua lubang menjadikan bilah yang digantung sekan seperti anyaman yang terangkai dan terjalin satu sama lain. Sistem lubang emapat pada bilah hanya terdapat pada gamelan Selonding dan Gambang (Widiana, 2019)

Selonding memiliki ciri khas tersendiri di beberapa daerah Di Tenganan, instrumentasi Selonding terdiri dari gong ageng, gong alit, kempul ageng, kempul alit, penem, petuduh, nyongnyong ageng, nyongnyong alit. Sedangkan di Bebandem, Selonding terdiri dari jegog, menanga, gangsa pemade, suir dan kebyok (Widiana, 2019) Kemudian di Bungaya terdiri dari penanga, penanga bali, gangsa agung, gangsa alit, kasumba, petuk dan pemarep (Ganeshwari, 2017).
Pada gamelan Selonding, laras yang dipakai adalah laras pelog saih pitu atau pelog tujuh nada yang terdiri dari 5 nada pokok dan 2 nada pemero Namun masing-masing nada bisa menjadi nada pokok tergantung pada patet yang dimainkan. Terdapat 6 patet pada gamelan Selonding, diantaranya patet Panji Marga, Sondong, Puja Semara, Kesumba, Sadi dan Salah
Gamelan Selonding pada masyarakat Bali Aga sendiri memiliki fungsi sebagai pengiring upacara keagamaan masyarakat setempat. Misalnya, Selonding di Tenganan digunak-

an untuk mengiringi tari Rejang dan Mekare-kare atau Perang Pandan Di Bungaya, gamelan Selonding berfungsi sebagai pratima atau perwujudan jasmani para dewa, juga ditabuh pada saat upacara usaba dangsil. Di luar Bungaya, gamelan Selonding dimainkan di Puri Agung Karangasem pada saat upacara pitra yadnya dan maligia. Ini merupakan satu- satunya gamelan Selonding dimainkan di luar desa Bungaya, karena desa Bungaya memiliki kaitan yang erat dengan Puri Agung Karangasem (Ganeshwari, 2017)
Selonding masih eksis hingga kini sebab masih ada anggota masyarakat yang mewarisi dan mampu memainkannya. Kendati hanya dimainkan pada saat-saat tertentu saja, masyarakatnya tetap memiliki rasa ikatan yang kuat kepada Bhatara Bagus Selonding. Misalnya, di Bungaya setiap purnama masyarakatnya selalu menghaturkan sesaji kehadapan Bhatara Bagus Selonding Bagi mereka, gamelan Selonding bukan hanya sebuah alat musik tetapi juga bagian dari kehidupan religius masyarakatnya (Ganeshwari, 2017)
Di luar masyarakat Bali Aga, Selonding mempunyai dipandang sebagai alat musik biasa dan difungsikan pada berbagai macam upacara yang bersifat umum, bahkan biasa ditampilkan pada festival-festival seni dengan repertoar-repertoar ciptaan baru para komposernya. Adapun gending yang dimainkan biasanya gending petegak untuk iringan prosesi upacara di Tenganan Pegringsingan dan Bungaya atau desa-desa Bali Aga lainnya, seperti Rejang Ileh yang biasa digunakan untuk mengiringi tari Rejang dan Mekare-kare untuk mengiringi ritual Perang Pandan, namun kini dimainkan sebagai tabuh instrumental tanpa ada kaitan ritual seperti konteks aslinya.
DAFTAR PUSTAKA :
Bandem, I. M. (2013). Gamelan Bali Di Atas Panggung Sejarah. Denpasar: Badan Penerbit STIKOM Bali.

Ganeshwari, N P (2017) Eksistensi Gamelan Selonding di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud, 56-63
Sudiarsa, I W (2021) GAMELAN SALONDING MASUK HOTEL Studi Kasus: PERKEMBANGAN GAMELAN SALONDING DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM
Widyanatya, 31-36
Sukerta, P M (2010) Tetabuhan Bali I Surakarta: ISI Press Solo
Widiana, I W (2019) Karakteristik Gamelan Selonding Bebandem Dan Selonding Tenganan "Studi Komparasi Intramusikal". MUDRA Jurnal Seni Budaya, 61-72
Sumber Foto :


Sumber: warisanbudaya kemdikbud go id


Desa Tenganan Pegringsingan atau dikenal juga sebagai Desa Bali Aga (desa tua) terletak di ujung timur pulau Bali tepatnya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Di desa ini terdapat salah satu objek kebudayaan yang ditetapkan pemerintah melalui Kemenristekdikti sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional tahun 2021. Objek tersebut adalah Tari Abuang Luh Muani, tarian yang bermakna sebagai simbolik pengikat daha dan truna (remaja perempuan dan laki-laki) agar tidak menikah dengan remaja dari luar desa.
Tari Abuang Luh Muani diperkirakan muncul sejak Desa Tenganan Pegringsingan berdiri bersamaan dengan adat istiadat dan beberapa tarian yang ada di desa tersebut, tepatnya pada abad X setelah Mayadanawa dikalahkan oleh Bhatara Indra (Lety, Ni Kadek 2016). Tari Abuang Luh Muani ditampilkan sebagai rangkaian penutup upacara Usaba Kasa pada sasih kasa yang menurut masyarakat setempat merupakan bulan suci kelahiran sesuhunan (leluhur) dan diselenggarakan setiap tahun di Pura Bale Agung, Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Menurut Kamus Bali Indonesia, kata luh artinya wanita dan muani artinya laki-laki. Sedangkan kata abuang memiliki arti menari dengan menuangkan air nira sebagai persembahan suci (Bandem, 1983:3) Namun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tari Abuang Luh Muani ini diartikan sebagai tarian yang dilakukan oleh dua orang (berpasangan) yaitu, truna (pria) dan daha (wanita) dengan merentangkan tangan ke samping lalu ke depan dan ke belakang mengikuti alunan gamelan selonding yang tidak terpaku pada dasar pakem-pakem tari Bali.
Sebagai sebuah tarian kuno, gerakan pada Tari Abuang Luh Muani sangat sederhana yakni badan hadap ke depan dan merentangkan kedua tangan, mengayunkan tangan kanan ke depan kaki kiri ke belakang tangan kiri ke belakang demikian sebaliknya Penari truna (pria) juga melakukan gerakan yang sama namun dengan posisi yang berhadapan sehingga terlihat berlawanan dan saling mengisi.
Tari Abuang Luh Muani menggunakan iringan musik gamelan selonding yang merupakan jenis musik tertua di Bali Kata selonding diduga berasal dari dua kata yaitu kata salon dan ning yang berarti tempat yang suci Dilihat dari fungsinya bahwa selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan (Lety, Ni Kadek 2016) Penabuh gamelan pun tidak boleh sembarang orang melainkan mereka yang sudah disebut Juru Gamel yang ditetapkan melalui sebuah upacara adat.

Tari Abuang Luh Muani memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, pertunjukkan ini diyakini dapat mempertemukan para daha dan truna agar saling mengenal satu dengan yang lainnya Terdapat sebuah aturan yang bersifat mengikat di desa ini dan masih diterapkan sampai sekarang. Aturan tersebut mengharuskan para daha dan truna menikah dengan sesama remaja dari desa setempat agar jumlah krama (penduduk) desa tetap terjaga. Apabila truna desa menikah dengan daha dari luar desa maka tidak akan dilibatkan dalam setiap kegiatan adat dan tidak berhak menjadi krama desa Hal inilah yang menjadikan Tari Abuang Luh Muani ini sangat penting untuk tetap dijaga dan dilaksanakan
Daftar Pustaka
Lety, Ni Kadek (2016) "Tari Abuang Luh Muani di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem" Skripsi Program Studi Seni Tari fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar
Kemendikbud (2018) "Tari Abuang Luh Muani" https://warisanbudaya kemdikbud go id/?
newdetail&detailTetap=2335#: :text=Tari%20Abuang%20Luh%20Muani%20merupakan,yang%20mendalam%20diiringi%20 gamelan%20Selonding, sumber dari internet (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023)
Bandem, I Made 1983 Ensiklopedia Tari Bali Denpasar: Akademi Seni Tari Indonesia Denpasa


































Pulau Bali dibangun berdasarkan konsep-konsep Agama Hindu yang mengajarkan agar umatnya berpandangan dan bersikap selaras, serasi dan seimbang. Oleh karena itu masyarakat Bali memiliki kesadaran bahwa alam semesta merupakan kompleksitas unsur yang satu dengan yang lainnya yang saling terikat dan membentuk suatu sistem kesemestaan.
Tri Hita Karana (tiga penyebab terciptanya kebahagiaan) memunculkan tata cara dalam kehidupan yang tidak akan dapat dipisahkan dalam tradisi-tradisi kehidupan umat Hindu Tradisi serta ritual yang dilakukan


yang dipercayai tentu memiliki tujuan tersendiri, baik untuk memohon perlindungan dari Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur, atau sebagai pengingat bagi masyarakatnya Jika dilihat sebagai pengingat, maka akan banyak sekali tradisi serta ritual yang bertujuan menjadi pengingat bagi manusia agar senantiasa mengingat Pencipta-Nya, salah satunya adalah tradisi Ngusaba Lampuan di Desa Bayung Gede
Desa Bayung Gede merupakan salah satu representasi desa Bali Aga yang terdapat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Desa Bayung Gede memiliki berbagai macam tradisi unik, Salah satunya adalah tradisi Ngusaba Lampuan
Tradisipada umumnya sangat beragam dan terdapat di beberapa daerah di Bali, diantaranya Ngusaba Nini, Ngusaba Desa, Ngusaba Guling, Ngusaba Tegen, serta Ngusaba Lampuan yang akan dibahas oleh penulis. Secara umum tradisi ini bertujuan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, maupun dengan sesama manusia itu sendiri seperti yang terkandung dalam filosofi Tri Hita Karana.
Ngusaba Lampuan merupakan tradisi yang memfokuskan ritualnya kepada masa karantina bagi pemuda – pemudi Desa Bayung Gede. Tradisi ini diadakan setiap lima tahun sekali atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tetua adat setempat Ngusaba Lampuan adalah upacara untuk memohon kehadapan Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar para pemuda – pemudi diberi kewajiban lahir dan batin sehingga dapat menunaikan kewajiban hidup pada masa berumah tangga dan bermasyarakat. Tradisi ini bisa disepadankan sebagai ritus inisiasi atau masa peralihan kelompok pemuda-pemudi dari fase anakanak menuju dewasa.
Dalam pelaksanaan tradisi Ngusaba Lampuan, Jro Lampuan Lanang (pemuda) dan Jro Lampuan Istri (pemudi) diwajibkan menggunakan pakaian tradisional dan sederhana, yang sudah ditentukan oleh para tetua Desa Bayung Gede Untuk Jro Lampuan Lanang memakai busana berupa kemben atau kain Bali, saput meselibeh (memakai selempang selimut), meseet golok (membawa golok), mekalung desar (ikat kepala), ngadut kompek (dompet) yang terbuat dari bambu yang dianyam menyerupai bentuk dompet Dompet ini berisi daun sirih, buah pinang, tembakau, gambir, dan kapur sirih, yang nantinya akan dikunyah oleh para Jro Lampuan Lanang di tempat upacara Pelampuan itu dilaksanakan. Mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan baju dan alas kaki Jro Lampuan Istri biasanya memakai busana kemben atau kain Bali, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh menggunakan baju melainkan menggunakan kain Bali sebagai pengganti baju tersebut, serta tidak boleh memakai alas kaki
Sarana dan prasarana tradisi ini juga sangat unik dan berbeda dengan sarana upacara atau
tradisi lainnya, yakni dengan menggunakan
jajan biyu atau jajan yang dibuat dari pisang
mentah yang diparut Parutan pisang ini kemudian dicampur dengan tepung beras merah
kemudian digoreng Jajan ini dibuat oleh masing
– masing Jro Lampuan Lanang dan Jro Lampuan
Istri secara urunan atau iuran yang nantinya
akan digunakan untuk membayar denda tiap
pelanggaran yang dilakukan oleh Jro Lampuan
Lanang dan Jro Lampuan Istri selama prosesi tradisi Ngusaba Lampuan dilaksanakan
Fungsi secara religi dari tradisi Ngusaba Lampuan di Desa Bayung Gede untuk memohon keselamatan kepada Tuhan dengan segala manifestasinya, serta memohon agar Tuhan merestui para generasi muda dalam menjalankan kewajiban lahir dan batinnya setelah memasuki masa menikah atau bermasyarakat.
Fungsi sosial adalah mengajaFungsi rkan masyarakat untuk bisa saling menghormati antar warga dan menjalin hubungan yang harmonis serta bisa menjadikan pembelajaran ke tahap kehidupan selanjutnya.
Fungsi pendidikan untuk mendidik, melatih para pemuda-pemudi Desa Bayung Gede agar siap ketika memasuki kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.
Fungsi Etika, etika selalu menguraikan baik dan buruk, salah dan benar, tentang pola pikir, perkataan dan perbuatan manusia dalam berbuat sesuatu Begitu pula dalam
Sarana selanjutnya adalah Penjor Lampuan yang

terdiri dari dua buah penjor yang diikat menjadi satu Satu penjor terbuat dari bambu yang utuh tidak boleh ada cabang yang patah, goresan, mati buku / garis hitam melingkar pada ruas bambu dari sisi pangkal sampai ke ujung dengan hiasan daun enau muda Penjor lainnya terbuat dari batang bambu yang telah dipotong ujungnya dan di atasnya ditancapkan jejahitan dari daun enau muda. Penjor ini dibuat oleh masing-masing Jro Lampuan Lanang. Sarana lainnya yakni Lampu / Damar Suar Melin yang pada tradisi Ngusaba Lampuan merupakan lampu sakral yang terbuat dari tiga unsur alami yaitu tabung minyak dari pangkal pohon pisang, bersumbu parutan kulit pohon bambu yang dianyam, dan minyak kelapa sebagai bahan bakar dan sebilah bambu sebagai tangkai berpasangan yang digantung
Lampu atau masyarakat setempat menyebutnya dengan damar suar melin ini memiliki makna sebagai upaya penerangan batin.
membuat sarana upacara atau ritual dan banten yang harus diketahui etika atau susila dalam membuatnya. Hal tersebut bertujuan agar nilai, makna, serta tattwa di dalam
banten atau sarana ritual tersebut tidak menghilang.Fungsi Tradisi Ngusaba Lampuan
Nilai
dari
Ngusaba Lampuan didasari keyakinan umat Hindu akan Panca Sradha yaitu dengan melaksanakan tradisi Ngusaba Lampuan Masyarakat Desa Bayung Gede dapat memohon kesejahteraan kepada Tuhan dengan wujudnya atau manifestasinya sebagai Bhatara Siwa dan Bhatari Durga
Nilai Etika, salah satu nilai etika yang terdapat pada tradisi Ngusaba Lampuan yaitu pada saat melaksanakan upacara Ongge-ongge Tepatnya pada saat Jro Lampuan Lanang dan Jro Lampuan Istri selaku salah satu tetua adat saling berbalas pantun serta memberikan petuah mengenai Susila dan tattwa
Prosesi pelaksanaan tradisi Ngusaba Lampuan memerlukan
waktu serta tahapan-tahapan yang tidak sedikit Sebelum
berlangsungnya tradisi ini para Jro Lampuan Lanang dan Jro
Lampuan istri serta seluruh masyarakat Desa Bayung Gede
melaksanakan upacara Matur Piuning (upacara memohon restu) kepada Tuhan yang dipimpin oleh Jro Kubayan serta para tetua Desa Bayung Gede Upacara ini dilaksanakan tujuh
hari sebelum upacara puncak tradisi Ngusaba Lampuan
dilaksanakan Setelah tujuh hari berlalu para Jro Lampuan
Lanang dan Jro Lampuan Istri kembali melaksanakan Matur
Piuning di Pura Puseh Pingit untuk melaksanakan upacara

puncak dari tradisi Ngusaba Lampuan, mereka dipingit selama kurang lebih 5 sampai 7 hari.
Pelaksanaan upacara puncak tradisi Ngusaba Lampuan
yang dilaksanakan selama beberapa hari kedepan akan
meliputi beberapa kegiatan yakni pada hari pertama Jro
Lampuan Lanang dan Jro Lampuan Istri melaksanakan
Pedangsilan serta melakukan sembahyang di Pura Bintak. Di hari kedua para Jro Lampuan Lanang dan Jro Lampuan Istri akan mempelajari bagaimana cara membuat dan mempersembahkan Jajan Biyu (jajan pisang) Pada hari ketiga
seluruh Jro Lampuan Lanang dan Jro Lampuan Istri akan
berpindah tempat pingit / karantina dari Pura Penataran
Bintak menuju Pura Bale Agung. Selanjutnya di hari keempat
Jro Lampuan Lanang dan Jro Lampuan Istri melaksanakan
upacara yang disebut dengan Upacara Ongge - ongge atau
sebuah permainan yang bernuansa lucu seperti saling
membalas pantun Kemudian di hari kelima Jro Lampuan
Lanang dan Jro Lampuan Istri melaksanakan sebuah upacara
Babuangan Sundingan atau semacam perang menggunakan
daun suren (tumbuhan jenis paku), upacara ini dilaksanakan


oleh seluruh masyarakat Desa Bayung Gede.
Namun sebelum upacara ini dimulai, seluruh Masyarakat
Desa Bayung Gede melaksanakan persembahyangan bersama
untuk memohon keselamatan dan kelancaran jalannya upacara. Sesajen atau upakara yang digunakan berupa banten peras lengkap dengan pejati atau daksina dengan tumpeng sejumlah 5 buah. Sarana lain meliputi canang pangkonan sebanyak 4 buah, jajan, aneka buah-buahan, daging ayam serta sampian peras lengkap dengan porosan, bunga dan rampe. Tradisi ini ditutup dengan ritual penyineban. Tahap akhir ini harus dilakukan di hari baik (dewasa ayu) pula agar segala harapan bisa tercapai Dalam prosesi ini, Jro Lampuan Lanang dan Jro Lampuan Istri akan kembali ke rumah masing-masing sebagai tanda berakhirnya prosesi Ngusaba Lampuan. Jro Lampuan Lanang membawa kayu bakar saat meninggalkan tempat upacara dengan harapan kelompok laki-laki ini akan menjadi penerang dalam kehidupan rumah tangga kelak baik dalam keluarga batih maupun keluarga besar. Jro Lampuan Istri akan membawa sayur mayur sebagai simbol dan harapan kesejahteraan keluargannya kelak
Sumber foto: Facebook com / Bayung Art

Pada dasarnya tradisi Ngusaba Lampuan memiliki makna sebagai upaya peringatan kepada pemuda dan pemudi untuk tetap menjaga tradisi yang ada serta pengingat akan tanggung jawab mereka nanti setelah menikah dan menjalani hidup bermasyarakat. Di era modern ini, banyak pemuda dan pemudi yang mulai meninggalkan identitas kultural mereka serta sikap apatis mereka terhadap tradisi mereka. Hal inilah yang membuat mereka lupa akan identitas dan kewajiban mereka yang sebenarnya. Melalui tradisi Ngusaba Lampuan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Desa Bayung Gede ini, diharapkan mereka kembali ingat akan tanggungjawab dan kebudayaan serta tradisi yang mereka miliki. Hal ini penting dilakukan karena akan menjadi bekal mereka dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat kelak yang sederhana dan bersahaja seperti para tetuanya terdahulu
TRADISI NGUSABA LAMPUAN DI DESA PAKRAMAN BAYUNGGEDE KECAMATAN
KINTAMANI KABUPATEN BANGLI (Perspektif Pendidikan Agama Hindu). Yanti, Ni Luh Eka 2019. 3, Denpasar : Jayapangus Press, 2019, Vol. 3. 2579-9843.
UKM KARYA ILMIAH MAHASISWA. 2020. Kearifan Lokal Bali Di Era Milenial. 2020 . 2020. Kearifan Lokal Bali Di Era Milenial Denpasar : UNHI PRESS, 2020 978-623-796-315-8.

Dalam suatu masyarakat, tentunya terdapat seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi lingkungan sekitarnya. Tokoh tersebut selain dikenal karena kontribusinya bisa juga dikagumi karena kisah inspiratif yang dimiliki dan menjadi contoh bagi orang lain Begitu pula di Desa Sukawana, desa yang merupakan bagian dari Kabupaten Bangli ini tentunya sudah tidak asing ketika kita berbicara tentang Bali Aga.

Jro Sabaraka, begitulah tokoh yang lahir di Desa Sukawana pada tanggal 15 juli 1965 ini kerap disapa oleh masyarakat Beliau menghabiskan masa kecil hingga remaja di Desa Les, Kecamatan Tejakula namun sewaktu-waktu tetap menyempatkan diri untuk pulang ke Desa Sukawana. Pada tahun 1980 beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Les dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tejakula hingga tamat pada tahun 1983. Kemudian beliau kembali melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di salah satu SMA swasta pada saat itu yaitu di SMA Bakti Yasa Tejakula dan tamat pada tahun 1986.

Menurut cerita beliau pada saat itu di Singaraja hanya terdapat satu SMA negeri yaitu
SMAN 1 Singaraja yang sudah tentu penuh
dengan kompetisi Hal tersebut membuat sekolah swasta menjadi pilihan beliau dalam melanjutkan pendidikan. Seusainya mengenyam pendidikan
selama kurang lebih dua belas tahun, pada tahun
1987-1992 beliau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di STKIP Agama Hindu
Singaraja dengan mengambil jurusan agama. Di tahun 1992 sebelum menyelesaikan studinya, beliau sudah diambil untuk bekerja sebagai
pegawai di suatu yayasan bernama Yayasan
Mandara Giri di Singaraja


Beliau memiliki suatu kisah menarik berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang antropolog berkebangsaan Jerman bernama Thomas A Reuter Di akhir tahun 1992
Jro Sabaraka bertemu dengan Thomas di daerah
Penulisan dalam keadaan bingung Thomas yang notabene seorang mahasiswa S3 dari salah satu universitas di Australia pada saat itu sampai di Penulisan dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebagai bahan disertasi.
“What are you doing now and what can I help you?” Begitulah kira-kira pertanyaan yang dilontarkan Jro Sabaraka ketika pertama kali melihat Thomas yang kebingungan Thomas dengan topik penelitian mengenai kosmologi kehidupan di Kintamani lantas meminta bantuan beliau untuk menemaninya selama proses pencarian data penelitian.
Sedikit cerita bahwa pada saat itu meskipun terdapat beberapa akademisi dari beberapa kampus di Bali, namun kebanyakan masih melihat daerah Bangli seperti tidak ada peradaban maupun hal yang menarik untuk diteliti Hal tersebut juga dapat dilihat ketika Thomas Reuter sampai di Kintamani dalam keadaan minimnya catatan mengenai daerah tersebut dikarenakan sentral kota pada saat itu terletak di Denpasar sehingga desa yang berada di daerah pegunungan tak ubahnya bagaikan kota mati.
Seiring berjalannya waktu, Thomas pun menemukan beberapa hal menarik tentang masyarakat Bali Aga khususnya dalam hal sistem kepemimpinan yang disebut ulu apad Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Reuter yang didampingi Jero Sabaraka akhirnya mempelopori adanya penelitian lainnya di daerah Bali Aga. Hingga saat ini para peneliti muda yang ingin melakukan penelitian dengan topik Bali Aga pun masih menjadikan Jero Sabaraka sebagai salah satu narasumber yang dapat dimintai informasi mengenai apa dan bagaimana Bali Aga itu sendiri.


“Dongeng adalah medium terindah dalam tradisi lisan nusantara”
- Pramoedya Ananta Toer -

Raksasa berkata tidak ada melihat siapa-siapa. Kecurigaan muncul di benak para perangkat desa setelah melihat adanya butir-butir jagung yang bercecran di sekitar goa tersebut Merujuk pada rasa curiga, perangkat desa kembali mengadakan musyawarah untuk menemukan cara yang bisa memusnahkan kedua raksasa tersebut.

Disamping senang menculik para penari rejang, sepasang raksasa itu konon katanya juga sering merusak ladang para penduduk di Desa Subaya hingga menimbulkan kecemasan yang sama seperti hilangnya para penari rejang Dari musyawarah yang diadakan oleh perangkat desa tersebut akhirnya didapatkanlah strategi untuk melenyapkan kedua raksasa Subaya tersebut yaitu melalui kegiatan syukuran yang melibatkan si raksasa. Para penduduk memberikan makanan berupa buahbuahan, daging, dan hasil bumi lainnya yang membuat sepasang raksasa itu terlampau kenyang dan akhirnya tertidur. Ketika sepasang raksasa terlelap dalam tidurnya, para penduduk mulai memasukkan duk ke dalam goa tempat raksasa hingga penuh Setelah penuh, duk tersebut kemudian dibakar dalam posisi kedua raksasa terjebak di dalam goa dan tidak bisa bernafas hingga akhirnya mati
Setelah tewasnya kedua raksasa tersebut, maka upacara yang dilaksanakan di Pura Puncak Penulisan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya penari rejang yang menghilang Di kalangan masyarakat dari empat puluh lima desa di atas hingga saat ini terdapat kepercayaan bahwa tulang dari si raksasa dapat dijadikan sebagai boreh (obat tradisional masyarakat Bali). Namun, hampir tidak satu orang pun yang berani masuk ke goa tersebut karena dikenal angker dan berada di tengah hutan.

Desa Sukawana merupakan desa kuno yang terletak di daeran perbukitan Kintamani Desa ini memiliki sejarah panjang serta dilengkapi juga dengan beberapa keunikan baik dari segi upacara, sistem pengetahuan, sistem pemerintahan, maupun cerita rakyat yang beredar Sejak dahulu masyarakat Sukawana memiliki upacara besar yang melibatkan empat puluh lima desa yang berkiblat di Pura Puncak Penulisan. Pada purnama sasih kapat tepatnya pada saat terdapat upacara di pura tersebut, keempat puluh lima desa akan bekerjasama dalam melaksanakan upacara agama. Satu hal yang menarik dari upacara tersebut yaitu konon katanya terdapat sepasang raksasa yang senang menculik para penari yang sedang pentas pada saat upacara berlangsung.
Dikisahkan ketika upacara dilaksanakan terdapat sebuah pementasan tari rejang adat di pura tersebut. Ketika tarian rejang adat di pentaskan selalu terdapat kabut tebal yang menyelimuti penari. Ajaibnya, ketika kabut tersebut berangsur-angsur menghilang, para penari di baris paling belakang juga turut menghilang tanpa diketahui oleh siapapun. Hal ini terus menerus terjadi hingga menimbulkan tanda tanya besar bagi penduduk maupun perangkat desa.
Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali dua kali tetapi berkali-kali hingga menimbulkan keresahan bagi warga Menyikapi hal tersebut, perangkat desa pun mengadakan sebuah rapat untuk menangani masalah hilangnya para penari. Dari rapat tersebut kemudian dihasilkan sebuah keputusan untuk tetap melanjutkan tarian rejang adat, hanya saja penari akan dibekali semacam jagung dan kacang-kacangan dalam bentuk bungkusan yang diikat di pinggang setiap penari.
Suatu ketika upacara tersebut dilaksanakan dan tarian rejang adat dipentaskan, kabut pun mulai turun sehingga perlahan-lahan penari rejang mulai terlihat samar hingga akhirnya penari yang berada di barisan paling belakang menghilang. Karena sudah dibekali tanda sebagai pelacak dari jagung, para perangkat desa pun mencari penari yang hilang dengan mengikuti jejak dari jagung maupun kacangkacangan yang jatuh di atas tanah hingga akhirnya sampai di Desa Subaya. Di desa itu para perangkat desa menemukan goa besar yang ternyata dihuni oleh dua orang raksasa laki-laki dan perempuan. Mengetahui hal tersebut, penduduk kemudian melontarkan pertanyaan:
“Wahai tuan apakah anda melihat anak kecil disini?”
















Kintamani merupakan salah satu tempat wisata di Bali Berbicara kintamani, tak terlepasdarikeelokandankeindahanalamnyayangmembuatorangakanterkagum Selain itu, Kintamani juga terkenal dengan kopi dan jeruknya Kopi Kintamani merupakan komoditasutamayangadadiKecamatanKintamanidanfunfact-nyakopikhaskintamani merupakan kopi jenis Arabika terbaik bahkan sudah diekspor ke beberapa negara seperti Amerika,Australia,Jepang,China,Jermandannegaralainnya
KopiinidapatkitatemukandisalahsatudesayangadadiKecamatanKintamani yaitu, Desa Mengani, Kecamatan Kintamani Masyarakat setempat menyebutnya dengan
KopiMengani Namun,mengapaKopiMenganibisamenjadisalahsatukopiyangcukup terkenal,karenakopiinimemilikicirikhastersendiri KopiMenganiinijugatidakmemiliki cita rasa atau aroma rempah-rempah khas jenis kopi di Indonesia lainnya Sedangkan untukbuahnyacenderungberukuransedangdibandingkankopipadaumumnyadantidak terlalu terasa pahit serta memiliki rasa asam seperti jeruk. Inilah yang membuat Kopi
Mengani disukai Selain itu kopi yang sudah menjadi komoditi ekspor ini juga memiliki kadar kafein yang tidak terlalu tinggi Kopi Mengani memiliki rasa masam seperti Jeruk Hal ini dipercaya karena masyarakat Mengani menanam kopi bersamaan dengan jeruk disatu lahan yang sama Namun belum ada penelitian lebih lanjut dari mana rasa masam kopimenganiiniberasal
MenurutBendesa,kopiMenganisudahadasebelumtahun1980-andandimasaitu bisa dibilang masa jayanya produksi kopi khas Mengani Pada tahun 1990 harga kopi di pasar Dunia mengalami penurunan, sehingga banyak petani kopi yang mulai beralih ke jeruk.ProduksikopiMenganipunmengalamipenurunandanketenarankopimenganikian meredup KepalaDesaMenganiIKetutArmawanyangjugaseorangpetanikopiberupaya mematenkan kopi khas mereka dengan label atau brand nama Desa Mengani agar kopi Mengani kian terkenal Ia berharap bisa mengembangkan desanya jadi sentra dan ekowisata kopi dan jeruk Namun harapan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah,terlebihlagipengurusanperizinanyangsulit

Kopimenganikianmeredupdikarenakansalahsatupabrik produksi kopi yang terdapat di desa mengani telah berhenti beroperasi dimana terjadi sengketa antara pihak perusahaan dengan pengontrak pabrik Petani kopi mengharapkan pabrik pengolahan kopi Arabika milik Pemkab Bangli di Desa Mengani, Kintamani bisa segera beroperasi kembali agar dapat membantu petani dalam memproduksi kopi, masyarakat berpendapat, dengan beroperasinya kembali pabrik tersebut maka petani kopi bisa mendapatkan harga yang lebih pantas Saat ini sebagian kecil petani di Desa Mengani mengelola hasil panennya dalam skala rumahan Petani lebih banyak dijual dalambentuk“habispetik” Petanilokalbiasanyamenjualkopi ke Perusahaan besar Petani dengan Perusahaan tersebut biasanya memiliki perjanjian kontrak Jika rasa kopi berbeda dari yang sebelumnya akan mendapatkan komplain dan Perusahaan akan menurunkan harga yang ditetapkan dengan petanilokal



Desamenganihanyamengenalduajeniskopiyaitukopikopyoldankopicobra Perbedaanduajeniskopitersebutyaitudariukuranbuahnya Buah kopi kopyol lebih besar dari buah kopi cobra Masa pertumbuhan kopi cobra lebih cepat yaitu 2 tahun, sementara kopi kopyol membutuhkan waktu3sampai4tahunhinggaberubah Penanamanbijikopibiasanyadilakukandipertengahantahun Teknikuntukmenanamkopidenganmencari buahkopiyangberbijiduayangtumbuhdipertengahanbatangpohonkopi Bijikopitersebutkemudiandicucibersihhinggatidakadabakteriyang menempel pada biji. Setelah dicuci, biji kopi disemai dan ditanam dengan pasir serta pupuk yang sudah difermentasi. Tanaman kopi yang sudah tumbuhdaunakandipindahkankepolybag


Bibitpohonkopimemerlukanwaktu3bulanuntuktumbuhbesardanbisalangsungdipindahkanuntukditanamdilahankopi Untukmasapanen biasanya di bulan februari hingga agustus tergantung masa pertumbuhan pohon kopi Kopi jenis cobra, bisa menghasilkan hingga 6 kilogram Sementarakopijeniskopyolhanyamendapatkan14kilogrambijikopi Seusaipanen,kopiakandieksporkedalamnegerihinggaluarnegeri Negara yangseringdieksporyaituJermandenganalasankarenanegaratersebutmempermudahkegiatanmengeksportanpaadaaturantertentu PetaniKopi Mengani enggan mengirimkan komoditas kopinya ke negara yang memiliki regulasi dan peraturan rumit terkait ekspor kopi seperti Australia dan Jepang











-


SpecialThanksto:




 SMA NEGERI 1 KINTAMANI
DESA BAYUNG GEDE DESA SUKAWANA
DESA SELULUNG DESA MENGANI
SMA NEGERI 1 KINTAMANI
DESA BAYUNG GEDE DESA SUKAWANA
DESA SELULUNG DESA MENGANI
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
Nelson Mandela-