A ssalamu’alaikum

PELINDUNG
Rektor Universitas Islam Indonesia PEMIMPIN UMUM RR. Ilmia A. Rahayu SEKRETARIS UMUM Dwisaptina DP BENDAHARA UMUM Dian Dwi Kurniawati PEMIMPIN REDAKSI Widiyanto
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI SF. Salam SEKRETARIS REDAKSI
Abdul Wahid Fauzie REDAKTUR PELAKSANA Sigit Pranoto, Atfas Ferry, R. Jimmy Pramana, Fajar Said REDAKTUR FOTO
Ujang Priatna STAF REDAKSI Fitriyan Zamzami, Ahmad Makhali, Heriyanto Citra Buana, Andi Priantoko, Sastrarum N. FOTOGRAFI
Indra Yudhitya, M. Ali Prasetya, Adhitya Awan, M. Isa.


RANCANG GRAFIS

Pandu Lazuardy P, Ponco Tristiyono. PENELITIAN & PENGEMBANGAN
Mulianne, Astutik, Firmansyah, Weka Swastika Wardani, M. Ulil Fahmi, Indiah Wahyu Andari, Solikhudin H. PUSAT INFORMASI &
Asriani P.I, Nugroho Nur Cahyo, M. Wahyu Gandewo PERUSAHAAN
Wawan

Basyori,
Nugraha
Bimaersy Putro, Riandaru Nugroho.
ALAMAT

TIDAK sedikit kawan yang menanyakan kapan HIMMAH akan terbit. Sudah sampai mana penggarapannya? Kenapa tidak (pernah) terbit tepat waktu? Ada yang lebih menyakitkan. Memang HIMMAH masih ada? Begitu pula dalam sebuah forum dengan rektorat. Ada yang bilang, HIMMAH sekarang, kalah jauh ketimbang HIMMAH di tahun 1980-an. Terbit rutin tiap bulan.
Ini kami akui. Tapi, masa-masa itu, sangat kontras ketimbang sekarang. Mulai dari sistim negara hingga kehidupan kampus. Di masa itu, lingkungan tempat HIMMAH berada, juga dalam kondisi top performance. Tidak jarang ditemui, debat bermutu dalam permasalahan sosial, hukum, maupun soal agama. Konon, masa itu, Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan salah satu kiblat pemikiran Islam moderen di Indonesia.
Bagaimana sekarang? Kami tidak bisa banyak berkomentar. Cukup banyak ‘penjara-penjara panoptik’ yang menyelimuti kehidupan kampus. Mulai dari absensi, wajib jilbab, aturan sandal jepit, hingga rencana penggusuran kantor lembaga mahasiswa di Cik di Tiro (salah satu di antaranya adalah kantor HIMMAH). Kampus dibikin senetral mungkin. Adem ayem. Tanpa demonstrasi, karena terlampau banyak mahasiswa yang secara sistemik dibikin study oriented. Kami tumbuh di tengah keprihatinan. Wallahu’a’lam.
Sidang Pembaca yang terhormat,
Soal majalah, kali ini, HIMMAH mengalami perubahan lumayan banyak dari edisiedisi sebelumnya. Perubahan itu tidak didasarkan pada metode trial and error semata. Bentuk penyampaian majalah kali ini didasarkan pergulatan konsep jurnalisme yang relatif baru. Kami menyakini pertanggungjawaban pada warga merupakan salah satu komitmen besar kami. Tiap reporter setidaknya menggunakan predikat ‘saya’. Sedikit mungkin memakai predikat ‘HIMMAH’ (seperti kebanyakan pada edisi-edisi sebelumnya). Alasannya: pertanggungjawaban wartawan kami pada warga. Liputan edisi perdana ini pun berusaha kami sajikan secara dinamis. Tidak kaku.
Adalah kedatangan Bill Kovach di awal Desember 2003 lalu yang bikin kami, mau tidak mau, harus melakukan evolusi dalam praktik jurnalisme selama ini. Sebelumnya, HIMMAH juga mendapat pengetahuan penting dari Dr. Violet B. Valdez, Direktur ‘Center for Journalism’, Universitas Ateneo Manila, Pilipina. Beliau mengenalkan gagasan Pyramid of Competence. Kontribusi keduanya merupakan bagian penting dari perjalanan HIMMAH edisi ini. Selamat membaca.
Wassalamu’alaikum
berupa artikel atau opini, diketik dua spasi, maksimal 4 halaman kuarto.
berhak mengedit tanpa mengubah esensi tulisan. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan sepantasnya.
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PERS MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Periode 2003 - 2004
M. Ali Prasetya/ HIMMAH
M. Isa HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
DATA
W. Saputro, Kurnia
Ardhi
S,
REDAKSI Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta 55223 Telp. (0274)542141 Pesawat 13 Faks. (0274) 563207 home page http://more.at/himmahonline e-mail himmah_media@mailcity.com Izin Terbit SK Menpen RI 1094/SK/Ditjen PPG/SIT/1987 ISSN 0216-4272 Percetakan NINDYA GRAFIKA Jl. Anggajaya I 180A, Condong Catur, Yogya karta (0274) 884126 ..........................
Redaksi menerima tulisan dari luar
Redaksi
IFTITAH REDAKSI
PeNAMBANGAN marmer yang berlokasi di Dusun Selorejo, Magelang, ternyata tak jauh dari sorak-sorai masalah. Warga di sekitar tempat penambangan merasa dirugikan. Perusahaan penggali marmer, yang kini di bawah kuasa PT. Margola, punya kesan tak ambil peduli. Padahal telah satu bukit habis dipapras dan rata dengan tanah. Bukit lainnya tinggal menyusul dan menunggu nasib sama. Bagaimana sebenarnya derita dan tuntutan warga terhadap hal ini?



Pe MBUKAAN lebar-lebar pintu pengelolaan air oleh swasta, patut dikritisi. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi air. Rakyat semakin dijauhkan aksesnya terhadap air (bersih). Bagaimana sebenarnya swasta melakukannya? Apa imbasnya bagi warga?
BAGAIMANA Suku Tengger memahami identitasnya sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas, selepas jalur-jalur transportasi membelah keter batasan lingkungan dan arus migrasi semakin tak tertahan? Apakah jejak leluhur yang tergurat di atas lembaran sejarah masa lalu Tengger akan terus terpugar? Bagaimana pula orang-orang Tengger mendalami keseharian yang terkadang tak berpihak lagi terhadap nilai-nilai kultural dan norma komunal?
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Air Mengalir Makin Menjauh... DAFTAR ISI EDISI I LAPORAN UTAMA.......(11) LACAK........(43) ’rang-orang Tengger LAPORAN KHUSUS....(78) Agama...............................................................................( 33 ) Bismillah............................................................................( 05 ) Budaya.............................................................................( 94 ) Dialog................................................................................( 72 ) ekonomi............................................................................( 69 ) Komentar....................................................( 31 ) Lensa..........................................................( 49 ) Media..........................................................( 62 ) Nasional......................................................( 08 ) Pendidikan..................................................( 41 ) Kulit Muka: Jeritan Bukit Menoreh
Seandainya Saya Menwa UII
ApA yang menimpa Resimen Mahasiswa (Menwa) UGM beberapa waktu lalu adalah catatan penting betapa terinternalisasinya pola kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh Menwa yang notabene bernaung di kampus berlabel agama. p ertanyaan kita, adakah agama yang mengajarkan bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah? Dan, yang paling mengesalkan lagi insiden yang dialami oleh Menwa UGM itu disanggah oleh Edi p rayudi selaku Komandan Menwa UII, sebagaimana dilansir Suara Merdeka (26/01/2004), dengan dalil ”tidak ada peng rusakan dan pemukulan.”

Sungguh luar biasa, di mana seorang Komandan Menwa yang seharusnya berkata bijak nan jujur, menebarkan berita bohong yang tidak pernah diajarkan oleh agama apapun. padahal di harian yang sama, jika Edi prayudi membaca media massa, yakni pada tanggal 23/01/2004 memuat insiden ini dengan judul ‘Markas Menwa UGM Diserang Menwa UII, 2 Orang Luka’. Republika menurunkan ‘Menwa UII Serang Menwa UGM’. Semen-tara Kompas memberikan judul ‘Markas Resimen Mahasiswa UGM Diserang’.
Dari sajian berita tersebut, pembaca setidaknya punya kesan bahwa apa yang disampaikan Edi p rayudi sangat tidak rasional, konyol dan memalukan. Akal sehat telah dibunuh. Celakanya, Edi tidak tahu bahwa argumen pembelaan saja tidak cukup. Karena kejadian Menwa UGM sedikit banyak mempunyai implikasi ne gatif, kalau bukan akan menghancurkan citra institusi pendidikan kampus UII yang dengan susah payah dibangun oleh para insan akademisnya. Hal inilah yang menurut tafsir penulis tidak diperhitungkan oleh Menwa UII.
Seandainya saya Menwa UII, saya tidak akan berbohong dan menolak model kekerasan sekaligus provokasi senior saya untuk melakukan penyerangan kepada Menwa UGM. Logikanya adalah hal itu tidak lazim digunakan oleh mahasiswa. Dan kalaupun harus berhadapan dengan Men-wa UGM, saya akan menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan persoalan. Apalagi saya masuk di wilayah UGM tanpa membuat izin tertulis kepada Rektor UGM maupun kepada Menwa UGM.
Maka sangat wajar jika mereka menegur dan bertanya kepada anggota Menwa UII yang berlatih di lembah UGM. Karena
mungkin, mengganggu aktivitas mereka. Di sinilah penting persoalan etika bertetangga dibangun. Karena saya yakin bahwa saya pun akan tersinggung apabila Menwa UGM latihan di wilayah UII tanpa pem beritahuan tertulis.
Berangkat dari pemahaman seperti ini, sekali lagi seandainya saya Menwa UII akan meminta maaf dan mengakui segala kesalahan yang dibuat anggotanya. Apa-lagi pembantu Rektor bidang Kemaha-siswaan UGM dan UII sudah sepakat. Dan kesepakatan itu, penulis ikut terlibat di dalamnya.
Muhtar Haboddin dan Naru Keluarga Menwa UGM Bulaksumur H 1, Yogyakarta
Info Beasiswa
SAYA ingin berbagi pengalaman mengenai tips/ tata cara pengajuan bea-siswa bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Sekarang saya mahasiswa S-2, program mahasiswa penerima B pp S (Be a -siswa pendidikan pascasarjana) di Universitas Udayana, Bali. Mungkin ada teman atau adik-adik dari mulai SD sampai perguruan Tinggi yang ingin mendapatkan beasiswa, silakan menghubungi alamat saya. Mudahmudahan saya dapat membantu. Di sam ping informasi-informasi lain yang sangat berguna.
Saya tunggu konfirmasi dari temanteman sekalian dan jangan lupa sertakan perangko balasan secukupnya.
KAMI menawarkan secara langsung kepada masyarakat umum, pelaku UKM dan koperasi berupa modal kerja dan penge m -bangan usaha. Juga bantuan beasiswa cuma-cuma dari jenjang SDS3, Diploma, p oliteknik bagi siswa/i, mahasiswa, peneliti, karyawan dan guru. Serta bantuan berupa buku dari pelbagai disiplin ilmu dan dana hibah bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM/LSM) lokal. Karenanya, bagi yang membutuhkan paket bantuan tersebut silahkan menghubungi kami melalui surat dan melampirkan tiga perangko kilat untuk balasan.
Dengan senang hati surat yang masuk akan segera kami tanggapi.
Andi Syamsuddin Ashar LEMBAGA INTAN PERSADA CORP. Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 1. Bulukumba, Sulawesi Selatan Po. Box. 81 IPC Bulukumba 92511 Sul-Sel.
Pendataan Alumni MUHIBBAH/ HIMMAH Penanggulangan Kemiskinan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
K AMI LpM HIMMAH UII saat ini sedang melakukan pendataan kembali para alumni MUHIBBAH/HIMMAH dari perio de 1967 hingga 2001.
Rencana ke depan kami akan mengadakan reuni keluarga besar MUHIBBAH/HIMMAH untuk ke seluruhan periode. Karena itu kami mengharapkan para pembaca yang saudara-kerabatnya alumni MUHIBBAH/HIMMAH dapat segera mengirimkan data pribadi dengan alamat terbaru.
Data dapat dikirim ke alamat L p M HIMMAH UII Jl. Cik Di Tiro no. 1 Yogyakarta 55223, faks. (0274) 563207 atau lewat e-mail himmah_media@mailcity.
com
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pusat Informasi dan Data
Sugianto Suryo Prayogo, S.P. (Mahasiswa S-2 Manajemen Agribisnis Universitas Udayana, Bali)
Jl. Tukad Banyusari No. 8, Sanglah, Denpasar, Bali.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 ASSALAMU’ALAIKUM

Bukan Negeri (dan Kampus) Tempat para Begal
SALAH

besar bila menyebut Indonesia sebagai negara paling korup se-Asia. Salah besar jika negeri asal seorang taipan yang pernah menyokong kampanye presiden Amerika Serikat ini dibilang menempati posisi enam terbawah dalam hal korupsi versi Transparancy International
Para aktivis, akademisi, atau para profesional, bisa jadi sedang lupa jika pernah mengatakan terjadi desentralisasi korupsi. Kalau dulu, di Orde Baru, korupsi berlangsung secara istana sentris, sekarang tidak lagi.
Tidak betul pula, partai yang eksis di masa Soeharto dituduh menerima uang miliaran rupiah tanpa peras keringat, seperti bagaimana para petani mengumpulkannya. Dan, jelas-jelas bohong, jika ada yang nyeletuk ada money politics di Senayan, atau di beberapa pemilihan kepala daerah: Bali, Jakarta, Jawa Tengah, atau Sumatera Selatan. Mungkin juga daerah lain di tanah air ini, yang disebut banyak media itu.
Bukanlah tergolong penebangan liar, apa yang sedang berlangsung di pedalaman hutan Kalimantan Selatan. Tapi adalah pengusahaan hutan.
Termasuk fitnah bila ada yang berkomentar banyak wartawan amplop di Jogjakarta--dan tentu di banyak kota lainnya. Pasti bohong jika telah terjadi pemukulan kepala pemimpin redaksi sebuah majalah kesohor. Terlebih di depan mata seorang kepala satuan kepolisian. Yang benar: tidak dipukul, melainkan cuma ditawarin sarapan!
Sama halnya mencemarkan nama baik, jika ada yang mem-beritakan seorang kakek ‘tahan’ berbuat mesum dengan beberapa karyawatinya. Padahal polisi saja, yang katanya paling berwenang, menegaskan buktinya tidak cukup.
Tak seorang pun akan berani berkata bahwa tentara tidak loyal pada negara--(baca: pemerintah). Demi terjaganya ‘persatuan dan kesatuan bangsa’. Hingga setiap usaha ‘separatisme’ pasti akan dibungkam. Memperpanjang darurat militer di Aceh, yang di awal berdirinya republik, sempat menghibahkan Meunasah. Sampai-sampai tidak diperlukan parameter kesuksesan darurat militer.
Mari meluangkan waktu melihat kondisi dalam kampus. Adalah kabar bohong, jika terjadi pencurian komputer berkalikali di kampus universitas Islam tertua di Indonesia ini. Tiga
kali dalam dua bulan, dua kali dalam tempo kurang dari dua puluh hari. Ironisnya, ada sebuah kampus yang mengalami tiga kali pencurian. Jika ditotal sedikitnya lima puluh komputer raib. Tapi sekali lagi perlu diingat, bisa jadi itu hanya kabar burung belaka.
Coba tengok sebentar. Siapa yang berhak mengatakan betul atau salah sebuah tindakan? Menetapkan betul-betul bohong atau bohong-bohongan betul seseorang itu dianggap maling? Siapa yang bisa bersabda hitam atau putihnya seseorang? Dan itu berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat? Dia tak lain adalah hakim, si waliyyullah. Sosok suci ‘pemilik pengadilan’. Oleh karenanya, tidak sedikit yang datang berduyun-duyun mencoba mencari keadilan.
Bisa jadi ceritanya terbalik. Beberapa peristiwa yang saya sebut di atas adalah secuil dari tumpukan kasus yang terjadi di negeri ini. Sangat ringkas di antara ribuan peristiwa buruk yang membentang. Jika benar seperti yang dituduhkan, maka si toga hitam pasti sudah menghukumnya. Tapi, buktinya?
Sebenarnya, Haryatmoko, seorang filsuf, pernah meng ungkapkan tentang hal ini. Menurutnya, lembaga peradilan --tentu termasuk oknum pejabatnya--menjadi lembaga yang melegitimasi ketidaksalahan seseorang. Tempat mencari kartu bebas dosa sosial. Menepis anggapan yang berkembang di masyarakat, bahwa ia telah menyengsarakan rakyat. Kasus seorang politisi senior adalah contoh paling hangat. Dan juga, pengampunan beberapa debitor nakal lewat kebijakan release and discharge.
Tentu tidak sulit untuk menyebut: ”baru diproses di pengadilan. Maka, hargailah itu..” atau ”sedang diurus polisi, jaksa, dan seterusnya..” Maka publik pun seperti terdiam.
Keadaan yang macam itu tidak menutup kecurigaan terjadinya persekongkolan tidak suci. Konspirasi antara yang tidak suci--para maling, koruptor atau preman--dengan yang sebenarnya suci dalam arti seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Salah satu alasannya, kata Prof. Satjipto Rahardjo, salah seorang pemikir hukum progresif, karena tercerabutnya moral dari hukum.
Inilah yang bikin negara (dan kampus) ini bukan tempat para begal
 Oleh WIDIYANTO
Pandu L. Patriari HIMMAH
Oleh WIDIYANTO
Pandu L. Patriari HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
.
Dari Malari Turun ke San -
BERBICARA perubahan dalam konteks Indonesia, maka tidak akan terlepas dari gerakan mahasiswa. Sejarah mencatat, perubahan yang terjadi di Indonesia selalu digerakkan oleh mahasiswa bersama rakyat. Misalnya, perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang didalangi oleh aktivis angkatan ’66, kasus penolakan modal asing Jepang tahun 1974, yang dikenal dengan sebutan Malari, sampai penjatuhan kediktatoran rezim soeharto atau reformasi. perubahan-perubahan di atas adalah bentuk penyikapan mahasiswa terhadap kondisi negara (suprastruktur) waktu itu. Bentuk kepedulian terhadap realitas lingkungannya.
Lahirnya kesadaran mahasiswa akan realitas lingkungannya itu tidak terlepas dari mudahnya mahasiswa untuk meng akses informasi yang berkembang, tidak seperti masyarakat umumnya. Dengan informasi, mahasiswa sadar akan makna sebuah penindasan dan ketidakadilan. Yang akhirnya melahirkan naluri per-lawanan, sebagai respon terhadap penin-dasan dan ketidakadilan yang diterimanya. ”Hal ini juga tidak terlepas dari posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang netral,” ujar Ade Achmad Faidulloh, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Univer sitas Islam Indonesia (UII). ”Di samping itu, mahasiswa adalah masa-masa transisi
dari kepentingan,” kata Ade melanjutkan. Melihat peranan mahasiswa yang signifikan dalam setiap perubahan me lahirkan ketakutan-ketakutan bagi rezim pemerintahan yang berkuasa. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh penguasa untuk membelenggu dan meredam per golakan mahasiswa, baik dengan intervensi langsung ke kampus atau lewat kebijakankebijakan yang memberatkan mahasiswa. pada masa Orba, lahirnya kasus Malari sebagai bentuk penolakan terhadap ma-suknya modal asing akhirnya berbuntut pada keluarnya kebijakan penguasa Orde Baru tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kem a hasiswaan (BKK). Lahirnya NKK/BKK berbuntut pada perombakan sistim pendidikan dan kelembagaan Dewan Maha siswa (Dema). Konsep Dema diganti, sistim pendidikan dirubah, aturan drop-out (DO) lahir. Dengan lahirnya NKK/BKK di bawah rezim kediktatoran Soeharto, maha-siswa tidak bebas untuk berbicara, berpolitik, apalagi melakukan kritikan terhadap peme rintah. Ini salah satu bentuk ke kerasan negara terhadap rakyatnya.

Lantas bagaimana dengan Orde yang katanya Reformasi ini? Apakah kekerasan dan pengekangan terhadap mahasiswa telah usai? Menurut Ade, pengekangan terhadap mahasiswa pada masa Orba sampai Orde
Reformasi tidak ada yang berubah.”NKK/ BKK kan enggak ada yang dicabut, aturan presensi masih ada,” jelasnya.
Tak hanya itu. Sekarang, terdapat banyak aturan yang menimpa mahasiswa di kampus. Bentuknya beraneka ragam pada tiap-tiap kampus. Seperti lahirnya Kode Etik Mahasiswa (KEM) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. p emberlakuan presensi 75 persen yang ketat sebagai syarat mengikuti ujian di Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (MIpA) dan di beberapa fakultas lainnya di UII, termasuk Fakultas psikologi. pemberlakuan jam malam dalam penggunaan sekretariat unit kegiatan mahasiswa (UKM) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
* *
KODE Etik Mahasiswa adalah sekum pulan aturan yang mengatur tentang mahasiswa dan tidak terkait dengan studi. Seperti tata cara berpakaian dan batasan penggunaan jam kantor UKM. Di tingkatan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, KEM sebenarnya masih menjadi polemik. Bebe rapa kali mahasiswa melakukan demon s -trasi menentang pemberlakuan KEM. Seperti aksi yang dilakukan oleh Forum Mahasiswa Dua Ribu Tiga (FORMAGA)
Oleh FAJAR SAID
Kreativitas dan nalar kritis mahasiswa yang terus saja diancam dan
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 KEMAHASISWAAN
*
Adhitya Awan / HIMMAH
yang salah satu tuntutannya adalah menolak KEM.
Adapun permasalahan yang sangat pelik dalam KEM tersebut adalah adanya aturan-aturan seperti, batasan jam buka kantor lembaga kemahasiswaan yaitu dari jam 07.30 pagi sampai jam 21.30. Hal lain yaitu tata cara dalam hal berpakaian seperti larangan untuk berambut gondrong, pakai kalung, gelang, anting, celana sobek, dan kaos oblong.

Menurut Munir ‘Che’ Anam, presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), lahir nya KEM di IAIN Sunan Kalijaga di-putuskan sepihak oleh Senat Institut, dengan berlandaskan peraturan pemerintah (pp) nomor 60 tahun 1989.
Ia menandaskan, ”lahirnya KEM sejalan dengan perubahan IAIN menjadi Univer sitas Islam Negeri (UIN). Hal ini tidak terlepas dari kepentingan neoliberalisme ketika ingin menjadikan kampus sebagai pasar kerjasama.”
”Kalau tidak menginginkan adanya Kode Etik Mahasiswa, maka harus men cabut pp nomor 60 tahun 1989. Karena landasannya di sana.”
pihak Rektorat memang tertutup dalam membuat keputusan tentang KEM. Hal ini diakui oleh DR. Ismail Lubis, pembantu Rektor III, ketika ditanya tentang proses rembug b a reng antara Rektorat dengan mahasiswa. ”Belum ada (rembug ba-rengred), dan kami juga tidak mem-buka pintu lebar-lebar untuk itu karena pe-ngalaman selama ini dikasih hati, minta rempelo,” tandasnya.
Munir menilai, ada kesamaan antara NKK/BKK dengan KEM. ”Saya lihat sama-sama untuk memberangus kreativitas mahasiswa, dan mahasiswa dibelenggu oleh aturan-aturan yang mengikat,” ujar-nya.
DR. Ismail Lubis, mengatakan bahwa lahirnya KEM adalah untuk menertibkan kesemrawutan peng-gunaan kantor UKM. Di samping itu adanya mahasiswa yang berpakaian yang tidak semestinya menurut agama, seperti pakaian wanita yang tembus pandang, transparan. Hal lain yaitu adanya mahasiswa laki-laki yang memakai tatto, anting maupun celana sobek. ”Inikan sangat tidak layak, apalagi mahasiswa IAIN Sunan Klaijaga,” katanya.
Menurut Ismail Lubis, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam KEM masih ditoleransi, karena masih dalam proses sosialisasi. ”Tidak d iber-lakukan semuanya,” jawabnya ketika ditanya tentang pemberlakuan KEM.
”Akan tetapi ada beberapa aturan yang akan ditindak tegas apabila terjadi pe-lang-
garan, seperti pakai sandal dan anting,” kata Lubis.
”Larangan pakai anting, sandal, itu yang utama. Baik dosen di kelas maupun karyawan tidak akan melayani mereka yang pakaiannya tidak sesuai dengan kode etik. Tegas, saya pun begitu jika ada mahasiswa yang pakai sandal.”
Sampai saat ini pemberlakuan KEM masih belum berjalan efektif. Sebagian mahasiswa masih ada yang berpakaian kaos oblong, pakai anting dan berambut gondrong. Dan kantor UKM masih tetap buka tanpa ada batasan jam tutup seperti yang terdapat dalam KEM. Meski KEM sudah mulai diberlakukan sejak 1 September 2003. Bisa jadi ini merupakan salah satu bentuk penolakan mahasiswa terhadap pemberlakuan KEM.
* * *
S EDANGKAN di UII, terdapat b e berapa fakultas yang sangat ketat dalam menerapkan presensi 75 persen sebagai persyaratan dalam mengikuti ujian semes ter. Seperti di Fakultas MIpA, dan psikologi. Sementara di beberapa fakultas lainya lebih ‘lunak’. Tapi banyak dosen yang pen-ilaiannya didasarkan pada jumlah keha-diran alias presensi di kelas. Bukan pada kema m puan peserta didik dalam memahami mata kuliah yang di-ajarkan.
Kebijakan presensi ini sebenarnya melahirkan pro-kontra di tingkatan maha siswa. Ada mahasiswa yang setuju dan ada yang menolak. Dan sebelumnya telah terjadi aksi yang dilakukan oleh sebagian maha-siswa Fakultas MIpA untuk menolak kebijakan presensi tersebut.
Jaka Nugraha, M.Si, Dekan Fakultas MI pA
dan indeks prestasi (Ip) semester maha siswa yang cukup baik.
”Dari hasil angket yang disebarkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia menghasilkan mayoritas mahasiswa men dukung kebijakan itu,” aku Jaka Nugraha.
Sebagian mahasiswa yang tidak setuju dikarenakan alasan ada aktivitas di luar. Dan pihak fakultas, tambah Jaka, akan mem-berikan ijin bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan resmi atau sakit.
Suryani, mahasiswa Fakultas MIpA jurusan Farmasi, menilai kebijakan presensi ada sisi positif dan negatifnya. Sisi posi tifnya adalah mahasiswa jadi terpacu untuk hadir kuliah. ”Akan tetapi sisi negatifnya yaitu ada mahasiswa yang nggak bisa hadir seperti lagi Kuliah Kerja Nyata (KKN) sementara mereka tidak boleh ijin. Dan tidak semua dosen mau memberikan ijin bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan di lembaga kemahasiswaan,” kata Suryani.
Lain halnya dengan Merdeka Ita. Mahasisiwi FH ini menilai lahirnya kebijakan presensi lebih disebabkan oleh faktor ketidakcakapan dosen dalam mengalhkan ilmu kepada peserta didiknya.
”Seharusnya menekankan kualitas dosen dari absensi,” sarannya.
Merdeka juga mempertanyakan tentang aturan dan sanksi bagi dosen yang tingkat kehadiran mengajarnya rendah. ”Apakah ada aturan yang mengatur dosen? Lantas bagaimana dengan tanggung jawab seo rang dosen?” ujarnya menutup pe m bicaraan.
mengatakan, lahirnya kebijakan presensi 75 persen merupakan keputusan di tingkat universitas. Akan tetapi i m plementasinya di tiap-tiap fakultas bersifat kondisional. Dan yang pertama kali mem berlakukan kebijakan presensi te r sebut adalah Fakultas psikologi dan MIpA.
Menurutnya, kebijakan presensi telah melahirkan hasil yang positif pada maha siswa. Seperti proses belajar mengajar, kehadiran dosen yang semakin meningkat
yang jelas de-ngan kondisi terkekang, mahasiswa tidak dapat mengaktualisasi kreativitasnya.
Pandu L. Patriari HIMMAH
Apapun jawabannya,
��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 KEMAHASISWAAN
Cermin Retak Buat Parkir
Naiknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun telah menimbulkan masalah pada ruang parkir. Butuh sistem penataan yang bijak untuk mengatasinya.
Oleh R. JIMMY PRAMANA
BARISAN
kendaraan bermotor itu berjejer rapat di bahu jalan. Hanya dipisahkan sebuah ruas jalan seukuran satu setengah meter. Tampak seorang petugas parkir lalu-lalang untuk membenahi letak parkir kendaraan agar leluasa untuk keluar masuk. Entah berapa kali dia menyeka keringat yang bercucuran di dahinya. ”Iki rada (ini agak-red) repot, Mas. Tunggu sebentar lagi,” tukasnya ketika saya mencoba untuk mengajak ngobrol. Setelah memberikan karcis pada pengendara yang baru datang dan merapikan barisan parkir, barulah ia mau berbincang.
”Maklum hari libur. Banyak orang yang datang ke Malioboro untuk berbelanja atau lihat-lihat,” ujar Haryono, 32 tahun, salah seorang petugas parkir di bilangan Jalan Malioboro. Haryono telah menjalani profesi sebagai petugas parkir dalam kisaran dua tahun ini. Ia mengakui harus bekerja keras bila hari libur.
”Saya harus siap terus. Sekalian ngatur kendaraan yang mau diparkir. Kadangkadang orang markir-nya sembarangan,” keluhnya sembari menerangkan bagaimana pekerjaannya mengatur parkir kendaraan bermotor.
Sudah jadi rahasia umum, jika Jalan Malioboro yang membentang di jantung Kota Jogjakarta ini sarat akan permasalahan lalu-lintas. Di antaranya kemacetan dan parkir. Bandingkan dengan era tahun 1970an, sepeda merupakan alat transportasi massal yang mayoritas lewat Malioboro. Jauh beda dengan kondisi sekarang.
Memang tak dapat dipungkiri bahwa alasan utamanya adalah makin pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertambahan kendaraan bermotor. Ruang kosongruang kosong yang dulu banyak tersisa di Malioboro, kini banyak digunakan untuk aktivitas perdagangan.
Tentu ini berpengaruh pada penyediaan ruang parkir. pemkot Jogjakarta sebenarnya sudah menyediakan area parkir di bagian utara Jalan Maliboro, Taman Abu Bakar Ali. Sedangkan, di bagian selatan juga ada Taman p arkir Bank Indonesia dan area parkir di sekitar pasar Beringharjo. Namun melihat dari pemanfaatannya, terasa kurang optimal. Taman parkir Abu Bakar Ali dan Taman p arkir Bank Indonesia banyak
dimanfaatkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus. Sedang, motor roda dua jarang yang menempatinya. padahal bila melihat dari kuantitas jumlah kendaraan di Jogja, kendaraan roda dua merupakan alat transportasi terbanyak. ”Kalau motor (roda dua-red) jarang yang mau parkir di sini. Masalahnya tempat parkir terletak di bagian ujung jalan. Saya sendiri malas kalau nanti harus berjalan lagi,” papar Budi, salah seorang pengguna jasa parkir.
Ketiga tempat parkir itu berada di ujung Jalan Malioboro. perlu bolak-balik untuk kembali ke salah satu tempat parkir tersebut. panjang Jalan Malioboro kurang-lebih satu kilometer. Bolak-balik berarti harus me nempuh dua kilometer. Tampaknya hal inilah yang bikin para pengguna motor enggan memarkir kendaraannya di area parkir tersebut.
Bisa jadi karena keterbatasan area parkir yang ada, membuat para pengelola perparkiran terpaksa menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai area parkir. Gejala itu tidak semata hanya di Jalan Malioboro. parno, 35 tahun, petugas parkir di pasar Kranggan mengatakan bahwa sangat sulit bila tidak menggunakan trotoar atau badan jalan. ”Kita harus menggunakan tempat yang mana, Mas? Yang penting kita bisa men g atur dengan baik dan orang pun merasa cukup tenang bila kendaraannya ada yang menjaga,” lanjutnya. Selama ini dia belum pernah mendapatkan komplain tentang penggunaan badan jalan maupun trotoar sebagai area parkir.
Yadi, 25 tahun, salah seorang petugas parkir di Malioboro mengaku pernah mendengarkan ada pengguna jalan yang mengeluh tentang ruang gerak para pejalan kaki yang semakin terbatas oleh adanya parkir kendaraan. ”Saya mendengarnya ketika mereka sedang berbicara. Walaupun tidak disampaikan secara langsung kepada saya,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa di Malioboro, trotoar jalan diperbolehkan sebagai area parkir oleh pemda. Namun mobil tidak diperbolehkan untuk memarkir kendaraannya di trotoar Malioboro.
”Di sana kok ada mobil yang parkir?” tanya saya. Sambil melirik, Yadi sesekali menghisap rokok kretek di tangannya. ”Itu
kerjaannya oknum.” Tak jelas siapa yang dimaksud oknum. Ia tak mau menjelaskan lebih lanjut.
p emanfaatan parkir yang lebih cen derung on street atau menggunakan area parkir di badan jalan inilah yang me-nyebabkan bertambah ruwetnya per masalahan lalu-lintas di Jogja. Sangat sedikit pengelola parkir yang menyediakan lahan parkir atau off street. Dan tentu saja berkurangnya badan jalan yang seh a rusnya dimanfaatkan oleh para pengguna kendaraan dalam menempuh perjalanan menimbulkan dampak k e macetan lalulintas.
* * *
HERU SUTOMO, M.Sc, Kepala Dewan peneliti di pUSTRAL (pusat Studi Trans portasi dan Logistik) Universitas Gadjah Mada (UGM) membenarkan tentang ru wetnya permasalahan parkir di Indonesia, khususnya Jogja. ”pengembangan pusat perekonomian baru seperti pembangunan mal dan pusat perbelanjaan untuk m e ngurangi arus pengunjung yang kemudian berhubungan dengan parkir tidak efektif. Hal ini dipengaruhi dari tipe masyarakat kita. Semakin banyak pusat ekonomi yang baru, semakin banyak pula cost yang dihabiskan oleh masyarakat. Dan hanya menyedot masyarakat di sekitar daerah itu saja,” lanjut Heru.
Selain berkaitan dengan tata ruang, masih banyak permasalahan parkir lain yang cukup krusial untuk diperhatikan: soal tarif, tentang kewajiban penggantian hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir.
”Dalam pemecahan permasalahan perparkiran, ada dua solusi yang menurut saya, bisa digunakan. pertama, menambah lahan parkir. Lalu yang kedua m e ng e lolanya,” ujar Heru Sutomo.
penyelesaian masalah yang pertama, Heru melihat sebuah hal yang kurang efektif untuk dilakukan. p enambahan lahan parkir dinilai belum efektif karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Heru, langkah strategis yang harus di-lakukan adalah dengan membenahi pe ngelolaan. Kalaupun ingin menaikkan tarif parkir, tetapkan saja dengan harga yang sangat tinggi.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
NASIONAL
”Sekalian saja harga parkir ditetapkan Rp. 50.000. Hal ini dilakukan agar ada pembelajaran dalam mengoptimalkan perjalanan keluar bagi para pengguna kendaraan,” tandasnya. Namun untuk menuju hal itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. pemerintah juga harus menyediakan sarana pendukung seperti lancarnya akses kendaraan umum untuk dipergunakan bagi masyarakat. Hal ini menurut Heru merupakan satu langkah yang cukup logis untuk dilakukan.
Dalam melihat permasalahan parkir, Heru melihat ada unsur yang terlupakan. Dalam pembagian tarif parkir yang per sentasenya 60-40, 60 persen untuk p e merintah dan 40 persen untuk pengelola parkir, tetap saja memberatkan para pe ngelola parkir. Apalagi bagi para petugas parkir yang ada di lapangan. Hal ini disebabkan pada adanya setoran-setoran lain pada pihak tertentu. ”Sebenarnya 40 persen itu cukup bagi petugas parkir. Namun karena adanya setoran pada para ‘mafia’, makanya jadi tidak cukup,” tukas Heru.
Kehadiran para ‘mafia’ ini dinilainya
seperti bayangan. ”Kita tidak bisa m e lihatnya dengan jelas. Sehingga bila kita ingin menembaknya, ada kemungkinan salah sasaran.”
Lebih lanjut, Heru merasakan perlunya menghadirkan pihak ketiga ini—selain pemerintah dan pengelola parkir—dalam membicarakan mengenai pembagian hasil. Bukankah ini sama saja mengakui eksistensi para ‘mafia’ di dunia perpakiran? Kenapa tidak dilakukan saja tindakan tegas, misal pemberantasan ‘mafioso’ ini?
Secara umum, masalah perparkiran ini menimpa di kota-kota besar di mana pun. Bukan hanya menimpa Kota Jogja saja. Di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Ban dung dan Surabaya pun mengalaminya. Kota yang setidaknya menjadi sentrum kegiatan ekonomi, industri maupun politik. Kota metro-megapolitan.
Dr. Harun Al-Rasyid Lubis, M.Sc, staf pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi perparkiran di Bandung. Dalam tulisannya yang berjudul Strategi dan Kebijakan Tata Ruang dan Tran s
portasi Tatar Bandung 2020 , ia m e ngajukan beberapa solusi. Antara lain dengan menguatkan pelayanan tran s portasi untuk mengurangi jumlah peng gunaan parkir. Hal ini, menurutnya, kembali menjadi sebuah pertanyaan bagi pihak pemerintah Kota (pemkot) Bandung dan juga pemkot-pemkot di kota lainnya: sudah adakah kesiapan untuk menuju ke arah sana?
Tentu saja permasalahan-permasalahan ini semakin menambah rumit bagi jalannya kehidupan. Juga bagi pedestrian yang tentu mengharapkan adanya kenyamanan dalam menggunakan haknya sebagai pejalan kaki.
Saya pernah iseng menanyakan masalah ini pada seorang pejalan kaki di Jalan Malioboro. ”Apa yang Anda sangat harapkan sebagai pejalan kaki?”
”Kenyamanan bagi para pejalan kaki. Dan juga (untuk) orang-orang cacat,” katanya.
 HIMMAH
Petugas Parkir. Banyak yang memanfaatkan sebagian badan jalan untuk jasa parkir.
HIMMAH
Petugas Parkir. Banyak yang memanfaatkan sebagian badan jalan untuk jasa parkir.
��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 NASIONAL Adhitya Awan /

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 MR. X Pandu L. Patriari / HIMMAH
Air Mengalir Makin Menjauh...
AIR merupakan barang publik yang jumlahnya terbatas. Keberadaannya menyangkut hajat hidup seluruh makhluk hidup di planet ini.
Kerawanan atas air sangat memungkinkan terjadinya protes sosial yang luar biasa. Karena air juga menyangkut urusan duniawi dan ukhrawi (macam: wudlu, ritual di Sungai Gangga). Sembilan tahun yang lalu, Wakil presiden Bank Dunia, Ismael Seralgedin, pernah berkomentar tentang hal ini. Bahwa, perang selanjutnya adalah perang Air. Fakta miring itu, kini telah mendunia.

Di Indonesia, pasca pengesahan Undang-undang Sumberdaya Air, keberadaan air makin jadi persoalan. Lantaran pengesahan praktikpraktik komersialisasi maupun privatisasi air oleh negara. Tak ayal akan melanggengkan diskriminasi akses terhadap petani, kaum miskin kota, dan mereka yang ‘kalah’ oleh struktur sosial. padahal air seharusnya dikelola lembaga publik yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak oleh perusahaan swasta, yang berorientasi komersial.
Komodifikasi air oleh swasta, sebenarnya dapat dilihat dalam beberapa bagian. Tulisan panjang berjudul Pengusahaan Air, Proyek dan PDAM berisi anatomi mengenai hal itu. Bagaimana swasta telah memainkan perannya dalam pengelolaan air di Indonesia, yang secara sistematis bikin sebagian besar warga kesulitan akses terhadap air.
Tulisan kedua, Menengok Air di Negeri Seberang, merupakan potret beberapa negara yang telah menyerahkan pengelolaan airnya pada swasta. Gejolak sosial di Cochabamba, sogok di perancis, krisis air bersih di Himalaya. Gambaran yang menunjukkan ekspresi warga akibat privatisasi air.
Terakhir, Kedatanganan yang Tak Diharap, sebuah laporan peristiwa lokal Jogjakarta. Di mana telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara pemprop DI Jogjakarta-Amiwater, perusahaan air minum dari Arab Saudi, dalam perjanjian penyediaan air bersih. Kerjasama yang layak untuk dihentikan.
Semuanya adalah fakta di mana Air Mengalir Makin Menjauh...
Yudhitya
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
Widiyanto Indra
/ HIMMAH
Pengusahaan Air, Proyek dan
Masuknya swasta dalam persoalan air di dalam negeri. Oleh WIDIYANTO
SIANG, 26 Oktober 2003. Sehari menjelang puasa Ramadhan. Ribuan orang memadati puluhan mata air yang tersebar di kota Klaten, demi menjalankan ritual padusan . Mensucikan diri dengan cara mandi atau merendam badan.
Di kawasan Janti, luar kota Klaten, banyak orang rela antri menunggu giliran mandi. Dari anak-anak hingga orang yang sudah berumur memadati jalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Yang naik motor, knalpotnya menyembulkan asap sengak. Belum lagi sinar matahari yang menyengat. Umpatan keluar dari mulut orang yang tak sabar.
”Neraka bocor,” kata seorang pemuda. p ekikan keras itu disambut deru tawa kawan-kawannya. Umur mereka tak lebih dari 25 tahun.
Setengah jam lebih terjebak dalam kemacetan. Cukup untuk memutuskan putar haluan. Tak tahan antri yang tak jelas kapan akan sampai. padahal tempat yang saya tuju hanya berjarak kurang dari seratusan meter. Sebuah bangunan yang banyak dibicarakan warga. Terutama kalangan petani. pabrik pT Tirta Investama, pro–dusen air dalam kemasan ternama, Aqua
Ukurannya sangat besar. Banyak sisi bangunan belum dilapisi semen. Hanya sebagian yang beratap. Tanda belum seratus persen jadi. Sekelilingnya lahan pertanian yang kering kerontang. ”Dulu bangunan itu juga sawah,” kata Suradi, pemilik warung di depan bangunan itu. Menurutnya, bangunan itu baru dibikin sekitar dua tahun yang lalu.
Tampak lalu lintas di depan pabrik tersebut lumayan ramai, karena letaknya cukup strategis. Antara kawasan Janti yang terkenal dengan area pemancingannya, dengan jalan raya Jogja-Solo. Tepatnya di daerah Wangen.
Itu hanya pabrik pengemasannya saja. Mata air atau umbulnya tidak di situ. Jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik. Sekitar dua kilometer. Untuk mencapai lokasi, harus melewati jalan kampung selebar 2,5 meteran. Berkelok-kelok. Ter–letak di wilayah ponggok, Sigedang, Kecamatan p olanharjo, Kabupaten Klaten.
Di samping ada mata air yang di–manfaatkan Aqua, di lingkungan umbul
ini terdapat dua mata air lainnya. Warga menyebutnya Umbul Sari. Keduanya di bawah pohon beringin yang lebat. Sedang, umbul yang dipakai Aqua , terletak di persawahan yang menguning.
Sebelum memasuki Umbul Sari ini, saya dihentikan oleh sekelompok warga. Mereka minta ‘retribusi’ pemandian. Besarnya Rp 1.000 per orang. Terpampang jelas di papan tulis di pintu masuk. Hal yang sama dilakukan warga di umbul-umbul sekitar.
”Maaf, ini benar Umbul Sari?” tanyaku.
”Benar. Saya ganti namanya, mas,” kata seorang warga. ”Sekarang jadi UmbulAqua.” Tentang ini pun tertulis di papan di pintu masuk.
‘Umbul-Aqua’ tertutup bagi warga. Di lokasi terdapat rumah kecil yang terkesan mewah. Tepat berada di atas keluarnya mata air. pagar kawat melingkarinya. Air yang keluar lantas dialirkan melalui pipa yang terpendam di bawah tanah menuju ke lokasi pabrik pengemasan di Wangen.
”Sekarang daerah sini sudah mengalami perubahan, mas,” kata seorang warga sekitar. ”Kalau dulu kelihatannya alami. Ada arcanya segala,” tambahnya. pendirian pabrik air kemasan di Klaten ini merupakan rencana perluasan pe–rusahaan air minum Aqua. Sebagaimana dikutip dari Suara Merdeka , Direktur Industrial p T Tirta Investama, kala itu masih dijabat Willy Sidharta, menegaskan bahwa pihaknya menginvestasikan lebih dari Rp 200 milyar untuk pembangunan pabrik di Klaten ini. Tahap pertama, mereka akan menginvestasikan Rp 142 milyar, dan tahap kedua sebesar Rp 90 milyar.
polanharjo kabupaten Klaten, tempat pengambilan air oleh Aqua tergolong dataran agak tinggi. Lebih tinggi dibanding wilayah Klaten lain seperti Ceper, atau perkotaan sekalipun. Untuk itu pada awal Januari 2002, wakil dari Aqua tersebut menjanjikan kepada publik: tidak akan mengganggu kebutuhan penduduk di daerah Klaten yang agak rendah.
”pabrik itu akan memanfaatkan debit air 45 liter per detik, dan menurut survai pengambilan itu tidak akan mengganggu air yang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Sebab, di lokasi pabrik terdapat beberapa mata air yang berdebit 500-1.500 liter per
detik,” katanya.
Rasanya tidak mungkin demikian. Air mengikuti gerak gravitasi bumi. Dari hulu ke hilir. Dataran tinggi menuju ke wilayah yang lebih rendah. pengambilan air—yang berada di daerah atas—akan berpengaruh pada daerah bawah. Hukum alam pun berlaku.
Ini termasuk salah satu teori atau prinsip umum berkaitan dengan air yang dikenal dewasa ini. Disebut teori aliran air alamiah. Ada juga yang menyebutnya sebagai integritas teritorial. Artinya, bahwa mata air yang merupakan bagian dari teritorial suatu daerah, maka pemilik daerah yang lebih rendah sebenarnya juga memiliki hak atas air. Tanpa dirintangi oleh pemilik daerah yang lebih tinggi. prinsip ini dipakai untuk pengelolaan air di kebanyakan negara kesatuan.
Ketiga teori tentang air lainnya adalah teori kedaulatan teritorial, teori pembagian yang adil dan teori kepentingan komunitas. Kumpulan teori ini dikemukakan oleh Vandhana Shiva dalam Water Wars
Teori aliran air alamiah tampaknya tidak berlaku bagi Umbul-Aqua.
Sadono, petani asal Desa Borongan, p olanharjo mengatakan bahwa setelah beroperasi dua tahun terakhir ini, debit air untuk pertanian sudah dirasakan menurun, terutama di daerah hilir pada musim-musim kemarau. Sehingga dengan demikian bu–didaya tanaman tidak bisa maksimal. Akibatnya, penghasilan petani baik secara kuantitas maupun kuyalitas telah merosot.
”Dampak langsung terhadap petani tidak ada. Tapi, secara tidak langsung ada,” kata Ipung, aktivis Indonesian Forum on Globalisation (Infog) Solo. Sebuah lem–baga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkonsentrasikan kajiannya pada ma–salah air.
”Dulu mereka (petani) mendapatkan air dari Sigedang karena ada pabrik gula (pG) Ceper yang mengambil air dari sana. Tapi, sekarang pG Ceper berhenti produksi. Terus bagaimana nasib mereka?” katanya.
Mata air di Klaten ini merupakan salah satu dari belasan mata air yang sudah dimiliki Aqua . Bahkan, mata air di pandaan, Jawa Timur lisensinya telah diberikan kepada pT Tirta Jayamas Unggul. Begitu pula mata air milik Aqua di Mambal, Bali telah diberikan kepada p T Tirta
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Dewata Semesta.
Menurut sejumlah laporan, Aqua seka–rang menempati urutan wahid dalam urusan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia. Willy Sidharta yang sekarang menjabat presiden Direktur (presdir) p T Aqua Golden Missi–ssipi pernah mengklaim Aqu a menguasai 50 persen pasar domestik. ”pasar 50 persen ini equilibrium. Kita tidak boleh turun dari 50 persen ini,” katanya.
Omzet penjualannya terus merangkak naik. Berdasar laporan tahunan, tahun 2000 perusahaan ini berhasil menjual 1,57 milyar liter air. Tahun berikutnya lebih men–cengangkan: 2,36 milyar liter air!
Indikasi yang memperkuat argumen tersebut antara lain berubahnya mode cara minum masyarakat kebanyakan. Dulu, masyarakat minum air dengan tempayan atau periuk-periuk tradisional. Hadirnya AMDK membuat identitas kelas tersendiri di kalangan masyarakat. Keberadaanya menjadi trendsetter . Kebanyakan orang lantas beralih ke identitas baru tersebut.
Aqua juga menggunakan branding campaign : ‘minum air delapan gelas sehari’. Istilah yang digunakan untuk
keperluan kampanye mereknya. Menum–pang slogan kesehatan: minum air tujuh gelas sehari.
Aqua pertama kali digagas oleh al–marhum Tirto Utomo. Seorang pengusaha yang pernah malang melintang di pertamina di tahun 1960-an. pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perminyakan.

Di pebruari 1973, ia mendirikan pT Golden Mississipi sebagai produsen Aqua. Menurut website resminya, Aqua tidak ditanggapi positif masyarakat di awal kehadirannya.
”periode 1974-1978 merupakan periode sulit. perusahaan berusaha bertempur habishabisan untuk mengelakkan pe–rusahaan dari kebangkrutan.”
Tirto Utomo punya usul untuk meng–atasinya. Dengan menaikkan tarif untuk menutup cost production recovery. Ini baru impas di tahun 1978.
”Semua bernafas lega.”
pada 1 Maret 1990 perusahaan ini pun go public. Namanya ditambah dengan kata ‘Aqua’ di muka nama perusahaan lama. Menjadi pT Aqua Golden Mississipi. Ini
merupakan konsekuensi logis dari aturan legal tentang perusahaan. Tidak boleh menggunakan nama sama atau mirip. publik harus dibolehkan dalam penyertaan modal berupa kepemilikan saham.
Sebelumnya, di tahun 1987, sebuah langkah agresif ditunjukkan Tirto Utomo. Yakni, dengan mengakuisisi perusahaan sejenis. pT Varia Industri Tirta, produsen AMDK bermerek Vit p ernah mencuat dengan iklan: Olala.. Klaimnya, total produksi Vit sekarang mencapai 287 juta liter per tahun. Bisa jadi ini adalah merek kedua, setelah Aqua Tahun 1994, dibentuk perusahaan baru di bawah bendera pT Aqua Golden Missi–ssipi. Bernama pT Tirta Investama yang populer dengan sebutan Aqua Group. perusahaan baru ini lantas tampil sebagai pemilik saham terbesar pT Aqua Golden Mississipi. Sekitar 75,3 persen. Sisanya dimiliki publik.
p erusahaan raksasa asing, ‘Danone’ tampaknya melihat Indonesia sebagai pasar air yang potensial. ‘Danone’ merupakan perusahaan multinasional berpusat di perancis. Bergerak di bidang diary pro–duct,
Salah Satu Mata Air Sigedang. Tempat pengambilan mata air Aqua berada di balik pagar besi itu.
Indra Yudhitya
/ HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
LAPORAN UTAMA
bottled water, dan biskuit. per–usahaan ini mengklaim mendominasi 15 persen pasar dunia untuk diary product
Begitu pula untuk kategori produk air minum dalam kemasan lewat Evian, Volvic, dan Badoit.
Mengapa ’Danone’ memilih Asia? Kenapa tidak belahan dunia lainnya? Jika di Asia, kenapa tidak mendirikan pe–rusahaan sendiri? Tapi justru membeli perusahaan lokal. Apakah ini termasuk strategi ekspansi mereka? Ini menjadi bahan pertanyaan tersendiri.
Ignas G Sidik, pengajar senior sekaligus ketua riset prasetiya Mulya Business School punya analisa tentang ini. ”Sebab, pasar di benua (Asia) itu, dengan jumlah penduduk yang berlimpah, masih men–janjikan pertumbuhan sebesar 11 persen untuk AMDK-nya,” komentarnya se–bagaimana dikutip dari Warta Ekonomi
”Bandingkan dengan pasar Eropa yang hanya bisa menawarkan pertumbuhan 3 persen.”

Untuk itu ‘Danone’ dikabarkan mulai melakukan pembelian perusahaan AMDK di beberapa negara Asia. Dimulai aksi pembelian dua perusahaan air mineral di Cina, lalu perusahaan air minum di Si–ngapura. Begitu pula di Indonesia.
Dan benar. ‘Danone’ telah melakukan perluasan bisnisnya di Indonesia. Hal itu dibuktikan lewat pembelian 40 persen saham milik pT Tirta Investama, produsen Aqua. Terjadi pada 1998. Saat di mana nilai penjualan bersih maupun net income-nya mengalami kenaikan tajam.
Tampaknya situasi politik Indonesia yang memanas, kala itu, tidak berakibat bu–ruk bagi bisnis Aqua . Malahan sebaliknya.
p roses pembelian saham p T Tirta Investama oleh ‘Danone’ ini dilakukan oleh Feddian pte Ltd. perusahaan yang didirikan berdasar hukum Singapura kepunyaan Danone Asia Ltd Singapore. perusahaan ini merupakan satelit dari Compaigne Grvais Danone of paris, perancis. praktik macam ini mempermudah perusahaan raksasa melakukan perluasan bisnisnya. Dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di banyak bidang. Entah jasa, pialang saham atau lembaga pembiayaan. Tapi, tujuannya tunggal: ekspansif.
p embelian 40 persen saham milik pT Tirta Investama oleh ‘Danone’ telah diperkuat pemerintah lewat Menteri In–vestasi/ Kepala Badan Koordinasi p e–nanaman Modal. Disetujui dalam Ke–putusan Menteri (Kepmen) Investasi nomor 33/ U/pMA/1998. Mulailah zaman masuknya dana asing dalam Aqua.
Air minum Isi Ulang. Termasuk kategori praktik komodifikasi air.
”Dua-duanya saling membutuhkan. ‘Danone’ membutuhkan basis di Indoensia, sedangkan kita membutuhkan partner strategic yang bisa mendorong per–kembangan kita. Dan ternyata, begitu kita sudah joint venture , perkembangan kita lebih cepat. Karena ‘Danone’ punya strategi yang kuat dan komitmen yang tinggi,” kata Willy Sidharta, presdir pT Aqua Golden Mississipi dalam wawancara dengan sebuah media terbitan Jakarta September 2003 lalu.
Sejak awal tahun 2000, produk merek Aqua dipasarkan dengan nama ‘AquaDanone’. Di botol Aqua pun ditambah atribut ‘Danone’.
Setahun kemudian, ‘Danone’ bikin gebrakan. Menambah kepemilikan sa–hamnya di pT Tirta Investama. Dari cuma 40 persen menjadi 74 persen. ”Aqua siap dalam volume, sebagai merek pertama di Asia dan nomor dua di dunia,” tulis pers rilisnya kala itu.
Diane d’Oleon dari ‘Danone’ pernah mengatakan, ”pemerintah juga siap me–nyetujui permintaan (transaksi) ini.”
pada akhir 2001, sekali lagi ‘Danone’ membuat kejutan. Melakukan aksi buy back pendapat lain juga menyebut kon–solidasi perusahaan. Orang awam me–nyebutnya aksi pembelian kembali saham perusahaannya yang telah dimiliki publik. Kali ini selaku pemilik saham mayoritas pT Tirta Investama, ‘Danone’ membeli 15.64 persen saham pT Aqua Golden Mississipi yang sebelumnya dilempar ke publik. Total saham ‘Aqua-Danone’ di pT Aqua Golden Mississipi menjadi 90.99 persen saham. Sebelumnya hanya 75.3 persen. Lagi-lagi transaksi ini dilakukan lewat Feddian pte
Ltd. Jadilah ‘Danone’ sebagai ‘penguasa’ Aqua yang secara tidak langsung me–nguasai pasar air di Indonesia. Mungkin pula di Asia.
p T Tirta Investama juga memiliki sebuah perusahaan AMDK yang pabriknya bertempat di Medan, Sumatera Utara. Namanya pT Tirta Sibayakindo. Besaran kepemilikannya, menurut Willy Sidharta kepada Bisnis Indonesia, adalah 75 persen. perusahaan ini belum go public . Mem–produksi Aqua dan Vit.
p ada Mei 2002 yang lalu, presdir p T Aqua Golden Mississipi itu pernah me–nyatakan bahwa pihaknya ingin melakukan delisting . Untuk sementara menghapuskan pencatatan saham Aqua dari Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kembali menjadi perusahaan tertutup. ”Kalau Tirta Investama sebagai perusahaan yang belum go public merger dengan perusahaan tercatat ( p T Aqua Golden Mississipi) tentu akan sulit di–laksanakan. Karena itu, Aqua direncanakan delisting dulu dari BEJ untuk merger, dan selanjutnya mencatatkan kembali sa–hamnya di bursa,” jelasnya saat itu. Apapun yang dilakukan perusahaan tersebut, toh yang diuntungkan nantinya juga pemilik mayoritas saham perusahaan: Danone yang asal perancis itu.
Aksi pembelian saham mayoritas pe–rusahaan lokal oleh asing macam ‘Danone’ ini dibolehkan sejak pemerintahan Ab–durrahaman Wahid. Ada aturannya dalam Keputusan p residen (Keppres) nomor 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan persyaratan Tertentu Bagi pe–nanaman Modal. Untuk bidang usaha pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk umum seperti Aqua, pemodal asing
Adhitya
/ HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Awan
dapat menguasai saham hingga 95 persen.
Tindakan perusahaan raksasa ‘Danone’ ini, masuk kategori praktik akuisisi pertama. Menguasai tidak hanya mereknya, melain–kan juga termasuk perusahaan, distribusi, maupun sarana produksi sekalipun. praktik akusisi kedua, adalah mengambil mereknya saja. Urusan produksi, distribusi, dan pemasaran, semuanya memakai fasilitas pengambil alih.
Ada peristiwa serupa yang menyita perhatian publik. p eristiwa pengambil alihan atau akuisisi perusahaan air minum AdeS oleh ‘The Coca-Cola Company’. Dalam proses ini berlangsung model akuisisi ketiga. proses akuisisi di mana hanya mereknya saja yang diambil alih. Tidak termasuk sahamnya. Fasilitas produksinya tetap memakai pabrik lama. Hanya urusan distribusi dan pemasaran yang ditangani perusahan pengambil alih. Dalam hal ini PT Ades Alfindo Putra Setia, produsen AdeS sebagai perusahaan yang diambil alih, dan pT Coca-Cola Indonesia selaku pengambil alih.
Menurut Info FreshWater , buletin terbitan Infog, perusahaan minuman karbonasi terbesar di dunia itu sebenarnya telah melakukan bisnis air di Indonesia sejak 1990an. Waktu itu, selain mem–produksi minuman karbonasi, The CocaCola Company juga memproduksi air dalam kemasan. Mereknya Bonaga.
”Karena pertimbangan pasar produk ini tidak luas, maka awal 2000 Bonaga berhenti produksi,” tulis buletin itu. Tahun itu pula, perusahaan global ini secara bersamaan membeli tiga merek AMDK lokal milik PT Ades Alfindo Putra Setia lainnya: Desca, Desta, dan Vica.
The Coca-Cola Company merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Mengklaim menguasai separuh pasar soft drink dunia. Untuk usaha AMDK-nya merek AdeS, di Indonesia, relatif lebih kecil ketimbang Aqua.
Ada perbedaan pola ekspansi ‘The Coca-Cola Company’ dengan ‘Danone’ dalam pengusahaan air di pasar Indonesia. Jika ‘Coca-Cola’ hanya membeli mereknya, sedangkan ‘Danone’ membeli tidak hanya merek, melainkan saham, hingga pemasaran milik perusahaan lokal Aqua.
Kejadian macam ini mengingatkan saya pada Soekarno lewat analoginya tentang imperialisme. Mirip seekor naga. Kepalanya yang notabene untuk melahap makanan, berada di Indonesia. Sedang, perut sebagai simbol akumulasi kekayaan berada di perancis dan Amerika Serikat. Soal ini saya mengamininya.
* * *
B ELAKANGAN , bermunculan banyak pengusahaan air lewat depot pengisian ulang. Bisa jadi ini adalah bentuk ‘per–lawanan’ atas tingginya harga AMDK bermerek. Macam Aqua dan AdeS Sup–rihatin, staf pengajar Departemen Te–knologi Industri p ertanian Institut per–tanian Bogor (IpB) dalam tulisannya Keamanan Air Minum Isi Ulang menya–takan, bahwa industri air minum depot isi ulang (AMDIU) telah menjadi salah satu alternatif bisnis skala usaha kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air di kota besar-kota besar dengan harga terjangkau.
Otomatis keberadaanya mengancam perkembangan perusahaan AMDK yang
wandi yang mengeluarkan beleid tentang persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan perdagangannya, 21 November 2003 lalu. Salah satu klausulnya menyatakan bahwa kemasan suatu merek air minum dalam kemasan pakai ulang, hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. ”Ke–tentuan ini tidak bermaksud mematikan pengusaha depot air minum isi ulang. Mereka tinggal beli galon-galon polosnya. Gampang. Kami mau bantu,” katanya kepada Tempo News Room.
Meski demikian, baik AMDK bermerek maupun AMDIU bukan tanpa masalah. Semuanya termasuk praktik pengusahaan air. Bisa dibayangkan. Berapa milyar liter air setahun yang telah dikomodifikasi? Berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut? Apa imbas terhadap masyarakat atas praktik pengusahaan air macam ini? Bagi per–tanian? Ketahanan pangan? Bukankah hal ini riskan dengan kerawanan sosial? Bagaimana kesediaan air nanti pada akhir–nya? Bukankah air termasuk ke–butuhan dasar dan hak asasi manusia? Bagaimana peran negara dalam hal ini? Kenapa praktik ekspansif pengusahaan air terus terjadi? Bahkan terus meningkat?
p engusahaan air macam ini bukan masuk kategori privatisasi. ”Itu swasta murni. Bedanya, kalau swasta murni sejak dari awal ia sudah mengkonsentrasikan bisnisnya ke air,” komentar Mulyadi dari Infog yang saya temui akhir Oktober silam di kantornya. Di komplek perumahan Fajar Indah, Solo.
telah mapan. Ini pernah diakui oleh Willy Sidharta, presdir pT Aqua Golden Mi–ssissipi dan juga selaku ketua Aspada. Aspada kependekan dari Asosiasi p e–ngusaha Air Minum dalam Kemasan.
Secara umum, menurut Willy Sidharta, pertumbuhan AMDK sekarang sebesar 78 persen. Menurun drastis bila dibanding tahun sebelumnya.
”Kenapa kecil atau merosot dari tahun 2002 yang 25-30 persen? Karena kita kehilangan pertumbuhan di pasar galon. Untuk galon, pasarnya diambil oleh depot isi ulang. Sementara untuk kemasan tetap tumbuh dua digit (sekitar 20 persen), dan ini berdasarkan proyeksi kita. Gara-gara isi ulang di galon inilah, Aqua menurun hingga 5 persen,” katanya seperti dikutip dari Warta Ekonomi
Dalam sebuah pemberitaan, ia men–dukung Menteri perindustrian dan per–dagangan (Menperindag) Rini M.S Soe–

”Sebenarnya air itu tetap public goods Menjadi komoditas ekonomi karena jum–lahnya semakin berkurang. Itu bisa salah karena air punya nilai tinggi bukan dari sisi ekonomi,” kata Budi Wignyosukarto, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Budi Wignyo terlibat aktif dalam Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air. Konsorsium banyak LSM dan akademisi yang getol mengkritisi RUU Sumber Daya Air yang direncanakan sebagai pengganti UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan.
Salah satu keberatan dalam draft RUU Sumber Daya Air yang sering dilontarkan petani adalah soal hak guna usaha air. Diatur dalam pasal 9 ayat 1, berbunyi;
Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha degan izin dari Peme–rintah atau pe–merintah daerah sesuai dengan kewena–ngannya.
Saya pernah mengikuti sebuah forum publik petani-koalisi rakyat untuk hak
Pandu L.
Patriari / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
atas air-panitia kerja (panja) RUU Sumber Daya Air DpR RI. Forum yang diprakarsai oleh Infog. Hadir dalam pertemuan itu Erman Soeparno, ketua panja, yang saat itu mengenakan batik necis. Dia adalah po–litikus dari partai Kebangkitan Bangsa (pKB). Muqawwam, anggota panja dari p artai p ersatuan p embangunan ( ppp ), Nila Ardhianie, direktur Infog dan juga ko–ordinator advokasi koalisi dan seorang pejabat dari Departemen permukiman dan prasarana Wilayah (Depkimpraswil). Tentu juga puluhan petani dari Jatim-Jateng dan DI Jogjakarta.

Di hadapan petani, dua anggota parlemen itu mengaku bahwa dirinya berasal dari keluarga petani. ” p etani sekarang ini enak bisa mengenakan pakaian yang bagus. Zaman bapak saya dulu tidak seperti ini,” kata Erman Soeparno.
Budi Wignyosukarto tampak hadir duduk bersebelahan dengan Wijanto Hadipuro, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Katholik (Unika) Soegijo pranoto, Semarang. Wijanto pernah hadir di pertemuan forum air sedunia atau world water forum (WWF) tahun 2003 di Jepang. Dia datang beserta beberapa aktivis LSM Indonesia.
WWF merupakan pertemuan tiga ta–hunan para stakeholders tingkat dunia. Baik wakil dari pemerintah, chief executive organization (CEO) perusahaan mu–ltinasional yang bergerak khusus di bidang air. Dan juga LSM.
”Kalau di tingkat pemerintah-CEO itu jauh lebih terkoordinir. Mereka punya global water pertnership , world water panels Yang jadi masalah adalah di masyarakat dan LSM. pada saat forum, mereka itu terpecah-pecah. Tidak terkoordinir,” kata Wijanto Hadipuro kepada saya.
”Rekomendasi Anda saat itu?” tanyaku.
”Tergantung forumnya. Di level menteri kaitannya dengan proyek. Jika forumnya LSM adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam pengelolaan air,” jawab Wijanto.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa jargon LSM saat itu adalah water is life. Bukan water for live. ”Kalau yang kapitalis water for live. Kalau kita adalah water is life, air adalah kehidupan sehingga harus ada jaminan dari pemerintah,” tegas
oleh Ipung, aktivis Infog. Tujuannya, menggali masukan-masukan petani untuk disampaikan ke panja-pemerintah. Sedang, sesi kedua pertemuan petani dan panja.
Seorang petani asal Sukoharjo me–lontarkan pendapatnya. ”Saya usul kepada panja yang terhormat,” kata petani itu mengawali dialog.
”Agar RUU (SDA) ini dipending.”
Selanjutnya, ia meminta kepada panja agar Menteri Lingkungan Hidup juga diikutsertakan dalam pembahasan. ”Alasan ketiga, RUU ini hanya mementingkan eksploitasi saja, tanpa mementingkan pelestarian. Artinya, hanya untuk ke–untungan saja. RUU ini tidak memihak petani untuk mengembangkan pertanian–nya.” Terdengar gemuruh tepuk-tangan puluhan petani lainnya yang hadir.
petani tadi masih melanjutkan.
”Menyebabkan tumbuhnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), karena kalau mau membuka perusahaan air sangat gampang. RUU ini akan menimbulkan konflik horisontal petani, karena pe–ngelolaan irigasi yang dikelola negara,” lanjutnya. ”RUU ini memberikan peluang perusahaan membeli mata air.”
Sayang, RUU telah disetujui parlemen di Senayan, pertengahan pebruari 2004 lalu.
Boleh dibilang, ada satu hal yang
dikhawatirkan petani tani adalah soal diskriminasi akses air. Meski dilontarkan petani asal Sukoharjo, namun perlakuan diskriminatif macam ini seperti sudah menjadi peristiwa umum.
Saya pernah mendiskusikan tentang ini dengan Abdul Arif, Ketua ‘Dutha Tani’, sebuah organisasi tani yang berbasis di Karawang, akhir Desember 2003 silam. Kabupaten Karawang termasuk lumbung padi dengan total sawah seluas 93.950 hektar. Bersebelahan dengan kabupaten p urwakarta, tempat waduk Jatiluhur berada. Irigasi sawah Karawang diambil dari waduk Jatiluhur itu.
Abdul Arif bercerita bahwa di tahun 2003 lalu, Bupati Karawang Ahmad Dadang mengeluarkan surat edaran perihal pela–ksanaan Program Intensifikasi Pertanian Musim Tanam Gadu. Konon, saat itu, tujuannya mereduksi lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Menurut klaim pemkab Karawang ada sekitar 22.000 hektar sawah mengalami kekeringan.
Surat edaran bupati Karawang itu berisi tiga kebijakan: gilir-giring distribusi air ke petakan sawah yang dapat melibatkan unsur kepolisian dan angkatan darat. ”Untuk desa, pembina polri dan pembina AD,” kata Abdul Arif.
Kebijakan kedua: program penanaman singgangisasi sebagai alternatif padi.
FORUM publik petani-panja-koalisi siang itu berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama pertemuan antar-petani. Dipandu
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
* * *
Singgang merupakan tunas yang tumbuh dari batang padi yang selesai dipanen. Biasanya untuk pakan bebek, karena nilai karbohidratnya sangat rendah. ”Sing–gangisasi jelas-jelas tidak memperhatikan sistim budaya. Melecehkan kemanusiaan. Dan merupakan tambah memiskinkan,” komentarnya.
Tambah bikin kesal Abdul Arif adalah kebijakan bupati Ahmad Dadang yang ketiga. p rogram pompanisasi. p rogram berupa pemberian kredit, mungkin lebih tepatnya utang satu unit pompa air merek Domfeng seharga Rp 8 juta kepada petani. Diangsur delapan kali, sekali setiap musim panen. ”padahal harga pompa merek sama, di pasaran tidak sampai segitu,” kata Arif. Menurutnya, uang pompa itu berasal dari kadeudeuh Gubernur Jabar, Nuriana, yang seharusnya dibagikan gratis.
Kekeringan di Karawang ini boleh dibilang agak aneh. ”Karena sebelumnya, Karawang belum pernah mengalami ke–keringan,” katanya. Usut punya usut, aliran air untuk sebagian wilayah Karawang, menurut penelitian Dutha Tani, dialihkan untuk kawasan industri. Diantaranya, untuk sebuah industri ban mobil.
Diskriminasi akses air ini bukan masalah kelokalan. Tapi, sudah melewati sekat-sekat wilayah. Diskriminasi yang dialami petani Sukohajo secara tidak langsung merupakan diskriminasi terhadap petani Karawang.
Begitu pula sebaliknya. Ada pelanggaran terhadap kaidah universal, berupa per–lakuan diskriminatif terhadap petani.
”Memang istilah water security tidak sepopuler food security, namun mustahil ketahanan pangan bisa dicapai Indonesia tanpa adanya ketahanan air,” tulis Wijanto Hadipuro dalam Ketahanan Air dan Ketahanan Pangan. Lewat proyek irigasi adalah salah satu penunjangnya.
”Saya pikir sekarang hanya air yang dapat dinikmati gratis oleh petani dan rakyat. Apabila RUU SDA ini disahkan, maka dikhawatirkan harga air yang tinggi. Sehingga dikhawatirkan muncul kekacauan sosial,” kata Wardiyono, petani dari Klaten.
”Harga kekacauan sosial itu mahal,” tegasnya dalam forum publik panja-petani di Solo itu. ”Air itu dingin, tapi kalau sudah rebutan, sampai dilakukan dengan gebukan pacul.” Bisa dimaklumi, karena air ibarat nyawa bagi petani. Tidak ada air, maka petani tidak dapat bercocok tanam.
Ini soal distribusi atau irigasi per–sawahan. Tentang ini pula pernah menjadi perdebatan sengit di kalangan tiga orang menteri: purnomo Yusgiantoro, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Hari Sabarno, menteri Dalam Negeri; dan Soenarno, menteri p ermukiman dan pra–sarana Wilayah.
”Sekarang jaringan irigasi itu dikelola masyarakat lewat pp nomor 77 tahun 2001.Itu diserahkan ke petani. Belum seratus persen dikerjakan petani, karena beberapa daerah menyerahkan (kepada) p3A. Sama saja,” kata Budi Wignyosukarto me–nerangkan. Selain sebagai dosen, Budi Wignyosukarto juga menjabat kepala Laboratorium Hidrologi Fakultas Teknik UGM.
p 3A singkatan dari perkumpulan petani pengguna air. Badan hukum yang berdiri berdasarkan perda tiap kabupaten. Kon–sekuensinya, p3A dapat melakukan tin–dakan hukum, diantaranya adalah meng–alihkan haknya kepada subyek hukum lainnya. Termasuk swasta.
”Karena ini dimanfaatkan untuk publik, maka irigasi air ini diserahkan ke publik. Kalau seperti ini kenapa harus mengundang investor? Kalau seperti ini, maka air bukan lagi barang publik. Karena publik tidak memiliki akses,” lanjut Budi Wignyosu–karto.
Irigasi masuk dalam skema syarat utang Bank Dunia di sektor air yang diterapkan pada Indonesia. Terkenal dengan sebutan Watsal, singkatan water resources sector adjustment loan. Bank Dunia mengucurkan utang sebesar 300 juta dollar untuk Watsal sejak 1998. Dibagi menjadi tiga tahap yang masing-masing punya syarat sendiri.
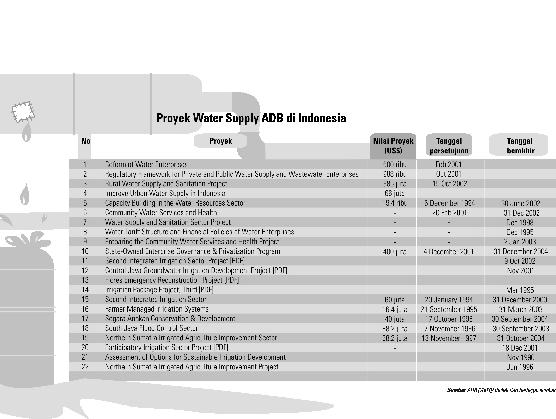
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
Untuk tahap pertama salah satu sya–ratnya adalah menetapkan kebijakan pembaharuan pengelolaan irigasi dengan mengenalkan sistim irrigation service fee. Iuran bagi pemakaian air oleh petani. p erdebatan tiga menteri terkait soal irigasi tadi terjadi tatkala Menkimpraswil Soenarno mengeluarkan kebijakan mo–ratorium program pKpI, singkatan dari p embaharuan Kebijakan p engelolaan Irigasi. Dalam pKpI, memuat ketentuan bahwa irigasi dikelola oleh petani. Bukan pemerintah.
Dalam sebuah suratnya yang ditujukan ke Menteri perekonomian, awal September 2003 silam, Soenarno menjelaskan be–berapa alasan. Yang mendasar, tentu menyangkut perkembangan pembahasan RUU SDA.

”Dalam pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, dapat di–kemukakan bahwa DpR tidak menyetujui adanya penyerahan kewenangan pe–ngelolaan irigasi dari pemerintah daerah ke petani pemakai air,” kata Soenarno dalam surat tersebut. Beruntung saya memperoleh kopian faksimilinya.
Selanjutnya, Soenarno menegaskan bahwa wewenang pengelolaan irigasi berada di tangan pemerintah atau pemda. ”Sesuai dengan kewenangannya se–bagaimana telah dirumuskan dalam pasal 12 RUU SDA.”
pasal itu menerangkan, untuk jaringan irigasi dalam satu kabupaten menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot. Lintas kabupaten/kota tanggung jawab propinsi, lintas propinsi atau negara menjadi tang–gung jawab pemerintah.
p etani hanya pelaksana- cum- peme–lihara jaringan irigasi.
Menteri purnomo Yusgiantoro lantas kirim surat ke Menkimpraswil Soenarno. Dia keberatannya dalam hal pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada wilayah sungai. ”Kami tidak dapat mema–haminya. Berhubung secara alami (natural boundary), sungai sangat berbeda dengan cekungan air tanah,” kata purnomo Yus–giantoro kepada Soenarno dalam suratnya yang bersifat segera itu. Tertanggal 12 September 2003.
Air tanah memang jadi wewenang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Meskipun pemkab atau pemkot yang menarik pajaknya. Sedang air per–mukaan di bawah pengelolaan Dep–kimpraswil.
Beberapa hari kemudian giliran Men–dagri Hari Sabarno menyurati Ketua Komisi IV DpR dan Ketua panja RUU SDA. Masih seputar pengelolaan irigasi.
Ada tujuh poin pernyataan Hari Sa–barno yang ditulis dalam surat itu. Intinya, pp nomor 77 tahun 2001 itu masih tetap berlaku.
poin lain adalah, ”pp nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi memberikan ke–sempatan kepada petani yang mempunyai keinginan dan kemampuan mengelola irigasi di wilayahnya sampai jaringan sekunder dan primer dengan membentuk Gabungan petani pemakai Air (Gp3A) dan Induk petani pemakai Air (Ip3A),” tulis Mendagri Hari Sabarno.
pp nomor 77 tahun 2001 itu, lanjut Hari Sabarno, merupakan respon positif ter–hadap tuntutan desentralisasi dan demo–kratisasi pengelolaan irigasi.
”prinsipnya memberikan peluang ke–pada masyarakat petani untuk mengelola jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.”
Air sungai termasuk air permukaan. p rinsip umum dalam pengelolaannya adalah one river one management. Tidak mengenal batas administratif seperti batas kabupaten atau kota.
”(Dalam) air itu ada siklus hidrologi yang tidak bisa dikelola secara parsial. Jadi mengapa negara yang harus mengelola air? pemerintah itu banyak, parsial. Bahwa air tidak bisa dikelola oleh pemda dan pemkot. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 bahwa daerah yang tidak mampu dalam hal pembiayaan, akan digabung atau di–likuidasi oleh daerah lain. Akhirnya, daerah berlomba-lomba mencari pAD. Air salah satu sumbernya,” kata Wijanto Hadipuro ketika saya temui di kantornya. pAD kependekan dari pendapatan asli
daerah.
p erusahaan negara yang mengelola air permukaan adalah perusahaan umum (perum) Jasa Tirta. Berkedudukan di bawah Depkimpraswil. p erum ini mengelola sungai untuk irigasi. Selain itu juga mengelola bendungan-bendungan yang tersebar di daerah.
Menurut kantor kementerian p e–rencanaan p embangunan Nasional/ Kepala Bappenas, ada dua Rancangan pp (Rpp) Jasa Tirta yang akan dibahas untuk memenuhi Watsal tahap ketiga. Rpp Jasa Tirta I dan Rpp Jasa Tirta II.
Jika mengarah ke swastanisasi perum Jasa Tirta bisa jadi tambah ruwet. ”Banyak air yang dijual untuk kepentingan industri yang mungkin memberikan prioritas yang lebih rendah ke kebutuhan pokok. Seperti Aqua di Klaten, Jawa Barat di daerah Karawang. Sehingga petani yang awalnya bisa memanfaatkan irigasi, sekarang tidak. padahal petani menyediakan beras untuk negara,” kata Budi Wignyosukarto.
”(Dan juga) untuk memproduksi pa–ngan!”
Menurutnya, hal ini seharusnya perlu diperhatikan. ”Sehingga akses masyarakat terhadap air lebih baik,” katanya pada saya pertengahan November lalu.
Dalam pengelolaan air, peranan lembaga keuangan internasional tak dapat di–lepaskan. Funding internasional macam Asian Development Bank (ADB) atau Bank Dunia pengaruhnya sangat dominan. ADB telah memulai sejak 1969 dalam pembiayaan proyek irigasi. Bank Dunia sejak 1983. Menurut sebuah laporan perusahaan lokal juga turut ‘bermain’ dalam beberapa proyek. Macam pT Wavin Duta Jaya, Jakarta dan pT Krakatau Tirta Industri.
Jika ditotal, proyek kedua lembaga internasional itu saja bisa sampai puluhan proyek. Baik proyek irigasi atau air per–kotaan. Jenis proyeknya beragam. Mulai dari pembiayaan proyek, pembangunan instalasi pipa, pembacaan dan pencatatan meter hingga joint venture dan hutang perusahaan daerah air minum (pDAM). Dana yang digelontorkan pun tak sedikit. Khusus Bank Dunia sendiri mengeluarkan USD $ 2,921.75 juta, termasuk USD $ 300 juta untuk Watsal.
Wijanto Hadipuro sekarang sedang meneliti salah satu proyek air yang didanai lewat pinjaman Bank Dunia. Tentang pembangunan Bendung Klambu-Kudu di Semarang. ”penelitian ini baru dalam tahap proposal pembuatan proposal,” katanya lewat surat elektronik. Lewat penelitian ini, katanya, bisa diketahui kebenaran ke–gagalan proyek IpA Kudu dalam proyek
Pandu L.
Patriari / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
‘Semarang-Surakarta Urban Development p roject’. I pA singkatan instalasi pe–ngelolaan air. ‘Semarang-Surakarta Urban Development project’ merupakan proyek Bank Dunia dengan partner pDAM Se–marang berjangka waktu 7 tahun: dari 1994 hingga 2001. Belakangan diketahui proyek tersebut tidak mencapai target.
”Apakah karena pembobolan saluran air dari Bendung Klambu ke IpA Kudu oleh masyarakat ataukah tidak? Jika benar, apakah hal ini disebabkan pembangunan yang tidak bersifat partisipatif? Atau
seluruh Indonesia.
Masih menurut laporan lembaga itu, sebagian besar p DAM dalam kondisi mengenaskan. Tahun 2001, terdapat 201 unit pDAM yang total utangnya Rp 3,4 trilyun. 186 diantaranya tidak mampu melunasi utangnya karena pelbagai alasan. ”Ada 25 pDAM yang utangnya lebih besar dari asetnya,” kata Wijanto Hadipuro.
Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun berikutnya. Total utang p DAM bermasalah merangkak naik menjadi Rp 4 trilyun. ”Hanya sepuluh persen yang
yang asetnya sebagian besar dimiliki oleh pemda kabupaten atau kota. Singkatnya, pDAM adalah badan publik yang mengelola air perkotaan, oleh karenanya social oriented.
Tidak semua orang perkotaan mendapat pelayanan pDAM. Sekarang ini, 41 persen penduduk tinggal di perkotaan. Dari 41 persen ini, hanya 51,7 persen mendapat akses air bersih. ”Buruk sekali,” kata Wijanto.
Besar kemungkinan, kondisi pDAM yang demikian jadi alasan pembenar oleh swasta untuk masuk. Menggantikan peran pemerintah dalam pengelolaan air. ”Betul. Yang pertama mereka incar adalah air perkotaan,” kata Wijanto dalam sebuah perbincangan dengan saya.
Mungkin ini adalah panggung pe–mentasan. pDAM kebagian peran aktor, sedang lembaga donor sebagai si sut–radara. Aktor mau tak mau harus tunduk pada aturan main sutradara. Naskahnya berupa skenario pemberian bantuan atau utang. Bisa jadi berujung pada resep swastanisasi.
praktik privatisasi pun dimulai.
masalah lain?” jelas Wijanto.
”Tentu (juga) bagaimana jalan keluar–nya.” Dia sendiri pernah mempresentasikan kegagalan ini dalam sebuah diskusi. Dikatakannya, meski mendapat suntikan dana dari Bank Dunia, performance pDAM Semarang ternyata tidak banyak beranjak. Cakupan pelayanan masih sekitar 45,99 persen dari seluruh wilayah kota Semarang. Jumlah pelanggan hanya meningkat tipis: dari 108.728 menjadi 113.849 pelanggan pada Juni 2002.
”Jika dibandingkan target SemarangSurakarta Urban Development p roject, pencapaian tersebut tidak memenuhi target. Cakupan pelayanan harusnya naik dari 40 persen menjadi 60 persen,” kata Wijanto sebagaimana dikutip dari Kompas Secara umum pDAM, seperti pDAM Semarang ini, berfungsi melayani air bersih perkotaan. Berdasarkan data p erpamsi, jumlahnya sampai tahun 2002 ada 293 unit di seluruh Indonesia. perpamsi kependekan dari persatuan perusahaan air minum
termasuk sehat. Sedang sisanya boleh dikatakan setengah sakit, malah ada yang sudah ‘diinfus’. Karena itu perlu penyehatan organisasi p DAM,” kata Kumala Siregar, Ketua Umum perpamsi saat bertemu dengan presiden Megawati, Januari 2002 lalu.
Menurutnya, kerugian yang dialami pDAM bermasalah ini karena faktor mismanajemen dan kenaikan tarif yang tidak teratur.
padahal tidak sedikit proyek pDAM yang bertujuan berusaha memperbaiki kondisi. Sebagai contoh proyek ‘Sema–rang-Surakarta Urban Development pro–ject’. Adanya proyek Bank Dunia itu memang tidak bikin penampilan pDAM Semarang terlihat apik. Utangnya pun tetap menumpuk. Bahkan, p DAM Semarang tercatat sebagai salah satu pDAM oleng Tahun 2002, menurut laporan perpamsi, utang domestiknya sekitar Rp 8,7 milyar, sedang utang luar negerinya mencapai Rp 110,56 milyar.
pDAM merupakan perusahaan daerah
Konsep ini terjadi tatkala ada pengambil alihan peran negara oleh swasta dalam urusan publik. Termasuk penguasaan aset atau kepemilikan saham pDAM. Tercatat sudah lima perusahaan asing yang mem–privat p DAM: Thames Water dan Suez Lyonnaise di Jakarta, Biwater di Batam, Cascal BV di p akan Baru, Vivendi di Sidoarjo dan Waterleiding Maastschappij Drenthe di Manado. p DAM Semarang sendiri sudah membuka diri pada swasta. Belakangan, pDAM pati juga dalam proses privatisasi setelah disetujui oleh par-lemen setempat. Bisa jadi pDAM yang kayak begini, jumlahnya makin membengkak.
Mulyadi dari Infog menyatakan bahwa untuk pengambil alihan saham milik pe–merintah di pDAM, kasus perusahaan Air Minum Jakarta Raya (pAM Jaya) adalah yang pertama. Awal mula peristiwanya rumit. Berbau skandal politik yang me–libatkan Sigit Harjojudanto, anak mantan presiden Suharto. Dan juga Anthony Salim.
The Water Barons menyebut awal kasus ini sejak Bank Dunia setuju me–minjami US$ 92 juta kepada pAM Jaya, di Juli tahun 1991. Tujuannya: memperbaiki infrastruktur, membangun tanaman pe–nyaring air di daerah pulogadung, Jakarta Timur. program ini disesuaikan dengan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), sebuah konsorsium lembaga donor.
The Water Barons adalah kumpulan
 Perusahaan Publik PDAM. Kinerja buruk jadi faktor pembenar masuknya swasta.
Indra Yudhitya HIMMAH
Perusahaan Publik PDAM. Kinerja buruk jadi faktor pembenar masuknya swasta.
Indra Yudhitya HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
laporan investigasi proses privatisasi air di berbagai belahan dunia yang melibatkan beberapa perusahaan air dunia macam Thames Water Overseas, Vivendi, Lyo–nnaise des Eaux. Indonesia dan Filipina, negara Asia yang masuk dalam liputan ini. Dikerjakan oleh International Concorcium of Investigative Journalist (ICIJ).
Dalam laporannya, yang dikutip dari dokumen Bank Dunia, disebutkan bahwa OECF menganjurkan Indonesia untuk melakukan privatisasi. Tahun 1993, Thames Water yang pertama kali menguasai pAM Jaya. perusahaan yang berpusat di London ini menggandeng Sigit Harjojudanto de–ngan memberikan kompensasi 20 persen saham.
Sedang Info Freshwater, buletin ter–bitan Infog, menyebut awal mula pri–vatisasi pAM Jaya terjadi pada 1994. Saat pT Kekar plastindo, perusahaan milik Sigit Harjojudanto, bermitra dengan Thames Water, mengajukan proposal pembangunan pipa distribusi dan sistim jaringan pada pAM Jaya. ”proposal disetujui oleh pAM Jaya pada 31 Agustus 1994, lantas Kekar plastindo sepakat mengembangkan area operasi dalam empat bagian wilayah-timur Jakarta,” tulis Info Freshwater.
Maret 1995, lanjut laporan itu, p T Kekar plastindo menyetujui proposal untuk mengelola distribusi air utama di area 2 dan 4. pembagian wilayah air di Jakarta ini jadi
penting ketika perusahaan swasta asing lain, Suez Lyonnaise masuk pAM Jaya. Menurut The Water Barons, perusahaan ini masuk lewat perantara Bernard Laf–rogne, seorang insinyur teknik prancis, keturunan Vietnam. Dia pernah bekerja di Bank Dunia untuk proyek Indonesia dan juga menjabat konsultan pAM Jaya.
Suez Lyonnaise juga menggunakan Anthony Salim melalui perusahaannya pT Garuda Dipta Semesta untuk masuk di pAM Jaya, kroni Suharto saat masih berkuasa. Salim mendapat jatah 60 persen saham.
Kedua perusahaan ini berbagi area, menyuplai kebutuhan air di Jakarta. Meng–gantikan peran pAM Jaya yang dulu milik pemda DKI Jakarta.
”Jakarta cukup besar untuk dua pe–rusahaan (air),” kata Lafrogne seperti dikutip dari The Water Barons . Untuk Thames Water-Kekarpola Airindo (menurut Info Freshwater: tanpa kata -pola, nama baru Kekar plastindo) mendapat jatah sebelah timur Sungai Ciliwung. Dan, Lyonnaise des Eaux-Garuda Dipta Se–mesta dapat sebelah barat Sungai Ci–liwung.
pemisahan area distribusi air Jakarta, saat itu, dilakukan oleh Menteri pekerjaan Umum, Radinal Moochtar. Disinyalir atas perintah Suharto. Bisa jadi karena me–nguntungkan Sigit Harjojudanto, sang anak, maupun Anthony Salim, sang kroni.
Kejadiaan ini menuai protes dari para pekerja di perusahaan sama sebelumnya: pAM Jaya. Tahun 1998, saat Suharto turun dari presiden, kedua perusahaan asing kemudian melakukan negosiasi ulang kontrak sebelumnya. pengaruh anak-kroni Suharto ‘dihilangkan’ dari pAM Jaya. Sahamnya dibeli.
Negosiasi ulang kontrak dilakukan tahun 2001 yang melahirkan perusahaan baru: pT Thames pAM Jaya yang 95 persen sahamnya dimiliki Thames Water, sedang sisanya oleh pT Terra Metta phora. Dan, pT pAM Lyonnaise Jaya (palyja) saham mayoritas dipunyai Suez, 5 persennya oleh pT Bangun Cipta Sarana.
Kondisi pun tak membaik. Masih sering ada surat pembaca mengeluh entah karena aliran air tak lancar, pipa meter yang tidak stabil, hingga tarif yang tidak wajar. Soal tarif, bahkan pada 2003 lalu, duta besar (dubes) Inggris untuk Indonesia, Richard Gosney, meminta pemerintah untuk me–naikkan tarif. ”Untuk mengurangi beban perusahaan,” katanya. Thames Water , salah satu perusahaan yang mengambil alih pAM Jaya berasal dari negara asal Richard Gosney, Inggris.
Belum lagi tentang karyawannya yang masih sering demo. Menuntut ketegasan direksi pAM Jaya: perusahaan yang dulu milik pemda dan sekarang sudah dikuasai swasta. Seperti terjadi September 2003 yang lalu. Di mana karyawan menuntut tunjangan kepada direksi pAM Jaya.
”Masak sih mereka (pT Thames pAM Jaya dan pT palyja) yang mempekerjakan, kami yang bayar,” kata Ifie S. Laili, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) pAM Jaya kepada media waktu itu.
Itu baru privatisasi pAM Jaya.
Wijanto pernah menegaskan suatu hal pada saya. ”Ini bukan dilema!” katanya. ”Karena kalau kita tahu pelayanannya buruk, kita harus awasi dia. Kalau kemudian itu dikelola swasta, pengaruhnya besar. Jika air itu dikelola oleh pemkot, maka urusan–nya hanya kita dengan pemkot. Tidak ada hubungannya dengan orang lain,” katanya. ”Memang kalau dikelola swasta bakal tidak korup?” Betul sekali.

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Pandu L. Patriari / HIMMAH
Menengok Air di Negeri Seberang
saya.
”Jadi sebenarnya istilahnya sama saja,” komentar Habibullah soal WUA, syarat angsuran kedua program Watsal.
Sisa angsuran, sebesar US$ 150 juta ini yang belum dikucurkan ke pundi pe–merintah. Santer beredar kabar di ma–syarakat, bahwa pembahasan RUU Sumber Daya Air ini untuk memenuhi pesanan tersebut. Yakni mengganti aturan yang telah lampau ada. Sejak tahun 1974.
Sempat ada rencana, akan disahkan bulan Oktober 2003 silam. Tapi, setelah melihat respon masyarakat yang begitu luas, RUU Sumber Daya Air, pada waktu itu, tidak jadi disyahkan.
Soal isu ius constituendum ini pesanan Bank Dunia, Ketua p anja RUU SDA, Erman Soeparno pernah membantahnya. Seolah-olah tidak ada intervensi.
”Saya tegaskan berkali-kali dalam media massa, bahwa kita membuat ini kan ke–daulatan kita,” katanya dalam sebuah forum pertemuan di pertengahan November 2003 lalu.
KETIKA Rancangan Undang-undang (RUU) Sumber Daya Air belum diketok untuk disetujui, telah beredar kabar di masyarakat bahwa beleid ini merupakan ‘barang titipan’ Bank Dunia. Satu rangkaian dalam paket utang pemerintah Indonesia untuk program Watsal. Kependekan dari water resources sector adjustment loan Rangkaian draf perjanjian untuk reformasi kebijakan air. Besaran utangnya US$ 300 juta atau sekitar Rp 2,4 trilyun dengan kurs Rp 8.000 per dolar.
Utang ini dibagi dalam tiga termin pencairan. pertama kali diturunkan bulan Mei tahun 1999 sebesar US$ 50 juta. Tentu ini bukan uang yang datang tiba-tiba alias gratis. Ada syaratnya: pembentukan tim koordinasi pendayagunaan sungai dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS); dan menetapkan kebijakan pengelolaan irigasi. Yang terakhir ini sudah dikukuhkan lewat Instruksi presiden (Inpres) nomor 3 tahun 1999 tentang Kebijakan pengelolaan Irigasi.
Angsuran kedua direncanakan cair Desember 1999. Tapi, akhirnya molor hingga akhir 2001. Nominalnya lebih besar ketimbang angsuran sebelumnya. Yakni: US$ 100 juta. Sebagian kalangan menilai
molor karena ketidakmampuan pemerintah memenuhi syarat yang diminta institusi paling berpengaruh dalam soal keuangan di banyak negara miskin: Bank Dunia. Di antara syarat yang diminta adalah pem–bentukan water user asociation (WUA). Dalam istilah Indonesianya dikenal dengan sebutan asosiasi atau perkumpulan petani pengguna air (p3A).
p emerintah sebenarnya pernah me–nerbitkan peraturan pemerintah (pp) nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi yang sempat bikin polemik di masyarakat itu. Alasannya, ”sebelum ada p3A, di masyarakat sudah ada yang mengurus irigasi. Kalau di Jawa istilahnya jagatirta ,” kata Habibullah, aktivis Serikat Tani Merdeka (Setam), Jogjakarta. Setam tercatat sebagai salah satu partisipan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang getol melakukan kritisasi draf UU Sumber Daya Air sebelum disahkan. p3A, lanjut Habib, hanya terdapat di wilayah yang terkena proyek Bank Dunia semata. Dan tidak di semua wilayah terdapat proyek itu. ”Yang tidak terjangkau namanya ya seperti nama yang dianut masyarakat setempat,” katanya kepada

”(Ada rencana) waktunya dibatasi sampai Desember 2003, saya patahkan,” lanjutnya. ”Kenyataannya kan tidak.”
Memang benar soal timing. Bagaimana dengan isi ketentuannya? Berpihak kepada siapa? publik atau cenderung ke swasta? Bukankah dalam pencairan angsuran kedua oleh Bank Dunia juga terlambat? Apakah itu menampik tudingan adanya intervensi?
Tidak jelas betul. Yang pasti aturan kadung diketok parlemen Senayan, 20 pebruari 2004 lalu. Lewat kebijakan ini, peluang pengelolaan air oleh swasta di Indonesia semakin terbuka lebar. Meski sebelumnya tidak sedikit pengelolaan air yang ‘dipegang’ swasta. Macam p eru–sahaan Air Minum Jakarta Raya (pAM Jaya) yang masih saja berkelut masalah.
Soal nuansa privatisasi air dalam UU Sumber Daya Air ini, pernah dicemaskan oleh Nila Ardhianie, Koordinator Advokasi KRUHA dalam sebuah artikelnya yang berjudul Mengapa Privatisasi Air Bikin Orang Khawatir di Harian Kompas Artikel tersebut dimuat tepat pada sidang pari–purna DpR untuk mengesahkan RUU Sumber Daya Air. Dalam artikel tersebut, ia
Beberapa negara telah memprivatisasi pengelolaan airnya. Dikarenakan tekanan utang atau koneksi pengua
Menentang RUU SDA. Ada indikasi kuat Watsal adalah skenario Bank Dunia.
Widiyanto
HIMMAH
Oleh WIDIYANTO
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
/
menilai privatisasi air berpotensi akan bikin kekacauan sosial. Mirip di Cochabamba, Bolivia tahun 2000.
Di kota terbesar ketiga Bolivia itu, pada awal 2000, terjadi demonstrasi besarbesaran menentang masuknya konsorsium swasta dalam pengelolaan air publik setempat. Konsorsium tersebut membentuk pe-rusahaan baru yang bernama ‘Aguas del Tunari’. Didukung oleh peru–sahaan waterproject terkemuka: Bechtel dan United Utilities.
”Mereka mau memprivatisasi hujan,” kata Oscar Oliviera, pemimpin buruh setempat dalam The Water Barons
Menurut Jim Schultz, Direktur Eksekutif ‘The Democracy Center’, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Cocha–bamba, dalam Bolivian Rise Againts Globalized Water Price, ceritanya berawal

pakaian.
Kenaikan itu tentu saja memberatkan. ”Di negara yang rakyatnya tergolong beruntung untuk mendapatkan 100 dolar per bulan,” tulis Jim Schultz. Beberapa artikelnya tentang privatisasi air di Cochabamba kemudian diterbitkan dengan titel Globalization and War for Water in Bolivia
Reaksi masyarakat setempat ditandai dengan pembentukan La Coordinadora. Sebuah aliansi yang terdiri dari pribumi, buruh, pedagang, kaum pecinta ling–kungan hingga pejuang hak asasi manusia. Koalisi ini, pada 4 pebruari 2000, lantas melakukan pemogokan massal di kota Cochabamba. Massa, tulis Schultz, me–lakukan longmarch sepanjang kota. Tidak ada aktivitas berarti. Tidak ada bus tran–sport, penerbangan atau mobil berse–liweran.
Sehari berikutnya, presiden Bolivia, Hugo Banzer mengerahkan ribuan aparat polisi untuk mengatasinya. Mengutip Oscar Oliviera, pemimpin buruh yang juga pemimpin La Coordinadora, presiden Banzer menyebut demonstran sebagai ekspresi fasisme, tindakan ilegal dan tidak mewakili warga Cochabamba.
p residen Hugo Banzer merupakan pemimpin diktator yang pernah memimpin Bolivia sejak 1971 hingga 1978. Saat itu, ia terpilih tidak lewat pemilihan umum, melainkan lewat kudeta. Menjadi presiden terpilih di tahun 1997. Banzer juga karib diktator Chile, Augusto pinochet.
polisi yang dikerahkan hanya punya satu kewajiban: patuh pada kekuasaan.
”Bagaimana jika kamu disuruh mem–bunuh saya sekarang, apakah akan kamu lakukan?” tanya Jim Schultz pada seorang polisi.
”Tentu,” jawabnya.
dari tekanan Bank Dunia pada pemerintah Bolivia untuk menjual pengelolaan airnya. Itu terjadi, lanjutnya, pada Desember 1999. Dan sejak Januari 2000 ‘Aguas del Tunari’, perusahaan swasta bikinan, itu mulai beroperasi dengan menarik rekening bulanan pelanggan
Alangkah terkejut ketika pelanggan mendapati kenaikan empat kali lipat dari tarif sebelumnya yang saat itu masih dikelola pemerintah setempat.
”Apa yang kita bayar untuk air setara dengan apa yang kita bayar untuk ma–kanan, pakaian dan kebutuhan lain untuk anak kami,” kata Tanya p aredes se–bagaimana dikutip dalam tulisan Schultz. Tagihannya naik dari 5 dolar menjadi 20 dolar. Tanya paredes adalah seorang ibu dengan lima anak bekerja sebagai penjahit
”Bukankah warga di sini juga punya hak untuk protes atas harga air yang melonjak?” tanya Jim lagi.
”Ya..Kita semua punya hak. Saya hanya ikuti aturan,” jawab polisi itu.
Jawaban polisi tersebut setidaknya adalah realitas. polisi lokal melihat orang tuanya demonstrasi di jalanan Cocha–bamba juga merupakan realitas. Itu bikin presiden Banzer memutuskan untuk ‘meng–ambil’ juga, aparat polisi dari luar wilayah Cochabamba. Bisa jadi ini strategi represif Hugo Banzer, sang diktator.
April 2000. Sudah empat bulan ber–langsung demonstrasi menentang keha–diran ‘Aguas del Tunari’ di Cochabamba. p erusahaan hasil konsorsium Bechtel dan United Utilities. Bechtel Corporation merupakan perusahaan waterworks yang
bermarkas di San Francisco, Amerika Serikat.
Dalam kasus Cochabamba, mengutip statement yang dikeluarkan Bechtel Cor–poration April 2000, Bechtel Enterprises, salah satu anak perusahaan Bechtel Corporation, menggandeng Edison S.p.A, sebuah afiliasi dari Montedison Group, perusahaan energi terbesar di Italia. Keduanya lantas bikin perusahaan kon–sorsium bernama Internationat Water Limited (IWL). pusatnya berada di London. Lewat inilah Bechtel masuk dalam penge–lolaan air publik di Cochabamba, Bolivia.
The Observer edisi 23 April 2000, pernah mengungkapkan peran IWL di Cochabamba. Mulai alasannya kenapa IWL tertarik, dan bagaimana kemungkinan cara yang ditempuh. Menurut media terbitan London itu, IWL punya kepentingan karena rencana monopolinya mengelola sumber air distrik Cochabamba dengan menghubungkan proyek dam Misicuni. Sebagai catatan bahwa proyek dam Misi–cuni sebagian dimiliki IWL.
Jika itu berlangsung, maka warga tidak ada pilihan kecuali hanya memilih IWL. ”Ini adalah hati, jiwa dan justifikasi oleh sistem yang disebut kapitalisme,” tulis The Observer
Harian itu juga melansir kemungkinan IWL ‘bermain’ lewat Jaime p asamora, pemimpin partai yang berafiliasi dengan presiden Hugo Banzer.
”Misterioso.”
Jumat, 7 April 2000. Demonstran tetap bertahan pada tuntutan: menolak kehadiran swasta dalam sistem pengelolaan air Cochabamba. Mereka berkumpul di pusat plasa, berseberangan dengan kantor pemerintahan. Memblokade jalanan. Sambil membawa tongkat dan sapu tangan untuk mengantisipasi serangan gas air mata. Media lokal berspekulasi pemerintah Bolivia akan mengumumkan keadaan darurat perang.
Dan terbukti benar.
Keesokan harinya, pukul 10 pagi, presiden Hugo Banzer mengumumkan pem–berlakuan martial law . Dengan keadaan begini, ”Banzer mencabut hampir seluruh hak-hak sipil, sedikitnya empat orang ditangkap, membatasi kebebasan pers. Stasiun radio lokal diambil alih oleh militer atau dihentikan siarannya,” tulis Jim Schultz. Hingga malam harinya, polisi mendatangi rumah-rumah para demonstran dan menangkap kurang lebih 20 orang. Dikabarkan pula, Victor Hugo Daza, se–orang remaja berusia 17 tahun tewas tertembus peluru di bagian kepalanya.
Beberapa hari berikutnya, diberitakan,
Pandu L. Patriari / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Diskriminasi Air. Menimpa kaum marjinal di negara yang telah memprivatisasi pengelolaan airnya.
Direktur Bank Dunia waktu itu, James Wolfensohn, datang ke Bolivia. Tak lebih karena kepentingan ekonomi-politiknya.
Menurut The Water Barons , wacana pri–vatisasi air di Cochabamba sebenarnya telah mengemuka sejak 1995. ”pemerintah Bolivia sepakat, sebagai bahan kebijakan, dengan pandangan Bank Dunia, bahwa privatisasi diperlukan di sana,” kata Christoper Neal, bagian external affairs Bank Dunia untuk Amerika Latin kepada International Concorcium of Investigative Journalist (ICIJ), penulis The Water Barons.

Bank Dunia merupakan lembaga ke–uangan supranasional yang sarat akan kepentingan ekonomi-politik Amerika, selaku penggagas dan ‘penguasanya’. Didirikan di Bretton Woods, New Ham–pshire, Amerika Serikat tahun 1944.
Menurut Bruce Rich dalam buku Meng–gadaikan Bumi, definisi Bank Dunia tentang ‘politik’ dan ‘pengaruh politik’ tampak seperti yang digambarkan dalam Alice in Wonderland . Bagaimana pun bentuk praktiknya, yang jelas menurut Bank Dunia bukan termasuk politis karena tindakan itu tidak dirumuskan sebagai tindakan politis. Sejak semula penggunaan pengaruh dan tekanan politik oleh Bank Dunia terus berlangsung. pengaruh dan tekanan politik itu tidak dirumuskan dalam syarat-syarat pinjaman pada proyek-proyek tertentu, tetapi pada persoalan yang lebih luas dari kebijakan sosial dan ekonomi nasional. Bisa jadi ini ditemukan lewat
kasus Cochabamba di Bolivia mau–pun Watsal di Indonesia.
Tak jauh beda dengan Negara Bagian Gujarat dan Maharashtra, India. Menurut Vandhana Shiva dalam Water Wars, Bank Dunia mendorong privatisasi sebagai pengganti dari sistim pengairan yang sarat teknologi yang dulu diprakarsai Bank Dunia sendiri. ”Hasilnya adalah percepatan penghisapan air tanah,” tulis Vandhana Shiva. Ia adalah pemikir- cum -aktivis pecinta lingkungan yang berasal India. pernah memimpin Interational Forum on Globalization di tahun 1993. Sebelumnya ia adalah seorang pemikir fisika terkemuka. Latar belakang kepindahan disiplin ilmunya ke ekologi didasarkan pada lenyapnya sumber air di Himalaya. Tempatnya bermain sewaktu kecil.
Meski berada di tempat paling basah di bumi, menurut Vandhana Shiva, Himalaya mengalami persoalan air minum. Tak lain karena pengrusakan hutan besar-besaran untuk industri.
Di p erancis, privatisasi air kental dengan nuansa skandal politik tingkat tinggi. Bahkan, menurut The Water Barons, presiden Jacques Chirac sempat dimintai keterangan kejaksaan setempat. Untuk menjelaskan seputar privatisasi penge–lolaan air di paris. Sebelum jadi presiden, Chirac merupakan walikota p aris sejak 1977 hingga 1995. Setelah itu, ia terpilih menjadi presiden dan menjabat untuk kedua kalinya di tahun 2002. Menurut kumpulan laporan investigasi ICIJ itu, Jacques Chirac punya hubungan dekat dengan Jerome
Monod, chief executive organization (CEO) Suez Lyonnaise des Eaux, perusahaan air terbesar di dunia.
” p erancis adalah tanah kelahiran privatisasi air,” demikian The Water Barons. Setidaknya tindakan itu telah dimulai sejak zaman Napoleon. Tiga perusahaan air swasta terbesar, bermarkas di negara ini. Yakni: Suez Lyonnaise des Eaux, Vivendi Environnement, dan Saur. Ketiganya, lansir The Water Barons, menguasai 80 persen pasar air di perancis.
Menurut klaim ICIJ, Suez memiliki total pelanggan 115 juta orang pelanggan di 130 negara di dunia. Vivendi punya 110 juta. Sedang, perusahaan swasta air ketiga Thames Water, yang dimiliki RWE Jerman, memiliki 70 juta pelanggan.
Kota Grenoble, perancis, adalah paris yang lain. Di kota ini pada 1994, Jerome Monod, membantu proses privatisasi pengelolaan air setempat. Dengan cara menyuap sebesar $3 juta untuk dana kampanye ilegal dan juga tuduhan pe–nipuan pelanggan. Akibatnya, Alain Carignon, walikota Grenoble saat itu dihukum. Begitu pula dua executive Suez: Jean-Jacques prompsy dan Maro-Michel Merlin. Sedang, keterlibatan Monod tidak bisa dibuktikan.
Lebih menyedihkan lagi imbas pri–vatisasi air di Afrika Selatan. Ribuan orang terjangkiti kolera lantaran tidak dapat mengakses air bersih. Di kota Nkobongo, pengelolaan air dikuasai oleh Saur, peru–sahaan swasta asal perancis. Aliran air ke rumah David Radebe, seorang warga setempat, terpaksa diputus. Tidak kuat bayar.
penduduk diperkenalkan pembayaran air dengan sistem yang terhitung edan . p akai cara mirip kartu telepon. Untuk mengaksesnya, harus beli voucher kartu air terlebih dahulu. Digosok ke tiap keran yang aktif. pelayanan air akan berhenti jika kartu telah habis. Artinya, pelanggan harus beli voucher lagi.
”Voucher meters merupakan tipuan busuk,” kata McDonald, seorang peneliti di Universitas Witwatersrand, Afrika Selatan.
Dan ujungnya, yang jadi korban adalah mereka yang tak berduit. Tak mampu beli lantaran privatisasi air. Mereka tersebar di pilipina, Argentina, Australia, bahkan di negara Amerika Serikat sekalipun.
Tak terkecuali Indonesia.
Indra Yudhitya HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
Bukan Lautan Hanya Kolam
Salah satu alasan yang lumayan masuk akal dan digunakan swasta untuk mengambil alih urusan publik adalah tingkat korupsi yang hebat. Kondisi sebagian besar Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), yang milik publik itu, menunjukkan gejala demikian. Menurut laporan Perpamsi 2002 saja, total utang PDAM yang berutang--lebih dari 180 unit PDAM--sekitar Rp 4 trilyun. ”Bahkan ada 25 PDAM yang utangnya lebih besar ketimbang total asetnya,” kata Wijanto Hadipuro, dosen Universitas Katholik

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Sumber Data: Laporan perpamsi 2002/ diolah redaksi HIMMAH
Soegijapranata, Semarang. Meski demikian privatisasi bukan jalan terbaik. Karena tidak ada jaminan dikelola swasta pun, korupsi bakal lenyap.
”Salah satu langkah terbaik adalah partisipasi warga lewat pembentukan forum pelanggan,” tambahnya. Sehingga dapat diawasi jalannya pengelolaan PDAM. Tidak korup melulu. Berikut adalah 100 PDAM dengan utang terbesar:

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
Kisah Partnership swasta-
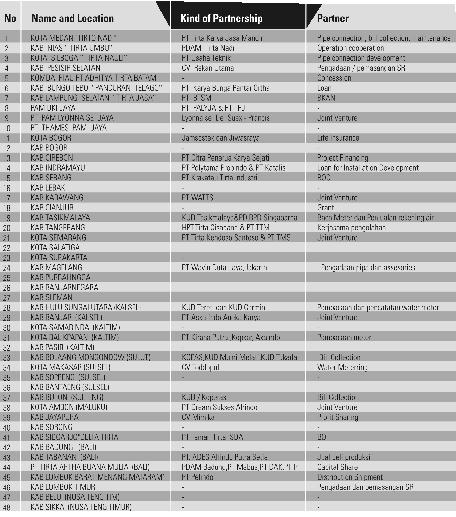 Berikut adalah sedikit gambaran kemitraan yang terjadi antara PDAM dan beberapa kontraktor jaringan perpipaan di Indonesia.
Sumber Data: partnertship Swasta pDAM - Di Indonesia
Berikut adalah sedikit gambaran kemitraan yang terjadi antara PDAM dan beberapa kontraktor jaringan perpipaan di Indonesia.
Sumber Data: partnertship Swasta pDAM - Di Indonesia
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
”Air untuk Industri Beri
Proritas Rendah Bagi Kebutuhan Pokok”
Pandangan Anda tentang air?
Dalam UUD 1945, air dikuasai negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masy a -rakat. Negara adalah rakyat, bukan peme-rintah yang hanya penerima mandat. Air milik bersama karena menurut siklusnya. Lewat tanah atau saluran, sumursumur milik rakyat. Hanya pada waktu penge-lolaan, air itu menjadi punya nilai ekonomis. Tapi sebetulnya itu tetap public goods. Menjadi komoditas ekonomi karena jum-lahnya semakin berkurang. Itu bisa salah karena air punya nilai tinggi bukan dari sisi ekonomi.
Realitasnya?
Undang-undang yang ada belum bisa menjamin hak akses terhadap air. Banyak air yang dijual untuk kepentingan industri yang mungkin memberikan prioritas lebih rendah ke kebutuhan pokok. Seperti Aqua di Klaten. Jawa Barat di daerah Karawang. Sehingga petani yang awalnya bisa meman faatkan air untuk irigasi, sekarang tidak. padahal petani menyediakan beras untuk negara untuk memproduksi pangan. Tapi kalau dihambat untuk mendapatkan air untuk produksinya, itu tidak benar. Ini yang seharusnya diperhatikan. Sehigga perlu UU pengaturnya. Supaya akses masyarakat terhadap air lebih baik. Kalau UU malah mengesahkan praktik yang tidak baik, ini akan meresahkan. privatisasi adalah hak pengelolaan air diberikan swasta, publik tidak diberikan hak untuk mengatur. Kalau rakyat tidak ikut menentukan nilai, maka akan menghidarkan akses rakyat yang tidak mampu untuk membayar.
Bagaimana dengan perusahaan air macam Aqua ? Ini bukan hasil privatisasi.

Itu masuk ke industri. Maka dalam UU nanti harus ada prioritas penggunaan air. Sekarang ini belum tegas. Dalam hak guna pakai tidak membayar, ini tidak memerlukan ijin. Sedang hak guna usaha, nanti meme r-lukan ijin. Yang menjadi masalah kalau terjadi kekurangan air. Siapa yang nanti diprioritaskan? Yang punya hak guna usaha pasti yang akan menang karena mereka punya bukti legal formal. Walaupun nanti ada alokasi air lewat Dewan Air di tingkat pusat atau daerah. Makanya diperlukan prioritas. Dalam RUU (sudah disyahkan-red) adalah kebutuhan pokok. Dalam UU, prioritas selanjutnya ditentukan peme-rintah daerah. Memang dalam ayat selan-jutnya dikenal adanya kompensasi. Dari yang tidak penting bisa didahulukan daripada yang penting. Ini kan berbahaya. ini yang ditakutkan masyarakat.
Berarti perusahaan seperti Aqua juga dapat mengancam aksesibelitas masya rakat terhadap air? Kalau dia mengeksploitasi air besar-besaran saya kira iya.
Bagaimana cara untuk membatasinya? Kita harus tahu bahwa air milik publik, maka tidak boleh air dikuasai privat. Dalam UU itu harus ditegaskan. Di samping bahwa air tidak hanya untuk minum tapi juga untuk lingkungan. Jadi tidak semua air tidak bisa dimanfaatkan semua.
Kebanyakan privatisasi air ini dilakukan di negara berkembang. Ada kecenderu ngan apa menurut Anda? Di negara-negara berkembang banyak utang, maka memerlukan investasi. Sehing ga orang yang mau berinvestasi dapat
menguntungkan. Kalau di Helsinki, air pDAM itu gratis, karena tidak menimbulkan efek nilai tambah. Tapi untuk pertanian harus bayar karena produknya dijual. Kalau di sini beda konsepnya. Air minum harus bayar lebih mahal ketimbang bensin. Sehingga para pemodal menginvestasikan ke negara-negara berkembang. Tapi ter nyata itu dilawan karena air adalah kebu tuhan pokok. Mereka melihat, seperti Aqua, itu mendatangkan keuntungan yang besar.
Sejauh mana Anda mengamati perdebatan air di Bank Dunia?
Itu perdebatan lama. Idenya memang meningkatkan partisipasi masyarakat supaya tidak tergantung lagi pada dana pemerintah. p adahal sekarang petani membutuhkan air yang paling banyak. Kalau itu diserahkan petani, subsidinya dikurangi, maka beban petani menjadi lebih berat. Harga beras kita mahal, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jika kita lihat bagaimana beras dari luar negeri relatif murah, karena negaranya memberikan perhatian besar kepada petani. Subsidi yang besar.
Anda melihat perubahan kebijakan Bank Dunia?
Saya tidak begitu melihatnya. Bank Dunia itu kan disetir oleh donor-donornya. Mereka ingin World Bank memberikan tempatnya untuk berinvestasi di sini. Sekarang World Bank dalam Watsal mem-punyai program reformasi kebijakan sektor air. Dan dikhawatirkan negara-negara donor yang ada di belakang Bank Dunia membuat
Salah satu penyebab petani menderita adalah perlakuan diskriminatif masalah air. Penggunaan air, dalam banyak kasus, lebih diutamakan untuk kalangan industri. Berikut petikan wawancara Widiyanto dari HIMMAH dengan Ir. Budi Wignyosukarto, dosen sekaligus Kepala Laboratorium Hidrologi, Fakultas Teknik UGM tentang hal itu.
Indra Yudhitya HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN UTAMA
Ir. Budi Wignyosukarto:
Kedatangan yang Tak Diharap
IVON
kecewanya bukan main. Air yang mengalir ke rumahnya masih saja kotor. Hingga perlu waktu untuk mengendapkan dulu, sebelum dipakai. ”Coba saja lihat sendiri di kamar mandi,” katanya.
”Kayak ada serpihan pasirnya.”
padahal tidak sekali, dua kali ia sudah mengadu ke pDAM Sleman, tempatnya berlangganan air. Hasilnya? Nol alias tidak ada perubahan. Ia mengaku selalu bayar rekening tiap bulan. Ivon adalah seorang advokat yang tinggal di sebuah perumahan di Kecamatan Kalasan, Sleman.
Keluhan Ivon tak hanya itu. Airnya malah sempat macet selama seminggu. ”Itu terjadi dua kali,” katanya.
Ia tambah kaget ketika saya tanyai perihal kerjasama pemprov D.I. Jogjakarta dengan Amiwater dalam penyediaan air bersih. Sebuah perusahaan air yang berpusat di Tyrol, Swiss. Dalam perjanjian ini Amiwater diwakili direktur anak pe–rusahaannya, Inframan: Kordi Khaled Abdul Fatah.
”Saya baru dengar kali ini,” katanya.
”Benar, lo!”
p adahal penandatanganan memo–randum of understanding (MoU) Sultan HB X-Amiwater ini sebenarnya terjadi sudah lumayan lama: 30 Juni 2003 lalu. Nominalnya sekitar 25 juta dollar AS. Terdiri atas tiga buah MoU: perjanjian pengam–bilan Air, Off Take, dan perjanjian DBOT, singkatan dari design , build , operate dan transfer pemprov dalam perjanjian pengambilan Air ini berperan sebagai pemberi lisensi, sedang Inframan sebagai pemegang lisen–si. Isi perjanjiannya terhitung gendeng . pemegang lisensi diberi kewenangan yang sangat luas. Tapi sebaliknya untuk pemberi lisensi. Misal, dalam poin 3.3,
”Pemberi lisensi akan memberikan akses yang tidak dibatasi pada pemegang lisensi untuk memanfaatkan sumber air baku dan ke lahan umum dan penduduk.” Ada tujuh sumber mata air yang re–ncananya akan digunakan di perjanjian ini. Kesemuanya berada di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah:
* mata air Treko
* mata air Tampir Kulon
* mata air Kanoman
* mata air pisangan
* mata air Ngasem
* mata air Gending
* mata air besar vulkanik dengan kua–litas yang baik di lereng barat Gunung Merapi.
Karena urusannya lintas propinsi, maka harus diadakan perjanjian antar-gubernur yang bersangkutan untuk urusan ini. ”Itu sudah oke,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi D.I. Jogjakarta, Bambang S. priyohadi.
Sepanjang penelusuran saya, mata air yang dimaksud itu belum beres. Ini fakta keganjilan pertama. Bahwa Sekda Bambang S. priyohadi, sendiri sebenarnya sudah berkirim surat ke Gubernur Jateng, Mar-diyanto, sekitar awal Oktober 2002. Dela-pan bulan sebelum penandatanganan MoU.
Dalam surat itu, Bambang S. p. me–nyatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan air baku yang cukup untuk diolah menjadi air bersih oleh tiga pDAM di D.I Jogjakarta. Ditambahkan juga dalam surat itu, pemaparan survei awal Bambang S. p. terhadap beberapa mata air yang ternyata sama seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Sekaligus debitnya.
Bambang S. p. tidak jelas menyebut ketiga p DAM dalam surat tersebut. Ini bisa jadi pertanyaan awal kenapa Sekda propinsi tidak secara tegas menyatakan pDAM mana saja yang dimaksud? Kenapa mata airnya sama dengan sumber mata air yang dimaksud dalam perjanjian? Apakah ini akan digunakan untuk memenuhi MoU dengan Amiwater? Yang kenyataannya terbukti delapan bulan kemudian? Jika dirunut, ini jelas terkait erat dengan MoU Sultan HB X-Amiwater via Inframan.
Djoni Supardi, Direktur Utama (Dirut) pDAM Kabupaten Mungkid, menyatakan kepada saya bahwa sampai sekarang ia belum menerima proposal MoU peng–ambilan air baku di wilayahnya. ”Saya belum lihat MoU-nya,” katanya.
”Harusnya ada perjanjian antara Jogja dengan sini (Kabupaten Magelang-red). Kita ikutnya ya nanti kalau sudah sampai pada tahap perencanaan.”
Fakta lain yang membuktikan bahwa terdapat ketidaksiapan perencanaan mata air dalam MoU adalah seorang Sudoyo, 62 tahun, penduduk Treko, Candisari.
pemilik tanah yang kebetulan terdapat mata air. Hanya di atas tanah miliknyalah satusatunya mata air yang terdapat di daerah itu. Dia justru bercerita bahwa dirinya pernah didatangi oleh Djoni Supardi dari pDAM Kabupaten Magelang.
Ini merupakan fakta keganjilan kedua. Mata air Treko, salah satu mata air yang dimaksud dalam MoU, belum sepenuhnya dibebaskan dari pemilik tanahnya.
Masih dalam perjanjian pengambilan Air. Dinyatakan bahwa pemberi lisensi, dalam hal ini pemprov D.I.Jogjakarta, akan menerbitkan asuransi tanpa biaya atau pasar setempat, semua keinginan yang diperlukan untuk pengambilan air baku secara kuantitas dan kualitas, sebagaimana diuraikan di sini dan kelanjutan dari dokumen teknik.
Bisa jadi ini ibarat amunisi ultra-power bagi Inframan.
Sedangkan untuk perjanjian Off Take tak jauh beda. Boleh jadi malah lebih mengerikan. Dari perjanjian ini akan di–bentuk BpAB. Singkatan dari Badan pengelolaan Air Bersih. Dalam keterangan–nya, yang dimaksud BpAB adalah peru–sahaan yang akan didirikan di Jogjakarta, dan tunduk pada hukum Indonesia (single off-take) atas nama pDAM. Keberadaannya permanen.
Kedudukan BpAB akan menggantikan peran tiga unit pDAM di Jogjakarta. Dalam laporan media massa yang dimaksud ketiga pDAM itu adalah pDAM Kodya Jogjakarta, pDAM Sleman dan pDAM Bantul. Sebagai catatan, selama ini, keberadaan p DAM berada di tingkat kota, bukan provinsi.
Sekda Bambang S.p. pernah mengata–kan bahwa, ”di pDAM itu ada problem kebocoran. Nanti pengembalian (investasired) akan sulit.”
Soedaryanto, pjs Dirut pDAM Sleman membantah hal itu. ”Kita malah untung. Cash-flow,” katanya sebelum pensiun per 1 Maret 2003 lalu. Demikian pula kata Dachron Saleh, Dirut pDAM ‘Tirtamarta’ kota Jogjakarta. ”posisi keuangan pDAM sudah mendapatkan keuntungan walaupun belum dapat mendukung sepenuhnya program penggantian perpipaan secara total,” katanya menjawab pertanyaan tertulis saya.
Jika skema dalam perjanjian Off Take ini diterapkan, maka secara otomatis peran ketiga pDAM itu akan bergantung
Gubernur D.I. Jogjakarta, Sultan Hamengku Buwono X, pernah menandatangani nota kesepahaman dengan Amiwater,
Oleh WIDIYANTO
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
pada kontrol BpAB. Tidak lagi berusaha sendiri mengelola mata air untuk mensuplai pe–langgan.
padahal ketiga pDAM, menurut Soe daryanto, telah melakukan kerjasama dalam sebuah forum bersama. Tidak bersifat per–manen dan yang jelas masih ‘mengakui’ keberadaan ketiga pDAM. ”Sudah survei awal, lalu sudah mendapatkan rancangan biaya,” katanya.
Forum bersama itu bahkan telah ter bentuk sejak Januari 2003. Lima bulan sebelum penandatangan MoU p emprov D.I.Jogjakarta-Amiwater.
Di sini bukti keganjilan ketiga. Kenapa perjanjian ini tidak langsung ke pDAM? Tapi justru ke provinsi. Bukankah antartiga pDAM itu terdapat forum bersama? Mengapa lantas mengambil alih peran p DAM? Apakah karena faktor utang pDAM yang menurut Sekda bakal bikin kuatir investor? Toh, dua orang dirut telah membantahnya.
Di samping itu, yang juga ditetapkan dalam perjanjian Off Take ini adalah pembentukan perusahaan konsorsium yang bertanggung jawab untuk melakukan desain, konstruksi dan pembangunan, operasi dan perawatan. Bernama PIC , Project Implementing Consortium dengan pemegang saham utama adalah Inframan. Jangka waktunya 25 tahun dan itu bisa diperpanjang lagi.
Secara logika, ini merupakan praktik masuknya Inframan untuk mengurusi pe–ngelolaan air tiga pDAM di Jogjakarta. pengelolaan yang seharusnya dikelola oleh lembaga publik
* * *
S UATU siang di akhir Juni 2003. Dua orang laki-laki dengan pakaian rapi, menandatangani sebuah perjanjian pe n ting. Tentu dua orang itu bukan orang sembarangan. Yang mengenakan jas adalah orang nomor satu di Jogjakarta, Sultan HB X. Seorang lagi, di sebelah kirinya, menge nakan pakaian ke-Arab-an: penutup kepala, baju gamis. Dialah Kordi Khaled Abdul Fatah, Direktur Inframan, perusahaan air dari Swiss.
Hadir beberapa pejabat penting di ling–kungan provinsi dan beberapa kabupaten di Jogjakarta. Diantaranya Soedaryanto, pjs Dirut pDAM Sleman.
Setelah penandatanganan itu, ia lantas berbincang dengan Ngarso Dalem (Sultan HB X). ”Wah, Bapak Gubernur, kami itu kaget,” katanya.
”Yang sudah ya sudah, nanti kita melibatkan,” ujar Soedaryanto mengutip Gubernur D.I.Jogjakarta, Sultan HB X.
”Jadi judulnya, saya kaget,” kata Soedaryanto pada saya. Maklum, “s e belum itu, kami belum tahu isi MoU itu.”
Hal yang senada juga dialami Dach–ron Saleh. ”Saya tahu setelah diundang pada saat penandatanganan,” katanya. Sebelumnya pun ia mengaku tidak pernah dilibatkan.

Keduanya membantah pernyataan bahwa Sekda Bambang S.p. telah mem–beritahukan rencana kerjasama ini, dua tahun sebelumnya.
Ini bentuk keganjilan berikutnya.
Dalam sebuah pemberitaan di Kompas, seminggu setelah penandatanganan, Ibnu Subiyanto, Bupati Sleman meny a takan bahwa pihaknya belum sepakat dalam tarif Rp 800 per meter kubik yang ditetapkan
pemprov D.I Jogjakarta. Harga jual air oleh pDAM Sleman sampai Desember 2003, kata Ibnu Subiyanto, berkisar Rp 1.000 per meter kubik.
”Tentu dengan selisih Rp 200, jelas tak cukup untuk membiayai operasional,” katanya saat itu. Karena menurutnya tarif yang ditetapkan pemprov D.I.Jogjakarta, itu terlampau tinggi. Bisa-bisa ini adalah bentuk keganjilan untuk kesekian kalinya.
Tapi untunglah itu semua sudah berlalu. Karena MoU akhirnya dihentikan.
Gubernur DIJ Sri Sultan HB X. Pernah menandatangani MoU dengan investor asing untuk mengelola air bersih di Jogja.
HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
LAPORAN UTAMA
Dokumen
Dr. Wijanto Hadipuro:
”Tak Ada Swasta Beri Barangnya pada Orang tak
Kondisi sebagian besar PDAM di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Padahal perusahaan ini merupakan milik publik yang diserahi untuk melayani kebutuhan air perkotaan. Bagaimana komentar akademikus Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang yang ikut gabung dalam Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), mengenai hal itu?
Menurut Anda, soal air ini harus dikelola oleh negara?
Menurut saya harus dikelola negara. Saya belajar UU perancis yang katanya banyak perusahaan swasta besar di sektor air. Bahwa air itu harus dikelola oleh negara. Jerman itu sangat anti-privatisasi air minum. Karena mereka tahu kalau air dikelola swasta, maka akan berakibat fatal bagi warga negaranya. Menurut saya air ini harus dikelola oleh negara. Negara harus memberikan kita, akses air. Lalu dikelola pemerintah korup. Di sektor irigasi; pDAM air perkotaan, karena rakyat tidak dilibatkan di situ. Menurut saya, air itu merupakan hak asasi, negara harus menjamin kita untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu harus dikelola oleh pemerintah. Tidak mungkin oleh privat. pemerintah wajib memprioritaskan kita untuk me n -dapatkan air bersih. Untuk mengatasi masalah korupsi, nepotisme, mestinya masyarakat dilibatkan. Sayang kontrol dari masyarakat belum sampai ke sana.
Termasuk pemasangan instalasinya? Oh ya, itu termasuk kewajiban. Akses kan termasuk jaringan pipa. Apa perlu m e- libatkan swasta? Kita kuatir, kalau pri-vatisasi berjalan, seperti dalam RUU, di mana swasta itu boleh mengelola teknologi modifikasi cuaca, hujan itu bisa dilakukan oleh swasta. Satu sungai bisa dikelola oleh swasta. Akhirnya pengelolaannya kan parsial. Itu berbahaya sekali. Air itu ada siklus hidrologi yang tidak bisa dikelola secara parsial. Jadi mengapa negara yang harus mengelola air? pemerintah itu banyak, parsial. Bahwa air tidak bisa dikelola dalam batas-batas wilayah ad-ministratif. Bukan dikelola oleh pemda dan pemkot. Akhirnya daerah berlomba-lomba mencari
pAD (pendapatan asli daerah-red). Air itu salah satu sumbernya.
Sejauh pengamatan Anda, masuknya swasta ke PDAM, apakah karena financing atau pengelolaan PDAM? Ya. pDAM buruk sekali. Sekarang ini 41 persen penduduk tinggal di perkotaan. Dari ini, hanya 51,7 persen yang mendapat akses air bersih. Buruk sekali. Ada 25 pDAM itu utangnya lebh besar dari asetnya. Utang itu datangnya dari mana? ADB dan juga WB.
Efeknya yang paling ditakutkan dari privatisasi?
Efeknya orang miskin. Ini kalau di per kotaan, ini akan semakin jauh dari akses air bersih. Apa ada perusahaan swasta yang memberikan barangnya kepada orang tidak mampu? Tidak ada.
Menurut Anda, sejauh mana LKI ini mengintervensi PDAM di Indonesia? Intervensinya macam-macam. Di Surakarta lewat utang. Ada 27 proyek World Bank yang beroperasi di Indoensia. Mulai dari tahun 1983-2002. Banyak yang termasuk air perkotaan. Termasuk Semarang. Ada syarat yang baik, yang tidak sesuai menurut saya adalah pelibatan swasta dalam sektor air.
Anda sempat menyinggung adanya peru-bahan policy World Bank soal air, tra-dable water rights. Itu paper yang dikarang oleh paul Holden dan Marten Thobani. Kalau 1993 itu ada paper water resource management policy paper. Dia tidak menyebut secara tegas, dan di appendixnya yang konyol. Di situ dikatakan water market. Itu tidak mungkin, karena ada empat faktor yang meyebabkan
kenapa air tidak dapat digunakan dalam mekanisme pasar. p ertama, air adalah barang publik. Itu tidak bisa langsung mekanisme pasar menyelesaikan itu. Harus ada intervensi pemerintah. Yang kedua, masalah ekstralitas. Saya mencemari air.lalu saya dibebani berapa? Itu sulit dihitung. Saya mencemari air di daerah hulu,berapa kerugian yang dialami di derah hilir. Itu sulit untuk dihitung. Selain itu, air tidak hanya public goods tapi juga harkat goods. Harkat kita sebagai manusia. Untuk wudlu tanpa air, kita tidak mungkin menjadi manusia yang sehat. Sehingga nanti banyak kepentingan masyarakat te r -ganggu. Akhirnya muncul kepentingan politis. Dan keeempat, biaya transaksinya sangat besar. Konyolnya World Bank sendiri mengakui ada market failure, kegagalan pasar.
Itu berlangsung sejak tahun 1993? Sejak tahun 1993 kemudian dibenarkan lagi tahun 1996, tahun 2003 ada suatu dokumen lagi bernama water resource strategic: an overview . Mereka membenarkan policy tahun 1993. Bahkan sekarang yang lebih berbahaya adalah mereka akan kembali lagi ke bendungan-bendungan besar. Karena air itu sering mubasir. Ini akan ada Kedung Ombo-Kedung Ombo lagi. Sampai s e karang World Bank masih menganggap ini benar.
Tawaran Anda, masyarakat ikut terlibat berpartisipasi? Betul. Aktif, kalau lewat dewan butuh 2-3 periode untuk mendapat anggota dewan berkualitas.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
PASAR AIR DAN POLITIK UANG
Oleh NANANG I. KURNIAWAN
DALAM perkembangan peradaban manusia, air memainkan peranan penting. Sejarah menunjukkan bagaimana sungai, laut, hujan, danau ataupun mata air menjadi sentrum dinamika masyarakat. Dengan kata lain air adalah kehidupan itu sendiri. Water is life
Persoalan air menjadi serius manakala air tak terdistribusi merata. Sementara itu kebutuhan akan air tidak pernah surut karena meningkatnya jumlah penduduk dan pen g gunaan air yang makin beragam. Di sinilah orang mulai menyoal tentang krisis air. Tahun 2002 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa kini terdapat lebih dari satu miliar orang yang tidak memiliki akses atas air bersih dan lima juta orang meninggal tiap tahunnya karena meminum air yang terpolusi. Krisis ini akan meningkat pada tahun 2010 di mana diperkirakan sekitar 2,5 milyar penduduk dunia akan mengalami kekurangan air.
Perkembangan yang ada kini justru menunjukkan wajah yang ironis. Krisis air yang sebenarnya mesti ditangani dengan nalar water is life justru diubah menjadi water is commodity Permintaan yang makin tinggi atas air dijawab dengan prinsip ekonomi neoliberal yang menyatakan bahwa segala interaksi sosial adalah ekspresi interaksi ekonomi. Suplai terhadap permintaan air direduksi maknanya secara ekonomis sehingga menanggalkan dimensi sosiologis, religius, kultural maupun ekologis.
Kelangkaan ( scarcity ) adalah jantung ekonomi liberal. Dengan ini maka korporasi akan mengkonversi krisis ekologi sebagai pasar kelangkaan. Kontrol atas kelangkaan sumberdaya air sudah barang tentu menjadikannya sebagai sumber profit. Bagi para pendukung ekonomi neoliberal sistim pasar adalah jawaban terbaik bagi penyediaan air di dunia. Dalam konteks ini air dimengerti sebagai sumberdaya alam yang mesti diletakkan dalam hukum permintaan-penawaran serta harga pasar. Di sinilah ekonom liberal berbicara tentang pentingnya hak atas pengelolaan air.
Dengan adanya pasar air, maka pemegang hak-hak atas air tidak hanya akan berpikir tentang apa yang bisa dihasilkan air bagi mereka, tapi juga tentang opportunity cost dari air. Sehingga nilai tertinggi dari penggunaan air adalah adanya insentif bagi penggunaan yang lebih efisien dan realokasi air ke nilai penggunaan yang lebih tinggi (secara ekonomi).
Makin tingginya permintaan air membuat bisnis air menjadi lahan yang menggiurkan bagi korporasi. ekspansi ke sektor air semakin hari semakin besar. Privatisasi air di dunia saat ini sudah menjadi bisnis bernilai 400.000.000 dollar AS per tahun. Perusahaan air multinasional berharap bisa lebih meningkatkan keuntungan mereka m e lalui perdagangan dan investasi internasional dalam mengendalikan suplai dan pasar air.
Tentu upaya ini tidak mudah karena menghadapi tentangan keras baik dari masyarakat pengguna air maupun organisasiorganisasi non pemerintah. Kisah usang kembali diulang di mana mereka kemudian meminta bantuan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membuka pasar air di berbagai negara.
Dalam satu dekade terakhir, perusahaan multinasional (Trans National Corporations/ TNCs) yang bergerak dalam usaha air telah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk meratakan jalan privatisasi di berbagai negara. Lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut melebarkan pasar air dengan men-desakkan deregulasi sektor air dan membuka investasi asing melalui perjanjian utang
dengan negara yang bersangkutan. Kongkalikong antara TNCs dan le m bagalembaga internasional tersebut bisa dilihat di berbagai forum global. Dalam ‘World Summit on Sustainable Dev e lopment’ (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002, dirumuskan kesepakatan dalam masalah sanitasi dengan jalan privatisasi. Pada bulan Maret 2003, ‘World Panel on Financing Water Infrastructure’ (WPFWI) di Jepang, juga telah menjadi ajang bagi berbagai lembaga donor untuk mendesakkan privatisasi sektor air. Mereka menggagas apa yang disebut sebagai financing water for all Tapi gagasan ini ditengarai beberapa kalangan sebagai bagian dari desain membuka pasar air. Dengan logika water for all maka yang muncul adalah: siapa yang bisa menyediakan dialah yang memiliki kuasa.
Dalam forum itu IMF, misalnya, merekomendasikan korporasi swasta untuk terjun dalam sektor air. Selain itu IMF juga merekomendasikan kepada pemerintah-pemerintah lokal untuk bekerjasama dengan swasta dalam pengelolaan air. Rekomendasi IMF inilah yang disebut sebagai public-private partnership. Bahasa halus privatisasi.

Politik utang memang merupakan alat ampuh privatisasi air yang dilakukan sejumlah lembaga keuangan internasional di negara berkembang. Dengan politik ini peran negara, yang seharusnya menjadi penyedia jasa serta penjamin terdistribusinya air secara murah dan adil berubah menjadi sebatas regulator.
Privatisasi air yang didesakkan lewat mekanisme utang itu jelas akan membawa implikasi yang besar. Paling jelas adalah bahwa privatisasi membatasi akses orang terhadap air. Mereka yang bisa mengakses air adalah mereka yang mampu membayar. Artinya orang-orang miskin akan mengalami kesulitan mendapatkan air karena mereka harus membayar tinggi. Privatisasi air juga akan memperlebar ketimpangan kaya dan miskin, sebab pasar air, baik langsung maupun tidak, akan mengambil hak air orang miskin ke orang kaya. Dengan privatisasi air ketimpangan desa dan kota akan semakin tinggi, di mana air akan lebih banyak dibawa ke kota yang derajat modernisasinya lebih tinggi dan terdapat lebih banyak konsumen yang kuat membayar air. Akibat lainnya adalah bahwa privatisasi akan membuka peluang kerusakan lingkungan akibat over eksploitasi.
Dengan gambaran macam ini maka menjadi logis untuk mengatakan bahwa privatisasi air bukanlah jalan yang tepat untuk mendistribusikan air secara adil dan manusiawi. Negara tetap harus memainkan peran pengelolaan air untuk kepentingan publik. Tentu dengan catatan dilakukan perbaikan manajemen internal dan perluasan kontrol publik atas air sehingga bisa menjamin setiap orang mendapat akses yang adil atas air, termasuk orang miskin. Dengan cara ini maka fungsi air secara sosial dan kultural bisa bekerja serta menempatkan air dan manusia dalam kontinum kehidupan. Sementara, privatisasi air hanya akan berakibat pada pembatasan akses atas air. Dan itu berarti pula sebagai komodifikasi kehidupan.
*Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Mahasiswa Program Master of Public Administration di Adger University College, Norwegia
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
*
KOLOM
Gardu Listrik. Kenaikan harga listrik bikin masyarakat harus cari alternatif untuk berhemat.
Menghemat Listrik Tanpa Mencuri
Oleh AHMAD MAKHALI

KETIKA ditanya bisakah kita hidup tanpa listrik? Semua orang sepakat menjawab tidak. Listrik memang telah menjadi bagian vital kehidupan manusia sejak ditemukan oleh Thomas Alva Edison di tahun 1881. Dan yang paling sering dibincangkan sekarang, tak lain adalah soal tarif yang mesti dibayar. Terlebih ketika pemerintah punya rencana menaikkan secara gradual Tarif Dasar Listrik (TDL) rata-rata sebesar 29,43 persen pada April 2000 lalu.
Kegiatan menghemat listrik seakan jadi menu pembicaraan utama. Menghindari
pemborosan. Dan, tentu saja memotong ongkos yang bakal banyak dikeluarkan. Iklan layanan sosial penghematan listrik pun dipajang mentereng oleh pemerintah via perusahaan Listrik Negara (pLN).
Uups..! Tidak perlu kuatir dulu. Telah ditemukan salah satu alat yang dapat membantu berhemat listrik. Diberi nama Power Up. Nastitin seorang ibu, lulusan Fakultas Teknik Sipil dan p erencanaan (FTSp) Institut Teknologi Nasional Malang yang bikin alat itu.
Menurut sang penemu, pada dasarnya alat ini bukan hal baru karena sudah ada beberapa alat sejenis yang diproduksi
di luar negeri. Rangkaiannya cukup se–derhana. ”Hanya terdiri dari beberapa komponen yang kami rangkai menjadi kapasitor untuk sentral satu rumah,” ujarnya pada saya lewat telepon.
Bagaimana Power Up dapat berfungsi menghemat listrik? perlu dipahami, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pemborosan listrik secara terus-menerus, tanpa disadari. Bisa jadi karena jaringan kabel yang telah usang. Atau tegangan yang tidak semestinya. Yang jelas, pem–borosan daya listrik tetap saja dapat terjadi. Di situlah alat ini dapat menghemat listrik.
Caranya lewat penetralisiran. Power Up dapat menghilangkan daya semu pada saat tarikan awal daya listrik sebuah peralatan elektronik. Dengan mencegah masuknya arus berlebih pada tarikan awal, maka jumlah arus ( ampere ) pada beban yang terpakai dengan tegangan tetap (voltage) akan turun. Sebagai akibatnya, daya (watt) yang terpakai juga akan terkurangi. peng hematannya lumayan banyak, berkisar antara 10-25 persen dari total beban yang sedang aktif.
Alat ini bekerja efektif pada tegangan maksimal 250 V, dengan beban antara 450 – 4.400 watts.
Dengan hilangnya daya semu yang ditimbulkan pada tarikan awal tersebut, kekhawatiran akan terjadinya anjlok saat menghidupkan peralatan elektronik secara bersamaan, dapat dihilangkan. Daya yang diperoleh pun jadi maksimal. Alat ini pun tahan terhadap panas, dan dalam kondisi standby diperkirakan mampu bertahan selama lima tahun. Karenanya alat ini sangat cocok untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, atau pun ruko.
Cara penggunaannya relatif mudah. Hanya dipasang dengan stop-kontak, lalu nyalakan. perlu diperhatikan pula, stopkontak yang kurang baik, misalnya kendur, dapat menimbulkan percikan api. Ini bikin bahaya
Sekarang, Power Up sudah mulai banyak digunakan di masyarakat. Hari–wibowo, salah seorang diantaranya. Ia menggunakan alat ini karena seringnya pemakaian peralatan listrik di rumahnya yang secara bersamaan.
”Ini juga salah satu upaya menekan biaya listrik,” jelasnya.
Meski demikian, menurut pengakuan Nastitin, Power Up masih banyak ke–kurangan.
Namun, paling tidak ia sudah membantu meringankan beban masyarakat atas biaya listrik yang tak karuan!
Indra Yudhitya / HIMMAH
Bagaimana alat ini bekerja dan berguna demi menyiasati TDL yang melan
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 SAINTEK
Tak Cuma Sehelai Kain
Oleh FIRMANSYAH
RISNA, seorang mahasiswi. Kuliah di Fakultas Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Suatu siang, ia terlihat berjalan santai. Me–ngenakan kerudung yang ujungnya diikat ke belakang. Melingkari lehernya. Baju yang dikenakan Risna pun lumayan ketat, hingga bentuk tubuhnya terlihat jelas. Sesekali tangannya meraih ujung baju yang sedikit terangkat. Style celana jeans plus sepatu hak tinggi menjadikannya makin percaya diri. Ia melangkah gontai menuju kampus.
Di tempatnya belajar itu, tiap mahasiswi wajib mengenakan kerudung. Tak terkecuali dosen atau pegawai kampus. pokoknya yang perempuan. Mau tak mau, Risna pun harus menaatinya. Walau, bisa jadi dalam batinnya menolak.
Meski begitu, tak jarang juga ditemui mahasiswi yang berkerudung asal-asalan. Dibiarkan begitu saja oleh dosennya.
Seperti yang diungkapkan oleh Imel. Teman sekampus Risna, dari FTI UII. ”Kalau kita mau bicara jujur, kita tidak setuju (wajib kerudung-red), sebab dari pihak universitas juga tidak mendukung, seperti halnya para dosen ataupun bi–rokrasi,” katanya.
”Maksudnya, ketika kita berpakaian yang tidak sesuai dengan syarat jilbab (kerudung-red) itu sendiri, tidak ditegur sama dosennya.” Imel menambahi, ”kalau mereka (dosen dan karyawan-red) tidak mendukung, ya udah, jilbab ditiadakan saja.”
Imel secara tidak langsung mengkritik pengawasan praktik wajib kerudung di kampusnya. Ketentuan yang telah di sahkan lewat Surat Keputusan (SK) Rektor nomor 40 tahun 2001 tentang Tata Tertib Kampus. Inti surat keputusan itu adalah pengharusan berbusana muslim, tidak ketat apalagi transparan.
Ini permasalahannya. Kebijakan kam–pus mengikat ranah yang dianggap hak privasi seseorang: kewajiban mengenakan simbol keagamaan.
” p ihak kampus tidak mewajibkan ber–jilbab, akan tetapi mengharuskan ber–kerudung dalam menjalankan aktivitas kampus,” ujar Rektor UII, Lutfi Hasan,
ketika saya temui di ruang kerjanya.
Ada perbedaan pokok antara jilbab dan kerudung. Jilbab adalah kain yang me–nutup semua aurat tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan wanita. Sedang, kerudung cuma sebatas menutupi bagian kepala wanita.
Lutfi juga bilang bahwa tidak ada ketentuan khusus bagaimana memakai kerudung dan seperti apa modelnya.
”Dengan adanya kebijakan seperti ini, kita akan membuat kampus bernuansa islami. Walaupun ada banyak kendala yang dihadapi,” tambahnya.
Kehidupan kampus islami macam apa tidak disebutkan secara spesifik oleh Lutfi. Apakah kehidupan yang para kaum perem puannya mengenakan kerudung semua? Sehingga mereka dapat diklaim memiliki tingkah laku yang sesuai dengan makna dan nilai kerudung itu sendiri? Lantas meng usahakannya lewat jalan apapun, termasuk dalam aturan kampus? Tak jelas betul.
Aturan wajib kerudung di UII ini memang relatif baru. Sekitar empat tahun. Bermula pada penyambutan bulan suci Ramadhan tahun 2000. Seluruh mahasiswi, tanpa terkecuali dosen dan pegawai, wajib mengenakan kerudung dalam menjalankan aktivitas kampus. pasca-ramadhan, wajib
kerudung pun berlanjut. Diharuskan tiap hari Senin-Jumat. Sebelum akhirnya, diatur dalam ketentuan rektor itu.
Ketentuan serupa dapat dijumpai di kampus-kampus lain di Jogjakarta. Macam Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
pemberlakuan kewajiban ini di kampus melahirkan fenomena jilbab gaul. Bisa jadi ini adalah salah satu bentuk protes ter–selubung di kalangan muda perempuan penghuni kampus atas kewajiban itu.
”Kalau saya lihat adanya pemakaian jilbab atau kerudung gaul itu, bukan sepenuhnya kesalahan mereka (mahasiswi red), sebab masih banyak dosen ataupun para birokrasi yang tidak memberikan contoh. Bahkan, mereka mengenakan hanya sekadar kewajiban kampus saja. Lebih dari itu, jilbab (dan kerudung-red) lepas dari kepala mereka,” komentar Irfan Suryahardy Awwas, Ketua Lajnah Tan-fidziyah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). IMM merupalan organisasi Islam radikal yang memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia. Dideklarasikan tahun 2000 di Jogjakarta oleh beberapa tokoh Islam ‘garis keras’. Termasuk Abu Bakar
 Kewajiban mengenakan jilbab ataupun kerudung masih jadi perdebatan banyak orang. Kenapa banyak peraturan
Jilbab Gaul. Hasil dari regulasi yang dipaksakan.
Adhitya Awan / HIMMAH
Kewajiban mengenakan jilbab ataupun kerudung masih jadi perdebatan banyak orang. Kenapa banyak peraturan
Jilbab Gaul. Hasil dari regulasi yang dipaksakan.
Adhitya Awan / HIMMAH
33 33HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
AGAMA
Ba’asyir.
Wajib jilbab atau kerudung tak cuma di kampus. Di beberapa kota bahkan sudah mewajibkannya lewat peraturan daerah (perda). Catat saja: kabupaten Cianjur, Banten, dan pamekasan, Madura. Jika dikaji, ini sangat menarik. Terlebih bila dikaitkan dengan maraknya tuntutan pemberlakuan Syariat Islam oleh ‘pengua sa’ di daerah.
Sebenarnya banyak istilah untuk menyebut jilbab. Ada charshaf di Turki, pardeh di India dan p akistan, milayat di Libya dan chador untuk Iran. Di Irak disebut abaya. Dan hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan dan Yaman.
Dalam Al-Qur’an, setidaknya dikenal tiga pandangan tentang jilbab. Pertama, hijab atau kewajiban berjilbab. Ayat yang mengatur hal ini diturunkan kepada istriistri dan keluarga nabi agar mengenakan jilbab. Tapi ayat ini juga berlaku bagi khalayak muslimah lainnya. Alasannya, mengandung perintah dan kemuliaan akhlak.
Kedua, khimar. Yakni anjuran agar
ke–wajiban atau yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam.
Secara umum, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah jilbab merupakan identitas budaya Arab semata? Atau jilbab merupakan bagian dari kewajiban dalam Islam? Apakah benar jilbab telah menjadi identitas kelas sosial tertentu? Menjadi pembeda antara si miskin dan si kaya. Karena masih jadi dilema, bukankah lebih santun jika pemakaian jilbab ini didasarkan
Azra menerangkan bahwa jilbab sekarang sudah cenderung masuk dalam dunia gaya model ataupun fesyen. Ketimbang sub stansi ajaran agama. Hal ini dicontohkan-nya dengan Rukun Islam yang terakhir: naik haji.
”Sekarang, orang menunaikan ibadah haji tidak lagi terkait dengan kewajiban, tetapi sudah berevolusi menjadi gaya yang mengidentikkan bahwa saya adalah orang kaya,” kata prof. Azyumardi Azra yang juga Rektor di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
* * *
D I SEBUAH trotoar kampus UII. Be r -jalan seorang gadis yang seluruh tubuhnya diselimuti jilbab. Selembar kain yang berukuran lumayan besar. Kurang lebih dua kali lipat ukuran tubuhnya. Ditambah dengan kerudung. Nyaris tak tersisa anggota tubuhnya yang terlihat oleh orang lain. Semuanya tertutup kain. Kecuali mata dan telapak kedua tangannya. Alya, begitu gadis itu biasa dipanggil oleh teman-temannya.
menjuntaikan kerudung sampai menutupi dada. pemakaian jilbab pada masa ini ialah merupakan kebiasaan dari kebanyakan orang Arab yang memakai pakaian yang melapisi sekujur badan. Bagi yang men dukung wajib jilbab, ayat ini juga mengan jurkan agar menutupi muka dan telapak tangan.
Terakhir, jalabib. Yang mengindikasi–kan bahwa perempuan diharuskan me–manjangkan pakaian mereka dengan tujuan pembedaan antara perempuan merdeka dengan budak. Untuk bertindak dan berkelakuan sopan. Dan juga merupakan bentuk perlindungan agar tidak diganggu oleh kaum laki-laki.
Sekitar tahun 1991, seorang indone–sianis asal perancis, Andree Feillard, pernah melakukan penelitian tentang persepsi pemakaian jilbab ataupun kerudung ini di Indonesia. Ia adalah penulis buku NU vis a vis Negara yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Jogjakarta.
Hasil penelitian Andree Feilard ternyata cukup mengesankan. Bahwa pemakaian kerudung ataupun jilbab pada zaman dahulu (sebelum tahun 1980), lebih dilihat dari kepantasan terhadap busana yang mereka kenakan. Bukan berasal dari
pada kesadaran perseorangan? Bukan dengan dipaksa?
”Saya setuju ada aturan berpakaian, tapi bukan berjilbab atau tak berjilbab. Umum aja, misalnya berpakaian itu harus rapi dan sopan. Kemudian, sopan dan rapi itu dijelaskan lagi, misalnya tidak ketat dan menantang,” kata Nong Darol Mahmada lewat surat elektronik pada saya. Hal macam ini, menurutnya, memerlukan peraturan yang lebih detail tentang busana muslim, seperti apa yang harus dikenakan.

”Karena kalau formalisasi atau atu–rannya hanya berjilbab, maka banyak sekali orang yang berjilbab tetapi memakai bajunya seksi sekali,” tulisnya.
Nong dikenal sebagai aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), Jakarta, dan juga sebagai editor buku Kritik Atas Jilbab, karangan Muhammad Sa’id Al-Asymawi. Buku tersebut diterbitkan oleh JIL bekerjasama dengan The Asia Foundation.
Memang dalam SK Rektor UII tidak ada kejelasan bahwa mahasiswi harus me–ngenakan jilbab atau tidak, tapi hanya sebatas kerudung. Tapi itu juga tidak tertulis. Yang ada hanya kewajiban me–ngenakan busana muslimah.
Dalam sebuah seminar dengan tema Rethinking Islamic UII, prof. Azyumardi
Ia tidak mengenakan jilbab gaul seperti kebanyakan perempuan sepantarannya. Tapi memilih menggunakan jilbab yang diyakini sesuai dengan Syariat Islam. Jika kesadaran macam ini terus berkembang, maka jilbab tak lagi hanya identik identitas kelas sosial tertentu atau identik dengan perempuan muslimah. Bisa jadi lebih luas. Jadi fenomena perlawanan. Nasaruddin Umar pernah mengutarakan hal ini lewat artikelnya, Fenomenologi Jilbab
”Ketika gerakan para mullah mulai marak di Iran pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya ketika Imam Khomeini berhasil menggusur Reza pahlevi yang dipo–pulerkan sebagai antek Barat di Timur Tengah, maka Khomeini menjadi lambang kemenangan Islam terhadap boneka Barat. Simbol-simbol kekuatan Khomeini, seperti foto Imam Khomeini dan komunitas Black Veil menjadi tren di kalangan generasi muda Islam di seluruh dunia,” tulis Nasaruddin.
”Semenjak itu jilbab mulai menghiasi kampus dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Identitas jilbab seolah sebagai lambang kemenangan,” tambahnya.
Tentu sekarang tinggal bagaimana cara menyadarkan. Bukan berarti lantas me–maksakan lewat segudang aturan.
mereka mengenakan hanya sekadar kewajiban kampus saja. Lebih dari itu, jilbab (dan kerudung-red) lepas dari kepala mereka,” komentar Irfan Suryahardy Awwas.
Pandu L. Patriari / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 AGAMA
Testimoni Seorang Dosen UII
Kepada Yth. Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta
Assalamualaikum wr. wb.
Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Seiring dengan surat ini, kami ingin menyampaikan isi hati yang mendalam tentang perlakuan pihak pimpinan Universitas Islam Indonesia terhadap beberapa dosen, khususnya diri saya secara pribadi. Adapun kasus yang terjadi berdasarkan fakta adalah:
1. Tidak dibayarnya secara penuh gaji yang telah menjadi hak kami sesuai dengan pengajuan pihak jurusan Teknik Industri dan pihak Fakultas Teknologi Industri (FTI), Universitas Islam Indonesia (bukti pembayaran gaji pembayaran sks = 0, pada tanggal 25 maret 2004) seperti terlampir.
2. pemotongan gaji secara tidak sah dengan dalih pembayaran ZIS, tanpa jelas akadnya (lebih cenderung pemaksaan).
Fakta-fakta tersebut di atas tidak dapat diterima akal sehat, yang memahami manajemen dan nilai-nilai islami. Menejemen Islam dalam hal penggajian seorang pekerja haruslah ditunaikan secara tepat waktu bahkan dibayar sebelum keringatnya kering. Fakta pertama di atas semakin menegaskan bahwa pihak universitas tidak memahami ajaran Islam bersama kemulian-Nya. Dalam masalah ini, pimpinan universitas terlihat arogan. Hal ini berdasarkan dialog antara kami dan pimpinan FTI serta penyampaiannya dari salah satu karyawan, bahwa pihak rektorat justru menyalahkan karyawan baik di tingkatan universitas maupun di fakultas. padahal kalau kita paham tentang konsep kepemimpinan Islam, maka seorang pemimpin dalam Islam berarti ia adalah KHADIMATUL UMAH. Yang berarti dia adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya (umatnya). Tapi dengan fakta tersebut di atas, pimpinan universitas justru melepas tanggung jawab dengan dalih perubahan menejemen mutu sesuai dengan sasaran mutunya. Naudzubillahi min dzalik. Seorang pemimpin yang melanggar ajaran Allah dan rasul-Nya masih selalu merasa benar.
Sedangkan fakta yang kedua, menunjukkan korupsi gaya baru dengan dalih kemajuan agama Islam. Hal ini sangat mudah dipahami karena tidak ada satu ajaran Islam yang mengajarkan syariat zakat yang dilakukan tanpa melalui mekanisme akad yang halal antara muzakki dan LAZIS. Seperti kita ketahui bersama, kebijakan pemotongan gaji untuk zakat dilakukan dengan mekanisme himbauan dan seseorang yang tidak mengumpulkan himbauan tersebut dianggap sepakat dengan kebijakan pemotongan gaji untuk ZIS. padahal seharusnya kita tahu bahwa kebijakan yang demikian sama saja dengan cara pemaksaan hanya dibungkus dengan istilah kebijakan dan menafikkan nilai-nilai Islam tentang syuro. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak karyawan yang tidak ridho untuk dipotong karena pada hakikatnya gaji mereka setiap bulannya belum memenuhi nisab untuk dizakati (bahkan sebenarnya mungkin mereka justru layak menerima zakat).
Dari fakta dan uraian di atas maka kami mengambil sikap:
1. Kami tidak akan pernah mentolerir segala bentuk kejahatan dan kezaliman pemimpin di Universitas Islam Indonesia dengan mengambil langkah tidak akan memberikan ujian dan melanjutkan mengajar empat mata kuliah yang telah diminta oleh jurusan TI dan FTI UII. Adapun tuntutan kami tersebut adalah:
a
. Menuntut pimpinan UII melalui pimpinan FTI, yang telah menugaskan kami mengajar, untuk menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada kami secara terbuka dan dengan surat resmi.
b
. Menuntut pimpinan UII untuk membayar pinalti menejemen karena kelalaiannya dengan membayar tiga kali total gaji yang seharusnya diterima pada tanggal 25 maret 2004.
c. Meminta maaf secara terbuka dan dengan surat resmi kepada para dosen yang sampai saat ini juga telah dizalimi karena tidak dibayar gajinya.
2. Kami menghimbau kepada bapak dekan, para dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan UII untuk tidak mempercayai dan mendukung kepemimpinan pimpinan UII beserta kebijakan-kebijakannya.
3. Kami mengajak kepada dekan, para dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkunan UII untuk menjaga lembaga milik umat Islam ini dari kezaliman yang senantiasa ingin menggerogoti ajaran Islam. Karena salah satu jihad yang paling besar adalah mengucapkan hal yang benar meskipun di hadapan penguasa yang zalim.
Demikian surat ini kami buat untuk mengingatkan kita dari orang-orang yang zalim, serta didasari oleh rasa memiliki kepada UII ini.
Wassalamualaikum wr. wb.
Tembusan:
1. Ketua Badan Wakaf UII
2. pimpinan UII
3. pimpinan fakultas di lingkungan UII
4.Dosen, karyawan dan mahasiswa UII
 Ir. R. Chairul Saleh, M.Sc, ph.D
Pandu L. Patriari / HIMMAH
Ir. R. Chairul Saleh, M.Sc, ph.D
Pandu L. Patriari / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
KOMENTAR
Nyanyian Sunyi yang Terpinggirkan
Oleh INDIAH WAHYU ANDARI dan WEKA SWASTI WARDHANI
JALAN itu dulunya sepi. Kebanyakan
hanya pemandangan sawah dan p epo-ho n an terbentang di kanan-kirinya. Ada juga beberapa rumah penduduk, bangunan-bangunan sederhana khas suasana per-desaan. Kehidupan bercocok tanam pun sangat dekat dalam keseharian pen-duduknya.

Lambat laun jalan yang men g h u bungkan kota Jogja dengan kaw a san wisata Kaliurang itu semakin ramai. Bagai mana tidak? Letaknya strategis untuk pengembangan bisnis.
Di salah satu penggalan jalan yang terbentang sejauh kurang lebih 23 kilometer itu dibangun pusat-pusat pendidikan seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Sentra pendidikan Bank Rakyat Indonesia (Sendik
BRI), serta Akademi Keperawatan (Akper) ‘panti Rapih’, yang mengundang banyak orang dari seluruh penjuru tanah air untuk datang dan tinggal di sana. Semuanya berada di kawasan kilometer 14, desa Bojotan, kelurahan Umbulmartani, kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
Koentjoro, dosen Fakultas psikologi Universitas Gadjah Mada, menerangkan bahwa pembangunan UII di jalan Kaliurang berfungsi sebagai urban generator, yaitu penggerak adanya masyarakat urban semisal mahasiswa dan pengusaha, serta berfungsi social generator atau penggerak sosial, seperti adanya perubahan budaya dan gaya hidup.
Hal itu secara langsung maupun tidak
mempengaruhi sistim mata pencaharian, dari sistim agraris bergeser ke sistem industri. Namun, pergeseran itu kadang tak diiringi dengan pola pikir masyarakatnya. Pendeknya, perubahan fisik yang sangat cepat itu belum tentu dapat ditanggapi secara cepat pula oleh masyarakat.
p onijo (41), Kepala Dusun Lodadi, di mana wilayahnya menjadi daerah yang terkena pembangunan kampus UII, merasa bahwa memang perkembangan wilayah ini cepat sekali. Dia mengaku terus terang bahwa masyarakat sekitar pada umumnya merasa diuntungkan dengan berdirinya kampus tersebut, khususnya secara ekonomi.
”Sekarang hampir semuanya memiliki
Tumbuhnya pelbagai gedung megah di sebuah kawasan kerap kali meminggirkan warga setempat. Wilayah Kaliurang kilometer 14 salah satunya.
Pembangunan Rumah. Di Jogjakarta, banyak yang melakukannya dengan cara mengubah fungsi lahan persawahan milik warga sekitar.
Indra Yudhitya
HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 PSIKOLOGI
/
kost-kost-an,” ujarnya. Akan tetapi m e mang banyak juga pemiliknya adalah kalangan pendatang. Umumnya mereka membawa orang lain untuk menjaga kostannya. ”Secara umum,” tambahnya, ”hubu ngan dengan masyarakat sekitar tidak ada masalah.”
Di sisi lain ponijo mengakui bahwa peningkatan penghasilan itu kurang diser tai kemampuan untuk mengelola uang. ”Ya..kami ini seperti orang kaya baru. Begitu dapat uang banyak langsung pengen beli ini-itu. p adahal kan belum tentu perlu.”
Walaupun demikian, p onijo masih mempertanyakan satu hal dari pendiri kampus UII dulu tentang janji mereka mempekerjakan penduduk sekitar. ”Sampai sekarang mana? Cuma dua orang yang sekarang jadi satpam itu,” keluhnya.
Tidak semua penduduk Lodadi memiliki bangunan kost-kost-an. ”Di antara mereka kebanyakan menjadi buruh bangunan,” ponijo melanjutkan.
Di atas tanah kas desa itu kini telah berdiri bangunan-bangunan megah pusat pendidikan. Bangunan yang konon dihara p kan melahirkan manusia-manusia pe m baharu negeri ini. Bangunan yang ternyata mengundang bangunan-bangu-nan lain untuk berdiri.
Tentu saja gedung-gedung itu berdiri bukan tanpa sebab. Mereka yang mampu melihat peluang bisnis beramai-ramai membangun usaha di sana. Sayangnya, pola pikir itu belum tertanam di benak masyarakat setempat. Masyarakat agraris itu kini harus berhadapan dengan pesatnya pembangunan yang memasuki kawasan mereka dan menuntut pola hidup serta pola pikir baru.
Kami mencoba mengunjungi beberapa petani yang menjual sawahnya dengan pola berbeda. Mereka adalah pemilik tanah di kawasan pinggir Jalan Kaliurang kilo-meter 11.
Salah satunya adalah pak Dal, begitulah orang-orang sering memanggilnya. Siang itu pak Dal sedang melihat-lihat kolam ikan yang tidak begitu luas. ”Ini milik saya, modalnya dari penjualan tanah di depan itu,” terangnya.
Suara gergaji mesin memecah terik matahari siang itu. Kayu yang dipesan untuk pembangunan mushola. ”Orang hidup kan harus imbang. Di samping berbuat jelek juga ada perbuatan baiknya,”
p ak Dal mengajak duduk di bawah rimbun pepohonan.
Dia mulai bercerita tentang penjualan tanahnya. ”Itu kan untuk memudahkan pewarisan, wong kami juga enggak bisa
nggarap tanahnya. Kalau berbentuk duit kan terserah kita nanti mau diapain,” jelasnya.
Lain lagi dengan cerita pak Sagiman (60), malam itu bersama anak, istri, dan dua orang cucunya dia bercerita tentang penjualan tanah yang berbuntut panjang.
Berawal dari penjualan tanah di bawah tangan tahun 1995 yang diperantarai oleh seorang Kepala Dusun (kadus) setempat. ”Karena waktu itu dia yang menjadi ujung tombak masyarakat daerah ini kalau ada apa-apa,” dia memulai cerita. Waktu itu p ak Sagiman yang purnawirawan angkatan bersenjata, masih bertugas di Ujung pandang. ”Kataya sih laku 90 juta, Tapi sampai detik ini kami tidak pernah menerima uang dan bahkan tidak tahu siapa yang membeli tanah itu,” tuturnya.
Kemudian dia kembali ke Jogja dengan maksud untuk menyelesaikan duduk permasalahan. Akan tetapi mereka yang terlibat dalam kasus ini selalu berkelit jika dimintai pertanggungjawaban. Karena geram, pak Sagiman membuat surat ser tifikat atas tanah yang dimilikinya itu.
Selanjutnya atas usahanya sendiri, tanah tersebut dijual secara resmi. Ternyata, pembeli pertama yang merasa telah menge luarkan uang untuk tanah itu tidak terima dan menuntut ke pengadilan.
pak Sagiman mengaku tenang menang gapi tuntutan itu karena dia merasa tidak bersalah. Bahkan, pembeli kedua yang telah membeli secara sah menyatakan siap maju ke pengadilan setelah mendengar penuturannya.
Di ruangan yang amat sangat sederhana itu, putrinya menceritakan betapa emosinya mereka menghadapi Kadus setempat yang telah dianggap memakan uang mereka dan sempat memaki-maki bapaknya.
Sempat suatu siang mereka ribut-ribut. ”Dia bilang, kalau macam-macam tak bunuh kamu! Enak saja. Sudah makan uang saya, masih mau membunuh pula. Daripada begitu mending saya yang membunuh sekalian,” tutur pak Sagiman sedikit emosi.
Keributan itu memang sempat mengun dang polisi. Akan tetapi kasusnya tak terdengar lagi sampai sekarang.
”Waktu itu saya ke kantor polisi ditanyatanyai, sambil dia mainin mesin ketiknya. Ya udah cuma itu saja,” jelas putrinya.
Kini p ak Sagiman dan keluarganya tinggal menungu panggilan dari pengadilan berkait kasus penjualan tanahnya.”Yang penting ini cepat selesai,” harapnya.
putrinya kini memiliki sebidang tanah berikut rumah di Ujung p andang dan tinggal di sana bersama suami. Sementara
pak Sagiman ingin tetap tinggal di Jogja karena merasa dekat dengan keluarga.
Di sisi lain ada juga petani yang memiliki pandangan berbeda berkait dengan kep e -milikan tanah di daerah tersebut.
parwoto, seorang petani dari daerah Gentan yang juga Ketua Setam (Serikat Tani Merdeka), sebuah lembaga swadaya masyarakat pertanian, adalah salah satu contoh petani yang tetap mempertahankan tanahnya dari para calo tanah.
”Wah, sudah berapa kali kita dikejar untuk menjual tanah itu,” katanya. Mulai dari didatangi ke rumah, hingga tanahnya dijadikan tempat pembuangan sampah.
Usahanya kemudian adalah mendirikan bangunan ruko di sana dan meny e w a kannya. Ruko itu tidak terlalu besar. Hanya terdiri dari dua buah bangunan.
”Tapi ini usaha keluarga. Tanah itu nantinya akan diwariskan orang tua kepada kami, tiga bersaudara. Nah, saya sekarang kebagian yang mengelolanya,” katanya. Dengan cara demikian, dia berharap tanah ini dapat diwariskan dalam bentuk yang lebih produktif.
Mustaqfirin, dosen Fakultas Psikologi UGM, dalam soal ini memandang fenomena ini adalah sebagai hasil dari pilihan masyarakat itu sendiri. ”Sebenarnya orang mau jadi pegawai, pengusaha, atau pengangguran itu ya hasil dari pilihannya,” jelasnya.
p ermasalahannya, bagaimana orang memilih tentu terkait dengan tingkat pendidikannya, latar belakang kehidupan nya, lingkungan sosialnya dan banyak faktor lain. Untuk menghadapi keadaan seperti itu, solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah memberikan pendam pingan bagi warga. Namun, adakah yang mau bertanggung jawab?
perubahan gaya hidup, taraf ekonomi, pola pikir, dan pelbagai kesenjangan serta kecemburuan sosial bukanlah perihal baru lagi. Bermacam bangunan telah berdiri dan membuka pelbagai gejala perubahan. Aneka jasa konsumsi, pendidikan, atau pelayanan tempat tinggal, telah me n stimulus geliat tabiat masyarakat setempat yang sangat berbeda jauh sebelum keha diran mereka.
Kini, lalu-lalang kendaraan serta ber bagai aktivitas manusia telah menutupi kesunyian dan kedamaian yang dulu pernah hadir menghiasi Jalan Kaliurang kilometer
33� �HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 PSIKOLOGI
14.
Sinden, Tak Lekang oleh Waktu
”Duk samana kang dadya tumbaling Nagri

Gugur lir kusuma Ngrungkepi Ibu Pertiwi Prang lumawang gur kha nika.”
SUARA tembang ‘Megatruh’ dari mulut jalan desa itu terdengar begitu lirih. Bau khas tanah selepas diguyur hujan lekat tercium ketika saya mulai melangkahkan kaki menyusuri lintasan desa tersebut. Desa yang menyimpan banyak potensi seni ini termasuk wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Tiap pagi dan sore, kerap terdengar suara gamelan Jawa.
Mayoritas penduduk laki-laki di daerah ini adalah petani dan pedagang. Tidak sedikit pula diantara mereka yang terjun jadi pebisnis hiburan: menawarkan jasa sewa alat hiburan maupun sound system. Sedang kan yang perempuan, kebanyakan memiliki profesi sebagai penyanyi atau sinden. Ada pula yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan suami.
Daerah ini merupakan ‘markas besar’ para sinden. Sinden papan atas, macam Anik Sunyahni hingga Waljinah lahir dari daerah ini. Anik Sunyahni, seorang sinden yang tenar lewat tembang ‘Urip Mung Mampir Ngombe’. Seniwati yang sekolah dasar (SD) saja tidak rampung. Konon sekarang, bayarannya untuk sekali pentas sampai belasan juta rupiah. Sedang, Waljinah, sinden yang lebih senior k e timbang Anik Sunyahni. Ia melejit lewat tembang ‘Walang Kekek’.
Seorang sesepuh desa setempat me–ngatakan, ”Dulu di sini banyak sinden tayub. Sekarang, sinden tayub tinggal sedikit. Yang masih banyak itu sinden karawitan atau campursari.”
Sinden tayub merupakan sinden yang di samping nembang, terkadang juga terlibat joged bareng dengan tamu. Me–ngenakan kain panjang yang dilingkarkan badan keduanya: sinden dan tamu. Sang tamu kebanyakan kaum lelaki.
Sinden sendiri adalah pekerjaan seni, pelestari tradisi budaya murni. Dari mulut
Oleh ASRIANI PRAVITA INDRASWURI
Usia boleh saja bergulir menurut kehendak Jangka Semar. Tapi, titah seni tidak akan lepas dari aliran darah seorang Sinden.
Sinden Menembang. Selalu berada di tengah laki-laki demi tujuan mulia.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
INSANIA
sinden, terlantun tembang Jawa. Mengalun indah. Diiringi suara tabuhan gamelan. Komposisi yang lembut dan fantastik ini memang tidak akan meningkatkan kadar andrenalin. Namun sebaliknya: bakal bikin hati tenang para pendengar. Ini dikarenakan beat-beat yang tercipta lewat rangkaian gamelan terpadu dengan lantunan sinden yang mengiringinya.
Sinden mirip seorang aktris layar lebar. Dalam banyak hal, ia dituntut mampu membuktikan kemampuannya di papan pementasan: pertunjukan wayang, tayub maupun karawitan. Secara kontinyu.
Menjadi sinden memang tidak mudah. Niat dan bakat saja tidaklah cukup. Harus senantiasa berlatih, punya modal tampang dan berpenampilan menarik. Syarat tam–bahan lainnya: tahan godaan. Terlebih bagi pesinden tayub. Maklum, ia harus seorang perempuan yang rentan terhadap godaan laki-laki iseng. Besar pengaruhnya, lan–taran budaya Jawa yang patriarkis: merunut laki-laki yang cenderung dominan dan berkuasa, sedang perempuan sebagai kaum minor dan tertindas.
Mungkin ini telah terjadi sejak masa lampau. Zaman di mana Jawa diperintah model kerajaan. Monarki absolut.
pada mulanya adalah seni karawitan murni yang tergolong eksklusif. Kesenian ini hanya ditampilkan dalam acara resmi kerajaan. Tujuannya menghibur penghuni keraton. Karawitan juga menjadi iringan khas bagi aneka macam tarian Jawa. Sehingga tidak mengherankan bila pada zaman itu, sinden menjadi sosok istimewa dalam kehidupan warga keraton. punya posisi kunci di setiap pertunjukan kara–witan.
Saat memasuki lingkungan keraton ini, maka sinden mengabdikan diri untuk darah seni. Sebagai wujud rasa hormat bagi junjungan mereka: keluarga kerajaan. Ritual kejawen kerap dilakukan sebelum me–lakukan pagelaran. p enampilannya pun dipoles khusus. Menarik. Tak jauh beda dengan sinden yang pentas di tengah masyarakat umum atau di luar keraton.
Seorang sinden, di luar maupun di dalam lingkungan keraton, sama-sama harus punya kemampuan plus dalam menembang maupun menari. Yang bikin beda adalah tingkat kehalusan dan kelengkapan alat pengiringnya. Di masyarakat umum tidak semewah dalam lingkungan keraton.
Selain itu, di luar keraton, seni yang berkembang pesat saat itu di samping karawitan murni, ada seni cokek atau lazim disebut tayub. Ini cikal bakal lahirnya sinden tayub, yang biasanya ditampilkan saat pesta perayaan untuk bersenangsenang. Identik dengan umbar birahi dan mabuk-mabukan. Untuk jenis sinden yang satu ini, citranya terkesan kasar bila dibandingkan dengan sinden yang tampil untuk lingkungan keraton.
Berbeda ketika penjajah mulai ‘men–cekik’ negeri ini. Bagai wujud air yang tergantung bentuk wadah penampungnya. p ara penjajah tidak hanya mengobrakabrik sistim pemerintahan, namun seni dan budaya asli juga dicabik-cabik. Kesenian jadi carut-marut dan makin bernilai rendah. Tergantung penjajah memandangnya. Dan, budaya lokal pun otomatis tercemari.
Tak terkecuali dunia sinden.
Seperti yang dituturkan Mbah Joyo, sosok pesinden berusia senja asal Gon–dang, Sragen, Jawa Tengah. Tampaknya, ia masih ingat kejadian masa lalu. Kala sinden hidup di bawah pemerintahan kolonial.
”Rumiyen, pas zaman penjajahan, sak bare mentas ting gene ki demang napa pak lurah sing enten londone, yen mang–keh kepilih, mesti ken nglayani ten kamar. Londo niku gegirisi, sadis. (Dulu, waktu zaman penjajahan, kalau sesudah pentas di tempat pak demang atau pak lurah yang di situ ada tamu belanda, kalau (sinden) terpilih, pasti disuruh melayani di kamar. Belanda itu kejam,” ungkap Mbah Joyo sambil matanya menerawang jauh.

p adahal, menurutnya, sinden m e rupakan salah satu ritual Jawa sebagai media perwujudan doa kepada Tuhan. Makanya, sebelum pentas, sinden di–harapkan berdoa. ”Supados pementasane lancar. (Supaya pementasannya berjalan lancar),” tambahnya.
Saya tidak bisa mengorek keterangan lebih lanjut, karena nenek yang satu ini lebih banyak menggunakan aksi diam.
Menjadi sinden laksana menjadi se–orang selebritis. Sebab dalam perjalanan kehidupannya di masyarakat mirip taya–ngan infotainment di tivi. Senantiasa jadi sorotan, santapan pembicaraan yang empuk, bahan cibiran warga saat belanja, atau saat petan (mencari kutu) —galibnya kebiasaan sebagian perempuan desa. Gosip miring seputar gaya hidup sinden, tentang cara hidupnya, sampai hubungan personal kehidupan pribadinya dikorek habis. Ruang privasinya berubah jadi ruang publik seolah-olah ia tak punya kehidupan lain, selain menyinden. padahal tiap orang punya dua dimensi: kehidupan privat dan publik.
”Jadi sinden itu susah, kalau tidak bisa membawa diri, bisa-bisa kena booking,” tutur Ani, perempuan yang terbilang anyar dalam dunia persindenan di Gondang. Dia mengaku baru dua tahun terjun jadi sinden.
Booking merupakan istilah bagi lelaki untuk minta ‘pelayanan tambahan’. Entah berupa ajakan makan, teman mengobrol hingga ajakan berhubungan badan.
Ani bukanlah seorang sinden tulen. Dia sebenarnya seorang kasir sebuah toko bangunan. Dia sudah punya tiga anak. Bekerja pagi: mulai jam 09.00 hingga empat sore.
”Kalau malam saya nyinden ,” katanya.
Itu terpaksa dilakukan Ani lantaran keinginannya mendapat tambahan peng–hasilan. Soal profesionalitas sebagai sinden, tak perlu diragukan. Dirinya tidak cuma
33� �HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 INSANIA
Indra Yudhitya HIMMAH
bisa menembang, bila disuruh me–nyanyi campursari pun ia mampu. Ter–gantung kerja yang diberikan.
”Tapi, bukan berarti kalau nyinden, saya asal-asalan loh. Bisa nggak laku, ntar ,” katanya sambil tertawa.
Dunia persindenan tergolong dinamis. Menuntut para sinden untuk serba bisa. Termasuk menolak ajakan booking
”Saya pernah mengalaminya,” kata Ani.
pada waktu itu, sehabis pertunjukan, ada seorang tamu yang menghampiri dan mengajaknya berkencan. Terang saja, ia tolak mentah-mentah. Bahkan, dia me ngaku, pernah ada tamu yang sampai datang ke toko tempatnya bekerja. Tamu itu tentu saja laki-laki.
”Saya kan jadi ngeri,” katanya. ”Tapi, saya nggak kapok jadi sinden. Sebab jadi Sinden itu mulia.”
Menjadi sinden adalah pilihan dalam hidup. perlu pengakuan dan pengukuhan oleh masyarakat maupun pemerintah lewat lembaga pendidikan macam STSI, Surakarta. STSI kependekkan dari sekolah seni tari Indonesia. Sekolah tinggi ini mengajarkan seni karawitan. Secara tidak langsung juga mengajarkan tentang sinden karawitan atau sinden secara umum. Di kabupaten Ngan–juk, Jawa Timur, ada semacam lembaga kursus (sekolah) persindenan, yang bila lulus, mereka kelak dikukuhkan dalam upacara khusus. Bila belum dikukuhkan, mereka belum boleh menerima pekerjaan.
Kini, kondisi telah berubah. Jaman juga telah berganti. Tidak hanya ada sinden karawitan atau tayub, tapi juga ada sinden campursari. Jenis sinden baru ini seperti sinden karawitan. Namun musik pe–ngiringnya berupa perpaduan gamelan dengan alat musik yang relatif modern. Macam gitar, drum maupun keyboard . Bisa jadi ini merupakan bentuk penerimaan perkembangan jaman.
Sinden campursari tentu tidak bisa dipisahkan dengan aliran musik campursari. Jenis musik yang mulai muncul awal dekade 1990-an. Salah seorang pen–cetusnya adalah Manthous, seniman kondang asal Wonosari, Yogyakarta.
* * *
DI DAERAH Gondang, Sragen, tidak sedikit sinden yang mampu hidup layak hanya dari hasil menyinden, yang bisa jadi merupakan warisan turun-temurun. Ke–giatan belajar menyinden pun tampaknya telah menjadi kebiasaan.
Menurut Ati—begitu biasa dia di–panggil—menyinden merupakan pilihan
untuk menyambung hidup. Jadi sinden, baginya, merupakan pekerjaan tetap yang harus dijalani dengan serius. Cita-citanya ingin jadi sinden besar kayak Anik Su–nyahni atau Waljinah, yang karena lewat nembang, bisa bikin album dan dinikmati orang banyak.
” Nembang itu hebat, enggak kalah dengan dangdut atau musik lain. Bahkan, suara sinden yang lagi nembang diiringi alunan gamelan bisa jadi terapi dan men–jadikan orang lebih relaks loh,” katanya.
”Apalagi kalau yang nembang saya. Coba saja kalo nggak percaya,” kata Ani pada saya. Kali ini dia setengah promosi.
Banyak jalan menuju ketenaran. Ingin jadi sinden tenar perlu senantiasa berlatih untuk mengasah kemampuan vokalnya. Bukan hanya seperti calon penyanyi pop saja yang dikarantina dan digembleng sebelum jadi penyanyi pujaan, tapi menjadi sinden pun demikian. Butuh gemblengan dan asahan tiap hari supaya suaranya makin ‘berkilau’.
Tiap sinden punya kiat masing-masing untuk ke sana. Tak ada jalan baku. Ter–masuk dengan cara memberi pelayanan lebih bagi tamu. Ini yang ditempuh seorang sinden, sebut saja namanya Susi. ”Sekali berlayar, dua, tiga pulau terlampaui. Itu pedoman saya,” katanya ketika bertemu dalam sebuah pertunjukkan.
Dirinya menjadi sinden karena ada yang merekomendasikan. Susi memang seorang sinden panggilan. Jika ada orang yang menawarinya, maka ia akan menyinden. Jika tidak ada, ia tak menyinden. Tak sungkan-sungkan, Susi suka memberi layanan tambahan bagi tamu yang hadir. Atau siapa pun yang menginginkan.
”Saya nggak peduli dicap buruk. Wong saya butuh uang untuk hidup. Saya siap menanggung risikonya,” kata Susi enteng seperti tanpa beban. ”Biasanya, job tam–bahan saya terima setelah mentas.”
Bagi Susi, pekerjaan menyinden itu pekerjaan mulia. Tentang pelayanan tam–bahan itu perkara lain. ”Kalau ada yang mau dengan saya untuk sesuatu yang lebih, asal sama-sama cocok, ya nggak apa-apa, kan? Toh saya nggak melakukan tindakan kriminal,” katanya genit.
”Wong, sama-sama sadar dan suka.”
Itu merupakan sisi lain kehidupan Susi di samping menyinden. Tak bisa disalahkan. ”Janganlah meributkan urusan orang. Uruslah urusan masing-masing,” dia berpesan.
”Udah dulu ya, saya harus pergi. Sudah dijemput,” katanya tersenyum genit sambil berlalu. Ia bergelayut mesra pada tangan seorang laki-laki yang menghampirinya.
”Tau, kan?”

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 INSANIA Iklan
Menanti Generasi dari Kampung Jalanan
Oleh ATFAS FERRY
SUASANA
damai malam itu menambah
getarnya gerak langkah kami untuk memasuki kawasan dan kehidupan yang terpinggirkan itu. Terlihat semangat lang-kah seorang pemuda yang mengabdikan diri dan menghabiskan waktunya untuk sebuah kampung atau desa tertinggal yang sangat membutuhkan binaan pendidikan ini. Raut wajahnya berkerut menunjukkan keletihan yang tak terbendung. Demi meneruskan semangat juang anak-anak jalanan.
Tak terasa suasana desa yang damai tapi butuh perhatian pemerintah ini, ternyata di atasnya terdapat sebuah kampus universitas yang megah. Dihiasi lampu-lampu kota yang memberikan kesan kemewahan dan keagungan. Sementara di bawah perbukitan kota itu terlihat ke-sibukan-kesibukan para anak didik yang selama ini tak mampu memenuhi haknya sebagai seorang siswa di sekolah-sekolah sebagaimana biasanya.
Rumah-rumah yang dibangun dengan kerajinan tangan, kursi-kursi yang tidak cukup memadai, tenaga pengajar yang kurang, dan suasana malam yang hening di kala itu, tak menyurutkan semangat para anak didik dan para pengabdi ini untuk melanjutkan estafet perjuangan yang juga memiliki hak dan kewajiban sebagai anak bangsa di masa depan. Selain mereka dituntut untuk melanjutkan estafet sebagai anak bangsa, mereka juga dituntut untuk men g hidupi keluarga dan diri mereka sendiri. Mereka adalah sekelompok anak jalanan yang hidup di sebuah pe r ka m pungan di jalan Tentara Rakyat Mataram, kampung pingit, Yogyakarta, yang sangat membutuhkan perhatian pendidikan oleh segolongan pihak, utamanya pemerintah.
”Sebenarnya perkampungan yang telah dijadikan tempat perkumpulan anak jalanan dan pendidikan informal seperti ini sudah sejak tahun 1960-an. padahal dahulu akan dibelikan tanah untuk panti sosial, namun ada seorang Bapak yang menginginkan tanahnya diwakafkan, maka inilah tanah yang dijadikan tempat orang-orang jalanan untuk proses belajar mengajar,” kata Fajar, salah seorang pengajar anak-anak dan pengajar orang tua jalanan di kampung itu.
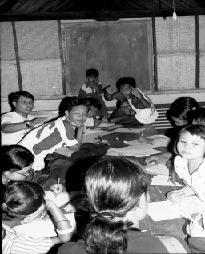
pendidikan informal ini mempunyai misi untuk membuka ruang ekspresi bagi anak-anak yang terancam putus sekolah agar beberapa keterampilan dapat mereka kuasai, salah satu keterampilan mereka
dengan membuat layangan, topeng dan seni tari. Sementara dari pihak orang tua, mereka dipaksa untuk menabung selama dua tahun demi untuk masa depan anak dan keluarga mereka sendiri.
”Karena target kami secara psikologis, mereka harus kuat secara mental dengan uang mereka untuk mencari jalan hidup sendiri tanpa harus mengamen dan mintaminta lagi,” tambahnya.
Perhatian terhadap pendidikan informal di Indonesia masih tergolong rendah, sementara konsep pendidikannya
Indra Yudhitya
HIMMAH
Proses Belajar. Dalam kesederhanaan dan minimnya fasilitas pun mereka lakukan.
41 41HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 PENDIDIKAN
/
Sekolah yang diikuti oleh orang kam pung dan anak jalanan ini memiliki enam kelas untuk tingkat SD dan tiga kelas untuk tingkat SMp.
”Namun, yang paling menguji dan menantang kami sebenarnya adalah faktor kesabaran dalam mengajar mereka, karena jiwa-jiwa mereka sudah terbiasa keras,” ucap Gembong, salah seorang pendidik yang baru mengabdi selama lima bulan terakhir.
Sementara itu Saryono, 13 tahun, salah seorang anak jalanan yang menetap sejak tahun 1991, yang tinggal di kampung ini memiliki pengalaman pahit yang sampai saat ini harus diterimanya hingga masa tua. Kisah sedih dan mengharukan terpancar dari raut wajahnya yang sudah terbiasa menerima kehidupan keras tersebut. Anak yang bercita-cita akan menjadi polisi ini terpaksa harus memutuskan sekolahnya sejak kelas 4 SD dan mengabdikan diri di jalanan untuk mengamen demi menyam bung hidupnya.
Namun pendidikan informal yang diajarkan oleh para pengabdi masyarakat ini masih terus berlanjut demi menyambung cita-cita anak jalanan yang lain, sekalipun tanpa ijazah.
”Saya pernah sekolah Mas, tapi hanya sampai kelas empat. Setelah putus sekolah saya kembali ke jalanan untuk mengamen sampai saat ini. Karena di sekolah, saya dianggap keras dan sering tawuran. pasalnya saya selalu dilecehkan oleh teman-teman. padahal saya masih kepingin melanjutin sekolah saya. Tapi saya masih melanjutkan belajar saya di kampung ini,” katanya kepada saya dengan nada sen-dunya.
Lain halnya dengan ungkapan yang diutarakan oleh Trismina, seorang ibu warga kampung pingit yang sudah menetap selama satu setengah tahun dan sudah memiliki tiga orang anak ini.
”Masalah pendidikan di kampung ini tergolong masih kurang, terutama dari segi tenaga pengajarnya, kurang person. p erhatian kepada anak-anak juga tidak menyeluruh, serta kurangnya pengajaran keterampilan. Namun perhatian yang lebih besar diberikan oleh para pengajar tersebut terpusat kepada anak-anak yang sudah putus sekolah.”
”Sedangkan menetap di kampung ini kami diwajibkan untuk membayar Rp. 1.000 per hari selama dua tahun. Agar kami siap untuk pergi dan menggunakan uang kami yang telah ditabung per hari tersebut selama dua tahun kepada Yayasan Sugiopranoto. Kami hanya diberikan kontrak selama dua tahun, dan kami akan digantikan kembali oleh pendatang baru.
Tapi kami berterima kasih telah diberikan rumah gratis di sini,” ujarnya.
Dinamika kehidupan yang terus ber ke m bang membawa konsekuensi ko n sekuensi tertentu terhadap kehidupan keluarga. Banyaknya tuntutan kehidupan yang menerpa keluarga beserta dampak krisis yang ditandai dengan bergesernya nilai-nilai dan pandangan tentang fungsi dan peran keluarga menyebabkan te r jadinya berbagai perubahan mendasar tentang kehidupan keluarga. Struktur, pola hubungan, dan gaya hidup keluarga banyak mengalami perubahan.
Kalau dulu biasanya ayah berperan sebagai pencari nafkah tunggal dan ibu sebagai pengelola utama kehidupan di rumah, maka sekarang banyak di antara keluarga (khususnya kampung jalanan) yang harus melibatkan anak untuk meng hidupkan keluarga, sekalipun anak tersebut belum cukup umur untuk mencari nafkah.
”Undang-undang untuk melindungi anak itu memang harus ada karena riset saya di Jakarta menunjukan bahwa anakanak jalanan itu dimanfaatkan oleh orang tua mereka. Tapi persoalannya Undangundang untuk itu setelah disahkan sulit untuk ditegakkan,” komentar prof. Suyanto, p h.D, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta kepada saya.
* * *
M ASALAH konsep pendidikan i n formal, juga seharusnya diperhitungkan untuk masa depan anak yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Masa depan anak bangsa ini juga bergantung pada konsep pendidikan yang benar-benar memiliki persaingan dengan sekolah formal.
Menurut Ki Hajar Dewantara, salah seorang guru yang bijak dan tauladan pada masa kemerdekaan, pendidikan bagi bangsa Indonesia harus dilakukan melalui tiga lingkungan yaitu keluarga, sekolah dan organisasi informal. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai sekarang, keluarga be r pengaruh besar terhadap perkembangan anak manusia
Tapi, semangat juang perkampungan ini masih terus dilanjutkan oleh Sumini, salah seorang ibu yang sudah sepuluh tahun mengabdikan diri dan bekerja di Yayasan Sugiopranoto atau Realino, sekaligus menjadi pengawas perkampungan ini. Selain beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu tersebut diberikan dari Yayasan Sugiopranoto, ia juga memberikan perpanjangan kontrak tempat tinggal bagi para keluarga kurang mampu tersebut.
Dengan mengatasnamakan Yayasan Su giopranoto yang saat ini sudah menyatu dengan Yayasan Realino. Keduanya berkantor di Jalan Mataram Yogyakarta.
Masalah konsep pendidikan yang selama ini diterapkan di daerah per-kampungan jalanan ini adalah lebih fokus pada keluarganya, karena hal yang paling diutamakan adalah keluarga dahulu. Sementara anak hanyalah berupa k e butuhan saja.
”pendidikan bagi anak-anak yang tidak sekolah itu selalu diberikan keterampilan berupa sulak, seni musik agar membantu mereka mengamen, membuat figura, dan ada juga yang memberikan banyak cerita bagi anak-anak. Sehingga selama itu menghasilkan buat mereka, maka tetap akan kami bimbing,” ujar Stefanus Winarto.
Dia adalah father dari perpustakaan Ignatius yang juga terlibat mengawasi perkam-pungan ini.
”Sementara misi sebenarnya yang diberikan oleh Yayasan ini adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka saja, agar mereka tidak lagi hidup di jalanan setelah menetap dua tahun di kampung pingit tersebut.”
Di pihak lain, p rof. Suyanto, p h.D, menjelaskan bahwa, ”mengenai konsep pendidikan informal itu yang penting adalah bagaimana agar langkah awal anak-anak didik tersebut mampu baca tulis, diiringi dengan proses pemberdayaan mental diperkuat, sehingga bila dites sudah cukup memenuhi standar nasional.”
”Selain itu dari pihak pemerintah juga harus peduli dengan keadaan seperti itu. Tapi pemerintah saat ini masih dalam keadaan miskin, makanya masalah pen didikan informal ini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan masyarakat. Akan tetapi salah satu kepedulian p e merintah yang harus dicurahkan adalah tanpa mengenakan pajak kepada keluargakeluarga tersebut,” demikian tuturnya.
”Akan tetapi bila berbicara mengenai program akademisi, maka universitas menyediakan tiga program yang sampai saat ini masih berjalan. Yaitu program penelitian lapangan, pengajaran dan pengabdian masyarakat,” tambahnya.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 PENDIDIKAN
DUSUN Selorejo di kaki pegunungan Menoreh, Magelang, Jawa Tengah, seketika bergejolak. Wilayah yang banyak dikelilingi bukit-bukit berbatu marmer itu kini terancam rusak. Aktivitas penambangan sejak tahun 2000 oleh pT Margola adalah biang musababnya. Akar kejadiannya sebetulnya telah berlangsung lewat dua dekade silam. Ini diselingi proses pindah tangan yang berlarut-larut. Sebelum kehadiran Margola, lahan seluas 18 hektar yang dibeli dari warga setempat dan kini jadi lokasi beroperasinya penambangan masih teronggok tak terpakai.
Sekarang situasinya sungguh berkebalikan.
Warga Selorejo mulai mempersengketakan lagi tanahnya yang dijual tahun 1982 itu. pasalnya, sewaktu proses jual-belinya di bawah tekanan, janji tanpa terpenuhi, dan harga yang tak sepadan. Kini, sebagian warga yang dulunya berdiam di area penambangan bertahan hidup di lereng bukit yang laten longsor. Semuanya berujung simpul bahwa aktivitas penambangan mesti segera ditutup. Sayangnya, Margola tak hirau. penambangan terus berjalan meski telah menggerus satu bukit. Bising suara dari mesin-mesin pabrik seakan telah menguburkan jeritan warga. . . .
 Tim LACAK
Tim LACAK
Penulis: Sigit Pranoto, SF. Salam
Reporter: Fajar Said, Herianto CB, AW. Fauzie, Firmansyah.
Indra Yudhitya HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
L A C A K
MATA Uminingsih menerawang kosong ketika bercerita tentang bukit berbatu dekat rumahnya. Senyumnya seperti tertahan, seakan ada getir dan sedih yang terpendam dalam batin nya. ”Dulu sebelum ada pT Margola di sini tidak bising, malam tenang. Sekarang, rasanya tidak karuan terutama bagi anak-anak sekolah,” keluh Uminingsih.
Kebisingan, dampak dari penambangan pT Margola ini dira sakan warga Dusun Selorejo pada umumnya, terutama yang berada di tepi lereng bukit, di antara lokasi penambangan.
Rumah ibu dari tiga orang anak ini berdinding kayu, bermukim di kawasan lembah bukit Menoreh, di atas lereng. Ia bermukim bersama 127 warga lainnya. Rumahnya itu berjarak sepuluh meter, berdampingan dengan lokasi pabrik, posisinya sejajar dari bawah. Di belakang rumahnya, terdapat lokasi bukit yang masih tersisa. Satu meter dari pagar pembatas pabrik, masih ada satu rumah lagi milik warga bernama Yudi.
Inilah kawasan bukit Menoreh, begitu warga biasa menyebutnya. Ia berada di Dukuh Selorejo, Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. posisi pabrik pT Margola sendiri berada di antara bukit ini, menyatu dengan lokasi tambang marmer. Luas lahan pabrik 18,1 hektar. Bukit yang jadi santapan penambangan itu mengandung mangan, fosfat, dan kalsit. Di antaranya bisa digunakan bahan baku membuat keramik. Tak sedikit pula warga memanfaatkan tanah itu sebagai lahan pertanian. Ini tentunya sebelum terjadi penambangan oleh pT Margola.
Anehnya, dalam dokumen perusahaan: Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UpL), tertulis lahan bukit Menoreh hanya tanah tegalan yang tandus dan tak cocok untuk dijadikan lahan pertanian.
Hamparan tanah yang berbukit-bukit itu tidak sebatas digunakan sebagai bahan membuat marmer atau ladang pertanian, namun layak berpotensi menarik wisatawan lokal. Konon, menurut pen gakuan warga setempat, di tumpukan tanah yang kini jadi sengketa itu terdampar bermacam bentuk batu unik dan menarik. Ditambah, terdapat situs Gua Lawa.
”Mas, kalau datangnya sebelum ada pT Margola bisa menyak sikan indahnya alam sekitar bukit ini, ada Batu Adeg, Batu Leter. Juga terdapat sembilan jenis gua,” kenang Kirman. ”Jadi bukan hanya Gua Lawa saja,” ujarnya bersemangat.
”Dulu orang yang berbondong ke sini pada kagum.” ucap Uminingsih, ”ketika kondisi bukit masih utuh dan belum ada penambangan oleh pT Margola.”
Juga biasanya, lokasi ini digunakan untuk kegiatan pelatihan panjat tebing dan perkemahan.
Jumlah bukit di lokasi penambangan ada empat buah. Dari jumlah itu, satu bukit sudah rata dengan tanah, dikenal dengan sebutan Watu Adeg. Bukit itu dipapras habis seperti tangan orang yang tengah menggerus garam. Imbasnya, bangunan yang men ghuni lokasi penambangan tergusur. Salah satunya, gedung SD, juga sumber mata air.

Dari sekian mata air di sekitar permukiman, yang dikenal warga adalah Tuk Mudal. Mata air ini digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kini Tuk Mudal itu sudah dikuasai oleh perusahaan guna kepentingan penambangan. Alasan peru sahaan, lokasinya berada di dalam lingkungan pabrik dan sangat tertutup untuk umum. Karena area lokasi pabrik sendiri dilingkari pagar kawat pembatas, maka kini warga kesulitan mengambil air dari mata air tersebut.

Itu soal kebutuhan air. Bagaimana dengan kondisi warga saat pabrik tengah beroperasi? Menghidupkan deru mesin back hoe
(bego) yang menyalak dan meraung-raung? Bagi mayoritas warga dusun Selorejo, tingginya tingkat kebisingan disertai gemuruh suara pabrik, barangkali, sudah jadi kawan akrab di telinga mereka.
Banyak di antara warga mengeluh akibat suara bising dari mulut mesin pabrik. Ini operasinya spartan, mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 12.00. Dilanjutkan lagi pada jam 1 siang hingga 4 sore. Selepas itu, aktivitas penambangan berhenti. Namun, tetap saja mesin Diesel hidup sampai pagi. Minggu libur.
Saat bego mulai perlahan-lahan memotong dan membelah batu marmer disertai penggalian dari ujung bukit, terdengarlah pekak keras gemeratak suara. Ini berdampak pada perkembangan kejiwaan atau psikologis warga sekitar. ”Anak sekolah tidak ten ang dan tegang,” keluh salah seorang warga setempat. ”Mereka mudah marah.”
Kebisingan tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar lokasi pabrik penambangan, yang bermukim agak jauh pun mengeluhkan. ”Rasanya tidak karuan baik siang maupun malam. Malam suara Diesel, apalagi siangnya gemuruh,” kata Misih kepada saya ketika ditemui di warungnya. Misih dulunya berjualan kebutuhan pokok di tempat yang sekarang jadi lokasi pabrik. Rumahnya berada persis di depan pabrik, sekarang ikut tergusur dan terusir. ”Saya dulu jualan seperti ini di depan pabrik, dipaksa untuk pindah, padahal awalnya diijinkan,” kenangnya. Ia termasuk dari 10 hingga 15 kepala keluarga korban penggusuran yang terpaksa harus pindah
Menambang Marmer. Satu bukit telah habis dikeruk akibat aktivitas Margola yang tanpa henti.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
tempat. Rumah warga yang tergusur itu sekarang menempati sebuah lereng bukit di atas ketinggian 100 sampai 200 meter, di sepetak tanah dengan kemiringan 70-80 derajat.
Ini tentunya sangat rawan longsor, terlebih jika musim hujan tiba.
Tepat di bawah bukit inilah mayoritas warga dusun Selorejo bermukim, ada sekitar 127 keluarga. Lokasi penambangan pT Margola berada di bawahnya lagi, dengan posisi berhadapan. Di tempat inilah, akan sangat jelas terlihat ulah bego meratakan habis tanah berbukit itu. Hampir ludes.
Lereng bukit yang ditempati rumah warga korban penggusuran ini memang rawan longsor. Tanahya kering, tandus tidak berbatu. ”Di bukit ini tidak ada apa-apa, lahan gundul, tanaman gersang,” kata Mbok Juandi. ”Sengsara sekali,” imbuh nenek yang jalannya tertatih-tatih ini. Mbok Juandi tinggalnya di atas puncak paling ujung, terpencil dari tetangganya yang senasib. Untuk sampai ke rumahnya harus melalui jalan yang curam. Ia ditemani satu orang cucu bersama dua orang anaknya. Suaminya meninggal sebelum penggusuran.
”Sudah sebelas tahun saya hidup di sini,” tutur Juandi.
pT Margola beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2000. Ka wasan bukit Menoreh merupakan nama lokasi dilakukan penamban
gan. Letak pT Margola di kesatuan wilayah perbukitan Menoreh, di tengah-tengah Dusun Selorejo. Daerah ini tergolong jauh dari lokasi perkotaan, alias terpencil. Dari arah kota Mungkid, belok kiri pada kilometer empat dari Desa Ngargoretno.
Bukit ini terdapat situs guanya. Dikenal, menurut warga, sebagai Gua Lawa. Istilah lainnya Gua pahlawan. Konon, gua ini menjadi tempat pelarian dan persembunyian pangeran Diponegoro ketika melakukan gerilya, di awal pertengahan abad ke-19, melawan Belanda.
Tentunya, dari cerita tersebut, ada nilai historis pada lokasi itu.
Jalan yang ditempuh ke Dusun Selorejo sebagai lokasi penam bangan ada dua jalur. Satu jalur melewati kawasan Candi Borobu dur, Magelang. Jalan ini tidak sulit. Jalur lainnya, melewati jalan aspal dari Tobong sampai Margola, kondisi badan jalan ini rusak berat, berlubang. Jalan ini kerap dilewati truk yang mengangkuti bongkahan marmer dari lokasi penambangan ke tempat pabrik. Dulunya, jalan ini dibangun warga bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disingkat ABRI, saat lagi marakmaraknya program AMD (ABRI Masuk Desa).
Ada beberapa rumah warga yang jaraknya berdekatan dengan lokasi pabrik. Baik yang menempati lokasi bawah, ataupun depan pabrik di sekitar area bukit Menoreh. Di situlah warga Desa Sel orejo bermukim. Sedangkan yang bermukim di lereng bukit adalah warga korban penggusuran. Itu terjadi pada tahun 1989.
Tahun 1982 mulailah akar konflik itu bermula.
Ketika itu Dusun Selorejo ‘kedatangan tamu’ dari Semarang bernama pT Bamarinco. Lantas melakukan pembebasan tanah seluas 11,5 hektar. Ia mengusung isu pembangunan, menjajakan impian kepada warga: lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup yang layak serta berkecukupan. Maka, Bamarinco mulai melakukan rencana awal dengan cara merekrut para cukong dari desa untuk dijadikan penghubung. Ditunjuk Subari, kala itu selaku Ketua LKMD, bersama tokoh masyarakat setempat.
Mereka ditunjuk langsung sebagai tangan kanan pT Bamarin co, dan melakukan proses pembebasan hak kepemilikan tanah warga.
Sampai di tahun 1985, pT Bamarinco keluar. Dikarenakan mengalami kerugian alias bangkrut. praktis, setelah itu, belum ada yang melakukan aktivitas penambangan. Yang tertinggal, hanya sebuah base camp saja di lokasi.
Di tahun 1986, datang investor yang berasal dari Korea. Mereka tertarik setelah mempelajari data-data tentang keberadaan marmer di kawasan bukit Menoreh.



Tahun 1987 sampai 1989 adalah kurun waktu pahit yang melanda warga Selorejo. Kali ini, berganti lain dan beralih nama menjadi pT Gramer Lampung. Ketika itu warga dipanggil ke Balai Desa dengan dalih melakukan rembug desa. Nyatanya, di sana membicarakan pembelian tanah. Menurut pengakuan warga yang enggan membebaskan tanahnya, selalu di bawah tekanan agar cepat-cepat menjual tanah. ”Masyarakat tidak boleh menolak walau dengan alasan lahan satu-satunya,” aku Suroso.
”Masyarakat pada saat itu dibayangi teror serta diintimidasi,” imbuh Suroso.
Anehnya, perlakuan itu dipraktekkan oleh camat bersama perangkat desa. Mereka membentuk tim yang terdiri dari aparatur keamanan untuk melakukan rembug desa dan melakukan pelbagai macam upaya supaya warga melepaskan tanahnya. Masyarakat yang menolak ajakan akan dicap sebagai anti-pembangunan, bah kan digolongkan pengikut partai Komunis Indonesia (pKI).
Adhitya
Awan HIMMAH
L A C A K HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
* * *
Yang ganjil, proses pembelian tanah itu dilakukan hanya dengan disodori berkas kosong yang sudah bermaterai. Warga disuruh menanda-tanganinya tanpa sebelumnya melakukan ke sepakatan harga. ”Masyarakat ditipu dan mengalami kerugian,” sesal Sugeng.
pada saat itu, warga dalam posisi serba bingung, karena perusahaan terkesan tertutup, tidak ada transpransi atau keterbu kaan. Semakin disayangkan sebab minimnya pengetahuan warga Selorejo yang rata-rata penduduknya adalah para petani. Mereka kurang mengetahui dengan jelas setiap keputusan yang diambil oleh pihak Margola.
”Warga tahunya kalau p T (Margola) adalah pemerintah,” simpul Bakti.
* * *

SELAIN Dusun Selorejo, Desa Ngargoretno terbagi men jadi delapan dusun: Tobong, Gondangan, Wonokerto, Ngembel, Sigabuk, Sumbersari, Karangsari I, dan Karangsari II. Dusun selorejo terbagi atas tiga rukun tangga, dihuni sekitar 127 kepala keluarga.
penggusuran yang dilakukan tahun 1989, menurut kesaksian warga, ada 34 rumah. ”Dengan luas tanah sekitar 18 hektar,” ungkap Kirman, seorang saksi sejarah pembebasan tanah.
pada waktu pembesaan hak kepemilikan tanah, pembelian tiap meternya dihargai Rp.1.250. perusahaan memberi ganti rugi pemindahan, tiap rumah Rp.300.000. pembelian tanah berlangsung selama tiga tahun. Dilakukan melalui sejumlah warga yang ditunjuk oleh Margola. Aparatur pemerintah kala itu, Komedi (almarhum) selaku Camat Salaman, Ahmad sebagai Kepala Desa Ngargoretno, dan Anang Tukiyo, warga biasa. Mereka mendampingi dan terlibat langsung ke lapangan mewakili pihak Margola.
Masa-masa setelah itu, sebagian besar warga mendapatkan intimidasi. Yang menolak menyerahkan tanahnya akan dicabut hak kepemilikannya, atau akan digusur. Suro Wardoyo, kerap disapa Mbah Doyo, warga korban penggusuran, mengatakan ka lau dirinya tidak tahu pada saat proses pembelian tanahnya. ”Kita disuruh tanda-tangani kertas kosong yang telah bermaterai, entah apa maksudnya.”
Dari cara proses pembelian seperti itu, warga menilai ada in dikasi terjadinya manipulasi.
”pembelian tanah tidak sesuai dengan janji,” tandas Mbah doyo.
Ganti rugi tanaman seperti singkong, cengkeh, kelapa,dan ke tela, tidak dihitung menurut ukuran luas tanah. perusahaan hanya memberikan ganti-rugi sebesar 25 juta. Dibagikan bagi seluruh warga yang digusur. Yang menangani waktu itu adalah Komedi, selaku camat, beserta sekretaris wilayah daerah. Lantaran takut dicap anti-pembangunan, warga akhirnya menjual tanahnya. ”Ada yang dituduh orang pKI dengan alasan menghambat pembangu nan,” ungkap Bu Sugeng.
proses pembagian ganti-rugi itu tidak merata. Ada warga yang hanya mendapatkan 3.000 perak. ”padahal mungkin dapat 500 juta, dilihat dari tanamannya yang rata-rata cengkeh,” kata Mbah Doyo.
pemindahan rumah dilakukan pada tahun 2000, namun ada sebagian warga korban penggusuran yang belum mendapatkan ganti-rugi. ”Saya menunggu uangnya selama setahun, baru dikasih dua ratus ribu,” kata Marwan yang baru mendapatkan ganti rugi tahun 2000. Biaya ganti tanaman sebesar Rp.200.000.
Ada beberapa warga mengatakan bahwa harga tanah tahun 1982 adalah 1.750.000.
Sebenarnya di tahun 1988, proses peralihan penguasaan tanah berada di tangan pT Gramer Lampung. Namun, perusahaan ini menunjuk pT Giri Kemusuk Yogyakarta. pemiliknya adalah probo Soetedjo, saudara mantan presiden Soeharto. Konon perusahaan inilah yang bertugas menangani proses jual-beli tanah dari warga. Sampai akhirnya warga dusun Selorejo melepaskan tanahnya, setelah terus dipengaruhi dengan aneka upaya. Termasuk melaku kan pemanggilan, baik lewat aparatur desa maupun para cukong.
Yang disebutkan terakhir itu melakukanya dengan cara men datangi warga dari rumah ke rumah. Namun anehnya lagi ketika proses jual-beli, malah dilakukan melalui ppAT. Bukan lewat prose dur pembebasan tanah yang berlaku pada saat itu, dengan ukuran tanah yang tercantum dalam perjanjian yaitu letter C dan D.
Dalam kualitas penambangan kelas C dan D ini perusahaan akan dikenakan iuran tetap: eksploitasi dan produksi. Margola menanggung 26 marmer bernilai Rp.2.000 tiap ton-nya.
Nyatanya, pengukuran tidak disesuaikan jumlah luas lahan. Tan pa mengacu pada kertas perjanjian sebelumnya, tapi berdasarkan Dinas pertanahan Magelang. Menurut warga, banyak hasil ukuran tanah tidak sesui. Malahan, ukuran luas tanah banyak dikurangi.
Dari namanya, perusahaan pT Gramer Lampung ini jelas berasal dari Lampung. Dulunya menyandang nama pT Margo—sebelum berganti menjadi Margola. Ada kaitan dengan investor Lampung. Beberapa warga mengungkapkan, pT Margola mempunyai be berapa kantor fiktif, salah satunya berada di Semarang. Kantor ini diyakini dipergunakan untuk keperluan transit data, seperti faksimile misalnya.
pasca pT Gramer Lampung berdiri, belum ada aktivitas opera sional pabrik. Hanya mengambil batu di lokasi pembebasan lahan lantas dibawa ke Lampung.
Tahun 2000 hingga sekarang, penambangan marmer di kaki bukit Menoreh itu sepenuhnya di bawah wewenang pT Margola.
Kurun ini amat terasa menyesakkan bagi warga Dusun Selorejo. Lahan penambangan bertambah tiap tahun, mencapai 20 hektar: dua hektar teruntuk lokasi pabrik dan sisanya buat lokasi penam bangan. pT Margola, lantas mengajukan perpanjangan Surat Ijin pertambangan Daerah (SIpD) selepas habis masanya—biasanya tiap 10 tahun sekali. Ijin dikabulkan. 12 April 2000, Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto, mengeluarkan keputusannya. Ini berarti, kalau tanpa aral melintang, aktivitas penambangan sampai tahun 2008.
Setelah membangun satu lokasi pabrik dan penambangan dalam satu kawasan, Margola seakan tancap gas menggerus bukit-bukit Menoreh.
Sampailah terdengar ulahnya.
Terjadi di bulan Januari 2003 ketika warga Jawa Tengah marak membahasa proyek Jagad Jawa Candi Borobudur. Awalnya, yang muncul ke permukaan, kerusakan Gua Lawa dan isu krisis air yang melanda warga Selorejo. Ini disebabkan jarak area penambangan dengan Borobudur berdekatan sekitar sembilan kilometer.
Namun, Margola terus melaju membawa alat-alat berat ke atas bukit. Derum mesin tanpa henti meraung.
Warga berkumpul dan berkata: berhenti! Surat tuntutan pun diajukan. Mereka melayangkan protes dengan membawa berkas sengketa ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Tapi, pimpinan perusahaan Margola, Ana Maria Thenggono, tetap tidak bergeming.
”padahal kalau mau dibuat kerajinan, sampai tujuh turunan mungkin tidak habis.” Begitu ungkapan kesal yang terpendam dari
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Dari Pembebasan Tanah Hingga Menuai Sengketa



pT Bamarinco yang bergiat dalam penambangan marmer di tahun 1982 datang ke Desa Ngargoretno, tepatnya ke Dusun Selorejo. Melalui Kepala Desa dan Subari selaku Ketua LKMD, Bamarinco berkeinginan membeli sebagian tanah milik warga yang terletak di area perbukitan. Warga perlahan-lahan melepaskan tanahnya. Namun, Bamarinco tak jadi berdiri. Selang enam tahun kemudian, 1988, warga kedatangan ‘tamu’ lagi. Kali ini pT Gramer Lampung. Warga yang tanahnya belum mau berpindah tangan diusik lagi. Mereka diancam anti pembangunan, bahkan dicap pengikut partai Komunis Indonesia (pKI), dan tanah yang enggan dijual akan dilongsorkan atau diurug. Warga pun diimingi janji-janji muluk, yakni bekerja di pabrik, ganti lahan yang lebih baik, dan rumah serta aneka tanaman di lokasi sengketa akan diberi ganti rugi pemindahan. Upaya ini ternyata cukup berhasil dan mendinginkan ketegangan. Rupanya, dalam upaya pembebasan lahan itu, pT Gramer tak sendirian. Ada pihak setempat yang memban tunya, diantaranya, Komedi selaku Camat Salaman, Ahmad sebagai Kepala Desa Ngargoretno, dan Subari serta Anang Tukiyo, warga asli Selorejo. Sebelum beroperasi, pT. Gramer Lampung mengubah nama menjadi pT Margo. 24 Juli 1989, surat keputusan Gubernur bernomor 545/0182/1989 terbit. Isinya, pemberian ijin pertambangan daerah (SIpD) kepada pT Margo lewat Direktur Utamanya, Theng Un Laij. Lahan yang akan ditambang seluas 18 hektar. Ijin berjangka 10 tahun. Margo lantas mengangkuti bongkahan marmer dari lokasi dan dikirim ke Lampung. Warga diam. Tahun 2000, pT Margola (dari nama Margo dan Lampung) tiba-tiba mendirikan pabrik di tempat pertambangan. Lahan bertambah dua hektar. 5 Februari 2000, Bupati Magelang lewat surat No. 545/263/05/2000 memberikan rekomendasi perpanjangan SIpD bahan galian golongan C. 12 April 2000, melalui keputusan No. 503/13/C/2000 ijin pun dikabulkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto. Warga meradang. Setelah mendapat beragam tekanan, mulai 8 Januari 2003, Bupati Magelang mengajukan surat pemberitahuan kepada Margola yang berisi penghentian sementara kegiatan penambangan batu marmer. Namun, Margola menampiknya. Warga Selorejo tetap yang kena imbasnya.
 Peta Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dan Lokasi Penambangan Marmer di Dusun Selorejo, Jawa Tengah.
Peta Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dan Lokasi Penambangan Marmer di Dusun Selorejo, Jawa Tengah.
L A C A K HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Jalan Berliku di Balik Margola

Tidak jelas benar, siapa sesungguhnya pemilik PT Margola?
WALHI Yogyakarta, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam penanganan tuntutan warga Selorejo.
Adanya perpindahan tangan sampai beroperasinya pT Margola merupakan teka-teki bagi semua pihak, khususnya warga korban penggusuran.
proses pemindahan hak tanah antar-investor dan masyarakat melalui perantara menambah kusut kasus yang terjadi. Ada keti daksesuaian suara warga dan para tokoh masyarakat yang waktu itu ditunjuk oleh perusahaan melakukan sosialisasi, sekaligus saksi jual-beli tanah tersebut.
Bagi para warga Selorejo yang terkena penggusuran, pembelian yang dilakukan menyisakan harapan yang tidak sesuai dengan kes epakatan. Mulai dari pengukuran tanah, hingga waktu dan jumlah pembayarannya yang tidak merata.
”Belum menerima biaya pemindahan,” kata Marwan. ”Saya menunggu sudah setahun baru dikasih.”
p roses pembelian tanah d i lakukan di Balai Desa. Warga dikumpulkan dan diberi penyuluhan. para saksi, salah satunya, adalah warga yang mempunyai lahan paling luas di antara yang lainnya. ”Kepemilikan tanah paling luas dan dianggap terkemuka di desanya,” kata Dasuki mengacu saksi pembebasan hak atas tanah. Dasuki merupakan warga yang tinggal di Tegalombo. Dia saksi sekaligus yang tergusur karena lokasi rumahnya berada di tempat penambangan.
pERJALANAN saya mencari informasi perusahaan tidak ber henti pada lokasi pabrik di Selorejo saja. Mengacu pada dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Ling kungan (UKL–UpL), tertulis nomor telepon dan alamat faksimile yang terdapat di Semarang. Tempat inilah yang menurut beberapa pengakuan warga Selorejo sebagai kantor fiktif PT Margola.
Bertolak dari informasi itu, saya mencari alamat tersebut. Sore itu saya berangkat. Sampai di kota Semarang pukul 20.30. Saya melacak Jalan Erlangga Raya pleburan. Saya temukan tempatnya. Seketika, laju motor saya hentikan tepat di depan alamat rumah bernomor 12. Ternyata bukan berupa bangunan kantor umumnya. Berada di lokasi perumahan. Layaknya rumah biasa. Seperti tak berpenghuni: suasana dalam rumah gelap, hanya diterangi lampu teras depan rumah, pagar besi depan tertutup dengan taman yang kurang terawat.
prayuda, pengacara pT Margola, ketika ditemui di kantornya, Jakarta pusat, mengatakan bahwa masalah alamat kantor terjadi sebelum adanya otonomi daerah dan pihak pemerintah Daerah Magelang lebih mengetahui. ”Bagi kami ini sudah jelas tidak ada masalah,” katanya, mengacu pada pemerintah daerah selaku pihak yang mengeluarkan ijin penambangan.
Dalam isi dokumen UKL-UpL juga tertulis beberapa alamat perusahaan yang tidak menyatu. Mulai dari alamat kantor peru-sa haan, surat dan nomor telepon serta faksimile, serta status penanam modal yakni penanam Modal Dalam Negeri. Margola mengantungi ijin penambangan SIpD pada tahun 2000. Beban dari kontraktual yang harus dilaksanakan adalah membuat dokumentasi foto, baik lewat udara maupun darat.
Dihubungi melalui telepon, prayuda berujar, ”perusahaan ini merupakan konsorsium dengan pemilik saham orang dalam negeri dan orang asing dari Jepang.”
Selama beroperasinya penambangan, pihak Margola belum membuka akses informasi. ”Ada kesan tertutup,” kata Indra dari

Warga bersama beberapa LSM dan LBH Yogyakarta kini sedang melakukan upaya ke pihak pemerintah daerah agar pT Margola segera ditutup. Lantarannya, kondisi yang terjadi di lapangan sangat kontras dengan yang tertulis di UKL-UpL. Juga, selain karena dam pak langsung yang dirasakan warga sekitar lokasi, yakni kerusakan lingkungan yang teramat parah.
Ketidakterbukaan perusahaan, menurut warga yang menjadi saksi jual-beli tanah, salah satunya karena adanya pemberitaan yang tidak seimbang. ”Mereka mungkin trauma akan pemberitaan,” kata Dasuki, tokoh dan guru SD ketika ditemui saya di rumahnya.
pihak terkait sangat sulit dihubungi walaupun jelas–jelas tertulis dalam dokumen perusahan. Mengacu pada alamat telepon misalnya, ketika dihubungi, operaror dengan nada enteng malah berujar, ”ini perusahaan marmer Lampung, kita tidak ada hubungan dengan Margola.” Seketika itu langsung ditutup.
Dari sekian banyak alamat yang tertera, saya hanya bisa men emui dan mewawancarai prayuda.
Di dalam dokumen juga tersebut nama Ana Maria Theng gono.
Alamat kantor perusahaan yang dipakai terdapat di Jakarta. Tertulis jelas bahwa ia sebagai penanggung-jawab UKL-U pL dengan jabatan pimpinan perusahaan pT Margola. Menurut warga, Ana Maria jarang terlihat keluar-masuk lokasi pabrik. Hanya ada perwakilan saja.
Ketika dihubungi untuk dimintai keterangan, jawaban yang saya terima cukup singkat, ”saya tidak tahu, ini salah sambung.”
Ana Maria Thenggono lantas cepat berkata lagi, kali ini dengan notasi suara meninggi, ”siapa yang ngasih nomor telepon Anda?!” Belum sempat menjelaskan, telepon genggam di seberang suara buru-buru ditutup. Klik!
Indra Yudhitya HIMMAH
Kantor Pabrik Margola. Sangat tertutup bagi warga sekitar.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Lensa
Negeri Pewaris Surga yang Terusir
Setelah Margola beroperasi, masa depan warga Selorejo semakin suram. Perusahaan terkesan tutup mata.
MATAHARI sore perlahan beringsut ke balik bukit Menoreh saat saya pertama kalinya menginjakkan kaki ke Dusun Selorejo. Jam beranjak ke angka 15.30. Di saat menjelang malam, suasana di luar temaram gelap dan sunyi. Ini jauh panggang dari api jika mata saya tertumbuk ke lokasi penambangan. Setiap sudutnya, terpasang lampu penerang, menyorot ke bawah dari ujung bebatuan. Sangat mencolok.
Itulah situasi kecil yang mengandaikan keadaan lokasi penam bangan dengan wilayah tempat tinggal para warga Selorejo, yang kebanyakan pekerjaannya sebagai petani. pagi sekali mereka mulai berangkat ke lahan garapan, di sekitar kawasan bukit Menoreh. Tanaman utamanya adalah ubi-ubian, jagung, dan singkong. ”Beras kami beli,” kata Suyati, 60 tahun. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tanah pegunungan yang minim air biasanya lebih cocok ditanami jagung. Dulunya, jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjadi andalan warga adalah cengkeh, juga tanaman rempah buat bahan jamu. Bagi warga, hasil cengkeh kini tidak menunjang kebutuhan ekonomi lagi sebab di pasaran harganya anjlok, sangat murah.

Warga yang tinggal di lereng bukit merupakan status korban penggusuran.
Mereka terpaksa menempati lereng itu. Di bukit ini, ada 10 hingga 15 kepala keluarga. Rata–rata sudah belasan tahun bertahan hidup di tanah yang rawan longsor itu. Mereka dulunya tinggal di lokasi penambangan yang sekarang dikelola Margola. Lereng bukit itu sekilas tidak tampak berpenghuni. Bagi yang belum pernah mengenal wilayah Selorejo, mungkin akan tidak menduga bahwa di atas lereng itu ada penghuninya. Jarak antar-rumahnya pun sal ing berpencar. Ditambah pula rimbun pepohonan yang menutup penglihatan. Untuk mencapai ke lokasi lereng itu, saya harus naik melewati jalan setapak yang berliku, di atas tanah berkerikil. Jika hujan, tentunya jalan menjadi licin.
para ibu rumah tangga biasanya ikut mengolah lahan sawah atau berkebun, pergi bersama suaminya. Anak-anak yang sudah tidak sekolah lagi dibekali modal orang tuanya mengembala. Hewan piaran sejenis lembu atau kambing. Mereka biasanya merumput.
Dari tingkat pendidikan, anak–anak di Selorejo sangat minim. Data jumlah warga penggusuran rata-rata yang lulus Sekolah Menengah pertama (SMp) hanya sepuluh orang. Mayoritasnya lulus pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Anak Sayuti, Nasirun, 15 tahun hanya tamatan SD. Nasirun punya keinginan bisa sekolah lagi, namun terbentur pada beban ekonomi.
”Orang tua tidak kuat biayanya,” katanya, dengan logat kaku dan bahasa yang tersendat ketika saya mewawancarai di rumahnya.


Bagi anak-anak perempuan Selorejo biasanya merantau keluar daerah atau tetap bertahan hidup dengan bekerja seperti si Nasirun ini. Merumput sekaligus bertani di lahan garapan. ”Buat bekal untuk berkeluarga nanti,” ungkap Nuryadi, ayah Nasirun.
Barangkali Setiani, 13 tahun, anak perempuan Uminingsih yang masih duduk di tingkat tiga SMp, akan bernasib serupa. Dengan alasan himpitan ekonomi yang mendera orang tuanya, si anak memilih merantau atau tetap bertahan di kampung halaman.
Di Selorejo, demikian para orang tua, umumnya usia menikah relatif muda: 18 tahun bagi wanita, dan umur 20 tahun bagi pria. peran ibu rumah tangga yang tinggal di lereng bukit ini bertam
bah bebannya. Ini berkebalikan ketika warga masih tinggal di lokasi penambangan. Setidaknya, hasil dari tanaman singkong, kelapa, ketela, juga cengkeh cukup membuat mereka lebih sumringah. Berbeda dengan sekarang. Bahkan, untuk mengambil kebutuhan air saja sangat susah. Dulu mudah dan berkecukupan, karena di sekitar lokasi terdapat beberapa sumber mata air yang bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. pun buat mengaliri lahan-lahan pertanian. Kini, kondisinya amat sangat lain. Warga yang ingin mengambil air harus turun ke bawah bukit. para ibu yang sudah tua dan renta ini biasanya mengambil air pakai tempayan.
”Kalau musim kemarau harus ambil air dari bawah, jauhnya satu setengah kilometer,” kata Ibu Sugeng.
Saat musim kemarau, menurut warga, beberapa sumber mata air di lokasi lereng hanya mampu bertahan lima bulan. Setelah itu, perlahan-lahan air akan susut dan kering.
Warga Selorejo korban pembebasan tanah, sebagian ada yang masih punya lahan ladang. Sisa lahan yang dimiliki warga berada di atas bukit. Sedangkan bagi warga yang tidak punya lahan lagi, untuk memenuhi kebutuhan pokok, beralih mencari kayu bakar dan areng. Ada juga yang menjadi buruh tani.
”Mereka (buruh tani-red) bekerja di dusun sendiri,” kata Karyo prawiro. Ia sendiri, sewaktu terjadi penggusuran, dipaksa mencabuti tanaman jagungnya. padahal saat itu tanaman miliknya baru saja bersemi.
Hasil tanaman warga biasanya dijual di pasar terdekat. Bagi warga, hasil itu belum cukup benar menutupi kebutuhan pokok. p rawiro membandingkan ketika masih menempati lokasi pe nambangan. Lahan relatif subur dengan hasil tanaman yang banyak, ditambah pandapatan dari jualan makanan karena banyaknya para wisatawan yang berkunjung. Ini yang membuat prawiro amat ter pukul kini. Baginya, hal itu telah cukup memenuhi biaya anak-anak bersekolah dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Tuk Mudal. Sumber mata air utama warga yang dikuasai Margola.
Indra Yudhitya / HIMMAH
L A C A K HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Setelah terjadinya penggusuran warga otomotis hanya mengan dalkan sepetak sawah yang masih tersisa. ”Setelah ada Margola saya macet,” lirih Kirman.
”Dulu tiap kali mau lebaran sering ada keramaian pementasan,” kenang Uminingsih.
Lokasi yang dijadikan lahan pabrik pT Margola, bagi warga setempat, kini merupakan kuburan, di mana dulunya sebagai lahan menggantungkan kesejahteraan. Mereka juga sangat menyesalkan Dinas pariwisata yang tidak terlalu menanggapi lokasi yang ber potensi menjadi objek wisata tersebut, yang kini digerus habis aktivitas penambangan.

”Kalaupun direspon baru sekarang ini, setelah adanya gejolak dari warga untuk menuntut haknya,” ujar Uminingsih. penduduk Dusun Selorejo terdiri dari warga lokal dan pen datang. pekerjaan para pendatang biasanya menggarap lahan milik mertua. Mereka akhirnya menetap. Kebanyakan dari mereka ke beratan diwawancarai seputar penggusuran tanah. Namun dampak dari penambangan pT Margola ini juga ikut dirasakan langsung. ”Saya bukan orang sini, tapi lihat mereka mau nangis,” aku Bakti, yang berasal dari Bandung, suami dari anak perempuan Umining sih. Menurut penuturannya, banyak dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut. Hasil bertani warga berkurang, bah kan ada yang gagal panen sampai tiga kali musim tanam.
Soal hewan ternak adalah cerita lain lagi. Sebelum penam bangan bergulir, untuk menghidupi ternak warga hanya tinggal mengambil di sekitar bukit penambangan. ”Sekarang mencari
rumput di sekitar lokasi saja tidak boleh,” ungkap salah satu warga, menuturkan pengalamannya.
perusahaan ini dari awalnya berjanji akan memberikan kesem patan kepada warga lokal untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Namun pada kenyataannya warga lokal yang bekerja hanya ber jumlah lima orang. Alasan perusahaan simpel saja, yakni kualitas sumber daya manusia yang rendah. padahal janji itu telah membuat warga yang menyerahkan tanahnya di tahun 1982 percaya. Nyat anya, pekerja banyaknya dari Lampung. Warga pun menyatakan ketidakrelaanya. Ditambah pula ulah penambang yang telah me nyebabkan satu bukit rusak berat, teramat parah.

Upaya warga agar pT Margola segera ditutup terbentur pada legalitas yang dipegang pihak perusahaan. Warga menilai, sejauh hak-hak normatif sewaktu terjadi pembebasan lahan tak terpenuhi, maka secara langsung perusahaan yang berdiri di atas lokasi penam bangan tersebut cacat hukum. Margola menolak hal itu. Gubernur Jawa Tengah belum mencabut ijin penambangan. Backhoe di atas bukit Menoreh terus menggerus lahan berbatu marmer itu.
Simak ucapan Misih, salah satu warga korban penggusuran yang kini tinggal di atas lereng bukit yang rawan longsor, tentang Margola: ”Yang terpenting ditutup dulu, tidak diaduk-aduk seperti sekarang ini. Janji pT hanya diambil secukupnya, sekarang Masya Allah diaduk-aduk sampai dalam begitu.”
Indra Yudhitya HIMMAH
Aktivitas Menambang. Dampaknya teramat merugikan buat lingkungan dan warga setempat.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Alur aktivitas penambangan PT Margola ini secara sporadis berakibat buruk terhadap kondisi warga Selorejo.


Bermula dari kegiatan tambang di atas bukit berbatu yang menghasilkan bongkahan dan lempengan marmer, warga setempat terusik karena suara bising yang nyaris terdengar tiap hari. Ini akan berlanjut saat tumpukan marmer itu diangkut menuju lokasi pabrik. Dengan beban maha berat, kendaraan telah merusak badan jalan. Padahal warga pun memakai jalan yang sama. Kenyataannya, Margola seakan enggan memperbaikinya. Debu beterbangan ke mana-mana. Warga waspada.
Selanjutnya, lempengan marmer yang diangkut itu lantas diolah atau dimurnikan. Menjadi tegel atau ornamen. Ini pun mengakibatkan kebisingan. Sebab, kenyataannya jarak yang terbentang antar lokasi pabrik dengan tempat permukiman warga sekitar 100 meter. Amat riskan. Alat-alat berat yang menggali atau mengebor bukit Menoreh itu tentunya menyebabkan kerusakan ekologi.
Ini ditambah lewat kebutuhan air yang maha banyak buat memperlancar aktivitas keseharian PT Margola, entah untuk para pekerjanya atau buat pengolahan marmer. Tuk Mudal, sumber mata air utama warga, kini dikuasai. Dan perusahaan menutup aksesnya. Warga tak mampu berbuat banyak.

L A C A K HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Setumpuk Kesah Tanpa Ujung
Inilah pengakuan warga Selorejo yang menolak kehadiran penambangan. . . .
Karyo Prawiro (75)
”Ancaman warga korban pemindahan adalah longsor.” Begitu ungkap lelaki yang tinggal di area atas perbukitan—bersama 10 hingga 15 warga lainnya. Rumahnya yang berbilik bambu itu terhimpit tebing. Berjarak sekitar satu meter, seakan siap mengubur ketika terjadi longsor besar. Ini tampak terlihat saat saya mengamati bekas longsoran kecil disertai garis retakan tanah yang menganga.
Karyo tinggal bersama istri yang m engurus kebutuhannya sehari-hari. Istrinya mesti ke bawah jika hendak membutuhkan sesuatu. padahal kondisi kakinya sudah tidak kuat dikarenakan usianya yang renta. ”Anak? Saya tidak punya,” katanya.
Saya berdialog ringan dengannya sembari menelan sajian hi dangan keripik singkong. Dengan mulut terbata–bata ia bercerita, terkadang terhenti sejenak, berusaha mengingat dan mencermati serius pembicaraan saya akibat pendengarannya sudah berkurang. Ia mengisahkan peristiwa masa lalu ketika terjadi penggusuran.
Waktu itu, menurut penuturannya, ada yang memakai cara diculik. ”Saya disuruh kumpul di Balai Desa. Di sana sudah menung-gu Camat, Dansek, Carik, dan Anang.”
”Kita orang bodoh dan tidak tahu.”
Ia membandingkan bahwa kondisi sekarang sangat berbeda dengan dulu. ”Butuh duit bisa jual tanaman. Sekarang saya hanya jual arang, kayu pisang, cengkeh. punya tanaman cengkeh pun sudah tidak subur karena tanah di sini tandus.”
Saat tiba musim hujan, yang dikhawatirkan warga korban penggusuran adalah ancaman longsor. ”Saya harus selalu waspada jangan–jangan ada longsor,” kata Karyo prawiro.
Mereka bertahan untuk menahan kantuk, menghabiskan malam, dan menunggu hujan tanpa tidur dengan menyalakan api kecil di belakang rumahnya. Ini antisipasi jika tiba-tiba longsor menimpa rumahnya. Harta milik mereka satu-satunya yang tersisa.
Juandi (50)

Di puncak lereng bukit terjal, perempuan lewat separuh baya itu tinggal. Ia terpencil dari permukiman warga lainnya yang menempati lokasi di bawah.
Dari 12 kepala keluarga korban penggusuran, salah satunya adalah Mbok Juandi—begitu warga sekitar biasa menyapanya. Ia hidup bersama dua orang anak, ditambah satu cucu dari anak pertamanya yang sudah meninggal.
Sosok Juandi di dusun Selorejo cukup familiar. Barangkali karena nasibnya hingga masyarakat sekitar pun merasa iba. Seorang janda yang sudah tua, yang harus mengurus tiga orang anak, ditambah lokasi rumahnya yang berada paling ujung serta terpencil dengan warga sekitar Selorejo.
”Tiap hari bising karena suara penambangan,” ucap Juandi.
”Sekarang mendapatkan air untuk keperluan masak susah dan jauh. Untuk memenuhi kebutuhan air harus turun-naik bukit. Tiap hari tiga sampai empat kali saya dari atas ke bawah ambil air,” tuturnya, dengan nada yang teramat lirih.
Juandi merasa bahwa sekarang ada sesuatu yang kurang. Dan ia mengungkapkannya lewat hasil tanaman yang tak sebanyak dulu, yakni sewaktu ia tinggal di areal tanah yang kini jadi tempat penambangan. Di tempat tinggalnya sekarang, kata Juandi, sangat gersang dan tidak ada apa-apa.
”Dari tiga lokasi tanah yang dibeli pT,” kata Juandi, ”hanya dapat membeli dua tanah. Itu pun satunya saya gunakan untuk tempat tinggal ini.”
”Rasanya tidak senang dari cara-caranya (pengalihan hak atas tanah-red). Saya tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan warga lainnya, terutama para atasan.”
Ia bercerita tentang kondisi rumahnya.
”Kami sangat ketakutan, apalagi di tempat saya anginnya sangat kencang dan malam sangat gelap-gulita.Yang saya lakukan keluar rumah dan nyalakan api, termenung di pelataran rumah sendiri, mewaspadai jika tiba-tiba longsor. Mau berinteraksi dengan tetangga juga jauh. Saya hanya peringatkan anak-anak supaya tidak tidur malam itu.
Dan suatu ketika longsor pun tak terhindarkan.
”pernah longsor tiga kali, menimpa rumah saya sampai miring. Waktu itu hujan disertai angin.
Malam itu terpaksa saya berteriak-teriak membangunkan anakanak saya.”
Marwan (46)
Lelaki ini banyak tersenyum dengan logat jawanya yang kental. Suaranya pelan ketika saya mengajak berbicara. Sebelum ada penggusuran, sempat berjualan makanan untuk para pengunjung wisata. Ia adalah salah satu korban penggusuran karena rumahya berada di lokasi penambangan. pada waktu itu, di balai desa, tanahnya hanya dihargai Rp.1.250 per meter persegi.
”Saya menunggu uangnya selama setahun belum diberi, baru kemudian dari perusahan langsung memberikan kepada saya se banyak Rp. 200 ribu sebagai ganti-ruginya.”
Jual beli tanahnya pun tak mengikuti luas lahan rumah. Semua rata. ”Bekas rumah saya masih ada di depan pagar pT,” kenangnya.
Sekarang ini pekerjaannya menjadi buruh.
”Kalau untuk bertani sudah tidak punya lahan lagi,” ungkap Marwan.
Uminingsih (42)
”Kalau malam batu-batu yang terlihat itu seperti minta tolong.” Begitu ucap Uminingsih mengenai bukit yang kini jadi santapan back hoe (bego) itu.
Ia bersama suaminya, Suroso, sudah tidak punya pekerjaan tetap lagi. Sama-sama mantan pHK kemudian pindah dari Gombong ke Selorejo. Setibanya di kampung halaman itu, ternyata tanahnya sudah dijual oleh sang ayah ke pihak perusahaan.
Ia sekarang tinggal serumah dengan menantu, juga tiga orang anaknya dan satu orang cucu.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Tempat tinggalnya berdekatan dengan pabrik penambangan yang letaknya tepat di belakang rumahnya. Ini tentunya gemuruh penggalian dan pemotongan, serta bisingnya Diesel terdengar sangat kentara, dan memekakkan telinga.
”Rasanya tidak karuan, anak-anak sekolah tidak tenang belajar,” ungkapnya.
Ketidakrelaanya terhadap aktivitas penambangan itu disebabkan kerusakan alam yang teramat parah.
Ia mengenang peristiwa dimulainya penambangan bukit itu, di waktu Agustus tahun 2000 silam. Kini semuanya dalam kondisi yang sangat berkebalikan.
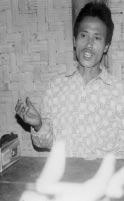

”Warga mengharapkan lokasi tersebut dijadikan tempat wisata, seperti taman batu misalnya,” ujar Uminingsih. ”Terutama kepada Dinas pariwisata setempat. Tapi tidak ada yang peduli dengan keindahan alam di sini.”
Uminingsih menyayangkan sikap sebagain pihak yang kini mulai ambil peduli terhadap kondisi lingkungan di dusunnya. ”Baru sekarang setelah ada tuntutan,” kesalnya.
”Sekarang kondisi di sini sudah rusak, dulu orang berbondong dan kagum. Yang kita sayangkan kenapa Dinas pariwisata tidak turun tangan?” heran Uminingsih.
Uminingsih beserta warga lainnya sudah kehabisan nafas untuk mencari jalan keluar dari belitan penambangan pT Margola ini. ”Kita sebagai masyarakat kecil tinggal angan-angan saja,” ucapnya, dengan nada pelan dan tertekan.
Ia amat sedih menyaksikan pemandangan hamparan bukit di depan matanya.
”Kadang ketika malam, bebatuan yang terlihat terkena lampu itu seperti menangis, minta tolong. Saya terbawa, jadi ikut menangis, sedih benar rasanya.”
Karena sekarang tanah warga telah menjadi hak milik pT Margola, ia sebenarnya tidak menuntut terlalu banyak, semisal tanahnya mesti dikembalikan. Tapi, ia hanya meminta kepada pihak penambang bahwa tanah itu jangan dirusak. Ini berarti aktivitas penambangan mesti ditutup, tanpa terkecuali.
”Itu saja tuntutan saya. Kalau bisa dijadikan objek wisata. Masyarakat sini biar bisa berjualan lagi.”
Suro Wardoyo (69)



Ia adalah warga korban penggusuran dan saksi sejarah pengambil-alihan hak tanah warga ke perusahaan. petani yang dikaruniai enam orang anak dan semuanya lulus sampai tingkat SLTA ini berujar, ”saya bersyukur bisa menyekolahkan mereka walau seorang petani.”
Mbah Doyo merupakan saksi alam bukit Menoreh yang masih perawan. Ia mengenang ketika dulu anak-anak melakukan wisata, mengamati gua, dan meyaksikan bebatuan. ”Tapi sekarang jadi rusak seperti itu.”
pada waktu proses peralihan tanah, kata Mbah Doyo, warga tidak tahu-menahu tentang keputusannya. Yang menentukan para tokoh masyarakat, termasuk perangkat desa yang ditunjuk sebagai perantara perusahaan. Sedang dari pihak perusahan sendiri, waktu itu adalah Subari dan Ana Maria.
Kurun 1985-2000, pembayaran dilakukan bertahap. Bagi warga yang tidak mau menjual tanahnya maka diintimidasi. ”Kalau tidak dipasrahkan, besok tanahnya bisa hilang,” katanya mengenang.
Waktu itu ada 14 warga yang bertahan dan dituduh sebagai pengikut partai Komunis Indonesia (pKI).
Janji perusahaan membuka lapangan kerja menurutnya tidak terbukti. ”Kondisi masy a rakat kini semakin miskin.” p ernah anaknya melamar kerja. Tetapi setelah masuk hanya digaji di bawah upah minimum reguler (UMR). Anaknya lantas keluar.
”Kami tidak menunutut gaji tinggi, hanya ingin disetarakan UMR Jawa Tengah.”
Bagi Mbah Doyo, selain sedikit harapan makmur, ada permintaan lain dengan para aparat pemerintah yang dulunya mengurusi ijin penambangan. ”Mudah-mudahan lahan itu bisa dikelola, dikembalikan ke masyarakat, dan pT. ditutup.”
Indra Yudhitya / HIMMAH
Indra Yudhitya / HIMMAH
Indra Yudhitya / HIMMAH
Uminingsih, Marwan dan Suroso. Bersama warga Selorejo lainnya menuntut PT Margola segera ditutup.
L A C A K HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Prayuda,SH, Kuasa Hukum PT Margola: ”Bukit Itu Tidak Ada Penghuninya...”
Kehadiran pT Margola menyimpan seribu pertanyaan yang belum terjawab, terutama di pihak warga Selorejo. perusahaan sangat tertutup kalau ditanya soal tuntutan warga dan kenyataan lingkungan di lokasi penambangan. Hanya kuasa hukumnya, prayuda, SH, yang kerap mewakili suara Margola. Wartawan HIMMAH, Sigit pranoto, Jimmy pramana dan Fajar Said berhasil mewawancarainya.
Apa posisi Anda di pihak PT Margola?
Kalau pengacara itu merupakan profesi saya di luar perusahaan. Kebetulan saja kami menangani masalah yang dialami pT Margola, di mana perusahaan ini merupakan investor lokal. Jadi merupakan satu-satunya perusahaan yang ada di kabupaten Magelang ini.
Kenapa posisi alamat kantornya banyak dan simpang siur?
Saya tidak bisa menjelaskan, coba tanyakan kepada Dinas pertanahan propinsi adanya beberapa alamat tersebut. Bukannya tidak mau menjelaskan. Kalau bagi kami ini sudah jelas berawal dari Semarang sampai pindah ke lokasi penambangan itu. Kan mereka yang mengeluarkan ijin? Bukannya dari kita.
Bagaimana menurut versi Anda ketika terjadi pembebasan tanah?
Kita kumpulkan warga bersama Kepala Desa yang sudah almarhum, Bapak Ahmad. pada waktu itu diadakan pertemuan, dimotori oleh camat. para warga yang keberatan juga dipanggil. Bupati pada waktu itu juga menjembatani masalah ini.
Kenapa ada ketidaksesuaian data dalam UKL-UPL terkait jarak penambangan dengan rumah warga?
Itu yang tahu sesepuh. p ada saat itu secara lisan sudah menghimbau, kalau bisa penduduk cari tempat tinggal sendiri, 200 meter dari pagar perusahaan.
Adakah bukti otentik dari jual beli yang dilakukan?
Ada di BpN (Badan pertanahan Nasional, red) semua. Sertifikat yang dikeluarkan dari ppAT, dengan konsekuensi kita tidak bisa menutup secara mendadak perusahaan ini. Harus melalui proses peradilan dulu.
Warga mengatakan adanya unsur paksaan saat proses jual beli, benarkah?
Tidak. Siapa yang memaksa dan ketemu dengan siapa? Itu
Dasuki, Saksi Pembelian Tanah:
pertanyaan yang belum terjawab oleh kami. pada waktu pem bebasan tanah ada tim dari BpN. Kalau memang ada yang merasa dipaksa silahkan melalui jalur hukum.
Anda tetap bersikukuh pada jalur hukum?
Lho, kalau kita tidak melewati prosedur hukum, kita tidak mungkin diberi ijin melakukan penambangan.
Kalau ditinjau dari segi Amdal bagaimana?
Ini sifatnya bukan seperti pabrik yang berpolusi udara, yang biasa berakibat pada kebisingan. polusi tidak ada sama sekali karena kita tidak mengkonsumsi bahan bakar.
Tanggapan Anda adanya keluhan warga akibat kebisingan suara penambangan?
Itu sudah kita cek semua. Terakhir karena ada pengaduan dari warga maka dari pemda memanggil ahli dari UpN Yogyakarta. Itu juga atas rekomendasi dari pertanahan propinsi supaya dicek. Ternyata hasilnya masih di ambang normal.
Faktanya, warga mengeluhkan kebisingan tersebut ?
Kalau tentang itu telinga mereka kan tidak terbiasa suara mesin. Ya, paling bisingnya biasanya suara kodok. Kita mengukur dengan mesin. Hasilnya masih diambang normal, berbeda antara hasil pakar dengan warga. Mereka maunya sunyi.
Tanggapan Anda tentang korban penggusuran yang tinggal di lereng bukit rawan longsor?
Saya rasa nggak ada. Bukit itu tidak ada penghuninya.
Bagaimana dengan situs Gua Lawa yang juga ditambang?

Semua itu hanya katanya. Dinas pariwisata juga mengatakan, ini tidak perlu dilindungi.
Menurut pendapat warga dulunya lokasi penambangan itu tempat wisata, bagaimana?
p ariwisata itu tidak ada. Logikanya daerah ini terpencil,
”Kalau Belum Menerima Itu Tidak Benar...”
pihak perusahaan menunjuk beberapa warga desa sebagai saksi saat terjadi pembelian tanah. Dasuki, seorang guru SD, salah satu dari warga Selorejo yang menjadi saksi itu. Ia sekaligus korban pembebasan tanah. Berikut petikan wawancaranya:
Apa tanggapan Anda adanya polemik yang terjadi?
Ada yang berbicara berdasarkan fakta, namun ada pula yang berbicara demi kepentingan tertentu: kelompok dan pribadi. Karena saya sendiri adalah warga yang terkena gusur dari lokasi tesebut.
Bagaimana dengan sejarah penambangan?
pertama kali ada penambangan sudah beralih tiga tangan kepemilikan. pertama hanya mengambil sebagian kecil tanah. Lama sesudahnya saya tidak tahu lagi pembelinya siapa.
Lalu setelah itu?
Ada investor lain. pT Gramer Lampung, kemudian setelah berhasil beralih ke pT Margo. Menurut perjanjian setelah memiliki hak tanah, pT Margo resmi mendirikan usaha, tapi belum ada pelaksanaan penambangan. Selama itu masyarakat menunggu dan berharap bisa bekerja, menambah tingkat perekonomian, juga tingkat pendidikan.
Siapa yang bertanggung jawab ter hadap pembebasan tanah?
Masalah pembebasan tanah ini adalah kepada p T Margo selaku pihak kesatu. Jual-beli tanah tersebut sudah disetujui oleh masyarakat, artinya kedua belah pihak sudah sepakat tidak mempermasalahkan, termasuk saya selaku pemilik tanah. Tanah saya di sana juga sudah dijual sesuai dengan kesepakatan harga.
Status tanah?
pT yang sekarang (Margola- red) hanya melanjutkan yang terdahulu. Artinya pada proses jual-beli dengan pihak pertama Margola tidak tahu. Yang dipercaya untuk melakukan jual-beli tanah adalah Subari, Anang Tukiyo, dan Ahmad (mantan Kadesred) orang yang dianggap penting sebagai juru bicara.
Apa posisi Anda waktu itu?
Hanya sebagai pemilik tanah, tidak ikut rembugan (kese-pakatan-
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004



Reorientasi Pendidikan
Keagamaan di UII
Upaya Membumikan Rahmatan Lil’alamin di Kampus Perjuangan
Oleh: ADEN WIJDAN
GLOBALISASI
di hampir semua lini kehidupan, yang juga telah lama melanda negeri ini, sudah dipastikan sulit dibendung oleh kekuatan apapun. Karenanya, batas-batas antar negara secara geografis menjadi tidak signifikan, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan sudah sirna dilihat dari mekanisme pertukaran informasi, pengetahuan, teknologi, nilai, budaya dan sebagainya. Terhadap fenomena ini Kenichi Ohmae (1995: 2) menyebutnya sebagai borderless world
Dalam kondisi dunia tanpa batas itu, ada beberapa isu yang terus menjadi bahan pe r bincangan yakni demokrasi sebagai instrumen berbangsa dan bernegara beserta nilai-n i lainya,dan pluralisme serta upaya pengarusutamaan kesetaraan jender.
Perbincangan demokrasi dan pluralisme sesungguhnya telah lama, terutama sejak negara ini mulai mendapat kemerdekaan dari negara penjajah. Namun begitu, saat ini semakin menguat karena merupakan kon sekuensi dari mekanisme pertukaran informasi yang dihantarkan globalisasi itu.
Dengan berkembangnya isu itu, maka ada kebutuhan masyarakat untuk berusaha m e maknai dan mengimplemen-tasikannya. Lebih jauh dari itu, kebutuhan itu terutama dirasakan karena ada beberapa kecenderungan yang membawa masyarakat pada perubahan cara pandang dan nilai yang selama ini dipegang.
UII sebagai salah satu institusi pendidikan Islam menjadi tumpuan banyak kalangan dalam upaya menjawab kecenderungan globalisasi itu. Dalam upaya merespon kebutuhan itu, setidaknya UII, secara institusional telah berupaya melakukan reorientasi visinya: Rahmatan Lil ‘Alamin, menjadi “rahmat bagi seru sekalian alam”.
Pertanyaannya, bagaimana implementasi visi itu dalam pelbagai kebijakannya?
Kalau dicermati, esensi visi itu lebih dekat pada upaya pengarus-utamaan “universalisasi” Islam. Jika ini maknanya, maka pendekatan yang dikembangkan adalah upaya menggali dan mengembangkan nilai-nilai dasar Islam seperti tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai

kesetaraan (egalitarianisme), toleransi (tasamuh), moderasi (tawasuth), dan keseimbangan (tawazun).
Dengan dasar pemaknaan visi UII itu, maka konsekuensinya proses pendidikan, baik orientasi maupun kontennya, menjadi mutlak untuk terusmenerus dilakukan perubahan. Dalam hal pe n didikan keagamaan juga tak terhindarkan lagi untuk diperbaharui. Tanpa ada upaya perubahan, sangat sulit dapat diharapkan akan fungsionalnya nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat yang selalu terus berubah.
Kalau boleh dicermati mengenai kinerja pendidikan keagamaan selama ini, lebih diwarnai orientasi formal, simbol dan hanya pada pe r mukaan saja. Namun begitu, bukan berarti tidak menyentuh yang bersifat esensial—meskipun masih amat sangat terbatas. Akibat dari proses seperti ini, lepas dari pendidikannya, menjadi tidak peka terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil pendidikan menjadi bebal terhadap persoalan kemanusiaan, persoalan moralitas, keti-dakadilan, korupsi dan seterusnya.
Dalam upaya reorientasi pendidikan keagamaan, maka sasaran utama pendidikan keagamaan adalah berupaya melakukan perubahan terhadap “mind set”, “world view” peserta didik terhadap persoalanpersoalan masyarakat-bangsanya. Maka, tugas pendidikan keagamaan lebih diorientasikan pada upaya pembebasan, sebagaimana fungsi awal agama itu yakni upaya pembebasan manusia dari keterkungkungan budaya, kemiskinan dan ketidakadilan.
“Siapa saja yang mengabaikan agama dalam analisisnya atas persoalan-persoalan kontemporer berarti mengambil resiko yang sangat besar,” tulis Peter L. Berger, sosiolog agama. Wallahu’alam.
* Staf pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam (PSI)-UII.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
KOMENTAR
Stop! Bukan untuk Penjahat
Kelas Kakap
Oleh RR. ILMIA A. RAHAYU
”Operasi yang dimulai sekitar pukul 21.30 Wita ini diawali dari tempat hiburan di kawasan Jalan Nusantara yang merupa–kan kawasan padat hiburan di Makasar. Tim terpadu yang terdiri dari aparat kepolisian dan pemerintah kota Makasar langsung memeriksa kamar yang dihuni pasangan mesum yang sedang berduaan. Bahkan, dalam penggebrekan petugas menemukan pasangan yang sedang dalam keadaan tidak berpakaian, petugas juga menemukan sejumlah celana dalam (celdam) dan BH yang berserakan. Meskipun demikian, pihak pengelola hanya mendapat teguran dari tim terpadu dan tidak mendapat tindakan hukum.”
Lena Sari Aristianti, sang presenter membaca prolog di atas dalam liputan kriminal Patroli yang ditayangkan di Indosiar, pada tanggal 1 Januari 2004 lalu. pembacaan teks di atas dibarengi dengan visualisasi sejumlah wanita setengah telanjang berlarian menjauh menghindari kamerawan. Wanita yang ketangkap duluan, menutup muka mereka. Sedang yang lelaki, tengah mengenakan pakaian. Mereka bukanlah pasangan suami-istri.

Dapat dikatakan mereka tertangkap basah dalam operasi aparat ketika sedang bersenggama di sebuah diskotek.
Liputan tentang pembunuhan, operasi razia tempat pelacuran, kasus perkosaan, penjambretan maupun liputan tentang penggrebekan diskotek seperti di atas, dapat kita saksikan tiap hari, di tiap stasiun teve.
Ada dua kategori untuk liputan kriminal: news dan in depth.
Liputan kriminal news, biasanya dalam satu program terdiri dari banyak berita. Itu sepotong-potong. Hanya liputan sewaktu penggrebekan atau kala pelaku sudah babak belur di kantor polisi. ”Idealnya rutin. Tapi, saya tidak bisa,” jawab Wiwik Susilo koresponden SCTV untuk wilayah Yog–yakarta kepada Firman, Sigit dan Fahri dari HIMMAH. Wiwik di samping membuat liputan kriminal Buser, ia juga harus mengerjakan liputan untuk program berita Liputan 6. ”Kayaknya saya tidak kuat,” tambahnya.
Liputan news macam ini hanya mem–berikan informasi selapis. Sekali liputan, selesai. Ada trial by the press. Media teve menempatkan mereka, yang monyongnya berdarah, pelipisnya bocor, maupun yang ber tatto sebagai pihak yang salah. Banyak waktu, teve juga memberi detail informasi pribadi tentang pelaku. Tanpa disamarkan.
Media jarang meliput peristiwa pasca–penangkapan. Bagaimana proses per–adilannya? Bagaimana putusan hakimnya? Apakah mereka terbukti bersalah oleh pengadilan? Berapa tahun hukumannya?
Ini penting. Liputan kriminal yang sekali tayang bertentangan dengan prinsip kebenaran dalam jurnalisme. Kebenaran yang dibangun berlapis-lapis. ”Seperti stalagmit dalam sebuah gua, (terbentuk) setetes demi setetes seiring perjalanan
waktu,” tulis Bill Kovach dan Tom Ro–senstiel, dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme
Sedang, untuk kategori in depth , liputannya berupa reportase kasus yang dikupas agak mendalam.
* * *
AWALNYA, adalah Cakrawala pro gram berita sore milik An TV. Tayang tiap pukul 5 petang. ”program ini identik dengan tayangan kriminal,” kata Wiwik Susilo. Setelah itu, menjamurlah program serupa. Ada Patroli di Indosiar, Buser di SCTV , Sergap di RCTI . Belakangan, lahir Sidik di TPI, Brutal di Lativi Modus liputan kriminal di TV7 , serta Kriminal di Trans TV. Metro TV juga bikin acara serupa, Bidik.
Tiap program menunjukkan ciri sendiri. Biasanya di akhir acara. Sergap dengan Bang Napi, Buser dengan info orang hilang. Sedang, Bidik dengan komentar kaum selebritas terhadap tindak kriminal tertentu. Ini untuk kategori news.
Untuk kategori liputan kriminal in depth, hampir tiap stasiun teve memilikinya. Sebut saja Derap Hukum untuk SCTV , Jejak Kasus di Indosiar, hingga Investigasi di Lativi. Tentang label ‘Investigasi’, suatu konsep jurnalisme selidik yang sekarang ditengarai mengalami inflasi.
Liputan kriminal tivi pun hanya berkutat di kota besar-kota besar saja. Macam
Hubungan wartawan-polisi di balik maraknya liputan kriminalitas di teve.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 MEDIA
Jakarta, p alembang, Medan, Lampung maupun Makasar. Tidak seluruh wilayah di negeri ini. Ini mencitrakan beberapa kota besar itu identik dengan kriminalitas.
”Secara umum, program liputan kriminal ini dibuat karena peringkatnya tinggi,” kata Andreas Harsono, redaktur pelaksana Pantau. Bekas majalah bulanan yang sering meliput isu jurnalisme. ”Bahkan bisa dua digit, ketika kebanyakan program berita peringkatnya jarang bisa tembus dua digit.” Di teve, peringkat merupakan penilaian sedikit atau banyaknya pemirsa pada suatu tayangan. Menjadi acuan standar para pengelola media.
”Jadi tujuan program macam ini adalah mencari pemirsa sebanyak-banyaknya dan terbukti memang cukup banyak pemirsa yang menunggu-nunggu program kri–minalitas macam ini,” kata Andreas Har–sono lewat surat elektronik.
Saya pernah mendiskusikan tentang liputan yang konon disukai banyak ibu rumah tangga ini, dengan Nezar patria, Sekretaris Jendral (sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, pada akhir Desember 2003 lalu. Nezar, wartawan muda yang kini bekerja di majalah berita ming–guan (MBM) Tempo . Kala itu, ia sedang cuti dari tempatnya bekerja. Masduki, Ketua AJI Jogjakarta juga ikut dalam diskusi kecil. Tak ketinggalan, Sumanto, wartawan Forum Keadilan.
”Jika kita bicara dalam konteks media, kita sulit mengkategorisasikan (liputan kriminal) ini sebagai jurnalisme atau hiburan,” ujar Masduki sambil mem–bandingkan liputan kriminal dengan liputan seksualitas, berbau mistis dan selebritas.
”Kalaupun itu hiburan, ia cukup mahal harganya,” timpal Nezar.
Obrolan kami malam itu berlangsung santai. Bertempat di kantor AJI Jogjakarta, di daerah Suryomentaraman, Keraton Jogjakarta.
”Saya tahu sering ada reka ulang dalam liputan, karena wartawan datang terlambat. perlu ada reka ulang,”kata Nezar patria. Ia menceritakan, pernah ada kasus dalam fakta, orang yang didakwa penjahat belum tertembak, namun dalam reka ulang pen–jahat itu lantas ditembak. ”Saya kecewa dengan praktik ini,” ungkap Nezar.
pada suatu kesempatan Atmadji Su–markidjo, news director RCTI mem–benarkan tentang reka ulang ini. Bahkan, katanya, itu sering terjadi. Terkadang justru wartawanlah yang memaksa melakukan rekayasa.
”Agar lebih dramatis,” ungkap Atmadji. Ia menambahi, ”itu tidak berlaku di RCTI. Ketika saya membuka rubrik kriminal,
kita harus patuh pada cara peliputan yang benar. Tidak boleh ikut-ikutan merekayasa dan membuat laporan setengah fiktif, setengah jurnalistik. Kalau jurnalistik, ya jurnalistik.” Benarkah?
* * *
LIpUTAN kriminal sekarang adalah li–putan di tempat kejadian perkara (TKp). Liputan model baru ketimbang liputan sebelumnya. ”Dulu, liputan kriminal hanya liputan komando, konferensi pers ke–polisian,” kata Wiwik Susilo. Wartawan menunggu pernyataan resmi polisi tentang suatu kasus. Sekarang tidak.
Lihat saja dalam tiap liputan kriminal. Wartawan terlihat bergerombol dengan polisi dalam usaha menangkap penjahat. Ikut berlarian kecil mengejar pelaku kri–minal. Soal waktu tidak jadi masalah. Kadang siang, malam pun oke.
Objek di-shoot sedekat mungkin.
”Kita merekam kejadian di lapangan, terserah, dia mau berdarah-darah atau tidak. Sama meliput kasus lain. Bentrok dan berdarah-darah. Itu rangkaian kejadian. Akhirnya terekam dalam kamera,” aku Wiwik Susilo.
Akhirnya, teve belum mampu meng–hilangkan tayangan yang tak manusiawi. Tidak ada sensor untuk peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas dan sadisme. Orang ditampilkan dalam keadaan berpakaian minim. Hanya memakai celdam. p elacur yang dalam keadaaan setengah telanjang.
Bukan itu saja. Aksi pemukulan polisi terhadap orang yang dicap penjahat. Mayat yang membusuk. Bandar narkoba yang terseok-seok lantaran ditembak kakinya. pokoknya macam-macam.
Atmakusumah Astraatmadja, mantan Ketua Dewan pers, menyayangkan liputan yang vulgar. Wartawan senior itu mengakui jarang menonton liputan macam itu. ”Saya tidak menyukai,” katanya. Selama menjabat ‘wasit’ pers, lanjut Atma-panggilan Atma-kusumah, jarang sekali ia menerima peng-aduan masyarakat untuk program kriminal ini.
Lantas bagaimana wartawan bisa bikin liputan kriminal dengan mudah? Bagaimana mengurus surat ijin liputan ke pihak kepolisian? Bukankah ketertutupan biro–krasi jadi kendala utama bagi liputan pers di Indonesia?
Liputan kriminal dapat pula disebut embedded journalism. Liputan yang dibuat wartawan dengan cara menumpang polisi. Jurnalisme embedded di Indonesia, marak diperbincangkan saat genderang ‘perang Aceh’ di tabuh pemerintah, Mei 2003 silam.
Sejumlah wartawan mengikuti pembekalan militer oleh TNI, dan meliput perang TNIGerakan Aceh Merdeka (GAM) itu dengan mengikuti gerak TNI saja.
Begitu pula untuk liputan kriminal. Atmadji mengakui bahwa RCTI, tempatnya bekerja, mempunyai akses khusus ke kepolisian. Bentuknya memo bersama antara RCTI dengan kepala kepolisian RI (Kapolri). Isinya, kata Admadji: instansi kepolisian memberikan kemudahan kepada wartawan untuk meliput peristiwa kriminal.
”Tapi itu tidak mengikat kita. Hanya mengatur hubungan yang sehat antara kepolisian dan RCTI,” kata Atmadji, Ini dibuat tahun 2001 lalu. ” Indosiar juga punya memorandum of understanding (MoU) dengan Kapolri,” tambah Atmadji. Bisa jadi ini juga berlaku di stasiun teve lainnya. Walhasil, liputan kriminal teve terlihat seragam.
Hubungan wartawan dengan polisi ini memang rentan dalam hal independensi. Ketidakbergantungan. Ada kecenderungan polisi diberikan proporsi besar. Melacurkan keberimbangan dalam meliput.
Dalam hal ini Wiwik Susilo mengakui. ”Yah, kita terdikte dalam proses mengambil momen dan kejadian. Kita tidak bisa lepas dari kebijakan polisi. Ini kan kasus mereka. Namun dalam proses pelaporan, mereka tidak bisa pesan apapun.” Independensi menurutnya ada pada proses penulisan naskah dan editing.
Andreas Harsono punya pendapat tentang hal ini. ”Wartawan bukan mitra polisi. Wartawan harus bekerja secara independen dari polisi. Hukum ini jelas sekali. Wartawan bukan mitra siapa pun. Ia adalah pelayan publik,” katanya.
”Lobby boleh-boleh saja, tapi wartawan juga harus sadar bahwa ia adalah wartawan yang bekerja independen dari polisi. Kalau polisi melakukan sesuatu yang salah, misalnya main pukul atau tembak, itu harus disiarkan juga, walau konsekuensinya, kita merusak lobby mereka.”
”Batasan independensi menurut an–da?” tanya Widiyanto dari HIMMAH
”Batasannya adalah wartawan bisa tetap asosial dalam pergaulan dengan polisi atau sumber mana pun. Wartawan bukan anti-sosial tapi asosial dalam pengertian wartawan tak mencari teman, tapi juga tidak mencari musuh,” kata Andreas.
”Karakter macam ini memudahkan
63 63HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 MEDIA
Ada Bill
Perjalanan guru jurnalisme selama di Jogjakarta-Magelang.
Oleh WIDIYANTO
JUMAT, 5 Desember 2003, di waktu petang. Waktu yang kami tunggu-tunggu. Saat itu kami akan kedatangan seorang wartawan senior dari Amerika. Namanya Bill Kovach. Dia akan hadir dalam peluncuran majalah Pantau dan buku yang ia tulis bersama Tom Rose n stiel, Sembilan Elemen Jurnalisme. Buku hasil terjemahan Yayasan p antau, organisasi yang menerbitkan majalah Pantau.
Bukunya mungil dengan warna sampul sama dengan buku aslinya: putih dan hitam. ”Buku ini adalah bible of journalism,” kata Andreas Harsono dalam pertemuannya dengan Akhyar Adnan, pembantu Rektor (purek) IV bidang Hubungan dan Kerjasama Universitas Islam Indonesia (UII), akhir Oktober 2003 silam. Andreas Harsono pernah menjadi murid Bill Kovach di Harvard University ketika mendapat beasiswa Nieman Fellowship, tahun 19992000.
”Ah tidak begitu,” kata Akhyar.
”Holy book of journalism.”
”Oke. Holy book of journalism,” kata Andreas Harsono. p ercakapan tentang perbedaan istilah buku itu terasa sedikit sensitif. Kami semua memahaminya.
Kedatangan Andreas ke kampus pusat UII, Oktober 2003 itu, adalah awal dari sebuah acara prestisius. Ia menjelaskan keinginannya untuk mengadakan ke r jasama bedah buku Se m bilan Elemen Jurnalisme
penulisnya, Bill Kovach dari Amerika, akan datang sendiri. ”Dia ingin melihat Indonesia secara langsung,” tambah Andreas Harsono. Tidak lewat sebagian media terbitan Amerika yang terkadang ada bias kepentingan. Memang, tidak semua media luar negeri seperti itu. Kebetulan pas pertemuan, ia membawa koran The Herald Tribune. Headlinenya tertulis jelas: “Why Do They All Hate America.”
*
SORE itu, cuaca Jogjakarta tidak begitu bersahabat. Langit tampak mendung. Diselingi gerimis kecil. Saya bersama Ilmia, Kurnia Basyori, Nugroho Nurcahyo dan Wahyu Gandewo dari HIMMAH berangkat ke bandara Adi Sutjipto. Tujuannya, menjemput Bill Kovach dan Andreas Harsono yang terbang dari Surabaya. Di sana, kami bertemu kawan dari Pantau, namanya Tita Suwage. Dia bersama Alia Swastika.
Di Jogjakarta merupakan acara
ketiga Bill dalam rangkaian kunjungannya di Indonesia. Sebelumnya, wartawan ber–pengaruh di Amerika itu telah singgah di Medan dan Sura–baya. Untuk mendiskusikan konsep sembilan elemen jur–nalismenya.
p ukul 16.20. p esawat Merpati jenis Fokker nomor penerbangan MZ-729 dijad–walkan tiba di bandara. Tak lama berselang terlihat Andreas Harsono dengan seorang bule yang telah berumur. Orangnya tampak masih segar. Tidak seperti kebanyakan orang tua sepantarannya: 70 tahun lebih. Dialah Bill Kovach.
Dalam perjalanan dari bandara ke Novotel, tempatnya menginap, kami sempat berbincangbincang ringan. Tentang perkuliahan, aktivitas mahasiswa, hingga soal lalu lintas Jogjakarta yang semakin ruwet.
Malamnya, ia ada agenda makan malam dengan Ratih Hardjono. Ratih tak lain adalah bekas murid Bill dalam program yang sama dengan Andreas: Nieman Fellowship. p rogram yang bertujuan me–ningkatkan mutu jurnalisme.
Dari Indonesia yang pernah mengikuti program ini hanya empat orang. Selain Andreas dan Ratih, peserta lain adalah Sabam Siagian dan Goenawan Mohamad.
Keesokan harinya, saya dan Ilmia mendapat kesempatan menemani Bill Kovach ke Magelang. Berkunjung ke candi Borobudur dan ke galeri lukisan milik Oei Hong Djien, seorang kurator lukisan.
Bill tampaknya sangat menyukai seni. Ia terlihat sering membawa sketch untuk menggambar. ”Kenapa tidak menggunakan kamera saja?” tanyaku.
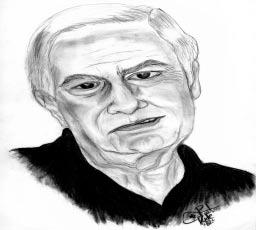
”Saya suka yang natural,” jawab Bill.
Begitu memasuki lingkungan ca ndi, ia lantas men-sketch Borobudur dari ke jauhan. Saya, Ilmia dan Andreas men g ambil jarak di belakangnya.
Goresannya selesai dalam 15 menit. Kami lantas menyusuri jalan ke arah candi. Borobudur, tempat ritual umat Budha. Dibangun oleh Sanmaratungga zaman pemerintahan Dinasti Syailendra abad ke8 Masehi. Suasananya sejuk. Dilingkupi pemandangan indah perbukitan Menoreh,
Gunung Merbabu, Merapi, dan gunung kembar: Sindoro-Sumbing.
Dalam lokasi candi, Bill mampir ke musium melihat dokumen sejarah pe–mugaran Borobudur paruh pertama: antara 1905 hingga 1910. Dokumen itu berupa batu, barang pecah-belah, hingga foto Kasijan Cephas yang mengabadikan proses pemugaran Borobudur. Kasijan Cephas adalah fotografer Jawa yang berpen-didikan Belanda.
Sebelum dipugar, candi yang masuk dalam tujuh keajaiban dunia ini, sempat terkubur dalam tanah. Terkubur sejak pertengahan abad ke-10, dan baru di–temukan kembali pada 1814 oleh Thomas Stanfford Raffles. Dia waktu itu menjabat sebagai gubernur kolonial Inggris di negeri ini. Belanda sebagai penguasa pengganti Inggris lantas memugar candi Borobudur dengan biaya 100.000 gulden. Arsiteknya didatangkan langsung dari negeri Belanda, Van Erp. Di foto dokumenter yang dipajang di museum, tampak sang arsitek sedang berpose di stupa paling atas. juga ada foto candi sebelum pemugaran.
p emerintahan Soeharto juga pernah merenovasi Borobudur. Selama sepuluh
Pandu L. Patriari / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
* *
MENTOR
MENTOR
tahun: 1973-1983. pembiayaannya berasal dari Unesco, organisasi khusus bagian dari perserikatan Bangsa-bangsa (pBB).
Dua tahun setelah selesai pemugaran paruh kedua ini, Borobudur jadi berita besar. Dibom! Tersangkanya mubalig Husein Ali Alhabsyi. Ada yang bilang motifnya adalah protes kebijakan pe–merintah dalam menangani kasus Tanjung priok.
Menuju puncak candi tidak seperti melangkah biasa. Tapi, mengandung makna. Candi terbesar umat Budha ini dibagi dalam tiga bagian. Dan disitulah letak maknanya: perjalanan kehidupan manusia.
Bagian pertama, Kamadhatu. Tahap ini menunjukkan tingkat paling rendah dalam kehidupan manusia: kehidupan duniawi. Dari pesta sampai passionate . Simbol itu tertera jelas dalam relief-relief yang ter–tempel di dinding candi.
Bill sempat bikin sektsa di area ini.
Tingkat selanjutnya adalah Rupadhatu. Berisi gambaran kehidupan Sidharta Gautama sebelum menjadi Buddha. Terdiri dari sekitar 2.000-an ornamen.
Top level melukiskan penyerahan dan pemisahan manusia dari kehidupan dunia–wi. Disebut Arupadhatu. Digambarkan lewat sebuah stupa besar. Berdiameter kurang lebih 15 meter. Disekelilingnya terdapat 72 stupa berukuran agak kecil. Mitosnya, siapa yang mempu menyentuh patung di dalam stupa ini, dia akan kaya. Banyak orang penting dari negara sahabat yang pernah sekadar mencobanya. Tak terkecuali Bill Kovach.
Setelah ke candi Borobudur, Bill me-ngunjungi galeri milik dr. Oei Hong Djien, seorang kurator lukisan kenamaan. Ga-lerinya bukan galeri umum, tapi galeri pribadi. Letaknya di gedung belakang rumah Oei yang asri itu.
Tak kurang dari 1.000 menjadi ko–leksinya. Mulai dari lukisan karya pelukis sekaliber Soedjojono, Nasirun, Entang Wiharso, hingga karya perupa muda Anusapati ada di situ. Saya tidak melihat lukisan yang beraliran Mooi Indie. Aliran seni lukis yang menggambarkan Indonesia serba bagus. Tidak menggambarkan ke–adaan negeri ini yang sebenarnya saat itu. Aliran yang cukup populer di awal abad ke-20, kala masa kolonial Belanda.
Senin, 5 Desember 2003, pukul 09.00.
Tibalah saatnya acara inti Bill di Jog–jakarta: diskusi dan launching buku Sembilan Elemen Jurnalisme dan majalah Pantau . Sebagai panelis lainnya adalah Soetomo parasto dari Dewan pers, sedang bertindak selaku moderator Lukas Is–pandriarno dari Universitas Atma Jaya Jogjakarta.
Sekitar 120 peserta yang hadir. Ke–banyakan dari kalangan pers mahasiswa. Ini bisa jadi berpengaruh pada pertanyaan yang disampaikan dalam diskusi. Semua pertanyaan berkisar tentang jurnalisme. Tidak ada pertanyaan tentang media Barat atau pun Islam yang menurut saya kadang terjebak dalam generalisasi masalah. Suatu metode yang bertentangan dengan praktik jurnalisme yang menuntut perlu fokus pada masalah tertentu.
Beberapa pertanyaan pagi itu seputar kebenaran dalam praktik jurnalisme mau–pun konsep tentang ombudsman media. Tak luput tentang kebebasan pers. Semua dijawab Bill dengan elegan.
Mungkin acara dengan Bill yang paling berkesan bagi saya adalah kunjungan ke redaksi suratkabar harian (SKH) Kedau–latan Rakyat (KR). Di kantor media yang konon punya reputasi buruk dari sisi kesejahteraan karyawan. p un demikian dengan kelakuan pemiliknya, Soemadi M. Wonohito yang sempat terserempet kasus pelecehan terhadap beberapa pekerja perempuannya.
Tidak sedikit pula, wartawannya yang menerima amplop. Untuk ini Bill sempat bertanya, ”Kenapa kita harus datang ke koran yang korup ini?” kata Bill bernada meninggi.
Kali ini Novita Wund, dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ikut dalam kunjungan ke KR. Kami hadir sejam lebih awal dari jadwal semula. Oleh karenanya terpaksa menunggu lumayan lama di ruang tamu kantor KR. Tak ada ‘pejabat teras’ KR yang muncul menemui kami.
”Kantor kayak ini, seperti kantor media di Amerika tahun 1940-an. Buat kota yang berpenduduk 20 ribu,” kata Bill ketika menunggu di ruang tamu.
”Berapa jumlah penduduk di sini?”
”Sekitar 3-4 juta orang,” jawabku.
”Woow...”
Dia memberi penjelasan tentang letak ruang redaksi yang baik. Biasanya tidak berada di lantai satu atau lantai dasar. Melainkan di lantai agak atas. Lantai bawah buat ruang perusahaan atau iklan. Agak tinggi lagi diperuntukan buat kantor redaksi. Lebih tinggi lagi buat redaktur atau editor. Bill berkomentar tentang kantor redaksi KR yang selantai dengan kantor bagian perusahaan
Octo Lampito, redaktur pelaksana KR akhirnya datang menemui Bill. Hanya dia seorang. Dalam perbincangan dengan Octo, Bill tidak pernah terlihat tersenyum. Mimik mukanya serius. Suasananya relatif tegang.
”Koran ini didirikan oleh dua orang: M Wonohito dan Samawi, pada 40 hari sebelum kemerdekaan,” kata Octo Lampito. Soemadi M. Wonohito, pemimpin umum KR , adalah anak M. Wonohito. Sedang, Samawi punya anak bernama Idham Samawi sekarang menjabat sebagai bupati Bantul.
Dialog agak menegang tatkala Bill menanyakan soal amplop. ”Kami sudah tegaskan kepada wartawan kami tentang larangan menerima amplop,” kata Octo.
”Apakah itu secara tertulis?!!”
”pada dasarnya kami tegaskan itu dalam setiap pertemuan,” kata Octo. Redaksi KR tidak menuliskan larangan menerima amplop itu dalam kotak keterangan penerbit seperti media-media kebanyakan. p er–nyataan larangan amplop merupakan bentuk komitmen profesional kinerja wartawan.
Octo lantas menanyakan komentar Bill tentang tiga media terbitan pT Badan p enerbitan KR, yakni Koran Merapi, Minggu Pagi, dan KR itu sendiri. Koran Merapi tergolong media yang tidak serius. Cenderung sensasional, lebih cocok disebut praktik jurnalisme kuning, yang oleh Bill disebut racun demokrasi. Minggu Pagi media mingguan yang agak serius. Dan yang paling serius adalah KR . Ketiga contoh media tersebut tampak tergantung di dinding tempat kami berbincang.
”Jarang saya melihat media di Amerika seperti ini. Satu perusahaan menerbitkan tiga jenis media yang berbeda,” jawab Bill
”Ini membuat pembaca punya tiga kepribadian yang berbeda.”
”Bagaimana dengan lay-out-nya?”
”Itu seperti sebuah sirkus,” kata Bill menunjuk Koran Merapi . ”Anda ikut organisasi kewartawanan?” tanya Bill.
”Ya di persatuan Wartawan Indonesia ( p WI). Saya duduk sebagai seorang pengurus di sana,” kata Octo.
”Berarti kamu punya kode etik?”
”Ada. Besok saya bawakan.”
Keesokan harinya Bill Kovach ber–diskusi dengan 20 pemimpin media seJogjakarta-Surakarta. Termasuk Octo Lampito yang bikin wawancara khusus dengan Bill yang dimuat di koran KR. Dia bercerita tentang pentingnya mempraktik–kan jurnalisme yang baik. ”Karena jurna–lisme dan demokrasi akan hidup bersamaan. Demikian pula sebaliknya: jurnalisme dan demokrasi bisa mati bersamaan pula.” Ucapan yang terus-menerus mengiang di telinga saya.
65 65HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Sudah Jatuh Ketiban Tangga

Potret nasib korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh ABDUL WAHID FAUZIE
pARJIYO , 52 tahun. Laki-laki tua berambut putih itu tampak kuyu. Dia berbaju lusuh. Bisa jadi sekarang dia tinggal meratapi nasib. Mungkin juga ia lelah menunggu keadilan. Sudah tiga tahun perkaranya diproses. Sampai sekarang tidak ada jawaban.
”Hukum itu untuk siapa?”
”Untuk sepihak?”
”Saya akan tuntut keadilan!!” katanya.
p arjiyo adalah korban pemaksaan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan oleh oknum masyarakat di lingkungan desanya. Sebagai korban, parjiyo menga–lami viktimisasi atau pengkorbanan. Dia pernah diancam akan dibunuh, jika ia tidak memberikan tanahnya itu. Bahkan, tambah
parjiyo, tiap malam keluarganya sempat kena teror. Mati-matian ia pertahankan rumahnya. Itu membuat dirinya kerap berurusan dengan aparat.
Cerita lainnya: saat ingin membela diri karena dikepung beberapa oknum ma–syarakat, ia diseret polisi lantaran me–ngacungkan senjata tajam kepada beberapa oknum itu. p adahal mereka sendiri, lan–jutnya, membawa senjata tajam. Namun, mereka yang mengepungnya, justru di–biarkan begitu saja. ”Senjata saya diambil. Saya dibawa ke kepolisian,” lanjut parjiyo.
Ia kemudian bikin buat perjanjian dengan polisi yang menangkapnya. ”Kalau saya dibawa, pokoknya keluarga saya
dijaga. Setelah pulang dari kantor polisi, saya ngeh lihat rumah saya dihancurkan,” kenangnya, saat saya bertandang melihat lokasi rumahnya. ”Aneh.”
Rumah yang ditempati p arjiyo dan keluarganya itu pun sudah musnah. Tak bisa ditempati lagi. Dirusak oknum masya–rakat desanya yang ingin membebaskan tanah miliknya itu. Tanpa ganti rugi sepeser pun.
Saya sempat ditunjukkan tempat pem–buangan barang berharga milik keluar–ganya. ”Di sumur ini barang saya di–masukkan. Ada pakaian, ada kursi, perabot masak dan banyak barang yang belum saya ketahui,” katanya.
Tidak hanya itu. ”Uang saya Rp 2 juta pun lenyap. Entah ke mana. Kandang
Aparat Kepolisian. Menggantikan posisi korban dalam peradilan pidana.
Indra Yudhitya
HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 HUKUM
/
dibakar. Sapi, puluhan ayam dan bebek hilang. Sesudah dilaporkan ke polisi, sapi itu dikembalikan tanpa memberi tahu.”
Ini model viktimisasi pertama: p arjiyo meng–alami kerugian karena kelakuan orang lain.
Itu baru dialami parjiyo seorang. Belum lagi perlakuan buruk yang menimpa istri dan anaknya yang ditimpuk batubata merah oleh oknum masyarakat. potensi orang lain menjadi korban macam ini jelas akan terjadi. Ada multiplied effect , pelipatgandaan dampak dan siapa bakal menjadi ‘korban selanjutnya’. Ini terjadi karena parjiyo selaku ‘korban pertama’ mempunyai je–jaring relasi dengan lainnya. Ia memiliki istri, dan punya anak yang berpotensi sebagai ‘korban selanjutnya’ yang minimal bakal kena dampak kerugian secara immaterial: takut, rendah diri, malu sampai permissi–veness atau pembiaran suatu ketidakadilan menimpa dirinya. Bahkan, bisa pula secara fisik.
Itu terbukti pada seorang anaknya, Nur Arif, 20 tahun. ”Saya dikeroyok pakai tangan kosong. Setelah jatuh, saya dihajar di jidat dan punggung pakai batubata,” ungkapnya. Ia salah seorang anak parjiyo yang saya temui. ”Anehnya lagi, polisi yang ada di situ hanya berucap: Sudahsudah,” tegasnya.
” p olisinya dua orang,” lanjut Nur Arif.
”Waktu saya (dianiaya), sama. Dua orang juga,” ungkap bapaknya, parjiyo. Mereka mengadu ke polisi. Namun, polisi bukan meneruskan untuk diproses, tapi sebaliknya: menuding parjiyo dan anaknya memutar-balikkan fakta.
parjiyo pernah dipenjara selama tiga bulan, karena ‘memberi pelajaran’ pada seorang oknum masyarakat. parjiyo me–nempeleng kepalanya. Ini terjadi garagara si oknum tersebut menabrak dirinya dengan sepeda motor. ”Anehnya saya yang dipenjara. padahal dia yang nabrak!” kata parjiyo.
”Saya curiga pada polisi. Setiap kali saya dan mereka mengadukan kejadian, mesti pihak kami yang diproses,” katanya dongkol. parjiyo baru terkena viktimisasi kedua. Indikasinya, selaku korban tindak pidana, keberadaan p arjiyo diabaikan oleh polisi atau jaksa. pengaduannya tidak segera diproses. Tiap kali berhadapan dengan kepolisian tempatnya mengadu, ia hanya mendapatkan kata-kata, ”Tinggal tunggu jaksa saja.” Itu terjadi sampai sekarang.
Bahkan sampai langkah politis se–kalipun terpaksa parjiyo lakukan. Mengirim surat ke kejaksaan, DpRD DIY, Komisi
Ombudsman Nasional (KON), dan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
NASIB parjiyo sama halnya dengan seorang korban pelecehan seksual. Sebut saja namanya Bunga. pelakunya, bos koran lokal terbesar di Jogjakarta. Firmansyah dari HIMMAH berhasil menemuinya lewat bantuan Sulistiyani, Koordinator Koalisi Aktivis Anti Kekerasan Terhadap p e–rempuan (KAAKT p ). Koalisi yang didirikan oleh beberapa lembaga swadaya masya-rakat (LSM) dan aktivis perempuan ber-dasar atas keprihatinan banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap beberapa karyawati perusahaan koran tersebut oleh sang bos. ”Saya berani melapor karena sudah terlalu banyak korban,” tutur Bunga yang didampingi Sulistiyani dan Damairia pakpahan dari koalisi.
”Saya tahu, mereka (korban pelecehan) tidak berani melapor karena ada ancaman atas kejadian yang dilakukan bos mereka. Bahkan dalam hal ini yang jadi saksi pun siap diperkarakan,” lanjutnya.
”Ia adalah martir,” kata Sulistiyani.
Bunga lalu mengadu ke Kepolisian Kota Besar (poltabes) Yogyakarta sekitar Mei 2002 yang lalu. Ia telah mengalami vik–timisasi pertama.
”Dari segi immaterial berupa dampak sosial dan malu. Dari segi material jelas sekali. Ini ada di Kitab Undang-undang Hukum p idana (KUH p ),” tutur Bunga. ”Dengan adanya laporan seperti ini diharapkan pelakunya diadili dan ini juga menyangkut kekerasan terhadap perem–puan!” tegasnya.
”Adakah harapan dari polisi waktu itu?”
”Saat itu ada, walaupun tipis. Dan harapan saya, kasus seperti ini harus diketahui oleh masyarakat. Waktu itu saya berharap pada polisi agar bisa memproses dan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan jalur hukum. Agar praktik seperti ini tidak berlanjut. Karena korbannya bukan hanya seorang istri atau ibu rumah tangga, tapi seorang gadis yang k e -semuanya sangat dirugikan. Dengan adanya saya melapor, paling tidak saya mengurangi atau membuat sadar,” kata Bunga.
Sulistiyani menambahi, ”ada asumsi dalam menangani kasus (pelecehan) pe–rempuan, polisi selalu meminta bukti empirik. Hal seperti ini harus dihilangkan untuk kepekaan (polisi) terhadap korban perempuan.”
Sungguh tragis. Viktimisasi kedua menimpa Bunga: pengaduannya tidak dilanjutkan. Justru Surat p ernyataan p enghentian p erkara (S p -3) dari polisi
yang ia terima. Alasan polisi waktu itu, dianggap kurang bukti. padahal menurut Bunga yang menyandang status sebagai korban, pengaduannya itu sudah cukup. ”Saya merasa polisi yang memproses hal ini tidak sungguh-sungguh,” papar Bunga. ”Ini terlihat sejak awal.”
Sulistiyani yang duduk berhadapan dengan Bunga, sore itu, ikut berkomentar, ”Kalau begini, ada kerugian dua kali. pertama pelecehan terhadap korban dan terakhir kerugian karena polisi tidak serius menangani kasus,” jelas Sulistiyani.
Dalam hal ini saya sepakat dengan Sulistiyani: double victimize . Bunga sempat protes. Dia menggugat polisi yang mengeluarkan surat penghentian perka–ranya. Ia menolak pengaduannya dianggap polisi kurang bukti. Bunga-polisi justru berkonflik di praperadilan. Ini bisa terjadi lantaran hubungan Bunga selaku korban dengan polisi tidak berakibat hukum ketika mengadu. Bunga dianggap sebagai pihak yang pasif dalam proses berperkara pidana ini. Sebagai korban, Bunga punya ke–dudukan yang lemah.
Tentang kedudukan korban tindak pidana ini pernah dibahas dalam disertasi Dr. Mudzakkir di Universitas Indonesia (UI). Judulnya Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Intinya, sistem pera dilan pidana (Indonesia) belum mampu meng- cover kepentingan-kepentingan korban. Korban hanya punya pilihan untuk melaporkan kasus ke polisi. Hubungan korban-polisi sifatnya tidak mengikat, tidak seperti hubungan tersangka atau terdakwa dengan pengacaranya. p olisi bertugas menyelidiki pengaduan atau laporan terjadinya kerugian pada korban. polisi lantas mengambil alih kedudukan korban sebagai pihak yang dirugikan. Istilah umumnya mewakili korban. Tindakan polisi ini dilakukan atas nama negara.
Aturan macam ini dapat kita lihat di Kitab Undang-undang Hukum Acara p idana (KUHA p ). Di kitab itu, posisi korban tidak jelas diperhitungkan.
Sahlan Said, pengajar mata kuliah hukum acara pidana di Universitas Islam Indonesia (UII) pernah mengatakan hal itu. ”KUHA p kita memang belum ada perhatian terhadap korban. KUHAp kita belum mengatur tentang itu,” ungkapnya. ”Saksi korban itu hanya diperiksa pertama kali. Apakah itu (termasuk) perlindungan terhadap korban atau tidak?” tambahnya. Sahlan Said adalah seorang mantan hakim di p engadilan Negeri ( p N) Jogjakarta. Terkenal sebagai hakim yang jujur dan terkadang progresif dalam memutus per–kara. Tak jarang pula, ia menangani
66� �HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 HUKUM
* * *
perkara besar di Jogjakarta. Seperti kasus Jogja Expo Center (JEC) yang menghukum dua tahun Herman Abdurrahman, anggota DpRD DIY. Sahlan mengajukan pensiun dini sebagai hakim setelah hendak dimutasi ke Kendari, Juli 2003 lalu. Ada indikasi ia sengaja ‘dibuang’. Dalam perkara Bunga, Sahlan Said pernah bertindak sebagai hakim di praperadilan tingkat pertama.
Saya menemuinya di sela-sela ke–sibukannya mengajar. Di kesempatan itu pula, ia mengatakan bahwa KUHAp kita tidak seperti hukum beracara dalam hukum Islam. ”(Di mana) korban dapat menentukan sendiri berapa hukuman yang pantas diberikan kepada terpidana,” kata Sahlan Said.
Banyak putusan kasus yang justru cenderung merugikan korban. Entah karena besarnya kerugian yang ditanggung atau bisa jadi karena sistem peradilannya yang korup. ”Bahkan ada adagium barangsiapa kehilangan kambing, setelah lapor kepada polisi, maka ia akan kehilangan sapi. Itulah yang terjadi dalam negara ini,” komentar Sahlan Said. UU perlindungan saksi juga belum ada.
Bagaimana komentar polisi?
Saya minta pendapat Eko Wahyudi, anggota unit reserse poltabes Jogjakarta, tentang posisi korban secara umum di mata polisi. Saya menemuinya di ruang kerjanya, Markas poltabes Jogjakarta sebelah selatan
Malioboro. Menurutnya, polisi secara umum sudah melayani korban dengan baik. ”Kalau ada satu, dua, ini sifatnya ma–nusiawi. Oknum. Tidak pernah ada polisi yang memberhentikan perkara, kalau syarat yang ada dalam KUHAp itu tidak ter–penuhi,” jelas Eko Wahyudi.
”Saya pikir saksi korban masih di–lindungi karena diwakili oleh pemerintah,” ungkapnya. pemerintah yang dipahami Eko adalah lewat polisi atau jaksa.
Jika memang demikian, bagaimana polisi mampu ‘menaksir’ kerugian yang dialami korban? Baik secara material maupun immaterial. Sejauhmana polisi mampu mewakili korban? Bagaimana jika ke–wenangan tersebut disalah-gunakan? Dengan mengeluarkan S p-3 yang tidak ‘diakui’ korban, misalnya. Ini jadi per–tanyaan mendasar tentang hubungan korban-polisi dalam penyelidikan atau penyidikan perkara pidana.
Sesuai dengan aturan main, setelah penyelidikan atau penyidikan oleh polisi selesai, maka proses selanjutnya adalah pelimpahan berkas ke kejaksaan. p e–nuntutan oleh jaksa, alat negara yang masih tetap mengatas-namakan korban. Hanya tingkatannya lebih tinggi ketimbang polisi. Tugas utamanya melakukan penuntutan berdasar keterangan yang diperoleh polisi. Tentu termasuk juga keterangan korban.
Saya minta pandangan Ranu Mihardja, seorang jaksa di kantor Kejaksaan Negeri

(Kejari) Jogjakarta menyangkut hal ini. Di kantor itu, Ranu juga menjabat sebagai Kepala Bidang Humas dan p enegakan Hukum Kejaksaan Negeri Jogjakarta.
”perlindungan seperti apa yang dimaui korban? Korban kan sebenarnya di–lindungi (dalam KUHA p ) dan dalam pelaksanaannya juga dilindungi,” kata Ranu Mihardja.
Ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Bagaimana dalam proses penuntutan di peradilannya? Apakah tuntutannya sudah sesuai dengan kerugian yang diderita korban? Apakah jaksa pernah konsultasi dengan korban? Meminta pendapat korban tentang hukuman apa yang diinginkannya?
”Saya pikir tidak ada jaksa seperti itu. Semua jaksa tidak ada yang menanyakan kepada korban tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada terdakwa,” ung–kap Ranu Mihardja ”Kalau ada jaksa seperti itu, berarti ia tidak profesional. Sudah menyimpang dan harus diber–hentikan. Jaksa konyol namanya. Bunuh diri!” katanya tegas. p ernyataan Ranu tersebut berlaku umum.
”Bolehlah berpikiran seperti itu. Ini jadi masukan bagi hukum di Indonesia, tapi bukan untuk mempengaruhi,” lanjut Ranu Mihardja.
Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, korban ditempatkan sebagai saksi korban. Diminta sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum.
Hanya itu, tidak lebih.
Banyak korban lantas mengambil alternatif lain. Menggugat secara perdata atau lewat praperadilan. peradilan khusus yang memproses perkara berkaitan dengan penahanan, penangkapan, atau peng–hentian perkara oleh polisi atau jaksa yang dianggap ‘tidak beres’. Seperti menimpa Bunga.
Bunga bahkan mengalami viktimisasi ketiga. Diberitakan buruk di koran milik orang yang telah melecehkannya. ”Dika–renakan dia pemilik media, saya diberitakan dalam banyak hal. p enggelapan, uang iklan masuk ke dalam rekening pribadi, dan sebagainya. Bahkan dalam berita tersebut, saya diposisikan sebagai buron,” tuturnya.
Di praperadilan pertama ia punya harapan besar. ”Sebab hakimnya p ak Sahlan, yang dikategorikan sebagai pe–negak keadilan,” kenang Bunga.
Ia memang menang di praperadilan pertama. p utusan S p -3 polisi yang menya–takan kurang bukti, dianulir. Tapi, pihak polisi selaku tergugat mengajukan
Tiap kali berhadapan dengan kepolisian tempatnya mengadu, ia hanya mendapatkan kata-kata, ”Tinggal tunggu jaksa saja.” Itu terjadi sampai sekarang.
Melapor Polisi. Langkah yang bisa ditempuh korban untuk menuntut keadilan.
Indra Yudhitya
HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 HUKUM
/
Sepenggal Cerita Ekonomi Lokal
ingatkan perasaan banyak orang akan pahitnya kemiskinan. Banyak yang me–ninggal, dan bunuh diri akibat kondisi macam itu. Pulung Gantung . Dan, bisa jadi daerah ini adalah sebuah miniatur bagi jutaan daerah miskin di Indonesia. .
Barangkali juga tak beda jauh dengan perjalanan di pegunungan lain. pada saat musim hujan begini, tak sejengkal tanah pun luput untuk tidak ditanami. Beragam palawija seperti jagung dan ketela, tumbuh di mana-mana. Bahkan, di perkuburan sekali pun.

”Tapi kondisi ini berbalik saat kemarau tiba. Tanah di sini tandus, dan yang bisa dijual hanya batu. Tanah di Gunung Kidul sebagian besar mengandung batu, batu itu nanti dipakai untuk campuran pembuatan kaca,” cerita Ngatidjo, Ketua Bidang Training dan p engembangan Koperasi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah atau biasa disingkat Bekatigade, pada saya.
”Karena itu datangnya musim hujan tidak akan disia-siakan oleh penduduk untuk menanam segala yang bisa.”
MENUJU Desa p anggang, Gunung Kidul. Sama halnya melakukan per-jalanan jauh. Butuh waktu kira-kira dua jam perjalanan dari kota Jogjakarta. Melewati jalan berkelok-kelok, membelah gunung dengan hamparan ladang hijau dan hutan. Sejauh mata memandang, tampak p e-gunungan kapur Kidul yang menghijau. Mengikis habis kesan tandus di musim kemarau. Sebagian rakyat Indonesia mengenal Gunung Kidul sebagai daerah tandus, sebagian yang lain bahkan mung kin tidak mengetahuinya. Namun Oktober yang lalu, saat musim hujan tiba, saat saya melakukan liputan, beberapa daerah di Gunung Kidul ini mengalami banjir. Karena konstruksi tanahnya yang sangat sulit mengikat air.
Di daerah Gunung Kidul ini meng–
Gunung Kidul dipisahkan oleh daerah Batur Agung di sebelah utara, Lembah Wonosari di tengah dan wilayah p e–gunungan Seribu di sebelah selatan. Daerah Batur Agung merupakan daerah vulkanik tua yang mempunyai kesuburan tanah yang tinggi. Tapi karena banyak erosi, kesuburannya menjadi berkurang. Se–karang, lagi digalakkan penghijauan dan ini bikin Bupati mendapat penghargaan karena keberhasilannya melaksanakan program penghijauan itu. Namun masih bukan tanpa masalah. Belakangan, industri mebel di propinsi D.I. Jogjakarta yang menjamur, sedikit banyak merangsang maraknya pencurian kayu jati di sini. Hutan jadi gersang dan gundul. Kekeringan melanda, mungkin terjadi akibat gundulnya
Aktivitas ekonomi yang beradap tasi dengan budaya setempat sebagai salah satu wujud gerakan ekonomi
Oleh ASTUTIK dan ILMIA A. RAHAYU
Indra Yudhitya/
HIMMAH
Industri Kecil. Mampu bertahan meski cuma berbasis lokalitas.
66� �HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 EKONOMI
hutan ini.
*
ADZAN dhuhur baru saja selesai di–kumandangkan. Sampailah saya di lokasi koperasi kredit mendasar, binaan Bekati–gade. Beberapa karyawannya menyambut dengan ramah. Terlihat ada dua orang yang melakukan transaksi siang itu.
Koperasi ini oleh sebagian penduduk setempat dianggap sebagai penggerak ekonomi lokal di Desa Giri Sekar, panggang ini. Dibangun sebagai penunjang dana. Memperlancar transaksi ekonomi warga–nya. Koperasi ini berdiri tahun 1990.
”Mulanya berdiri, kami melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat menerima dengan baik,” tutur Suprihanti mengawali perbincangan. Sehari-harinya perempuan paruh baya ini bekerja sebagai petugas pe–ngawas lapangan pada koperasi tersebut. Suprihanti mengaku pernah merasa ke–sulitan akibat kecurigaan warga setempat tentang pendirian koperasi ini.
Namun karena ada sosialisasi bahwa koperasi ini menginginkan kemajuan eko–nomi rakyat, mempererat rasa kekeluargaan dan gotong royong, maka masyarakat menjadi sadar dan ikut berpartisipasi menjadi anggota koperasi.
Dengan proses lama, kurang lebih empat belas tahun, aset yang dimiliki sekarang mencapai Rp 1,4 miliar. Jumlah yang mengagumkan. padahal simpanan awalnya hanya sebesar Rp 800 ribu.
Yang masih dikeluhkan Suprihanti hanyalah sikap warga yang cenderung nrimo dan susah diajak maju. Di samping itu tingkat pendidikan warga yang ke–banyakan hanya lulusan sekolah dasar.
Budaya seperti ini merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat tradisional. Tentu saja ia bukan lahir dengan sendirinya. Kolonialisme yang lama dan melakukan konspirasi dengan kekuatan feodal, meng–konstruksi masyarakat menjadi kaum dengan nilai, sikap, perilaku budaya yang membuat mereka terperangkap dalam pemiskinan.
Meski kultur tersebut sepertinya sudah mendarah daging, bisa jadi tidak laku buat Suprihanti dan pengurus koperasi lain yang dengan tekun mengelola koperasi ini. Dan membuatnya mampu bertahan.
Bambang Nindyo Yuwono, Sekretaris Bekatigade yakin bahwa keberhasilan koperasi itu tergantung pengurusnya.
Ungkapan Bambang ini menunjukan bagaimana lembaga-lembaga ekonomi masih memposisikan masyarakat menjadi objek yang hanya mampu dimobilisasi, namun tidak menempatkannya sebagai pelaku utama ekonomi. Tak terkecuali Bekatigade-nya.
Yang selalu tidak bisa dinafikan dari
daerah-daerah miskin di Indonesia adalah masuknya modal asing. Baik berupa hibah maupun utang. Lihat saja penelitian yang pernah dilakukan Indonesian Coruption Watch (ICW) di kawasan Indonesia timur yang menunjukan besarnya utang pada masyarakat lokal ini. Gagalnya Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project dan Sulawesi Agriculture Area Development Project yang dibiayai Bank Dunia. penelitian ICW mengenai peristiwa itu kemudian dibukukan dengan titel: Utang yang Memiskinkan.
Dalam konsepsi ekonomi-politik neo–
liberal, sekali lagi, apa yang disebut dengan bantuan ini, yang ditujukan kepada negaranegara miskin sebagai instrumen pemutus rantai setan kemiskinan.
‘Fighting poverty.’
Dalam konsepsi struktural, mekanisme kekuasaan finansial yang bertopeng malai–kat disebut dengan pemiskinan. Oleh Dos Santos, seorang yang menjadi penegak teori ketergantungan, hubungan ini di–sebutnya sebagai ketergantungan fi–nansial industrial. Di sini tidak terjadi dominasi politik, tapi negara pinggiran macam Indonesia ini dikuasai kekuatan-kekuatan
 Menjual Jamu. Usaha kecil informal perlu bantuan dan perhatian dari berbagai kalangan.
Menjual Jamu. Usaha kecil informal perlu bantuan dan perhatian dari berbagai kalangan.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 EKONOMI Indra Yudhitya / HIMMAH
* *
finansial dan industrial dari negara pusat. Hal ini terjadi melalui penanaman modalnya baik langsung maupun lewat kerjasama.
p un demikian dengan Bekatigade. Untuk menunjang kebutuhan dana, peng–urus koperasi ini diberikan kucuran dana dari Merc Corporation America yaitu sebuah funding yang meminjamkan dana dengan bunga yang dianggap rendah: sebesar 2 persen.
Rubiyo adalah salah satu nasabahnya. Ia mengaku dengan adanya koperasi ini membuat usaha kelompoknya sangat terbantu. Ia telah mendapatkan bantuan berupa uang dan alat-alat produksi.
”Dua juta dengan bunga 2,5 persen,” katanya, ”juga mendapat pinjaman dana lunak untuk menyediakan alat seperti papan, alat pukul besi, susuk dan wajan.”
”Usaha produksi emping di sini berjalan cukup baik, bahkan satu hari bisa lima kilogram. Tiap kelompok terdiri sepuluh sampai dua belas orang, namun pe–masarannya susah,” kata p rihanti. Dia merasa kewalahan dalam memenuhi pe–sanan.
Namun, sebagian dari mereka mengata–kan pertumbuhan ini tidak maksimal. Masih terdapat hambatan. Ada beberapa infras truktur yang belum mendukung. Misalnya, mereka tidak mampu membuat jaringan ekonomi yang dapat menyalurkan hasilhasil industri kecil mereka. Juga kurangnya sumberdaya manusia yang cakap, yang mampu mengelola industri ini.
Bahkan, tidak ada yang merasa punya kebutuhan akan pelatihan. padahal Ngatijo juga menginginkan adanya inisiatif dari warga.
Belum lagi, ditambah dengan biaya sosial yang harus dikeluarkan: macam tradisi hajatan pada upacara pernikahan atau khitanan, dan upacara adat lain membebani warga desa
Sudah jadi rahasia umum, bahwa kebanyakan masyarakat desa punya ciri: komunal dan homogen. Agak berbeda dengan warga kota yang cenderung individualistis. Kultur desa yang demikian lebih gampang untuk mendorong ter–ciptanya kapasitas ekonomi lokal. paling tidak ini yang terjadi di Desa Giri Sekar, Kecamatan panggang, Gunung Kidul ini.
Menurut hasil penelitian Djuneidi Saripurnawan, Ngatidjo dan Juni Thamrin tentang ekonomi lokal di Giri Sekar, pang–gang, bahwa sebagian besar rakyatnya adalah petani yang kebanyakan memiliki areal pertanian cukup. Sudah ada kelompok atau organisasi-organisasi seperti koperasi simpan-pinjam, arisan dan kelompok kerja tani.
Di samping juga telah ada modal sosio-
kultural berupa komunalitas yang masih kental, yang ketika dimobilisasi akan mampu membentuk kehidupan yang lebih kualitatif.
Hasil riset mereka itu telah diterbitkan oleh Bekatigade yang bekerja sama dengan Yayasan penguatan partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (Yappika), Jakarta. Berjudul: Kapasitas Ekonomi Lokal; Studi Penjajagan Penguatan Ekonomi Lokal dengan Community Currencies System.
* * *
TAK jauh beda dengan ekonomi lokal di Desa Giri Sekar, Kabupaten Gunung Kidul, di Sanur, Denpasar juga terdapat aktivitas serupa.
Akhir tahun lalu, Ilmia A. Rahayu melakukan liputan ke Bali untuk menge tahui sejauh mana eksistensi desa-desa adat di sana. Tak terkecuali, kisah tentang ekonomi lokalnya.
Bali adalah pulau yang terkenal dengan pariwisatanya. Tidak sedikit wisatawan asing tinggal menetap dalam tempo lama setiap tahunnya. Sehingga banyak budaya yang saling berinteraksi dan berebut eksistensi. Termasuk salah satunya adat Bali dan agama Hindu yang memberi warna kehidupan di pulau Dewata, surga bagi para Dewa.
Untuk menjaga eksistensi budayanya, desa adat di Bali, termasuk desa Sanur, mendirikan usaha yang mereka sebut sebagai Lembaga perkreditan Desa (LpD). Sebagian rakyatnya merasa koperasi ini bisa meringankan biaya, terutama untuk pembiayaan kepentingan adat macam upacara keagamaan, pembangunan pura dan bangunan lain.
Seperti diketahui umum, bahwa setiap upacara adat atau upacara keagamaan lain yang diselenggarakan di Bali ini, terkadang menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Upacara adat Ngaben, misalnya, dapat menelan biaya ratusan juta rupiah. Dan tak jarang upacara macam itu dijadikan objek wisata.
Dengan dijadikannya upacara adat atau upacara agama sebagai objek pariwisata, dikomersilkan, maka boleh dibilang telah terjadi pergeseran makna kegiatan itu. Dari yang sifatnya mistis dan suci, menjadi ritualitas belaka. Lebih buruk hanya berorientasi ekonomi semata. Hal ini akan menciptakan beban tersendiri bagi ma–syarakat tak mampu.
Kepala Desa Sanur menceritakan pada saya tahun 2003 lalu, bahwa Walikota Denpasar pernah memberi bantuan kepada 1.400 desa adat. Besarnya Rp.25 juta rupiah tiap desa. Dana ini oleh pemerintah Desa
Sanur, lantas dipakai untuk program pe–ngentasan kemiskinan dan pembangunan jalan. Dimulai dengan penyaluran dana kepada masyarakat melalui LpD.
Di desa adat ini tidak ada unsur paksaan untuk meminjam. Jadi siapa yang mau memanfaatkan, maka dia diperbolehkan meminjam dana. Tapi LpD selalu memeriksa untuk mengantisipasi jika mereka memiliki dua kredit, misal di BNI dan BCA. Mereka akan dimintai laporannya pada pasowanan agung yang dihadiri oleh semua anggota dan pengurus agar bisa mengetahui asetaset desa.
Di samping itu, L pD juga memiliki bidang usaha berupa tempat cuci mobil dan kios-kios tempat berjualan. Mereka mene rapkan prinsip sewa dulu, setelah dikelola dengan sungguh-sungguh, baru diberikan secara cuma-cuma. Dari seluruh peraturan desa adat ternyata tidak ada penolakan dari warganya.
Ketika ditanya mengenai modal awal LpD, Kepala Desa Adat Sanur menjawab bahwa dana berawal dari pemerintah, kas desa adat, iuran masyarakat dan tentunya utang dari lembaga internasional. Bahkan untuk meyakinkan bahwa ketentuan dan manajerial yang disarankan oleh World Bank dijalankan oleh Desa Adat, di–lakukan konsultasi yang dilakukan secara rutin. Untuk Bali, konsultan proyeknya ditangani oleh BUIp, singkatan dari Bali Urban Infrastruktur Project.
Sebagai kompensasinya, desa adat diberikan utang lagi dengan embel-embel bunga yang sangat ringan.
Untuk masalah pembangunan jalan, desa adat mendapat konsultasi dari World Bank . p embangunannya dimulai sejak tahun 1998. Rencana pembangunannya akan dilakukan tiga kali. Namun, sekarang baru dua kali pelaksanaannya.
Satu kali pembangunan biasanya menggunakan dana hingga Rp.500 juta. Kontribusi dana terbesarnya sekitar 80 persen dari World Bank. Sisanya, diambil dari LpD.
p injaman uang dari Wold Bank ini bersifat pinjaman lunak dengan jangka waktu 10 tahun.
”Negara yang berutang, dan dibayar bersama oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya kemudian.
��1 1HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 EKONOMI
Abidah Al Khalieqy : “Ketidakpuasan itu Bukanlah pada Al-Qur’an”
DI zaman jahiliyah, keberadaan perempuan selalu dipredikatkan sebagai penghalang kemajuan peradaban. Oleh karenanya, memiliki anak perempuan senantiasa bakal bikin aib keluarga. Dengan pemahaman bahwa perempuan merupakan pertanda ganjalan besar yang akan datang menghalangi roda ekonomi keluarga. padahal jika dirunut ke sejarah, kaum laki-laki harusnya berterima kasih pada perempuan, karena kaum hawa inilah yang mengawali bagaimana cara bercocok tanam, ketika mereka ditinggal berburu. Di zaman moderen sekarang pun demikian. perempuan terbukti punya peran besar dalam keluarga, lingkungan masyarakat bahkan sampai kehidupan kenegaraan. Tidak lagi hanya sekadar kanca wingking lelaki seperti laiknya budaya Jawa kuno.
Abidah El Khalieqy, seorang penulis yang terikat secara emosional terhadap ketidakadilan yang diterima oleh kaum hawa, mengisi harinya dengan menebarkan ide kesetaraan perempuan terhadap laki-laki dalam kehidupan sosial. Menelurkan gagasan bahwa, menurutnya, posisi perempuan dan laki-laki dalam kitab suci itu hampir sama. ”Ada perbedaan, tapi itu tidak mutlak,” katanya.
Kepada HIMMAH ia tetap menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dari segi hak dan kewajiban.
Mbak Ida—begitu ia sering disapa—kemudian menuliskannya dengan sederhana ide-ide feminim tersebut dalam buku, jurnal atau makalah-makalah diskusi. Selain itu juga ia kerapkali mendapat undangan untuk menghadiri dan mengisi seminar dengan tema feminisme.

Berikut petikan wawancara khusus yang dilakukan oleh Firmansyah dan Astutik dari HIMMAH, bertempat di kediamannya, daerah Maguwo, Jogjakarta.
Bagaimana pendapat Anda tentang perempuan dari sudut pandang agama?
Islam mendudukan perempuan sederajat sama dengan halnya kaum laki-laki dalam konteks spritualitasnya. Secara riil, perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Al-Qur’an jelas menyatakan perbedaannya. Tapi tidak semuanya mutlak berbeda. Ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga ada perbedaannya, perbedaan itu sangat jelas seperti kaum laki-laki memberi nafkah kepada sang istri dan istri tidak wajib memberi nafkah pada pihak laki laki, ada banyak hal yang membedakan mereka, sebab antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa disejajarkan dalam satu kursi dalam segi kewajiban dan hak mereka berbeda. Dan pihak perempuan tidak bisa dihukumi lebih rendah dari pihak laki laki, dan orang laki laki tidak bisa juga dengan mengatasnamakan ayat arrijal qowwamun ala nisa’ atau laki laki lebih tinggi dari perempuan itu tak bisa. Ayat tersebut kan ada kelanjutannya. Kemudian persamaan antara keduanya dalam hak untuk menuntut ilmu, sebab pada kontek ini kewajiban antara keduanya sama. Apalagi dalam hal ketakwaan, Islam sama sekali tidak membedakan antara keduanya, sebab di hadapan Allah, manusia diukur dari segi ketakwaannya.
Bagaimana dengan poligami. Seperti yang kita ketahui poligami merupakan bagian dari ketidakadilan terhadap perempuan, tetapi ini diperbolehkan oleh agama. Apakah ini menyangkut keadilan dan kesederajatan antara laki laki dan perempuan?
Sebenarnya kita tak bisa melihat suatu persoalan hanya pada satu pandangan, sebenarnya ayat dalam surah An-nisa’ ayat 3 tersebut berkesinambungan pada ayat selanjutnya. Dan saya memahaminya sebagai ayat monogami sebab persoalannya kenapa wahidatan (satu saja). Dalam ayat tersebut Allah sendiri mengatakan bahwa sekali kali kamu tidak akan bisa adil. Jadi Allah saja sudah mengatakan bahwa karakter manusia tidak bisa adil, maka ketentuan orang tersebut monogami, pawahidatan. Jadi jika sudah ada ketentuan seperti ini, buat apalagi membahas persoalan selanjutnya seperti mastna, tsulasa, arba’a itu sudah tidak penting lagi. Konteknya kita harus melihat pada asbabun-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat). Kita sudah tahu betapa bijaksananya Al-Qur’an dalam menjelaskan apa yang baik bagi manusia dengan sebijaksana mungkin. Jadi tidak langsung dengan kesan memaksa dan harus menikah satu kali saja, ini kan frontal, tidak sesuai dengan keadaan Islam datang, jadi dengan adanya kata kata masna sulasa warruba’ itu kehalusan.
Apakah hal ini benar-benar menutup kemungkinan kaum laki laki untuk poligami?
Kita harus mencari keterangan terhadap poligami apakah memang dilarang atau ada ketentuan yang bersyarat jika harus
M. Ali
Prasetya / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 DIALOG
dilaksanakan, hal ini kita tidak hanya menuju kepada Al-Qur’an, tapi masih ada sunnah rasul, dan kita tahu apa yang dilakukan oleh rasul itu merupakan sunnah. Dalam hal ini rasul juga melakukan poligami. Tapi yang dilakukan oleh rasul itu sesuai dengan AlQur’an, tidak ada praktik diskriminasi terhadap perempuan, sekalipun masih banyak kontroversi terhadap poligami yang dilakukan oleh nabi. poligami yang dilakukan oleh seorang nabi pun masih ada konflik -konflik keluarga, yang dalam hal ini antara Aisyah dan Zaenab. Di antara mereka selalu saja bermusuhan. Sebenarnya dalam pernikahan Nabi, belum bisa menyatukan istriistrinya. Bukan saya mengatakan poligami nabi tidak berhasil, dan ini menunjukkan sifat manusiawi terhadap nabi, bahwa ternyata poligami yang dilakukan oleh seorang rasul pun kurang sakinah, dan jelas poligami tidak membuat suatu keluarga menjadi sakinah antara istri yang satu dan yang lainnya terjadi kecemburuan terus menerus, kemudian saling benci-membenci dan ini berlangsung pada anak-anak mereka. Kemudian bagaimana ketika Mariam Al Ibtia salah satu istri nabi yang sampai melahirkan dan dari sini mulai timbul kecemburuan dari istri-istri yang lainnya. Dan pada saat itu luar biasa kecemburuannya sampai-sampai nabi mengharamkan istri-istrinya bercampur dengan Mariam.
Jika begitu, apakah poligami merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan?
Sebenarnya ajaran poligami itu sebelum Islam datang pun sudah ada, tapi mungkin ketentuan-ketentuannya berbeda, dalam tataran prinsip dasarnya Islam itu monogami. Tapi saya tidak berpendapat islam tidak memperbolehkan poligami. Jika dibilang bagian dari diskriminasi mungkin juga ya, karena apa yang dipraktikkan selama ini oleh umat muslim dalam berpoligami tidak manusiawi tidak memenuhi rasa keadilan dan dari sini jelas di sana ada diskriminasi. Kita tak bisa mengatakan Islam mendiskriminasi perempuan, tapi ini dalam praktek umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam itu ternyata mendiskriminasi perempuan. Jadi lebih tepatnya ini dilakukan oleh umatnya. Bukan ajarannya. Bahkan ajarannya pun sudah jelas, jadi mana ajaran nabi itu yang membawa kebaikan dari praktek poligami tersebut, kita tahu sendiri apa yang dilakukan nabi pada istrinya tapi ternyata para istrinya pun masih tetap saling cemburu dan saling benci dan mungkin ini bisa seumur umur.
Oh ya, dalam buku Perempuan Berkalung Sorban, Anda mengangkat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul, bekerja dan sebagainya. Seperti apa Anda melihat ruang pergaulan perempuan jika dibanding dengan laki-laki?
Memang ada perempuan yang tidak merasa bebas dengan adanya Islam, maka saya kira pemahamannya terhadap Islam masih sangat sempit. Kalau kita memahami Islam secara kaffah, justru di sini kita terbebaskan dan tercerahkan. Jadi islam itu sama sekali tidak ada membatasi ruang gerak peempuan. Jika memang ada, dalam ruang apa ? jika memang kita ingin bebas merdeka yang sesuai dengan fitrah, kita sebagai manusia maka kita harus merengkuh Islam itu secara keseluruhan dan harus mempelajari Islam itu sungguh-sungguh.
Kenapa sebagian teman jamaah seakan-akan apatis pada feminis?
Ya, ketika kita bicara soal feminisme, bayangan kita adalah pilihan kebebasan, ya ini banyak hal dan banyak macam. Hal ini boleh jadi selama ini terlalu diperjuangkan oleh wanita itu bersifat kekuasaan (power) jadi mereka ingin mangantusiaskan. Kalau sudah dilihat dari kesan pertamanya saja sudah berbeda, sebenarnya feminisme memperjuangkan nilai-nilai yang manusiawi
dan sebenarnya kata kata feminisme itu bukan milik barat, ya memang dari sana tapi sebenarnya itu milik kita semua. Kita bisa menggunakannya siapa saja bisa menggunakannya. Kita sebagai muslimah kenapa kita harus alergi karena ini memperjuangkan tentang kemanusiaan dan apa salahnya kita menerimanya. Jadi kita juga harus melebarkan cara pandang kita yang sebenarnya kita phobi terhadap suatu istilah dan apa yang tersimpan di dalamnya. Banyak kok, dari teman teman Indonesia juga seperti Ratna Megawangi, dia kan dulu sangat feminis barat. Tapi sekarang dia kembali lagi ke akarnya dan dia berjuang pada garis-garis feminis yang dimasukkan kedalam roh Islamnya, karena ia merasa selama ini arah dia itu ke mana yang telah meninggalkan rumah dan pada akhirnya ia kembali ke rumahnya yang semula ia tinggalkan. Ini terjadi sebab pernah bertemu dengan seorang sufi, yang dengan tenang mengatakan bahwa antara laki laki dan perempuan itu berbeda seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Qur’an, sama seperti halnya antara siang dan malam, orang miskin dan orang kaya dan Islam yang mengatakan itu jadi tidak ada orang itu yang sama rata dan sama rasa. Ya memang harus ada perbedaan. Dan ini tercipta berpasang-pasangan dan ini merupakan sunnatullah. Demikian dialognya yang akhirnya mengembalikan ibu Mega kembali pada ‘rumahnya’.
Bagaimana dengan kepemilikan harta antara laki-laki dan perempuan (suami-istri)?
Bagian perempuan itu satu sepertiga dan itu sepenuhnya milik perempuan, jadi harta itu tidak boleh diambil oleh suami dan tidak ada kewajiban menafkahkannya, jadi sebenarnya pembagian itu sama. Laki-laki mendapatkan warisan lebih besar tetapi ia punya kewajiban untuk menafkahkan semuanya pada keluarganya, uang perempuan itu milik perempuan pribadi. Dalam Islam, kalau ia mau mencari nafkah itu masalah lain lagi, tapi dari uangnya itu ia tidak memiliki kewajiban, jadi uang tersebut murni miliknya. Dalam perceraian perempuan memiliki khulu’ untuk menceraikan suaminya, jika di antara mereka tidak ada kecocokan lagi maka diwajibkan pada istri membayar denda kepada si suami, tapi tidak banyak masyarakat yang mengenal khulu’ kecuali ketika mereka sudah menikah
Kenapa hal ini terjadi? Apa ada pengaruh dari luar?
Mungkin ini pengaruh Bahasa Arab pada Bahasa Indonesia. Bagaimana jika laki-laki punya kewajiban mencari nafkah, dan perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dan ini kejadiannya banyak sekali.
Apa hal ini sudah ada tanggapan dari femenis feminis lain?
Teman teman feminis juga melakukan banyak diskusi tentang ayat mengenai perempuan, kalau saya sendiri berpendapat sebenarnya ketidak puasan itu bukanlah pada Al-Qur’an, tapi pada realita sehari-hari. p adahal Al-Qur’an tidak seperti itu, karena pemahaman yang kurang tentang Al-Qur’an, jadi harus ada pemahaman ulang. Sebab tidak selamanya tafsiran ulama itu benar. Kenapa kita tidak mencoba menafsir ulang yang lebih bisa memecahkan persoalan tersebut.
Abidah El Khaliqy lahir di Jombang pada 1 Maret 1965. Sekolah dasar ditamatkannya di tanah kelahirannya. Se-lanjutnya meneruskan di pesantren khusus perempuan di Pasuruan daerah Bandung, Jawa Barat. Semasa kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta, ia terlibat
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 DIALOG
aktif dalam sebuah organisasi-ekstra kemahasiswaan. Mulai menulis sejak duduk di bangku kelas 2 Tsanawiyah (SMP). Beberapa karyanya sudah banyak diterbitkan, di antaranya buku berupa puisi dan novel; perempuan Berkalung Sorban, Menari di Atas Singgasana, dan Ibuku Laut Berkobar.
Siapa yang menjadi inspirasi dalam tulisan Anda?
Banyak teman curiga bahwa saya terpengaruh oleh Nawal elSaadawi. Ada banyak yang meneliti untuk skripsi, perbandingan, dan lain lain. Dan mengatakan Nawal itu memang menempati satu kesan tersendiri.

Kenapa harus Nawal?
Karena saya suka bahasa yang diungkapkannya. Nawal itu lugas tapi tak terjebak pada vulgarisme, dan jika dilihat dari sastranya juga tinggi, apa yang diceritakannya sangat jujur, karena ia bergelut dalam hal itu. Sebagai konselor, ia sering mendengarkan tentang banyak hal. Sebenarnya apa yang dialami Nawal sangat ekstrim atau tragis, sebab ia tidak diterima oleh feminis Islam dan dimusuhi oleh feminis barat bahkan parahnya ia malah dipenjara. Dan saya kagum dengan kehidupan Nawal. Boleh jadi dikatakan saya memang pengagum Nawal, baik dari fiksi maupun non fiksi. Saya juga kagum dengan kehidupan pribadi Nawal. Selain itu, kita jangan lupa siapa Ibrahin Ai haq, Rabiah al-Adawiah, al-Hallaj, Siti Jenar.
itu?
Mungkin ada pengaruh, jadi kalau pengaruh itu dari pikiranpikiran. Nawal mengungkapkan tapi tidak sengaja, jadi ketika membaca kemudian sangat terkesan, boleh jadi apa yang kita baca merasuk dalam kesadaran internal kita sehingga ketika kita berhujat, mengungkapkan sesuatu apa yang terkesan itu boleh jadi apa keluar, kira-kira begitu, tapi tetap yang saya sampaikan tetap membumi yang berbau budaya kita.
Dari beberapa karya Anda, banyak mengangkat perempuan dalam Islam apa Anda termasuk kategori seorang feminis muslimah?
Memang saya lebih tertarik pada feminisme muslimah karena saya melihat feminisme barat sudah terlalu jauh. Feminisme itu macam-macam. Nawal tidak diterima di feminisme radikal, tapi ada banyak orang mengatakan Nawal termasuk ke dalam feminis radikal. Bagi saya ia tetap seorang feminis.
Sebenarnya ada tidak batasan pergaulan bagi perempuan?
Batasan batasannya dalam Islam terhadap pergaulan baik lakilaki maupun perempuan itu sama. Kenapa Al-Qur’an mengatakan bahwa hendaknya bagi kaum laki-laki menundukkan pandangan, mereka begitu juga dengan perempuan. Jadi bukan dikarenakan laki-laki dan bergaul seenaknya, dan perempuan terbelenggu. Islam
Apakah Nawal berpengaruh besar dalam pemikiran Anda
M. Ali Prasetya
HIMMAH
Di Antara Tumpukan Buku. Abidah berusaha menyebarkan gagasan-gagasan feminisnya lewat berbagai tulisan,
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 DIALOG
/
tidak ada ajaran seperti itu, Islam itu sama, memberikan batasan pada laki-laki dalam sosialisasi masyarakat. Ini tidak diskriminasi, apa perempuan harus dikurung di rumah? Terus laki-laki bebas bergaul, tidak juga kan? Tidak ada batasannya. Dan jika perempuan keluar harus dengan muhrim, itu dilihat dari kondisinya, kemudian batasan berpakaian, khususnya masalah jilbab. Sebenarnya kewajiban atas jilbab itu seperti apa? Dan sebatas apa? Dan bagaimana dengan laki laki? Jadi selama ini yang kita pahami di ayat tersebut adanya kata-kata yang menunjukkan agar dikenal, tapi dikenal seperti apa, atau agar mereka tidak diganggu.

Bagaiman jika pencitraan itu merupakan hasil dari konstruksi yang membekukan perempuan. Sudah pernahkah, sejarah menemukan masa jayanya kepemimpinan perempuan?

Ini tidak jauh jauh dan dekat dengan kita, seperti halnya Margareth Tatcher. Dalam hal ini tergantung bagaiman cara kita memandang suatu persoalan, apakah sesuatu itu dipandang besar atau kecil, jika hal itu berhubungan dengan kekuasaan, apakah seseorang itu dianggap hebat, besar, jika ia hanya seorang pemimpin saja. Atau penguasa saja, tidak kan ? Kalau kita berpikir seperti itu sebagai orang yang punya kehebatan, kecermelangan, kemuliaan itu sebetulnya bisa menjangkau berbagai aspek hanya masalah kekuasaan saja. Jadi kekuasaan itu berhubungan dengan sistim, bagaimana suatu kelompok masyarakat bisa berjalan itu tidak selalu ditentukan dengan kekuasaan jadi kalau kita ingin mengukur perempuan itu dengan kekuasaan tidak ada yang jadi presiden, dan itu artinya tidak ada perempuan yang berjaya, dan hal ini tidak bisa.
Dalam hal ini terjadi kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam posisi sosial?
Kalau menurut saya pernah bahkan sering, jadi biasanya perempuan itu menempati posisi yang sangat bagus dan manusiawi itu biasanya ketika di suatu masyarakat di mana di sana revolusi baru saja dimulai, misalkan pascarevolusi prancis. pas 100 tahun setelah revolusi digencarkan, kondisi perempuan di barat luar biasa, kemudian yang dekat dengan kita, yakni ketika Muhammad penuh dengan kegemilangan, ya seperti halnya adanya Robia’ah Al-Adawiah yang ada pada masa itu. Kebiasaan yang ada ketika revolusi baru saja dimulai, maka perempuan bangkit dan sesuai dengan pepatah, adanya kemajuan pasti adanya kemunduran. Hal
ini mengalami kemunduran dan kemunduran kemudian ada lagi kebangkitan. Roda berputar.
Boleh tahu pengalam mbak Ida ketika berada di pesantren?
Oh dalam masa studi saya di sana justru saya sendiri ingin berontak. Kondisi pesantren baik yang moderen ataupun yang tradisional hampir sama. jika kita mengatakan disana ada diskriminasi terhadap perempuan memang benar dan saya merasakan itu. Walaupun tidak mengerti apa arti kata diskriminasi waktu itu. Saya rasa beragama disebabkan oleh keturunan, dalam perjalanan hidup saya tidak ada pengalaman agama secara menghentak seperti halnya yang dialami oleh mbak Megawangi padahal hal-hal seperti ini saya dambakan. pengalaman saya selama ini biasa-biasa saja. Justru pengalaman agama saya menguat ketika saya mendalami persoalan feminis ini dan ini saya rasakan ketika bersinggungan terhadap keadilan dan terhadap perempuan dan di sini saya bayak terkejut dengan Islam. Dalam hal ini saya merasa seakan-akan baru lahir. Tidak pada persoalan lain
Sejak kapan mbak bersinggungan dengan feminis?
pertama kali saya memfokuskan pandangan saya terhadap feminis ketika saya aktif di HMI. Di sini saya mulai menangkap banyak wacana tentang feminis, dan di sini juga saya mulai menulis tentang feminis, dan juga terlibat dalam pembicaraan teman-teman dan saya merasa cocok.
Tentang kesibukan Anda, bagaimana pendapat dari suami, anak dan keluarga Anda?
Dalam hal ini saya mengenggap sudah ada kesepahaman antara kami berdua, yang jelas ketika jam 1 ini waktu yang tidak boleh
M. Ali Prasetya HIMMAH
Perempuan Berpolitik. Aktivitas yang sama dilakukan oleh kebanyakan kaum laki-laki.
Demonstrasi. Bentuk protes perempuan jika mendapat ketidakadilan.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 DIALOG
Sri Sumarwati: ”Saya Hidup untuk Anak
Oleh FAJAR SAID
Kondisi bangunan itu tampak rapuh, serapuh usianya. Dinding bagian kiri, kanan dan belakang masih men g gunakan gedhek, bambu yang dianyam. Atapnya sudah tak beraturan. Tampak tempat tidur yang jumlahnya dipaksakan, ditambah dengan beberapa kursi dan sederet buku yang tersimpan rapi di sebuah rak kayu yang berfungsi sebagai perpus–takaan. Di sudut ruang tamu ada teve tua, sebagai media informasi dan penghibur penghuninya. Di belakang bangunan itu ter-dapat kandang ayam dan itik. Dan di samping bagian depan terdapat kios yang menyatu dengan bangunan. Itulah kondisi kontrakan panti asuhan Atap Langit yang dikelola Sri Sumarwati.
Bermula pada 1987, Sri Hamim— pang-gilan akrab Sri Sumarwati—sakit keras. Tujuh bulan berada di ICU dengan kondisi penglihatan yang tidak berfungsi. Lumpuh. Kadang sadarkan diri, terkadang tidak. Sri Hamim memiliki harapan, apabila kehidupan berpihak padanya, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Niat itu ia wujudkan dengan mendirikan panti asuhan Atap Langit, yang dikelola secara pribadi mulai tahun 1987, sampai saat ini.

Dengan modal nekad dan keberanian disertai keyakinan bahwa setiap anak memiliki rezeki sendiri-sendiri, Sri Hamim terus berjuang untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan anak asuhnya. Hal ini juga yang membedakan panti Atap Langit dengan panti lainya. ”Kalau panti yang lain kan sudah ada dananya. Semen-tara kami hanya modal nekad,” ung-kapnya.
Berbagai pekerjaan dijalankan bersama anak asuhnya. Mulai dari jualan pakaian, sembako, dan makanan ringan. Di samping itu juga beternak ayam dan itik. Hanya untuk membiayai panti Atap Langit
Anak asuhnya sekarang berjumlah 68 orang. Yang perempuan berjumlah 33 orang, sementara yang laki-laki berjumlah 35 orang. p adahal daya tampung panti hanya untuk sekitar 60 orang. Sisanya tinggal di luar.
”Karena memang di sini tidak ada tempat, ruangan ini entar jadi area tempat tidur,” kata Sri Hamim sambil menunjuk ruang tamu yang dihiasi dengan piagam penghargaan anak asuhnya.
Anak yang ditampung di panti Atap
Langit sangat variatif: anak jalanan, anak kaum dua’fa, anak keluarga broken home dan korban kerusuhan di Maluku. Asalnya pun beragam. Ada yang dari Jakarta, Madura, palembang, Surabaya, Wonogiri dan Maluku. ”Tapi mayoritas anak jalanan dan semuanya bersekolah baik yang tinggal di panti ataupun yang diluar panti.”
”Anak jalanan adalah pemberi ke–hidupan dan mereka perlu dikasihani. Karena sebenarnya mereka ingin hidup layak, tapi tidak diberi kesempatan oleh siapa saja,” kata Sri Hamim yang kerap dipanggil Mama oleh anak asuhnya.
Banyak cara yang dilakukan oleh wanita kelahiran Keparakan, Jogja, ini, untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak jalanan. Sekali lagi, baik mereka yang di panti maupun di luar panti. Dari membuka warung kesehatan di pingir-pingir jalan untuk memberi pelayanan kesehatan kepada mereka yang sakit, sampai mengundang mereka untuk mandi ke rumah, di samping makan bersama dan memberikan pakaian secukupnya. Ini adalah bentuk kepedulian Mama terhadap kaum termarjinalkan.
Kondisi tubuh yang sering sakit-sakitan tidak mengurangi rasa kasih sayang dan perhatian Mama terhadap anak asuhnya.
Mereka merupakan bagian dari hidupnya. Buat Sri Hamim, itu adalah kebahagian tersendiri untuk hidup bersamanya.
”Saya hidup untuk anak-anak, setelah saya pelihara anak-anak, saya merasa bahagia.”
Hamdani, salah satu anak di panti asuhan Atap Langit ini sangat merasakan kasih sayang yang diberikan Sri Hamim terhadapnya. ”Mama itu seperti ibu kandung sendiri,” nilai Hamdani. Di sam-ping itu, terkadang Sri Hamim juga mema-rahi anak asuhnya sebagai bentuk kepe-dulian. ”Kami juga merasakan amarah dari mama, dan kami terima dengan senang hati. Karena kita tahu marahnya orang tua itu hanya di luarnya saja, padahal mungkin di dalam hatinya penuh dengan kasih sa yang,”ungkapnya.
Hamdani berasal dari Maluku Utara. Saat ini ia bersekolah di Sekolah Menegah Umum (SMU) Institut Indonesia 1 Yog yakarta. Sejarah kedatangannya ke panti Atap Langit yaitu pada tahun 1999 kala terjadi kerusuhan berkepanjangan di daerahnya. Ibunya menelpon ke Atap Langit untuk menitipkan Hamdani.
Heri Aswan, anak asuhnya yang lain. Ia berasal dari palembang. Kisahnya bisa sampai ke Atap Langit , bermula pada
Sri Sumarwati. Bekerja keras menghidupi banyak anak jalanan.
Indra Yudhitya / HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
SOSOK
Jalanan...”
waktu berumur enam tahun. Ketika itu ibunya mengajak mencari bapaknya yang bekerja di pulau Jawa. Sesampainya di Stasiun Senin, Jakarta, Heri berpisah dengan ibunya. Akhirnya Heri ikut orang lain. Sungguh malang, ia ‘diperalat’ untuk jadi peminta-minta. Jadi seorang pengemis. Sampai suatu saat, Heri berkenalan dengan Sugeng, seorang anak jalanan yang turut bermain film Daun di Atas Bantal. Film yang bercerita tentang kejahatan terhadap anak-anak jalanan. Sugeng, kala itu, mengajaknya ke Jogjakarta.
Menurut Heri Aswan kasih sayang yang besar yang diberikan Sri Hamim terhadapnya membuatnya merasa Sri Hamim seperti ibu sendiri. ”Mama sudah seperti ibu sendiri,” tegasnya.
Imi patimah, asal Surabaya juga punya penilaian sama dengan yang lainya. ”Mama baik dan sayang sama anak-anak. Sudah seperti keluarga sendiri,” ujarnya.
Bentuk kasih sayang Sri Hamim ter hadap anak asuhnya diwujudkan lewat kepedulianya terhadap masalah pe n didikan. Semua anak asuhnya diseko-lahkan tanpa terkecuali. Tapi, biaya pendidikan yang sangat mahal terkadang bikin wanita ini stres berat dan mem-buatnya sering sakit-sakitan. Tak jarang Spp anak-anak asuhnya telat dibayar. Sementara surat dari sekolah terus ber–datangan. Kadang, itu membuat anak asuhnya tidak boleh masuk sekolah. Sampai ia mampu melunasi. ”Makanya saya sakit, karena kepikiran. Saya kena radang otak. Tidak boleh banyak berpikir. Tapi bagaimana saya tidak sedih. Anak-anak selalu tanya: Mama kapan bayar sekolah?” ungkapnya dengan raut muka sedih.
Berbagai usaha ditempuhnya untuk dapat mencari uang tambahan untuk dapat membayar uang sekolah dan kebutuhan anak asuhnya. Bahkan dengan mengajar menari poco-poco, sekalipun.
Kondisi kesehatannya yang lemah, di–tambah dengan jumlah ginjal yang tidak sempurna, tidak menyurutkan semangat Sri Hamim untuk terus berjuang membiayai Atap Langit
”Saya bener-bener banting tulang. Ginjal saya tinggal satu. Setiap ke kantor saya harus bawa sendok sama serbet
karena kejang,” ujar wanita yang bekerja di BKKBN ini.
Harapan tinggal harapan. Berharap pemerintah belum mau mendengar jerita n -nya. Keinginan untuk memiliki pondok sendiri belum terwujud. Bahkan untuk membayar kontrakan panti pun kesulitan. ”Saya kepingin pemerintah mau mendengar tangisan saya. Kadang saya sampai merinding kalau tidak bisa bayar kontra-kan,” ujarnya.
”Saya berharap pemerintah mau mem–belikan tanah ini, paling tidak. Biar lebih tenang. Tidak setiap tahun saya harus menabung untuk biaya sewa. Biaya itu bisa untuk kesejahteraan anak,” harapnya.
Melihat kesuksesan anak asuhnya yang sudah keluar dari panti adalah kepuasan dan kebanggan tersendiri bagi Sri Hamim. Sudah banyak anak asuhnya yang sudah mandiri dan berkeluarga. Bahkan ada yang sudah mampu membeli tanah.
Berbagai penghargaan telah diperoleh Mama berkat kepeduliannya terhadap anak jalanan. Di tahun 1993, misalnya. Mama mendapat penghargaan sebagai p ekerja Sosial Teladan tingkat nasional. p ada zaman pemerintahan Gus Dur, ia diberi peng-hargaan untuk membina pendidikan anak jalanan. Dan, penghargaan sebagai ibu yang peduli dengan pendidikan pada anak dari presiden Megawati.

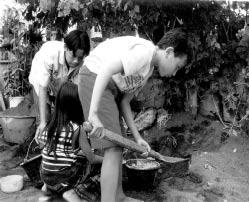 Anak-anak Atap Langit. Memerlukan bantuan demi masa depan. Indra Yudhitya HIMMAH Indra Yudhitya / HIMMAH
Anak-anak Atap Langit. Memerlukan bantuan demi masa depan. Indra Yudhitya HIMMAH Indra Yudhitya / HIMMAH
�� ��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 SOSOK

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 ’rang-orang
Berkisar tiga abad lalu, suku Tengger tersuruk dalam peluh kolonialisme. Mereka memeras keringat demi menambah dan menambal kas negara Belanda yang terkuras akibat pertempuran melawan kerajaan-kerajaan Pribumi. Peta distribusi pun tergelar demi kelancaran garapan pelbagai hasil pertanian. Orang-orang Tengger mulai membuka pintu hubungan dengan ke hidupan luar. Paruh kedua abad ke-20 gejolak politik nasional meradang hingga menjalar ke wilayah ini, dan imbasnya terjadi serangkaian pembunuhan yang tak terpermanai. siapapun mengira hidup seperti itu tinggal menyisakan puing reruntuhan. Na mun, masyarakat Tengger tetap bersikukuh, meski jalannya teramat sukar ditempuh. konon kata ‘tengger’ menyiratkan perihal itu, sebab ia dapat diartikan kokoh, tegap. Orang Tengger adalah orang yang berbudi luhur, jujur dan bijak. Membaca kehidupan kawasan yang membentang ke empat kabupaten di sisi timur Jawa ini —Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang— sama halnya membuka perkamen tua tentang beragam adat dan tradisi leluhur, juga risalah pengorbanan tak kunjung padam. Bagaikan negeri fiktif Macondo dalam novelnya Gabriel Garcia Marquez, One Hundred Years of Solitude, Tengger menangkup perubahan jaman yang selalu datang dan lewat, tak bisa menampiknya tapi gigih untuk terus bersitahan.Akhir Agustus silam, selama lima hari, wartawan HIMMAH SF. Salam dan fotografer Indra Yudhitya, merekam denyut kehidu pan di kawasan Jawa pegunungan ini. simaklah sejumput nekrologinya.

HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 LAPORAN KHUSUS
Tengger
Hidup Damai yang Tahu Bahasa Bintang
Di Tengger, kehidupan seperti gemerisik angin: tenang sekaligus punya daya mengguyahkan.
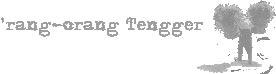
iNimusim kemarau yang terasa menjengahkan di siang Minggu terakhir di penghujung bulan agustus 2003. sinar terik dan desir angin kering bergelayut sepanjang jalan saat Marsai Madrim menyusuri hamparan tanah berpasir nan luas itu. sebagai pegawai polisi hutan (jaga wana) di Taman Nasional Bromo-Tengger-semeru (TN-BTs) di Probolinggo, ia mesti mengambil jalan pintas agar cepat sampai ke rumahnya di kota Malang. kali ini perjalanan pulangnya tidak sendirian: saya dibonceng di atas bangku sepeda motornya. satu sepeda motor tentunya tak cukup menampung tiga orang. karenanya Marsai meminta ban tuan seorang kawannya sesama pegawai di TN-BTs agar ikut mengantarkan.
”kalau yang sudah biasa, nggak capek,” ucap Marsai kepada saya selagi sepeda motornya berjalan di atas tanah bertumpuk pasir tersebut. Saya mendengar dengus nafas berat saat ia mengucapkan hal itu.
saya dan Marsai sedikit terlambat rupanya. Mereka meninggalkan kami jauh di depan. Tampaknya, Marsai hati-hati sekali mengendarai laju motornya. ia tak ingin mengambil resiko berat jika tiba-tiba roda motornya terselip di atas tumpukan pasir ini. Namun, saya dan Marsai sangat menikmati perjalanan menyusuri padang luas penuh tana man adas ini. akhirnya, saya pun sampai di Desa Ngadas rejo, kecamatan Ponjokusumo, Malang. ini desa adalah tempat yang saya tuju, dan Marsai yang mulanya menawari saya agar pergi ke sini.
saya diperkenalkan dengan suyak, berusia 48 tahun. ia pegawai TN-BTs juga, seturut dengan dua orang yang membonceng kami. Bedanya, suyak ditempatkan di desa ujung selatan kota Malang ini.
s elepas berhenti, tak berselang lama Marsai pamit pergi. ia harus meneruskan perjalanan pulangnya ke kota Malang. seorang pegawai yang sama dengan Marsai, yang mengantarkan kawan saya, juga harus balik lagi ke tempat kerjanya. ia akan menyusuri jalan semula yang tadi dilewati. saya mengucapkan terima kasih kepada keduanya.
eMPaT hari yang lalu, saya memasuki wilayah Tengger lewat pintu Probolinggo.
Dari empat kabupaten yang masuk dalam kawasan pegunungan Tegger, jalur inilah yang kerap dipakai oleh para pelancong kebanyakan. selain mudah dan tidak me makan waktu banyak, ongkos naik kendaraan pun sangat murah. Ditambah kondisi lajur jalan raya utama yang baik dan nyaman.
Para pengunjung akan ditarik retribusi karcis saat mobil mulai melewati Desa Ngadisari. Di sinilah pintu gerbang berupa tiang besi yang menutupi badan jalan terpasang. Umumnya tiap kepala dihitung rp.1000. kalau di Pasuruan, mereka membayarnya saat melewati Desa Wonokitri. se dangkan Lumajang di Desa senduro, dan Malang adalah Desa Ngadas rejo. Uang retribusi tersebut adalah salah satu pemasukan TN-BTs
Dari terminal Probolinggo di daerah bawah, angkutan umum itu akan berhenti di Desa Cemoro Lawang. sebelum nya, mengikuti jalur jalan raya dari atas, mobil menyusuri Desa Ngadisari, Wonotoro, lantas Ngadas. Cemoro Lawang inilah yang berbatasan langsung dengan hamparan lautan
pasir Tengger—disebut juga Segara Wedhi—dan merupakan desa paling ujung dari tubir kabupaten Probolinggo. Desa ini berada di ketinggian sekitar 2.000-an di atas permu kaan laut, dan banyak dipadati homestay (rumah inap) dan hotel melati. sehari harga homestay berkisar rp.20.00030.000. Banyak penduduk yang menjadikan rumahnya sebagai homestay. atau kalau tidak, biasanya homestay dijadikan satu tempat atau berdampingan dengan rumah penduduk.
Pengunjung yang ingin menyusuri hamparan lautan pasir umumnya menyewa kuda, atau bagi yang punya cukup uang menaiki hardtop—mobil dengan roda besar. Harga sewa satu kuda berkisar rp.20.000 - 25.000, sedang hardtop antara rp.150.000 - 200.000.
Dari atas tebing tanah dekat deretan bangku kayu di se berang sebuah hotel di dekat kantor TN-BTs, saya menatap padang luas nan putih berpasir di kejauhan. inilah rupanya sejarah Tengger bermula dan terbentuk. Juga disitulah daya tarik Tengger yang banyak menyedot para pelancong untuk ramai-ramai berdatangan: Gunung Tengger.
Di abad purba, kawah pegunungan Tengger pernah meletus, dan konon kini jejaknya tergurat berupa lautan pasir itu; sebuah caldera, barangkali sisa-sisa karena gugur, terpelanting, atau kerucut-kerucut gunung api yang teng gelam ke dalam bumi. Dataran pasir itu sebagian bekas alas kawah gunung berapi Tengger, tingginya kira-kira 2.085 dan 2.120 meter di atas permukaan laut.
Gunung Tengger ini berbentuk seperti kerucut raksasa yang dipotong bagian atasnya, sampai akhirnya terbentuk berupa lingkaran dinding tanah, sangat luas, panjangnya dari Utara ke selatan tak lebih 9 kilometer, dan dari Timur ke Barat sekitar 10 kilometer. Di bagian dindingnya itu teramat curam, dan jalannya kecil menurun sampai ke tanah lapang berpasir tersebut. Di atas lautan pasir itu terpacak kelompok pegunungan yang masih aktif: Gunung Penanjakan, Widodaren Giri, Batok, dan Gunung Bromo.
Bagi orang Tengger, Gunung Bromo laiknya “sang pen guasa jagad” yang telah menciptakan leluhur mereka. ia adalah keramat, sang Hyang Brama, dimana tiap bulan ke-12 dirayakan sebuah ritual bernama Yadnya Kasada, yakni upacara adat yang mengguratkan mitologi asal-usul suku Tengger, nenek-moyang mereka: pasangan rara an teng dan Jaka seger.
Di sepanjang tepi kawah gunung ini pula, para pelancong akan bertumpuk saat pagi buta, dan menyaksikan semburat sinar matahari pagi merekah kali awal di balik bebukitan. kesannya serempak: menakjubkan.
DUa puluh enam tahun lalu, terbilang ada seorang peneliti dari amerika yang datang dan menetap lama di Tengger. i a memasuki Tengger lewat pintu Pasuruan, mencatat kehidupan masyarakat lereng atas lalu menuliskannya, dan jadilah sehimpun buku.
Orang itu dikenal dengan nama Robert W. Hefner. Bu kunya bertajuk The Political Economy of Mountain Java; An Interpretative History, diterjemahkan menjadi Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, oleh salah satu
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
penerbit indonesia.
Hefner, dalam risetnya tentang Tengger, tidak saja cermat soal memetakan kehidupan masyarakat pegunun gan. Namun hasil kajiannya masih menjadi acuan penting mengenai perhelatan politik di daerah Jawa pegunungan bagian Timur pasca-tragedi 1965/1966. Sewaktu Hefner meneliti, Tengger baru lepas satu dekade dari kecamuk peristiwa tersebut, dan pemerintah tengah gencar mela kukan perubahan.
Geger Tengger memotret arus perubahan ekonomi sosial dalam komunitas dataran tinggi pegunungan, dan menjadi laporan tentang etnografi historis. Salah satu bab menjelaskan kondisi pertanian pegunungan sewaktu negara gencar mengembangkan revolusi hijau. Yang lain soal dera jat konsumsi orang-orang dataran tinggi di Pasuruan dan pengaruhnya terhadap ikatan komunal, setelah mengenal modernisasi lewat aparatus desa. Dan satu bab menyentil perkelahian poltik aliran di antara masyarakat dataran rendah yang umumnya beragama islam, dan dataran tinggi yang kerap dicap sebagai “Golongan Partai Komunis”, juga sebagian dari kalangan nasionalis.
Pada akhirnya, tulis Hefner, sebuah komunitas akan menjalin kesadarannya terhadap dunia luar yang lebih luas. Dan dalam hidupnya akan timbul pertanyaan tentang identitas dan masyarakat.
Tengger, saya kira, tak pernah habis dibaca dalam guratan catatan yang demikian, pun hingga saat ini. Dan
itulah soalnya.
Desa Ngadas rejo sangat jauh berbeda dengan desadesa lain yang saya jumpai sewaktu di Probolinggo. Me masukinya seperti menatap daerah yang belum terjamah amat oleh adab yang bernama global. ”aliran listrik,” kata Wardiono, ”mulai masuk pada awal tahun 2000.” Wardiono berusia 47 tahun, orang asli Ngadas rejo. ia kini selaku kepala dusun. ”itupun,” kata Wardiono, ”harus menunggu dari tahun 50-an.”
”Lho, lantas sebelumnya untuk penerangan pakai apa?” tanya saya.
”Pakai accu,” jawabnya. ”atau Diesel sekalian.”
Di dusun ini, hanya ada delapan rT dan satu rW dari 317 kepala keluarga (kk). Jumlah sekolah dasar hanya satu. kalau ada anak yang ingin meneruskan pendidikan nya, mereka mesti ke Tumpang, daerah bawah tepi kota Malang. Guru yang mengajar cuma tiga orang, didatangkan dari bawah. Mereka, umumnya, tidak kerasan mengajar. Penyebabnya, barangkali di Ngadas rejo ini terlalu sepi, jauh dari permukiman penduduk di sekitarnya. Per-kam pungan mengikuti jalur jalan raya. ini berarti warga Ngadas rejo harus ke bawah jika membutuhkan keperluan aneka macam, yang artinya mesti turun ke kota.
Meski di desa-desa lain pada kawasan Tengger, seharihari aktivitas warganya banyak dihabiskan di ladang, namun di sini tampak sangat berbeda. Tak ada angkutan
 Menggendong Rumput. Aktivitas keseharian bagi suku Tengger Cemoro Lawang yang derajat ekonominya rendah.
Menggendong Rumput. Aktivitas keseharian bagi suku Tengger Cemoro Lawang yang derajat ekonominya rendah.
LAPORAN KHUSUS HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
yang menyusuri ruas jalan desa ini. Hanya mobil bak terbuka yang sesekali lewat mengangkuti hasil pertanian penduduk untuk dibawa ke pasar di daerah dataran ren dah, atau mobil milik pribadi. Biasanya untuk angkutan sehari-hari, warga umumnya memakai sepeda motor milik sendiri.
Daerah ini juga kerap dilewati para pendaki yang hendak ke Gunung Semeru. Di sini, bisa sesekali menatap jelas puncak Mahameru, ”tempat berteduhnya para dewa”, begitu orang-orang berkata.
Desa ini pun termasuk dalam kawasan inclave.
Maksudnya sebuah wilayah yang berada di tengah-ten gah kawasan taman nasional, berbatasan langsung dengan deretan hutan cagar alam kepunyaan Perhutani. Inclave terdapat juga di Desa ranupane, kecamatan senduro, Lumajang.

”Harapan kami itu, dikirim guru, dibangun sekolah,” ujar Wardiono kepada saya di rumahnya. ”kami sering usul, ndak berhasil-hasil. Minta bantuan, minta dibenahi.”
suyak yang sedari awal ikut berbincang pun mengiyakan. ia memiliki anak laki-laki yang bersekolah di Tumpang. Jika anaknya ingin pulang ke rumah, ia yang antar-jemput. ”anak saya biasanya kalau pulang akhir bulan, Mas,” kata suyak. anaknya saat itu kebetulan tengah pulang.
”saya bukan orang sini,” ucap suyak, ”tapi sudah lama di sini, mendapatkan istri orang sini. Yah, sudah jadi ma syarakat sinilah.”
Perbincangan di tempat kediaman Wardiono itu disela suguhan makanan. sejurus suyak berucap, ”kalau ndak
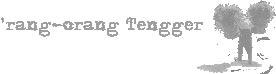
mau dimakan berarti ndak mau rejeki.”
”Oh, ya?” Saya setengah terkejut. ”Ya,” terang Suyak, ”di sini seperti itu, kebiasaan warga. kalau ndak dimakan, Mas-nya main lagi ke sini, tuan rumah ndak bakalan lagi menawari.”
”Ya. Itu sudah pasti.” Wardiono ikut menegaskan. kami berempat tersenyum lunak.
seNJa itu, di hari yang sama, saya berkenalan dengan Marsai Madrim. ia menawari saya bermalam di sebuah rumah milik jawatan perhutani. rumah itu ia pakai sebagai tempat tidur dan istirahat selepas seharian bekerja. ia dan Bustang menempati rumah yang terpancang di belakang kantor TN-BT s Probolinggo di atas tanah yang sedikit berundak itu. Bustang bekerja di tempat yang sama dengan Marsai. ia selaku koordinator urusan umum pada seksi i saya dipersilahkan duduk-duduk di depan bangsal di tempat kerjanya. Badan masih merasa kelelahan rupanya. separuh hari itu saya turun ke Desa Ngadisari, bertemu dengan kepala desanya, supoyo. Tak jauh amat sebenarnya. Barangkali tak lebih dari tiga kilometer dari tempat pember hentian angkutan umum Cemoro Lawang. Hanya saja mobil, selaku angkutan keseharian warga sini, mesti menunggu lama penumpang biar terisi penuh. Hingga tentunya waktu terbuang dengan hanya duduk diam di bangku mobil. saya turun tepat di depan kantor kepala desa. Waktu itu, di pelataran tanah lapang, warga tengah bermain bola voli. Mereka sedang merayakan Tujuh Belas Agustus-an. supoyo berada di antara warganya yang menyaksikan di
Menjual Rumput Pakan Kuda. Salah satu bentuk mencari nafkah di tengah himpitan dan gelombang modernitas.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
tepi lapangan. saya memperkenalkan diri. ia mengajak ke sebuah ruangan.
rupanya, perayaan kemerdekaan bergema juga di sini, persis laiknya di daerah-daerah lain di dataran rendah.
”anda bawa surat ijin tidak?” tanya supoyo. ”Maksud Bapak surat izin dari lembaga kami?” Saya lantas menun jukkan tanda pengenal diri dari institusi, dan menyodorkan bukti majalah. ”Bukan ini,” kata supoyo, ”Tapi dari pemer intah daerah kabupaten Probolinggo.”
Supoyo melanjutkan, ”Maaf Mas, ini sudah ketentuan pihak kabupaten dengan desa di sini. Yang lain pun seperti itu.”
”Maksud yang lain?”
”Yah, yang mau penelitian.”
s aya menerangkan bahwa hendak wawancara, dan mau bercakap terlebih dahulu dengannya, sebelum untuk beberapa hari, sosok kami berdua akan kerap terlihat di lintasan jalanan desa, bertemu dan berbicang dengan warga Tengger.
”Oh, itu ndak apa,” kata supoyo, ”sama warga ndak apaapa, boleh. Tapi kalau wawancara saya, saya ndak kasih jaminan. Ini sudah keputusan Pemda, Mas. Maaf saja. Nanti beda lagi suara di sini dengan yang di sana.”
Perdebatan kecil itu berlangsung lama.
Pendapat saya, dalam beberapa hal, tidak sejalan dengan ucapan dan anjuran kepala desa. keputusannya tetap, yakni mesti membawa surat ijin dari pemerintah daerah (pemda) kabupaten Probolinggo. Dari penjelasan supoyo, setidaknya saya menimang pertanyaan, apakah pekerjaan wartawan sekaligus juga dibilang sebagai sebuah tindak penelitian?
Marsai telah mempersilahkan ruangan bagi tempat tidur kami.
”ambil saja kasurnya,” anjur Marsai. ia menunjuk letak kasur yang terpacak berdiri di tepi ujung ruang tengah. saya lantas membenahi kasur yang memang tergeletak tak terpakai.
saya lelap. Udara malam bertambah dingin, seakan menyusup ke sela-sela selimut, menusuk pori-pori kulit tubuh.
HEFNER menyusun Geger Tengger selama hampir dela pan tahun. kali awal di tahun 1977, lalu 1978 sampai 1980. ia kemudian datang lagi di tahun 1985.
Dalam catatan akhirnya, Hefner banyak bercerita men genai pengalamannya bertemu dengan orang-orang Tengger, khususnya menyangkut pertumpahan darah 1965-1966.
Pada awalnya, tulis Hefner, warga ketakutan dan eng gan berbicara. Selain karena faktor kemampuan verbal orang-orang Jawa pegunungan yang tidak suka banyak bicara, juga oleh sebab pandangan warga Tengger, bahwa tak baik sebenarnya jika kita berbincang kelewat pintar dengan orang-orang yang sudah tua usianya. Meski, saat itu, pendidikan dan transportasi telah membawa perubahan yang besar.
Di tahun 1985, Hefner setengah tergeragap. Sebabnya, warga sudah berani berterus terang mengenai keterkaitan mereka terhadap peristiwa tersebut.
Pertemuan Hefner dengan tiga narasumber kunci, yang berbeda latar belakang, dan saling bertaut, membawanya pada serangkaian kejadian dalam kebetulan yang aneh. Tiga orang itu adalah, satu dari petani lereng atas yang aktif pada golongan kiri Pesindo (Persatuan indonesia), yang lain dari dataran rendah yang punya peran sentral dalam kegiatan Partai Nasionalis di dataran tinggi, dan satunya penduduk desa lereng tengah yang jadi anggota Nahdlatul Ulama.
Bagi Hefner, tak mudah memang menyusun sejarah lisan dari labirin ingatan masyarakat Tengger yang dikatup
rapat-rapat. Baginya, etnografi historis tidak sebatas per masalahan keterbukaan seseorang menghargai orang lain. Namun, tulis Hefner, juga perihal pemilihan narasumber, perumusan pertanyaan dan sebuah identitas seseorang dalam masyarakat.
ia berharap, sejarah yang telah ditulisnya dapat berbi cara soal kebenaran dari dua kutub yang berlainan wajah. Di akhir tulisannya, Hefner tak mampu menahan rasa harunya sewaktu menghadapi pelbagai pengakuan yang ia dengar dan rasakan. Kadang Hefner lukiskan sebagai kekaguman tak terperi, kadangkala sebuah kesedihan yang tak terberi.
SAYA mesti ke kantor Pemda Probolinggo. Ini memang jauh dari rencana semula. Tak apa, pikirku, setidaknya ada bukti yang menegaskan apakah pernyataan supoyo benar ataukah tidak. Tentunya, bukan soal siapa yang benar, tapi lepas dari kategori itu, ada sikap yang dapat dirangkum dari tiap jajaran birokrat pemerintahan tentang bagaimana mer eka memandang suku Tengger. apakah perlakuan mereka terhadap orang-orang Tengger ini beda dengan masyarakat umum? Lantas jika memang beda, dimana kesan beda itu? apakah karena keunikan suku Tengger lalu para aparatus pemerintah ini ramai-ramai menjualnya menjadi komoditas pariwisata? atau tidak sebatas itu, artinya memang diperha tikan saksama kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat Jawa pegunungan ini? sebuah masyarakat yang masih erat jalinan komu nalnya, entah sosial maupun kultural, adalah himpunan orang per orang yang secara sadar ataupun tidak toh akan membuka pintu lebar-lebar terhadap kehidupan luar. se bab boleh dikatakan mereka nantinya menjadi bagian dari masyarakat dunia. ini tentunya soal waktu, juga akses. Terlebih Tengger adalah wilayah yang memiliki keterbatasan demografis. Masalah transportasi acapkali menjadi kendala. Namun, dalam dua dekade terakhir, persoalan itu sudah tak berbekas di hampir keseluruhan wilayah Tengger. Tentunya, ini mendatangkan dampak yang tak hanya menyenangkan, tapi juga menggelisahkan.
saat pengaruh dari luar itu meretas ke hampir tiap pelosok suatu wilayah, boleh jadi saai itulah resiko hadir. ketimpangan dan keretakkan tak terhindarkan.
Di awal abad ke 19, wilayah Tapal kuda Jawa Timur menjadi tempat tujuan migrasi besar-besaran masyarakat Madura. Di peta pulau Jawa, Pasuruan dan Probolinggo masuk wilayah Tapal kuda itu. Dikatakan Tapal kuda, sebabnya memang deretan wilayah itu melengkung seperti ladam. Maka, bisa jadi itulah salah satu pengaruh luar yang masuk ke Tengger. Namun, peran kolonial Belanda di awal abad ke 18 yang membuka lahan-lahan pertanian di lereng atas Tengger pun tak boleh dikesampingkan. ini seperti membedah bagaimana perubahan dan pengaruh luar tiap masa dan kurun waktu tertentu berkelindan dan berpilin di tanah Jawa pegunungan ini, secara sinambung maupun terputus.
Di Cemoro Lawang, kini banyak warga Madura yang menetap selaku pedagang dan penjual jasa. ini tentunya berpengaruh terhadap pola konsumsi dan sosial masyarakatnya. Orang Tengger mencoba beradaptasi dengan gejala kehidupan luar yang menelingkupinya. Teorema yang kuat adalah pihak yang menang menjadi penanda dalam struktur ini. Yang jadi soal, bagaimana mereka mencerap kenyataan itu lantas bergerak dan keluar dari himpitan dan bertahan. Mengenaskan barangkali. i ni bukti bahwa masyarakat dengan tradisi leluhur yang kental memiliki persoalan yang kompleks. Tidak semata masalah ekonomi atau kepentingan kelas, tapi dimensi kultural dan sosial pun merupakan jejar
LAPORAN KHUSUS HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
ing nyata yang tak boleh luput dari perhatian.
SETIBANYA di depan gedung Pemda Probolinggo, saya lantas bertemu dengan seorang pegawai humasnya, sug iarto. katanya, untuk sekadar meliput tak perlu surat ijin. ”kalau untuk penelitian itu harus, kan nanti tinggalnya lama di sana,” ujar sugiarto. ”saya sering memberikan reko mendasi ijin sama mahasiswa-mahasiswa,” lanjut sugiarto, “tapi jika mau penelitian saja.”
saya pun lantas pergi.
sesampai di Cemoro Lawang, saya berkenalan dengan senewo di dalam ruangan Taman Nasional. ia bekerja di TNBTs selaku polisi hutan, asli suku Tengger, asal Ngadisari. Usianya, saya taksir, tak lebih dari 40-an, punya anak dua, istrinya bukan asli Tengger.
”Dia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan lebih ba gus daripada saya, ha...ha...,” ujar senewo, sembari tertawa tipis, mengacu pada istrinya.
”Waktu saya habis digunakan untuk mengabdi di kehu tanan,” aku senewo. ”Tapi, seperti warga masyarakat yang sama, saya juga melakukan kewajiban-kewajiban saya di desa. Diantaranya, ikut menjaga siskamling, gotong-royong. Juga melengkapi kewajiban iuran pada desa.”
”sebulan berapa iurannya?” tanya saya.
”5.000 rupiah. saya kira itu.”
”Punya tanah?”
”Tetap punya tanah,” jelas senewo. ”Jadi disini itu mer eka punya tanah garapan, sejelek apapun punya tanah.”
Ucapan senewo ini mempertegas perkataan yang dilontarkan seorang temannya dari polisi hutan, bernama se mangat, usia 45 tahun, asli Tengger juga. ia berkata bahwa warga Tengger itu memiliki pandangan tersendiri kalau soal tanah. ”Mereka,” kata Semangat, “tak berani menjual tanah sembarangan.”
”sudah turun-temurun,” semangat menegaskan.
Di akhir perbincangannya, senewo berharap mengenai kedua anaknya. “Jadi sebelum mendapatkan ijazah SLTP, dia tidak diperkenankan untuk kawin dulu.”
”syukur kalau bisa melanjutkan ke tingkat atas (sMUred),” tandas senewo.
saya lalu berbenah. Malam kian merapat.
Oleh Marsai dan Bustang, saya diberi lima lembar kertas mengenai TN-BTs. Pada bagian Permasalahan Prioritas, di perbedaan persepsi antara pemkab Probolinggo dengan pegawai TN-BTS, Marsai membubuhkan catatan. Yang dibutuhkan di Taman Nasional, tulis Marsai, bukan tenaga penarik retribusi karcis, melainkan petugas kebersihan.
Hasil penarikan retribusi itu, dari para pengunjung yang hendak ke Bromo maupun semeru, memberikan pendapatan ke pelbagai institusi. Data jumlah pengunjung dan penerimaan retribusi setiap tahun selalu naik. Di tahun 2002 saja, uang hasil retribusi sampai rp.250.590.000 dari 149.921 pengunjung dalam negeri dan 5.925 wisatawan as ing. Hasil penerimaan ini lalu dicacah, 40% untuk tiap-tiap jawatan TN-BTs, dan 20-30% bagi pemerintah propinsi, si sanya diperuntukkan ke Departemen kehutanan. ini sejalan sejak terbitnya sk. Menhut No.878/kpts-ii/1992 tentang Pembagian Penerimaan karcis Masuk.
Untuk warga Tengger?
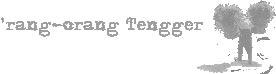
Bagi sebagian orang yang cukup mampu ekonominya, kehadiran TN-BTs bisa menambah pendapatan, semisal usaha jasa rumah inap atau menarik hardtop atau kuda ter untuk para pengunjung. Meski, sebetulnya, kini usaha jasa tersebut lebih banyak dikelola oleh orang-orang dari daerah bawah. Bagi lainnya, yang rendah tingkat ekonominya, terkadang sebagai penyedia rumput untuk makanan kuda. rumput yang mereka jual dalam dua keranjang penuh itu
seharga rp.10.000.
sekali waktu, saya pernah bertemu dengan seorang pengemudi truk. ia kerap menggunakan truk pribadinya itu di saat mengantarkan hasil pertanian para petani Teng ger. kubis, kentang, bawang daun, adalah hasil panen yang mesti ia bawa ke pasar di daerah dataran rendah. ia bernama Martoyo, usianya 54 tahun, memiliki empat anak dan delapan cucu.
saya mengenalnya ketika ia membawa saya dari persim pangan pintu Ngadisari setelah, malam sekitar pukul tujuh, saya tak mendapatkan angkutan umum lagi. saat itu saya baru saja dari desa Ngadas untuk bertemu Mudjono.
Mudjono adalah salah seorang kepala dukun adat yang cukup dihormati sekawasan Tengger.
SUYAK telah beranjak dari tempat duduknya. Saya pamit pergi. Wardiono memberi salam perpisahan. ”Hati-hati di jalan,” Wardiono berucap. saya mengiyakan.
selepas diantar suyak, saya berhenti di depan mobil bak terbuka yang tengah dimuati tumpukan berkarungkarung kubis.
sembari menunggu mobil penuh muatan kubis, saya duduk sejenak di atas tanah yang agak berundak.
setelah temannya selesai mengangkuti kubis ke dalam lambung mobilnya, si pengemudi itu lantas menyuruh saya naik dalam pick up-nya. Temannya duduk di belakang, di atas tumpukan kubis. Belum lama berjalan, mobil berhenti lagi. rupanya, masih ada berkarung-karung kubis di depan kanan jalan yang harus diangkuti. seorang perempuan yang kami taksir sebagai pemilik kubis itu meminta pengemudi mengangkut hasil pertaniannya. Padahal, sepertinya lam bung mobil itu sudah tak memungkinkan lagi menambah muatan.
”Besok saja,” anjur si pengemudi, ”sudah ndak bisa muat.” Pengemudi itu berkata dalam logat Jawa Timur-an yang kental. saya lihat wajah perempuan separuh baya itu sedikit muram.
Mobil lalu berjalan lagi. Teman si pengemudi lantas naik di depan, di samping saya. Dua bangku mobil diisi empat orang. kami agak berdesak-desakkan.
si pengemudi ternyata saudara dekat Wardiono. Mer eka berdua, pengemudi dan temannya, adalah orang asli Ngadas rejo.
Mobil kemudian melaju amat perlahan di ruas jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Di luar, hujan turun amat rinai.
sepanjang perjalanan pulang itu, saya lalu merenungkan larikan-larikan setitik pertemuan dengan beberapa warga Tengger.
setelah melewati jarak yang cukup jauh, mobil akhirnya menyusuri ruas jalan sebuah Desa bernama Gubuk Klakah yang kali pertama ditemui selepas dari Ngadas rejo. Di de pan jalan sedang ada perayaan kemerdekaan. Orang-orang berhamburan dan memadati badan jalan. Mobil sesekali berhenti. Bersamaan laju mobil yang tersendat-sendat, saya menyaksikan suasana meriah dari arak-arakan pesta per ingatan kemerdekaan itu.
ingatan saya lantas melebar pada orang-orang Tengger lereng atas. saya menimbang, ini perayaan tak jauh beda dengan suasana Tujuh Belas agustus-an orang-orang Teng ger di Desa Ngadisari.
apa makna perayaan kemerdekaan bagi orang-orang Tengger, yang umumnya telah berganti usia dan berbeda ja mannya ini? sebuah perayaan yang bagi saya tak semuanya tak terlepas dari peristiwa 1965-1966. setelah hampir tiga puluh tujuh tahun berlalu, apakah mereka mengetahui kehidupan orang-orang terdahulu yang telah lama menetap
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Petani Tengger Lereng Atas

Seharian bekerja tanpa membedakan peran laki-laki dan perempuan.
di Tengger, sebelum mereka lahir, mengenai pertaliannya terhadap petistiwa itu? ataukah yang menguras pikiran mereka kini sepenuhnya pada persoalan mencari nafkah? seperti si pengemudi dan temannya ini yang mengantar kan ratusan kubis dari para petani Ngadas rejo ke pasar Tumpang?
karena, bagi saya, ternyata hidup menjadi diri sendiri tidaklah mudah, terlebih saat pergaulan menjadi sangat terbuka dan jalinan komunikasi merambah ke segala arah termasuk kawasan Tengger yang terpencil sekalipun, seperti yang pernah ditulis oleh Hefner dalam kesimpulan risetnya itu.
saya beranggapan bahwa hidup mereka seakan hidup yang tahu bahasa bintang, sebab yang mereka kerjakan tak lain adalah sebentuk pamrih. setidaknya, ratusan kubis itu telah menjadi menu makanan keseharian para penduduk dataran rendah.
Di luar kaca mobil, arak-arakan semakin meriah. anakanak mengecat badannya yang setengah telanjang, para remajanya bernyanyi di atas panggung terbuka yang berdiri di tepi kanan jalan, dan pelbagai spanduk berisi ucapan ke merdekaan dipasang berjejer sepanjang kiri-kanan jalan.
ruas jalan yang sempit ini semakin terasa sesak dan terlihat padat.
MUDJONO mempersilahkan saya duduk di kursi ruang tamu di rumahnya yang cukup luas. Baginya, warga Tengger mesti mengetahui dan melestarikan pelbagai ritual upacara adat dan budaya nenek-moyangnya itu. ia berpendapat, pemuda Tengger harus diberi pengertian dan pengetahuan tentang betapa pentingnya upacara adat bagi keber-lang sungan hidup suku Tengger. Dalam beberapa kesempatan, Mudjono bahkan kerap memberikan pen-jelasan langsung kepada anak-anak muda Tengger.
”kasada itu paling dinanti-nantikan,” ucap Mudjono, mengacu pada upacara adat yang dirayakan tiap bulan ke-12 sewaktu purnama menurut hitungan kalender suku Tengger itu. Di tahun 2003 lalu, Perayaan kasada jatuh pada bulan Oktober dalam hitungan kalender nasional. Yadnya kasada sendiri, ungkap Mudjono, pada dasarnya perayaan
untuk menerangkan sejarah masyarakat Tengger.
”Biasanya sebelum kasada para kepala desa kumpul Mas. saya juga ikut,” jelas Mudjono.
Hampir dua jam itu saya berbincang dengannya. saat hari kian beranjak senja, saya pun lantas pamit pergi. Pada malam terakhir di Cemoro Lawang, Marsai menawari saya untuk ikut perjalanan pulangnya ke Malang pada besok paginya. ia berencana menuju tempat tinggalnya lewat jalan pintas melalui lautan pasir pegunungan Tengger. katanya, saya akan bertemu dan melihat warga Tengger yang masih asli. saya menjelaskan bahwa tujuan kami bukan untuk mencari daerah yang seperti itu, tapi melihat kondisi suku Tengger di saat sekarang, apapun rupanya. kami sepakat.
MOBiL berhenti. Menepi ke pinggir sisi kiri badan jalan. kedua mata saya terlihat sayu dan mengantuk. saya dibangunkan oleh pengemudinya. Jam menunjukkan pukul lima sore. Pengemudi itu berkata, ”sudah sampai, Mas.”
”Tumpang ya?” tanggap saya.
”Ya,” jawabnya.
”Nanti mas jalan ke arah sana, lurus aja, ketemu termi nalnya,” ujar si pengemudi, seraya telunjuk tangan kanan nya diarahkan ke jalan raya yang melebar bersilangan, yang tepat berada di samping kanan mobil.
saya lantas sigap memberikan upah tumpangan. Dia menerimanya, kemudian berucap dengan senyum simpul, ”terima kasih, Mas.”
”sama-sama,” ucap saya, ”terima kasih juga.”
Mereka menutup kembali pintunya. Mesin dihidupkan. kepala pengemudi dijulurkan ke luar kaca mobil, sejurus ia menoleh ke belakang, takut ada mobil yang melintas. Teman satunya berteriak, ”terus.., terus..., yo...” Mata pengemudi kini sepenuhnya diarahkan ke depan jalan, duduk di be lakang setir mobil. sebelum pergi, mereka berpaling, lalu berucap penuh nada harap, ”hati-hati yah...”
saya jawab dengan anggukan kepala. Bibir saya melepas senyum lugas.
Mobil pun deras melaju.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Dan Leluhur pun Mengeja Wak-
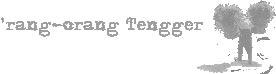
Ritus perayaan adat, artefak-artefak tua dan jejak-jejak ziarah agama membentuk silang kebudayaan yang saling taut dan berliku.
sYAHDAN , di tubir abad ke-15 pada akhir masa keruntuhan kerajaan Majapahit, tersebutlah seorang dara bernama rara anteng yang diperintahkan mencari sebuah tempat aman. Putri keturunan raja terakhir Majapa hit Brawijaya V dari rahim Permaisuri Padmi ini pun lantas pergi bersama para punggawanya. Di Desa Penanjakan mereka menetap.
Tepat dengan amuk kemunduran Majapahit itu situasi kediri pun mengalami keguncangan yang tiada menentu. Jaka seger, seorang putra Brahmana, kemudian mengembara. Seraya mencari pamannya yang tinggal di dekat Gu nung Bromo, ia pun sampai ke Desa keduwung.
rara anteng dan Jaka seger lalu bertemu dalam satu pangkuan tangan seorang pendeta bernama resi Dadap Putih, yang berasal sekitar Majapahit; Jaka seger diangkat sebagai muridnya dan rara anteng menjadi anak angkat. Oleh induk semangnya, keduanya lantas disuruh menikah. Jaka seger kemudian dinobatkan sebagai raja bergelar Purba Wasesa Mangkurat ing Tengger atau penguasa Teng ger yang budiman.
Bertahun-tahun lamanya mereka belum dikaruniai seorang anak pun. sepasang suami istri itu lalu berlaku tapa. Mereka rela berjanji mengorbankan salah seorang anaknya asalkan permohonannya didengar oleh Penguasa Bromo. kedua pasangan itu lantas dikarunia 25 putra; seorang bungsu diberi nama raden kusuma.
sampai tibalah waktunya untuk menepati janji itu. Den gan hati yang terkatup rapat mereka merasa begitu berat mengorbankan anak bungsunya itu. Disembunyikanlah raden kusuma. kebahagiaan yang tenang sedari lalu kini terusik. konon, sang Hyang Bromo kemudian murka dan menyemburkan lava merah dari perutnya seakan bumi saat itu tengah sekarat. akhirnya, raden kusuma pun hilang dan terserap ke kawah Gunung Bromo.
Dalam gemuruh suara tanpa rupa, raden kusuma ber pesan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. ia berkata bahwa setiap bulan kasada (bulan kedua belas dalam hitun gan kalender Tengger) mereka harus menyajikan sebagian hasil bumi ke kawah Gunung Bromo demi sekuntum tanda tabik atas kemurahan sang Hyang Widi.
Begitulah. Legenda tersebut setiap tahun lantas diceri takan kembali menjelma sebuah pementasan sendratari di atas sanggar terbuka di Desa Ngadisari dalam serangkain altar persembahan upacara adat Yadnya Kasada. Sebu tan Tengger sendiri, menurut sebagian orang yang mem percayainya, berasal dari gabungan nama terakhir kedua pasangan tersebut.

”Masyarakat Tengger percaya pada bulan kasada itu kurbannya Dewa kusuma,” demikian ucap Mudjono kepada saya sewaktu di rumahnya.
Perayaan Yadnya Kasada ini diikuti oleh para dukun dan masyarakat Tengger dari empat penjuru kabupaten. Berpusat di Desa Ngadisari, mereka lantas menuju pura agung di kaki utara Gunung Batok di atas hamparan lautan pasir. Para dukun dan masyarakat Tengger yang mengikuti prosesi adat ini tumpah ruah menjadi satu dengan ratusan orang dari berbagai wilayah yang menyaksikannya. selepas tengah malam, para dukun yang diwajibkan memakai selem pang sebesar setagen itu mengucapkan mantra di depan Prasen, yakni sebuah tempat air suci yang disebut Tirta Pawitra, dan prapen yaitu tempat membakar kemenyan.
Di atas dinding prasen tersebut tergurat lukisan beragam dewa dan lambang sodiak.
sembari mendaraskan doa kepada sang Hyang Bromo, dukun memercikkan air suci itu ke aneka sesajen yang dibawa oleh para pelabuh. Orang Tengger yang melarung bermacam sesajen adalah orang-orang yang kadung berjanji dan berikrar sesudah harapannya terpenuhi laiknya leluhur mereka. Kala fajar mulai merekah di balik bebukitan, saat itulah mereka mendaki dan membuang sesaji ke dalam kawah Gunung Bromo. Usai prosesi, warga mengadakan kenduri di masing-masing desa.
Mudjono menjelaskan kepada saya bahwa tak sebatas Yadnya Kasada saja yang dirayakan dalam laku ritual adat Tengger. ada banyak upacara adat lainnya yang seakan sudah menjadi bagian keseharian hidup warga Tengger. Perayaan itu biasanya mengikuti siklus kehidupan manusia: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Beragam pemujaan atau pujan yang mengatur tata perilaku suku Tengger pun terhampar. Pujan-pujan itu adalah kapat (bulan ke-4), kapitu, kawolu, dan kasanga. ”itu dirayakan di rumahnya kepala desa,” ucap Mudjono mengacu tempat perayaan pujan.
Bahkan terdapat pula upacara ruwat. Perayaan adat ini dilakukan jika dalam suatu keluarga ada orangtua me miliki tiga anak yang satu laki-laki dan dua perempuan, begitupun sebaliknya. Bila mempunyai anak lima laki-laki atau perempuan semua maka harus diruwat juga. ruwat desa bisa dilaksanakan jika terjadi suatu peristiwa alam seperti kemarau panjang, naiknya suhu panas Gunung Bromo, atau hasil pertanian yang sedikit. intinya sama yakni memberikan keselamatan kepada tiap masyarakat
Bangunan Pura Tengger. Jejak peninggalan agama leluhur yang masih terpelihara.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Tengger di tiap desa yang ditempatinya. ”Upacara yang wajib dilaksanakan oleh perorangan adalah saat perkawinan,” tandas Mudjono.
karo, Unan-unan, entas-entas merupakan ritual adat bersama suku Tengger seperti Yadnya Kasada, bedanya dirayakan di tiap-tiap desa. karo adalah upacara terbesar bagi masyarakat Tengger seperti Hari raya idul Fitri bagi umat islam, dilaksanakan sewatu bulan kedua saat tanggal tujuh dan sebagai penghormatan kepada ne nek-moyang yang telah meninggal baik perempan maupun laki-laki. sedang Unan-unan adalah peray aan yang mengabdikan sepenuhnya pada pe r hit u ngan penanggalan Tengger. karena itu sistem kalender di Tengger sangat jauh dari batasan aturan konvensional.
Perhitungannya begini: setiap dua bulan, kalender berkurang satu hari. Jika satu tahun, enam hari yang berkurang. Nah, jangka lima tahun berarti sudah satu bu lan. ”Maka itu,” ucap Mudjono, ”di laksanakanlah upacara Unan-unan sebagai p e nye m purnaan bulan. Jadi pada waktu lima tahun itu di sempurnakan kembali.”
Pelbagai macam ritual adat terse but mengandung makna tertentu, tapi sejatinya berakar sama yakni meresap nilai-nilai yang ditelurkan para leluhur. Untuk soal itu, Mud jono memiliki selarik pemahaman. ”Masyarakat Tengger masih mengenal apa yang dinamakan walat.”
Walat dapat pula dikatakan hukum karma atau kar mapala atau hukum perbuatan. ini suatu pengertian yang kerap disandingkan dalam ajaran agama Hindu atau Budha. apakah masyarakat suku Tengger beragama Hindu ataukah Budha? Tak gampang dan tak sesederhana menjawabnya. kadang identitas agama Tengger acapkali berujung soal pelik. Mudjono punya pengalaman dan cerita menarik dalam soal ini.
saat itu—Mudjono lupa ketika saya tanya tanggal, bu lan dan tahunnya—ia diundang di suatu pertemuan antar pemuka agama Hindu. Di sela acara, terdapat seorang tokoh dari Bali yang bulat mengusulkan adat Bali masuk ke dalam aktivitas keagamaan Tengger. Kontan, ia tegas menolak. Mudjono lantas balik bertanya. ”saya tanya, sekarang kalau budaya dan adat masyarakat Tengger dari Bali, buktinya mana? saya gitukan,” kata Mudjono kepada saya, mengenai ucapannya terhadap orang tersebut di pertemuan itu. ”saya ndak mau, seandainya apa yah adat di Tengger sini mau dirombak, dihilangkan. saya ndak mau.”
saya lalu bertanya kepada Mudjono kenapa sebabnya ia berkata seperti itu, dan apa yang membuat Tengger begitu berbeda secara essensial dengan Bali. ”karena apa? ini sudah peninggalan dari nenek-moyang saya, leluhur saya. Jadi misalnya ada orang bilang Tengger akan di-Bali-kan, saya menolak. saya tidak berani untuk mengubah sesaji di Tengger. kami tetap melaksanakan adat yang telah diting galkan oleh leluhur dan yang diwariskan.”
”Di Bali mengenal kasta-kasta, di sini lain,” tandas nya.
Mudjono melanjutkan, ”gini yah, adat di Tengger kalau dari segi mantra, dukun dan peralatannya, bukan dari Bali.
soalnya, masyarakat Tengger sebelum mengenal agama Hindu (Bali- red ), sudah melaksanakan ajaran-ajaran agama yang telah diwariskan oleh para leluhur. Betul kalau sumbernya dari kitab Weda, namun pelaksanaannya apa yang telah dilaksanakan nenek-moyang, yah itulah yang diteruskan.”
Padahal saat pertemuan itu, hingga sekarang, Mud jono adalah ketua Parisada Hindu Dharma kabupaten Pro bolinggo. Lelaki yang akrab disapa Pak Mudjok ini seakan tak mempersoalkan identitas jabatan dari suatu agama resmi pemerintah. Dalam lembar biodata yang saya minta untuk diisi olehnya, ia cukup membubuhkan ‘petani’ sebagai pekerjaannya dengan jabatan selaku ‘dukun’.
Tiga puluh tujuh dukun yang tersebar di empat kabu paten kawasan Tengger tidaklah mengacu pengertian dukun oleh orang-orang Jawa di dataran rendah. Bukan seperti santet, dukun bayi atau dukun pengasihan, melainkan bisa disamakan sebagai pemimpin sebuah agama: seorang pastur, pendeta, biksu, romo, atau kyai sekalipun. karena perihal ini pula, mengapa Mudjono begitu tegas menolak jika terdapat orang yang menyamakan Tengger serupa Bali.
Dukun di Tengger seperti sekelompok penjaga tra disi. Mereka seakan menuntun masyarakat Tengger untuk mengeja jejak-jejak leluhur terdulu.
”Tugas dukun Tengger seperti apa?” tanya saya.
Mudjono menjawab, ”dukun di Tengger bukan untuk mengobati orang yang sakit, tapi melaksanakan upacaraupacara adat.” setengah menandaskan, ia melanjutkan, ”memang tidak saya perbolehkan kalau orang Tengger itu (jadi dukun klenik-red), karena nanti mantra-mantra untuk upacara adat itu akan kecampuran dari mantra lain-lain itu. Nanti disalahgunakan.”
”Inisiatif saya memang ndak boleh.” Mudjono kali ini mempertegas.
Barangkali contoh yang paling menarik adalah ritual adat bernama entas-entas. Di Bali adat ini amat mirip dengan perayaan Ngaben. keduanya sama-sama dirayakan ketika ada orang meninggal. Bedanya, dalam Ngaben mayat dibakar, dan itu tentunya butuh biaya tidak sedikit. sedang entas-entas mayat hanya dikubur, namun setelah lewat 44 hari dibuatlah imitasi berupa boneka yang nantinya di arak lantas dibakar atau dibuang ke dalam jurang. Boneka itu disebut pitera, tingginya dua sampai empat desimeter dan terbuat dari kain dan dihias tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga.
”Jadi rohnya diundang, dukun yang mengundang. in tinya, simbol saja yang dibakar,” ucap Mudjono. ”kalau di Tengger seperti Ngaben, bisa repot masyarakat Tengger. Biayanya banyak.”
Lepas dari soal menyamakan Tengger serupa Bali, seb etulnya banyak hal, juga kekuasaan, yang punya niatan sama, yang hendak mengukuhkan Tengger dalam satu identitas, satu agama, ataupun satu muara asal-muasal. Pada 6 Maret 1973, pemerintah Orde Baru lewat Parisada Jawa Timur menerbitkan surat keputusan No.00/PHB Ja tim/kept/iii/1973, yang menyatakan masyarakat Tengger sebagai pemeluk agama Budha Mahayana. imbasnya, tak sedikit dukun Tengger yang dilantik menjadi biksu. Mundur ke tahun 1969, seorang tokoh Hindu dari surabaya melantik banyak dukun Tengger menjadi Pamangku.
adalah Mudjono yang lantas menceritakan kepada saya mengenai penemuan sebuah prasasti.
Di sekitar 1971, di puncak Gunung Penanjakan, seke lompok arkeolog menemukan sebongkah prasasti. setelah diteliti saksama, ditengarai sebagai peninggalan kerajaan singasari. Pasalnya, di tubuh prasasti tersebut tergurat nama raja kartanagara dan pahatan bertarikh 1225 M.

LAPORAN KHUSUS HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Peta Kawasan Pegunungan Tengger
”Menurut hemat saya,” ungkap Mudjono, ”sebelum Majapahit berdiri, Tengger telah ada manusianya. Jadi jika Tengger itu murni pelarian Majapahit saya sendiri merasa kurang pas.” kini prasasti tersebut berada di Museum Mojokerto.
s ingasari dan Majapahit adalah dua kerajaan yang pernah meramaikan sentra kekuasaan politik Jawa Timur dalam bentangan sejarah Nusantara lama. k erajaan s ingasari —terletak di ujung barat pegunungan Teng ger—memerintah hanya dalam tempo 1222 M sampai 1292 M. kerajaan Majapahit berkuasa sesudahnya, pernah berhasil menyatukan Nusantara dalam kesatuan maritim dan menjadi kerajaan laut terbesar yang gemilangnya tiada terkira. kerajaan ini mampu mempertahankan tampuk kekuasaannya dari 1292 hingga sekitar 1520 M. kedua kerajaan tersebut memberikan sumbangan terbesar bagi kebudayaan Nusantara dalam persebaran shiwaisme dan Buddhisme, sampai melebar ke kerajaan Blambangan yang terletak di Bali.
Di paruh pertama abad ke-16, kerajaan Demak mengikis perlahan-lahan kemegahan Majapahit. Puak ini menyetir dan mengalihkan lagi sejarah ke bagian barat Jawa, juga sekaligus menyebarkan islam.
Blambangan adalah kerajaan Hindu-Budha terakhir di Jawa. Melalui raja Trunajaya lantas surapati, puak Blam bangan menjadi pihak yang sukar ditaklukan bagi Mataram islam. Mataram pun kemudian menggandeng kekuatan Belanda. Di paruh terakhir abad ke-18, lewat cara picik Belanda yang membantu islamisasi keluarga kerajaan Blambangan, pemberontakan perlahan-lahan surut.
ada hal yang harus dibayar mahal: jumlah penduduk di pedalaman berkurang akibat perang berkepanjangan itu. Orang-orang Tengger yang kukuh mempertahankan basis kulturalnya kemudian berpindah ke daerah lereng atas. Mereka lantas masih menjaga dialek yang tidak baku, tra disi keagamaan dan tatanan masyarakat yang jauh berbeda ketimbang orang-orang ngare —begitu istilah Tengger lereng atas menyebut orang daerah bawah.
Pada 1743 Belanda, atas jasanya membungkam para pembelot, diberi kuasa penuh atas hampir seluruh pesisir utara dan ujung timur pulau Jawa, Tengger termasuk di dalamnya. Hefner mencatatnya sebagai gejolak kekuasaan baru di bawah pemerintahan kolonial.
Dalam kitab Nagarakertagama dari abad ke-14, karan gan Mpu Prapancha, disebutkan bahwa sewaktu berkuasa, raja rajasanagara —lebih dekat dikenal sebagai Hayam
Wuruk (1350-1389)— pernah berjalan mengitari pegunun gan Tengger serta sesekali singgah di daerah lereng ten gah. Tengger dulu, tulis Hefner, menjadi pusat komunitas kependetaan shiwa dan Budha yang menyembah dhay ang-dhayang pegunungan. Bahkan Gunung Bromo, dalam sebuah mitos, dikatakan sebagai tempat dewa api Brahma atau Brama, namun tidak sepenuhnya diidentikkan dengan dewa-dewa india yang dikenal ukuran arsitektural ritus-ri tus pemujaannya sangat gigantik, terutama shiwa. Perihal ini lantas tertulis di prasasti Walandhit yang ditemukan di dekat Gunung Bromo pada awal abad ke-20.


Pengaruh Hindu dan Budha bukanlah soal yang terban tahkan. Claire Holt, dalam Art in Indonesia: Continuities and Change (1967), menulis bahwa sejarah kebudayaan Nusan tara adalah proses yang terhampar dalam serangkaian gerak osmosis, semacam perembesan kultur. Denys Lombard yang menulis Nusa Jawa: Silang Budaya mengatakan hal serupa. Jejak-jejak kebudayaan indonesia bukanlah dialektika. Me lainkan lebih ke arah kebudayaan yang saling serap antara warisan-warisan lokal dengan pengaruhnya. Tak terkecuali pula agama-agama india. Pengaruh kebudayaan india be gitu kental. Ini terlihat dalam bukti-bukti epigrafi sejarah Nusantara lewat rekaman Holt dalam bukunya itu.
Tengger pun serupa. ia muncul dalam bentuk yang ber beda: sebuah wilayah, juga kebudayaan, yang menyimpan jejak-jejak kompleks dari untaian sejarah asia Tenggara, begitu anasir Robert W. Hefner dalam Geger Tengger. Hefner memahamai lokasi risetnya itu sebagai benteng terakhir Hinduisme Jawa —sebagaimana istilah sinkretisme ‘islam Jawa’.
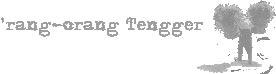
Pasca-kejatuhan Majapahit, Tengger tersuruk dalam pertempuran yang bikin resah lewat islamisasi kerajaan Demak dan kerajaan kecil Hindhu Blambangan di ujung timur pulau Jawa yang menampiknya.
identitas Tengger tak lepas dari jalinan sejarah masa silam tersebut. Juga angin perubahan yang terus bergulir, mendefinisikan di tiap pasang-surut kebudayaan, di tiap generasi, turun-temurun. inilah risalah leluhur yang belajar mengeja arah gerak waktu.
”Permohonan saya kepada masyarakat sekawasan Tengger adalah di antara adat dan agama harus berjalan dengan imbang, tidak ada pembedaan. adat dan budaya tetap dilestarikan, dan agama tetap dijalankan.” Begitu ucap Mudjono kepada saya di suatu hari di bawah langit senja Tengger yang terlihat memerah.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Peluh di Terik Tegalan
Seorang warga Tengger giat memelihara sepetak ladang demi sekerat harapan. LeLaki muda itu tengah merawat sehampar ladang yang menjorok ke tepi badan jalan utama. ia mengenakan celana dan kaos berlengan panjang, juga memakai topi melebar ke depan yang menutupi kepalanya. seakan tak cukup menahan terik panas matahari, kepalanya dililit kain sarung sampai ke dagu. sedang sepatu karet hijau melingkari kedua kakinya hingga ke tungkai betis. Di bawah kakinya terhampar tanah berdebu dan berpasir.

Ladang yang diinjak lelaki tersebut ditumbuhi tanaman bawang brei yang terlihat menghijau. ia sedang memetik ujung daun brei yang berwarna kuning kecoklatan, memisahkan yang masih segar terawat dan membuang yang telah busuk dan mengering. rumput liar yang bertumbuhan dan menjalar di atas ladang tersebut disapu olehnya den gan sebilah sabit lalu dibuang ke dalam anyaman karung plastik putih. Sangat telaten. Ia bernama Yanto, usianya 24 tahun.
”asalnya dari mana?” tanya saya. ”saya dari Lumajang,” jawabnya, mengacu kepada kota yang terletak di sebelah timur pegunungan Tengger.
Yanto bukan asli suku Tengger dan ladang itu bukan miliknya. ia tenaga kerja upah, bekerja dan tinggal serumah di tempat majikan yang memiliki ladang tersebut. Dua bulan sekali ia pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang.
”Upahnya berapa?” saya bertanya. ”sehari sekitar rp 7.000 dan 8.000,” jawab Yanto, seraya mata dan tangan nya begitu awas memperhatikan perkembangan tanaman ladang tersebut. ”Bawang brei ini panennya tiga sampai empat bulan sekali,” tambahnya.
Bawang brei atawa bawang daun adalah salah satu tanaman selain kubis dan kentang yang biasanya menghuni lahan ladang lereng atas sekitar pegunungan Tengger. ketiga tanaman tersebut menjadi hasil pertanian utama bagi wong
gunung —sebutan suku Tengger daerah atas. Lahan lereng atas Tengger berupa bebukitan yang berundak-undak dan dikenal sebagai tanah tegalan. Dalam kondisi ekologi yang serba terbatas itu, para petani Tengger mencoba beradap tasi. Mereka kerap melakukan tumpangsari di atas lahan tersebut. Umumnya bawang brei tumbuh dalam kondisi tanah yang agak basah dan gembur. Bagi lahan yang kering, jagung putih teramat cocok. keduanya ditanam setelah pan en kentang saat musim penghujan, dan kubis ketika alam terjerembab dalam kekeringan yang teramat panjang.
Boleh jadi sistim tumpangsari itu sangat dikenal dalam budaya pertanian orang-orang Jawa pegunungan ini. Mer eka melakukannya demi menghambat laju hama lalat yang kerap merusak lahan ladang dan menyiasati siklus musim yang acapkali datangnya tak terencana.
Namun, tak semudah itu bayangannya memang. Lahan lereng yang curam dan amat minim ditumbuhi aneka pohon berpokok batang kokoh selain julangan cemara menyimpan sekelumit peristiwa yang mengkhawatirkan. Longsor men jadi perihal yang senantiasa tercatat dalam ingatan para petani tegalan ini.
”sebagian tanah yang kemiringannya sudah 60 dera jat umumnya mengalami longsor,” ucap senewo kepada saya.
”Longsor itu,” kata semangat di akhir agustus silam, ”kemiringan tanahnya, Mas. Jadi dimana-mana kalau long sor itu.” senewo dan semangat selain sebagai polisi hutan adalah petani Tengger asli.
”Tapi sekarang masyarakat perlahan-lahan sudah mulai mengerti,” ungkap senewo mengenai sesama warga Tengger
Musim Kemarau. Anakanak Tengger Ngadas Rejo ikut antre mengambil air bersama orang tuanya.
LAPORAN KHUSUS HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
Ngadas Rejo, Malang. ”Yang jadi kendala itu kalau musim kemarau itu ada lalat, rada (agakred) susah. entah dari mana. Tapi sebelum ada pupuk (kimia-red) itu ndak ada, setelah itu makin banyak. Lalatnya yang besar itu. Jadi kalau ada lalatnya, makanan ndak mau dimakan.”
kesemuanya bermula di awal tahun 70-an. saat itu pemerintah tengah gencar melakukan program revolusi hijau bagi lahan pertanian di hampir seluruh kawasan indonesia. Lewat para aparatus desanya, para petani lereng atas Teng ger mesti mengubah kultur bertaninya. Mereka tak sungkan mengkonsumsi pupuk kimiawi demi mempercepat pertumbahan tanaman di atas lahan pegunungannya. Pola konsumsi dan pertanian masyarakat Tengger pun lantas berubah pula.
Hasil produksi berlimpah memang dan sejalan dengan niatan pemerintah yang tengah berambisi memenuhi swasembada pangan dan pertanian. Namun di balik itu tersembunyi kecacatan yang menjelma kenyataan. Hama tanaman dan longsor kini banyak merusak ladang para petani tegalan tersebut. Teknologi pertanian itu sebenarnya mem bawa keuntungan ekonomis bagi para petani kecil dan besar di daerah lereng atas. Tetapi dalam lain hal telah menciptakan permasalahan ekologis yang sangat besar, boleh jadi dapat memperpendek usia pertanian milik para petani lereng atas ini.
saat musim kering itulah segala hal bisa berubah dalam sekali tempo.
Desa Ngadas rejo sedikitnya mengalami imbas yang nyata. ”kesulitan musim kemarau itu ya tanam ya. Mau tanam itu ndak bisa. Hanya tanahnya itu memang sulit. Mau panen sampai gagal karena serangan hama. kubis itu jualnya itu murah, hanya 300 per kilo. Tapi tetap saya ini berladang. Memang di sini itu tidak semua tanaman mem butuhkan air yang banyak.” Wardiono menjelaskan.
”semuanya,” lanjut Wardiono dengan mimik serius, ”banyak (yang menanam-red) bawang putih, ya lumayanlah. sekarang saya ndak mau, menghabiskan (ladang-red) itu ndak mau. Yang lain itu kaya’ gitu, kalau kelihatan mau merosot, semuanya itu dijual.”
”kalau musim kering ini, kentang itu sudah tiga setengah bulan sudah bagus. Musim hujan, lima bulan, tapi hasilnya agak berlipat. Jadi imbang itu. kalau kering, orang sini banyak pakai obat namanya apa racun itu, eh…pestisida itu. Tapi kalau musim hujan itu, dampaknya kurang.”
Meski umumnya tak seproblematis dengan yang diha dapi oleh para petani Jawa di daerah bawah dan pesisir, namun terkadang para petani Tengger mesti memutar otak dan tenaga ketika genangan air sungai mulai susut dan sukar didapatkan. Terlebih pemerintah kita amat terkenal lamban menangani permasalahan yang menyangkut hajat hidup para petaninya. Dari penjelasan Wardiono itu, petani Tengger nyatanya tak mampu berbuat banyak saat tana man ladangnya tak kuat bertahan lama terhadap pengaruh luar yang menyesakkan itu. Hama tanaman yang menyebar, berkurangnya kesuburan tanah akibat aneka obat-obatan, lantas ditambah musim kering yang berlarut-larut, adalah perihal yang berkelindan jauh, saling susul-menyusul.
Bagi petani Tengger hal itu mengurangi jerih keringat yang bercucuran saat mereka berladang hampir seharian. Walaupun nasibnya tak sehitam petani Jawa pesisir yang tersuruk oleh lilitan utang atau tak punya tanah sama seka li. singkatnya, petani Jawa pegunungan ini mesti menapak
pengorbanan yang kadang penuh onak dan duri.
Bilamana hal itu menimpa para petani miskin Tengger yang jumlahnya tak sedikit?

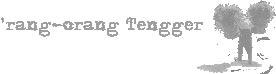
anasirnya begini: saat yang lebih kaya mampu membeli pupuk kimia, yang miskin berkerut keningnya. ketika hama menyebar ke setiap ladang akibat obat-obatan anorganik itu, yang hanya memiliki sepetak ladang tak mampu membeli penangkalnya. Dan kala harga tanah melonjak naik sedang yang miskin tak kuat memelihara lahannya lagi, maka mer eka pun berkesimpulan menjualnya kepada orang-orang di daerah bawah. Hidupnya pun lantas terserak menjadi buruh upah, pedagang keliling, atau bagi mereka yang tinggal di desa Ngadisari kemudian menyabit rerumputan untuk dijual sebagai pakan kuda wisata.
Tak sebatas itu saja. Jika tergelar upacara adat, mereka yang tinggal di pondok kecil mesti ikut berperan, sebab orang-orang Tengger begitu patuh terhadap para dukun dan kepala desanya.
kini bagi wong Tengger segalanya adalah soal bagaima na memelihara dan membagi kesederhanaan. Terlebih ketika perubahan kian menggerus nilai tradisi leluhur, dan pemujaan terhadap perihal yang konsumtif tak lagi disembunyikan di dalam laci almari atau di bawah kasur tempat tidur.
”Yang kaya itu tetap membutuhkan si miskin untuk pertanian. Mereka diminta untuk membantu tetangganya yang membutuhkan tanah garapan. itu pun juga diberikan upah sesuai dengan yang umum. Jadi mereka sampai ti dak nganggur. Tidak ada pembedaan antara si miskin dan si kaya,” ungkap senewo dalam nada suara yang lembut dan tenang.
Ya, selarik kenyataan yang semoga tetap terjaga teruntuk masa-masa seterusnya.
Perempuan Suku Tengger. Meski usianya sudah tua masih giat berladang.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
SUATU
Minke!
Si pemantik api kesadaran bangsa..
Oleh: NUGROHO NUR CAHYO, M. WAHYU GANDEWO dan SF. SALAM
hari pramoedya Ananta Toer
ditawari kerjaan oleh seorang sahabat bergelar profesor dari Universitas Leiden, Belanda. Ia diminta mengajar di Universitas Respublika (sekarang Universitas Trisaktired ). ”SM p saja saya tidak tamat, kok diminta ngajar. Bagaimana?” heran pram kepada kawannya itu. Si sahabat itu malah menjawab dengan nada harap, “Kami percaya pak pram bisa.”
Akhirnya, pramoedya pun mulai meng ajar. Di kelas, di depan 26-an mahasiswa, pram merasa canggung sendirian. Ia pun lantas memberi pekerjaan pada setiap anak didiknya supaya mempelajari surat kabar sebelum dan awal abad 20 selama satu tahun.
Dari kumpulan tugas itulah, pram lantas kenal kali pertama dengan sosok pribumi bernama Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, atau familiar dengan inisial T.A.S.
Setelah mempelajari naskah kerja para mahasiswanya, pram cukup yakin untuk membuat studi sendiri tentang sosok satu itu. Ia kemudian menulis mengenai Tirto. Terbitlah sebuah karya pena tentang tokoh itu dari tangan pram. Ia kasih predikat Tirto sebagai Sang pemula dan ia jadikan sebagai judul bukunya. Rupanya tak hanya non-fiksi saja p ram membuat catatan ingatan mengenainya, dalam fiksi pun sosok Tirto didedahkan, malahan menjadi tokoh utama dengan nama fiktif Minke. Novelnya itu dikenal khalayak ramai sebagai Tetralogi pulau Buru, yakni Bumi Manusia ; Anak Semua Bangsa ; Jejak Langkah; dan Rumah Kaca
Sejak itu sosok Tirto mulai dikenal. Sewaktu pram belum menulis ihwal tokoh satu ini, banyak orang yang tak mengenalnya. ”Jadi waktu itu tidak dikenal itu Tirto,” pram berkata saat ditemui Fajar Said, Jimmy pramana dan Sigit pranoto dari HIMMAH di rumahnya, Bogor, November tahun lalu.
Lantas siapa sebetulnya Sang pemula atawa Minke ini?
Orang yang lebih dulu mengenal Mas Marco Kartodikromo hendaklah jangan melupakan sosok Tirto. penulis Student Hidjo itu rupanya adalah salah seorang murid dari Tirto. Marco sendiri salah satu murid yang begitu mengagumi gurunya itu. Bahkan, dalam salah satu tulisannya, ia menyebut Tirto sebagai “indoek Journalist Boemipoetra di ini tanah Djawa,” yang “tadjam sekali beliau poenya penna”. Dan
dari keahlian gurunya itu, Marco mengenang, ”Banjak pembesar-pembesar jang kena critieknja djadi moentah darah.”
Di lain kesempatan dalam tulisan yang isinya hampir sama, Marco menjulukinya sebagai “penggoncang Bumiputra bangun dari tidurnya”. Tentunya, tak sebatas kagum, Marco pun meneruskan hal sama yang pernah dilakoni oleh gurunya itu semasa hidupnya, yakni menjadi jurnalis handal, terlebih dalam menterakan setiap laku cacat para pejabat di pemerintahan kolonial.
Inspirasi Tirto memang menyebar kemana-mana. Inilah yang kurang te r pahami oleh sejarah modern Indonesia.
Tirto Adhi Soerjo adalah salah satu tokoh yang masuk dalam golongan pelopor dan perintis gerakan nasion awal, yang mahfumnya dinamakan periode Kebang kitan Nasional.
Ia pun pribumi kali pertama men g gawangi bangsanya untuk soal dunia kejurnalistikan. Sebuah pilihan yang masa itu menandai sikap yang tidak saja sangat modern, tapi sekaligus berani dan visioner. Ia sadar, masa itu rakyat Hindia belumlah cakap benar membaca, tergolong kecil saja yang mahir baca dan tulis, ”mungkin hanya tiga persen,” ujar pram. ”Itu pun di kalangan priyayi saja.”

”Dan priyayi ini,” lanjut pram, ”men dapat kesempatan sekolah, dididik menjadi alat kolonial. praktis selebihnya rakyat buta huruf.”
Lalu kenapa Tirto memilih pers dalam membentuk kesadaran nasion itu? Sikap nya ini bukan tanpa sebab. p ram me n cermatinya seperti ini: ”Jadi, masa itu enggak bisa kita berhubungan langsung dengan rakyat, biasanya hanya lewat pers. Jadi koran itu dibaca oleh seseorang, tetangga-tetangga lalu merubung, dan mendengarkan penjelasan-penjelasan. Jadi gerakan massa itu dikendalikan melalui pers.”
”Karena itu jugalah maka Tirto memilih pers supaya langsung mengembangkan melalui kehidupan sosial,” tegas pram.
Kehidupan sosial inilah yang dik e depankan Tirto. Bukan bagi golongan elit, tidak pula kaum dari lapisan yang di atas-atas saja, melainkan pergerakan yang ditempa sepanjang hidupnya adalah untuk anak bumi kebanyakan.
Lahir di Blora tahun 1880, Tirto tumbuh sebagai seorang keturunan priyayi te r
kemuka. Ia dibesarkan lewat pencerahan neneknya, Raden Ayu Tirtonoto. Tanpa neneknya, barangkali hidupnya pun sedikit lain. pengaruhnya amat dalam terasa di benak Tirto dan menjadi bekal bagi cita-citanya memajukan negeri dan bangsa di kemudian hari.
Setidaknya makna di balik ucapan sang nenek sejalan dengan kisah h i dupnya, ”Anak cucu hamba akan suruh mencari pahala dalam kemiskinan. Artinya tidak dengan pertolongan, hanya dengan tenaganya sendiri.” Itu untaian kalimat dari jawaban Tirto kepada Ir. H.H. van Kol (1852-1925) yang setidak-tidaknya adalah cermin keluarga Tirtonoto saat terjadi peristiwa m emilukan selepas kakeknya, R.M.T Tirto noto, meninggal dunia. Van Kol sendiri adalah orang Belanda periode politik etik kolonial yang menaruh penghargaan atas jasa Tirto. Saya menuliskan ini dari sumber buku pram, Sang pemula, di lembar halaman yang berkait soal keluarga Tirto.
p engaruh sang nenek itulah yang membuat Tirto menjadi sosok lain dari kalangan bangsawan-priyayi. Jiwa dia lektis, ketidaksenangannya terhadap ketidakadilan, terutama dari aparat ko lonial, menyebabkan Tirto tersisih dari saudara-saudaranya yang telah mapan oleh gelar dan pangkat.
Dalam soal itu, pram membubuhkan catatan soal Tirto sebagai “si anak hilang”.
Sekitar umur 14 tahun, selepas tamat HBS, Tirto yang punya nama kecil Djo
L.
HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 RIWAYAT
Pandu
Patriari /
komono ini lantas melanjutkan sebagai eleve pada sekolah kedokteran STOVIA di Betawi. Ia tidak menamatkan sekolah dokternya itu. Hanya menyelesaikan sampai tingkat empat—enam tahun dari keseluruhan yang umumnya delapan tahun. Dan belum jelas apa musababnya. Namun yang terang, pada masa itu amatlah lazim dikatakan bahwa bagi bangsawan pribumi, sekolah dokter bukanlah prestise bagi golongannya. Dan Tirto sungguhlah beda.
Sejak ia hidup di Betawi, cita-citanya terbit dan mulai berkembang. Hingga di usia 20-21 tahun karirnya menanjak benderang sebagai pengarang dan jurnalis pribumi termashur pada zamannya. ”Nampaknya kepergiannya ke Betawi merupakan pem bebasan dari semua ikatan dan peraturan ketat kasta bangsawan-priyayi terhadap anggota keluarga yang miskin dan tidak berdaya. . .” demikian simpul pramoedya Ananta Toer.
pada Februari 1903, sejarah mencatat akan kehadiran penerbitan pribumi pertama kalinya di tanah Hindia, bernama Soenda Berita. praktis sebelum tahun 1900, surat kabar p ribumi sama sekali belum ada. Sejumlah media cetak memang hadir di tanah jajahan Olanda ini, namun sebatas terbitan Eropa—yang pada masa itu disebut “pers putih”.
Soenda Berita berbentuk terbitan berkala mingguan. Tirto selanjutnya meng awali programnya berupa menaikkan pengetahuan bangsanya, dan me m pe r siapkan pembaca untuk memasuki zaman modern. Berkala ini pun pencetus awal dibukanya aneka rubrik bagi wanita pri bumi, dan ditulis oleh para wanita sendiri. Model ini akhirnya banyak diikuti terbitanterbitan lain di Hindia Belanda.
Oleh sebab masalah finansial dan lantaran ditinggalkan Tirto ke Maluku, harian ini tidak bersitahan lama.
Van Heutsz. Kasusnya itu mengambang karena dibekukan oleh Gubernur Van Heutsz untuk meredam gejolak lebih lanjut di Hindia Belanda, di samping bentuk pembelaannya terhadap Tirto.
Namun, semenjak Gubernur Van He utsz digantikan oleh Idenburg, mulailah awan hitam menggelayut di pundak Tirto. Kasus masa lalunya dengan A. Simon dihidupkan kembali. Karena adanya forum privilegiatium, yakni semacam hak yang dimiliki golongan priyayi sebagai perisai terhadap hukum penjara dan siksa, ia kebal masuk bui. Namun berujung pada pem buangan ke Lampung selama dua bulan.
pEKUBURAN Manggadua, Jakarta. Di sebuah hari suram, 7 Desember 1918, terdapat iring-iringan kecil—sangat kecil— yang mengantarkan seonggok jenazah ke pembaringan terakhir. Tak ada pidato yang mengiringinya. Tanda jasa sebagai bakti amalan dalam hidupnya yang pendek pun sepi darinya. Sehabis itu, orang lantas pergi dan meninggalkannya. Itulah terminal akhir menggetirkan yang menimpa seorang Tirto Adhi Soerjo. Sebuah situasi penghujung yang sangat berbeda jauh jika disa n dingkan pada upaya seorang Tirto dalam menggetarkan dan menggedor jantung Republik bahwa ini negeri mesti keluar dari cangkang, harus berdaulat, dan merdeka.
Hidup mulia; mati tragis!
Bagai sebutir kersik pada karang, Tirto lenyap dan tertelan sejarah bangsanya sendiri. Namanya lumat dihapuskan di atas perkamen sejarah Republik. Orang Belanda yang berjasa besar dalam soal ini adalah Snouck Hurgronje (1857-1936) dan D. A. Rinkes (1878-1954). Keduanya menjabat penasihat pemerintah untuk Urusan pri bumi di Algemeene Secretarie (Sekretariat Negara). Hurgronje yang pertama, sedang Rinkes penggantinya. Bisa dibayangkan, segala ihwal dalam tubuh penggerak kesadaran pribumi pada waktu itu akan tercatat oleh kedua orang itu.
pada Sang Pemula, atas ulah Hurgronje, Tirto kali pertama masuk dalam Catatan p emerintah p usat Hindia Belanda. Ini terjadi pada 1902 saat Tirto berhasil membongkar skandal Residen Madiun J.J. Donner melawan Bupati Brotodiningrat.
Januari 1907, sepulang dari Maluku, Tirto mulai menerbitkan surat kabar yang sama sekali baru di Hindia Belanda. Baik dari visi dan misinya, juga pengemasannya.
Surat kabar itu dinamainya Medan Priyayi, berkantor di Betawi.
Menurut p ram, Medan Priyayi ini sangat lain dengan Soenda Berita . ”Ia mempunyai wawasan nasional, meliputi seluruh Hindia Belanda dan menggunakan bahasa Melayu lingua-franca sebagai bahasa redaksinya.”
Tirto membuat ini koran laiknya usaha dagang. Medan Priyayi berdiri sebagai sebuah Naamloze Vennootschap (sekarang p erseroan Terbatas- red ) dengan cara mengumpulkan modal dari para calon langganan melalui pembayaran di muka sebagai saham perusahaan. Tawaran brilian ini memberikan contoh anyar pada warga pribumi agar memulai menggunakan dana masyarakat untuk berniaga. Tidak perlu modal sendiri.
Ini tindakan menjadi sebuah “Jejak Langkah” baru dan revolusioner dalam usaha perniagaan pribumi.
Medan Priyayi merupakan suratkabar pribumi yang amat digemari oleh bang sanya. Tirto merintis kesadaran bangsanya akan arti penting hak keadilan, dan berani menyuarakan kebenaran. Beragam kasus timbul di lingkup pejabat kolonial oleh sebab tulisan-tulisan Tirto yang lantang dan teramat memekakkan demi kepentingan rakyat kecil.
Kasusnya dengan A. Simon dalam skandal pengangkatan lurah desa Bapa ngan, rupanya menyimpan perma-salahan di pengadilan. Tirto dikenal dekat dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu:
Agustus 1912 Medan Priyayi dinya takan pailit. Tirto menangguk utang dan diajukan ke pengadilan. Terang ini ulah kolonial, bukan karena cacat semata pada diri Tirto. pemerintah kolonial tak ingin Tirto berkembang cukup jauh dalam upaya menyuluh bangsanya. Tirto masa-masa itu bagai orang yang berdiam diri di sebuah “Rumah Kaca”. Dalam Sang Pemula , dibentangkan nyata bahwa Rinkes lah otak di balik semuanya.
pengadilan memutuskan ia bersalah. Tirto disandera. pertengahan pertama 1913, Tirto menjalani hidup di tanah pembuangan selama enam bulan.
Semua yang dibangunnya itu akhirnya runtuh, bersamaan dengan nama baiknya. ”Yang tinggal hidup adalah amal dan semangatnya,” tulis pram.
Di tahun 1973 makam Tirto dipindahkan dan menempati komplek pemakaman ke luarga di tengah-tengah pemakaman umum Bogor. Di atas batu nisan tua itu, tergurat kata-kata Perintis Pers . Ini mengacu keputusan Menteri p enerangan/Ketua Dewan p ers, yang dikeluarkan pada 1973.
Tirto diberi gelar Bapak perintis pers Indonesia.
Bagi p ram, itu adalah sebuah gelar yang sederhana dan pemerintah merasa cukup menganugerahi Tirto hanya sebatas itu. “Orang lupa bahwa Tirto memulai keban g -kitan nasional. Karenanya ia diteng-gelamkan oleh Belanda,” ungkap pram, tegas.
Simak ucapan p ram soal Tirto d i bandingkan para penggerak lainnya di masa awal Kebangkitan Nasional: ”Tirto bergerak terutama di kalangan orang yang dianggapnya golongan merdeka. Artinya, orang yang tidak makan gaji dari Belanda. Nah, ini sejiwa dengan pedagang kecilkecil itu.” Suatu jejak yang tergolong amat modern di masa itu.
Layaklah ia disambut sebagai Sang
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 RIWAYAT
* * *

Yang Indah, yang Sekarat
Bagaimana seni macapat masih bertahan hingga kini? Adalah orang-orang uzur yang memulai dan memuliakannya.
Oleh FITRIYAN ZAMZAMI dan SF. SALAM
MALAM Rabu pon tengahan Februari silam lewat pukul delapan. Sekitar tiga puluhan orang yang sudah termakan usia duduk bersila dan melingkar di atas lantai sebuah pendapa. Langit sedikit tak be r-sahabat, gerimis menetes amat perlahan. Dalam dingin pualam pendapa itu, mereka lantas bergiliran mendaraskan pitutur yang digoreskan oleh tangan para leluhur. Terdengarlah lantunan tembang, tanpa diiringi bunyi gamelan, sonder karawitan.
Sekejap, waktu seakan berhenti dan melompat tiga atau empat abad ke belakang di kala para sunan masih keras me m propagandakan Islam di atas Jawa yang Hindu. Tiap Metrum yang tersurat seolah membawa sebuah nuansa magis yang bersahaja. Lewat rima-rima yang tersusun, membentuk jiwa-jiwa adiluhung, dan meretas jalan senyap untuk urip lan megatruh (hidup dan meninggal).
Adalah Macapat, syair yang mengalir halus dibacakan bergilir oleh kumpulan orang tua malam hari itu. Sebuah bentuk budaya Jawa yang kini mulai kehilangan tempat. Tergerus dunia yang bergerak sangat cepat dalam jaringan impuls digital. Menggeliatkan dirinya, menolak kep u nahan. Memagari diri dari dunia.
Mereka membacakan syair macapat (macapatan) itu di sebuah tempat bernama Rumah Budaya ‘Tembi’. Dipimpin oleh seorang koordinator kegiatan, orang-orang sepuh tersebut lantas maju satu per satu setelah dipanggil namanya lewat daftar
hadir, menghampiri meja duduk dari kayu yang telah disediakan di tengah lantai pendapa, kemudian menyanyikannya. Sewaktu saya sengaja datang ke tempat itu, mereka tengah melantunkan salah sebuah bagian dari Serat Centhini.
Ketika bergantian menyanyikan untaian syair Serat Centhini tersebut, ada-ada saja tanggapan dari orang-orang yang sedang mengikuti dan mendengarkan. Umumnya kesalahan m ereka banyak terletak pada tidak tepat mengucapkannya, atau menya nyikannya. Ini jamak tentunya. Mereka bukanlah para penembang macapatan yang mahir, hanya amatir. Ditambah pula mata mereka yang sudah mulai rabun. Malam pula.
Tampaknya, mereka melakukan aktivitas rutin tersebut tanpa sedikit pun beban. Kerap kali terdengar derai tawa dan senyum sumringah. Tetapi keseriusan adalah ihwal yang tak perlu ditawar. Serius tapi santai, begitulah kiranya. Dan jika terdapat salah ucap atau salah eja dari mereka, pemandu saresehan macapat cepatcepat akan meluruskannya. Ia sangat peka rupanya. Ia bernama Joyo Sumarto, kerap diimbuhi kata ”Mbah” di depan namanya. Karena sebe-tulnya ia sudah sangat tua, tak jauh berselang usianya dari “para muridnya”.
Mbah Joyo adalah salah satu pengurus dari Rumah Budaya ‘Tembi’. Ia ditempatkan di bagian pengelola museum dan pusaka sejak kali pertama Tembi berdiri di tahun
1999. Tembi sendiri adalah sebuah lembaga yang mengkaji secara khusus kebudayaan Jawa. Sebelumnya, dari 1963 hingga 1998, Mbah Joyo bekerja selaku pamong desa Timbul Harjo, Bantul, pada bagian kese jahteraan masyarakat.

”Ini milik pribadi. punyanya pak Swan toro,” kata Mbah Joyo mengacu pemilik Rumah Budaya ‘Tembi’.
p. Swantoro cukup dikenal oleh ling kungan surat kabar nasional Kompas. Ia pernah menjadi wakil pemimpin redaksi di koran yang banyak dibaca oleh warga Indonesia itu. Setelah melebarkan sayap ke penerbitan dan toko buku Gramedia, Swantoro lantas menjadi direktur kepus takaan populer Gramedia, atau disingkat KpG. Ini penerbit tergolong sangat mapan di dunia perbukuan Indonesia. Saya cukup terkejut juga ketika melihat koleksi Swan toro dalam ruangan pusaka yang dipelihara Mbah Joyo itu. Setidaknya, hanya orang yang punya modal besar, bahkan kelewat besar, untuk mendirikan lembaga budaya seperti Tembi ini. Ornamen pusaka-pusaka tersebut yang tergolong antik tak mainmain bilangan harganya.
Upaya yang tergolong berani dan sangat ambisius tentunya.
A pA itu macapat? Macapat secara umum adalah sebuah bentuk tulisan jawa. Disusun dengan struktur baris, rima dan pemenggalan yang memungkinkannya dibaca secara melodis. Bentuk penulisan yang sering kita temui dalam literatur-
Seni Macapat. Keberadaanya memprihatinkan sebab sangat tergantung pada generasi uzur.
Adhitya
HIMMAH
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
BUDAYA
Awan /
literatur pramodern dari banyak budaya lainnya seperti Bagavad Ghita , Iliad , bahkan Al-qur’an
”Mungkin disebabkan karena naskah macapat tidak dicetak banyak,” ucap Suryanto Sastro Atmojo, Kepala pengelola Rumah Budaya ‘Tembi’, kepada saya sewaktu malam latihan macapatan.
”Malah,” lanjut Suryanto, ”cuma satu naskah dan baru digandakan bila naskah awalnya sudah mulai rusak.” Sehingga, demikian tambahnya, untuk penyampaian kepada khalayak diperlukan sebuah bentuk yang tidak saja menarik secara substansial, namun juga melodis.
Secara harfiah, menurut Mbah Joyo Sumarto, macapat merupakan akronim dari: ”le MAca Papat-papAT” (di baca empat-empat). Yang dibaca empat-empat dalam hal ini suku katanya alias wanda. Contohnya: pa-Da-Gu-Lang, Nge-Ning-Kal-Bu Ing-Sas-Mi-To, Am-Rih-Lan-Tip Macapat juga adalah ‘maca dengan tepat’. Menegaskan bahwa pembacaan macapat lebih cenderung pada pemahaman lirik, baru kemudian disusul keindahan lantunan lagu.
Macapat bukanlah suatu bentuk tem bang yang berdiri sendiri, tapi lebih merupakan kesatuan dari sub-sub bentuk yang menguatkan liriknya masing-masing. Ini disebut pupuh atau metrum, biasa pula dinamakan tembang. Masing-masing metrum memiliki bentuk melodis, juga aturan mengenai jumlah baris per bait (guru gatra), jumlah suku kata per baris (guru wilangan ), huruf hidup terakhir dalam setiap baris (guru lagu), struktur pemeng galan atau pedhotan , dan pe m -bagian dalam antar baris.
Nancy K. Florida, seorang peneliti literatur kebudayaan Jawa, merefleksikan macapat begitu liris di bukunya yang bertajuk Writing the Past, Inscribing the Future . Ia mengandaikan macapat ini sebagai suatu tembang yang hadir untuk menghasilkan makna potensialnya. Buku nya itu dalam salah sebuah bab berisi gubahan Babad Jaka Tingkir.
”Dengan memiliki strukturnya sendirisendiri (walaupun tidak baku), metrummetrum ini membuat sebuah karya macapat menjadi tembang yang kaya bukan hanya melodis namun juga bentuk lirik,” itulah simpul orang barat pertama yang menerima gelar ningrat dari Keraton Surakarta ini. Nancy diberi sebutan Kangjeng Mas Ayu Tumenggung Budayaningtyas.
Sub-sub bentuk dari macapat ini terdiri dari lima belas bentuk yang dikelompokkan dalam tiga Rum: Macapat Alit, Macapat
Tengahan, Macapat Sekar atau Ageng
Dalam Macapat Alit terdapat sembilan metrum, sedang Tengahan dan Sekar masing-masing tiga. Metrum-metrum ini diberi nama merunut siklus hidup manusia, seperti Mijil yang berarti masa pertama keluarnya manusia dari rahim; Gambuh, yaitu saat dimana mulai tumbuh cinta antara dua manusia; Megatruh atau lepasnya ruh dari jasad.
p erlambang siklus hidup ini me m pengaruhi watak melodis tiap-tiap metrum. Misalnya Mijil, ditembangkan dengan suasana jiwa penuh kerinduan seperti saatsaat penantian kelahiran seorang manusia.
Atau Megatruh yang pelantunannya membangkitkan kedukaan dan penyesalan mendalam, suasana yang tertangkap saat seseorang tengah diambil jiwanya. Melalui metrum-metrum tersebut menegaskan makna. sifat larik, baris, dan melodinya secara tersendiri saling mengisi, bersi tegang namun merengkuh satu sama lain. Darinya sebuah tembang macapat mem bangkitkan makna kolektifnya.
perbedaan macapat dengan seni tem bang Jawa lain semisal sindenan yakni tidak boleh diiringi dengan alat musik apapun. ”Orang yang melakukannya mesti sendiri-sendiri,” ucap Mbah Joyo kepada saya.
”Kalau untuk latihan bersama-sama boleh,” ungkapnya. ”Tapi pas dite m bangkan hanya boleh satu orang, karena macapat adalah keahlian olah vokal.”
AWALNYA, macapat mempunyai fungsi sebagai media yang digunakan oleh para ulama untuk menghembuskan Islam pada masyarakat Jawa di abad 17 sampai 18. Untaian syair yang terdapat pada macapat awal tersebut sepenuhnya berisi pituturpitutur atau petuah-petuah untuk hidup dan berkehidupan.
Dalam perkembangannya, isi macapat meluas mencakup segala pembahasan, dari mitologi jawa kuno tentang perwaktuan dalam Serat Kalatidha ; sejarah tentang tanah jawa dalam Babad Jaka Tingkir ; sampai sekelumit seksualitas yang diumbar tanpa batas dalam Serat Centhini. Walau pada umumnya selalu dimulai dengan pujipujian terhadap Allah dan Rasulullah.
p embacaan macapat dulunya hanya dilakukan dalam lingkungan keraton. Karena biasanya yang memiliki beragam naskah macapat hanya dari kaum alit dan sebagai konsumsi terbatas bagi kalangan istana. Namun seiring lebih mudahnya diakses, macapat pun mulai diperdengarkan kepada rakyat biasa.
Mulailah kurun evolusi itu bergulir.
Dalam masyarakat kontemporer, macapat lantas diajarkan sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah dasar dan menengah di Jawa Tengah khususnya. Tetapi seiring selesainya jenjang pendidikan tersebut, macapat pun tak lagi mempunyai tempat di hati kebanyakan muda-mudi Jawa, yang akrab dengan tontonan televisi dan lagulagu MTV.
”Mereka lebih memilih mendengarkan kebudayaan barat yang tidak adiluhung itu,” lirih Aris warsito kepada saya. Ketiga putra Aris Warsito pun tidak ada yang mendalami macapat.
Acapkali dalam gelaran Tujuh Belas Agustus-an, macapatan masih sering diperlombakan Tetapi tak banyak kaum remaja yang ikut berperan. Hanya orangorang lanjut usia yang mengikuti pe r lombaan tersebut.
Nasib pelantun macapat kini bertumpu pada mereka yang sudah mulai termakan usia. Anak-anak mereka sedikit yang mencoba mendalami di luar konteks pela jaran. Sarasehan-sarasehan macapat masih ramai dikunjungi memang, tapi hanya oleh mereka yang usianya terbilang 40-an ke atas.
Mbah Joyo dan Aris sama-sama per caya bahwa macapat masih dapat mene guhkan keberadaannya. Mungkin sampai setengah abad ke depan. Tetapi, di tengah hiruk pikuk nilai yang tak tersaring sem purna di ujung jaman ini, ditengah dunia yang menganggap budaya hanya sebagai akumulasi estetika yang bisa dijual, ma capat seperti kehilangan makna. Hanya hadir dalam nada-nada tanpa substansi. Ia seakan dalam fase yang tinggal sekarat.
MALAM semakin merapat. Giliran itu telah mencapai pungkas ketika jam ber dentang lewat pukul sebelas. petikan siter penutup karawitan sudah diperdengarkan. Waktu pun kembali dari pengelanaannya. Orang-orang uzur itu saling berjabat salam. Mereka perlahan-lahan meninggalkan tempat pendapa Rumah Budaya ‘Tembi’.
Rupanya, banyak pula dari merka yang menggunakan alat kendaraan sepeda onthel, yang konon dulunya pernah mengisi wajah khas Djogja. Barangkali nasib macapat pun tak beda jauh dengan sepeda onthel yang tengah dipakai oleh mereka.
Meski separuh kabur, saya masih mendengar sayup-sayup lantunan pitutur yang digoreskan tangan para leluhur itu: pada gulang ngening kalbu Ing sasmito amrih lantip
Ojo pijer mangan nindro Kaprawiran den kaesti pesunen sarira nira
��5 5HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 BUDAYA
Pepesan Kosong Rapor Konvensi
Meski pelbagai konvensi internasional telah diratifikasi, di negeri ini kekerasan semakin menjadi-jadi.
langsung ketahuan bersalah melakukan kejahatan karena telah tertangkap tangan, tetapi ada juga yang sudah menerima pukulan, hantaman, oleh oknum aparat hukum padahal dirinya masih belum defi nitif terbukti melakukan suatu kejahatan.
Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia yang disahkan pada tahun 1948 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang, tanpa pengecualian apapun, mem peroleh hak azasi berdasarkan atas ke nyataannya sebagai insan hidup. Sehingga baik status seseorang itu adalah seorang tersangka maupun terdakwa, hak-haknya sebagai insan hidup patut dihargai dan dihormati.
Berikut adalah cerita beberapa korban yang menuturkan kesaksiannya kepada HIMMAH, ketika kami berkunjung ke Lembaga pemasyarakatan (Lp) Wirogunan, Jogjakarta. Ada sebut saja Gono, 19 tahun. ”Sekitar setengah jam dipukul dan sambil ditanya. Walau sudah ngaku masih dipukul,” ungkapnya waktu diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pe m bunuhan. ”Belum lagi pemukulan itu ditambahkan di sel,” lanjut Gono.
Kalau Gono (nama-nama tahanan selanjutnya dalam tulisan ini juga bukan nama sebenarnya) pernah merasakan pukulan dengan rotan dan kayu kotak, maka Yono, 26 tahun, laki-laki yang terlibat kasus narkoba pernah dipukul pakai shockbreaker
pENYIKSAAN merupakan manifestasi dari kekerasan. Kekerasan apapun itu bentuknya tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui acara kriminalitas seperti p atroli, Sergap, atau Buser yang d i tayangkan televisi swasta dapat kita temui pelaku penyiksaan tidak hanya anggota masyarakat sipil, tapi juga anggota aparat hukum. Dilihat dari subjek pelakunya, penyiksaan oleh aparat hukum tersebut dapat berakibat fatal bagi tegaknya hukum di Indonesia.
Siaran berita elektronik dan cetak juga memberitakan, orang-orang yang te r identifikasi menjadi korban dari penyiksaan tersebut beragam baik berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun profesi. Korban dari perlakuan oknum aparat hukum yang tidak sewenang-wenang itu, ada yang memang
”Sewaktu di p oltabes saya ditanya sambil dipukul.” p emukulan yang d i lakukan kepadanya berlangsung selama sejam. Waktu ia baru ditangkap pun langsung dipukuli pakai pentungan polisi dan pakai shock-breaker

Lain halnya dengan Nani, 23 tahun, perempuan yang tertangkap tangan oleh polisi di sebuah hotel di Jogjakarta ketika sedang melakukan pencurian sepeda motor bersama teman-temannya. Ia bercerita pe ngalamannya saat pertama kali ditangkap, dia sudah ditodong pistol dengan perlakuan yang kasar. Kemudian, ”ketika di sel, diancam mau dibakar,” imbuhnya.
Dan Cahyo, 14 tahun, anak laki-laki yang didakwa melakukan pemerkosaan anak di bawah umur ini mengaku sering dipukul oleh yang menginterogasinya.
”Saya di polsek dipukul di perut oleh polisi dan dihantam pas ditanya. padahal saya langsung mengaku,” kata Cahyo kepada HIMMAH.
Oleh
Pengeroyokan. Jadi masalah serius karena tidak adanya tanggungjawab negara.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 INTERNASIONAL
Adhitya Awan / HIMMAH
”Saya juga sering disuruh melakukan onani di depan aparat!”
perlakuan oknum aparat hukum ter sebut terhadap Gono, Yono, Nani, dan Cahyo tergolong dalam tindak kekerasan yang berbentuk penyiksaan. p adahal Universal Declaration of Human Right itu telah diakui di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa ini masih kerap terjadi? Apakah karena aparatnya yang tidak paham tentang deklarasi itu atau karena sistem kita yang masih kacau?
Kasus yang terjadi di Jogjakarta ini sekiranya hanyalah bagian kecil dari rapor merah pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas praktik penyiksaan di negeri ini.
”Di Indonesia sekarang itu siapapun yang berurusan dengan aspek aparatus terutama dalam proses hukum entah saksi, tersangka, dan sebagainya, tidak ada perlindungan yang memadai, bahkan hakim-hakim di pengadilan juga belum berani memutuskan lain, ketika dia me ngetahui para tersangka membuat p e ngakuan atas penyiksaan,” komentar Munir, Direktur Imparsial, The Indonesian Human Rights Watch
Sebagai bagian dari komunitas negaranegara di dunia, upaya Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum di dalam negeri selalu dipantau oleh dunia i n ternasional. Apalagi sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Anti- p enyiksaan ( Convention Against Torture ) pada 28 September 1998, sebagai salah satu dari 126 negara pihak pada Konvensi, I n donesia berkewajiban menyampaikan laporan tahunan (Annual Report) kepada Komite Anti-penyiksaan, mengenai lang kah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia (-pemerintah) sebagai upaya mengimplementasikan poin-poin yang tertuang dalam Konvensi Anti-penyiksaan, yaitu dalam waktu satu tahun setelah Konvensi ini berlaku di Indonesia.
Adalah Sri Wartini Dosen Universitas Islam Indonesia bagian Hukum I n te r nasional mengemukakan, ”Konvensi Anti-penyiksaan itu kan merupakan salah satu pelaksanaan dari prinsip Declaration of Human Rights . Bahwa di dalamnya meng-atur mengenai proses pemeriksaan perkara yaitu untuk membawa keterangan dari pihak korban dan atau pihak tersangka tidak boleh dengan cara-cara kekerasan.”
Laporan tahunan (Annual Report) itu nantinya diserahkan kepada Komite Antipenyiksaan (Committee Against Torture). Laporan Indonesia kepada Komite tersebut merupakan laporan Indonesia yang per tama (maka disebut laporan awal atau
Initial Report sebelum kemudian menjadi laporan tahunan atau Annual Report ) sejak I n -donesia menjadi negara pihak pada Kon-vensi Anti-penyiksaan dengan meratifikasi Konvensi ini melalui Undangundang nomor 5 tahun 1998. Komite Anti- p enyi k -saan yang mengevaluasi hasil Laporan tahunan (Annual Report) Indonesia, kemudian mengeluarkan simpulan dan rekomendasi implementasi Konvensi Anti-penyiksaan di Indonesia.
”Dan di dalam konvensi itu kan ada komitenya. Komite untuk pengawasan semua anggota yang telah meratifikasi konvensi ini. Namun apakah benar mereka telah melaksanakan apa yang tercantum dalam konvensi ini?” kata Wartini.
Komite Anti- penyiksaan merupakan badan yang dibentuk berdasarkan pasal 17 dari Konvensi untuk memantau pelak sanaan Konvensi oleh negara-negara pihak dan beranggotakan 10 pakar independen yang dipilih oleh negara-negara pihak. pada tanggal 22 Nopember 2001 lalu, Komite Anti-penyiksaan mengadakan sidang ke-27 nya di Jenewa.
Komite tersebut mencatat sejumlah kemajuan yang telah dicapai Indonesia sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan p emerintah Indonesia untuk memberantas praktik penyiksaan sesuai dengan tuntutan dari Konvensi.
Siaran pers pTRI (pusat Telekomunikasi Republik Indonesia) di Jenewa me m beritakan di antara kemajuan yang dicatat komite adalah reformasi sistem hukum dan revisi konstitusi dan legislasi untuk memperkuat perlindungan HAM, penge sahan Undang-undang pengadilan HAM serta rencana pengesahan Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban.
Hal-hal yang menjadi sumber kepr i hatinan juga menjadi catatan Komite antara lain adalah banyaknya laporan mengenai praktik penyiksaan oleh aparat keamanan, termasuk di daerah-daerah konflik dan kurangnya jaminan mengenai adanya penyelidikan yang cepat dan tidak memihak (impartial) terhadap laporan praktik-praktik penyiksaan yang d i sa m paikan kepada aparat yang berwenang.
Untuk mengetahui efektif tidaknya Konvensi Anti-penyiksaan ini kemudian untuk mengevaluasi apakah Konvensi Anti-penyiksaan ini dalam level nasional memang sudah dilaksanakan atau belum.
”Ini kan harus ada monitoring, sebagai salah satu cara untuk memonitor selain adanya pengawasan yaitu, laporan (Initial Report dan Annual Report red) dari negara pihak. Laporan ini kemudian nanti yang akan dievaluasi kebenarannya, ini di-cross-
check dengan keadaan sebenarnya benar tidak apa yang dimuat di dalam laporan ini,” jawab Wartini.
pembuatan Initial Report dan Annual Report juga musti berdasarkan data atau informasi yang akurat sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.
”Di dalam laporan ini kan harus memiliki kebenaran informasi yang objektif tidak boleh memanipulasi data, memanipulasi informasi,” tambahnya.
Lain halnya pendapat Munir.
”Dalam Annual Report itu Indonesia hanya menjawab secara normatif, s e betulnya lebih basa-basi ya, ketimbang menggambarkan sebagai proses koreksi signifikan.”
p esimisme seakan terekspresikan oleh Munir, mengomentari minimnya pengung-kapan dan penghukuman terhadap para oknum aparat hukum pelaku tindak penyik-saan. ”Karena Annual Report yang harus dikirim pada tiap periode itu kan men-cerminkan apa yang sudah dilakukan Indonesia untuk memperbaiki perilaku aparatus negara di dalam upaya melakukan interogasi kepada orang yang diduga melakukan suatu kejahatan,” ungkapnya.
”Tetapi boleh dikatakan hampir tidak ada dan bahkan masih sedikit sekali kasus-kasus yang memberi contoh bahwa penyik-saan di tempat-tempat penahanan itu dihukum, karena justru dilindungi para pelakunya,” tambah Munir.
p elaksanaan Konvensi Anti- p enyi k saan di Indonesia memang bisa menjadi salah satu tolak ukur penegakan HAM di negeri ini. Tidak hanya butuh konsistensi dan konsekuensi dalam men e -rapkan prinsip-prinsip Konvensi Anti-penyiksaan, tetapi yang lebih subtansial diperlukan perubahan secara komprehensif berkaitan dengan transformasi pendidikan HAM kepada para oknum aparat hukum. pen didikan HAM merupakan bekal untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tanpa menggunakan cara-cara penyiksaan di dalam birokrasi.
”Sehingga dengan tidak adanya metodologi itu boleh dikata angka penyiksaan di Indonesia jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan karena itu masih menjadi perilaku umum pejabat publik kita di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa,” ungkap Munir.
Dan, karena pula manusia sejak lahir, punya hak untuk tidak dikasari. Atas nama negara sekali pun.
�� ��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 INTERNASIONAL
Perpustakaan Lokal Penyadaran Sosial
Oleh ABDUL WAHID FAUZIE
SEJUK. Mungkin hanya kata tersebut yang pantas untuk menggambarkan ke-adaan ruangan berukuran 7 x 4 meter itu. p intunya dibuka lebar-lebar. Angin pun bertiup riuh-rendah. Meski berada di dalam rumah, ruangan itu terbuka untuk siapa pun. Ruang milik publik. Biasanya baru ramai sore hari: saat anak-anak pulang sekolah. Letaknya di antara dua petak sawah. Terkenal dengan sebutan ‘Rumah Sawah’. p erlu jalan kaki lewat tegalan untuk mencapai rumah itu. Di depannya dibangun kolam kecil yang di atasnya dibuat pe-nyangga, agar dapat diduduki. Dari sana terhampar pemandangan hijau dedaunan. Sangat menyenangkan.
Ibarat rangkaian kereta api, rumah itu terdiri dari tiga gerbong. Satu ruang keluarga, satu ruang dapur dan satunya lagi ruang untuk umum. ”Memang rumah ini tadinya dibuat tiga rangkaian dengan dapur berada di tengah agar ia bisa diakses siapa saja,” ujar Sriwahyaningsih, pemilik rumah itu kepada saya di sela-sela kesi-bukannya. Konsep ruang publik itu diubah olehnya menjadi sebuah perpustakaan yang tidak seperti perpustakaan ke-banyakan. Tapi, sebuah perpustakaan anak berbasis lokal, bernama Salam. Kepen-dekan dari Sanggar Anak Alam.
”Saya ingin mengajarkan mereka (anakanak-red) membaca kehidupan dan alam. Karena hidup dan alam bukan sesuatu yang terpisahkan,” kata Wahyah—nama pan g gilan Sri Wahyaningsih—memberi alasan.
Wahyah adalah ibu rumah tangga. Lulusan Akademi perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ‘Yo’. Dilahirkan di kota Klaten, 42 tahun yang lalu. Anaknya lima: dua anak kandung, seorang anak angkat dan dua orang anak asuh. ”Ibu itu orangnya enak, enggak ngebeda-bedain anak,” kata Indah, 14 tahun. Indah ikut dengan Wahyah sejak umur dua tahun.

Wahyah juga seorang pustakawati. Salam merupakan buah karyanya di Bantul. perpustakaan berbasis lokal kedua yang
pernah ia bikin. Sebelumnya, di tahun 1989, ia pernah mendirikan perpustakaan serupa di Lawen, Banjarnegara. Untuk mencapai ke perpustakaannya di Lawen, kata Wahyah, diperlukan waktu berjalan kaki sekitar 10 kilometer. Di Bantul, ia ingin mengulang kesuksesannya seperti di Lawen, Banjarnegara itu.
Wahyah mengaku terilhami untuk mendirikan perpustakaan komunitas kem-bali, ketika ada salah seorang murid yang datang kepadanya. ”Saya bisa sukses seperti ini karena di waktu kecil saya sudah mengenal orang-orang besar seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Saya diajari diskusi,” kata murid itu seperti dikutip Wahyah.
Mahatma Gandhi pemimpin spiritual yang mengajarkan pesan moral dalam perlawanan melawan kolonialisme Inggris
di India. Sedang, Nelson Mandela adalah pemimpin golongan kulit hitam Afrika Selatan yang tertindas secara sosial. Melakukan perlawanan terhadap politik apartheid dan juga memimpin rekonsiliasi nasional Afrika Selatan.
Bagi Wahyah, buku merupakan sebuah kebutuhan. Memuat hasil karya pemikiran orang lain yang harus diketahui dan dipahami. Dan kini, buku-buku itu tak terjangkau oleh masyarakat banyak, baik dari segi jarak maupun dari segi finansial.
Dari segi jarak, misal. Karena perpustakaan yang disediakan pemerintah, belum bisa dijangkau masyarakat luas. Kebanyakan perpustakaan bikinan pemerintah itu berada di pusat kota. Sedang, di pelosok perdesaan hanya dilayani lewat perpustakaan keliling. Ini menunjukkan teori umum sentralisasi pembangunan di
Perpustakaan anak berbasis komunitas yang melayani warga perdesaan di Nitiprayan, Bantul, meng
Bermain di Salam. Perpustakaan anak yang dapat menjadi tempat bermain sekaligus belajar.
HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004
PUSTAKA
Adhitya Awan / HIMMAH
wilayah-wilayah tertentu. Terutama di perkotaan.
Dari segi finansial: harga buku makin menggila. Makin mahal. Tak terjangkau mereka yang berkantong pas-pasan. Ada indikasi telah terjadi proses kapitalisasi terhadap perbukuan.
Selain itu, Wahyah mengaku kecewa, karena merasa buku dinomorduakan. Tidak dijadikan prioritas, seperti laiknya produk komersial. ”Setiap penawaran-penawaran real estate atau sebagainya, selalu yang dikedepankan kehidupan hedonis: dekat dengan pusat kota, dekat dengan supermarket atau mal dan lainnya. Jadi terkesan, buku itu bukan sesuatu yang perlu dan belum menjadi kebutuhan,” lanjutnya.
Bisa jadi perpustakaan Salam adalah bentuk resistensi terhadap kondisi yang demikian.
pilihan Wahyah pada anak-anak karena, baginya, anak selalu memberi inspirasi kepadanya. ”Saya banyak belajar dari anakanak. Ada anak yang kritis, yang kadangkadang sampai saat ini tidak terpikirkan. Ada hal-hal sepele dari mereka yang memang tidak terpikirkan,” ung-kapnya.
Bukan hanya itu. Kehidupan anak yang diyakininya dengan kehidupan yang penuh dengan ajang bermain, harus dibiarkan bermain. ”Namun harus diarahkan. Jangan malah berbalik. Saat kuliah malah dijadikan ajang main-main karena masa kecil yang kurang terpuaskan. Sehingga ada statement: masa kecil kurang bahagia.”
Wahyah lantas bekerjasama dengan Trisno E. Situmorang, seorang pengelola buletin komunitas Omah . ”Saya punya cita-cita untuk merubah wajah dunia, walau tidak secara total. Maka saya ubah anak-anak, karena anak-anak adalah salah satu wajah dunia,” kata Trisno pada saya. ”Mulailah dari yang kecil dulu. Dari diri sendiri, dan mulai sekarang.”
* * *
SIANG itu, waktu menunjukkan pukul 1. Terlihat sekumpulan anak lelaki dan perempuan datang ke perpustakaan Salam. Menyempatkan waktu membaca buku.
”Enak sih baca di sini. Udaranya seger,” ujar Rosi, 10 tahun, salah satu di antaranya. Ia adalah siswa kelas lima di sekolah dasar Kumandaman. Tak jauh dari situ. Tak lama kemudian, Rosi terlihat sibuk membolakbalik bukunya. Demikian juga Ratri, 12 tahun.
”Saya suka di sini karena banyak bukunya,” katanya. Kala itu, Ratri tampak asyik membaca sebuah fabel: buku do ngeng tentang binatang.
”Soalnya tidak bayar,” tambahnya.
Walaupun di sekolah mereka ada per-
pustakan, namun keduanya mengaku, lebih merasa memiliki Salam . Mungkin juga karena konsep perpustakaannya yang dibikin beda dengan konsep perpustakaan orang dewasa. Untuk ini, Trisno E. Situmorang mengakuinya.
”Saya ingin mendesain ruang perpustakaan yang tidak baku seperti perpustakaan orang dewasa,” paparnya. Tidak terjebak pada pakem bahwa perpustakaan itu harus disamakan semua. Antara konsep perpustakaan mahasiswa dengan perpustakaan anak setingkat sekolah dasar (SD).
”Kalau konsep itu disamakan, maka akan menyebabkan anak itu tidak tergiur untuk membaca buku. Lain halnya dengan perpustakaan mahasiswa, walaupun perpustakaannya kumuh kayak gudang, mereka (mahasiswa- red ) pasti akan ke perpustakaan untuk cari referensi tugas mereka,” lanjut Trisno.
Bagi Trisno E. Situmorang, sebenarnya perbedaan perpustakaan dengan gudang amatlah tipis. ”Kalau perpustakaan itu terlalu dijaga ketat dan memiliki buku yang sangat banyak, namun sedikit orang yang bisa mengakses ke sana. Apalah bedanya dengan pusat gudang kertas bekas? Jadi buku itu hanya dijadikan sebagai pajangan saja,” jelasnya lebih lanjut. Kenyataan tersebut menumbuhkan inspirasi bagi kolega Wahyah di Salam itu. Bagaimana memfungsikan perpustakaan sebagai sebuah perpustakaan.
Ruangan berpenyangga empat tiang, berlantai keramik itu memang dipenuhi beratus-ratus buku: cerita fiksi, non fiksi dan beberapa novel. ”Dulunya sih ada 300 buku, itupun dari koleksi pribadi saja,” kata Wahyah. Ia bukan tipe orang egois dalam pengetahuan. Tidak ingin hanya dirinya yang mengetahui suatu hal lewat buku.
”Daripada buku itu saya baca sendiri, kenapa orang lain juga tidak ikut me m bacanya? Agar sama-sama mengambil manfaat dari itu semua.”
Memang tak ada tivi di ruang baca itu. Hanya ada sebuah tape compo tak menyala. Di sampingnya terdapat sebuah kursi panjang. Untuk istirahat, mungkin. Berjajar dengan sekeranjang tumpukan buku. Tampak pula keranjang roda yang terisi dengan buku. Di depannya, ada rak yang lagi-lagi terisi dengan buku. Tersusun rapi. ”Itulah yang membuat saya berpikiran agar anak-anak itu bisa aktif. Karena saat ini dengan teknologi anak-anak jadi pasif: cuma nonton tivi, main PS saja,” ungkap Wahyah. PS adalah akronim dari Play Station , jenis permainan impor modern yang digandrungi tidak saja oleh anak-
anak, tapi juga oleh tidak sedikit orang berumur.
perjalanannya untuk mendirikan perpustakaan tidak begitu saja berjalan mulus. Banyak orang-orang yang mengusiknya. ”Sampai-sampai saya dibilang tidak punya kerjaan. Ngurusin hal begituan,” kenang Wahyah. Itu terjadi, aku Wahyah, saat mendirikan perpustakaan komunitas baik di Lawen, maupun di Bantul.
Bukan hanya itu saja. Anak-anak yang diajak bermain ke rumahnya untuk membaca buku, malahan merusak bukubukunya. ”pertama mereka cuma liat-liat gambarnya, kemudian ditaruh, liat lagi, taruh lagi dan memang butuh pengertian karena banyak buku yang rusak,” kenang Wahyah sambil bernostalgia dengan masa lalunya.
Di balik pendirian perpustakaan itu, sebenarnya Wahyah punya maksud: untuk menyadarkan para orang tua bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dipelihara. ”Maka saya ajarkan anak-anak untuk kritis terhadap orang tuanya,” tegasnya.
Akibatnya, ia jadi sasaran kemarahan para orang tua.”Saya memang menunggu kemarahan orang tua mereka. Ketika mereka berkumpul, maka saya jelaskan kepada mereka bahwa anak itu adalah anugerah yang harus dijaga,” lanjutnya.
Kemarahan para orang tua anak-anak pun redam dengan terbentuknya kelompok belajar untuk orang tua. Kelompok belajar ini tidak ambil diam setelah mengetahui ada pelanggaran terhadap hak-haknya. Mereka pernah berdemonstrasi. Mendatangi kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DpRD) Banjarnegara karena, berdasar data yang mereka miliki, ada anggota dewan dianggap m e lakukan korupsi. ”Data itu mereka dapatkan dengan konkret. Tanpa man i pulasi,” kenang Wahyah.
Namun lagi-lagi Wahyah mendapatkan tantangan. Ia dituduh melakukan k e kacauan. ”Saya dianggap pecundang. Yang menggalakkan supaya masyarakat cerdas (seharusnya) kan pemerintah. Setelah mereka cerdas kok malah saya yang dianggap pecundang,” jawabnya enteng ketika ia dipanggil kepolisian tentang demonstrasi itu.
Sekarang ‘Wahyah’ telah berada dalam hubungan para orang tua dan anak-anak. Satu pesannya, bahwa, ”anak-anak cuma butuh figur saja,” ungkapnya, saat ber-gegas meninggalkan kami. Untuk memenuhi sebuah undangan. Meninggalkan anakanak yang masih terlihat asyik dengan
�� ��HIMMAH Edisi 01 /Thn.XXXVI I /M E I 2004 PUSTAKA
2004 diprediksikan orde baru bangkit lagi emangnye selama ini sudah mati?
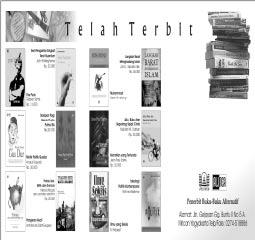
Seorang rektor diduga mengkorup biaya AC kampus Bisa jadi uang makan pun bakal diembat juga.
Banyak kalangan menilai UII ‘jago kandang’ Yang benar bukan jago kandang, melainkan betina yang di kandang melulu.
Gaji satpam UII sungguh memprihatinkan Mungkin uang UII habis untuk bikin gedung, fasilitas dan rapat-rapat pimpinan.
Gerakan Anti-politisi Busuk dideklarasikan Kalau gerakan anti-dosen, anti-rektor, anti-dekan busuk ada enggak ya?
Tidak sedikit aktivis mahasiswa yang jadi tim sukses para politisi atau jadi politisi Orde Baru Hitung-hitung menggadaikan idealisme untuk sementara waktu. Iklan

ABU NAWAS
