




Desember 2024


Lagi-lagi Biru melupakan keberadaan rol tersebut. Sudah dua tahun rol itu ada di tangannya, setelah seorang teman menyerahkannya dalam rangka buang sial Itu dari orang yang kusukai secara sepihak waktu masih sekolah, gadis itu mengaku Pakai saja. Kalau aku yang pakai, rasanya kayak berterima kasih pada orang itu atas setiap memori yang terekam di sana. Aku nggak mau berterima kasih
Berkali-kali Biru menolak. Rol ini sebuah kenang-kenangan pribadi Mungkin kalau teman tersebut memakainya sendiri hingga habis, perasaannya juga bakal tamat di foto terakhir? Tolakan Biru tidak mempan, hingga Biru pada akhirnya mengerti. Orang yang si gadis sukai akan segera menikah Tidak ada waktu untuk proses semacam itu. Semua harus enyah sekarang
Maka Biru, sebagai pemilik baru rol tersebut, mulai menuangkan ke dalam sana segala yang ia pandang Rol itu adalah kedua matanya sewaktu kali pertama menjejaki dunia orang dewasa Jelas isinya segera habis, sebab terlalu banyak kepingan dunia baru yang ingin ia reguk.
Dua tahun berselang dan Biru selalu lupa untuk mencucinya Barangkali rol itu terkutuk sejak awal–sejak diberikan pada si gadis oleh pemuda yang mengisi mimpi buruknya, hingga harus menemani Biru tertatih memasuki teritori buas nan asing.
Sudah saatnya melihat isinya

Puspa, main yuk.
Kalau ditanya ini apa, Biru juga tidak tahu cara menjawabnya Sebuah hubungan?
Sekadar selisih jalan? Semua menuntut Biru untuk mendefinisikan, semua menuntut Biru untuk menjelaskan.
“Kamu sudah dua puluh dua tahun,” tuding mereka, yang menurut Biru sama sekali tidak ada korelasinya Lantas kalau kepalanya sudah dua, dia otomatis tahu cara mendefinisikan, cara menjelaskan? Baik, kalau begitu tunggu sampai kepalanya tujuh Barangkali Biru jadi tahu cara mengungkap rahasia dunia
“Biru, cepetan! Ikut nggak?”
Sebuah pertanyaan dan sebuah lamunan yang terpecah
Keberuntungan bagi orang seperti Biru, Puspa tidak termasuk ke dalam “semua” yang tadi. Puspa cuma Puspa–tanpa perlu definisi, tanpa perlu penjelasan Sama seperti kelakuannya sekarang: pura-pura menyambung pagar kandang kuda, sekaligus pura-pura naik kuda juga Buat apa? Biru tidak tahu, tapi Biru tahu-tahu tertawa Baginya, Puspa selalu melakukan hal-hal luar biasa Mungkin itu yang membuat segala hal terkait Puspa memiliki hukum yang baru, hukum yang melanggar hakikat hukum itu sendiri: tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dijelaskan

Pergi ke kampus dan melihat wajah yang justru dikenal menjadi sebuah keistimewaan bagi Biru akhir-akhir ini Makanya, dia selalu menghabiskan beberapa detik lebih lama untuk memindai wajah orang-orang yang berselisih jalan dengannya di kampus. Menyusahkan memang–apalagi dengan masih adanya masker–tapi tak ada yang tahu setelah pertemuan itu mereka akan bertemu lagi atau tidak Jadi, Biru memilih untuk memastikan dirinya benar-benar sadar setiap bertemu orang-orang yang ia kenal
Kali ini dia tidak tahu siapa yang berseru duluan–dia atau Neri. “Ngapain di sini, Kak?” Biru bertanya “Biasa, nyelesaiin ini.” Dagu Neri menunjuk ke arah laptopnya “Kamu gimana kabarnya?”
“Gini-gini aja.” Tadinya, Biru hanya mau menjawab sampai di sana Titik Namun, di dunia ini memang ada jenis orang yang bisa membuat suatu titik meleleh jadi garis panjang Dan itu Neri, kakak tingkat yang kini sedang mendengarkan seluruh kabar Biru
Banyak hal sederhana yang menjadi perjalanan panjang karena Neri Bagi Biru, Neri merupakan pembuka gerbangnya menuju pengalaman-pengalaman pertama di kampus: pertama kali diwawancara untuk rekrutmen organisasi, pertama kali menjadi ketua magang BEM, pertama kali dipilih sebagai ketua biro, juga pertama kali mendapat job untuk memfoto orang-orang wisuda
Sekarang, seolah tahu bahwa waktunya di kampus ini sudah habis, dia bertemu dengan pembuka gerbangnya lagi Hanya saja, kali ini Biru bukan berjalan masuk–melainkan melangkah keluar.

Biru selalu meragukan kemampuan komunikasinya, tapi ketika ia memegang kamera dan menangkap rona kemerahan yang bersemu di pipi orang-orang yang memakai toga, mendadak lidahnya tidak kelu.
Mendadak Biru menjadi ahli dalam bertukar cerita tentang masa-masa di kampus, dengan orang-orang yang bahkan tak dikenalnya selama berkuliah.
kasih banyak, Bi! Kami pulang dulu. / Dengan senang hati, semoga kalian merona selalu
Tiga sepeda itu terlihat layaknya bocah kecil sedang jahil ikut numpang pada kendaraan orang: tertawa-tawa dengan kepala tengadah menerjang sinar mentari jam dua belas siang lewat setengah


“Sebenarnya dari mana asal mula orang Indonesia bikin kue kering untuk lebaran, ya?”
Kingkin menatap kakaknya dengan wajah lelah Ini kolaborasi perdana mereka berdua dalam membuat nastar dan 70% yang Biru lakukan adalah bertanya hal-hal trivial Lima belas persennya mencoba mencicipi selai nastar serta bahan kulit yang belum matang Lima belas persen lagi membuat nastar dengan bentuk yang jauh lebih bagus dibanding milik Kingkin–dan itu faktor utama yang menyedot energi adiknya.
“Ini teoriku,” kata Kingkin selagi telapak tangannya sibuk memutar-mutar adonan hingga berbentuk bola pejal “Kue-kue seperti ini, kan, asalnya dari negara-negara Eropa Mungkin Belanda yang membawanya masuk sewaktu zaman penjajahan Mereka makan kue waktu Natal Lalu, orang-orang kita ingin ikut-ikutan seperti mereka. Dibuatlah sesuai dengan selebrasi yang banyak dianut di sini ”
Biru mendengarkan dengan seksama “Serius?”
“Kataku juga apa, ini teoriku Kalau mau yang serius, cari di jurnal ”
“Tapi, kenapa kamu mengambil kesimpulan kalau orang-orang di sini suka ikut-ikutan?” Lama Kingkin diam.
“Karena memang seperti itu, Bi Kita semua suka memakai topeng yang sama karena terlalu takut berbeda ”
“Menurutku nggak nyambung,” bantah Biru langsung “Menurutku alasannya kadang sesederhana ‘Makanan ini enak’, ‘Oh, kita suka’, ‘Mari kita buat untuk hari spesial kita’ ”

Masih suatu misteri betapa cerita bisa mengantarkan kita mengenal orang-orang yang belum pernah kita lihat sebelumnya Biru menatap Bintang dan yang ditatapnya adalah pemuda yang pertama kali dilihatnya, tapi rasanya Biru sudah kenal Bintang sampai ke ukuran sepatunya. Atau lebih parah lagi, isi otaknya
Menempel pada Bintang, di jok belakang motor, adalah si pengantar cerita–si pengumpul data isi otak: Tavia. Tavia terkadang tidak dapat menerjemahkan otak
Bintang, jadi ia berkonsultasi pada Biru Biru lah yang harus menjabarkannya melalui pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh semua laki-laki tapi dirahasiakan dari perempuan (mungkin juga bukan dirahasiakan, mungkin hanya ada language barrier akut).
“Kok kalian cuma tatap-tatapan gitu?” protes Tavia “Kenalan, dong ”
Ah, satu lagi yang luput dari pengetahuan Tavia. Laki-laki biasanya tidak berkenalan. Tidak dengan cara seperti itu Biasanya lakilaki menghabiskan waktu beramai-ramai hingga pada suatu titik mereka sadar kalau mereka bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Baru setelah itu mereka berkenalan.
Jadi, Biru mengulurkan tangan dan tersenyum seramah yang ia bisa pada Bintang “Biru,” ia memperkenalkan diri dengan cara normal.
Sebab bagi Biru, pengetahuan semacam tadi tidak adil. Isi otak, aturan-aturan khusus, serta sandi-sandi tidak ada gunanya kalau cuma sebagian yang bisa menerjemahkan

Melepas anak bungsu adalah hal paling sulit bagi keluarga-keluarga se-Indonesia raya
“Benar bisa sendiri?” bergaung lagi dan lagi.
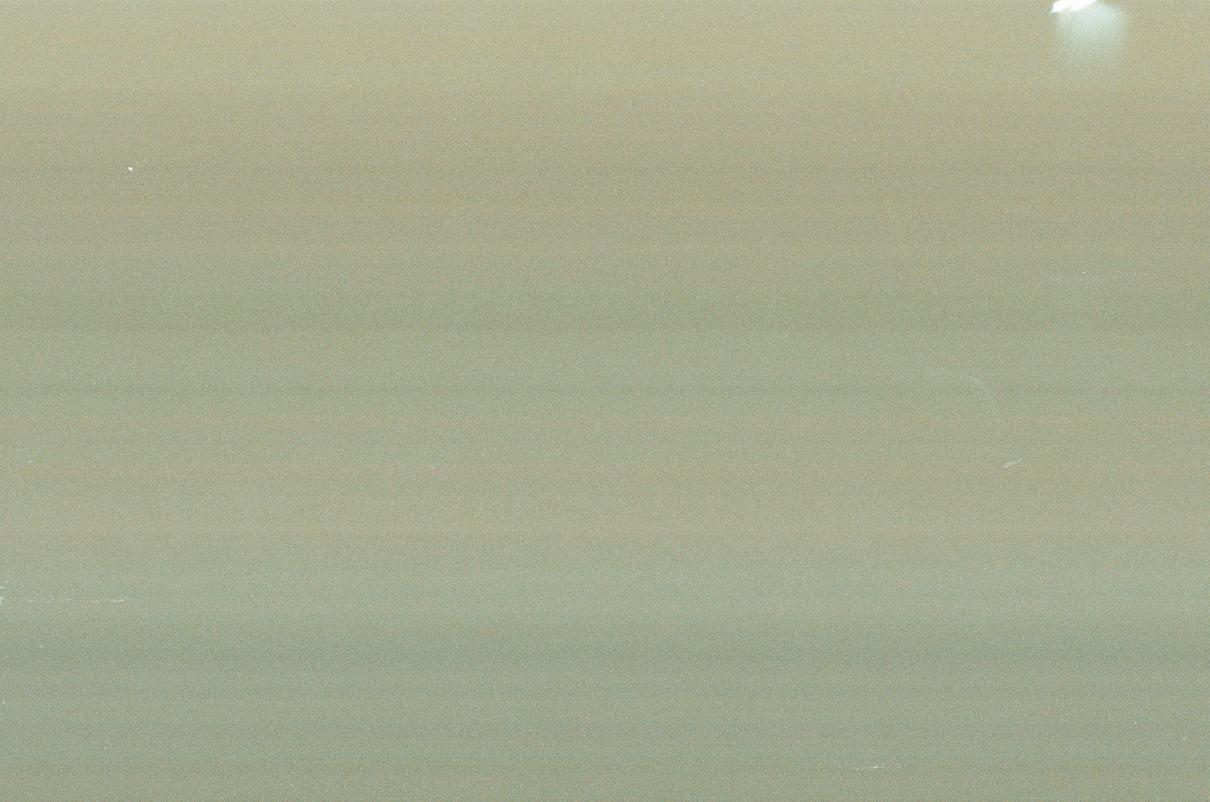
Apa yang dilihat manusia sewaktu penghujung hidupnya sudah di depan mata? Benar cahaya?
Atau sesuatu yang sama sekali lain–sebab bagaimana kalau hidup itu tidak ada ujungnya seperti kesalahpahaman akan bumi yang dulu disangka bertepi?

“Di usia segini, cuma ada dua kesempatan buat ketemu: kalau nggak pas lebaran, ya, pas pemakaman.”
Biru masih ingat kalimat yang keluar dari mulut Dita begitu tiba di pemakaman ayah teman mereka, empat tahun lalu
Kalimat yang hari ini sedang Dita tertawakan bersama Dina–kembarannya–dengan wajah yang sama sekali bukan milik orang tertawa
Biru ingat ayah Dina dan Dita, lelaki berpostur tegap yang selalu siap pasang badan manakala kedua anaknya kenapanapa. Juga tentang asap rokok yang mengepul sewaktu lelaki itu menepuknepuk punggung Biru, mewanti-wanti agar ia dan teman-temannya menjaga si kembar sewaktu geng kecil mereka hendak liburan keluar kota.
Sudah lama, sudah sangat lama. Kini foto berpigura yang dikelilingi rangkaian bunga itu menampilkan lelaki ringkih, digerus detak jam hingga pada akhirnya terbungkus kafan Tapi, Biru masih dapat merasakan sisa-sisa kekuatan lelaki itu pada udara yang mengisi tempat ini Semua orang yang hadir, seluruh pilu, digerakkan oleh kekuatan lelaki itu–sepanjang napasnya yang sekarang sudah berhenti.
Di hadapan dampak dari kekuatan tersebut, Biru tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sementara para perempuan saling memeluk dan menghapus air mata, Biru berdiri sekaku batang pohon Dia tidak pernah diajarkan caranya bergabung dalam kabung. Bahkan jika hatinya ikut koyak, dia tidak tahu cara menyampaikannya dengan layak.
Maka, yang Biru lakukan hanya memandangi si kembar Pandangan yang dibalas dengan dua pasang mata yang
membuat Biru berubah menjadi kelabu paling gelap Kemudian, satu per satu Dita tatap: orang-orang yang terakhir bertemu di zaman putih-biru dan tahu-tahu reuni di rumah duka.
“Nanti sering-sering ke sini, ya, kalian semua,” kata Dita “Rumah bakal sepi soalnya.”
Mendengar kalimat Dita, Dina tersenyum Senyum yang dilipat terlalu rapi untuk menjadi senyum sungguhan “Ayo kita foto dulu sebelum kalian pulang,” tambah Dina “Ayah gua pasti senang bisa menyatukan kembali kalian semua ”

Selama entah berapa detik, Biru mencaricari cara untuk berkedip
“Ini laptop lu?” ulangnya lagi dengan suara yang membuat Mauli meringis–diam-diam
mau pura-pura nggak saling kenal dengannya
“Lu udah nanya itu lima kali.”
“Lu satu-satunya teman gua yang laptopnya dilipat secara terbalik ”
“Ini tadinya punya uak gua,” jelas Mauli. “Dikasih gara-gara laptop gua yang lama rusak.”
“Keren ” Biru berdecak antusias Dirabanya permukaan laptop tersebut dengan mata berbinar. “Ini harganya bisa puluhan juta.” (Perkiraannya meleset banyak, tapi mereka sama-sama tidak tahu.)
“Bangga, kan, bisa berteman sama gua?”
Mauli mengacungkan jempol “Emang harusnya teman gua udah dua milyar dari dulu ”
“Sebetulnya, setelah gua pikir-pikir,” Biru memulai, mengingat-ingat kepribadian dia dan Mauli yang sejatinya lumayan mirip, “teman lu nggak sebanyak yang seharusnya karena lu kurang memperhatikan sekeliling.”
Kata-kata itu berusaha Biru tempatkan setidak berbahaya mungkin, tapi alis Mauli langsung turun–mau berperang satu sama lain “Gua memperhatikan, kok?” protesnya “Kalau gua aja nggak memperhatikan, terus lu apa?”
Biru semakin dalam berpikir, soalnya Mauli terlihat benar-benar yakin dengan dirinya sendiri Sambil berpikir, Biru iseng mencongkel lempengan merah yang tidak rata dari laptop Mauli–“HAH, LAPTOP GUA ADA STYLUS-NYA?!”
Giliran Biru yang berniat pura-pura tidak mengenal Mauli.
Di tangan Biru, stylus laptop berwarna hitam, dengan ujung merah yang kini berada di antara jempol dan telunjuknya
“Sumpah, gua baru tau laptop gua ada stylus bawaannya?!” Mauli bertepuk tangan dengan wajah terharu “Gua sampai beli universal stylus kemarin, tapi nggak kepakai soalnya jelek ”
“Tuh, kan ” Sekarang Biru berani menuduh “Lu memang memperhatikan, tapi cuma dari luar lingkaran Dari permukaan aja ” Kali ini tidak ada protes.


Biru curiga ia dan teman-temannya secara tak sengaja menjadi pelopor kegiatan badminton sekota Bogor Sekarang, setiap minggu ada saja foto lapangan beserta raket di Instagram–diunggah oleh berbagai gerombolan pemuda-pemudi yang mengenyam SMA negeri pada waktu bersamaan dengan Biru berseragam abuabu.
Begini, kalau memang benar Biru dan teman-temannya adalah pemantik api, Biru dengan bangga akan menunjuk Dayu sebagai legenda dari pergerakan ini Hanya saja, yang ditunjuk malah balik menunjuk Biru.
“Bukan gara-gara gua tau,” kata Dayu ketika mereka sedang istirahat di tengah permainan “Gara-gara elu, Bi Lu yang menginisiasi main badminton kalau lagi kumpul-kumpul ”
“Tapi, kenapa pada awalnya kita bisa kumpul-kumpul?” Biru tidak mau kalah–atau, dalam hal ini, tidak mau menang. “Itu karena lu, Day Lu sadar teman-teman kita banyak yang kesepian dan reuni adalah solusinya ”
“Tapi kalau reuninya kumpul-kumpul kayak biasa, nggak sebanyak ini orangnya Baru ketika lu ngajak reuni dalam bentuk badminton, orang-orang pada semangat,” kilah Dayu. “Lagian dari awal yang kita omongin kan penularan badminton sekota Bogor-nya Elu, Bi Lu pemantiknya ”
Biru mempertimbangkan ulang. Betul juga sih Hanya saja, dia merasa tidak berhak atas titel seperti itu Berbeda dengan Dayu, alasannya mengajak badminton sebetulnya murni karena memikirkan dirinya sendiri–Biru malas menghadiri reuni yang isinya kalau bukan gosip soal orang lain, ya pencapaian sendiri-sendiri Mana Biru tidak mengikuti kabar orang lain dan tidak punya pencapaian sendiri pula Itu namanya membunuh kesepian dengan ke-insecurean
Yah, melihat makin ramainya anggota badminton mereka, bahkan hingga menular ke alumni-alumni sekolah lain, Biru jadi sadar–rupanya bukan hanya dia yang merasa begitu.

Jakarta selalu pahit Tidak peduli semanis apa pun orang yang menemani Biru ke sana. Langit Jakarta selalu kelabu. Udaranya seperti seseorang baru saja meniupkan sarang laba-laba ke wajahmu–pengap dan lengket Biru tidak suka Jakarta Namun, lagi dan lagi, nasib membawanya ke sini Lagi dan lagi, hidupnya ditentukan oleh gedunggedung pencakar langit yang merunduk dan menatapnya tajam-tajam: Seberapa berharga ia untuk masuk ke dalam sana?

“Ini gaya bapak-bapak kalau lagi liburan,” deklarasi Biru pada Puspa Mencoba mencipta atmosfer menyenangkan di kota sibuk yang angkuh ini
Tanggapannya cuma tawa kecil dan sekilas pandangan tidak mau kalah Pertanda Biru harus siap-siap melihat gaya tandingan.

“Ini gaya ibu-ibu,” Puspa memulai. “Gaya ibu-ibu kalau?” Biru menagih lanjutannya
“Kalau apa, ya?” Gadis itu bingung sendiri. Padahal dia sudah susah-susah berhenti menuruni tangga dan berbalik menghadap ke arah Biru dengan pose seperti itu–tapi otaknya tidak mampu mendefinisikan itu pose ibu-ibu macam apa. “Yang jelas, gua pernah lihat pose kayak gini di status WhatsApp ibu gua.” Karena Biru tidak menanggapi penjelasannya, Puspa menambahkan dengan ragu, “Apa cuma ibu gua aja, ya, yang begitu?”
Tawa Biru lolos. Padahal, tadi Biru hening bukan karena meragukan Puspa atau apa Biru hening karena Biru jadi ingin ikut mendefinisikan–Biru jadi ingin menjelaskan
Bukan tentang gaya foto. Tentang hubungan mereka Tentang bagaimana Biru ingin sekali memfoto gaya Puspa yang seperti itu, mencetaknya dan memajangnya di ruang tamu untuk dipamerkan ke bocahbocah yang akan memanggil mereka kakek dan ne–
Biru berdeham dengan telinga bersemu merah Pikiran macam apa itu?


Toga dan jubah wisuda Biru dirampok oleh rombongan berbatik yang hendak melancarkan foto wisuda yang tertunda
“Itu toga sama jubahnya cuma satu?” Biru, di depan pagar rumahnya, keheranan “Cuma yang punya gua aja?”
Cengiran serupa muncul di wajah keempat oknum dalam mobil tersebut–bahkan tak repot-repot untuk turun dan mampir sebentar ke rumah Biru “Kita nggak ada yang bawa ”
“Terus, nanti kalian foto barengnya gimana?”
“Nanti si Usman pakai atribut, sisanya mah jadi groomsmen aja,” jawab Saddam asal.
“Atau nggak, si Usman pakai toga, Faroz pakai jubah, lu pakai slayer IPB, gua pakai selempang cumlaude, ” usul Faisal sambil menoleh ke arah Saddam “Deal?”
“Deal. ”
Kepala Biru langsung pusing Untung bukan dia yang jadi fotografer mereka

Kala Biru bertandang lagi ke rumah Dina dan Dita, memang ada keheningan yang tidak biasa di rumah tersebut Padahal, tiap kali Biru ke sana, yang ia temui cuma si kembar Jarang-jarang ia bertemu dengan orang tua mereka
Aroma keabsenan sang ayah begitu kuat, sampai-sampai Dina dan Dita harus mengajak teman-teman mereka untuk datang dan menggantinya dengan aroma lain: aroma bakar-bakar di teras rumah.
“Aturan sih pacar, ya, yang diundang ke sini kalau malam Minggu,” celutuk Gaza
“Waduh, lagi kurang semangat cari pacar.”
Dita menengadah dari aktivitasnya mengipasi sate. “Soalnya udah nggak ada bokap gue yang jadi wali kalau nikah nanti ”
“Berarti sekarang nggak ada target, nih?”
tanya Arif Biru diam saja memperhatikan Arif, walau agak curiga sobatnya itu bakal melakukan manuver gombal tertentu
“Ada lah Justru makin digeber sama abangabang gua,” Dina yang menjawab “Mumpung si Mamah masih ada, katanya.”
“Kalau gitu–” Tuh, kan Arif mulai melaksanakan aksinya.
“Kalau gitu, kita makan sate aja sekarang Mikirin jodohnya nanti,” sela Biru cepatcepat Waktunya belum tepat, Rif Ada duka yang masih menggantung di udara, tidak bisa dienyahkan walau dikipasi sekencang apa pun.

Badminton lagi Cari kerja, makan-makan, badminton. Itu-itu saja siklus hidup Biru saat ini–walau target kantor, teman makan, dan tim badmintonnya berbeda-beda.
Hari ini giliran teman-teman sejak SMP yang mengisi rutinitasnya. Kalau Biru boleh membandingkan dengan skill mereka zaman SMP, agaknya yang terjadi justru penurunan Lemak-lemak orang dewasa membatasi pergerakan mereka, tubuhtubuh itu kini kebanyakan duduk-duduk saja di kursi kantor
“Seru juga ya,” kata Ahmad “Rutin kayak gini yuk.”
“Ayo,” jawab semuanya–walau sama-sama tahu itu kesepakatan yang tidak akan ditepati

Sudah Biru bilang, kan, kalau salah satu pilar utama hidup orang dewasa adalah makanmakan bersama teman?
Katanya, orang-orang suka kasihan kalau melihat laki-laki makan Biru tidak pernah mengerti apa maksudnya, sampai dia menyaksikan proses Naufal, Aryo, dan Aga melahap hidangan di hadapan mereka sampai tandas.

Jadi, apa hal yang hanya bisa kita lihat kala kita menikmati hidup secara perlahan?
Semuanya, Biru, semuanya. Kita bisa melihat keutuhan dari semuanya.
Bagaimana kalau
ada yang tidak ingin melihat itu semua?
Bagaimana kalau ada yang ingin tidak merasakan apa-apa?
Tapi, Biru, bagaimana kalau melambat justru membuat ia sadar bahwa itu bukan yang ia inginkan?

Kesialan selalu menimpa orang-orang yang nggak pernah rutin berolahraga dan baru saja berniat mau memulainya.
Biru mengerjap dengan rahang menganga sedikit, menyimak kiamat kecil yang terjadi di depannya
“Kalau tulang gue retak, gimana? Kalau gue gegar otak, gimana? Kalau–” “Keseleo aja kok itu.” Dia akhirnya berani bersuara
Gadis yang tengah berbaring itu mengerang. “Kita bukan anak kecil lagi, Bi. Kalau kenapa-kenapa, nyawa kita nggak ada sembilan kayak dulu.”
Biru tidak pernah merasa nyawanya ada sembilan “Tapi kita juga masih dua puluh dua.”
Pada usia dua puluh dua tahun, temantemanmu lebih memilih berpose depan kamera dibanding memberikan pertolongan pertama
(Tidak ada korban jiwa dalam foto ini )
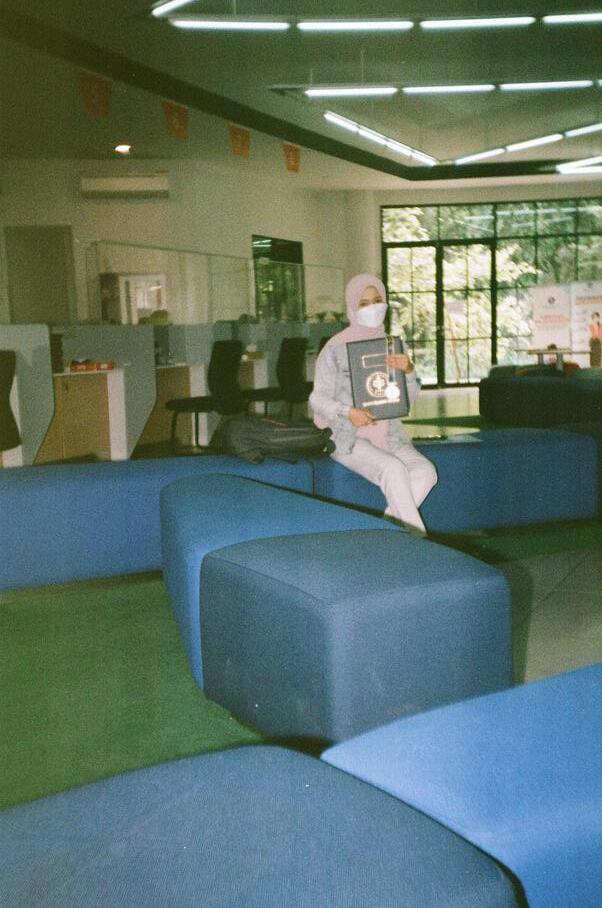
Banyak ijazah terbengkalai sejak pandemi Pandemi beres, ijazah sudah lama terlupakan di kepala Ijazah-ijazah itu mendekam di lemari universitas, menunggu-nunggu dijemput oleh pemiliknya yang tidak bangga-bangga amat dengan selembar kertas tersebut. Atau mungkin, dulu pernah bangga Kemudian kebanggaannya luntur, leleh dalam kubangan realita yang siap sedia menenggelamkan orang-orang baru dewasa.
Banyak sekali dokumen yang harus diurus sendiri selepas kita punya label di atas tujuh belas. Idealnya sih begitu–diurus sendiri, mandiri Hanya saja, yang namanya orang tua, kadangkala bersikeras menemani. Meski yang ditemani justru lebih tahu seluk beluk pendaftaran yang kini serba online Meski beliau hanya akan menunggu di sisi, sambil memastikan semuanya berjalan tanpa halangan yang berarti.


Rasanya opsi potongan rambut makin hari makin sedikit. Biru ingat, waktu kecil dulu, dia didorong untuk mencoba segala macam gaya rambut oleh ayahnya (ralat, bukan cuma didorong, tapi dijadikan eksperimen tanpa persetujuan) Dari botak plontos hingga mohawk, semua pernah berkuasa di kepalanya Beda dengan sekarang. Potongan rambut Biru ya itu lagi, itu lagi
“Oke, nggak, Pus?” Biru bertanya pada Puspa yang baru saja menekan shutter kamera analog.
“Kan gua belum bisa lihat hasilnya, harus dicuci dulu.”
“Bukan fotonya Rambut gua, maksudnya ”
Puspa mematut-matut dengan ekspresi datar. “Sama aja kayak biasa,” katanya. Sekelebat kecewa yang melintas di wajah Biru langsung membuat Puspa tersenyum geli “Sama bagusnya, maksud gua ”
Jemari Biru menggaruk dagu, otaknya mempertimbangkan komentar Puspa sungguhan atau tidak “Bosan juga ya, model rambutnya gini. Cuma beda panjang pendeknya aja ”
Bukan salah tukang cukur. Opsi yang diberikan tukang cukur selalu sama banyaknya Masalahnya ada di diri Biru sendiri. Mungkin juga di mata orang-orang yang memandang Biru, dunia yang memandang Biru. Mungkin juga masalah ini bukan benar-benar masalah Biru cuma makin lama makin mafhum kalau dia 1) tidak lagi seberani dulu, 2) bisa memilih potongan rambut yang membuatnya nyaman, 3) harus menampilkan diri sesuai dengan lingkungan yang ia masuki Tidak semua tempat kerja menerima kalau dia punya rambut dikucir kuda dengan warna senada dengan namanya–bukan berarti ia pernah mencoba.
“Gua suka kok. Rapi,” kata Puspa. “Nggak membosankan?”
“Nggak. Rambut lu nggak pernah membosankan, soalnya ada ini–tambah banyak ” Tangan Puspa terulur, menyentuh rambut Biru.
Ah iya. Rambut Biru tidak pernah membosankan-membosankan amat Ada helai-helai kelabu itu, terselip di antara semua yang pekat, entah kenapa memang hadir jauh lebih cepat Penanda umurnya, pemberontakan kecilnya.


Rasanya aneh kalau Biru mengingat bagaimana ia dan Puspa selalu berada di sisi satu sama lain selama bertahun-tahun, tanpa pernah benar-benar mengenal–setidaknya hingga beberapa bulan lalu
SMP yang sama SMA yang sama Fakultas yang sama Kesampingkan itu semua, toh pada akhirnya Biru tetap harus memutar seribu cara biar bisa berinteraksi dengan gadis tersebut pada awalnya. Ia putuskan nyalinya cuma sebatas minta bantuan lewat perantara kawan–yang pada berbagai momen terpaksa Biru singkirkan demi dapat kesempatan berduaan
Bagaimana cara orang dewasa mengutarakan isi hati, ya?
Biru dengan segala kabut di pikirannya juga tidak menyangka kalau pada akhirnya dia sendiri yang justru ingin mendefinisikan apa-pun-ini yang terjalin di antara ia dan Puspa Bisa jadi karena ada terlalu banyak peristiwa selepas memakai toga–dan senyum gadis itu efektif mengurai segala kekusutan jalinan benang yang kini tampaknya menggantikan otak Biru. Di antara semua ketidakpastian hidupnya, setidaknya Biru memerlukan satu saja hal yang pasti
Ditatapnya ketoprak di piring Puspa. Semakin sedikit dan semakin sedikit Seperti keberaniannya Ini bukan kali pertama Biru menyukai seseorang, tapi kenapa tidak pernah sesusah ini sebelumnya?
Pasti karena dunia orang dewasa Pokoknya akhir-akhir ini, tak peduli apa yang melenceng, itu salah usianya yang tidak lagi remaja Biru merasa dia jadi kurang bijak karena berpikiran seperti itu, tapi yang ada di kepalanya cuma benang kusut
Akhir hubungan di dunia orang dewasa cuma dua: menikah atau menjadi tamu pernikahan. Ketoprak di perut Biru jadi mendesak keluar lagi Apa tidak bisa mereka terus bermain-main di sekitar kampus saja, mencari tempat duduk-tempat duduk yang sudah Puspa hapal letaknya, memilih menu makanan di warung sekitar seperti ini?
Ah, ketoprak Puspa semakin sedikit
“Pus, Pus.”
Yang dipanggil menengadah “Kenapa, Bi?” “Itu, kucing.” Tahu-tahu Biru pasang alibi, menunjuk kucing yang sedang menunggu remah makanan jatuh dari meja Biru tersenyum terlalu lebar, seperti orang yang dinominasikan sebagai top 3 penduduk paling bodoh se-Jawa Barat. “Bukan, bukan kucing ” Puspa meletakkan garpu dan sendoknya. “Kenapa sih, dari tadi? Kayak mau ngomong sesuatu ” Biru terdiam Aduh, Puspa sudah serius begitu. Jantungnya jadi menggedor-gedor rusuk
“Bagaimana cara orang dewasa mengutarakan isi hati, ya?”
Mereka berdua sama-sama menatap satu sama lain untuk waktu yang terasa beberapa detik terlalu lama Bagi Puspa, itu karena karena dia sama sekali lengah Biru akan menanyakan hal tersebut Bagi Biru, itu karena dia tidak menyangka mulutnya akan berkhianat dan menyuarakan isi hatinya dalam mode loudspeaker
Cengiran Puspa muncul perlahan “Nggak usah diutarakan juga gak apa-apa ”
Biru mendengkuskan tawa tertahan “Udah ketahuan, ya?”
Maka Puspa ikut tertawa, walau wajahnya lama-lama merah juga “Udah ” “Jadi?”
“ Jadi ”
Biru bahkan tidak tahu kaidah bahasa
Indonesia macam apa yang mereka gunakan. Ini sama sekali tidak seperti dua orang dewasa yang membicarakan perasaan mereka, tapi ya sudahlah Yang penting dia sudah punya jawaban kalaukalau seseorang bertanya mereka ini apa
Lembaran hasil cuci film analog itu bergerak cepat di tangan Biru, seperti kartu yang sedang di-riffle. Sekilas pandang saja dan Biru tahu rol tersebut (nyatanya) tidak terkutuk
Ironisnya, rol yang berasal dari patahan hati temannya itu justru mengingatkan Biru tentang betapa beruntungnya ia Objek dalam foto-foto tersebut hampir semuanya manusia–jejak bahwa ada banyak yang sudi menemani Biru melewati rumitnya dunia selepas sarjana, meski ini sama-sama kali pertama mereka semua beranjak dewasa
Semua cerita dalam zine ini adalah karangan fiksi–meski ada realitas yang terselip
terima kasih untuk teman-teman yang telah kami pinjam namanya.
terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca sampai halaman ini.
“Sudut Pandang Warna Biru” edisi dua kami akhiri di halaman ini sampai jumpa @sudutpandangwarnabiru



