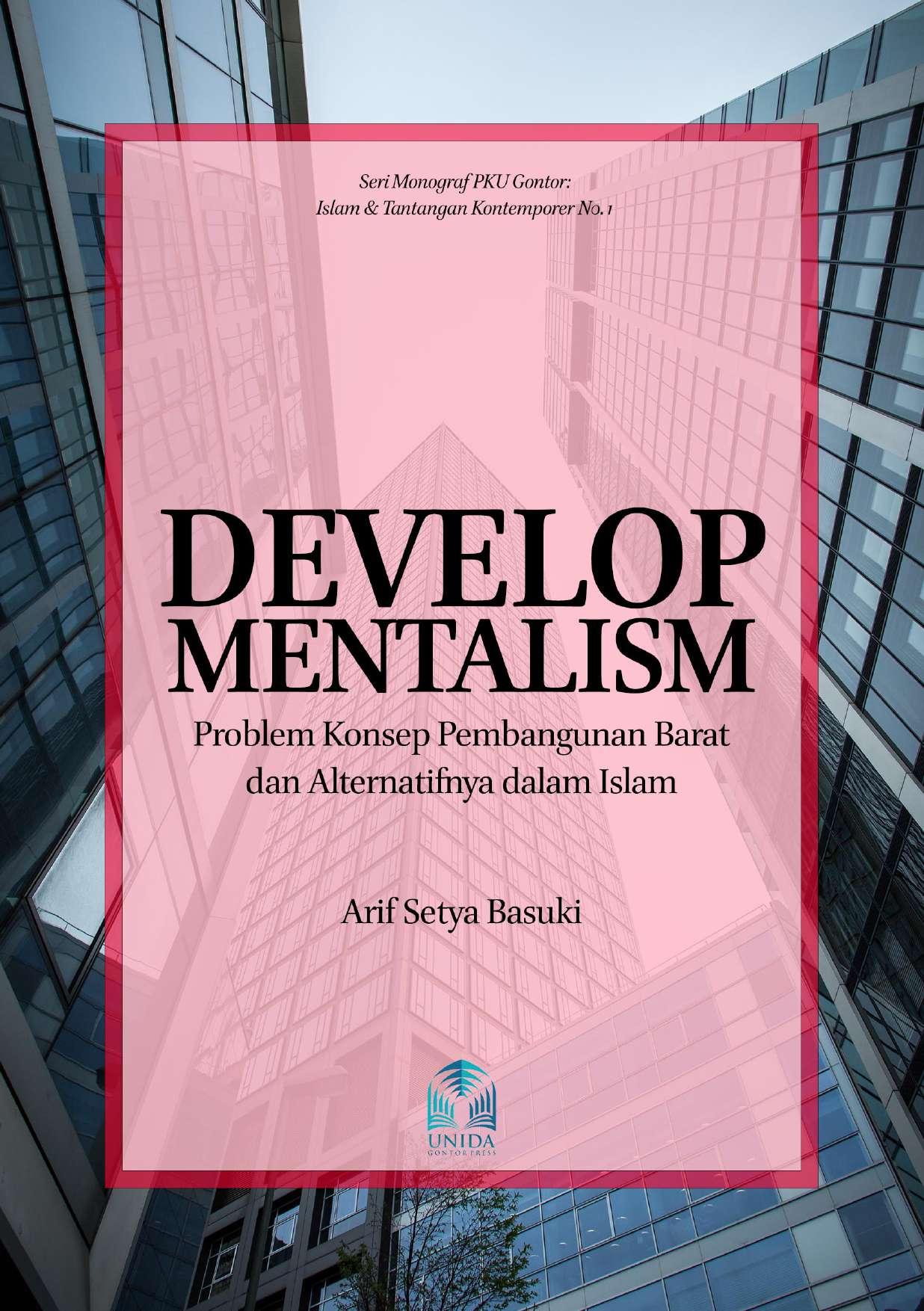
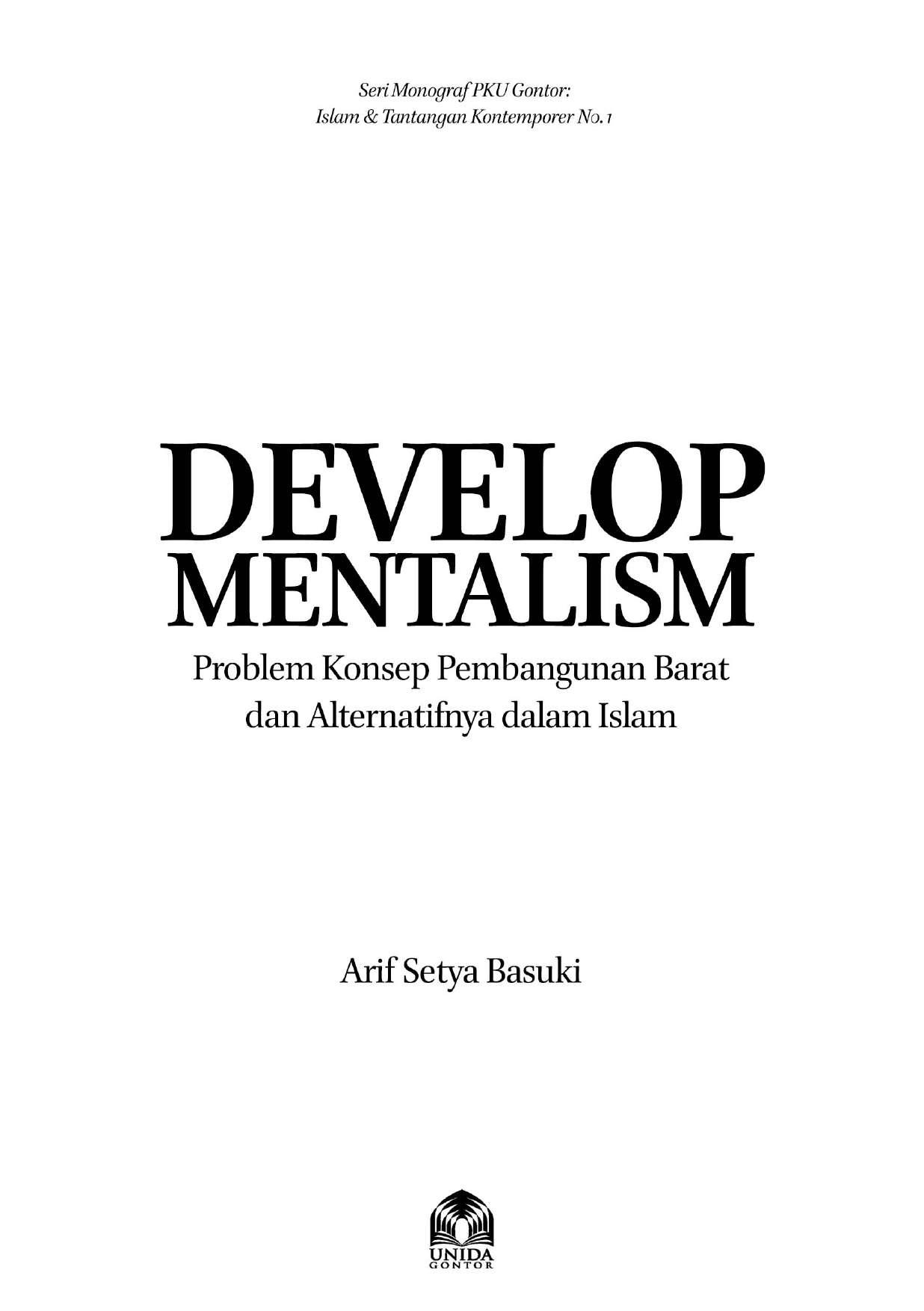


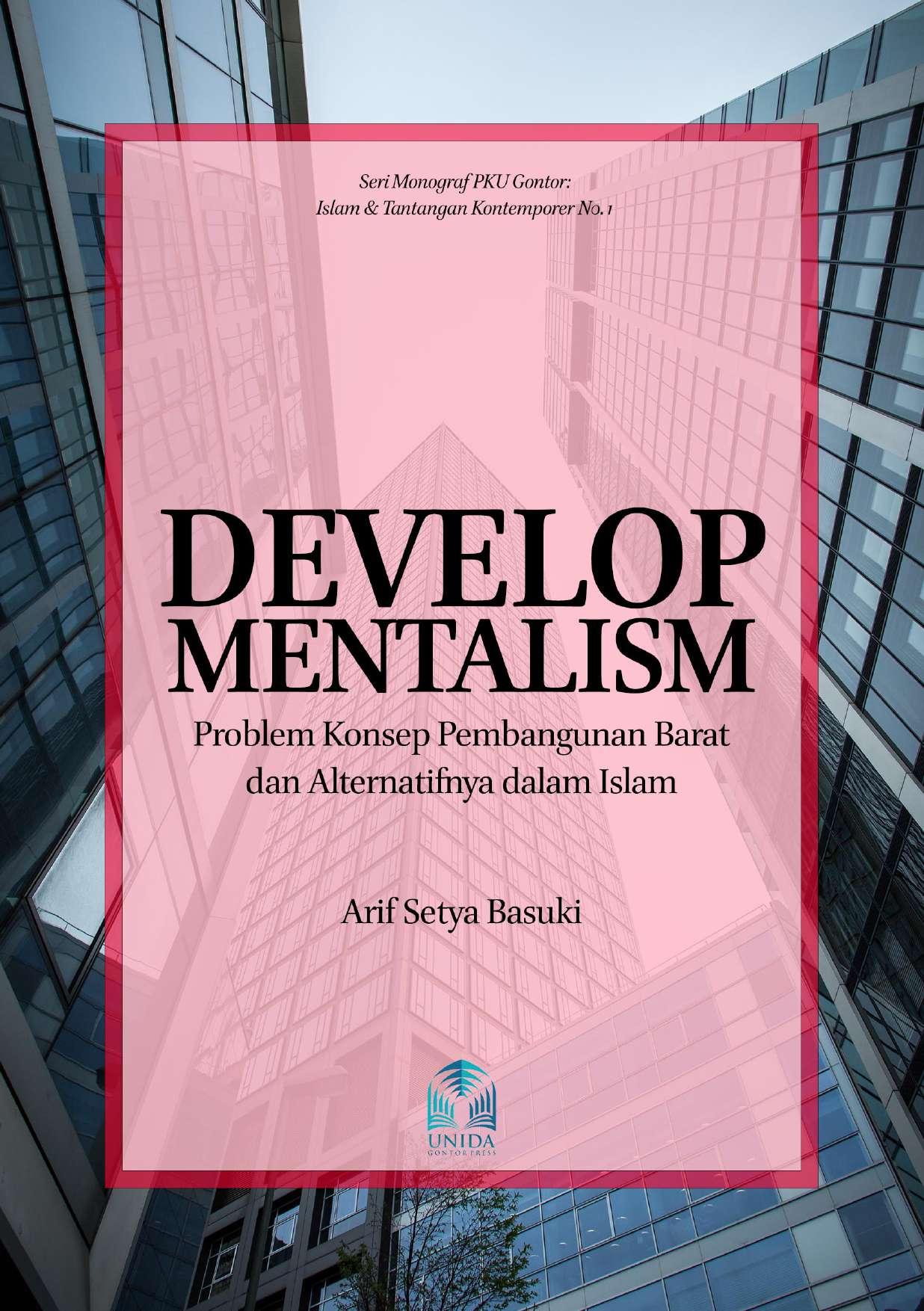
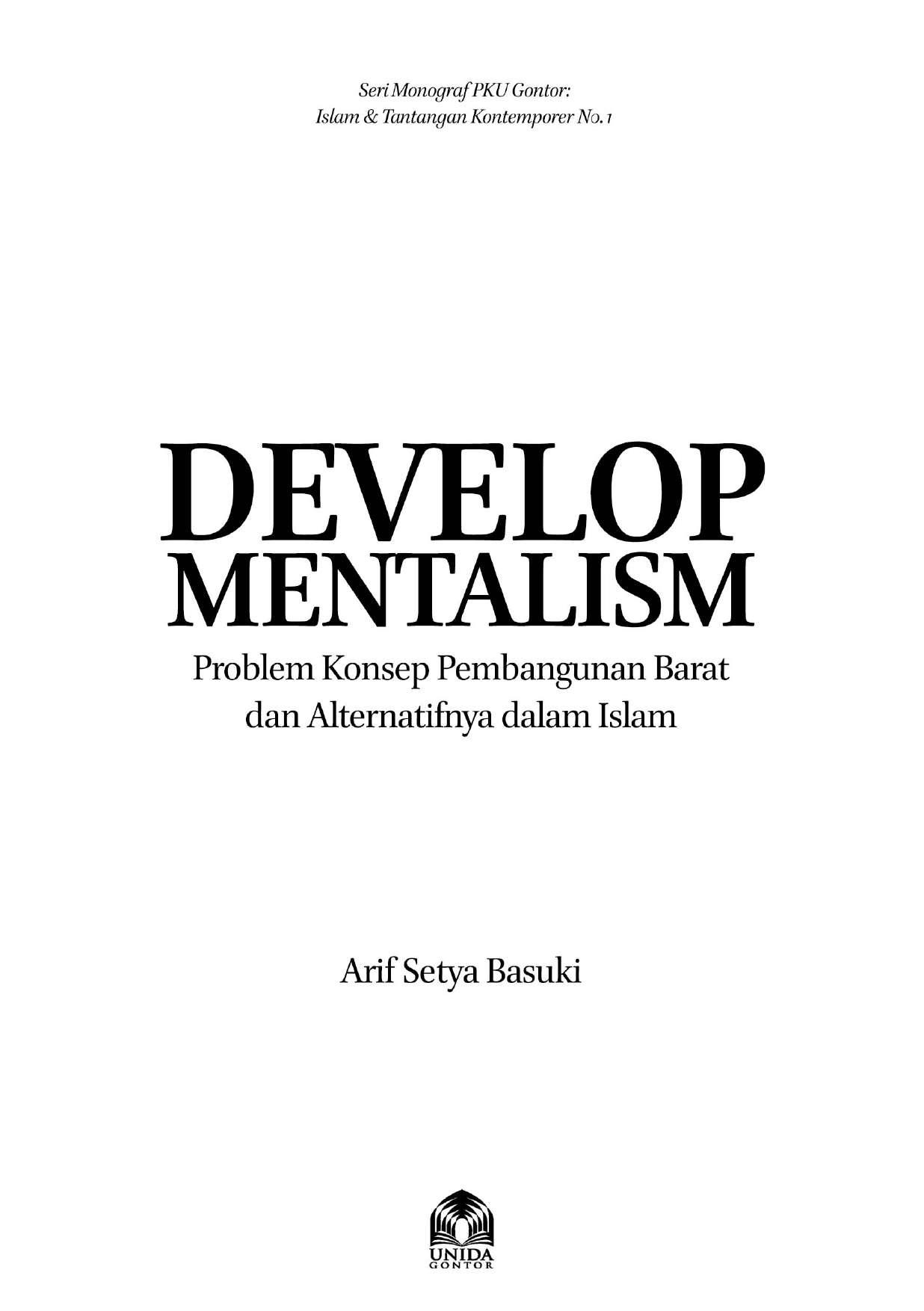

Direktur Program Kaderisasi Ulama
Universitas Darussalam Gontor
Pengantar Direktur PKU UNIDA Gontor
Pengantar Editor
Pengantar Penulis
Pendahuluan
Mengenal Pembangunan
a. Etimologi dan Terminologi
b. Globalisasi dan Universalisasi Istilah Pembangunan
c. Teori-teori Pembangunan
Pokok-pokok Pemikiran
a. Subjek dan Objek Pembangunan
b. Tujuan-Tujuan Pembangunan
c. Langkah Pembangunan
Tinjauan Kritis dan Implikasinya di Indonesia
a. Falsafah Pembangunan Bangsa
b. Intrusi Worldview dalam Pembangunan
Alternatif Konsep Pembangunan
a. Manusia: Subjek dan Objek Pembangunan
b. Fitrah: Tujuan Pengislahan
c. Langkah Pengislahan
d. Peran NGO’s dalam Pengislahan
Penutup
Daftar Pustaka
Palembang, tahun 2000. Pagi itu, Kota Palembang, masih rasakan sejuk angin reformasi. Sejuk yang tak pernah sejenak mengenal jeda, berleha menikmati hari. Sejuk Kota Palembang itu yang kemudian menjadi saksi, akan hawa nafsu manusia yang tiada habisnya.
Sepotong koran, tergeletak. Masih hangat, baru keluar dari mesin pencetak. Namun, koran tersebut tak berdaya dalam muramnya sebuah ruang, di sudut Kota Palembang. “Jum’at, 29 September 2000. Sebanyak 28 orang, termasuk tiga anak-anak, masuk rumah sakit karena kebocoran amonia,” demikian koran berkata.1 Beberapa puluh meter dari lembaran koran, berbaring pula lusinan tubuh manusia meregang nyawa.
Palembang tengah berduka. Pasalnya, apa yang terjadi bukanlah yang terakhir, dan bukan yang pertama. Adalah semenjak PT Pusri, salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara, membuka sebuah pabrik di pinggir Sungai Musi pada 1963, masyarakat mulai memiliki masalah polusi air dan udara. Selama Orde Baru tidak ada yang mereka bisa lakukan, tersebab tuduhan komunis yang selalu menekan, bagi mereka yang kritis dan tunjukkan sikap melawan.
Reformasi lalu memberi harapan. Namun bertahun-tahun, mulai dari
LBH sampai WALHI, dan berbagai organisasi lingkungan lainnya terus berjuang membela rakyat dan bumi. Namun apa daya, walau terus merusak tanah Musi, Pusri terus bertahan hingga hari ini.2 Bahkan seorang petugas di Palembang bersaksi, di level nasional sudah Pusri berikan dampak ekonomi. Jadi, apa yang sudah berlalu tidak perlu dianggap kembali.3
1 Elizabeth Fuller Collins, Indonesia Betrayed: How Development Fails (Honolulu: University of Hawaii Press, 2007), 93.
2 Aji YK Putra dan Robertus Belarminus, “Terpapar Gas Amonia, Ratusan Warga di Samping PT Pusri Sesak Napas” diakses pada https://regional.kompas.com/read/2018/11/02/19042621/terpapar-gas-amonia-ratusan-warga-di-samping-pt-pusri-sesak-napas?page=all 3 september 2017.
3 Collins, Indonesia Betrayed, 96.
Ilustrasi peristiwa di atas sesungguhnya hanya contoh kecil, dari ribuan bahkan jutaan lainnya, nasib tragis orang-orang yang menjadi korban pembangunan. Ironis memang. Pembangunan yang seharusnya menjadi kata positif dan membawa ‘perubahan’ menuju hal yang lebih baik, justru memberikan hal sebaliknya bagi masyarakat. Menggunakan tameng ‘pembangunan ekonomi’, maka kesenjangan sosial diabaikan. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin. Dengan ‘pembangunan ekonomi’, lingkungan dihancurkan. Sungai, udara, dan bahkan tanah tercemar dengan polusi. Akhirnya, masyarakat sendiri yang menjadi korban dari pembangunan.
Masyarakat namun begitu, tidak akan pernah bisa terlepas dari pembangunan. Mulai dari level internasional, PBB memiliki proyek pembangunan seperti Sustainable Development Goals (SDG’s).4 Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB juga turut mengikuti agenda tersebut.5 Dampaknya perencanaan pembangunan di level nasional sampai regional, dengan variasinya masing-masing,6 juga mengikuti agenda pembangunan berkelanjutan PBB.7 Pemerintah Desa kemudian sebagai institusi pemerintahan terkecil dalam sistem pembangunan nasional, juga wajib menyelaraskan agenda pembangunan mereka dalam dokumen-dokumen terkait seperti RPJMDes.8 Karena itulah di manapun WNI tinggal, baik di perkotaan ataupun pedesaaan, dari Sabang sampai Merauke, sedikit atau banyak ia akan selalu dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas pembangunan.
Secara global, dukungan para ilmuan terhadap aktivitas-aktivitas pem-
4 Menurut PBB, Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah seperangkat tujuan (17) dan target (169) yang ditujukan untuk menggapai apa yang belum diselesaikan oleh Millenium Development Goals (MDG’s). Lebih jauh lagi lihat United Nations, Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, (diambil dari https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Su stainable%20Development%20web.pdf, 2019)
5 Secara resmi pada tahun 2017 pemerintah RI telah menyepakati penyelarasan rencana pembangunan nasional Indonesia dengan SDG’s. Lebih lanjut lihat Perpres RI No. 59 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6 Untuk penjelasan mengenai masalah ini, silahkan rujuk UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7 Guna mengetahui lebih lanjut model integrasi antara perencanaan pembangunan nasional dan regional dengan agenda pembangunan berkelanjutan, silahkan lihat konten dan lampiran Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI No. 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), adalah dokumen yang menjadi dasar pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. RPJMDes disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya silahkan rujuk ke UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
bangunan juga semakin gencar selepas era kolonialisasi berakhir. Selama enam dekade silam, banyak dibentuk institusi khusus yang mengkaji permasalahan pembangunan di kampus-kampus internasional. Institute of Development Studies yang terbentuk di University of Sussex pada 1966 misal, menjadi titik awal studi pembangunan memasuki dunia akademis.9 Sekarang, kita bisa menemukan studi pembangunan di berbagai kampus dunia, seperti di SOAS London (Eropa), Queensland University (Australia), Nagoya University (Asia), atau UC Berkeley (Amerika). Studi-studi pembangunan juga masuk ke kampus-kampus di Indonesia. Contoh misal di salah satu universitas terbesar di Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Pembangunan tersemat pada nama dua program studi di UGM, yaitu Pembangunan Wilayah (Fakultas Geografi) dan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik). Para lulusan dari kampus-kampus tersebutlah yang kemudian mengisi jajaran penting dalam pemerintahan yang mengurusi permasalahan pembangunan negeri ini, seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Negara (Bappenas).
Perhatian yang sangat luas tersebut rasanya cukup untuk melihat betapa berpengaruhnya konsep pembangunan bagi kehidupan manusia. Namun begitu, perlu dipahami juga bahwa konsep “pembangunan” juga tidak muncul dari ruang hampa.10 Ia lahir dalam suatu konstruksi sosial atau budaya, yang membuatnya sarat akan nilai tertentu.11 Nilai-nilai tersebut, bisa jadi membawa kepentingan yang selaras dengan visi keindonesiaan dan keislaman, namun bisa juga tidak. Keika konsepsi dan realisasi pembangunan tidak sesuai dengan visi bangsa, maka insiden-insiden seperti yang terjadi dengan PT. Pusri di atas yang terjadi. Guna mengetahui letak permasalahan konsepsi-konsepsi pembangunan, diperlukan adanya investigasi yang lebih lanjut.
Kajian awal menunjukkan bahwa istilah “pembangunan” dalam konteks
9 Rob Potter, et. al, Key Concepts in Development Geography, (London: SAGE Publications, Ltd, 2012), 4
10 Kata development dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi (1) Perkembangan, (2) Pembangunan atau (3) Pertumbuhan. Kata pembangunan atau perkembangan akan digunakan secara bergantian dalam tulisan ini. Lebih lanjut lihat John M. Echols and Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 179.
11 Untuk penjelasan mengenai masalah ini, silahkan rujuk Gilbert Rist, History of Development, (London: Zed Books, 2008), 44.
pembangunan wilayah setidaknya dapat dilacak berasal dari kata “development”. Konsep tersebut mendapatkan momentumnya di dunia internasional pertama kali saat Presiden AS, Harry S. Truman, menyampaikan pidato pada tahun 1949.12 Amerika Serikat adalah salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia pada saat itu.13 Maka wajar jika diasumsikan perkembangan konsep “development” selanjutnya juga erat hubungannya dengan barat,14 khususnya barat era modern.15
Konsep dan karakter pembangunan modern tersebut yang sebenarnya telah menuai berbagai kritik.16 Beberapa misal mengatakan bahwa development memiliki karakter eurosentris.17 Konsepsi dan penerapan pembangunan fokus mengarah pada karakteristik eropa yang jelas memiliki banyak perbedaan dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Secara aplikatif dapat dilihat bagaimana proyek-proyek pembangunan menjadi penyebab meningkatnya polusi dan limbah industri, sampai ke menipisnya sumber daya alam serta degradasi lingkungan, seperti dalam kasus PT Pusri.18 Namun sayang, tidak banyak kajian yang secara ekstensif menjelaskan asal muasal konsep “development”, bagaima-
12 Pidato ini terkenal dengan julukan “Point Four”. Dalam pidato tersebut kata underdeveloped pertama kali digunakan dalam skala internasional. Kata tersebut dipakai untuk memberikan label bagi negara (dengan kriteria dari AS) yang belum maju atau berkembang. Lihat Rob Potter, et al, Key Concepts in Development Geography, 19.
13 Perlu dibedakan antara “salah satu” dengan “satu-satunya” negara yang berpengaruh. Lihat bahasan mengenai ini dalam Derek Leebaert, Grand Improvisation: America Confronts the British Superpower, (New York: Farrar, Straus, and Biroux, 2018)
14 Barat yang dimaksud bukan hanya mata angin atau lokasi geografis, tapi alam pikiran pandangan hidup. Seperti juga Barat, Kristen, Islam, bahkan Jawa adalah sama-sama pandangan hidup. Meski sama, namun kesamaan hanya pada tingkat genus, bukan spesies. Masing-masing memiliki karakter dan elemennya sendiri-sendiri. Lebih jelas mengenai ini lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Refleksi atas Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam, (Jakarta: INSISTS – MIUMI, 2012)
15 Prof. Hamid Fahmy Zarkasyi mendefiniskan barat modern sebagai periode sejarah dalam peradaban barat yang persisnya terjadi saat kebangkitan masyarakat Barat dari abad kegelapan kepada periode pencerahan, abad industri dan abad ilmu pengetahuan. Asasnya adalah rasionalisme, sekularisme, empirisme, dualisme, dan humanisme. Lebih lanjut lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis, (Ponorogo: Penerbit CIOS-UNIDA, 2010)
16 Untuk penjelasan mengenai masalah ini, silahkan rujuk Aram Ziai, ‘Post-Development 25 Years after The Development Dictionary’, Third World Quarterly 38, no. 12 (2 December 2017): 2547– 58, https://doi.org/10. 1080/01436597.2017.1383853; Stuart Corbridge, ‘“Beneath the Pavement Only Soil”: The Poverty of Post‐development’, The Journal of Development Studies, 1998, https://doi.org/10.1080/00220389808422549; Piers Blaikie, ‘Development, Post-, Anti-, and Populist: A Critical Review’, Environment and Planning A: Economy and Space 32, no. 6 (June 2000): 1033–50, https://doi.org/10.1068/a3251.
17 Kajian khusus mengenai hal ini lihat Ozay Mehmet, Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic Development Theories (London & New York: Routledge, 1999).
18 Proyeksi tersebut bisa dilihat dalam Donella H. Meadows, The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (New York: Universe Books, 1972); Terbuktinya prokyeksi bisa dilihat lebih lanjut dalam G Turner, ‘A Comparison of the Limits to Growth with 30 Years of Reality’, Global Environmental Change, 18.3 (2008), 397–411 <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.05.001>.
na ia berkembang, respon atau kritik terhadapnya, dan lebih jauh lagi bagaimana ia dipandang dari perspektif keindonesiaan dan keagamaan, khususnya agama Islam. Padahal, bangsa ini memiliki Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan.
Guna merespon problem di atas, tulisan ini akan mencoba mengkaji konsep development/pembangunan beserta alternatifnya. Buku ini memang tidak diniatkan untuk menjawab semua masalah yang berhubungan dengan diskursus pembangunan, namun akan lebih fokus membahas permasalahan fundamental beserta solusinya. Bagian pertama akan membahas mengenai konsepsi dan teori pembangunan secara umum. Bagian kedua menjelaskan mendiskusikan elemen-elemen kunci yang ada pada tiap konsep dan teori pembangunan. Refleksi kritis akan dampak konsepsi pembangunan yang umum digunakan di dunia modern sekarang ini akan disampaikan pada bab ketiga. Terakhir, akan disampaikan alternatif konsepsi pembangunan dari perspektif Islam yang harapannya dapat menjadi solusi problematika relasi antara pembangunan dan agama.
a. Etimologi dan Terminologi
Istilah pembangunan sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Asal mula pembangunan, atau development, setidaknya sudah mulai disebut dalam kamus Oxford terbitan tahun 1897. 19 Secara etimologis istilah tersebut memiliki bentuk awal develop yang berasal dari Bahasa Prancis (desvoleper, desvolosper atau desvolper) bermakna “membuka lipatan”. Asal kata ini sudah muncul dalam Bahasa Inggris, “disvelop”, dengan makna untuk membuka, untuk mengurai, atau untuk membebaskan pada abad ke-15. 20
Penggunaan kata pembangunan beberapa abad kemudian juga tidak mengalami perubahan yang drastis. Bentuk lengkap ‘development’ (develop v. + - ment) yang mulai muncul pada 1752-1851 memiliki makna yang tidak berbeda jauh dari develop, yaitu “mengeluarkan potensi” atau “membuka gulungan”. Catatan lain pada periode ini adalah istilah pembangunan ternyata digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hal-hal yang imateriil (pikiran manusia,21 ide,22 pemikiran manusia23) sampai ke hal materiil seperti bendera pasukan.24 Perkembangan penggunaan istilah pembangunan pada periode selanjutnya namun begitu, lebih didominasi untuk dunia materiil, khususnya biologi.
19 James A. H. Murray, A New English Dictionary on Historical Principles, vol. III D&E (London: Clarendon Press, 1897), 280.
20 Murray, III D&E: 279.
21 “That very philosophy, which had been adopted to invent and explain articles of faith, was now studied only to instruct us in the history of the human mind, and to assist us in developing its faculties and regulating its operations” Warburton, Introduction to Julian, (1750)
22 “One may develope an idea: it is what God has taught us to do in His successive revelations. But one cannot add to it, least of all in another age. Julius Charles Hare & Augustus William Hare, Guesses at Truth, (London: Taylor and Walton, 1848), 4.
23 “... in the progressive development of human thought, ....” Ibid, 250.
24 “When the red rose banner was developed in front of the Lancasterian army...” Alicia de Lacy, An Historical Romance, Vol.3. (London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternosteb-Row, 1814), 94.
Termin development mulai umum dipakai dalam dunia biologi semenjak awal abad 19. Sekitar tahun 1794-1863, hal tersebut ditunjukkan dengan digunakannya pembangunan secara bergantian dengan kata lain yang tenar pada saat itu, yaitu evolusi (evolution).25 Seperti evolusi, pembangunan bermakna mengeluarkan dari kondisi laten atau dasar; produksi kekuatan alam, energi, atau bentuk materi baru.26 Hal lain yang menarik adalah kata evolusi sendiri memiliki akar kata yang dekat dengan develop, yaitu evolvere yang berarti to roll out atau membuka gulungan.27 Mulai dari saat ini istilah pembangunan juga dapat dikategorisasikan penggunaannya kedalam dua hal. Pertama adalah dalam konteks proses, yaitu evolusi atau penyelesaian bertahap, dan kedua adalah dalam artian hasil, yaitu hasil dari evolusi tersebut.28
Penggunaan dan asal mula kata development yang dekat dengan kata evolusi di bidang biologi penting dicatat. Hal ini selaras dengan gagasan-gagasan yang muncul pada saat tersebut, sebuah ide yang disinyalir mempengaruhi pemikiran evolusi Darwin melalui terbitnya The Origin of Species. Contohnya adalah gagasan social evolutionism yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh seperti Auguste Comte29 atau Herbert Spencer.30 Konsep evolution atau development selepas Darwin juga digunakan dalam dunia sosial oleh tokoh lain seperti Edward Burnett Tylor31 atau Lewis Morgan.32
25 Murray dalam OED menyebutkan salah satu makna dari kata development: “Development of races of plants and animals: the same as evolution; the evolutionary process and its result.” Murray, A New English Dictionary on Historical Principles, III D&E: 280.
26 “evolution or bringing out from a latent or elementary condition; the production of natural force, energy, or new form of matter “, Murray, III D&E: 280.
27 Evolusi berasal dari kata Latin e (keluar) dan volvere (bergulung, berguling). Lebih lanjut lihat James A. H. Murray, A New English Dictionary on Historical Principles, Vol III D and E, (London: Clarendon Press, 1897), 353; Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2005), 222.
28 Gradual evolution or completion; also, the result of such an evolution or completion’, lihat dalam The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language (Florida: Trident Press International, 1996), 350.
29 Auguste Comte, adalah seorang tokoh yang terkenal dengan teori perkembangan masyarakat dari masyarakat teologis, metafisik, ke positif. Lebih lanjut lihat Kenneth E. Bock, Darwin and Social Theory, diambil dari Journal Philosophy of Science Vol. 22, No. 2, (The University of Chicago Press, 1955), 126.
30 Stephen K. Sanderson, Evolutionism and Its Critics: Deconstructing and Reconstructing an Evolutionary Interpretation of Human Society, (New York: Routledge, 2005), 27-30; namun perlu dicatat juga bahwa istilah Social Evolutionism atau Social Darwinism mulai tinggalkan, kritik mengenainya bisa dilihat dalam Donald M. Borchert, Encyclopedia of Philosophy, Vol. 3, 2nd Edition, (USA: Thomson Gale, 2006), 479.
31 “its various grades may be regarded as stages of development or evolution, each the outcome of previous history, Edward Burnett Tylor, Primitive Culture Vol.1, (London: John Murray Publication, 1871), 1.
32 Lihat dalam Robert A. Nisbet, Social Change and History: Aspects of the Western Theory of Development, (New York: Oxford University Press, 1969), 161.
Dipakainya istilah pembangunan dan evolusi secara bergantian adalah salah satu tanda lahirnya developmentalism¸atau pembangunanisme dalam dunia modern. Pembangunan dalam hal ini menjadi sebuah ideologi. Sebuah keyakinan dimana perubahan sosial terjadi menurut sebuah pola yang sudah ditetapkan sebelumnya, bersifat evolusioner, atau maju dengan arah yang sudah diketahui.33 Arah gerakan masyarakat dapat diibaratkan seperti tumbuhan atau hewan yang berevolusi. Pembangunan dengan berbagai bentuknya pada pandangan ini adalah sebuah hal yang natural, atau keniscayaan.
Hal menarik lain adalah sebelum dunia modern, anggapan bahwa ‘pembangunan’ adalah sebuah hal yang wajib atau niscaya juga dapat ditemukan. Sebelum era modern, tentu ide pembangunan muncul dalam berbagai ekspresi seperti pertumbuhan (growth) atau perubahan (change). Namun anggapan bahwa pembangunan, pertumbuhan, atau perubahan itu adalah sebuah hal yang niscaya dapat ditemukan sejak abad pertengahan (Agustinus) bahkan oleh pemikir klasik (Aristoteles).34
Artinya, anggapan bahwa pembangunan sebagai sebuah hal yang niscaya memiliki akar sejarah yang dalam, khususnya sejarah pemikiran Barat.
Permasalahan pertama yang muncul adalah, walaupun pembangunan dianggap sebagai sebuah keniscayaan dan memiliki akar sejarah yang panjang, secara istilah definisi termin development masih kabur.
Hingga sekarang, definisi pembangunan masih berbeda-beda tergantung siapa ahli yang mengutarakan.35 Potter misal mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang bertujuan memperbaiki orang dan tempat guna meningkatkan kebaikan bersama.36 Tokoh lain seperti Amartya Sen mendefinisikan pembangunan sebagai proses memperluas kemerdekaan
33 Topik ini akan dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya. Jan Nederveen Pieterse, ‘Dilemmas of Development Discourse: The Crisis of Developmentalism and the Comparative Method’, Development and Change 22 (1991): 6.
34 Gilbert Rist, The History of Development: From Western Origins to Global Faith, 3. ed., 2. impr (London: Zed Books, 2010), 49.
35 Silahkan lihat pembahasan definisi development yang problematik dalam Gilbert Rist, ‘Development as a Buzzword’, Development in Practice 17, no. 4–5 (August 2007): 485, https://doi. org/10.1080/09614520701469328.
36 Robert Potter, Geographies of Development: An Introduction to Development Studies (London & New York: Routledge, 2018), 8.
sejati seseorang.37 Perbedaan tersebut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana belum adanya konsensus mengenai definisi dan interpretasi dari “development”.38 Hal yang menarik adalah, walaupun istilah pembangunan belum pernah benar-benar mendapatkan definisi yang memuaskan, ia kemudian dapat dengan mudah meluas dan diterima oleh dunia internasional.
b. Globalisasi dan Universalisasi Istilah Pembangunan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, development bukanlah sebuah konsep yang asing ketika dunia memasuki abad ke 20. Namun hal yang perlu ditekankan adalah, istilah development belum benar-benar digunakan secara luas oleh dunia internasional hingga Perang Dunia II usai. Dengan kata lain, walaupun kesadaran akan pembangunan bukanlah hal yang baru, namun pembangunan sebagai sebuah ‘proyek internasional’ adalah sebuah fenomena kontemporer yang membutuhkan perhatian secara khusus.
Salah satu momen penting yang menandai dimulainya penggunaan konsepsi pembangunan dalam dunia internasional adalah pidato Presiden Harry S. Truman, pada 20 Januari 1949.39 Truman dengan pidatonya yang dijuluki “Point Fourth” atau Program Point Fourth40 tersebut menggunakan momentum yang ada sebagai pemimpin dunia pertama untuk memulai era baru, yaitu era pembangunan.41 Berikut adalah kutipan dari pidato tersebut:
“Fourth, we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of un-
37 Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy’. Lihat lebih lanjut dalam Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Anchor Books, 2000), 1.
38 David Simon, ‘Dilemmas of Development and the Environment in a Globalizing World: Theory, Policy and Praxis’, Progress in Development Studies 3, no. 1 (January 2003): 8, https://doi.org/10.1191/1464993403ps048ra.
39 Philip McMichael, Development and Social Change: A Global Perspective 6th ed, (London: SAGE Publications, 2017), hal. 44-45. Selanjutnya diringkas Development and Social Change.
40 Lebih lengkap lihat naskah asli pidato dalam Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, Year 1949, 5 (Washington DC: United States Government Printing Office, 1964), 112–16.
41 Gustavo Esteva, Development, dalam Wolfgang Sachs, The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as Power, 2nd ed, (London: Zed Books, 2010), 1. Selanjutnya diringkas Development.
derdeveloped areas.
More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate. They are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas.
For the first time in history, humanity posesses the knowledge and skill to relieve suffering of these people.
The United States is pre-eminent among nations in the development of industrial and scientific techniques. The material resources which we can afford to use for assistance of other peoples are limited. But our imponderable resources in technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible.
I believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their aspirations for a better life. And, in cooperation with other nations, we should foster capital investment in areas needing development.”42
Mungkin pada awalnya tidak terasa ada hal yang spesial dalam pidato tersebut. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat konsep-konsep kunci yang selaras dengan Zeitgeist atau spirit zamannya pada pidato Truman.43 Apa yang diserukan Truman dan Amerika Serikat kepada dunia melalui pidato tersebut tentu bukan kebetulan. Setiap kata yang diucapkan didasarkan pada konsep, dan setiap konsep tersebut memiliki sebuah kepercayaan tertentu. Dengan kata lain, apa yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah ekspresi dari sebuah worldview44 tertentu.
42 Bold dari penulis. Lebih lengkap lihat naskah asli pidato dalam Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, Year 1949, 5, (Washington DC: United States Government Printing Office, 1964), 112-116.
43 Gilbert Rist, History of Development, (London: Zed Books, 2008), 72.
44 Menurut Ninian Smart, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Lebih lanjut lihat Ninian Smart, Worldview: Crosscultural Exploration of Human Belief, (New York: Charles Scibner’s Son),
Pembangunan/development dalam Point Fourth, adalah salah satu konsep terpenting yang disampaikan Truman. Konsep underdeveloped (wilayah tertinggal) muncul di paragraf pertama, yang diidentifikasi sebagai permasalahan. Istilah development (pembangunan) kemudian muncul sebagai solusinya dalam paragraf keenam. Walau istilah underdeveloped pernah digunakan sebelumnya,45 ia baru relevan dalam skala internasional saat Truman menjadikannya konsep kunci dari kebijakan
Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada saat itu.46 Konsep tersebut yang kemudian menjadi inti worldview baru dalam melihat relasi antara barat dengan sisa dunia yang lain. Bahwa semua orang di dunia, walaupun dengan kecepatan masing-masing, bergerak dengan tujuan yang sama.47 Negara utara seperti AS berada di depan, sedangkan sisa dunia yang lain berada di belakangnya.48 Hal tersebut mempengaruhi pandangan banyak ilmuan dan pengambil kebijakan, misal dalam perspektif hubungan internasional.
Melalui pembangunan, dapat dirumuskan sebauh relasi baru dalam melihat interaksi antara negara satu dengan lainnya paska era kolonialisasi. Contohnya, perlu dipahami bahwa sebelumnya, hubungan “dunia utara” dengan “dunia selatan” secara umum dimaknai dalam relasi-oposisi antara negara penjajah dan negara terjajah.49 Berdasarkan pandangan ini, mereka yang menjajah ataupun terjajah berada dalam dua dunia yang terpisah, berbeda, atau saling berhadapan. Apabila pihak terjajah atau dunia selatan menginginkan perubahan, maka dampaknya adalah konfrontasi antara keduanya yang tidak akan terelakkan, seperti dalam bentuk perjuangan kemerdekaan.
Ketika Truman menyampaikan Point Fourth, sebuah konsep 1-2.
45 Gilbert Rist, The History of Development (London & New York: Zed Books Ltd, 2008), 72.
46 Gustavo Esteva, ‘Development’, in The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, ed. Wolfgang Sachs (London: Zed Books, 2010), 2.
47 George Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development, (London: Zed Books Ltd), 28.
48 Hal ini bisa dilihat pada contoh pidato Truman sebagai berikut: “...for making the benefits of our scientific advances and industrial progress” atau “The United States is pre-eminent among nations in the development of industrial and scientific techniques...”
49 Rist, The History of Development, 73.
dengan pandangan baru untuk melihat dunia diumumkan. Pandangan tersebut sekarang melihat bahwa semua manusia atau negara di bumi harus bergerak di jalur yang sama dan bercita-cita pada satu tujuan, yaitu pembangunan.50 Penggunaan konsep berkembang/developed dengan kurang berkembang/underdeveloped menawarkan bentuk relasi baru antar negara-negara yang akan berinteraksi paska kolonialisme. Makna kata underdeveloped memberikan sugesti bahwa dunia ini secara umum tidak lagi terbagi menjadi dua. Semuanya ibarat berada dalam satu jalan, walaupun ada daerah yang berada di depan (negara maju) dan ada yang berada di belakang (negara berkembang/kurang berkembang).51 Secara konseptual, perbedaan diantara ‘berkembang’/’kurang berkembang’ tidaklah absolut, karena sekarang semuanya berada di jalur yang sama. Konsep kurang berkembang bukanlah lawan dari ‘berkembang’, layaknya antara ‘terjajah’ dengan ‘penjajah’ pada masa kolonialisme. Analogi lain yang dapat digunakan adalah seperti evolusi tumbuhan dalam biologi, ‘belum berkembang’ hanyalah bentuk awal/embrio/biji yang belum sempurna dari tumbuhan dewasa. Pembangunan atau evolusi (mengafirmasi penggunaan istilah yang muncul pada abad ke 19) dengan begitu adalah jembatan untuk menghubungkan keduanya.52
Simplifikasi yang mungkin bisa dibuat adalah, hubungan antar negara berubah dari i) pemusnahan dan penaklukan (abad ke 16) menuju ii) eksploitasi pada kolonialisasi (abad ke 19), dan berakhir dengan integrasi dengan adanya bingkai konsep pembangunan pada abad ke 20-21. Berbeda dengan hubungan yang terjadi dalam kolonialisme, sekarang kedua pihak berada di lapangan yang sama.53 Satu mungkin berada di belakang yang lain, tapi mereka dapat terus mencoba (atau setidaknya berharap) untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Hal inilah kenapa development dapat disebut sebagai jalan baru untuk melihat atau menata
50 George Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development, (London: Zed Books Ltd), 3.
51 Development and Social Change, 45.
52 Gilbert Rist, History of Development, 75.
53 Rist, The History of Development, 74.
dunia ini.54
Konsep pembangunan yang telah naik menjadi standar utama dengan begitu telah menjadi worldview baru. Ia menganggap pembagian dunia adalah sebuah kewajaran, yang memproyeksikan takdir tunggal bagi seluruh negara. Legitimasi dari Truman menjadi awal titik naturalisasi pembangunan, yang membuatnya univesal sehingga sulit untuk dipertanyakan.55 Saat itu juga puluhan bahkan ratusan negara mendapatkan status ‘kurang berkembang’. Walaupun dengan segala keragaman kultural dan potensi yang ada, sejak saat itu mereka tidak lagi menjadi diri sendiri. Identitas mereka pada saat itu hanyalah cerminan realitas negara lain. Kebebasan mereka dalam kemerdekaan telah tereduksi dalam hal mendefinisikan diri sendiri. Hal ini juga menjelaskan kenapa teks rujukan dalam dunia ekonomi disebut An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, dimana ‘progres kekayaan’ dari setiap negara dihasilkan dari ‘kecenderungan alami akan manusia’.56 Progres atau pembangunan dengan begitu bukanlah sebuah pilihan, ia tidak dapat dihentikan dalam alur sejarah.57
Konsep development yang dikatakan sebagai alternatif pengganti kolonialisme juga dikatakan solusi bagi perbedaan ideologis antara kapitalisme dengan komunisme. Tujuan akhir tiap negara, yaitu kesejahteraan, utamanya bicara mengenai bagaimana tingkat produksi bisa meningkat, bukan perdebatan mengenai struktur sosial, kepemilikan sarana produksi, atau peran negara itu sendiri. Tanpa memperhatikan perdebatan semacam itu, pembangunan dengan simpel menawarkan standar baru dimana AS bisa berada di puncak rantai makanan.
Truman dan Amerika Serikat bukan tanpa persiapan ketika menyampaikan Point Four. Sebagai pemain utama pasca Perang Dunia II, AS
54 Development and Social Change, 4.
55 Perlu dicatat juga bahwa istilah pembangunan itu sendiri secara inheren menandakan adanya ‘peningkatan’ atau ‘kemajuan’, sehingga ia dapat menjadi candu yang membuatnya cenderung mudah ditoleransi atau dipromosikan walaupun memiliki dampak yang berbahaya. Rist, ‘Development as a Buzzword’, 485.
56 ‘That order of things which necessity imposes in general, though not in every particular country, is, in every particular country, promoted by the natural inclinations of man.’ Adam Smith, ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations’, Journal of Political Economy 13, no. 1 (December 1904): 502, https:// doi.org/10.1086/251119.
57 Rist, The History of Development, 40.
sudah mengeksekusi berbagai rencana untuk membentuk ulang sistem ekonomi dunia sebelum Point Four sampai ke publik. Contohnya adalah melalui Marshall Plan,58 yang kemudian dilanjutkan oleh program Bretton Woods.59 Melalui program inilah kemudian muncul dua badan yang memengaruhi perkembangan ekonomi dunia hingga sekarang: World Bank dan International Monetary Fund (IMF).
Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bagaimana konsep pembangunan tidaklah bebas nilai/kepetingan dan dipengaruhi oleh siapa yang membentuk. Era Pembangunan secara terencana dan terstruktur telah dimulai oleh Barat selepas era kolonialisasi. Walaupun penjajahan secara politik sudah berhenti, muncul bentuk penjajahan baru. Pada hari tersebut, milyaran manusia di dunia mendapatkan status: maju atau tertinggal. Sadar atau tidak, mereka mendapatkan sebuah status dari kacamata orang lain yang bahkan mungkin tidak mengenal diri mereka. Uniknya, tanpa penolakan, mereka mengikuti penilaian tersebut, dan meninggalkan nilai-nilai mereka sendiri. Itulah salah satu bentuk penjajahan intelektual yang mungkin juga terjadi pada bangsa Indonesia. Negeri dengan segala keanekaragaman ini dapat dengan mudah menjadi “negara berkembang”, dan harus mengikuti jalan pembangunan yang dibuat oleh orang lain.
Konsepsi pembangunan di atas yang kemudian akan dikembangkan secara lebih komprehensif menjadi teori-teori dan metodologi dalam dunia akademik di Barat. Lebih tepatnya mulai tahun 1960an, melalui departemen-departemen yang berkaitan dengan Development Studies di Eropa dan Amerika. Tidak ketinggalan, ilmuan-ilmuan dari Indonesia akan turut menggali ilmu pembangunan di kampus-kampus tersebut. Ilmuan yang kemudian pada zamannya akan menjadi tokoh-tokoh besar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Beberapa diantara mereka jugalah yang kemudian dikenal sebagai ‘Mafia Berkeley’,60 seperti Widjojo Nitisastro yang terkenal sebagai Kepala Bappenas kedua serta arsitek utama
58 Development and Social Change, 57-58.
59 Development and Social Change, 58-60.
60 Revrisond Baswir, Bahaya Neoliberalisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 6–7.
perekonomian orde baru.
Pertanyaan berikutnya adalah, apakah jalan tersebut dapat benar-benar menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh manusia, oleh bangsa Indonesia. Padahal faktanya, Barat sendiri terus berdialektika ketika membicarakan konsepsi dan teori-teori pembangunan. Belum pernah benar-benar ada suatu kesepakatan dimana satu konsepsi pembangunan benar-benar diterima secara mutlak oleh sebagian besar komunitas ilmiah. Hal tersebut yang akan coba disikapi secara kritis dan adil dalam bab berikutnya.
c. Teori-Teori Pembangunan
Tiap negara di dunia ini tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Hal tersebut yang kemudian juga menjadi sebab munculnya berbagai teori dalam mengimplementaskan pandangan pembangunan yang dijelaskan sebelumnya. Secara umum, teori-teori pembangunan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan.
Teori modernisasi adalah lahir pada masa perang dingin. Teori ini adalah bentuk respon akademisi atau intelektual Amerika Serikat terhadap perang yang terus terjadi. Mereka meyakini bahwa teori modernisasi dapat menjadi resep bagi negara-negara berkembang dalam menuju modernitas. Teori ini memiliki beberapa varian, yang masing-masing memiliki perbedaan mengenai apa faktor utama yang mempengaruhi pembangunan. Diantara teori tersebut adalah teori Harrod-Domar (pembangunan adalah masalah modal/investasi), teori Max Weber (nilai-nilai budaya), teori n-Ach (psikologi individu), teori W.W. Rostow (tahapan/ proses), teori Bert. F. Hoselitz (lembaga-lembaga sosial/politik), dan teori Alex Inkeles-David H. Smith (lingkungan kerja). Secara umum, berikut adalah beberapa karakteristik umum teori modernisasi:61 Pertama, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat dikotomi antara ‘modern’ dan ‘tradisional’. Modern merupakan simbol kema-
61 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 38–40.
juan, pemikiran rasional, atau kerja efisien. Negara-negara industri maju diasumsikan memiliki ciri-ciri masyarakat modern. Sebaliknya, masyarakat tradisional diianggap masyarakat yang belum ‘maju’, cara berpikr yang rasonal, serta kerja yang inefisien. Ini merupakan masyarakat di negara-negara miskin yang masyarakat pedesaannya mengutamakan usaha pertanian.
Kedua, teori modernisasi umumnya bersifat ahistoris. Hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal, dapat digunakan tanpa memperhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat. Misal, asumsi bahwa seluruh masyarakat pasti bergerak dalam garis lurus atau unilinear, tanpa atau sedikit memperhatikan konteks masyarakat dan perkembangan masyarakat tersebut sepanjang sejarah. Gerakan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dengan begitu adalah hal yang universal, berlaku dimanapun dan kapanpun. Masyarakat tradisional dengan begitu adalah masyarakat yang terbelakang, sesuai dengan perkembangan dalam garis lurus tersebut.
Ketiga, pendorong atau penghambat pembangunan menurut teori ini adalah faktor-faktor internal. Penyebab kemiskinan misal, harus dicari di dalam negara-negara miskin, bukan di negara-negara kaya. Contohnya adalah pendidikan yang belum memadai, atau modal sosial yang tidak terkelola dengan baik. Hal-hal tersebut adalah faktor internal negara bersangkutan.
Teori ketergantungan adalah bentuk kritik terhadap pengusung teori modernisasi. Masalah utama pembangunan menurut teori modernisasi, adalah keterlambatan negara-negara dalam melakukan modernisasi, dan solusinya adalah hubungan internasional (dalam bentuk bantuan atau perjanjian-perjanjian misal). Teori ketergantungan menolak tesis tersebut. Argumentasinya adalah penyebab kemiskinan dan permasalahan-permasalahan pembangunan adalah kondisi eksternal, justru struktur ekonomi dunia itu sendiri yang eksploitatif. Pendukung teori ini antara lain adalah Andre Gunder Frank, Dos Santos, Cardoso, dan Peter Evans. Secara umum, berikut adalah beberapa karakteristik umum teori
ketergantungan:62
Pertama, menekanan ‘faktor luar’ sebagai penyebab ketergantungan. Sebab utama yang menghambat atau mendorong pembangunan dengan begitu bukanlah masalah modal atau psikologi individu, namun terletak di luar jangkauan politik ekonomi dalam negeri suatu negara. Sistem ekonomi, sosial, dan politik peninggalan kolonial dan pembagian kerja internasional adalah penyebab terhambatnya pembangunan negara-negara berkembang.
Kedua, terhambatnya pembangunan merupakan dampak dari polarisasi regional ekonomi global. Mengalirnya ekonomi menjadi penyebab keterbelakangan dunia berkembang. Pada saat yang sama hal itu juga yang menjadi salah satu, jika bukan satu-satunya, faktor berkembangnya negara maju.
Ketiga, sebagai solusinya, teori ini menganjurkan pemutusan hubungan dengan sistem ekonomi global yang didasarkan pada kapitalisme. Satu-satunya jalan menuju pembangunan adalah dengan mengarahkan diri pada pembangunan yang mandiri. Setelah faktor tersebut diperhatikan, diperkirakan pembangunan akan terjadi secara alamiah sesuai dengan kondisi yang ada pada negara terkait. Teori terakhir adalah teori pasca ketergantungan. Pencetus teori in adalah Immanuel Wallerstein. Pendapatnya yang menarik disini adalah kriitiknya terhadap penjelasan relasi antar negara-negara dengan model dwi-kutub. Dunia terlalu kompleks untuk sekedar djelaskan dua kutub, sentral dan pinggiran. Banyak negara yang terletak di antara kedua kutub tersebut dan tidak tepat untuk dikategorikan sebagai ‘sentral’ ataupun ‘pinggiran’. Karena itu, Wallerstein merumuskan model tiga kutub, yaitu sentral, semi pinggiran, dan pinggiran.63
Kajian di atas sudah mengenalkan konsep-konsep dan teori-teori pembangunan secara umum. Konsep dan teori pembangunan, seperti yang sudah dibahas, memiliki varian luas yang dipengaruhi oleh ban-
62 Suwarsono Muhammad and Alvin Y So, Perubahan Sosial Dan Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 1994), 103–4, 159–61; Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, 96–97. 63 Muhammad and So, Perubahan Sosial Dan Pembangunan, 178.
yak faktor. Setiap konsepsi dan bangunan teori tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dari banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, akan terdapat kesamaan karakteristik-karakteristik pada setiap konsep/teori. Bagian berikutnya akan mengidentifikasi dan membahas elemen-elemen yang terdapat dalam setiap konsep pembangunan.
Guna menganalisis konsep pembangunan setidaknya terdapat tiga pertanyaan untuk dijawab. Pertama adalah subjek dan objek pembangunan, kedua apa tujuan pembangunan itu sendiri, dan ketiga bagaimana cara tujuan tersebut dapat dicapai.64 Konsep development dalam tulisan ini akan dikaji berdasarkan tiga pertanyaan tersebut.
a. Subjek dan Objek Pembangunan
Walau posisi manusia sudah jelas berperan sebagai subjek pembangunan, namun dalam sejarah objek atau sasaran pembangunan terus berubah.65 Dekade awal pembangunan menunjukkan manusia sebagai sekedar sarana, bukan sasaran akhir pembangunan. Hal tersebut ditunjukan dengan pendapat penemu Human Development Index (HDI) Mahbub Al-Haq, yang mengatakan “setelah beberapa dekade pembangunan, kita menemukan kembali yang sudah jelas-bahwa manusia adalah sarana sekaligus tujuan dari pembangunan ekonomi.”66 Artinya, pembangunan dari Barat awalnya tidak menganggap manusia sebagai tujuan akhir dari segala usaha pembangunan. Hal di atas disampaikan Mahbub karena adanya fenomena “the missing people in development planning”, atau hilangnya manusia pada dekade-dekade awal pembangunan. Saat bicara tentang pembangunan, umumnya adalah terkait investasi modal, dimana modal yang dimaksud adalah modal fisik/ekonomi. Bahkan modal manusia tidak diperhatikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Permasalahan selanjutnya muncul para pakar belum benar-benar selesai dalam mendefinisikan manusia.67 Ketika manusia ditempatkan
64 Wan Mohd Nor Daud, Pembangunan Di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 10.
65 Lihat ulasan yang cukup komprehensif mengenai hal ini dalam Erik Thorbecke, ‘The Evolution of the Development Doctrine, 1950–2005’, in Advancing Development, ed. George Mavrotas and Anthony Shorrocks (London: Palgrave Macmillan UK, 2007), 3–36, https://doi.org/10.1057/9780230801462_1.
66 ‘after many decades of development, we are rediscovering the obvious—that people are both the means and the end of economic development.’. Lihat lebih lanjut dalam Mahbub ul Haq, Reflections on Human Development: How the Focus of Development Economics Shifted from National Income Accounting to People-Centred Policies, Told by One of the Chief Architects of the New Paradigm (New York: Oxford University Press, 1995), 3.
67 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 564–65.
sebagai tujuan, maka diperlukan pengertian yang jelas mengenai hakikat manusia. Ketidakjelasan konsepsi manusia akan menyebabkan kebingungan konsepsi-konsepsi lain yang berhubungan dengan tujuan pembangunan, seperti konsep kebutuhan mendasar/basic needs atau kebahagiaan.
Pertanyaan yang muncul adalah kebutuhan mendasar atau kebahagiaan seperti apa yang idealnya didapatkan manusia dari pembangunan. Belum selesainya Barat dalam upaya pendefinisian manusia disisi lain disebabkan karena Barat mengungkap kebenaran dan realitas melalui tradisi ataupun premis-premis filsafat, yang menekankan manusia sebagai entitas fisik dan hewan rasional.68 Melalui kemampuan rasional yang spekulatif tersebut manusia moderen berusaha mengungkap makna eksistensinya.69 Karena konsepsi yang bersifat spekulatif, maka ia dapat selalu berubah pada setiap waktu dan tempat. Akhirnya, ia berpengaruh pada relatifnya nilai moral atau etika yang menjadi petunjuk hidup manusia, dan selanjutnya berdampak pada konsep pembangunan yang juga terus berubah.70
b. Tujuan-Tujuan Pembangunan
Karena pandangan yang menekankan entitas fisik dalam memandang manusia, dapat diasumsikan tujuan pembangunan yang terbentukbersifat materialistis.71 Hal tersebut ditunjukkan dengan PBB yang semenjak dibentuk mengajukan standar hidup yang lebih tinggi sebagai salah satu tujuan utama negara-negara PBB.72 Berdasarkan mandat tersebut dibentuk Sistem Neraca National yang melahirkan indikator pembangu-
68 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 135.
69 Lihat contoh dalam American Humanist Association, ‘Humanism and Its Aspirations: Humanist Manifesto III’, American Humanist Association, 2003, https://americanhumanist.org/what-is-humanism/ manifesto3/
70 al-Attas, Islam and Secularism, 135–37.
71 Materialistis adalah sebuah kecenderungan yang disebabkan oleh materialisme. Materialisme yang dimaksud disini adalah kata yang digunakan untuk menyiratkan peniadaan wujud supramateri, sebagai sebuah mazhab pemikiran eksklusivis yang menganggap eksistensi dan ranah wujud terbatas pada materi, membatasi wujud pada ranah yang dapat berubah [saja] dan membatasinya dengan ruang dan waktu. Pandangan ini menegasikan eksistensi segala sesuatu yang tidak bisa dicerap oleh organ-organ indra. Lebih lanjut lihat Murtadha Muthahhari, Filsafat Materialisme: Kritik Filsafat Islam Tentang Tuhan, Sejarah, Dan Konsep Tentang Sosial Politik (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2016), 10–11.
72 higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development’ lihat United Nations, ‘Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice’ (1945), 11.
nan pertama, GNP (Gross National Product).73 Segala usaha pembangunan kemudian diorientasikan hanya untuk kepentingan materi, diukur menggunakan pertumbuhan ekonomi. Walaupun GNP pada perkembangannya bukan satu-satunya standar pembangunan, hingga sekarang ia menjadi acuan universal bagi negara-negara yang secara umum tergabung dengan PBB.74
Tujuan pembangunan yang hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi (economic’s growth) sebenarnya telah dikritik pada tahun 1970an.75 Dudley Seers misal, memberikan perhatian kepada pemerataan (equity), kemiskinan (poverty), dan ketenagakerjaan (employment),76 berawal dari fakta pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjawab berbagai permasalahan yang kemudian muncul.77 Konsep basic needs dari International Labour Organization’s (ILO) World Employment Conference 1976 adalah salah satu tawaran solusi akan hal itu.
Selanjutnya, melalui berbagai kritik yang berkembang mengenai kemiskinan, ketidaksetaraan,78 dan kapabilitas79 lahirlah konsep Human Development (Pembangunan Manusia/PM).80 Problemnya walau orientasi pembangunan mulai bergeser dari economic growth menuju human development, 81 ia masih bersifat materialististik. Konsep Pembangunan
73 Philip McMichael, Development and Social Change: A Global Perspective, Sixth Edition (Los Angeles: SAGE, 2017), 4; Michael Ward, Quantifying the World: UN Ideas and Statistics (Indiana: Indiana University Press, 2004), 76–77.
74 Walau konsep GNP tidak digunakan kembali semenjak 1968, muncul bentuk modifikasinya: Gross National Income/GNI pada revisi SNN PBB tahun 1993. Lebih lanjut lihat Ward, Quantifying the World: UN Ideas and Statistics, 45.
75 Salah satu upaya mendefinisikan ulang pembangunan dilakukan Dudley Seers, ‘The Meaning of Development’ (Institute of Development Studies, 1969), 5.
76 Dudley Seers, ‘The Meaning of Development’, 5.
77 Richard Jolly, ed., UN Contributions to Development Thinking and Practice, United Nations Intellectual History Project (Bloomington: Indiana University Press, 2004), 111.
78 Richard Jolly, ‘The World Employment Conference: The Enthronement of Basic Needs’, Development Policy Review A9, no. 2 (October 1976): 31–44, https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.1976.tb00338.x; Terkait beberapa kritik akan konsep ini silahkan lihat Dharam Ghai, ‘Basic Needs and Its Critics’, The IDS Bulletin 9, no. 4 (22 May 2009): 16–18, https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1978.mp9004004.x.
79 Lebih lanjut mengenai ini lihat Amartya Sen, Commodities and Capabilities, 12. impr (New Delhi: Oxford Univ. Press, 2008).
80 Meghnad Desai, ‘Human Development: Concepts and Measurement’, European Economic Review 35, 1991, 352; lihat juga karya dari penulis periode awal Laporan Pembangunan Manusia PBB di Haq, Reflections on Human Development.
81 Pada periode yang sama muncul juga karya-karya feminis yang mengkritik peran perempuan dalam pembangunan. Salah satu karya paling awal yang muncul adalah Ester Boserup, Women’s Role in Economic Development (New York: St Martin’s Press, 1970); Lebih lanjut silahkan lihat Shahrashoub Razavi and Carol Miller, ‘From
Manusia dari Amartya Sen misal menekankan pada kebebasan positif (Sen sebut sebagai kebebasan substantif) dari seseorang, bagaimana ia menjadi kapabel, mampu, atau bebas memilih apapun yang diinginkan dalam hidup.82 Namun saat Human Development Index (HDI) dibuat,83 hidup yang dimaknai secara materialistis mereduksi index tersebut menjadi sebatas aspek kesehatan fisik (longevity), pengetahuan (higher education attainment), dan standar hidup layak (income).84
Pembangunan (economic’s growth) juga mendapatkan kritik oleh pemerhati/aktivis lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan atau alam bermula dari industrialisasi yang disebabkan negara-negara seperti Amerika Serikat.85 Salah satu karya paling terkenal berkaitan dengan ini adalah buku Silent Spring karya Rachel Carson, yang berisi kritik terhadap penggunaan pestisida dan dampaknya pada lingkungan.86 Perhatian lain muncul seiring berkurangnya SDA baik yang bisa diperbaharui ataupun tidak.87
Konferensi Dunia untuk Lingkungan Hidup di Stockholm 1972 kemudian menjadi salah satu penanda munculnya kubu lingkungan.88 Negara-negara utara umumnya menyuarakan hak-hak lingkungan, sedangkan keadilan ekonomi atau sosial dituntut oleh negara-negara selatan. Pembela pembangunan merasa upaya mengurangi ancaman terhadap alam akan menghambat pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya mereka yang ingin meratakan alokasi sumberdaya akan berlawanan dengan yang ingin melindungi alam.89 Dari situ kemudian lahirlah konsep Pembangunan Berkelanjutan.
WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse’, The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 1995, 57.
82 Amartya Sen, Development as Freedom, 64; Elizabeth A. Stanton, ‘The Human Development Index: A History’, Political Economy Research Institute, 2007, 9.
83 Elizabeth A. Stanton, ‘The Human Development Index’, 9.
84 Terdapat satu aspek lagi, yaitu pengetahuan, yang bagaimanapun juga mengabaikan aspek spiritual atau supramateri. Lebih lanjut lihat Desai, ‘Human Development: Concepts and Measurement’, 355.
85 Jolly, UN Contributions to Development Thinking and Practice, 125.
86 Rachel Carson, Silent Spring, (New York: Mariner Books, 2002).
87 Meadows, The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind.
88 Jolly, UN Contributions to Development Thinking and Practice, 125.
89 Iris Borowy, Defining Sustainable Development for Our Common Future: A History of the World Commission on Environment and Development (Abingdon, Oxon & New York: Routledge, 2014), 10–14.
Munculnya proyek Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan/PB)” merupakan upaya pendamaian kubu lingkungan dan kubu pembangunan.90 Diharapkan ada solusi pembangunan yang menegakkan keadilan tanpa melupakan keberlanjutan lingkungan. Karena itu pada 19 Desember 1983 PBB membentuk “Special Commission on the Environment for the Year 2000 and Beyond”, yang pada 1984 berubah nama menjadi “World Commission on Environmental Development” dan terakhir “World Commission on Environment and Development (WCED)”. Mereka ingin menjembatani pandangan awal yang menganggap pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan dua buah hal yang tidak kompatibel. Perubahan nama tersebut diharapkan membuat tensi menurun sekaligus merubah pola pikir stakeholder penentu kebijakan pembangunan dunia di masa depan, bahwa pembangunan dan lingkungan bisa berjalan beriringan.91
Pembangunan Berkelanjutan lahir pada 1987 saat WCED menyelesaikan laporannya, Our Common Future. 92 Our Common Future memberikan laporan lengkap mengenai ancaman yang dihadapi ekosistem dunia mulai dari populasi, pakan, industri, sampai ke urbanisasi. Dunia tidak bisa menolak kembali adanya berbagai permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah saat masalah lingkungan tidak bisa ditolak, masih terdapat banyak manusia yang belum bisa hidup dalam kondisi sejahtera.
Pembangunan Berkelanjutan93 adalah upaya untuk menjembatani permasalahan tersebut, yang darinya muncul tiga dimensi PB: ekonomi, sosial, dan lingkungan.94
Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam perkembangannya dapat dilihat sebagai solusi atau masalah baru. Pada satu sisi konsep tersebut menjadi solusi ketegangan antara kubu lingkungan dengan kubu
90 Wolfgang Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development (London: Zed Books Ltd, 1999), 76.
91 Iris Borowy, Defining Sustainable Development for Our Common Future, 55-58.
92 Lebih lanjut lihat WCED, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987).
93 Sustainable development is development ‘that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’. Lebih lanjut lihat WCED, 8.
94 Ben Purvis, Yong Mao, and Darren Robinson, ‘Three Pillars of Sustainability: In Search of Conceptual Origins’, Sustainability Science 14, no. 3 (May 2019): 681–82, https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5.
pembangunan. Namun masalah muncul saat berkelanjutan (sustainibility) sendiri sebagai sebuah konsep, ide, atau wacana juga memahami dunia dalam konteks materialistik.95 Hingga hari ini, aspek-aspek yang berkonotasi material, seperti “kebutuhan”, “sumber daya”, “distribusi barang”, “kesejahteraan”, bahkan “keadilan” menjadi inti argumentasi-argumentasi Pembangunan Berkelanjutan.96
Maka, akan menjadi sebuah ironi jika Pembangunan Berkelanjutan ingin diaplikasikan ke seluruh dunia. Prinsip-prinsip berkelanjutan sebenarnya merupakan hal sudah jamak bagi masyarakat yang sering disebut “tradisional”, masyarakat yang selalu dituntut untuk berubah oleh paradigma pembangunan modern, karena hidup untuk mereka tidak terlepas dari bagaimana menjaga alam bagi kebutuhan generasi berikutnya.97 Mereka adalah masyarakat yang selama berabad-abad telah menjalankan prinsip “berkelanjutan”, sebelum Barat modern menawarkan ide tersebut.98 Bagi masyarakat atau kebudayaan yang sedai awal melihat dunia materiil sebagai ilusi (seperti dalam Hindu, Indian, dsb), konsep ini tidaklah baru. Mengajak kebudayaan seperti tersebut mengikuti Pembangunan Berkelanjutan secara tidak langsung berarti mengajak mereka mengikuti pola pandang Barat semata.
Terakhir, perlu ditekankan bahwa sudah saatnya tujuan pembangunan idealnya tidak lagi terbatas pada aspek-aspek material saja. Secara strategis, setiap orang bisa mengajukan mempertanyakan apakah dengan aspek-aspek material saja ‘Pembangunan Berkelanjutan’ benar-benar bisa diraih. Pada titik ini, setidaknya para pendidik/advokat pembangungan berkelanjutan dan psikolog lingkungan semata jelas menjawab tidak. Guna mencapai pembangunan berkelanjutan, menurut mereka akan diperlukan adanya edukasi dan pemahaman yang berubah mengenai
95 Oliver Parodi, ‘The Missing Aspect of Culture in Sustainibility Concepts’, in Theories of Sustainable Development, ed. Judith C Enders and Moritz Remig (Abingdon, Oxon & New York: Routledge, 2015), 174–75.
96 Oliver Parodi, ‘The Missing Aspect of Culture in Sustainibility Concepts’, 182.
97 Ziauddin Sardar, ‘Beyond Development: An Islamic Perspective’, The European Journal of Development Research, no. 2 (1996): 42, https://doi.org/10.1080/09578819608426664.
98 Lihat dalam Parodi, ‘The Missing Aspect of Culture in Sustainibility Concepts’, 176.
lingkungan, dimana hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang materiil.99
Pertanyaan lebih lanjut dari contoh sebelumnya adalah, apakah salah jika dikatakan bahwa degradasi lingkungan seperti polusi merupakan ekspresi atau perwujudan dari krisis internal, non-materiil dari manusia. Nalar tersebut membawa kita pada pertanyaan terakhir, yang mungkin akan coba dihindari orang, apakah Pembangunan Berkelanjutan seharusnya juga mencakup pembangunan non-materi pada diri manusia.
c. Langkah Pembangunan
Jika tujuan pembangunan bersifat materialistik, maka dalam mewujudkannya ia cenderung selalu bertumbuh dan bersifat dualistik-evolusioner. Pertumbuhannya cenderung membelah realitas menjadi dua, antara superior dan inferior. Tingkat superioritas atau inferioritas diantara keduanya juga cenderung konstan.100 Sifat dualistik tersebut juga dibersamai asumsi bahwa pembangunan bergerak evolusioner atau linear, bergerak maju secara terus menerus untuk mengejar/catching-up101 atau diumpamakan seperti perkembangan makhluk hidup.
Tumbuhan pada fase biji merupakan sebuah entitas yang belum maksimal potensinya. Pembangunan yang secara etimologi bermakna mirip dengan evolusi merupakan proses dimana potensi tersebut tercapai, atau dengan bahasa lain, merupakan penghubung antara ‘belum berkembang’ dengan ‘berkembang’. Konsekuensinya, pertumbuhan setiap negara kemudian juga diibaratkan sama seperti makhluk hidup: ia adalah fenomena yang pasti terjadi. Setiap negara pasti akan tumbuh berkembang, baik digerakkan oleh faktor internal atau eksternal. Asumsi inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa apa yang dialami di Eropa, dipandang harus dilalui oleh negara-negara yang lain.102
Permasalahan di atas bisa dilihat melalui teori-teori pembangu-
99 Parodi, ‘The Missing Aspect of Culture in Sustainibility Concepts’, 182.
100 H. W. Singer, ‘Dualism Revisited: A New Approach to the Problems of the Dual Society in Developing Countries’, Journal of Development Studies 7, no. 1 (1970): 60–61, http://dx.doi.org/10.1080/00220387008421348; lihat juga The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language, 389.
101 Maria Mies, ‘The Myth of Catching-up Development’, in Ecofeminism, ed. Vandana Shiva and Maria Mies (London & New York: Zed Books, 2014), 55–56.
102 Esteva, ‘The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power’, 4; Rist, The History of Development, 75.
nan yang berkembang. Teori Modernisasi yang sudah disebutkan sebelumnya misal, melihat “modern” dan “tradisional” sebagai dua konsep yang asimetris.103 Karena itu modernisasi menuntut perubahan pada segala hal tradisional.104 Salah satu tokoh pendukung teori modernisasi, yaitu teori pertumbuhan Rostow, menunjukkan karakteristik pembangunan yang evolusioner.105 Rostow menetapkan lima tahap universal pembangunan didasarkan ke revolusi industri eropa, dengan asumsi semua masyarakat bisa mengikuti hal yang sama.106 Permasalahan muncul ketika ia digunakan pada dunia yang memiliki berbagai keanekaragaman. Contohnya adalah Suku Aborigin, yang diusir dari tanah mereka sendiri, karena tidak memanfaatkannya secara rasional seperti Barat.107 Tidak beradaptasi berarti “tradisional” atau “terbelakang”. Dampaknya adalah tergusurnya berbagai budaya atau kearifan lokal dalam suatu wilayah karena mengikuti nilai kemajuan dari Barat.108
Karakteristik dualistik yang bermasalah juga muncul dalam Pembangunan Berkelanjutan, antara manusia dengan alam. Artinya Pembangunan Berkelanjutan meletakkan alam sebagai the other, terpisah dari manusia, yang bisa diatur dan dieksploitasi sedemikian rupa,109 dan diinterpretasikan menjadi capital (modal). Hal tersebut ditunjukkan misal oleh WCED dalam Our Common Future¸yang mengatakan bagaimana alam ini sekarang harus dikelola.110 Mulai dari sini muncul varian kapitalisme, “green capitalism”. Hal ini disebabkan karena pendekatan ekologis
103 Teori modernisasi menguraikan secara rinci ciri-ciri masyarakat modern, namun tidak dengan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah hal yang tidak berguna sama sekali (residual). Samuel P. Huntington, ‘The Change to Change: Modernization, Development, and Politics’, Comparative Politics 3, no. 3 (1971): 293.
104 Muhammad and So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, 23.
105 Dimulai dari “masyarakat tradisional”, “prakondisi lepas landas”, lepas landas”, “mengarah ke dewasa”, dan terakhir adalah “masa konsumsi tinggi”. Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (London: Cambridge University Press, 1960), 4–11.
106 Sylvia Chant and Cathy McIlwaine, Geographies of Development in the 21st Century: An Introduction to the Global South (Cheltenham: Elgar, 2009), 29.
107 Potter, Geographies of Development, 9.
108 Vandana Desai, ed., The Companion to Development Studies, 3rd ed (London: Routledge, 2014), 85–86.
109 Hannah Holleman, Dust Bowls of Empire: Imperialism, Environmental Politics, and the Injustice of ‘Green’ Capitalism, Yale Agrarian Studies Series (New Haven: Yale University Press, 2018), 18; Jonathon Porrit, Capitalism as If the World Matters (Sterling, VA: Earthscan, 2007), 107.
110 Silahkan lihat teks aslinya “This new reality, from which there is no escape, must be recognized— and managed.” WCED, Our Common Future, 1.
yang mempertahankan status quo dan bahkan memfasilitasi pola ‘business as usual’ kapitalisme. Bahkan mantan Ketua Komisi PB Inggris mengatakan, “secara logis, apakah kita suka atau tidak, keberlanjutan harus dijalankan dalam kerangka kapitalis secara keseluruhan”.111
Tabel 1. Elemen-elemen Konsep Pembangunan (Barat)
Sumber Asas Subjek-Objek Prioritas Tujuan Langkah
Barat Materialisme Manusia-Alam (mulai bergerak ke manusia)
Materi (pertumbuhan ekonomi) Pertumbuhan (dualistic-evolusioner)
Sumber: konstruksi penulis (2020)
Apabila disimpulkan, seperti dapat dilihat dalam Tabel 1, prioritas dan langkah pembangunan dalam perspektif Barat tetaplah pertumbuhan ekonomi yang materialistik, bukan lingkungan. Walaupun munculnya aspek lingkungan merupakan sebuah kemajuan yang positif bagi manusia, lingkungan dalam perkembangannya justru berubah menjadi variabel dalam mempertahankan pembangunan.112 Pembangunan Berkelanjutan disini dapat disebut sebagai oxymoron, atau sebuah istilah yang cenderung bertentangan. Istilah tersebut menjadi kontradiktif karena ‘pembangunan’ yang semula menjadi sebab degradasi lingkungan justru sekarang menjadi hal yang wajib dipertahankan.113 Makna keberlanjutan dengan begitu bergeser, dari ‘konservasi alam’ menjadi ‘konservasi pembangunan’.114
Langkah pembangunan yang evolusioner dan dualistik telah teridentifikasi terdapat dalam konsepsi pembangunan modern. Hal tersebut wajar, karena ide-ide tersebut diformulasikan di dunia Barat, dan terpengaruhi oleh nilai-nilai sekuler. Bahkan konsep-konsep dan pro-
111 M.J. Harte, ‘Ecology, Sustainability, and Environment as Capital’, Ecological Economics 15, no. 2 (November 1995): 158–59, https://doi.org/10.1016/0921-8009(95)00043-7.
112 Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development, 34.
113 Rist, The History of Development, 193–94.
114 Sachs, Planet Dialectics: Explorations in Environment and Development, 81.
gram-program Pembangunan Berkelanjutan (MDG’s, SDG’s, dsb) juga terbentuk diatas budaya, filsafat, dan pengetahuan saintifik Barat.115 Setelah mengidentifikasi elemen-elemen mendasar dari pembangunan, bagian berikut akan mendiskusikan bagaimana kira-kira respon yang ideal dalam menghadapi permasalahan-permasalahan konsep pembangunan.
115 Parodi, ‘The Missing Aspect of Culture in Sustainibility Concepts’, 174–75.
a. Falsafah Pembangunan Bangsa
Semenjak awal kemerdekaan, perencanaan pembangunan sudah berjalan di Indonesia. Era pembangunan di Indonesia kurang lebih dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tahun 1947. Panitia tersebut adalah perancang dokumen perencanaan pertama dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Rancangan yang dibuat panitia tersebut berisi program pembangunan dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata. Panitia Pemikir inilah yang kemudian juga menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).116
Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, semenjak awal kemerdekaan juga ditunjukkan betapa eratnya hubungan antara perencanaan pembangunan dan konstitusi negara. Dimensi-dimensi konstitusional seperti dasar negara tidak terabaikan dalam diskursus pembangunan bangsa, mulai dari topik tujuan pembangunan, sistem kelembagaan perencanaan pembangunan, sampai ke proses dan pilihan paradigma pembangunan. Sejak 1945 hingga sekarang Indonesia memang telah mengalami lima kali pergantian konstitusi. Namun, ada hal yang tidak pernah tergantikan pada setiap amandemen UUD, yaitu Pancasila. Pancasila, di Indonesia, adalah hal yang semua warga negaranya bisa akui sebagai pandangan hidup (worldview) bangsa, falsafah negara, yang semestinya juga menjadi dasar Pembangunan Nasional.117 Pancas-
116 Anggota panitia ini antara lain adalah Drs Moh. Hatta, AK Gani, Moch. Roem, dan Sjafroedin Prawiranegara Mustopadidjaja AR, ed., Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2012), 25–30.
117 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025’ (n.d.).