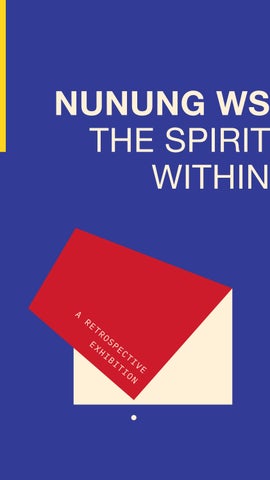11 minute read
JIWA DA LAM MA NUNG GAL
Pengantar Kuratorial
Pameran Retrospektif
Advertisement
Nunung WS
Galeri Nasional Indonesia
Oleh CHABIB DUTA HAPSORO
NUNUNG WS adalah sebuah nama untuk konsistensi, daya tahan, dan energi dalam seni lukis abstrak Indonesia.
Terlahir dengan nama Siti
Nurbaya, ia menggunakan nama
Nunung—yang merupakan nama panggilan oleh keluarganya— dan menyematkan WS, singkatan dari Wachid Sa’ad, nama sang ayah yang selalu ia hormati.
Karier Nunung merentang sejak awal dekade 1970an hingga hari ini. Ratusan lukisan telah diciptakannya.
Selain konsistensi, sejumlah gaya ungkap telah ia geluti.
Jiwa dalam Manunggal adalah sebuah pameran retrospektif oleh
Nunung WS. Pameran ini tidak hanya menampilkan karya-karya Nunung terdahulu, yang menunjukkan bahwa seolah kariernya telah selesai. Justru, pameran ini banyak menghimpun lukisan-lukisan terbaru Nunung, yang diciptakannya pada periode 2020 hingga 2023. Meskipun demikian, mereka tetap mewakili puncak-puncak atau tubuh-tubuh kekaryaan Nunung yang penting.
NUNUNG WS DALAM TIGA PERIODE
KEKARYAAN
Jika dijajarkan secara runut, tubuh-tubuh kekaryaan Nunung mencakup tiga periode: Pertama adalah manifestasi artistik dari pencerapan Nunung terhadap alam di sekelilingnya. Ketika Nunung berada pada masa puncak kebimbangan dan ketidakpuasan pada proses pendidikan seni rupa di Akademi
Seni Rupa (Aksera) Surabaya— tempat ia menimba ilmu, ada sebuah kesempatan yang mengantarkannya ke Jakarta. Kesempatan ini berupa sebuah pameran angkatan kelasnya pada 1971 di Galeri Cipta, Taman
Ismail Marzuki, Jakarta. Pada kesempatan ini ia bertemu dengan
Nashar pertama kali dan pada kesempatan itu Nashar memuji karya-karya Nunung yang sedang dipamerkan. Nunung pun sudah sejak lama mengagumi karya-karya
Nashar. Singkat cerita, kesempatan ini Nunung ambil untuk berani nyantrik kepada Nashar: ia acapkali berbulan-bulan hidup di Jakarta dan melukis di bawah bimbingan sang pelukis kelahiran Padang
Pariaman ini. Ada beberapa alasan yang membuat Nunung merasa nyaman dan cocok untuk belajar langsung di bawah bimbingan Nashar. Salah satunya adalah Nashar memandangnya sebagai rekan yang sederajat dan tidak canggung bahwa Nunung adalah perempuan.1
Di bawah bimbingan Nashar, kesadaran Nunung dalam melukis mulai berubah dari sebelumnya. Benda-benda, objek, dan pemandangan di sekitar dirinya mulai diwujudkan dalam sejumlah penyederhanaan yang bebas, bahkan melanggar kaidahkaidah bentuk dan anatomi figuratif (nonteknis) dan komposisi rupa yang membidang dengan warna-warna pastel yang tegas.
Akan tetapi, rupa pada lukisan itu tidak hadir pada karya-karya gambar Nunung. Di sini ia justru lebih ekspresif dan efisien dalam mengelola tinta cina, arang, dan cat air atau akrilik di atas kertas. Gambar-gambarnya banyak mewujud dengan tarikan-tarikan senapas dari cat air dengan sejumlah palet warna seperti biru, kuning, dan merah muda yang ringan diiringi dengan goresan-goresan arang. Nunung mengimba secara lebih “manasuka” objek-objek yang menggetarkan hatinya. Pada periode ini kita akan mendapati judul-judul karya yang merujuk ke sejumlah lokasi tipikal seperti Bali, Maninjau, dan Borobudur.
Kekaryaan Nunung pada periode ini menunjukkan apa yang disebut kritikus seni Sanento Yuliman sebagai lirisisme. Oleh Yuliman, banyak pelukis Indonesia yang mewujudkan pengalaman liris, yakni tentang alam atau kehidupan “tanpa melukis benda-benda dalam alam itu sendiri.”2 Meskipun beberapa kali kita masih dapat melihat dan merasakan bentuk bentuk perbukitan dalam karya Maninjau Nunung, tetapi rupa yang realistis dari lembah
Maninjau tak terlihat dalam karyakarya Nunung, terlebih kita tidak merasakan acuan-acuan tentang horison. Tidak ada ilusi yang mengimba dunia nyata dalam karya ini, melainkan “ketidakaturan dan variasi dalam bentuk, yang memperlihatkan rupa yang mempunyai prototipenya dalam alam” untuk

“mengungkapkan emosi dan perasaan pelukis dalam mengalami dunia.”3
Oleh Yuliman, lirisisme ini menandai seni lukis abstrak Masa Ketiga yang digeluti oleh banyak pelukis Indonesia sejak akhir tahun 1960-an.
Nashar, pembimbing Nunung, punya pemahaman yang unik sebagai pelukis perihal keterhubungan manusia dan alam. Nashar selalu berusaha ingin “bersatu dengan alam” yang ia elaborasi lagi dengan ungkapan, “Aku perhatikan sebuah kursi, aku rasakan benda itu, hingga timbul perasaan padaku bahwa kursi itu ialah aku sendiri.”4 Pada Nunung, prinsip melukis itu hadir melalui kesadarannya untuk tidak terlalu bergantung pada indra penglihatan.
Ia justru diminta Nashar untuk merasakan angin, mencium aroma, dan seterusnya, serta mendayagunakan intuisinya sebanyak mungkin.
Melalui ungkapannya, Nashar ingin menyatakan bahwa manusia memang seharusnya menjadi bagian dari alam dan bukan kebalikannya, alam menjadi entitas yang diobjektifikasi manusia. Oleh karena kondisikondisi tertentu, batin atau jiwa manusia juga seringkali tidak selaras dengan ritme-ritme alam.
Kita bisa menggarisbawahi bahwa periode di bawah bimbingan Nashar adalah saat di mana Nunung melatih diri untuk menajamkan kepekaan indrawinya, untuk menubuhkan dan menyelaraskan jiwanya dengan segala sensasi dan ritme-ritme alam.
Membicarakan tentang cerapan seniman pada alam, Bali memiliki posisi penting bagi Nunung, yang juga diinspirasi oleh Nashar.
Nunung pernah menyebut bahwa Bali merupakan “surga” bagi mata dan batinnya yang membuatnya lebih mudah menghayati dan dengan demikian manunggal bersama alam.
Nunung sempat beberapa kali menghabiskan waktu cukup lama di Bali bersama Nashar untuk melukis setidaknya pada pertengahan 1970an sampai 1980-an. Bagi Nunung, Bali juga menawarkan tata kehidupan yang holistis di mana kehidupan spiritual tidak terpisahkan dengan kehidupan sekuler atau sehari-hari.
Maka Nunung selalu terkesima ketika melihat upacara karena di dalamnya
“ada warna, gerak tarian, suara gending, dan musik yang menjadi satu.”5
Sebenarnya Bali tidak hanya memesona Nunung dan Nashar, melainkan juga pelukis-pelukis mancanegara dan dalam negeri sebelum dan sesudah mereka.
Ketertarikan ini lebih kurang dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh romantisasi dan imajinasi
Bali melalui lukisan-lukisan para pelukis Eropa yang bermukim di Bali pada masa kolonial, terutama pada abad ke sembilan belas hingga dua puluh.
Akan tetapi jika ditilik lagi,
Nashar dalam catatannya berusaha tidak mengulangi idealisasi turistik dari para pelukis Eropa itu. Dalam catatannya ia pernah tinggal sebuah desa miskin untuk merasakan kehidupan Bali secara lebih nyata di luar imajinasiimajinasi bentukan itu.6
Nunung pun demikian, kehidupan berkeseniannya di Bali ia lakukan dengan sederhana, bahkan cenderung bohemian karena ia acapkali hanya singgah di gardu-gardu atau menempati rumah kontrakan sederhana di Bali untuk beristirahat.
Perkembangan karya Nunung yang kedua berkutat pada ekspresi gestural, yang tercermin pada sapuan-sapuan kuas yang makin ekspresif dan semarak. Perkembangan ini sangat intensif ia jelajahi pada periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Dalam periode ini penghayatan Nunung makin mendalam terhadap benda-benda dan alam di sekitarnya, yang justru dalam manifestasinya makin menjauhi bentuk-bentuk atau figur-figur yang ia lihat di alam. Ini justru bertolak dari penjiwaan Nunung pada alam dan kehidupan sekeliling yang makin menubuh.
Nunung juga makin terobsesi dengan warna. Palet-palet warnanya pun makin beragam. Persepsinya pada warna memperlihatkan juga bagaimana warna menyatu dengan dirinya atau menjadi perpanjangan atas indra atau dirinya sendiri. Maka dari itu warna menjadi media untuk ungkapan yang liris, seperti yang ia nyatakan, “Warna bukan hadir sebagai warna, tetapi warna itu hadir sebagai ekspresi juga sebagai ungkapan rasa pribadi yang dalam.”7
Dalam menjelajahi ekspresi gestural ini, Nunung juga meneladani ekspresi khas kaligrafi, tidak hanya kaligrafi Arab, melainkan juga Jepang dan Tiongkok.
Ekspresi yang kaligrafis ini makin menuntun Nunung kepada pencarian pengalaman spiritual. Lekaklekuk garis (khat) yang khas pada kaligrafi menginspirasi Nunung dalam melahirkan sejumlah karyakarya dengan sapuan yang ekspresif dan semarak, sekaligus efisien dan hening.
Gairah seniman untuk mencari dan merasakan daya spiritual sangat umum terjadi pada periode 1970an hingga 1980-an. Gairah ini juga tidak terpisahkan dengan kerinduan para seniman pada budaya tradisi yang menjadi asal-usul mereka ataupun yang tidak. Satu alasan yang menyebabkan kecenderungan ini adalah kehidupan atau tata sosial modern telah merenggut atau menggantikan tata kehidupan tradisi yang holistis. Kehidupan modern yang diperkenalkan secara paksa oleh kolonialisme memisahkan antara kehidupan spiritual dan yang sehari-hari. Ini memberikan kegamangan bagi orang-orang Indonesia modern.

Keberjarakan seniman Indonesia pada hal-hal yang bersifat spiritualtradisional memberikan motivasi kepada seniman dan penyair untuk kembali mendekatinya. Sastrawan dan pemikir sastra Abdul Hadi
WM mengelaborasi tiga motivasi perupa dan sastrawan Indonesia untuk mendekati dan menyikapi kembali tradisi pada rentang tahun
1970-an hingga 1980-an. Pertama adalah adaptasi unsur-unsur budaya tradisional demi inovasi gaya ungkap. Para seniman dengan kecenderungan ini melihat tradisi sebagai unsur yang relevan bagi dunia mutakhir. Kedua, mengadaptasi kebudayaan daerah tertentu seperti
Jawa, Minangkabau, Melayu Riau, dan lain-lain untuk memberi corak khas terhadap kesenian Indonesia. Ketiga, meneladani aspek-aspek spiritual dan agama tertentu dengan menyadari bahwa budaya tradisional masyarakat Indonesia diperkaya oleh agama-agama dan kepercayaan besar.8
Dari ketiga motif yang diajukan
Abdul Hadi, kecenderungan Nunung dapat masuk ke motivasi pertama dan ketiga.
Meskipun Nunung kurang cocok disebut sebagai seniman yang terinspirasi oleh tradisi, tetapi latar belakang Islam keluarganya yang kental membuatnya juga dibentuk oleh tradisi Jawa yang telah lama berakulturasi dengan
Islam. Nunung dibesarkan dalam naungan kehidupan golongan santri yang memberinya landasan dan pola pikir religius yang kuat. Terlebih, suasana kehidupan Islam tradisional ini juga menjadikan Nunung merasakan pengalaman spiritual yang spesifik, yang lantas membuatnya untuk selalu mencari pengalamanpengalaman spiritual berikutnya melalui laku melukis.
Tentu saja peneladanan Nunung pada kaligrafi tidak mengarahkannya kepada pemunculan tulisan kaligrafi di dalam lukisannya. Nunung tidak terjebak kepada penciptaan kaligrafi—terutama Islam—yang hanya mengarahkan kepada pernyataanpernyataan doktrin dan teologi.
Nunung mungkin justru lebih bersemangat untuk memahami apa yang disebut oleh Abdul Hadi sebagai
Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam perkembangan tradisi dan peradaban masyarakat
Nusantara yang membentuk sistem kepercayaan, peribadatan, dan bentuk-bentuk spiritualitasnya.9
Untuk yang terakhir Nunung memenuhi salah satu wawasan estetik Islam yang diajukan oleh Abdul Hadi
WM, bahwa, “berkesenian merupakan ikhtiar mentransformasikan gagasan dan pengalaman batin ke dalam objek-objek estetik, bukan mentransformasikan objek-objek di luar dirinya yang dicapai oleh penglihatan indra.”10 Melaluinya, ekspresi kekaryaan Nunung pada periode ini naik setahap dari periode sebelumnya.
Ditegaskan kembali bahwa perkembangan praktik Nunung WS dikenali sebagai penemuan inovasi yang diilhami atas pencarian spiritual yang tidak terpisahkan dari kehidupan tradisional yang selama ini berkelindan dengan pengaruh Islam. Pencarian yang spiritual oleh Nunung ternyata menunjukan tidak terpisahkannya hal-hal spiritual dan budaya tradisi. Ini yang lantas digarisbawahi oleh filsuf A.K.
Comaraswamy, bahwa tradisi selalu menuntun kepada yang asali dan senantiasa mampu mewujudkan ekspresi estetik dari ilham atau perenungan yang bersumber dari yang transenden.11
Ekspresi-ekspresi gestural kaligrafi menuntun Nunung pada periode kekaryaan ketiga, yang menariknya makin dalam kepada pencarianpencarian suasana spiritual.
Periode ketiga ini terjadi sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang.
Ekspresi Nunung yang meneladani kaligrafi gestural bisa dikatakan tidak berlanjut pada pertengahan
1990-an. Ia menemukan gaya ungkap lain yang memungkinkannya terhubung pada pengalaman spiritual secara lain. Ia mulai mengembangkan bidang warna dan tumpukantumpukannya. Perbedaan mendasar dari ekspresi sebelumnya adalah pada periode ini Nunung banyak menghabiskan waktu untuk merenung dan membuat rancangan sebelum karya diekseskusi. Pada periode abstrak gestural sebelumnya Nunung lebih banyak mengandalkan spontanitas dan intuisi. Pada periode ini lukisanlukisan Nunung hadir dengan palet warna yang efisien.
Pada periode ketiga ini goresangoresan Nunung makin membentuk bidang dengan palet warna yang makin cermat. Bidang-bidang itu bertumpuk dengan batas-batas yang menyugestikan suasana ambang.
Langkah lain yang signifikan mulai dilakukannya dengan menyematkan objek-objek konkret pada lukisannya, misalnya dengan kertas transparan. Kertas transparan ini meredam intensitas warna pada bidang yang ditumpuknya sehingga memberikan sensasi temaram. Nuansa konkret juga dihadirkan Nunung melalui kertas yang dilipat dengan beberapa cara. Objek konkret dan sensasi rupa yang dihasilkan dari upaya non-melukis ini menghadirkan “nuansa abstraksi” yang kaya sekaligus menggetarkan. Gaya ungkap ini menunjukkan meluasnya sumber inspirasi Nunung. Nuansa transparan dan temaram itu bersumber dari sensasi rupa yang dilihat Nunung dan kelindan rumit benang-benang pada sarung ayahnya ataupun pada kain tenun Nusantara. Lipatanlipatan pada lukisannya dihadirkan dari ingatan masa kecil Nunung saat bermain melipat kertas.
Ini membuktikan bahwa pencarian Nunung terhadap yang spiritual selalu bersumber pada kenyataan atau dunia material yang dinamis dan sehari-hari. Dengan dimediasi laku-laku khas seni lukis, Nunung mencapai pengalaman mistik. Tidak berlebihan jika kritikus seni Carla
Bianpoen pernah menyebut Nunung, melalui laku melukisnya, sebagai peziarah di Tanah Suci.12
Dapat digarisbawahi pula bahwa kekaryaan Nunung WS adalah sebuah daur. Nunung selalu menengok dan meramu kembali pencapaianpencapaiannya terdahulu dengan kesadaran-kesadaran yang baru. Ini menuntunnya kepada cecabang baru yang membuka banyak kemungkinan. Pendekatan ini membuat tubuh kekaryaan Nunung khas: selalu ada pola atau order dalam cara menarik garis, penggunaan bahan, warna, dan seterusnya. Kita berhadapan dengan sebuah perkembangan kekaryaan yang tertata dan terukur.
NUNUNG WS DI TENGAH MEDAN SENI RUPA
INDONESIA
Menuju kematangannya sebagai seniman dan manusia, Nunung memang digerakkan oleh daya-daya spiritual. Melukis adalah metodenya bersenandika dan merenung untuk mencapai taraf spiritualitas demi mencapai kemanunggalan jiwa dengan zat-zat transenden. Ini adalah sebuah upaya yang membutuhkan komitmen total sepanjang hidupnya.
Komitmen yang diambil Nunung bukannya tanpa tantangan, mengingat dirinya adalah perempuan perupa
Indonesia di tengah medan seni rupa dan struktur kehidupan yang masih terbelenggu patriarki, terutama pada masa Orde Baru.
Masa 1980-an hingga 1990-an adalah masa di mana Nunung WS sangat aktif berkarya. Ia sangat sering berpameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Nunung juga acapkali melakukan perjalanan dan residensi seni, serta memperoleh sejumlah penghargaan. Situasi ini tampak menjadi anomali, mengingat Orde
Baru mengekang kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dunia seni. Aktivis gender Julia Suryakusuma telah menuturkan bahwa represi terhadap perempuan pada masa Orde Baru adalah berupa idealisasi dari peran tertentu perempuan yang menjebak mereka dalam ranah domestik.13
Dalam bidang seni rupa, Carla
Bianpoen dan seniman Mella Jaarsma menyatakan bahwa seniman perempuan masih jarang dilibatkan dalam pameran-pameran seni rupa berskala besar atau arus utama pada 1980an hingga 1990-an. Dalam pendapat mereka, ini disebabkan oleh stereotip pelaku seni dominan, yakni laki-laki, yang meyakini bahwa karya seniman perempuan kurang bermutu atau motivasinya berkeseniannya minim, sehingga layak disebut sebagai perupa paruh waktu atau perupa hari minggu.14
Bianpoen dan Jaarsma memperlihatkan penyebab munculnya stereotip itu dengan fakta-fakta yang menyedihkan yang terjadi pada sejumlah perupaperupa perempuan Indonesia setelah mereka menikah dengan teman-teman seprofesinya. Aktivitas melukis dan berkesenian mereka terhalang oleh peran-peran domestik mereka sebagai istri dan ibu, yang mencerminkan harus mengalahnya mereka pada ego sang suami yang juga seniman.15
Nunung mengakui bahwa ia beruntung memiliki keluarga yang menjunjung kesetaraan dalam pembagian tugas dalam berumah tangga. Di depan calon suaminya, Nunung yang sejak lama telah berikrar menjadi pelukis, secara asertif menyatakan bahwa keputusan apapun yang ia ambil dalam hidup, termasuk menikah, melahirkan, dan membesarkan anak, tidak boleh menghalanginya untuk terus melukis.
Begitupun Nunung yang juga tidak akan menghalangi calon suaminya untuk melukis. Nunung dan Sulebar
Sukarman, calon suaminya itu akhirnya menikah pada 1978 dan dikaruniai seorang putra bernama
Seno Ahmad pada 1979. Mereka terus merawat komitmen-komitmen mereka sebagai pasangan hingga Sulebar berpulang pada Mei, 2022 lalu.16

Meskipun cukup banyak mendapatkan keleluasaan, Nunung tidak berada pada posisi nyaman. Ia menyadari masih ada ketimpangan dalam kesempatan yang dimiliki oleh seniman perempuan Indonesia untuk berkarya dan berpameran.
Ia kemudian bersama-sama sejumlah seniman perempuan mendirikan kelompok Nuansa Indonesia pada 1985. Ia lantas menjabat sebagai sekretaris dalam kelompok itu.
Anggaran dasar kelompok Nuansa Indonesia kurang lebih menyatakan menyatakan bahwa kelompok ini hendak memperjuangkan kedudukan seniman perempuan Indonesia sambil meningkatkan martabat seni rupa Indonesia sebagai profesi.17
Nuansa Indonesia telah melakukan sejumlah pameran dan di antaranya juga berkolaborasi dengan senimanseniman perempuan di Malaysia. Namun, aktivitas kelompok ini menurun dan berhenti pada pertengahan 1990-an.
Bagaimanapun Nunung terus berkarya hingga kini dengan beragam ekpektasi dan tantangan yang dihadapinya. Maka dari itu seniman Teguh Ostenrik pernah menyebut Nunung sebagai seorang perempuan belum pernah gagal untuk membebaskan dirinya dari normanorma konvensional kehidupan.18
Catatan Akhir
1) Carla Bianpoen dan Mella Jaarsma, “Perempuan Perupa: Antara Visi dan Ilusi”, dalam Perempuan Indonesia, Dulu dan Kini, Mayling Oey-Gardiner
Mildred L.E. Wagemann, Evelyn Suleeman, Sulastri (ed.). (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) hlm. 87.
2) Sanento Yuliman, Seni Lukis Indonesia Baru: Sebuah Pengantar (Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1975), hlm. 37.
3) Ibid. hlm. 37, 40.
4) Nashar, “Surat Ketiga Belas”, dalam Nashar oleh Nashar (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002), hlm. 273.
5) Wawancara dengan Nunung WS pada 17 Mei 2023.
6) Nashar op. cit. hlm. 147, 151.
7) Nunung WS, “Wawasan berkarya”, dalam Katalog
Pameran Tunggal Nunung WS di Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta, 6-14 Desember 1989.
8) Abdul Hadi WM, “Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber”, dalam Kembali ke Akar Kembali ke Sumber: Esai-esai Sastra Profetik dan Sufistik Dr. Abdul Hadi WM, Ali Akbar (edi.) (Jakarta: Penerbit
Pustaka Firdaus, 1999), hlm.6.
9) Ibid. hlm. 13.
10) Ibid. hlm. 15.
11) Ray Livingstone, The Traditional Theory of Literature (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962), hlm. 15-17.
12) Carla Bianpoen, “A Pilgrim to Holy Land”, The Sunday Observer, 26 Oktober 1997.
13) Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 18-19.
14) Bianpoen dan Jaarsma op. cit. hlm. 74.
15) Bianpoen dan Jaarsma op. cit. hlm. 80.
16) Wawancara dengan Nunung WS pada 17 Mei 2023.
17) Sanento Yuliman, “Wanita Indonesia dan Seni Lukis” dalam katalog pameran Nuansa: Pameran Seni Lukis Wanita Indonesia-Malaysia, 1991.
18) Teguh Ostenrik, Perempuan Perupa: Antara Visi dan Ilusi, hlm. 89.