
7 minute read
ke Pengajaran
from MAJALAH KASADHAR
Den Baguse Ngarso Bawa Dunia Seni Peran ke Pengajaran
Dikenal aktif dalam dunia seni Yogyakarta, tetapi juga berkecimpung di dunia pendidikan. Baginya, keduanya sama-sama memainkan peran. Kiprahnya dalam dunia seni dilatarbelakangi motif ingin dolan.
Advertisement
Bagi generasi yang mengalami era 1990-an, khususnya di Yogyakarta, barangkali masih mengingat Den Baguse Ngarso. Sosok yang sombong, keras kepala, menjengkelkan, gila hormat. Sifatsifat negatif seolah melekat pada dirinya. Akan tetapi, keempat karakter itu tidak dirasakan redaksi Kasadhar tatkala bertandang ke rumahnya yang dipenuhi pepohonan rindang di kawasan Jogokariyan, Yogyakarta, Kamis (19/12/2019) siang.
Seorang pria paruh baya membukakan kami pintu depan rumah sembari tersenyum lebar. “Ngobrol-ngobrol di teras saja, ya,” katanya sambil menggelar sebuah tikar di teras rumah itu yang masih terlihat asri di tengah kepadatan pemukiman sekitar. Dialah Susilo Nugroho, yang lebih dikenal sebagai Den Baguse Ngarso, pada serial Mbangun Deso di TVRI pada medio 1990-an. Sosok fenomenal yang berperan sebagai tokoh antagonis pada acara televisi tersebut. “Pemberian nama Den Baguse Ngarso untuk memudahkan mengingat-ingat karakter tokoh yang bersangkutan saat naskahnya ditulis karena ceritanya berseri. Oleh karena itu, cari nama yang nyerempet-nyerempet karakter tersebut,” jelas Susilo. Dalam serial itu, ia selalu ingin menjadi yang terdepan dalam hal apa saja dan berlagak seorang bangsawan. Berangkat dari situ, dipilih nama Ngarso yang diambil suku kata Ngar-nya saja untuk menjadi ngarep yang berarti depan dalam bahasa Indonesia. Sementara Den Baguse identik dengan panggilan laki-laki Jawa yang memiliki fisik tampan, terutama dari kalangan bangsawan. “Sebenarnya ada tambahan pareng-nya di belakang, yang berarti boleh, menjadi Den Baguse Ngarso Pareng. Namun pareng-nya jarang disebut. Artinya tokoh ini kalau minta apa saja pasti diistimewakan,” tutur alumnus IKIP Sanata Dharma Yogyakarta angkatan 1978 itu. Saat menulis naskah “Mbangun Deso”, ia terbantu karena penamaan tersebut. “Selalu ingat, kalau Den Baguse Ngarso harus yang memiliki karakter seperti itu, tidak jauh -jauh dari ingin menang sendiri,” imbuhnya.
Semasa aktif mengajar Dok. OSIS SMK I N Bantul on Twitter
Berkesenian Sebagai Dolan Lain kisah dalam cerita, lain pula kisah dalam kehidupan nyata. Jika dalam cerita “Mbangun Deso” itu Susilo Nugroho menjadi orang yang seolah meremehkan keberadaan orang lain di sekitarnya, tidak demikian dalam jalan hidupnya. Dahulu saat mengenyam pendidikan di bangku SD dan SMP, ia mengaku tidak memiliki banyak teman. “Saya bersyukur kesadaran itu muncul, saat SMA saya merasa minder dalam pergaulan. Kemudian berpikir bagaimana caranya mendapat banyak teman, akhirnya bergabung ke kelompok teater di SMA saya. Sempat di-bully juga di sana, tetapi saya menjadi punya teman,” kisah Susilo. Pilihannya masuk ke teater karena merasa tidak memerlukan bakat khusus, seperti paduan suara atau sepak bola. Sewaktu SMA itu, dia pernah mementaskan naskah Putu Wijaya berjudul “Aduh”
pada suatu malam. “Padahal paginya ujian,” gelaknya.
Sejak saat itu, ia semakin percaya diri terhadap passion-nya dalam dunia seni peran. Susilo kemudian rutin mendapat undangan bermain teater di panggung-panggung seni di Yogyakarta saat itu. “Tidak memikirkan berapa uang yang didapat, saya mendapat imbalan saja sudah habis untuk jajan saat perjalanan pulang. Tidak masalah, karena sikap dasar saya berkesenian lebih karena dolan,” kata pria 60 tahun tersebut. Oleh karena pandangan itu, seni peran bukanlah hal serius baginya. “Namun, bagi saya menjadi kebutuhan primer, bukan dalam artian mempengaruhi hidup tidaknya, tetapi utuh tidaknya menjadi manusia,”sambungnya. Keseriusan dalam menekuni bidang ini lambat laun membuahkan prestasi. Saat berkuliah, dia mewakili IKIP Sanata Dharma dalam sebuah lomba drama dan berhasil meraih juara pertama. “Ada hal unik saat itu. Selain lomba drama, juga ada lomba lawak keesokan harinya. Seharusnya teman saya yang maju, tetapi karena dia tiba-biba berhalangan, malah dipasrahkan ke saya,” ceritanya sambil tertawa. Padahal saat itu ia mengaku tidak menguasai perihal lawak. Namun, dengan bantuan temannya tersebut dan rasa percaya diri yang tinggi, juara satu kembali dalam genggaman. Dua gelar berhasil ia persembahkan, juara satu lomba drama dan lawak. Hingga kini, humor menjadi salah satu identitas yang melekat pada dirinya walau dia mengaku lebih banyak berkecimpung di teater.
Torehan prestasi itu tidak luput dari perhatian IKIP Sanata Dharma. Setelah memenangkan dua lomba tersebut, Pembantu Rektor III saat itu, Mujanto, mendorong Susilo mengajukan beasiswa MAWI. Mendengar itu, ia bingung karena dari segi persyaratan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tidak mencukupi. “Untuk mengajukan beasiswa, syarat IPKnya harus minimum 2,75. Padahal saya hanya 2,50. Namun, Pak Mujanto tidak mempermasalahkan karena saya mempunyai prestasi non akademik,” tutur lelaki kelahiran Jogja. Tak disangka, pengajuan beasiswanya diterima sehingga saat itu ia yang mengambil Jurusan Ekonomi terbebas dari uang kuliah bulanan. “Setiap bulan juga mendapat Rp15 ribu,” ulasnya. Walau mendapat beasiswa karena prestasi non akademiknya itu, Susilo merasa ada faktor lain yang turut mempengaruhi. Faktor itu ialah kebersamaan yang menurutnya saat itu menjadi kekuatan IKIP Sanata Dharma dan tidak dimiliki kampuskampus lain. Hubungan antara dosen, karyawan, dan mahasiswa begitu cair. “Saat pulang dari lomba lawak, saya naik sepeda dibuntuti Pak Mujanto.
Menanyakan mengapa saya naik sepeda, tidak menggunakan moda transportasi lain. Kan rumah saya tinggal dekat situ, pak. Keesokan harinya saya dipanggil terkait beasiswa itu,” ceritanya bersemangat. Saking eratnya hubungan tersebut, ia memiliki pengalaman unik semasa kuliah. Supaya uang jajan tidak berkurang, dia sesekali meminta jatah konsumsi dosen di dapur kampus. “Bebas saja minta kepada yang jaga dapur. Komunikasi tanpa sekat, mungkin karena dahulu tahun 1980-an mahasiswa dan jurusannya belum sebanyak sekarang,” katanya.
Seni Era Dulu dan Sekarang
Lulus dari bangku kuliah, ia mulai menjadi seorang pengajar di salah satu SMA swasta di Yogyakarta. Walau demikan, kegiatannya dalam seni peran tetap tidak ditinggalkan. Keduanya sanggup berjalan beriringan. “Baik menjadi guru atau seorang pemeran di panggung, semuanya bermain peran. Itulah benang merahnya Tentu ada perbedaan, menjadi guru memainkan satu peran sementara menjadi pemeran panggung memainkan bermacam-macam peran,” ujarnya. Dia juga tidak terlalu memedulikan predikat yang tersemat kepadanya. Baginya, orang lain bebas menyebutnya sebagai seniman, penulis naskah, aktor, pelawak, sutradara, atau guru. “Saya hanya melakukan apa yang saya suka saja,” kata Susilo.
Hingga kini ia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan seni peran juga karena sikap dasarnya masih sama, ingin dolan, seperti saat remaja dahulu. Bahkan pernah dalam suatu pementasan, bayarannya sebagai sutradara dan penulis naskah tidak berbeda jauh dengan pemainnya. “Apakah saya protes? Tidak, karena itu sudah menjadi hobi saya, yaitu berkesenian. Namun saya juga bisa membedakan, mana yang dolan dan betul-betul profesional,” ucap Susilo seraya terkekeh. Dia sendiri membutuhkan seni untuk berbagai tujuan, antara lain menyeimbangkan hidup dan menghilangkan sekat-sekat dengan orang lain. “Saya yakin setiap orang secara tidak sadar juga begitu. Mereka tidak mesti menjadi seorang seniman, seperti orang suka sepak bola belum tentu dia adalah seorang pesepakbola,” kata pria yang juga salah satu pendiri Teater Gandrik ini. Berkesenian merupakan sebuah proses dan menurutnya hal inilah yang menjadi pembeda dunia seni dahulu dan sekarang.
Susilo berkata, dahulu orang menjalani latihan sambil berproses, dimulai dari latihan dasar dan terus meningkat. Padahal, tidak tahu kapan
Den Baguse Ngarso, Sihono dan Elisa dalam Pentas Wayang Kulit Dalang Ki Seno Nugroho di USD, Dok. Humas USD
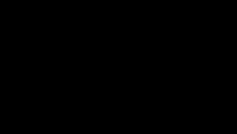

pentasnya. “Kalau memang ada yang membiayai, ayo pentas. Saya pernah latihan lama, tidak tahu kapan pentas. Sekarang berubah, semua terpatok target. Baru sekali latihan, sudah menanyakan pentasnya kapan,”paparnya. Zaman dahulu seni, khususnya di Yogyakarta, guyub dalam kondisi memprihatinkan. Susilo bercerita saat ia muda dahulu, sangat mudah menemukan pementasan gratis di setiap kampung dan kampus saban malam Minggu. “Jelek pertujukannya karena seadanya, tetapi semua senang karena berproses bersama. Lain sekarang, karena terpatok target, menjadi tidak belajar hal-hal di luar jalan yang sudah dirancang,” lanjut pria yang purnatugas dari SMKN 1 Bantul pada Februari 2019 lalu tersebut. Dia lantas mengisahkan contoh konkret dari fenomena ini yang juga merambah dunia pendidikan. Pada suatu waktu, bersama kelompok ketopraknya, ia akan mengadakan pentas dan membagi 100 tiket gratis kepada 25 sekolah di Yogyakarta. “Alokasi satu sekolah empat siswa, yang memenuhi undangan hanya empat sekolah. Saya marah waktu itu. Setelah ditelisik, 21 kepala sekolah yang sekolahnya tidak memenuhi undangan ternyata tidak membagikan tiket.” Mereka beralasan tidak memberi tiket-tiket itu karena khawatir para siswanya tidak belajar jika menonton ketoprak. Sebuah alasan yang membuat Susilo geleng-geleng kepala. Menurutnya, contoh kasus ini membuktikan kurikulum pendidikan mampu mengatur para siswa sedemikian rupa. “Saya akui anak-anak zaman sekarang lebih pintar, tetapi juga terbebani atau justru membebani diri dengan target dan program. Hal semacam ini juga menyangkut budaya, tentang tatanan kehidupan dalam masyarakat,” tukasnya sambil meminum secangkir teh hangat. Menurutnya, budaya tidak hanya sekadar yang tampak dan bisa bernilai ekonomis, seperti tarian dan pakaian tradisional. Namun, juga dapat merambah hal seperti tata nilai di masyarakat, utamanya mengenai sopan santun.
Pernah Dinilai Jelek
Sepanjang keaktifannya dalam dunia seni peran, banyak pengalaman yang telah ia rasakan. Salah satu yang paling dia ingat adalah ketika seorang temannya sendiri, penulis buku bahasa Indonesia untuk kalangan pelajar, menyinggung Susilo dalam sebuah buku ciptaannya. Namun isinya kurang mengenakkan di mana dalam sebuah contoh resensi, ia menulis Susilo tampil buruk pada sebuah pementasan Teater Gandrik. “Banyak yang menanyakan apakah itu menjadi beban bagi saya, tentu saja tidak. Beban bagi yang menulis buku, karena resensi tidak subjektif,” bebernya. Pengalaman tersebut tidak memengaruhi kiprahnya dalam bidang yang menjadi salah satu jalan hidupnya itu. Setelah pensiun sebagai guru, ia bisa makin fokus dalam dunia seni peran. Aktivitasnya juga tidak berkurang. Akhir tahun 2019, ia bahkan sudah memiliki sebuah acara pementasan ketoprak. “Saya mau latihan untuk pentas itu setelah ini,” ujarnya mengakhiri obrolan panjang kami selama kurang lebih 1,5 jam pada siang terik itu. (Dion)










